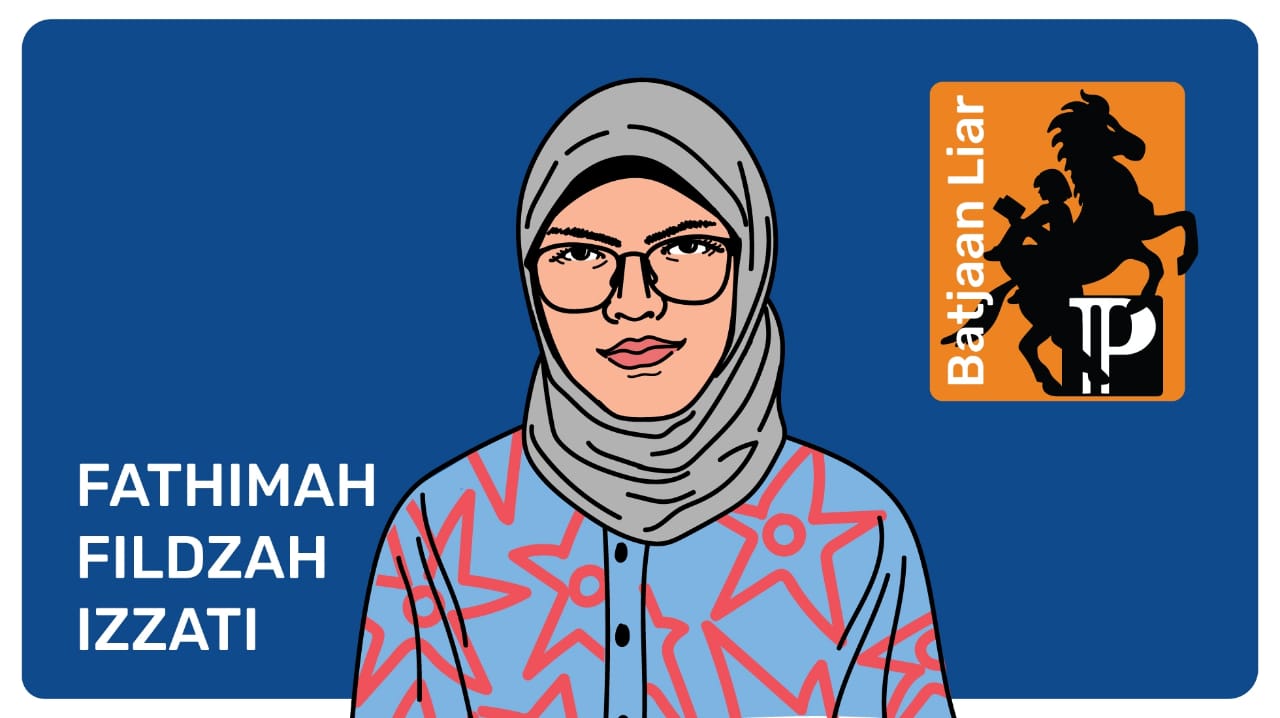Ilustrasi: Deadnauval
PENOLAKAN dan perlawanan hebat gerakan rakyat terhadap isi dan pengesahan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (kini telah menjadi Undang-Undang) telah membuat buruh/pekerja kembali diperbincangkan dalam diskursus politik di Indonesia. Setidaknya, di tengah pandemi ini, fenomena itu terlihat di ruang-ruang diskusi daring seperti webinar, status, cuitan, story hingga video singkat di berbagai platform media sosial. Mulai dari langgengnya sistem kerja kontrak/outsourcing, masifnya upah rendah, hingga terancamnya hak cuti haid, adalah beberapa aspek dalam UU Cipta Kerja yang menjadi fokus banyak orang.
Namun, di saat yang sama, narasi-narasi yang merendahkan buruh seperti, “kok pakai iPhone?”, “minta naik upah mulu tapi punya motor Ninja”, atau “karyawan SCBD bukan buruh” pun bermunculan.
Dua narasi perbincangan yang kontradiktif ini sebenarnya tidak mengherankan. Depolitisasi kelas pekerja pada masa Orde Baru hingga kini masih menyisakan kuatnya pemahaman di tengah masyarakat bahwa ‘karyawan’ itu berbeda dengan ‘buruh’, atau bahwa ‘buruh’ itu adalah orang rendahan yang semua-orang-ingin-menghindarinya. Akibatnya, masih banyak orang—yang sebetulnya adalah bagian dari buruh alias rakyat pekerja—kemudian menjadi antipati terhadap perjuangan buruh. Kelas buruh pun seolah tidak boleh berdemo, atau dianggap bodoh ketika memperjuangkan kehidupan mereka agar menjadi lebih baik.
Pada masa Orde Baru, perbincangan mengenai kehidupan kelas pekerja memang hanya dapat terjadi di ruang-ruang yang terbatas dan seringkali bersifat bawah tanah. Aksi-aksi serikat buruh untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih layak pun harus bertaruh nyawa. Tentu kita masih ingat peristiwa pembunuhan Marsinah pada 1993.
Seiring munculnya kebebasan berserikat—meski tetap saja ada upaya-upaya pemberangusan—setelah Orde Baru runtuh, kondisi kehidupan kelas buruh pun bukan hanya kembali ramai diperbincangkan tapi juga semakin luas diperjuangkan secara terbuka. Sudah banyak keberhasilan yang diraih oleh gerakan kelas pekerja. Namun, seiring kian intensifnya pengelabuan hubungan kerja di tengah menjamurnya bisnis teknologi saat ini, kesalahpahaman mengenai posisi kelas buruh pun kembali menguat. Kita bisa ambil contoh manipulasi diksi seperti pekerja start-up yang kerap disebut “entrepreneur”, atau pengemudi ojek online yang disebut “mitra”.
Kendati demikian, berbagai usaha untuk menjelaskan kenyataan-kenyataan sosial yang kadang tak kasatmata telah dilakukan. Di ranah pendidikan, situasi salah kaprah mengenai kelas buruh dan kehidupannya sudah mulai dibongkar secara mendalam di beberapa kampus lewat mata kuliah seperti politik perburuhan. Selain itu, riset-riset di Indonesia pun mulai banyak bermunculan, meski yang memijakkannya pada perspektif kelas dan perjuangan kelas masih terbatas jumlahnya.
Dengan kata lain, banyak riset mengenai kondisi pekerja di Indonesia sifatnya normies belaka seperti yang dilakukan oleh World Bank.
Selain dapat meluruskan berbagai kesalahpamahan yang terjadi di masyarakat tentang kelas buruh, riset tentang kelas pekerja dengan perspektif kelas dapat menjadi salah satu amunisi penting dalam aktivisme sosial. Oleh karena itu, dalam Batjaan Liar kali ini, saya akan memberikan rekomendasi 10 buku yang harus dibaca agar risetmu (kalau mau riset, ya) soal kelas buruh tidak se-normies laporan World Bank dan konco-konconya.
1. The Condition of the Working Class in England (Friedrich Engels, 1845)
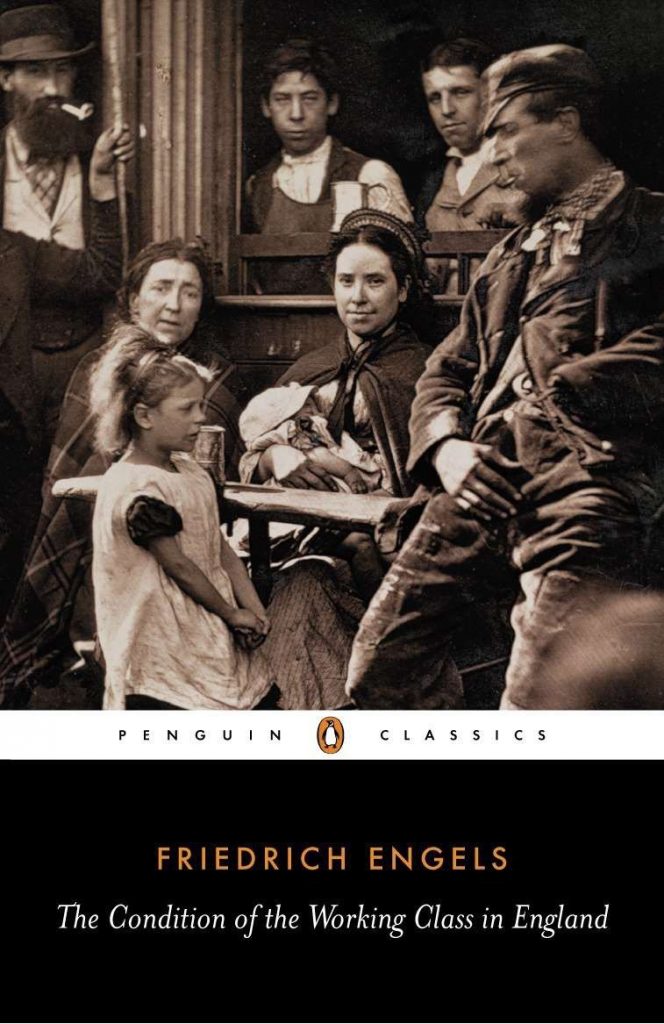
Karya Friedrich Engels (ilmuwan tandem Karl Marx) ini pertama kali terbit pada 1845. Buku yang mengambil lingkup kota industri di Inggris sekitar abad 19 ini adalah salah satu contoh terbaik bagaimana riset tentang kelas pekerja itu semestinya dilakukan. Buku ini wajib dibaca siapa pun yang ingin meneliti kondisi kelas buruh di mana pun, termasuk di Indonesia. Saya memiliki tiga argumen.
Pertama, buku ini membahas kondisi kelas pekerja secara komprehensif. Mulai dari situasi sosial ekonomi politik yang melatari kehidupan buruh; kondisi umum di tempat kerja, seperti jam kerja, upah, kesehatan dan keselamatan buruh di tempat kerja, termasuk dampaknya pada kesehatan mental pekerja; hingga kehidupan buruh sehari-hari, bagaimana tempat tinggal buruh, relasi sosial buruh di dalam rumah tangga dan masyarakat. Dengan kata lain, buku ini menyumbangkan ide mengenai tema-tema apa saja yang dapat diteliti soal kondisi kehidupan kelas buruh.
Kedua, melalui buku ini kita dapat mempelajari bagaimana Engels menggunakan metode penelitian yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ia ajukan. Condition of the Working Class menunjukkan keberhasilan Engels menjawab pertanyaan penelitian mengenai kondisi kelas pekerja di Inggris pada abad ke-19 dengan memadukan data-data kuantitatif dan kualitatif, serta observasi etnografis.
Ketiga, Condition of the Working Class menyediakan panduan mengenai cara-cara menganalisis persoalan kehidupan kelas buruh dari perspektif kelas. Dengan bernas, Engels bisa menjelaskan bagaimana eksploitasi kelas kapitalis terhadap kelas pekerja telah menimbulkan kesengsaraan yang luas dan dalam pada kelas pekerja ketika itu.
Lewat buku ini, kita akan memahami bahwa antagonisme kelas antara pekerja dan pengusaha/pemilik modal tidak terdamaikan.
2. Value Chains: The New Economic Imperialism (Intan Suwandi, 2019)
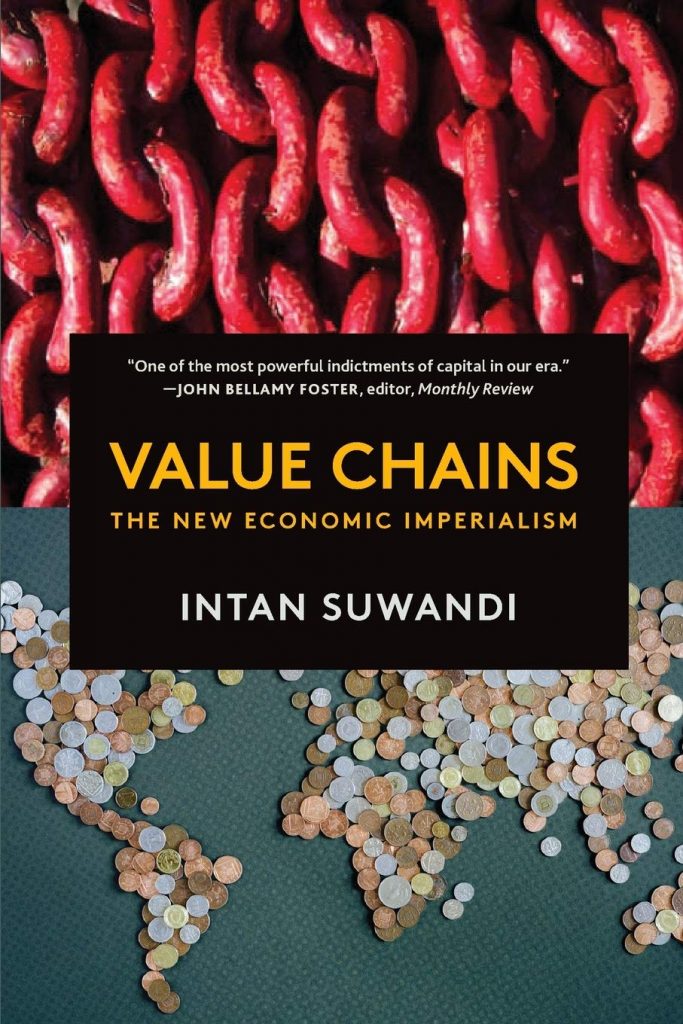
Buku yang ditulis oleh Intan Suwandi—akademisi dan peneliti Marxis asal Indonesia—ini memberikan dasar-dasar teoretis tentang kondisi ekonomi politik yang melatari dan menentukan kehidupan kelas buruh secara global. Saya pernah mengulas buku ini beberapa waktu lalu.
Dengan menggunakan sudut pandang Marxis, Intan membuktikan bahwa imperialisme masih eksis dalam rantai komoditas global (global comodity chain) dan rantai nilai global (global value chain). Intan melakukan analisis atas bentuk kontemporer dari imperialisme dengan melihat kesenjangan antara global north (negara-negara Utara) dan global south (negara-negara Selatan), yang berpartisipasi dalam skema rantai komoditas dan nilai di atas tadi. Value Chains menjelaskan mengapa buruh-buruh di negara-negara dunia Selatan—seperti Indonesia—akan selalu mendapatkan tingkat upah yang rendah, sembari terus didesak untuk meningkatkan produktivitas.
Pendeknya: diupah semurah mungkin tapi terus-terusan dituduh malas.
Selain itu, Value Chains juga menyediakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: pertama, mengapa lokasi-lokasi produksi komoditas selalu berada di negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, Filipina, India, Bangladesh atau Sri Lanka, sementara kantor-kantor pusatnya kebanyakan berada di negara-negara kapitalis lanjut seperti negara-negara Eropa atau Amerika Serikat; kedua, mengapa pasar tenaga kerja fleksibel dengan sistem kerja casual yang selalu menjadi pilihan dan menjadi kian intensif di seluruh dunia; ketiga, mengapa kontrol atas proses produksi menjadi kunci dari jalannya akumulasi kapital sehingga tempat kerja sesungguhnya adalah battle ground dari kelas buruh; hingga keempat, mengapa negara-negara berkembang di dunia ketiga/dunia Selatan memiliki tingkat polusi udara dan pencemaran lingkungan yang tinggi lagi berbahaya.
Singkatnya, buku ini sangat berguna bagi siapa pun yang ingin melakukan riset tentang kelas pekerja, karena dapat memberikan konteks ekonomi politik yang lebih luas mengenai kondisi kelas buruh yang kita teliti di tempat tertentu.
3. Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression (diedit oleh Tithi Bhattacharya, 2017)
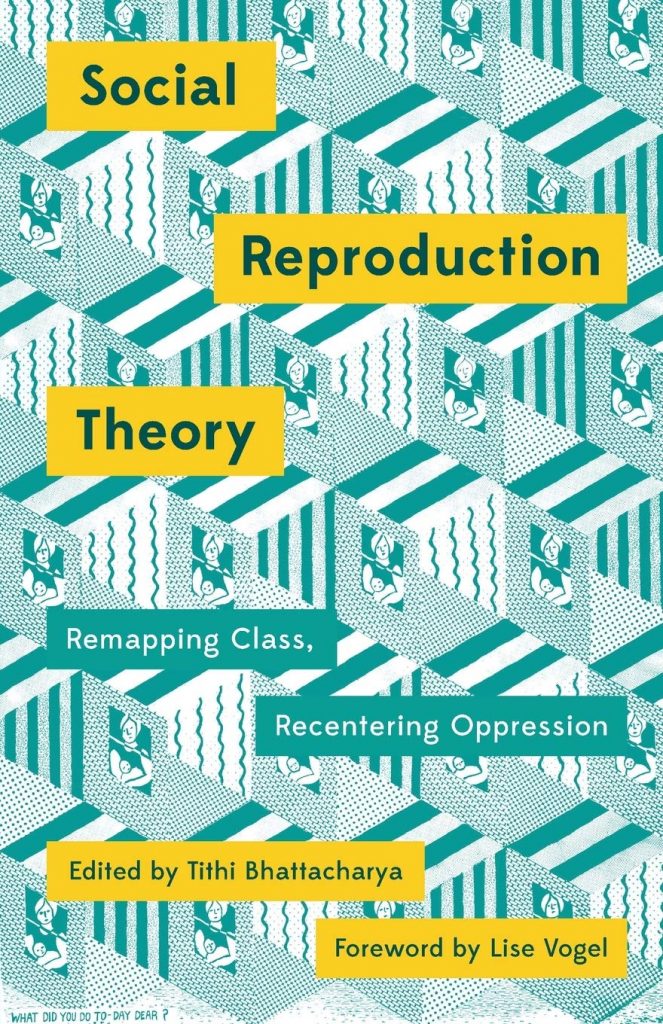
Setelah membaca buku Silvia Federici berjudul Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle (2012), saya menyadari kelindan erat antara kapitalisme dan patriarki sangat menentukan kondisi kehidupan kelas buruh di mana pun, termasuk di Indonesia. Beban kerja ganda yang dihadapi oleh perempuan dan feminisasi kerja, misalnya, merupakan hasil dari persinggungan yang erat dari kapitalisme dan patriarki. Oleh karena itu, ketika meneliti kondisi kelas pekerja, kita sudah tidak bisa lagi mengabaikan pertautan erat antara eksploitasi kelas pekerja dan ideologi supremasi laki-laki.
Di dalam buku yang terdiri atas 10 bab ini, tautan erat kapitalisme dan patriarki dijelaskan melalui teori-teori mengenai reproduksi sosial. Tulisan-tulisan para scholar di Social Reproduction Theory membongkar kenyataan tak kasatmata bahwa kapitalisme sesungguhnya bergantung dan ditopang oleh kerja-kerja reproduksi sosial, yang selalu dibebankan kepada perempuan. Kerja-kerja reproduksi sosial yang menciptakan beban ganda bagi perempuan seperti memasak, mengurus anak, membersihkan pakaian, dan sejenisnya ini, hampir selalu tidak dianggap sebagai sebuah kerja padahal posisinya amat krusial dalam kapitalisme.
Terkait itu, perjuangan para feminis Marxis otonomis seperti Silvia Federici dalam mengampanyekan Wages for Housework atau upah untuk kerja domestik pada 1970-an dapat dilihat sebagai upaya untuk mengakui bahwa reproduksi adalah bagian krusial dan tak terpisahkan dari kapitalisme, dan realm-nya tidak berada pada realm ‘of leisure’. Adapun para pekerja reproduksi sosial yang dibayar, seperti para pekerja di bidang pendidikan dan kesehatan, juga tengah berada di dalam masalah yang sama, yakni crisis of care (Fraser, 2017).
Selain karena menyediakan dasar teori mengenai reproduksi sosial dari berbagai sudut pandang—namun tetap menekankan pada posisinya di dalam kapitalisme—buku ini juga dapat menstimulasi periset dalam melihat tema soal kerja apa yang belum pernah diteliti atau cenderung dilupakan dalam riset-riset mengenai kelas buruh.
4. Bullshit Jobs: A Theory (David Graeber, 2019)
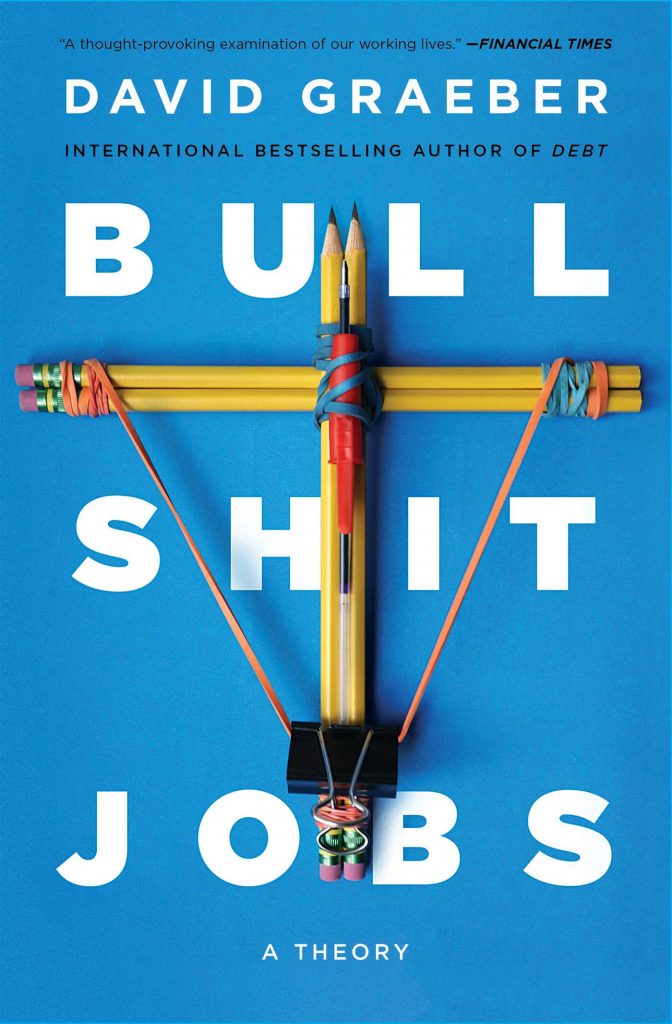
Buku yang ditulis oleh David Graeber–antropolog dengan pandangan politik radikal yang baru saja wafat—ini adalah salah satu karya riset yang paling menarik tentang kondisi kelas pekerja hari ini. Saya mengulas Bullshit Jobs secara khusus beberapa waktu lalu.
Dalam buku setebal 333 halaman ini, Graeber menumpahkan kegelisahannya mengenai bullshit jobs: pekerjaan-pekerjaan yang jika dilenyapkan pun tak akan membuat dunia terlihat berbeda. Graeber menulis berdasarkan pengakuan para pekerja yang berkorespondensi dengannya. Ia mengategorikan dan mendeskripsikan jenis-jenis pekerjaan yang termasuk ke dalam kategori bullshit jobs dan menganalisis mengapa serta bagaimana bullshit jobs terus berproliferasi di dunia. Selain itu, Graeber juga mengulas soal shit jobs atau pekerjaan-pekerjaan penting dan bermanfaat bagi masyarakat, yang dijalankan oleh para buruh dalam kondisi kerja yang buruk. Para pekerja cleaning service di kampus, misalnya.
Graeber berargumen bahwa berkembangnya bullshit jobs hingga saat ini berhubungan dengan dua hal. Pertama, menjamurnya bullshit jobs selaras dengan penurunan sektor agrikultur dan peningkatan service economy. Kedua, keberadaan bullshit jobs sejalan dengan logika feodalisme yang ada di dalamnya. Logika feodalisme dalam bullshit jobs ini, menurut Graeber, merujuk pada kebutuhan kapitalis dalam menunjukkan posisi mereka di kalangan kapitalis lainnya.
Meski terdengar masuk akal, namun menurut saya, tesis Graeber ini kurang memasukkan dimensi yang krusial, yakni “race to the bottom”, yaitu kolaborasi antara kelas kapitalis dan negara—yang selalu ada bersama kepentingan kelas kapitalis—yang berlomba-lomba untuk meningkatkan tingkat keuntungan/profit dengan menciptakan iklim yang baik bagi dunia investasi. Graeber luput mendiskusikan race to the bottom karena para pekerja yang berkorespondensi dengannya tinggal di negara-negara Eropa, AS, dan Jepang (negara-negara Utara). Dalam hal ini, ketika calon tenaga kerja di negara-negara Utara siap-siap menghadapi bullshit jobs, para calon tenaga kerja di Afrika, sebagian besar Asia, dan Amerika Selatan (negara-negara Selatan) siap-siap menghadapi shit jobs. Meski tentu saja kedua jenis pekerjaan ini tetap menjamur, baik di negara-negara Utara maupun Selatan.
Membaca buku ini membuat saya berpikir bahwa sesungguhnya kata-kata Marx: “From each according to their ability and to each according to their needs” adalah jawaban penyelesaian atas kondisi-kondisi kerja seperti bullshit jobs dan shit jobs yang dipaparkan Graeber dalam buku ini.
5/6. Buruh Menuliskan Perlawanannya (2015) dan Menolak Tunduk (2016)

Sebelum melakukan riset soal kondisi kelas buruh/pekerja, ada baiknya untuk baca dulu dua buku yang ditulis langsung oleh buruh dan aktivis serikat serta gerakan pekerja di Indonesia ini. Dua buku ini—masing-masing setebal 482 dan 426 halaman—adalah kumpulan tulisan mengenai pengalaman 27 buruh dan aktivis buruh berjuang di sektor ketenagakerjaan. Mereka menuturkan perjalanan hidup secara lengkap, dari mengapa menjadi buruh (yang kebanyakan buruh pabrik), kondisi kehidupan sehari-hari, hingga proses ketika memutuskan menjadi aktivis serikat dan gerakan buruh.
Dua buku ini akan membuat kita memahami dinamika kerja para aktivis buruh dan relasi-relasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Relasi-relasi sosial ini misalnya, seperti para aktivis buruh perempuan menghadapi situasi patriarkis dalam kehidupan dan perjuangan mereka, bagaimana mereka berhadapan langsung dengan bos di tempat kerja, dan sebagainya. Selain itu, para penulis juga secara rinci menceritakan dinamika perlawanan yang mereka lakukan, mulai dari mengorganisir pemogokan, mengajak teman-temannya untuk berserikat, hingga menyiapkan pendidikan di serikat.
Melalui dua buku ini, kita mungkin menemui perspektif berbeda soal kehidupan kelas buruh/pekerja, yang kemudian dapat membantu kita untuk memformulasikan pertanyaan penelitian atau bahkan merumuskan ulang pertanyaan awal yang hendak kita jawab dalam riset kita.
7. Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi, dan Proletariat Informal di Indonesia sejak 1980an (Muhtar Habibi, 2016)
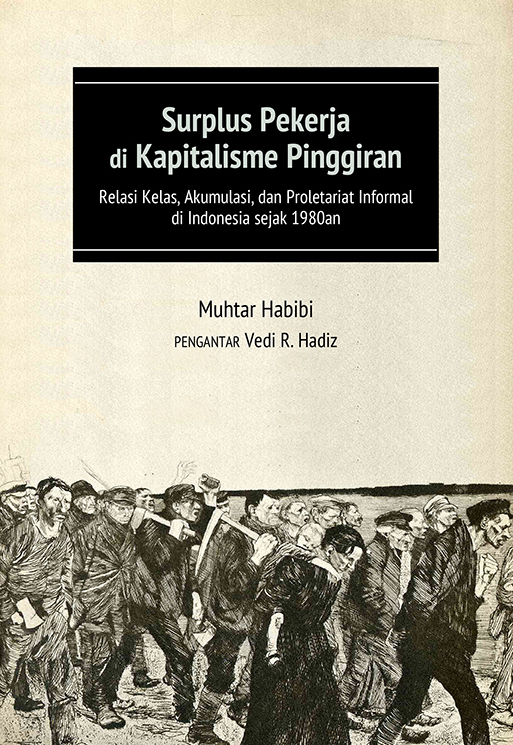
Buku nomor tujuh yang saya rekomendasikan ini bisa membantu peneliti melihat kelas buruh/pekerja dalam dimensi yang lebih luas. Dalam buku ini setebal 141 halaman ini, Muhtar Habibi—ilmuwan sosial asal Indonesia—membahas fenomena membludaknya para pekerja di sektor ekonomi informal lewat teori Marxis mengenai surplus populasi relatif. “Surplus populasi relatif” merujuk pada “para pekerja yang tidak terserap oleh akumulasi produktif kapital”, seperti proletariat informal atau pekerja lepas yang bekerja di sektor informal dan pengangguran. Secara spesifik, ia juga mengidentifikasi tipe-tipe pekerja dengan kondisi kerja rentan berdasarkan jenis-jenis surplus populasi dalam teori Marx.
Muhtar menganalisis tingginya jumlah pekerja—yang dihantui kerentanan—di sektor informal ini dengan melihat hubungan antara lemahnya proses industrialisasi dengan reorganisasi sektor pertanian di negara neoliberal Indonesia. Dalam hal ini, turunnya penyerapan pekerja di sektor industri berdampak pada meluasnya pekerja rentan di sektor informal. Kemudian, reorganisasi neoliberal sektor pertanian sejak 1980-an juga telah berkontribusi pada tingginya “global depeasanization” atau fenomena yang menunjukkan anjloknya jumlah petani yang memiliki akses langsung terhadap alat produksi (tanah). Hasilnya, banyak surplus pekerja dari sektor pertanian tidak terserap di sektor ekonomi produktif sehingga akhirnya mereka berada di dalam formasi surplus populasi relatif, termasuk menjadi buruh migran.
Lewat buku ini, Muhtar juga mengulas praktik neoliberal di Indonesia dalam kacamata historis. Satu poin penting yang perlu digarisbawahi adalah liberalisasi ekonomi tidak berarti menghapuskan sepenuhnya peran negara dalam mengatur ekonomi, melainkan mereorganisasi peran negara dalam ekonomi dengan melakukan deregulasi dan menciptakan iklim investasi bagi akumulasi kapital.
Sounds so familiar, bukan? Ingat MP3EI dan omnibus law Cipta Kerja bertujuan menghadirkan “iklim yang ramah bagi investasi”?
8. Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process Under Monopoly Capitalism (Michael Burawoy, 1979)
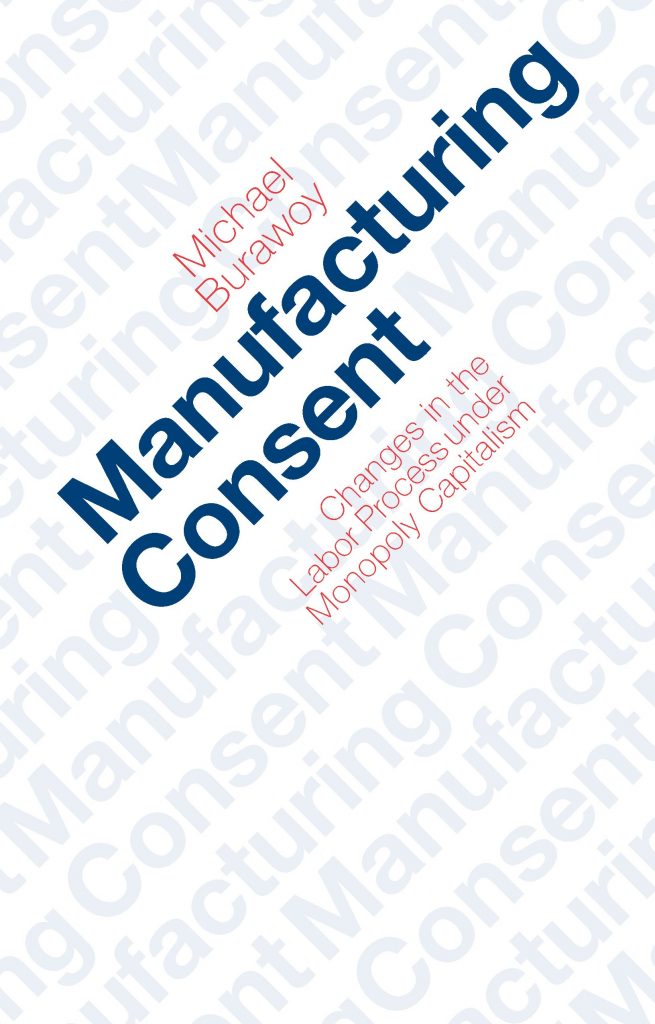
Bicara soal riset kelas buruh/pekerja, buku karya Michael Burawoy—sosiolog Marxis asal Inggris—ini tentunya harus masuk ke dalam list. Karya terbitan tahun 1979 ini adalah salah satu buku yang memberikan contoh terbaik bahwa riset mengenai kelas pekerja dapat dilakukan dengan menggunakan kacamata teoretis empiris yang kuat sekaligus.
Terdiri atas 12 bagian setebal 266 halaman, Manufacturing Consent menceritakan dengan detail hasil studi Burawoy mengenai perubahan-perubahan proses kerja melalui pengorganisasian kerja di level lantai produksi sebuah pabrik mesin selama 30 tahun (1945-1975). Tesis Burawoy: kapitalis secara terus-menerus melakukan penyesuaian-penyesuaian proses kerja dalam rangka mengamankan (securing) proses penghisapan nilai lebih (surplus value), sekaligus menyembunyikan (obscuring) eksploitasi di baliknya. Dalam hal ini, ia membandingkan pengorganisasian kerja di bawah rezim kapitalisme kompetitif dan kapitalisme monopolistik.
Temuan Burawoy: pengorganisasian kerja di bawah rezim kapitalisme monopolistik lebih mengarah pada ‘penundukkan’ pekerja secara hegemonik (melalui pembentukan consent pekerja di lantai produksi) alih-alih despotik (melalui tindakan koersif seperti pemotongan upah, pengawasan kerja yang ketat dan pemecatan sewenang-wenang) sebagaimana terjadi di sektor kapitalisme kompetitif. Lewat buku ini, Burawoy menggunakan konsep metaforik kerja sebagai permainan (game) untuk menjelaskan pengorganisasian kerja melalui pembentukan consent di kalangan pekerja—sebagai cara untuk securing dan obscuring penghisapan nilai lebih tadi. Pembentukan consent melalui proses kerja yang sama dengan (=) game ini kemudian mengaburkan relasi kelas sehingga berhasil dalam mengamankan proses penghisapan nilai lebih/surplus value.
Namun, Manufacturing Consent cenderung mengabaikan fakta bahwa pengorganisasian kerja secara despotik—yang menekankan koersi untuk para pekerja di lantai produksi—juga masih terus terjadi bukan hanya di sektor kapitalis kompetitif tetapi juga di sektor kapitalis monopolistik. Saat ini, kita pun masih dapat melihat contohnya di banyak pabrik di Indonesia. Meski demikian, bagi saya, buku Burawoy ini tetap penting untuk dibaca oleh siapapun yang ingin melakukan riset soal kelas buruh/pekerja karena keunggulannya dalam menampilkan riset yang kuat baik secara teoritis maupun empiris.
9. Against Creativity (Oli Mould, 2018)

Against Creativity membongkar mitos-mitos yang ada seputar pekerja kreatif, kreativitas, dan praktik kerja kreatif itu sendiri (lihat ulasan mengenai buku ini di sini). Saya memasukkan Against Creativity ke dalam list karena karya Oli Mould ini dapat membantu kita mengenali hal-hal terselubung di balik maraknya pengaburan hubungan kerja lewat wacana ‘pekerja kreatif’. Singkat kata, Against Creativity dapat membantu kita melakukan riset tentang kelas pekerja di industri kreatif.
Mould mengungkap problem ‘kreativitas’ yang kini menjadi kosa kata wajib kaum milenial perkotaan yang penuh previlese & ‘tech savvy’. Ia membongkar makna kreativitas yang telah terkooptasi dalam skema pengerukan profit ala neoliberalisme. Menurut Mould, kreativitas hari ini hanya akan bernilai sejauh ia dapat menghasilkan profit. Walhasil, kreativitas di era digital tak lain merupakan kreativitas algoritmik, yang secara esensial menghapuskan daya cipta kita sebagai manusia. Tak heran jika berbagai ungkapan tentang ‘kreativitas’ hari ini bersifat individualistis dengan prasyarat previlese sosial para pelakunya.
Tak semua orang, tegas Mould, bisa menjadi pionir seperti Mark Zuckerberg. Previlese sosial seseorang menjadi prakondisi tak terelakkan. Mayoritas masyarakat lebih sibuk mencari cara untuk keluar dari berbagai kesulitan hidup ketimbang berinovasi menggunakan segenap waktu mencari algoritma mutakhir untuk menciptakan sebuah platform digital. Oleh karena itu, negara mengajak para inovator pionir nan kreatif untuk terus mengkampanyekan ‘enterpreneurship‘ demi menutupi penggerusan social welfare yang terus terjadi.
Kreativitas yang individualistis itu pun menjadi prasyarat lahirnya berbagai jenis ‘creative work‘ yang kemudian menghasilkan berbagai macam kerentanan. Dimensi fleksibilitas dalam industri kreatif mensyaratkan pekerjanya untuk selalu berada dalam mode kerja sepanjang waktu. Sayangnya, kondisi ini belum sepenuhnya dipahami karena ilusi kreativitas yang tercipta telah mengaburkan hal tersebut.
Salah satu buktinya: fenomena ‘artwashing‘ atau gentrifikasi demi penciptaan ruang-ruang kapital atau wilayah-wilayah ‘trendi’ yang dapat menarik investasi. Maka dari itu, Mould menyerukan para ‘pekerja kreatif’ untuk melakukan perlawanan terhadap ‘artwashing‘ dengan selalu mempertimbangkan social ethics mereka di tengah pertarungan bertahan hidup.
Bagi Mould, menjadi kreatif berarti selalu mencari dan membuka kemungkinan terhadap hal-hal yang dianggap mustahil. Ia ingin menegaskan bahwa kreativitas sejatinya ialah manifestasi dari keyakinan bahwa “there are always alternatives!” Dengan kata lain, buku ini kemudian juga dapat mengajak kita untuk memikirkan dan memeriksa ulang tesis-tesis awal yang telah kita buat dalam riset yang akan kita jalankan.
10. Can the Working Class Change the World? (Michael D. Yates, 2018)
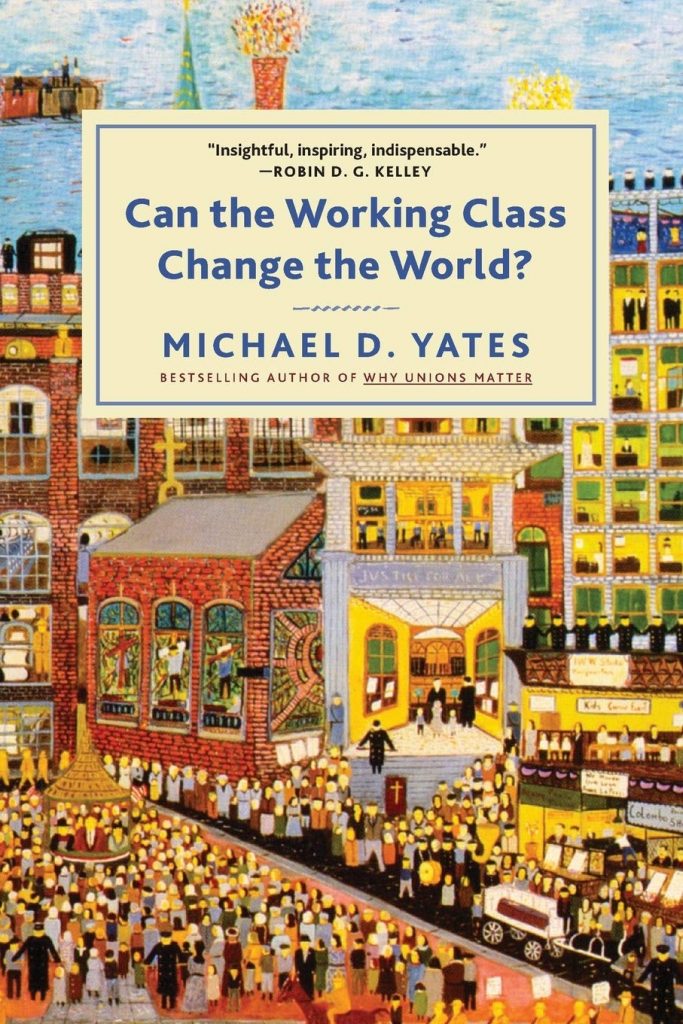
Last but not least, buku karya Michael D. Yates—akademisi Marxis sekaligus direktur Monthly Review Press—ini tak boleh dilewatkan. Di buku yang lebih menyerupai pamflet politik ini, Yates mengajukan tesis mengenai pentingnya orientasi politik buruh dan serikat buruh dalam mengubah kondisi kelas pekerja global. Pada bagian awal buku, Yates menguraikan data mengenai kondisi kelas buruh—dalam dimensi yang luas, artinya tidak terbatas pada mereka yang dikategorikan sebagai kelas buruh secara tradisional saja—mengulas persoalan reproduksi sosial, dan menjelaskan teori-teori dasar yang harus dipahami kelas pekerja, seperti kapitalisme, penghisapan nilai lebih, imperialisme, patriarki, rasisme, dan lain-lain.
Kemudian, Yates menjelaskan pentingnya serikat dan gerakan buruh yang dalam sejarah telah berperan penting dalam menciptakan kondisi kehidupan kerja yang lebih baik di seluruh dunia. Di tengah situasi serba sulit, perjuangan buruh rupanya telah mencapai banyak kemenangan.
Namun, untuk memenangkan pertarungan kelas, serikat dan gerakan buruh perlu melakukan dua hal. Pertama, melampaui berbagai tantangan yang ada seperti individualiasi pekerja yang kian masif, banyaknya involusi yang terjadi di dalam serikat buruh, dan sebagainya. Kedua, memastikan orientasi politik yang jelas. Argumen Yates: keterlibatan gerakan buruh dalam politik merupakan hal yang krusial. Ia pun memberikan contoh-contoh keberhasilan yang telah ada seperti yang ditunjukkan di Kuba, misalnya.
Can the Working Class Change the World? mengingatkan kita bahwa riset tentang kelas buruh perlu memiliki orientasi politik yang jelas agar dapat berkontribusi untuk gerakan buruh dalam pertarungan kelas.
Demi sebuah dunia yang akan kita menangkan.***
Fathimah Fildzah Izzati, peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI dan editor IndoPROGRESS. Ia lulus dari SOAS, University of London program studi MSc Labour, Social Movements and Development pada 2018.
Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda melalui tangan Balai Poestaka berusaha membendung arus penerbitan buku dan artikel karya para aktivis anti-kapitalis dan anti-kolonialis. Barisan literatur yang berperan besar menyuburkan gerakan politik kelas di Indonesia ini dicap Belanda sebagai “batjaan liar”. Kami mengklaim kembali istilah tersebut untuk sebuah rubrik berisi rekomendasi bacaan yang disusun secara tematik untuk merespons berbagai macam isu. Haris Prabowo adalah editor tamu Batjaan Liar. Sehari-hari ia bekerja sebagai jurnalis Tirto.id.