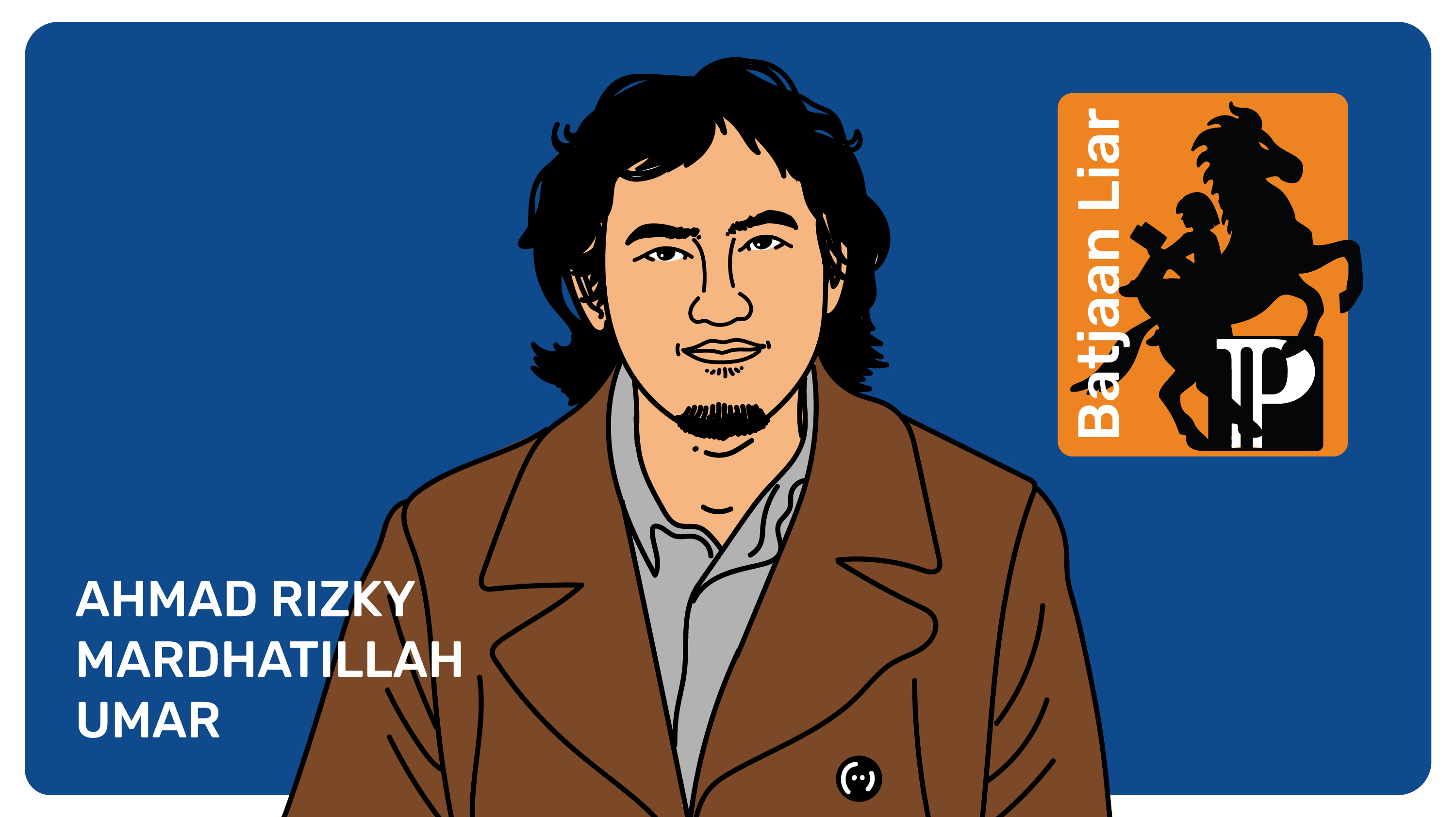Ilustrasi: Deadnauval
KAMU seorang mahasiswa jurusan hubungan internasional (HI) yang tak terlalu tertarik menjadi diplomat? Apakah dirimu berkuliah di jurusan HI namun lebih tertarik ke hal-hal di luar urusan studi HI? Ataukah dirimu berkuliah di jurusan HI, namun lebih senang membaca literatur humaniora lainnya—seperti sastra, sejarah, hingga filsafat—yang bikin rentan ditanya oleh orang tua: “memangnya itu bacaan mahasiswa HI, ya?”
Tenang, kamu tidak sendiri.
Saya ingat, saat masih menjadi mahasiswa baru HI bertahun-tahun lalu, salah seorang dosen—yang kini telah menjadi politikus kondang—melontarkan satu pertanyaan yang pasti dan kudu didengar oleh kami mahasiswa anyar: “siapa yang ingin menjadi diplomat?”. Hampir separuh isi kelas mengacungkan tangan. Namun, belakangan realitasnya jauh dari itu.
Setelah kami lulus, semuanya berubah. Ternyata yang berminat terus masuk korps diplomatik Pejambon—sebutan tenar lokasi Kementerian Luar Negeri yang berada di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat—cuma sedikit. Bayangkan, dari hampir setengah isi kelas tadi, yang berhasil masuk diplomat itu tadi hanya tiga orang. Sisanya? Tersebar di perusahaan multi-nasional, start-up, organisasi masyarakat sipil, lembaga-lembaga internasional, atau yang “apes“, jadi peneliti kacangan—ya, seperti saya ini.
Saya pikir fenomena seperti itu terjadi di banyak kampus. Entah itu kampus yang diklaim terbagus se-Pulau Jawa—yang sebenarnya biasa-biasa saja—maupun kampus-kampus kecil lainnya di setiap pelosok Indonesia. Apalagi ditambah adanya fakta bahwa: makin banyak jurusan HI dibuka, namun Pejambon tak kunjung merekrut pegawai baru. Alhasil, yang diterima menjadi diplomat semakin sedikit ketika lulusan HI melimpah tiap tahunnya.
Masalahnya, di benak para mahasiswa baru HI sudah tertancap impian bahwa menjadi diplomat adalah cita-cita sejak lulus SMA, dan salah satu jalannya adalah dengan menjadi mahasiswa HI. Saat masih berstatus mahasiswa baru, yang sering saya ikuti adalah kegiatan pelatihan semacam table manner yang lengkap dengan simulasi diplomasi persidangan PBB—dan itu cukup membuat kantong mahasiswa kering. Ada juga komunitas yang isinya mengajarkan simulasi persidangan itu, bahkan sampai ke luar negeri.
Namun, semakin kita bergelut dengan skripsi, lalu lulus, dan bekerja, bayangan itu tidak seindah cerita-cerita semasa semester pertama. Kita harus berhadapan dengan dunia yang kian berubah—dengan fakta pahit bahwa lulusan sarjana adalah buruh, yang tidak semuanya punya perlindungan hukum dan finansial. Semua itu ditambah beban kerja yang makin melimpah setelah adanya Omnibus Law berlaku.
Untuk itu, semakin relevan dan penting bahwa stigma “lulusan HI adalah calon-calon diplomat” layak digugat. Padahal, belajar studi HI bukan hanya untuk dapat ijazah keren, lalu kemudian bersaing di pasar tenaga kerja dan mendapatkan pekerjaan mentereng. Mempelajari studi HI adalah belajar tentang kontestasi ragam kekuatan politik yang selalu bertarung untuk mendefinisikan realitas politik internasional hari ini. Pun, sebagian dari realitas itu juga menentukan apa yang kita alami di Indonesia hari ini.
Lho, kok jadi mumet?
Oleh karena itu untuk menghindari kebingungan, saya akan merekomendasikan beberapa buku bagus, yang mungkin bisa jadi referensi alternatif para mahasiswa agar diskursus HI menjadi lebih segar dan kritis, dan tentu saja, sesuai dengan realitas Indonesia hari ini. Mengapa itu semua penting? Agar mahasiswa HI tidak dituding belajar sesuatu yang mengawang-awang nan abstrak, alias tidak bisa diraba karena hanya jadi urusan elite semata.
Di dalam daftar bacaaan ini, ada tujuh buku—plus satu bonus—yang saya rekomendasikan sebagai alternatif teman belajar HI di Indonesia, yang ditulis oleh akademisi asal Indonesia. Mudah-mudah, ini bisa membangun cara berpikir baru tentang studi HI hari ini.
1. Konferensi Asia-Afrika 1955: Asal Usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global Antiimperialisme (Wildan Sena Utama, 2017)
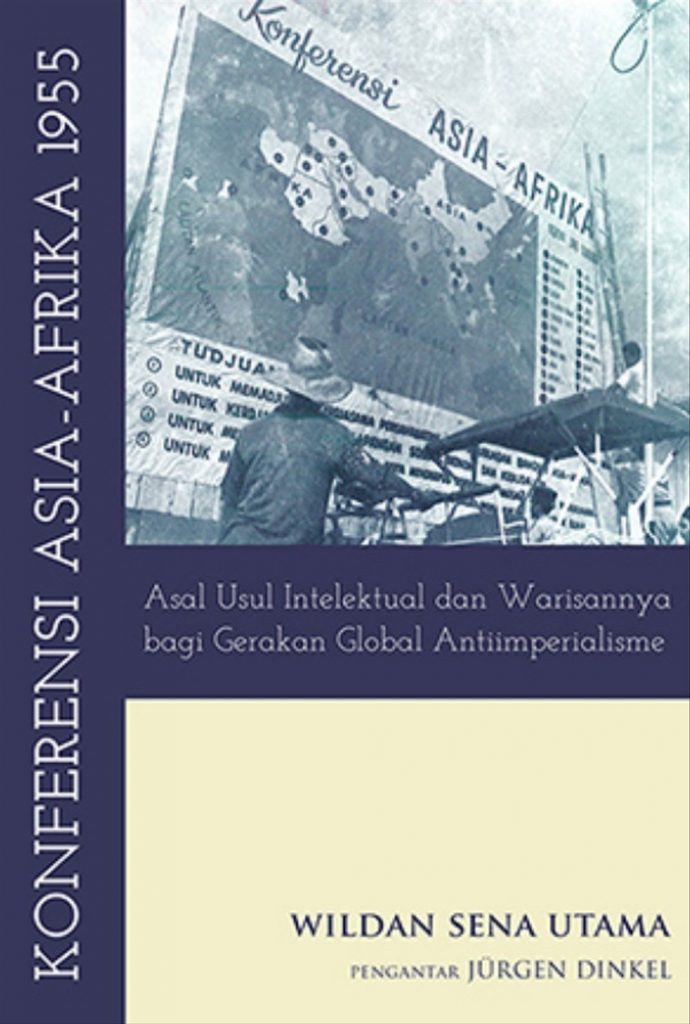
Jika ada satu warisan terbesar Indonesia dalam studi hubungan internasional kontemporer, mungkin Konferensi Bandung tahun 1955 patut menjadi kandidat paling kuat. Diselenggarakan atas sponsor lima negara—yang disebut oleh Cindy Ewing sebagai “Colombo Powers”, yaitu Indonesia, India, Pakistan, Burma, dan Sri Lanka—Konferensi Bandung menjadi satu trademark dari proses ‘dekolonisasi global’.
Buku Wildan Sena Utama menceritakan dengan apik sejarah Konferensi Bandung itu—yang bukan hanya pelaksanaannya, namun juga asal-usul intelektualnya dan warisannya bagi politik internasional hari ini. Sekarang, Konferensi Bandung mungkin hanya menjadi ritual seremonial yang dirayakan setiap tahun atas nama “Kerjasama Selatan-Selatan”. Namun, seperti pernah saya tulis di artikel lain, ratusan negara di seantero Asia dan Afrika berterima kasih pada Indonesia karena Konferensi Bandung membantu mendorong proses ‘dekolonisasi’, sebagai Resolusi Majelis Umum PBB bulan September 1960, yang jadi momen kemerdekaan banyak negara dari kolonialisme Eropa.
Buku ini awalnya ditulis untuk tesis di Leiden University di bawah bimbingan Thomas Lindblad. Konferensi Asia-Afrika 1955 menunjukkan bagaimana proses dekolonisasi tersebut bermula di Bandung dan beberapa konferensi pendahuluan di Kolombo, Bogor, Delhi, hingga Brussels.
Satu pertanyaan yang unik: kenapa penulisnya seorang sejarawan, bukan sarjana HI? Bukankah akan makin banyak orang bertanya “di mana letak HI-nya”? Jangan khawatir, ternyata selain Wildan, ada banyak akademisi studi hubungan internasional dari banyak negara yang juga pernah menulis tentang Konferensi Bandung. Beberapa bisa disebut, seperti Robbie Shilliam dan Quynh Pham, Vijay Prashad, Adom Getachew, hingga Amitav Acharya dan See Seng Tan.
Karya Wildan melengkapi karya-karya mereka dengan perspektif sejarah yang khas, dan tentu saja ditulis dalam bahasa Indonesia. Cocok buat yang ingin belajar HI dengan perspektif sejarah yang kaya.
2. Trilogi Ekonomi-Politik Internasional: Ekonomi Politik-Internasional dan Pembangunan (Mohtar Mas’oed, 1994); 3. Politik, Birokrasi, dan Pembangunan (Mohtar Mas’oed, 1994); dan 4. Negara, Kapital, dan Demokrasi (Mohtar Mas’oed, 1994)

Professor Mohtar Mas’oed sering disebut-sebut sebagai salah satu peletak dasar studi hubungan internasional di Indonesia melalui dua karya klasiknya: satu kitab babon tentang disiplin hubungan internasional, dan terjemahan disertasi doktoral beliau tentang ekonomi dan struktur politik Orde Baru.
Namun, menurut saya, karya beliau yang tak kalah bagus adalah trilogi tentang ‘ekonomi-politik internasional’. Karya pertama mengulas perspektif ekonomi politik tentang pembangunan, yang kedua tentang birokrasi dan politik, dan yang ketiga meletakkan dasar teori tentang negara dan demokrasi—yang juga masih memakai perspektif ekonomi politik yang kental. Ketiga buku tipis ini terdiri dari kumpulan esai yang diterbitkan oleh salah satu penerbit di Yogyakarta yang legendaris bagi para mahasiswa karena harga yang terjangkau: Pustaka Pelajar.
Memang, ketiga buku ini hanya kumpulan esai dan mungkin tidak sekomprehensif buku babon yang saya sebut di atas. Namun, di dalam tiga buku Mohtar ini, ia berusaha membangun cara berpikir ekonomi politik yang kritis-strukturalis untuk memahami diskursus politik internasional. Tiga buku ini berangkat dari disertasinya yang membahas perspektif ekonomi politik guna memahami fondasi struktur politik Orde Baru, yang akhirnya ia perluas spektrum kajiannya untuk ragam isu lain.
Ada banyak karya ekonomi politik internasional di kemudian hari, yang ditulis oleh murid-murid dan koleganya. Salah satunya adalah buku Muhadi Sugiono, Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan di Dunia Ketiga, yang banyak memperkenalkan mahasiswa—saya salah satunya—Antonio Gramsci dan teori-teori sosialisme kontemporer. Saya pernah menulis ulasan bukunya bertahun-tahun lalu di sini. Perspektif strukturalisme yang digunakan Mohtar membikin kita kenal dengan realitas ekonomi politik internasional hari ini, yang jauh lebih kompleks dari sekadar pertarungan diplomat di meja-meja perundingan.
5. Politik Pembebasan: Teori-Teori Negara Pascakolonial (Vedi Hadiz, 1999)

Vedi Renandi Hadiz dikenal luas di kalangan mahasiswa asal Indonesia di Australia, sebagai ‘guru’ kajian Indonesia di Melbourne. Kajiannya bertebaran dalam bahasa Inggris, dari politik perburuhan di Indonesia hingga populisme Islam. Konon, ia cukup disegani di komunitas studi mengenai Indonesia di Australia. Tapi, menurut saya, salah satu karya klasik beliau yang cukup orisinil, menarik, dan mudah diakses oleh mahasiswa berkantong receh seperti saya dulu adalah buku tipisnya tentang “teori negara pascakolonial”.
Buku ini adalah hasil dari skripsinya di Universitas Indonesia di bawah bimbingan Alm. Farchan Bulkin di akhir tahun 1980-an, yang akhirnya diterbitkan oleh INSIST dan Pustaka Pelajar. Lewat buku ini, Vedi berargumen bahwa teori-teori negara pascakolonial, yang dibawa baik oleh teori-teori dependensi maupun perspektif Marxis klasik, gagal menjelaskan banyak fenomena ekonomi politik di banyak negara berkembang. Pasalnya, perspektif mereka cenderung untuk melihat kapitalisme sebagai sesuatu yang berkembang secara global dan gagal menjelaskan variasi dan dinamika struktur ekonomi politik domestik.
Di dalam karyanya ini, ia mengajukan perspektif ‘produksionis’ yang waktu itu baru saja diajukan oleh Richard Robison dan beberapa murid beliau di Murdoch University. Kelak, Vedi melanjutkan studi doktoralnya di bawah bimbingan Robison dan menjadi salah satu intelektual mazhab Murdoch paling terkemuka di eranya.
Menurut saya, buku ini menarik bukan hanya karena argumen teoretisnya, tapi kemampuannya mengkritik beberapa tendensi teoretis di kajian Marxisme masa itu, dan menunjukkan satu perspektif alternatif. Ini sesuatu yang langka untuk sebuah skripsi seorang sarjana. Bahkan seringkali saya menemukan kolega mahasiswa doktoral Indonesia di luar negeri kesulitan mengkaji aspek ini. Kalau ada yang sedang ingin menulis skripsi, buku ini layak jadi salah satu acuan mahasiswa.
6. Value Chain: A New Economic Imperialism (Intan Suwandi, 2019)
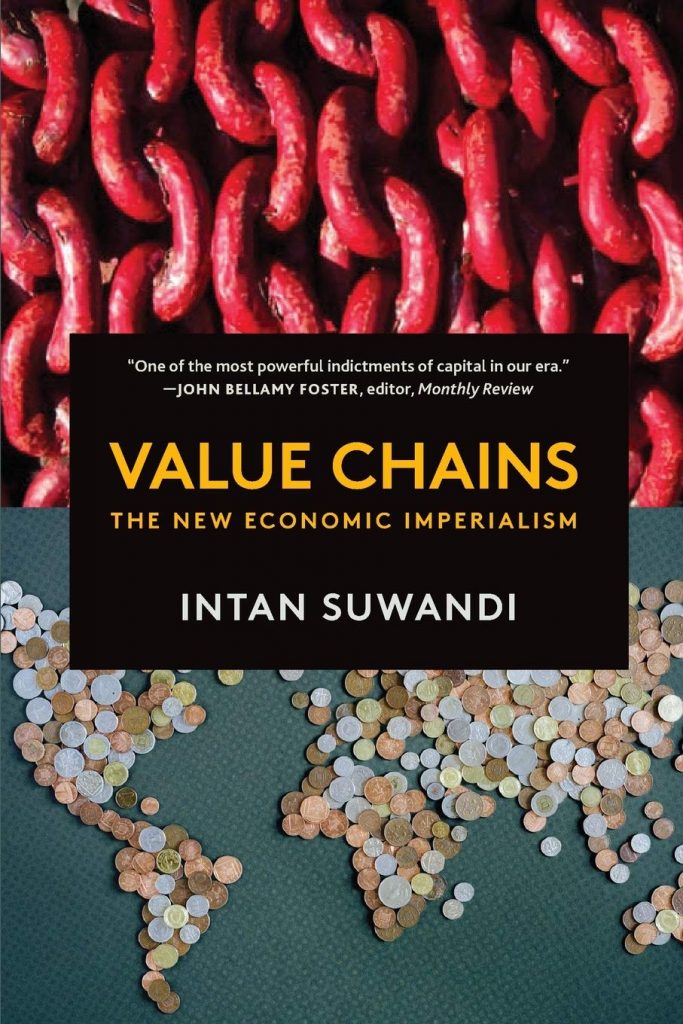
Beberapa waktu lalu, Ingrid Kvangraven menulis satu artikel tentang pentingnya membangkitkan kembali teori dependensi dalam studi ekonomi politik internasional. Salah satu karya baru yang dirujuk oleh Ingrid adalah buku terbaru Intan Suwandi tentang ‘rantai nilai global’. Buku ini lahir dari disertasi doktoralnyadi University of Oregon, yang beliau selesaikan di bawah bimbingan John Bellamy Foster.
Argumen Intan kira-kira seperti ini: kapitalisme global hari ini beroperasi melalui ‘rantai nilai’, yang hari ini bekerja melalui outsourcing dan rezim upah murah untuk memproduksi barang-barang mahal bermerk di negara-negara maju. Skema rantai nilai global ini menjadikan negara-negara yang tak punya industri—salah satunya Indonesia—sebagai bagian erat dari rantai produksi global, yang menyediakan tenaga kerja berupah murah yang siap dieksploitasi atas nama produktivitas.
Kedengaran familiar dengan keadaan hari ini, bukan?
Di pengantar bukunya, Intan menulis bahwa kajiannya ini terinspirasi dari pengalaman masa kecilnya di Indonesia. Ketika ada bangunan-bangunan besar milik orang kaya yang bersanding dengan gubuk-gubuk reot adalah bagian dari realitas normal masa itu. Anak-anak yang terlahir kaya memiliki sepatu bermerk Nike dan Adidas mahal, kebingungan tentang nasib Indonesia sebagai “dunia ketiga”, dan para pekerja serabutan yang bangun pagi sekadar untuk mencari nafkah.
Menurut Intan, realitas semacam ini justru menimbulkan pertanyaan: apa yang jadi akar masalahnya secara global? Jawaban yang ditemukan Intan: dari satu untaian rantai yang terhubung secara global—dari pekerja di pabrik, manajer-manajer perusahaan di Jakarta, konsultan manajemen di berbagai kota besar, hingga eksekutif di negara-negara maju. Jawaban ini melahirkan kesimpulan bahwa praktik produksi semacam ini adalah bagian dari imperialisme global baru.
Buku ini mendapatkan penghargaan Paul Baran-Paul Sweezy Award sebagai buku terbaik kajian sosiologi ekonomi di Amerika Serikat—diberikan oleh American Sociological Association. Sebagian isinya bisa diakses di sini.
Kendati demikian, buku ini tetap bagus untuk menambah referensi kita tentang ekonomi politik internasional hari ini—terutama karena realitas yang diangkat juga tidak jauh dari sekitar kehidupan Indonesia. Bagi rekan-rekan mahasiswa Indonesia di luar negeri (apalagi yang sekolah dengan beasiswa), buku ini mungkin bisa jadi referensi bagus untuk dibeli.
7. Competitive Pressure and Labour Rights (Hariati Sinaga, 2020)
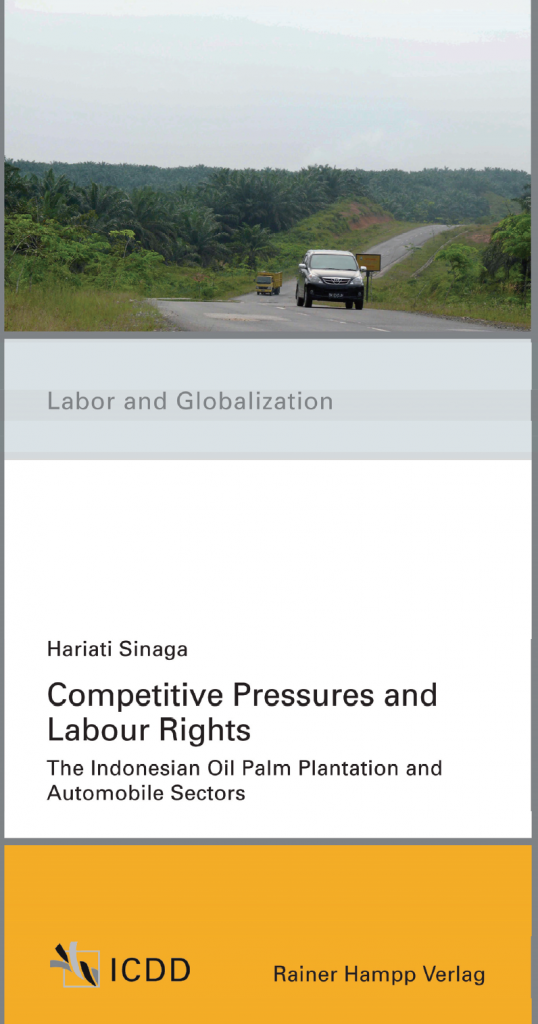
Dikenal di Twitter sebagai @buruhsiluman, Hariati Sinaga punya kajian yang cukup segar dan baru tentang model produksi global yang baru berkembang dalam satu dasawarsa terakhir yang didorong oleh liberalisasi perdagangan. Kajiannya cukup spesifik: tentang hak-hak buruh. Lagi-lagi, mungkin orang akan bertanya: ini HI-nya di mana? Padahal, diskusi tentang hak-hak buruh sudah menjadi bagian dalam pembahasan politik internasional sejak era Karl Marx.
Buku ini baru saja diterbitkan oleh Rainer Hampp Verlag, sebuah penerbit di Jerman.
Argumennya cukup menarik dan datanya empiris. Menurut Hariati, liberalisasi perdagangan melahirkan model-model kerja dan produksi yang bertitik tumpu pada tenaga kerja (‘labour-intensive’) dan pada gilirannya menindas hak-hak pekerja dengan alasan menaikkan produktivitas.
Mirip dengan kajian Intan, kajian Hariati Sinaga melihat rantai produksi sebagai sesuatu yang terhubung secara global, dan menurutnya malah terjejaring melalui liberalisasi perdagangan. Melalui perspektif yang disebut sebagai ‘jejaring produksi global’, Hariati meneliti bagaimana perusahaan mobil Jepang dan kelapa sawit Singapura-Malaysia—serta milik Indonesia—terhubung dengan negara, yang jadi regulator utama perekonomian, untuk memuluskan proses eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja di Indonesia. Konsekuensinya pun cukup banyak terutama bagi hak-hak buruh di Indonesia.
Buku ini lahir dari penelitian Hariati di University of Kassel, Jerman, yang memang cukup terkenal dengan kajian-kajian perburuhan. Kajiannya melengkapi perspektif ‘imperialisme baru’ yang diajukan oleh Intan, dan tentu sangat erat kaitannya dengan kita para pekerja yang siap-siap ditindas oleh satu set peraturan baru melalui UU Cilaka. Buku Hariati Sinaga bisa diunduh secara terbuka di laman ini.
8. Asal-Usul Kedaulatan: Telusur Psikogenealogis atas Hasrat Mikrofasis Bernegara (Hizkia Yosias Polimpung, 2014)

Konon, di antara jajaran editor IndoPROGRESS, Hizkia Yosias Polimpung adalah salah satu yang memiliki banyak fans. Sebagai pengusung perspektif psikoanalisis dan post-strukturalisme yang teguh, tulisan Yosie cukup banyak dijumpai di IndoPROGRESS maupun media lain. Salah satu yang cukup banyak jadi acuan adalah buku beliau tentang Asal-Usul Kedaulatan ini. Asal-Usul Kedaulatan adalah hasil dari tesis di Universitas Indonesia beberapa tahun silam, diterbitkan oleh Penerbit Kepik di Depok.
Dengan menggabungkan psiko-analisis Lacan dan genealogi Foucault, Yosie berargumen bahwa sejak zaman pencerahan hingga sekarang, negara memang didesain untuk mengurus kedaulatan dirinya sendiri di hadapan negara lain, dan tidak pernah benar-benar peduli dengan rakyatnya sendiri. Ini karena ada “hasrat mikrofasis” ketika negara itu dibentuk. Hasrat itu muncul memenuhi tujuan utama negara ketika ia dibentuk oleh para elitenya, yaitu untuk memenuhi kedaulatannya di mata negara lain. Jika ada ada retorika semacam HAM, demokrasi, memenuhi hak rakyat, atau seabreg janji-janji kampanye, ia cuma pemanis yang sifatnya artifisial. Negara dibentuk tidak untuk tujuan itu.
Dari itu semua, Yosie membikin satu teori yang kompleks tentang ‘kedaulatan’ dalam politik global kontemporer.
Bagi yang suka dengan teori (terutama yang kompleks), buku ini patut jadi rujukan. Hanya saja, kelemahannya satu: bukunya agak langka. Kendati demikian, masih ada di beberapa toko daring.
9. Genealogi Sastra Indonesia: Kapitalisme, Islam, dan Sastra Perlawanan (Okky Madasari, 2019)

Buku berikutnya yang akan saya rekomendasikan adalah karya teranyar Okky Madasari tentang sejarah sastra Indonesia. Sekilas, buku ini tidak ada sedikit pun memancarkan atmosfer studi hubungan internasional—selain fakta bahwa Okky adalah lulusan HI Universitas Gadjah Mada. Konon, buku ini lahir dari tesisnya saat studi sosiologi di Universitas Indonesia. Apalagi, Okky dikenal luas sebagai penulis banyak karya sastra berkualitas, dan bukan akademisi HI.
Lagi-lagi akan muncul pertanyaan: di mana letak HI-nya?
Pertanyaan itu akan hilang saat kalian membaca detil isi buku ini. Okky berargumen bahwa sejarah sastra Indonesia pada dasarnya adalah sejarah pertarungan wacana politik, yang dibentuk tidak hanya dalam konteks politik nasional—semisal Lekra versus Manikebu, tapi juga refleksi dari perubahan politik internasional. Okky melacak konflik Lekra dan Manikebu, yang berakhir saat pembantaian sepanjang 1965-1966, dan akhirnya disusul oleh komodifikasi karya sastra setelah Perang Dingin.
Polemik semacam itu, dengan manifestasinya dalam penulisan karya sastra di tingkat lokal, adalah warisan dari pentas politik global masa Perang Dingin antara Blok Barat versus Blok Komunis. Sejarah sastra Indonesia tak lepas seluruh diskursus itu. Bahkan, saat komodifikasi sastra menjadi umum akibat logika pasar yang menggiring pembaca, sastra perlawanan tetap menemukan ruangnya. Cara pandang ini yang menurut saya menarik dan penting untuk melihat penulisan sastra sebagai sesuatu yang terkait dalam pentas ekonomi dan politik global kontemporer.
Buku Okky ini dibaca dengan tandem bersama buku lain dari Almarhum Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca-1965. Almarhum Wijaya menceritakan lebih detil konteks transnasional dari pergulatan wacana sastra sekitar Orde Baru dan reformasi, menjadikan penulisan karya sastra bukan sesuatu yang ‘adiluhung’ atau bebas nilai, tapi terdapat kepentingan rezim politik yang sedang berkuasa. Belakangan, Okky kembali ke dunia HI dengan mencalonkan diri sebagai Ketua KAHIGAMA –Keluarga Alumni HI UGM—meski akhirnya tidak terpilih.
Aksi Massa (1926)
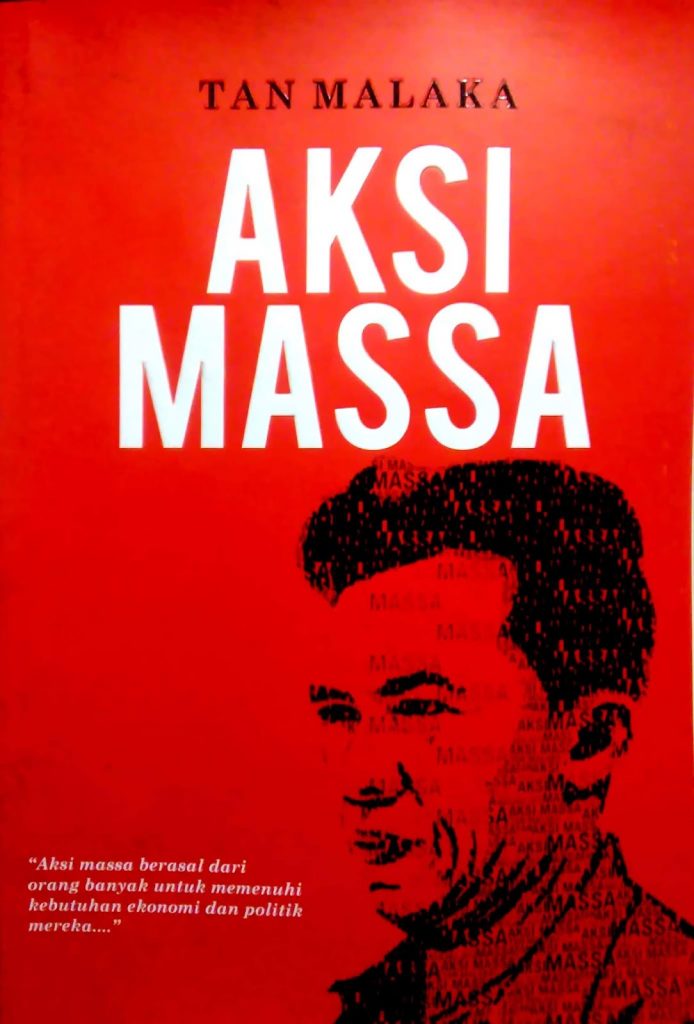
Yang terakhir ini bonus. Buku ini jelas bukan buku akademik hubungan internasional. Penulisnya tidak pernah kuliah, dan malah melajang hingga akhir hayat. Ia teguh dalam perjuangan mewujudkan kemerdekaan Indonesia dari Hindia-Belanda. Tapi siapapun yang pernah membaca karya-karya Tan Malaka, terutama Aksi Massa, kita akan melihat bahwa pemikirannya disandarkan pada analisis tentang situasi politik internasional yang cukup jitu dan unik. Pemikiran Tan adalah perspektif ‘Indonesia’ atas politik global, yang melahirkan gagasan tentang antikolonialisme yang khas.
Tan, sebagaimana tokoh pergerakan lain semacam Soekarno dan Hatta, tidak mendasarkan perjuangan kemerdekaan semata sebagai perjuangan ‘Pribumi versus Asing-Aseng’. Mereka meleburkan diri dalam konteks perjuangan politik global. Soekarno sejak tahun 1928 menulis bahwa gagasan perjuangan Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari Pan-Asianisme. Hatta datang ke pertemuan-pertemuan Liga Melawan Imperialisme di Perancis dan Belgia. Tan Malaka terhubung dengan komunisme global—dan belakangan dipecat dari PKI setelah membelot pada masa pemberontakan 1926-1927. Namun, alih-alih hanya copy-paste wacana komunisme global, Tan punya jalan pikiran sendiri.
Di dalam buku Aksi Massa, ia membayangkan federasi antara Indonesia, Malaya, dan Filipina, sebagai sebuah federasi geopolitik anti-kolonialisme yang memboikot semua moda produksi kolonial. Ia mengagumi Jose Rizal, yang dikenal sebagai bapak nasionalisnya Filipina. Dan perjalanannya dalam pelarian melahirkan gagasan tentang Republik Indonesia, bahkan jauh sebelum Soekarno-Hatta memproklamasikannya tahun 1945.
Sebagai pelengkap, buku Tan Malaka ini cukup memberikan perspektif ‘global’ tentang sejarah Indonesia, yang mestinya dibaca dengan gembira oleh mahasiswa-mahasiswa HI di Indonesia. Tidak kurang karena buku ini memberikan kita fondasi untuk memahami hubungan internasional hari ini, sebagaimana ditunjukkan oleh tujuh karya di atas. ***
Ahmad Rizky M. Umar adalah Mahasiswa Doktoral di University of Queensland, Australia. Aktif menulis untuk kolom Tabayyun dan pernah menjadi peneliti di Pusat Kajian ASEAN, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada.
Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda melalui tangan Balai Poestaka berusaha membendung arus penerbitan buku dan artikel karya para aktivis anti-kapitalis dan anti-kolonialis. Barisan literatur yang berperan besar menyuburkan gerakan politik kelas di Indonesia ini dicap Belanda sebagai “batjaan liar”. Kami mengklaim kembali istilah tersebut untuk sebuah rubrik berisi rekomendasi bacaan yang disusun secara tematik untuk merespons berbagai macam isu. Haris Prabowo adalah editor tamu Batjaan Liar. Sehari-hari ia bekerja sebagai jurnalis Tirto.id.