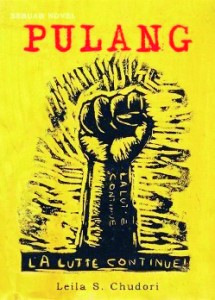Estetika dan Kritik Sosial dalam Karya-karya Oscar Wilde (Bagian 1)
Siapakah Oscar Wilde? Pembahasan atas kehidupan pribadinya yang bohemian dan flamboyan terutama hubungannya dengan Lord Alfres Douglas yang juga membuat dia dipenjara seringkali mengalihkan perhatian khalayak dan menimbulkan kesalahpahaman atas karya-karyanya. Namun, tentu saja ada beberapa hal menarik yang dapat kita kaji dari karya-karya salah satu penulis Anglo-Irlandia paling terkemuka yang juga salah satu seniman aliran estetik-dekaden paling terdepan ini.