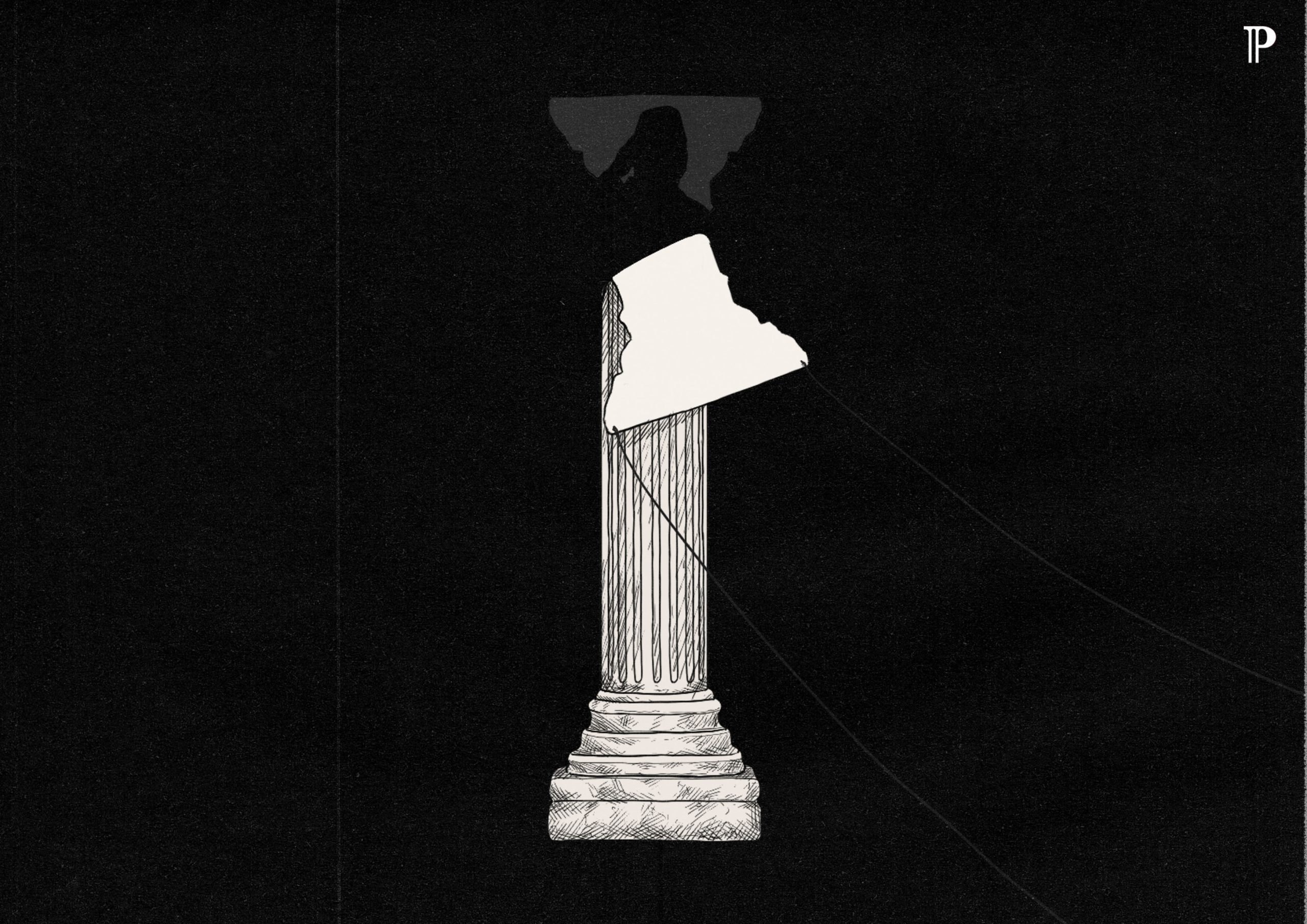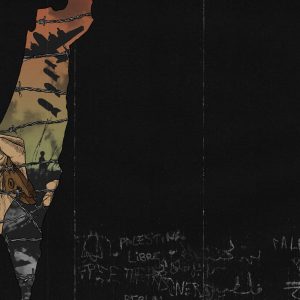Ilustrasi: Illustruth
KEBEBASAN pers merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem demokrasi yang ideal. Namun, di Indonesia, praktik kekerasan terhadap jurnalisme kritis malah semakin sering terjadi. Peristiwa paling terbaru adalah teror terhadap Tempo yang wartawannya dikirimi kepala babi dan bangkai tikus dua hari berturut-turut.
Peristiwa ini mengindikasikan bagaimana kebebasan pers dihadapkan pada represi sistematis, yang salah satunya adalah aksi intimidasi yang bersifat simbolik (Tapsell, 2017). Ada pesan politik yang jelas dari teror ini: bahwa kritik terhadap kekuasaan akan dibalas dengan upaya menakut-nakuti. Aktor represi baik negara maupun non-negara menggunakan kekerasan simbolik untuk mengendalikan wacana publik dan meredam suara kritis. Ini berbahaya sebab ketika media yang memiliki peran sebagai watchdog dipaksa bungkam, masyarakat kehilangan akses terhadap informasi yang akurat dan kritis. Dalam jangka panjang, kondisi ini berkontribusi pada pelemahan demokrasi deliberatif: ruang publik semakin didominasi oleh aktor-aktor yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan mampu memonopoli narasi politik.
Teror ini mencerminkan apa yang oleh para ilmuwan politik sebut sebagai “demokrasi prosedural”—sebuah sistem yang memiliki elemen-elemen demokrasi secara formal tetapi secara substansial masih jauh dari prinsip-prinsip demokrasi sesungguhnya (O’Donnell, 1993). Jika ancaman terhadap kebebasan pers terus dibiarkan tanpa pertanggungjawaban yang jelas (atau dianggap remeh, disebut “jangan dibesar-besarkan” oleh penguasa), maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia tengah mengalami dekadensi. Kepala babi dan bangkai tikus menjadi simbol dari erosi demokrasi yang kian nyata.
Berjalan Mundur, Jauh Sekali
Dalam hak asasi manusia (HAM), negara memiliki peran sentral sebagai duty bearer yang wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga (Smith, et al. 2008). Prinsip ini mengacu pada tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa kebebasan sipil—termasuk kebebasan pers—tidak hanya dijamin dalam norma hukum tetapi juga dilindungi dalam praktik.
Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang menjamin kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Sementara Pasal 28F pada intinya menegaskan hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pun menegaskan bahwa negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara—termasuk hak atas kebebasan berekspresi.
Dalam hal kebebasan pers, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara eksplisit melindungi kerja jurnalistik dari segala bentuk intimidasi dan intervensi. Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa “Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran.” Bahkan, Pasal 18 UU a quo menyatakan bahwa tindakan menghalangi atau menghambat kerja jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana dan denda.
Selain regulasi nasional, Indonesia pun telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang menjamin kebebasan pers dan hak atas kebebasan berekspresi. Misalnya Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki kebebasan berpendapat tanpa gangguan serta berhak mencari, menerima, dan menyebarkan informasi melalui media apa pun. Prinsip ini diperkuat oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 19.
Seluruh ketentuan itu kian tidak berarti apa pun. Dalam berbagai kasus, termasuk teror terhadap Tempo, negara abai dalam menjalankan mandatnya sebagai duty bearer. Toh sebelum Tempo ada kasus lain yang tidak kalah menyita perhatian publik, yaitu Narasi yang mengalami serangan siber.
Alih-alih memberikan perlindungan, aparat sering kali lamban menindak kasus-kasus terhadap jurnalis. Dalam praktiknya regulasi sering kali diabaikan, terutama ketika pers mengkritik aktor-aktor yang kuat baik secara politik maupun ekonomi. Ketidaktegasan negara dalam menindak pelaku teror semacam ini menimbulkan efek ketakutan (chilling effect) yang berujung pada pembungkaman kritik dan degradasi demokrasi. Fenomena ini menunjukkan bagaimana demokrasi di Indonesia mengalami regresi menuju demokrasi iliberal (illiberal democracy): institusi demokrasi tetap beroperasi secara formal tetapi kebebasan sipil semakin dikekang (Robet, et. al. 2020).
Atas dasar ini semua, kita tidak bakal heran membaca laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) yang menyimpulkan indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan. Faktor utama dari kemunduran ini tidak lain adalah meningkatnya kontrol terhadap media dan pembatasan kebebasan berekspresi. Salah satu alat yang digunakan untuk membungkam kritik adalah UU ITE. Pasal-pasal karet dalam peraturan itu kerap digunakan untuk menjerat jurnalis dan aktivis yang mengungkap ketidakadilan.
Fenomena digital authoritarianism semakin menguat. Pemerintah menggunakan teknologi untuk mengawasi, mengontrol, dan bahkan membatasi akses terhadap informasi yang dianggap mengancam stabilitas politik mereka. Pemblokiran situs berita independen, serangan siber terhadap media kritis, serta penyebaran propaganda digital menjadi bagian dari strategi baru dalam membungkam kebebasan pers.
Ketika pers tidak lagi bebas, maka ruang publik untuk berdiskusi dan mengkritik kebijakan pemerintah semakin menyempit. Hal ini berbahaya karena tanpa pengawasan yang ketat dari media, pemerintah dapat bertindak sewenang-wenang tanpa takut dikoreksi. Demokrasi tanpa kebebasan pers hanya akan menjadi demokrasi semu.
Ada pula tanda-tanda lain mundurnya demokrasi di Indonesia, menurut indikator dari Levitsky dan Ziblatt dalam How Democracies Die (2018).
Penolakan atau lemahnya komitmen terhadap aturan demokrasi
Dalam beberapa tahun terakhir, pelbagai tindakan pemerintah dan elite politik mencerminkan melemahnya komitmen terhadap aturan demokrasi. Misalnya wacana amandemen konstitusi khusus untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Penggunaan aparat untuk kepentingan politik pun semakin terlihat dalam pemilihan umum. Netralitas aparat dalam pemilu kerap dipertanyakan karena ada indikasi petahana menekan lawan politiknya dan menggunakan sumber daya negara. Ada pula regulasi-regulasi yang membatasi hak-hak sipil seperti UU ITE dan KUHP. Peraturan tersebut mengandung pasal-pasal karet yang menjadi instrumen untuk mengontrol kebebasan berpendapat dan menghambat kritik terhadap pemerintah.
Menolak legitimasi oposisi
Delegitimasi terhadap oposisi semakin sering terjadi dalam lanskap politik Indonesia. Pemerintah dan elite yang berkuasa kerap menggunakan narasi bahwa oposisi adalah ancaman bagi stabilitas nasional. Oposisi sering kali dikategorikan sebagai “anti-pemerintah”, “anti-NKRI”, “anti-Pancasila”, atau bahkan “pro-radikalisme”. Ini tidak hanya membatasi ruang kritik, tetapi juga menciptakan ketakutan di tengah masyarakat untuk bersikap kritis. Pelbagai instrumen hukum pun digunakan untuk melemahkan oposisi. Kasus-kasus hukum yang menimpa beberapa tokoh oposisi sering kali dapat dianggap bermuatan politis. Dengan kata lain, kriminalisasi.
Toleran atau bahkan mendorong kekerasan
Indikasi kemunduran demokrasi juga terlihat dari meningkatnya toleransi terhadap kekerasan politik. Kasus seperti serangan terhadap aktivis lingkungan dan pembela HAM sering kali diabaikan atau bahkan direspons dengan kriminalisasi. Aparat yang melakukan kekerasan dengan pentungan dan senjata lain untuk meredam demonstrasi pun semakin lazim terjadi. Lihat saja apa yang terjadi belakangan ini terhadap para demonstran yang menolak revisi UU Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Diam Bukan Pilihan
Demokrasi di Indonesia semakin hari kian kehilangan substansi. Kebebasan pers, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi, jelas menghadapi ancaman nyata dari pihak-pihak yang alergi kritik. Teror ini mengingatkan kita pada praktik otoritarianisme di masa lalu yang suka sekali membungkam media dengan cara-cara menyerupai mafia. Jika pola-pola intimidasi semacam ini terus dibiarkan, maka ruang sipil akan semakin menyempit, dan kita hanya akan menyaksikan demokrasi yang bersifat prosedural tanpa substansi.
Jurnalis bukan musuh negara. Mereka adalah pilar penting dalam menjaga transparansi, mengungkap kebenaran, dan memastikan kekuasaan berjalan dengan pengawasan. Jika mereka terus diteror, siapa lagi yang akan berani menyuarakan suara rakyat? Jika ancaman terhadap jurnalis dibiarkan tanpa penyelesaian yang adil, maka bukan tidak mungkin ke depan akan semakin banyak suara yang dibungkam. Demokrasi yang semestinya berfungsi sebagai ruang dialektika dan artikulasi kepentingan rakyat justru dikooptasi menjadi alat legitimasi penguasa. Pemilu mungkin tetap diselenggarakan, tetapi pilihannya telah dimanipulasi. Kebebasan berpendapat mungkin tetap dijamin, tetapi setiap kritik dibungkam dengan pelaporan atau ancaman.
Masyarakat sipil tidak boleh tinggal diam. Ketika kekuasaan menggunakan intimidasi sebagai senjata, maka kita harus menjadikan keberanian dan solidaritas sebagai tameng. Demokrasi bukan hanya soal prosedur elektoral, tetapi juga perkara keberanian untuk melawan ketidakadilan dan membela kebebasan yang semakin tergerus. Jika kita memilih diam, maka bukan hanya kebebasan yang hilang, tetapi juga masa depan yang adil dan demokratis bagi generasi mendatang.
Kami bersama Tempo! Kami bersama kebebasan pers! A luta continua, viva comrades!
Referensi
Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die. Penguin Us.
O’donnell, G. (1993). Delegative Democracy? Kellogg Institute.
Rhona K.M. Smith et al. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. PUSHAM UII.
Robet et al. (2020). Kultur Hak Asasi Manusia di Negara Iliberal. Marjin Kiri.
Tapsell, R. (2017). Media power in Indonesia: oligarchs, citizens and the digital revolution. Rowman & Littlefield International, Ltd.
Raihan Muhammad, Direktur Eksekutif Amnesty International UNNES