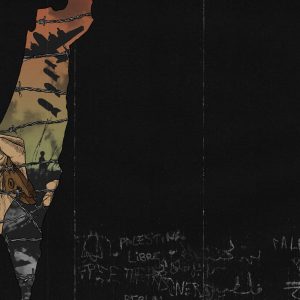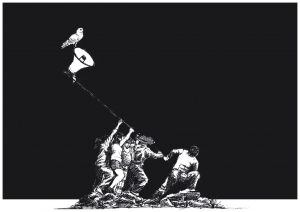Foto: Semaun (kiri) dan Darsono (kanan) pada permulaan gerakan komunis di Indonesia (J.Th. Petrus Blumberger, De Communistische Beweging in Nederlandsch-Indië, 1928)
EMPAT puluh sembilan tahun lalu Darsono pergi dari dunia ini. Ia dimakamkan pada 15 Januari 1976 di taman pekuburan Kesambi, Sompok, Kota Semarang setelah beberapa hari dirawat akibat kecelakaan di kamar mandi rumahnya.[1] Surat kabar Sinar Harapan kemudian menurunkan berita duka dengan nada romantik dan mengatribusi Darsono sebagai “perintis kemerdekaan”:
“Pemakaman, yang berangkat dari rumah kediamannya di Jl. Mangga VI Semarang, telah dilakukan dengan upacara militer yang dihadiri para muspida dan kawan seperjuangan dan bertindak selaku Inspektur Upacara Kolonel Infanteri Maryono. Masyarakat telah memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum perintis kemerdekaan R. Darsono, terlihat penuh sesaknya mereka memenuhi makam di mana ia diistirahatkan terakhir.”[2]
Tidak ada yang keliru dengan menulis Darsono sebagai “perintis kemerdekaan”. Namun lebih dalam dari itu dia adalah salah seorang pemimpin awal gerakan komunis di Indonesia. Berkuasanya rezim anti-komunis Soeharto ketika Darsono wafat menjelaskan mengapa status “kiri”-nya itu ditanggalkan.
Di Indoprogress, Alvino Kusumabrata telah menulis riwayat politik komunis Darsono tersebut.[3] Sementara anak Darsono, Alam Darsono, membuat catatan yang sangat padat namun cukup lengkap merangkum jejak langkah politik bapaknya. Dari Alam, dapat diketahui bahwa jalan politik Darsono tak hanya ditempuh bersama sayap komunis melainkan juga sosialis.
“Darsono; 1897–1976 (lengkapnya: Raden Darsono Notosoedirdjo): Muslim kiri; ahli agronomi; murid Henk Sneevliet; marxis, sosialis revolusioner, sosial demokrat, demokrat; salah seorang pendiri PKI [Partai Komunis Indonesia] pada tahun 1924; pemimpin redaksi majalah partai Api; wakil untuk Indonesia di Komintern; anggota dewan eksekutif; Ketua PKI; dibuang dari Hindia Belanda pada tahun 1926 bersama istrinya [Soewarni]; pindah ke Moskwa; berkonflik dengan Stalin pada tahun 1928; pindah ke Berlin pada tahun 1929; memutuskan hubungan dengan Partai Komunis pada tahun 1930 seturut dominasi politik Moskwa; menetap di Belanda pada tahun 1933; sempat menjadi anggota OSP [Onafhankelijk Socialistische Partij/Partai Sosialis Independen di Belanda] dan RSAP [Revolutionair-Socialistische Arbeiders Partij/Partai Buruh Sosialis-Revolusioner di Belanda]; anggota perlawanan [terhadap pendudukan Nazi] di Belanda; redaksi majalah mingguan De Vlam; kembali ke Indonesia pada tahun 1950.”[4]
Pergerakan nasional memang tidak bisa dibasiskan secara kaku hanya pada satu ideologi.[5] Demikian pun Darsono. Dia tidak diam di dalam tempurung PKI melainkan juga bercakap-cakap dengan subjek non-komunis dari pergerakan nasional.[6] Ia turut mewarnai perdebatan nasionalisme Jawa seperti yang dilayangkan Soetatmo Soeriokoesoemo, pemimpin organisasi etnik Comité voor het Javaans Nationalisme. Ia juga berdebat atas gugatan Islam-politik tentang inkoherensi marxisme dengan cita-cita pergerakan nasional yang diajukan oleh Hadji Fachrodin, pemimpin Sarekat Islam (SI).
Menjauh dari ingar bingar kerja politik Darsono, tulisan ini berpaling pada periode prapergerakan dirinya, sebuah faset hidup yang belum mendapatkan cukup perhatian.[7] Demikian karena karier pergerakan Darsono muskil diresapi dengan cermat tanpa memahami terlebih dahulu latar belakang kehidupan sebelum dirinya naik ke gelanggang politik. Tulisan ini bermaksud memenuhi tujuan itu.
Mendekati Darsono Prapergerakan
“Raden Darsono. Lahir di Pati, 15 November 1897.” Demikian tertulis dalam paspor yang digunakan Darsono untuk bepergian ke Eropa pada 1921 hingga 1922. Informasi mengenai paspor yang berkulit muka regelmatig Nederlandsch paspoort (paspor reguler Belanda) ini termuat dalam laporan Dinas Intelijen Pusat Negeri Belanda (Centrale Inlichtingendienst).[8] Laporan itu menerangkan penggeledahan polisi atas diri Darsono pada November 1921 di Kota Groningen. Penggeledahan ini sudah barang tentu berkenaan dengan sepak terjang Darsono dalam pergerakan nasional. Ketika itu dia sudah menjadi Wakil Ketua PKI.
Namun tentu paspor setebal dua-tiga lembar tak mampu bercerita banyak soal sosok Darsono. Tulisan ini akan bertumpu pada catatan-catatan dari Alam Darsono.[9]

Berangkat dari Trah Priayi
Kekuasaan kolonial Hindia Belanda tak mau mengambil risiko berlebihan dengan menyelenggarakan pemerintahan secara langsung (direct rule).[10] Apa yang mereka lakukan adalah memanfaatkan tata kekuasaan “pribumi” (selanjutnya disebut bumiputra) milik aristokrat setempat yang sifatnya tentu saja feodal. Efektivitas dan efisiensi eksploitasi sumber daya menjadi pertimbangan pokok mengapa para elite lokal itu tidak hanya dibiarkan melainkan juga disubordinasi ke dalam tata pemerintahan kolonial. Untuk alasan ini, alat legitimasi para elite lokal atas rakyat yang berasal dari budaya feodal seperti gelar-gelar kepriayian “raden” dan “raden mas” juga dipertahankan. Singkatnya, kolonialisme juga hadir lewat pemerintahan tak langsung (indirect rule) dari priayi.
Yang belakangan ini menjadi, mengutip sejarawan Heather Sutherland, “elite birokratis” dari kalangan bumiputera pada Pemerintahan Negeri (Binnenlands Bestuur, BB) yang secara khusus bertanggung jawab atas urusan rakyat kebanyakan.[11] Mereka mengurusi hal-hal teknis-lokal alih-alih strategis-nasional.
Keluarga Darsono berasal dari kalangan elite ini. Alam mencatat bapak dan kakek Darsono merupakan priyayi BB di Keresidenan Semarang pada permulaan abad ke-20. Sementara sang kakek telah moncer menjabat sebagai pegawai di Kawedanan Bandjaran, Japara, bapak Darsono menapaki karier berliku. Mula-mula, ketika Darsono masih belia, bapaknya bekerja menjadi juru tulis (carik) di kantor desa di Pati. Ia kemudian naik pangkat sebagai mantri polisi di pusat kota ketika Darsono telah memasuki masa sekolah dasar. Jabatan paling tinggi bapak Darsono adalah Asisten Wedana Semarang. Puncak karier sang bapak terjadi saat Darsono telah mendapatkan pekerjaan, sekitar pertengahan 1910-an.
Berstatus priayi berarti mesti konsekuen menjaga tradisi lama. Tindak tanduk paling kecil pun harus diperhatikan demi menjaga martabat. Namun demikian, Darsono kecil adalah bocah bengal yang ingkar terhadap tuntutan tersebut. Pengingkaran itu sampai-sampai membuat gusar kakeknya. “Semua kebiasaannya [Darsono] membuat sang kakek jengkel. Ia malu menjadi seorang priayi yang memiliki cucu demikian,” terang Alam.[12]
Alam menceritakan lebih jauh: “Darsono waktu itu sangat nakal. Ia begitu menyukai pertunjukan wayang kulit. Ketika tengah malam terdengar suara gamelan, dengan segera ia kemudian pergi untuk menonton. Setelahnya ia tak berani untuk pulang ke rumah dan lebih memilih tidur di belakang sang dalang. Ia juga sangat senang bermain dengan kerbau rawa atau ikut menggiring kambing bersama penggembala yang seusia dengannya.”[13]
Menjalani Pendidikan Dasar
Seturut dengan status kepriayian, Darsono menerima pendidikan secara Barat. Kaum kromo muskil untuk bisa belajar di sekolah binaan pemerintah kolonial seperti ini. Darsono mengenyam pendidikan tingkat dasar pada Sekolah Kelas Pertama (Eerste Klasse School) di Pati. Ia belajar di sana selama lima tahun.
Alam menggambarkan bapaknya menempuh pendidikan dasar ini dengan susah payah, terutama karena harus berpindah-pindah tempat tinggal. Di awal masa sekolah, Darsono diasramakan di pusat kota oleh orang tuanya yang ketika itu masih tinggal di desa. Ia kemudian diungsikan ke rumah pamannya saat yang belakangan mendapat jabatan sebagai mantri opium (mantri opiumverkoper) di Telogowoengoe. Untuk ke sekolah, Darsono harus berjalan kaki selama dua jam, pukul 4.30 hingga 6.30 pagi. Ongkos asrama barangkali jadi alasan kepindahan. Di tengah masa sekolah dasar ini bapak Darsono memperoleh pekerjaan sebagai mantri polisi di pusat kota. Darsono kemudian pindah lagi. Saat itu ia dapat bernapas lega dan mungkin bangun lebih siang.
Tentu masalahnya bukan cuma itu. Di sekolah Darsono benar-benar kelimpungan, terutama karena semua dalam belajar bahasa Belanda. Hal itu diakuinya kepada Alam seperti berikut.
“Di sekolah, para guru adalah orang Belanda. Mereka tak berbicara sepatah kata bahasa Melayu, apalagi Jawa. Mereka berbicara hanya dalam bahasa Belanda kepada para murid dan kami harus memahaminya. Jika kami tak memahami omongan mereka, atau jika mereka tidak memahami kami ketika berbicara, maka lantas saja kami dihukum. Ketika kami pulang ke rumah dengan catatan nilai buruk untuk pelajaran bahasa Belanda, bapak kemudian memberikan hukuman tambahan. Dengan demikian maka kami dapat menguasai bahasa [Belanda] itu secara cakap.”[14]
Kebiasaan sedari belia akan membentuk watak seseorang. Ini juga berlaku bagi Darsono. Buktinya, beratnya pendidikan dasar tak mengubah kebengalan dirinya. Dia tetap keranjingan menonton wayang kulit. Pada suatu faset, Darsono terseok-seok bahkan untuk sekadar hadir karena semalam suntuk menonton pertunjukan wayang. Bukannya mengakhiri kebiasaan itu, ia justru sempat nekat membolos berhari-hari. Buahnya jelas adalah hukuman. Ketika Darsono kembali, ia tak diperbolehkan masuk. Beruntung bapaknya menghadap kepala sekolah dan meminta maaf sehingga Darsono bisa kembali belajar.
Puncak kebengalan Darsono terjadi saat dia mencoba peruntungan mengikuti ujian pendidikan lanjutan. Alam menuturkannya seperti berikut.
“Sebelum Darsono lulus, ia telah mengikuti ujian untuk pekerjaan sebagai guru sekolah sebanyak dua kali. Ujian tersebut begitu sulit karena merupakan sebuah ujian kolasi [vergelijkings-examen]. Tetapi ia gagal. Bagian terbaik dari hal itu adalah ketika dirinya tengah mengikuti ujian tersebut di Jogjakarta. Saat itu orang tuanya tidak mengantongi uang. Mereka mesti menjual pusaka untuk membiayai Darsono. Namun, apa yang Darsono lakukan? Ia tidak berhasil dalam ujian dan dengan uang yang tersisa justru membeli setumpuk wayang kulit hingga memboyongnya pulang ke rumah. Dapat dipahami betapa bapaknya sangat marah.”[15]
Darsono akhirnya berhasil menamatkan sekolah dan mendapat ijazah Eerste Klasse School. Meski sekolah itu sama-sama dibina pemerintah kolonial, namun reputasinya di bawah sekolah serupa bernama Sekolah Dasar Eropa (Europeesche Lagere School). Privilese lebih akan dirasakan para lulusan “Sekolah Eropa” yang belakangan. Ijazah mereka langsung dapat digunakan untuk menembus pendidikan tingkat selanjutnya, sementara sekolah Darsono tidak.[16] Dalam ketakpastian pendidikan lanjutan dan tidak adanya jaminan pekerjaan, bapak Darsono dengan mengatakan, “Saya tidak ingin melihatnya, itu bukan ijazah dari Sekolah Eropa.”[17] Alam menyebut kata-kata itu membuat Darsono kecewa. Kian kesal karena sang bapak seharusnya dulu menyekolahkan anaknya di Sekolah Eropa. Kesia-siaan ijazah sekolah Darsono mutlak juga atas turut andil sang bapak sehingga tak pantaslah dia mengatakan yang demikian.
Namun rasa kecewa terhadap sang bapak tak menjadi melankolia berlarut. Darsono kemudian berinisiatif mengambil sekolah privat yang diselenggarakan oleh seorang Eropa di Pati bernama Tuan H. J. Mente. Ini adalah langkah persiapan untuk menghadapi ujian-ujian yang akan datang. Keputusan ini juga mesti dipahami sebagai upaya pembuktian Darsono akan kapasitas dirinya di hadapan sang bapak. Sebab, seperti diutarakan Alam, di sekolah privat tersebut Darsono tidak hanya belajar berbagai mata pelajaran formal tetapi juga turut menempa keterampilan kerja hingga mendapat upah. “Darsono juga bekerja untuk bapak dari Tuan Mente, seorang juru sita [deurwaarder]. Ia bekerja menyalin surat-surat untuk disita dan memperoleh penghasilan yang lumayan,” ungkap Alam.[18]
Meski kesiapan untuk dapat memasuki pendidikan lanjut kian mantap, Darsono tak segera mendaftar ujian penerimaan. Ia justru mengikuti ujian pegawai negeri tingkat rendah (klein ambtenaarsexamen). Saat itu, sertifikat kelulusan ujian tersebut sangat bernilai, tak hanya untuk masuk menjadi pegawai dalam birokrasi BB. Syahdan, Darsono lulus setelah dua kali percobaan ujian.
Penting untuk dicermati bahwa Darsono, seperti dituturkan Alam, tak melibatkan bapaknya dalam urusan karier dan pendidikan lanjut ini. Mampu memperoleh pendapatan dengan bekerja di bapak dari Tuan Mente barangkali menjadi alasan. Selain itu dia juga memiliki etos belajar dan kerja yang tinggi sampai-sampai membuat Tuan Mente bersimpati. Buktinya, ketika Darsono harus menebus sertifikat klein ambtenaar sebesar ƒ1.50, Tuan Mente menanggungnya bahkan memberikan lebih. “Darsono menerima ƒ10 dari Tuan Mente yang sangat bersenang hati,” terang Alam.[19]
Pendidikan Lanjut dan Karier Awal
Darsono dengan demikian telah berdaya atas pilihan karier dan pendidikannya sendiri. Alih-alih menggunakan sertifikat klein ambtenaar-nya untuk langsung bekerja meneruskan trah keluarga sebagai pegawai birokrat-administrasi atau mantri BB, ia justru mendaftar beasiswa pendidikan lanjut di Sekolah Penanaman hingga kemudian bekerja di bidang pertanian. Alam merangkum perjalanan pendidikan lanjut dan karier awal Darsono ini seperti berikut.
“Darsono kemudian mendapat beasiswa dan masuk ke Sekolah Penanaman di Soekabumi [Cultuurschool te Soekabumi]. Beasiswa yang didapatnya ialah sebesar ƒ25 dan ia hanya mesti membayar paling banyak ƒ5 untuk ongkos asrama. Bayangkan, bocah 15 tahun mendapat beasiswa ƒ25. Jumlah tersebut ketika itu ialah gaji seorang kepala juru tulis [hoofd schrijver]. Setelah menyelesaikan Sekolah Penanaman, Darsono kemudian bekerja sebagai pegawai agrikultur [landbouwkundig-ambtenaar] di Bangilan (dekat Tuban) dengan gaji awal 100 plus tunjangan ongkos transport.”[20]
Seperti diterangkan dalam sebuah catatan pemerintah kolonial, pekerjaan Darsono yang disebut Alam di atas, sebagai “pegawai agrikultur”, secara spesifik ialah penyuluh pertanian bagi petani bumiputra, tepatnya tijdelijk Inlandsch personeel werkzaam in het belang van de verspreiding van landbouwkennis onder de Inlandsche bevolking.[21] Namun, yang lebih penting dari sekadar titel ialah bagaimana Darsono melakoni pekerjaannya. Mesti diperhatikan bahwa dirinya tak sekadar duduk-duduk selayaknya birokrat. Alih-alih, ia terjun langsung ke akar rumput mengadvokasi rakyat; dalam hal ini mengenai masalah-masalah tani seperti yang dipelajarinya sejak di Sekolah Penanaman.
Secara prinsipil, pilihan pendidikan lanjut dan pekerjaan Darsono dapat dipahami sebagai bentuk pengingkaran berulang atas status kepriayian keluarga. Darsono memilih menjadi pegawai ambtenaar bukan sekadar atas motif jabatan dan hidup layak. Kepriayian yang berangkat dari budaya feodal lama, apalagi dalam latar negara kolonial, tak terlalu memusingkan hal ihwal problem mendasar akar rumput karena tolok ukurnya adalah pengabdian kepada kolonialisme. Kepriayian hanyalah legitimasi feodalistik elite bumiputra atas kaum kromo sehingga itu bisa cukup diraih dengan duduk-duduk di kantor BB, laiknya yang kakek dan bapak Darsono lakukan ketika yang belakangan ini telah naik pangkat dari mantri polisi menjadi Asisten Wedana Semarang.
Evaluasi mengenai hal di atas dapat diadakan dengan mengetengahkan cerita tentang bagaimana Darsono akhirnya undur diri dari pekerjaannya. Menjadi penyuluh pertanian membawa Darsono melihat kenyataan masalah kesehatan hewan ternak. Atas dasar problem urgen ini, ia kemudian berinisiatif memohon kepada atasannya untuk dapat menempuh pendidikan lagi di sekolah dokter hewan. Namun permohonan itu tak dapat tembus sehingga Darsono mengundurkan diri, seperti diceritakan Alam sebagai berikut.
“Sementara sang atasan sangat senang terhadap pekerjaannya, Darsono justru merasa tak puas dengan apa yang telah dicapai dan ingin terus belajar. Ia ingin belajar kedokteran hewan. Atasannya setuju dengan hal itu. Namun, ketika Darsono mengajukan surat permohonan studi lanjut tanpa tanda tangan atasannya (yang kebetulan sedang liburan), permohonannya ditolak. Ia sangat kecewa sehingga kemudian melayangkan surat pengunduran diri.”[22]
Manusia Darsono Prapergerakan
Pasca-pengunduran diri sebagai penyuluh pertanian, Darsono kemudian naik ke gelanggang pergerakan nasional sebagai seorang komunis—seperti telah terang disinggung pada awal tulisan ini. Namun, bagaimana kita mesti membentang benang merah keterkaitan antara hidup prapergerakan dengan perjalanan politik Darsono kemudian?
Berkali-kali disebutkan bahwa kehidupan prapergerakan Darsono adalah cerita pengingkaran diri terhadap status kepriayian keluarga. Darsono adalah seorang anak laki-laki sekaligus kakak tertua.[23] Dengan demikian, niscaya orang tua Darsono menaruh ekspektasi besar pada dirinya. Pengingkaran Darsono itu jelas memiliki arti sebuah usaha memotong warisan trah keluarga priayi. Komplemen dengan kesimpulan ini, Alam memandang seperti berikut.
“Darsono adalah orang Jawa yang ditakdirkan untuk mengikuti jejak langkah bapak dan kakeknya menjadi Inlands bestuurambtenaar. Di Jawa, ini memiliki arti ia yang termasuk ke dalam golongan priayi rendahan, yaitu kalangan bestuursadel. Bapaknya adalah seorang wedana dan Darsono semestinya juga menjadi wedana.”[24]
Namun upaya mengingkari status priayi dan pemberani tak secara gamblang menjelaskan keputusan Darsono menempuh jalan politik. Alam sendiri hanya mengajukan penjelasan bahwa yang langsung memengaruhi keputusan Darsono masuk ke dalam pergerakan adalah kegandrungan terhadap kisah-kisah wayang.[25] Alam mengutarakan bahwa epos-epos India dan mitos Ratu Adil—keduanya menjadi pokok cerita wayang kulit—begitu memesona Darsono. Berangkat dari isu kasta (dalam epos India) dan keniscayaan sejarah masa depan (dalam mitos Ratu Adil), Darsono disebut mafhum tentang persoalan kemanusiaan, ketidakadilan, dan ketaksetaraan sosial. Hal ini dengan sendirinya komplemen terhadap wacana-wacana marxis yang kemudian digelutinya, mengenai kelas dan materialisme historis.
Penjelasan Alam di atas jelas penting. Namun perlu dipahami bahwa Darsono juga manusia yang memiliki kualitas-kualitas tertentu. Kita mesti menaruh perhatian tentang bagaimana Darsono prapergerakan membangun etos diri dan mental berontak. Kedua hal itu, seperti diceritakan panjang lebar dalam tulisan ini, berakar pada hal ihwal yang lebih manusiawi. Seperti kata sejarawan Bambang Purwanto, “ketika manusia melakukan sesuatu sehingga meninggalkan jejak peristiwa masa lalu yang disebut sejarah, semua itu tidak hanya ditentukan oleh rasio melainkan juga emosi, hati nurani.”[26]
Mental berontak Darsono tidak dalam motif heroisme-perlawanan, melainkan dari konteks emosional atas sikap sang bapak. Begitu pula dengan etos dirinya. Darsono membangun hal itu dari spontanitas tuntutan hidup, seperti kemestian disiplin dengan tak manja berjalan kaki jauh menuju sekolah atau profesionalisme pekerjaan sebagai asisten penyalin surat. Etos diri dan mental berontak sebagai kualitas hidup pada periode prapergerakan mengendap, kemudian menuntun keputusan berikutnya Darsono di atas gelanggang pergerakan. Kualitas hidup itu memang terbentuk dalam latar cerita sebuah keluarga priayi. Namun, pada akhirnya, yang tinggal dari status kepriayian itu hanyalah gelar raden di depan nama, seperti tercatat dalam paspornya yang telah disinggung di muka tulisan ini.
[1] “R. Darsono, Semarangs strijder en pionier voor de vrijheid is overleden,” dalam Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Amsterdam: Raden Darsono Notosudirdjo Papers, ARCH02476, 5, Text of interview with and memories as told by Darsono. 1968, 1975 and n.d.
[2] “Perintis Kemerdekaan R. Darsono Meninggal Dunia”, Sinar Harapan, 21 Januari 1976.
[3] Alvino Kusumabrata, “Darsono, Anak Revolusi Kala Fajar Pergerakan Kiri Menyingsing”, http://indoprogress.com/2023/04/darsono-anak-revolusi/
[4] Alam Darsono, Het Zwijgen van de Vader (Nijkerk: Pengaarde, 2008), hlm. III.
[5] Memahami subjek pergerakan nasional dalam konstruksi dan batas-batas komunis-Islam-nasionalis adalah cara usang yang telah lama ditinggalkan. Indonesianis Takashi Shiraishi mengajukan penjelasan melalui monograf monumentalnya tentang ideologi yang bersifat cair di dalam pergerakan nasional. Indonesianis Benedict Anderson, dan kemudian juga diaplikasikan secara ekstensif oleh sejarawan Hilmar Farid dalam studi tentang bahasa dan politik pergerakan, menjelaskan diskursus wacana di dalam arena pergerakan adalah sesuatu yang dibayangkan (dikonstruksikan) oleh subjek-subjeknya, terlepas dari pilar politik mereka, bukan terberi begitu saja berdasarkan komitmen ideologi. Dengan kata lain, pergerakan adalah sebentuk eklektisisme dari ragam ideologi yang relatif terhadap subjek yang menjalaninya. Selengkapnya simak Takashi Shiraishi, An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912 –1926 (Ithaca: Cornell University Press, 1990); Benedict R. O’G. Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London: Verso, 2006); Hilmar Farid, Perang Suara: Bahasa dan Politik Pergerakan (Depok: Komunitas Bambu, 2024).
[6] Sebagai tinjauan umum tentang hal ini simak Ruth T. McVey, The Rise of Indonesian Communism (Ithaca: Cornell University Press, 1965); Lin Hongxuan, Ummah Yet Proletariat: Islam, Marxism, and the Making of the Indonesian Republic (New York: Oxford University Press, 2023). Mengenai Darsono di dalam perdebatan nasionalisme Jawa lihat Herman A. O. de Tollenaere, “The Politics of Divine Wisdom: Theosophy and Labour, National, and Women’s Movements in Indonesia and South Asia, 1875–1947” (Disertasi, Katholieke Universiteit Nijmegen, 1996), hlm. 305–15; Takashi Shiraishi, “The Disputes between Tjipto Mangoenkoesoemo and Soetatmo Soeriokoesoemo: Satria vs. Pandita,” Indonesia, No. 32 (Oktober 1981), hlm. 97–100. Sementara mengenai perdebatan Darsono dengan Islam-politik lihat Oliver Crawford, “Translating and Transliterating Marxism in Indonesia,” Modern Asian Studies, 2020, hlm. 14–20, 28–33, doi:10.1017/S0026749X20000104.
[7] Beberapa penelitian telah dan sedang dilakukan. Ramli, penulis asal Jakarta, telah menulis riwayat tentang Darsono ketika berpropaganda di Sinar Djawa sekalipun tak ditopang data primer yang mumpuni. Saya sendiri berfokus pada periode ketika Darsono masuk ke dalam pergerakan hingga dibuang pemerintah kolonial (1918–1925), sementara indonesianis Lin Hongxuan menaruh perhatian pada periode setelahnya, ketika Darsono berada dalam pembuangan di Eropa. Selengkapnya lihat Ramli, Raden Darsono Notosudirdjo (1918–1925): Jalan Merah Seorang Propagandis Dalam Surat Kabar Sinar Djawa (Surabaya: Pustaka Indis, 2023); Rahman C. Adiatma, “Sejarah Pemikiran Politik Raden Darsono Notosoedirdjo, 1918–1925” (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2024); Lin Hongxuan, “The Minor Key: Indonesian Marxists Sojourning Abroad,” Journal of World History, Vol. 35, No. 2 (Juni 2024), hlm. 261–296, khususnya hlm. 276–284.
[8] “Geheim rapport Centrale Inlichtingendienst, rapport van Politie Groningen, kabinet, No. 124, ‘Verslag van het congres van de Communistische Partij, gehouden op Zondag, Maandag, en Dinsdag g 12, 13, en 14 November 1921 te Groningen in het gebouw Ons Huis aan den Heereweg,’” 1921, dalam Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en Cultuur: Rapporten Centrale Inlichtingendienst 1919–1940, document nummer 07181, RN 516, Vooraanstaand communist naar Nederland, 23-12-1921.
[9] Catatan-catatan Alam termuat dalam sebuah risalah dan dua tulisan yang dibuat olehnya. Lihat “Memories Dr. Alam Darsono: herinneringen tijdens zijn jeugd, in de beweging, zijn externering en na zijn terugkeer naar Indonesia zoals Darsono die aan mij vertelt,” 31 Oktober 1975, dalam Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Amsterdam: Raden Darsono Notosudirdjo Papers, ARCH02476, 5, Text of interview with and memories as told by Darsono. 1968, 1975 and n.d.; Alam Darsono, Het Zwijgen van de Vader; Alam Darsono, “Henk Sneevliet, brenger van het marxisme naar Indonesië,” dalam Wij moesten door…, ed. Henk Smeets dan Dick de Winter (Ridderkerk: Sneevliet Herdenkingscomité, 2002), hlm. 17–28.
[10] Lihat Sartono Kartodirdjo, A. Sudewo, dan Suhardjo Hatmosuprobo, Perkembangan Peradaban Priyayi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hlm. 5–6, 18–19.
[11] Heather Sutherland, The Making of a Bureaucratic Elite: The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi, ASAA Southeast Asia Publications Series No. 2 (Singapore: Hineman Educational Books, 1979). Istilah bureaucratic elite ini mesti dibaca sebagai “elite birokratis”, bukan “elite birokrasi”. Elite birokrasi berarti para priayi bumiputra yang menjadi elite (pemuncak) di BB. Makna ini melenceng dari pengertian priayi yang sebenarnya, yaitu sebagai elite dari kalangan bumiputra yang mampu bekerja mengurus hal-hal birokratis di dalam BB. Jika mengacu pada pengertian elite birokrasi, maka status elite priayi yang hanya mengurusi persoalan teknis-lokal itu menjadi batal karena di atas mereka masih terdapat kelompok penjajah Belanda ras Eropa.
[12] “Memories Dr. Alam Darsono.”
[13] “Memories Dr. Alam Darsono.”
[14] Alam Darsono, Het Zwijgen van de Vader (Nijkerk: Pengaarde, 2008), hlm. 131. Keterangan mengenai hal ini juga dapat disimak pada Alam Darsono, “Henk Sneevliet, brenger van het marxisme naar Indonesië,” dalam Wij moesten door…, ed. Henk Smeets dan Dick de Winter (Ridderkerk: Sneevliet Herdenkingscomité, 2002), hlm. 21.
[15] “Memories Dr. Alam Darsono: herinneringen tijdens zijn jeugd, in de beweging, zijn externering en na zijn terugkeer naar Indonesia zoals Darsono die aan mij vertelt,” 31 Oktober 1975, dalam Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Amsterdam: Raden Darsono Notosudirdjo Papers, ARCH02476, 5, Text of interview with and memories as told by Darsono. 1968, 1975 and n.d.
[16] Mengenai hal ini selengkapnya simak Heather Sutherland, The Making of a Bureaucratic Elite: The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi, ASAA Southeast Asia Publications Series No. 2 (Singapore: Hineman Educational Books, 1979), hlm. 45–66; Christiaan L. M. Penders, “Colonial Education Policy and Practice in Indonesia: 1900–1942” (Disertasi, Australian National University, 1968).
[17] “Memories Dr. Alam Darsono.”
[18] “Memories Dr. Alam Darsono.”
[19] “Memories Dr. Alam Darsono.”
[20] “Memories Dr. Alam Darsono.”
[21] Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië 1917, Deel 2: Kalender en Personalia (Batavia: Landsdrukkerij, 1917), hlm. 468.
[22] “Memories Dr. Alam Darsono.”
[23] Adik-adik Darsono adalah Marto, Rukati, dan Tawi. Lihat Alam Darsono, Het Zwijgen van de Vader, hlm. 129.
[24] Alam Darsono, “Henk Sneevliet, brenger van het marxisme naar Indonesië,” hlm. 21.
[25] Alam Darsono, “Henk Sneevliet, brenger van het marxisme naar Indonesië,” hlm. 25.
[26] Bambang Purwanto, Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?! (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2006), hlm. xvii.
Rahman C. Adiatma adalah peneliti independen, alumnus program sarjana Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada.