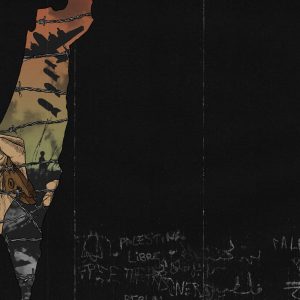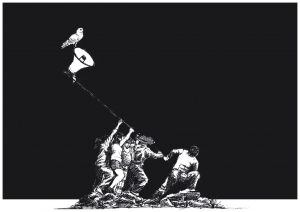Foto: Wikimedia Commons
SALAH satu babak penting dalam sejarah Indonesia yang hingga kini masih menjadi perdebatan, terutama di antara pengamat dalam negeri, adalah periode Demokrasi Terpimpin di bawah pemerintahan Sukarno. Sejumlah karya akademik sebenarnya telah banyak membahas periode itu, dan sebagian besar bersepakat mendefinisikannya sebagai rezim otoriter (Feith 2007; Bourchier 2015; Legge 1972; Crouch 2007; Robison 1986; Friedman 2021). Namun, banyak penulis Indonesia memberinya label kiri karena meyakini dia berpihak pada ide-ide yang dipengaruhi oleh marxisme dan dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagian, seperti Iqra Anugrah dan Airlangga Pribadi Kusman, bahkan menyebutnya sebagai pemerintahan bonapartisme sayap kiri. Sayangnya, basis argumen mereka sangat lemah dan data penunjangnya juga banyak yang kurang akurat. Pandangan mereka lebih banyak dicemari oleh fanatisme buta terhadap sosok Sukarno, sehingga sering tidak bisa membedakan antara retorika dan tindakan politik.
Pembacaan yang lebih akurat atas periode ini penting untuk menguraikan sejarah pembentukan struktur ekonomi-politik Indonesia, dan hal ini berguna dalam upaya memahami perkembangan politik kontemporer. Ringkasnya, kegagalan eksperimen demokrasi parlementer tahun 1950-an yang memberi justifikasi lahirnya otoritarianisme Sukarno dan kemudian Soeharto menunjukkan rapuhnya fondasi liberalisme politik di Indonesia; selain marjinalnya gagasan ekonomi liberal sebagaimana telah saya bahas pada tulisan sebelumnya. Ini bukan pembelaan atas liberalisme politik dan ekonomi atau bahwa demokrasi liberal adalah jawaban atas apa yang saya sebut sebagai state of disorder (kapitalisme yang bertumpu pada tatanan kekacauan), sebagaimana diharapkan oleh para pemikir pluralis-liberal atau yang disalahpahami oleh Angga maupun Prathiwi W. Putri dalam tulisan tanggapannya. Namun, uraian atas logika kapitalisme yang spesifik, yang memengaruhi beroperasinya lembaga-lembaga politik dan hukum, penting untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi apa yang memungkinkan dan apa yang menghambat konsolidasi kekuatan kelas pekerja maupun konsolidasi kekuatan yang menentangnya.
Sukarno seorang borjuis nasionalis liberal
Angga lebih banyak menelan mentah-mentah pemikiran Sukarno dalam memahami periode Demokrasi Terpimpin sehingga cenderung ideologis dan banyak mengandung bias. Sedangkan Iqra keliru membaca sumber yang dipakai. Dia merujuk buku Jeremy Friedman berjudul Ripe for Revolution: Building Socialism in the Third World untuk menyebut pemerintahan Sukarno pasca-1959 sebagai bonapartisme sayap kiri, padahal di sana tidak ada satu pun pernyataan yang mendukung argumennya. Friedman, yang sebenarnya hanya mendaur ulang karya-karya akademik sebelumnya dalam menjelaskan periode itu, juga mengategorikan Demokrasi Terpimpin sebagai rezim otoriter.
Lewat Dekrit 1959, Sukarno disebut telah menyingkirkan eksperimentasi demokrasi parlementer yang sesungguhnya bisa memberi jalan bagi kemenangan PKI. Kontribusi Friedman adalah memberi konteks ketegangan hubungan Uni Soviet dan Cina yang memengaruhi langkah-langkah politik PKI, termasuk ketika harus beraliansi dengan Sukarno. Menurut Friedman, Soviet pada awalnya meragukan keputusan PKI beraliansi dengan Sukarno yang hendak menyingkirkan demokrasi parlementer dan membentuk pemerintahan otoriter. Keraguan itu dikemukakan sebagai berikut (Friedman 2021, 48):
“Sukarno pada dasarnya adalah seorang borjuis, apa pun ia sebelumnya, ia sama sekali bukan seorang komunis. Apakah komunisme bisa dibangun di Indonesia dengan bantuan seorang borjuis nasionalis yang radikal?”
Friedman juga mengatakan bahwa marhaenisme, yang dipercaya oleh sebagian aktivis kiri pengagum Sukarno sebagai kontekstualisasi proletarianisme, mengandung bias ideologi borjuis. “Marhaen” tidak pernah didefinisikan sebagai kategori kelas dalam kerangka hubungan produksi kapitalisme. Definisinya lebih mirip dengan yang sekarang banyak digunakan oleh Bank Dunia, semata sebagai kategori ekonomi “golongan bawah” dan “miskin”. Karena itu pula tidak ada konsep perjuangan kelas dari marhaenisme, sebab struktur kelas di Indonesia diyakini berbeda dari yang didefinisikan dalam tradisi marxisme (Legge 1972). Upaya pembebasan marhaen diwujudkan melalui peningkatan standar hidup layak.
Soviet menilai konsepsi demikian adalah cerminan ideologi borjuis Sukarno dan PNI yang takut terhadap perjuangan kelas sesungguhnya yang direpresentasikan oleh PKI (Friedman 2021, 46). Akan tetapi, Soviet memang tak pernah memiliki sikap pasti atas langkah apa yang mesti ditempuh oleh PKI, sebab peluang dari berbagai opsi yang tersedia sama-sama kurang menguntungkan untuk mewujudkan sosialisme. Pilihan itu adalah: (1) mendukung demokrasi parlementer dengan risiko berhadapan dengan partai-partai lain terutama dari faksi Islam dan militer yang anti-komunis; (2) beraliansi dengan Sukarno dan mendukung otoriterisme serta bekerja sama dengan militer; (3) atau bergerilya lewat jalur bawah tanah (Friedman 2021, 51). PKI, seperti yang tercatat dalam sejarah, pada akhirnya menempuh jalur kedua. Soviet menyalahkan Cina yang dianggap telah memengaruhi PKI mengambil pilihan ini, meski kemudian memberi justifikasi kemungkinan pencapaian sosialisme lewat aliansi dengan borjuis nasionalis. Soviet juga pada akhirnya mendukung Sukarno dan memberi bantuan ekonomi dan investasi.
Namun, kegagalan PKI mendorong lebih jauh agenda-agenda sosialis terutama setelah Ekonomi Terpimpin dideklarasikan tahun 1963, serta semakin meruncingnya perseteruan dengan faksi militer dan islamis, membuat Soviet mengkritik kembali strategi PKI yang menempuh aliansi dengan Sukarno. Menurut Friedman, kegagalan itu juga disebabkan oleh faktor Soviet yang mendukung Sukarno dan aliansi PKI dengannya. Lebih jauh, Friedman (2021, 72) mengatakan:
“Pengalaman mencoba merekayasa transisi menuju ekonomi sosialis di bawah seorang nasionalis borjuis kecil radikal seperti Sukarno juga menjadi pelajaran bagi Moskow. Seseorang seperti Sukarno, meskipun ia sering melontarkan retorika anti-imperialis dan sesekali dengan genit menggunakan jargon sosialis, tidak akan pernah dapat dipercaya, tidak mau benar-benar mengambil langkah tegas yang akan menghancurkan kepentingan kelas pendukung borjuisnya; pada saat yang genting ia justru akan mengkhianati revolusi.”
Bagi Friedman, retorika nasionalisme Sukarno adalah bentuk keengganannya dalam mendorong perubahan modus produksi ekonomi secara serius. Duta besar Soviet pada saat itu juga mengemukakan bahwa Sukarno ternyata tidak lebih dari seorang borjuis kecil liberal. Friedman juga kembali menegaskan bahwa kesalahan terbesar PKI adalah terlalu optimistis menggantungkan perwujudan agenda sosialisme pada Sukarno. Menurutnya, “kendaraan utama revolusi sosialis adalah partai, bukan seorang pemimpin borjuis radikal” (Friedman 2021, 73).
Otoritarianisme Demokrasi Terpimpin
Seperti judul artikelnya, “Demokrasi Terpimpin Sukarno bukan Rezim Bonapartis Sayap Kiri”, Coen Husain Pontoh berpendapat bahwa Sukarno dan Demokrasi Terpimpinnya tidak tepat disebut sebagai rezim bonapartisme sayap kiri. Namun, tak jauh beda dengan Iqra, Coen juga melabeli era Sukarno sebagai rezim kiri—bukan bonapartis, tapi populis—yang “memosisikan dirinya sebagai musuh dari kelas borjuasi.” Secara problematik, Coen juga mengatakan bahwa Sukarno tidak pernah punya niat membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945 yang berwatak otoritarian. Untuk perkara ini, pertama-tama, hanya tuhan yang tahu niat dari tindakan politik seseorang. Kedua, yang mesti dianalisis adalah kenyataan sosiologis yang melahirkan tindakan penandatanganan Dekrit 1959 yang membuka jalan bagi otoritarianisme Demokrasi Terpimpin. Faktanya, Sukarno memang telah kehilangan kekuasaan di bawah sistem parlementer, dan ia bisa mengonsolidasikan kembali kekuatannya dengan membubarkan sistem itu.
Coen sudah tepat mengutip pernyataan Sukarno pada 1956, tepatnya pada peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober setelah melawat ke Cina. Itu adalah pernyataan ketidaksetujuannya terhadap demokrasi parlementer. Pernyataan yang terkenal itu berbunyi, “Kita telah membuat kesalahan terbesar pada tahun 1945 dengan membentuk partai, partai, partai. Marilah sekarang bersama-sama kita menguburkan semua partai!” Ini bukan pernyataan tanpa tendensi yang, sekali lagi, oleh Coen disebut “hingga saat itu tidak ada niat” menempuh jalur otoritarianisme.
Sebelumnya, di hadapan parlemen pada 26 Maret 1956 (Ichtiar Parlemen No 31 tahun 1956), Sukarno juga telah mengemukakan ketidaksetujuan terhadap demokrasi liberal karena dianggap tidak mencerminkan watak bangsa. Dalam pidatonya, Sukarno mengatakan bahwa “50 persen plus satu tidak selalu benar.” Ia juga mengontraskan demokrasi parlementer yang bercorak Barat dan mengutamakan individualisme dengan demokrasi ala Indonesia, yakni yang bertumpu pada kolektivisme dan “kegotong-royongan”—jargon yang kemudian terus direproduksi oleh Soeharto untuk menjustifikasi kekuasaannya yang otoriter (Feith 2007). Narasi serupa juga menjadi basis argumen Asian values yang digemari oleh pemimpin-pemimpin otoriter di Asia Tenggara untuk menolak demokrasi dan liberalisme politik.
Pidato-pidato Sukarno di tahun 1956, dengan demikian, adalah suatu pengantar atas proto konsep Demokrasi Terpimpin yang membuka jalan bagi sentralisasi kekuasaan.
Konsep Demokrasi Terpimpin sedikit banyak berpijak pada gagasan organisisme yang para periode awal kemerdekaan dikampanyekan oleh Supomo lewat ide negara integralistik (Bourchier 2015). Gagasan ini terinspirasi dari Nazi yang mengandaikan negara adalah kesatuan organik dan menekankan pentingnya kolektivitas. Ide ini diperoleh saat Supomo bersama beberapa tokoh pergerakan nasional bersekolah di Fakultas Hukum Universitas Leiden. Di tahun 1920-an, saat Supomo masih mahasiswa, pengaruh fasisme sangat kuat termasuk di kalangan terpelajar (Bourchier 2015). Jejak fasisme di Hindia Belanda juga dapat ditelusuri di Boedi Oetomo yang kerap disebut sebagai organisasi pergerakan pertama era kolonial. Haluan politik kanan jauh dari organisasi ini semakin diekspresikan secara lebih terbuka saat bertransformasi menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra) pada 1935. Para pemimpin Parindra secara terbuka menyatakan kekaguman pada Hitler. Meski tidak secara langsung bersinggungan dengan Parindra, ide negara integralistik Supomo memiliki akar yang sama. Di awal kemerdekaan, Supomo terlibat dalam perumusan konstitusi. UUD 1945 yang berwatak otoritarian sangat dipengaruhi oleh gagasan organisisme Supomo itu.
Sukarno kembali mengutarakan ide organisisme yang berwatak fasis itu dengan menyebut “negara sebagai organisme hidup”, sebagai kesatuan antara negara dan rakyat, pada 1957. Dia pun merujuk padanannya, konsep manunggaling kawula gusti. Sebagaimana telah saya singgung dalam tulisan sebelumnya, kemenangan ide fasis ini adalah hasil kolaborasi Sukarno dan Nasution, dua orang yang paling disingkirkan selama periode demokrasi parlementer. Berbagai pertikaian antar faksi politik serta menguatnya sentimen anti-sentralisme Jawa yang memicu pemberontakan-pemberontakan di daerah membuat Nasution, yang sebelumnya disingkirkan pada 1952, ditunjuk kembali sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada 1955. Dia ditugaskan memulihkan keadaan dan pada saat itu kembali menegaskan penolakannya terhadap sistem parlementer. Tak lama kemudian Sukarno mengemukakan pandangan seperti dijelaskan di atas, dan itu membuka pintu bagi aliansi dengan militer. Tapi Sukarno tak mau hanya menjadi instrumen yang memuluskan kepentingan militer. Karena itu dia juga berupaya membangun aliansi dengan faksi politik yang tersingkir pula oleh sistem parlementer, seperti PKI dan Partai Murba.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
Rapuhnya fondasi liberalisme politik
Berakhirnya eksperimen demokrasi parlementer pasca-Dekrit 1959 menunjukkan rapuhnya fondasi liberalisme politik di Indonesia. Ini bukan hanya refleksi dari periode penuh gejolak di tahun 1950-an, tetapi juga tercermin hingga saat ini. Liberalisme politik yang diintroduksi kembali setelah jatuhnya Soeharto, misalnya, bukannya makin meluas melainkan menyempit. Perlindungan dan pemenuhan hak-asasi manusia juga cenderung stagnan, hanya tertuang dalam konstitusi dan undang-undang tapi secara kualitatif hampir tak pernah terwujud. Lembaga-lembaga demokrasi dan hukum justru terus dibajak untuk melegitimasi kepentingan-kepentingan illiberal dan otoritarian. Pembalikan institusi liberal ini mirip seperti yang dilakukan Sukarno, meski dengan skala yang berbeda.
Kohesivitas faksi-faksi ekonomi-politik pasca-Soeharto lebih rendah daripada yang dapat diamati pada periode Sukarno, sehingga tidak ada kekuatan atau aliansi yang berhasil mengembalikan UUD 1945 meskipun aspirasi itu sudah ada sejak lama. Dulu kelas kapitalis belum tumbuh, tapi kini muncul faksi-faksi ekonomi dengan kapital besar yang tidak sepenuhnya otonom dari negara dan karena itu juga dipengaruhi oleh perseteruan dan perkubuan politik. Hanya saja, perseteruan di antara faksi-faksi ekonomi-politik ini belum sampai pada titik sebagaimana yang terjadi pada era 1950-an yang bisa memberi justifikasi sentralisasi kekuasaan untuk menciptakan stabilitas politik, seperti yang dilakukan oleh Sukarno dan Nasution tahun 1959. Meski demikian, narasi soal kegaduhan politik di bawah sistem multipartai juga sudah lama mengemuka bersamaan dengan aspirasi resentralisasi kekuasaan. Situasi ini melahirkan kenyataan bahwa tidak ada perluasan liberalisme politik, tetapi hal itu juga tidak membalik demokrasi Indonesia menjadi otoriter.
Desakan liberalisme politik di Indonesia sejak periode 1950-an lemah karena tidak ditopang oleh kelas sosial yang kuat, baik borjuasi ataupun buruh. Sebagaimana dijelaskan di muka, PKI sebenarnya punya kepentingan mempertahankan demokrasi parlementer meski cenderung dieksklusi oleh faksi liberal yang dominan, seperti Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan beberapa tokoh sentral seperti Mohammad Hatta. Terlebih, meski disingkirkan secara nasional, PKI berhasil memperoleh capaian fantastis dalam pemilu-pemilu tingkat lokal di Jawa. Jika Pemilu 1959 diadakan, bisa jadi PKI keluar sebagai pemenang. Namun kemungkinan itu tertutup setelah Sukarno mengeluarkan dekritnya, dan PKI menempuh jalur yang justru mengantarkan pada kehancurannya pada 1965. Setelah 1965, Soeharto berhasil mendemobilisasi gerakan buruh dan sejak itu pula upaya-upaya pengorganisasian kekuatan politik kiri cenderung gagal. Akibatnya, tidak ada penopang kuat institusi politik liberal pasca-Soeharto.
Bubarnya demokrasi parlementer juga menunjukkan kegagalan kelas menengah dan intelektual liberal dalam mempertahankan dan mendorong perluasan liberalisme politik. Situasi ini mirip dengan yang terjadi pada periode pasca-Soeharto. Namun, institusi liberal di masa kini bisa lebih lama bertahan karena derajat kohesivitas faksi-faksi ekonomi-politik dominan yang berbeda dari masa lalu, bukan sebab kekuatan kelas menengah dan intelektual liberal.
Merefleksikan kasus Prusia dan Eropa Timur awal abad ke-19, William Langer (1969) menyebut aspirasi liberal semacam ini sebagai liberalisme intelektual. Tidak ada basis sosial yang menopang desakan liberalisme politik itu. Dalam sejarah Eropa Barat, kelas kapitalis berperan sebagai penopang utamanya, hasil dari upaya melindungi kepentingan modal dari ancaman kelas atas tradisional. Tentu, liberalisme di sini masih terbatas untuk laki-laki, kulit putih, dan kelas menengah-atas. Namun, tanpa basis sosial, bahkan desakan liberalisme yang terbatas pun sangat lemah karena hanya menjadi aspirasi ideal yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan material kelas-kelas sosial yang dominan. Akibatnya, meskipun ada desakan liberalisme di Prusia dan Eropa Timur pada tahun-tahun itu dari kalangan intelektual dengan mengambil inspirasi dari pengalaman di Barat, institusi politik yang terbentuk tetap anti-demokratik dan anti-liberal. Jerman dan Eropa Latin bahkan melahirkan fasisme. Kelas kapitalis juga sangat lemah dan bergantung pada negara. Perluasan liberalisme politik lebih jauh di Jerman dan Eropa Barat baru terjadi pasca-Perang Dunia lewat desakan gerakan buruh yang makin menguat di era industrialisasi. Hanya saja, derajat kekuatannya tidak cukup untuk menghancurkan modus produksi kapitalisme dan menggantinya dengan tata ekonomi baru seperti di Uni Soviet, Cina, dan negara-negara sosialis Eropa Timur. Meski demikian, mereka berhasil membuka ruang politik yang makin inklusif serta memperluas peran negara dalam redistribusi kapital.
Di Indonesia, selain absennya gerakan buruh yang kuat, kelas kapitalisnya terus bergantung pada hubungan-hubungan patronase dengan politisi dan birokrat, dan ini yang juga membuat tidak adanya penopang liberalisme politik. Untuk mengakumulasi kapital, tidak harus ada persaingan yang sehat dan terbuka di antara sesama kapitalis yang memerlukan adanya kepastian hukum. Singkatnya, periode demokrasi parlementer era 1950-an serta perjalanan demokratisasi pasca-Soeharto yang tanpa diiringi liberalisme politik adalah produk dari situasi itu. Ini yang saya sebut sebagai state of disorder (Mudhoffir 2022). Meskipun banyak institusi liberal dibuat pasca-Soeharto, lembaga-lembaga itu jarang sekali berjalan sesuai dengan desain idealnya. Namun, tidak berarti bahwa demokrasi liberal adalah tipe ideal yang menjadi jawaban atas tatanan kecauan itu. Jawabannya terletak pada sejauh apa kelas pekerja dapat mengartikulasikan kepentingannya melawan kelas kapitalis berdasarkan pembacaan situasi objektif atas logika kapitalisme yang spesifik dan struktur ekonomi-politik secara luas.
Penutup
Tulisan saya sebelumnya tentang periode Demokrasi Terpimpin sebenarnya hanyalah catatan kaki atas pokok bahasan tentang peran ekonom-teknokrat pada era Soeharto dari Iqra. Angga tampaknya terprovokasi oleh catatan kaki itu. Ulasannya tampak sangat dicemari oleh fanatisme buta terhadap Sukarno ketimbang sebagai karya akademik yang bisa mengambil jarak dari realitas yang sedang diulasnya. Argumennya mirip seperti tulisan politisi-politisi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) loyalis Megawati Soekarnoputri. Bagi mereka yang sedang mabuk dengan imaji kesempurnaan Sukarno, termasuk Angga, pandangan semacam itu sangat bisa dimaklumi. Namun, yang mengherankan, ternyata banyak penulis kiri lain yang tampaknya juga kurang bisa menilai dengan jernih kepemimpinan Sukarno dan cenderung terkesima dengan kegenitan retorika sosialismenya.
Uraian saya ini menegaskan bahwa Sukarno tak lain adalah seorang borjuis nasionalis liberal yang tak berkepentingan mendorong perjuangan kelas dan mewujudkan sosialisme. Demokrasi Terpimpin adalah bentuk konsolidasi otoritarianisme awal kekuatan politik nasionalis dan militer. Dukungan PKI terhadap rezim otoriter ini juga yang mengantarkan pada kehancurannya, menutup peluang kemenangan melalui jalur elektoral. Namun, singkatnya periode demokrasi parlementer juga menunjukkan rapuhnya liberalisme politik saat itu karena hanya ditopang oleh aspirasi kelas menengah dan intelektual. Tidak ada kelas kapitalis, sementara PKI memilih beraliansi dengan Sukarno.
Situasi ini mirip dengan yang terjadi saat ini. Meskipun kelas kapitalis telah tumbuh, kepentingan material mereka tidak diwujudkan melalui liberalisme politik karena tergantung pada hubungan-hubungan patronase. Sementara itu, kelas buruh masih belum mampu merestorasi kapasitas pengorganisasian seperti pada era PKI. Ini yang membuat demokrasi di Indonesia berjalan tanpa liberalisme politik, meski faksi-faksi ekonomi-politik dominan tidak cukup kohesif untuk mengembalikan otoritarianisme seperti yang telah dilakukan oleh Sukarno bersama Nasution di tahun 1959.
Sumber Rujukan
Bourchier, David. 2015. Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State. London dan New York: Routledge.
Crouch, Harold. 2007. The Army and Politics in Indonesia. Jakarta dan Kuala Lumpur: Equinox Publishing.
Feith, Herbert. 2007. The Decline of Constitutional Democracy. Jakarta dan Kuala Lumpur: Equinox Publishing.
Friedman, Jeremy. 2021. Ripe for Revolution: Building Socialism in the Third World. London: Harvard University Press.
Ichtiar Parlemen No 31 tahun 1956
Legge, John. D. 1972. Sukarno: A Political Biography. Boston: Allen and Unwin.
McVey, Ruth T. 1965. The Rise of Indonesian Communism. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Mudhoffir, Abdil. M. 2022. State of Disorder: Privatised Violence and the State in Indonesia. Singapore: Palgrave Macmillan.
Pidato Sukarno pada Peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1956
Reeve, David. 1985. Golkar of Indonesia: An Alternative to The Party System. Singapore: Oxford University Press.
Robison, Richard. 1986. Indonesia: The Rise of Capital. Australia: Allen dan Unwin.
William Langer. 1969. Political and Social Upheaval, 1832-1852. New York: Harper and Row.
Abdil Mughis Mudhoffir, Alexander von Humboldt Research Fellow, Jerman