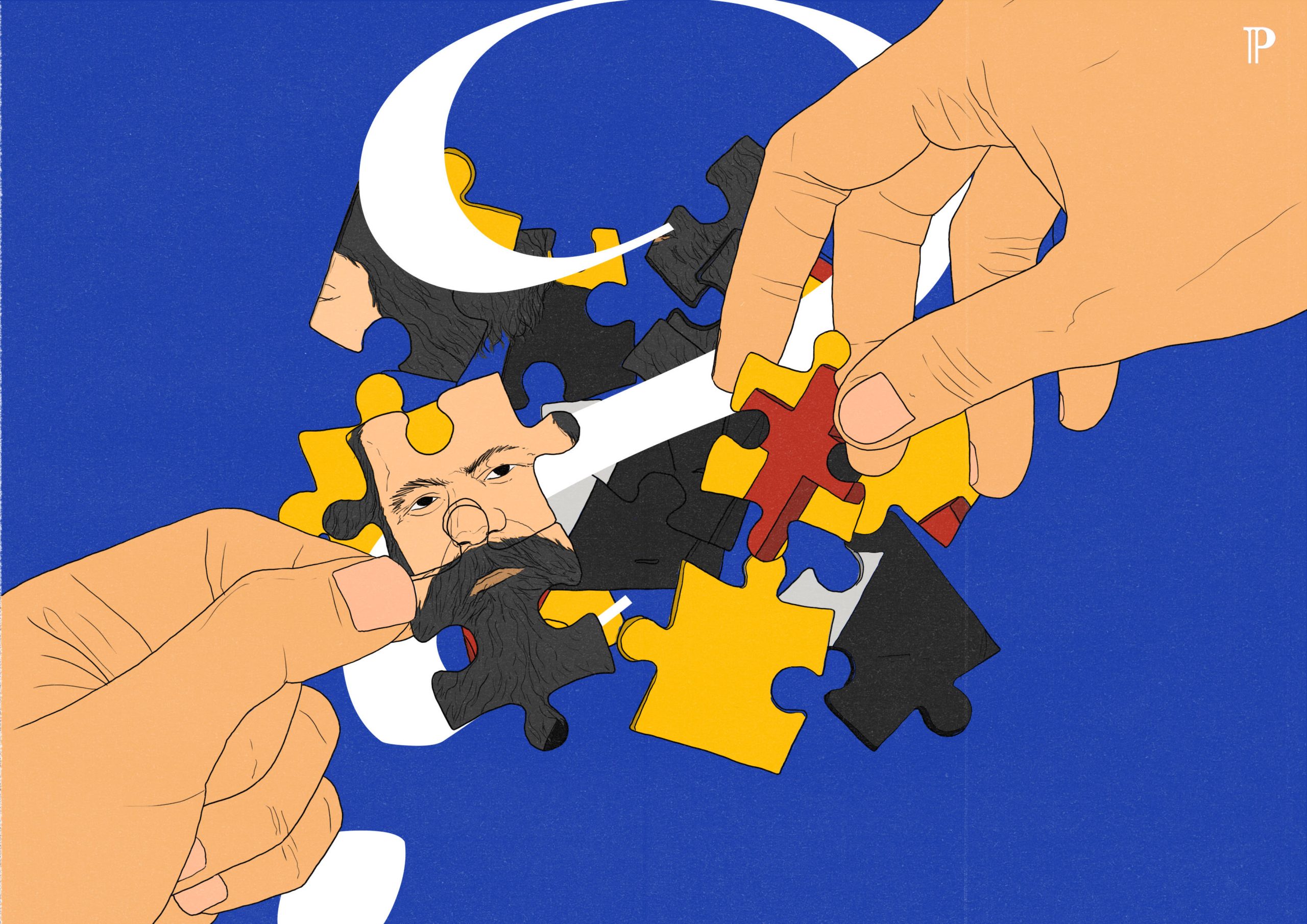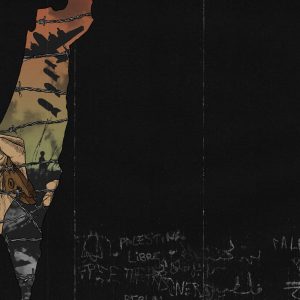Ilustrasi: illustruth
LAZIMNYA, para rohaniwan Kristen dari berbagai aliran cenderung menentang ideologi kiri serta organ-organ yang memang atau dianggap berafiliasi dengannya. Hal ini terlihat dari berbagai ensiklik seperti Nostis Et Nobiscum (1849) dan Rerum Novarum (1891). Meski menyayangkan kondisi pekerja yang semakin terpuruk dan sama-sama mengkritik “keserakahan berlebih”, “persaingan tak terkendali”, dan eksploitasi dari para pemodal, kedua surat edaran Paus tersebut juga menyatakan dengan tegas menolak sosialisme dan komunisme.
Bahkan, gereja Katolik memandang keduanya sebagai “ancaman” bagi kelas buruh. Nostis Et Nobiscum menggambarkan kaum sosialis dan komunis sebagai “pengacau” yang hidup subur dengan menciptakan “kekacauan” antara proletar dan kaum miskin dengan golongan lainnya. Mereka dipandang sebagai penghasut kaum tertindas untuk “mencuri” harta milik Gereja dan kelas atas serta “menipu” kelas bawah dengan memberi janji-janji palsu akan kehidupan yang lebih baik. Bahkan, ensiklik yang sama mengklaim bahwa kaum sosialis dan komunis di Italia mencoba membujuk kelas bawah untuk berpindah ke gereja-gereja Protestan, sebab gereja Katolik sudah tegas menentang mereka.
Adapun Rerum Novarum mengecam aspirasi kaum sosialis dan komunis mengenai kepemilikan bersama atas alat-alat produksi (dipahami gereja Katolik sebagai kepemilikan pribadi secara total). Ensiklik itu menegaskan bahwa kepemilikan pribadi adalah hal yang alami dan oleh karenanya menentangnya berarti melawan hukum alam dan hak asasi manusia. Dokumen yang sama menyatakan bahwa kepemilikan bersama yang dicita-citakan itu merugikan para “pemilik yang sah” dan, menurut interpretasi gereja, kelas buruh sebab mereka tidak lagi dapat menggunakan upahnya untuk memperbaiki taraf hidup.
Gereja-gereja Protestan pun setali tiga uang. Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), misalnya, mengeluarkan aturan bahwa umatnya yang menganut paham komunis (termasuk anggota Partai Komunis Indonesia/PKI dan atau organ-organnya) tidak diperbolehkan menerima perjamuan kudus (Van Klinken, 2014, hlm. 213). Gereja Kristen Sumba (GKS) pada tahun 1957 juga mengeluarkan peraturan serupa. Mereka baru boleh menerima perjamuan kudus setelah mengumumkan “pertobatan” di hadapan jemaat. Jika yang bersangkutan adalah pengurus gereja, mereka akan dicopot dari jabatannya. Peraturan ini dikumandangkan lagi pada 4 Desember 1965 sebagai bagian dari upaya penumpasan PKI di seluruh Indonesia (Van Klinken, 2014, hlm. 249).
Walau begitu, kelaziman selalu berdampingan dengan kejanggalan. Di tengah-tengah sikap gereja yang mengecam dan menentang komunisme, ada orang-orang yang “janggal”. Mereka di satu sisi merupakan bagian dari otoritas gereja (sebagai rohaniwan atau pendeta), tapi di sisi lain tidak menunjukkan permusuhan terhadap sosialisme dan komunisme. Lebih dari itu, mereka bahkan bergabung dengan organ-organ yang menganut aliran tersebut.
Hein Frederik Tampenawas: Domine-Nya Sarbupri
Hein Frederik Tampenawas mungkin harus menjadi salah satu nama yang langsung muncul ketika membahas rohaniwan Kristen yang “janggal”. Kejanggalan terbesar Hein adalah keanggotaannya di salah satu serikat buruh yang kelak berafiliasi dengan PKI, Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri).
Harian Rakjat edisi 22 September 1955 mencatat riwayat hidup Pdt. Hein secara singkat. Domine (sebutan lama untuk pendeta) Hein lahir di Kaweng, Kakas, Minahasa, pada 1898. Ia dikatakan menjalani pendidikan dasar di Sekolah Rakyat selama tujuh tahun, namun sebenarnya saat itu tidak ada sekolah dasar bumiputra. Kemungkinan besar ia masuk Sekolah Kelas Dua (Tweede Klasse School) yang masa belajarnya lima tahun dan terletak di keresidenan atau kawedanan. Keterangan “tujuh tahun” kemungkinan datang akibat masa studinya yang harus tertunda dua tahun.
Pdt. Hein kemudian lanjut di “sekolah Belanda” selama dua tahun. Kemungkinan, sekolah yang dimaksud adalah Kweekschool (Sekolah Guru), yang juga sekolah pilihan para calon pendeta Minahasa saat itu seperti Pdt. Hendrik Daandel. Setelah itu, ia masuk STOVIL (School tot Opleiding voor Inlandsche Leraren; Sekolah Guru Injil) di Tomohon belajar selama tiga tahun. Sekolah itu kini menjadi Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT).
Pada 1918, Pdt. Hein menjadi buruh perkebunan milik perusahaan bernama Moluksche Handels Vennootschap (MHV). Pertama-tama ia bekerja sebagai sebagai opzichter (pengawas) di perkebunan kopi “Tanauw” di selatan Manado, kemudian dipindahkan ke Manado menjadi wakil kepala gudang (magazijnmeester), dan terakhir di Pulau Talisei menjadi kepala pengawas (hoofdopzichter) di perkebunan kelapa “Talisse” pada 1941. Di era pendudukan fasis Jepang, Pdt. Hein diangkat menjadi Kepala Urusan Perkebunan di Minahasa.
Memasuki masa revolusi, tepatnya tahun 1947, ia ikut mendirikan Serikat Buruh Perkebunan Sulawesi Utara dan terpilih menjadi ketua cabang Sulut. Tiga tahun kemudian, setelah penyerahan kedaulatan, serikat buruh ini dilebur ke dalam Sarbupri. Pdt. Hein terpilih menjadi sekretaris umum Sarbupri cabang Sulut yang waktu itu juga meliputi wilayah Maluku Utara.
Bagaimana dengan karier kependetaannya sendiri? Pdt. Hein bukan pendeta yang ecek-ecek. Pada 1951, ia menduduki jabatan strategis dalam sinode (dewan) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM). Seperti diberitakan oleh Harian Rakjat tanggal 22 September 1955 dan Sin Po tanggal 9 September 1952, ia diangkat menjadi Kepala Tata Usaha dan bertugas di GMIM Sentrum Manado. Ia juga pernah bertugas sebagai pendeta di Tomohon (Pemandangan, 26 Januari 1955).
Di tahun 1955, ia sudah menjadi anggota pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sarbupri. Sebagai anggota pleno, Pdt. Hein menghadiri Kongres Kedua Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang diselenggarakan di Jakarta pada 9-20 Januari 1955 (Warta Sarbupri, 20 Januari 1955). Selain itu, ia juga diangkat menjadi anggota pleno SOBSI Sulut (Harian Rakjat, 20 Januari 1955). Tiga tahun sebelumnya, Pdt. Hein menjadi bagian dari utusan Indonesia yang menghadiri Konferensi Perdamaian Asia dan Pasifik di Beijing pada 2-12 Oktober 1952 (Sin Po, 9 September 1952).
Kesetiaannya pada Sarbupri dan kaum buruh sudah tak ayal lagi. Dia pernah ditawari masuk partai (tidak disebutkan namanya) dengan gaji sebesar Rp1.500, namun menolaknya secara halus dengan mengatakan, “lebih senang kerja untuk Sarbupri dengan honorarium yang tidak sampai Rp500.” (Harian Rakjat, 20 Januari 1955).
Kiprahnya di Sarbupri dan SOBSI membuat PKI tertarik untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota Dewan Konstituante dari kalangan non-anggota partai. Pencalonannya diumumkan pada 26 Januari 1955 (De Nieuwsgier, 26 Januari 1955; Pemandangan, 26 Januari 1955). Pdt. Hein mendapatkan Sulut/Tengah dan Sulawesi Tenggara/Selatan sebagai daerah pemilihannya (Kementerian Penerangan, 1956, hlm. 275, 278). Sayangnya dia tidak berhasil lolos. Setelah itu tidak ada lagi informasi yang bisa diperoleh tentangnya.
Ekhjopas Uktolseja: Wakil PKI di Konstituante
Jika Pdt. Hein gagal meraih kursi Konstituante, maka pendeta yang satu ini lebih mujur. Mengutip profil anggota Konstituante, Pdt. Ekhjopas lahir pada 14 Mei 1905 di Sirisori Amalatu (juga dikenal dengan Sirisori Serani), sebuah negeri (desa) Kristen di Saparua, Pulau Ambon. Dinamai demikian sebab ada pula negeri Sirisori Islam.
Pdt. Ekhjopas masuk STOVIL di Ambon pada 1923 dan lulus lima tahun kemudian. Setelah itu ia memulai pelayanan di Kepulauan Kei dan Aru. Ia juga menjadi directeur (kepala) di Kweekschool dan wakil pengurus sekolah Kristen di Tual. Jabatan ini diembannya dari 1928 hingga 1939. Ia mengakhiri kariernya di sini karena dipindahkan ke Patti (di Moa Lakor) sebab terlibat cekcok dengan seorang guru Belanda di Sekolah Martin Luther bernama M. de Wanna. De Wanna sendiri dipindahkan ke Sekolah HIS Kristen di Piru (Ambon Baroe, 9 September 1939).
Selain guru dan pendeta, Pdt. Ekhjopas juga anggota Sarekat Ambon. Pada 28 April 1934, dia diangkat menjadi anggota Central Comite Studiefonds Maloekoe (Komite Pusat Beasiswa Maluku) yang dibentuk untuk menggalang beasiswa guna memberi kesempatan para pemuda untuk berkembang secara spiritual (De Indische Courant, 1 Mei 1934).
Lima tahun kemudian, Pdt. Ekhjopas pindah ke Wonreli (di Pulau Kisar) dan bertugas di sana selama dua tahun. Ia kemudian pindah lagi ke Sanana (Pulau Sula Besi) pada 1941, kemudian ke Ternate dan Sofan (Pulau Taliabu) hingga 1945 dan bertugas di Kepulauan Sula. Dari tahun 1945 hingga 1947, ia bertugas di Hutumuri (Pulau Ambon) sebelum terakhir pindah ke Piru di Pulau Seram.
Setelah itu Pdt. Ekhjopas tidak lagi melayani umat di Kepulauan Maluku sebab pindah tugas ke Medan. Di sana ia bertugas sebagai pendeta di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel. Pengurus GPIB Immanuel memecatnya pada 7 Mei 1952, namun tidak jelas apa alasannya (Het Nieuwsblad voor Sumatra, 10 Mei 1952). Meski diberhentikan pada 1952, dalam profil anggota Konstituante tertulis bahwa Pdt. Ekhjopas masih bertugas di Medan hingga 1954.
Sama seperti Pdt. Hein, ia juga terlibat dalam Konferensi Perdamaian Asia dan Pasifik di Beijing pada 2-12 Oktober 1952 sebagai anggota panitia persiapan. Saat diwawancara oleh koresponden Harian Rakjat setempat, Pdt. Ekhjopas dengan tegas beroposisi terhadap Amerika Serikat. Dia menolak kebijakan embargo, bantuan militer, juga Mutual Security Act (MSA) yang ditawarkan ke berbagai negara guna menghambat penyebaran komunisme.
Selain itu, di momen ini pula sang putra Ambon menegaskan keanggotaan dalam panitia itu selaras dengan tugasnya sebagai seorang Kristen: untuk menjaga perdamaian. Ia pun menganjurkan umat Kristen untuk melakukan hal yang sama (Harian Rakjat, 14 Agustus 1952).
Pada 1955, Pdt. Ekhjopas pindah ke Pontianak dan bertugas sebagai pendeta GPIB setempat (Matondang, 1997, hlm. 117). Saat bertugas di sanalah dia dicalonkan PKI menjadi anggota Konstituante untuk daerah pemilihan Jawa Tengah dan Sumatra Utara dan berhasil terpilih (Kementerian Penerangan, 1956, hlm. 186, 250). Menurut Victor Matondang, tokoh Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Pdt. Ekhjopas dicalonkan dari golongan progresif nonpartai (Matondang, 1997, hlm. 117). Meski begitu, ia mewakili Fraksi PKI dan bukan Fraksi Republik Proklamasi seperti calon-calon nonpartai lainnya.
Menjelang Pemilihan Umum 1955, Pdt. Ekhjopas secara terbuka menulis ajakan untuk mendukung PKI. Ajakan itu dimuat dalam rubrik “Dari Hati Kehati” Harian Rakjat edisi 24 September 1955. Dalam artikel berjudul “Pilihlah Palu Arit” itu, Pdt. Ekhjopa mengecam penggunaan agama oleh kaum kapitalis untuk meraup modal sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan orang lain. Ia menyebut mereka sebagai “orang-orang yang sudah mati” (kalimat ini dikutip dari Lukas 9:60, yang sebenarnya tidak menyinggung keserakahan).
Di lain bagian, Pdt. Ekhjopa kembali mencela para kapitalis karena telah “sodorkan satu lagi ilah.” “Allah kapitalis ini,” katanya, “ternyata dipuja lebih keras dan disambut dengan lebih gembira oleh budak-budaknya.” Yang dimaksud tentu saja harta (baca: kapital). Pdt. Ekhjopas kemudian mengutip Matius 6:24. Di sana Yesus menegaskan untuk mengabdi kepada Allah semata dan tidak pada mamon atau harta.
Pdt. Ekhjopas juga menegaskan sekalipun agama tidak dapat diperalat oleh kaum kapitalis karena asalnya dari Tuhan, tetapi umat beragama harus waspada agar “jangan gila-gilaan dengan agama dan jangan biarkan agama dipermainkan.” Ia mengingatkan pentingnya bertanggung jawab atas rahmat Allah, sebagaimana Allah bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ia juga menyinggung tentang kehadiran “reformator-reformator” yang menyucikan “segala masjid dan gereja” dan menguduskan hati yang penuh dendam di tengah kekalutan dunia.
Bagian berikutnya berisi puji-pujian terhadap kemajuan yang diraih oleh demokrasi rakyat di Uni Soviet. Ia menggambarkan pemerintah Uni Soviet bak “ibu bapak” bagi rakyatnya. Untuk mengajak orang agar mendukung pemerintahan sosialis di sana, ia mengutip Roma 13:1 yang menyatakan bahwa semua pemerintah yang ada di muka bumi berasal dan ditetapkan oleh Allah. Terakhir, Pdt. Ekhjopas mendoakan agar komunisme itu sendiri segera terwujud di Indonesia. Baginya, hanya komunisme yang mampu memastikan terwujudnya hukum Allah di dunia ini, kemerdekaan bangsa dalam kehidupan bernegara dan beragama, menjadi “ibu bapak” bagi rakyat, dan menjamin keselamatan istri-istri dalam rumah tangga.
9 November 1956 menjadi tanggal penting bagi Pdt. Ekhjopas sebab di hari itu dia resmi menjadi anggota Konstituante. Berbagai sidang diikuti, termasuk pleno kedua yang diselenggarakan dari 30 Juli hingga 11 November 1958. Ia ikut dalam pembahasan asas-asas dasar Republik Indonesia untuk UUD yang baru (PKI dan Perwakilan, 1958, hlm. 20). Kita tahu bahwa Konstituante tak pernah sukses membuat konstitusi baru sebab dibubarkan Soekarno lewat dekret tanggal 5 Juli 1959.
Setelah itu, Pdt. Ekhjopas pindah ke Bogor. Victor Matondang mengisahkan bagaimana di sana Pdt. Ekhjopas memelihara berbagai hewan, terutama babi. Babi-babi itu dia potong sendiri dan dagingnya dijual ke Jakarta. Ia juga sering berkunjung ke kantor Parkindo yang terletak di rumah di belakang GPIB Immanuel untuk sekadar bercengkerama.
Pandangan politik yang janggal membuatnya bertentangan dengan jemaatnya sendiri. Beberapa tokoh jemaat bahkan terang-terangan melawannya, seperti G. M. A. Nainggolan yang saat itu anggota GPIB Depok. Agaknya, alasan serupa pula yang melatarbelakangi pemecatannya oleh pengurus GPIB Immanuel Medan. Matondang juga menerangkan bahwa sang domine menjadi tahanan politik (tapol) dan sempat diinternir di Pulau Buru (Matondang, 1997, hlm. 116-117). Sayang sekali, tidak diketahui bagaimana nasibnya setelah itu.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
J. Kagu: Disiksa karena Melawan Feodalisme
Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu wilayah yang masih didominasi oleh feodalisme di paruh keenam abad ke-20. Kekuasaan raja di sana sangat kuat sekalipun secara resmi sudah tidak lagi memegang kuasa. Para tuan tanah juga hampir tak tersentuh oleh kaum tani di bawahnya. Seorang pendeta dengan gigih menentang semua kesewenang-wenangan itu, sekalipun namanya tidak setenar dua tokoh pertama yang telah dikisahkan. Ia adalah Pdt. J. Kagu.
Pdt. J. Kagu kemungkinan besar adalah seorang pendeta GMIT. Tapi sayangnya tidak ada sumber detail yang meriwayatkan hidupnya. Cerita perjuangannya melawan feodalisme hanya dapat ditilik dalam sebuah takarir kecil pada gambar kader-kader Barisan Tani Indonesia (BTI) NTT yang dimuat dalam Suara Tani edisi Oktober 1960. Takarir itu menyebut bahwa pada September 1960 Pdt. J. Kagu dan para kader BTI disiksa hingga berlumuran darah karena melawan kebijakan kerja paksa yang berkedok “gotong royong” (Suara Tani, Oktober 1960).
Keterangan mengenai kasusnya disinggung sedikit lagi dalam tulisan S. M. Urbanus yang berjudul “Pulau2 Jang Menawan Hati”, dimuat di majalah Suara Tani bulan Januari 1961. Disebutkan bahwa penganiayaan terhadap Pdt. Kagu terjadi di Fatuleu (bagian dari Kabupaten Kupang). Ia bersama dengan 19 orang petani disiksa dengan cara dipukul hingga berdarah oleh seorang tuan tanah atas dasar kabar burung (Suara Tani, Januari 1961). Walau tidak menyebut namanya secara tegas, tetapi keterangan yang diberikan hampir sama dengan keterangan yang muncul pada takarir yang telah dibahas.
Memikul Salib dari Sisi Kiri: Sebuah Penutup
Demikian kisah singkat mengenai segelintir pendeta yang “janggal”. Sekali lagi, janggal karena walaupun bagian dari otoritas gereja, tokoh-tokoh ini tidak menunjukkan permusuhan terhadap sosialisme dan komunisme. Malahan, mereka bergabung dengan organisasi-organisasi yang (atau dianggap) mengusung ideologi tersebut.
Tulisan ini tentu tidak mampu menyebut semua rohaniwan yang “janggal”, tetapi setidaknya dapat menggambarkan bahwa pernah ada dinamika di gereja-gereja yang ada di Indonesia dalam menyikapi komunisme. Setidaknya nama-nama di atas telah membuktikan bahwa yang terjadi tidak hitam putih seperti yang umumnya dikisahkan.
Daftar Pustaka
Surat Kabar
“Studiefonds Maloekoe: Samenstelling van het bestuur”, De Indische Courant, 1 Mei 1934.
“Hasilnja perpoekoelan goeroe2 di Toeal”, Ambon Baroe, 9 September 1939.
“Ds Uktolseja: Rakjat terbanjak tjinta damai, bentji perang”, Harian Rakjat, 14 Agustus 1952.
“Irian Barat akan dibitjarakan dalam konperensi Perdamaian di Peking”, Sin Po, 9 September 1952.
“H.F. Tampenawas dan Purbodiningrat”, Harian Rakjat, 20 Januari 1955.
“Daftar Nama Utusan Sarbupri Dalam Kongres Ke II S.O.B.S.I.”, Warta Sarbupri, 20 Januari 1955.
“Nieuwe partijloze PKI-candidaten”, De Nieuwsgier, 26 Januari 1955.
“Lagi Orang2 Terkemuka Masuk Dalam Daftar ‘PKI’ ”, Pemandangan, 26 Januari 1955.
“Pemuka2 Agama”, Harian Rakjat, 22 September 1955.
Het Nieuwsblad voor Sumatra, 10 Mei 1952.
Uktolseja, Ekhjopas. “Pilihlah Palu Arit”, Harian Rakjat, 24 September 1955.
Buku dan Majalah
“Sidang Pleno Ke-II Konstituante Mulai Menghasilkan Beberapa Rumusan Setelah Tjara Kerdja Diubah”, PKI dan Perwakilan, Vol. 3, No. 4, Triwulan Keempat 1958.
Kementerian Penerangan (1956). Kumpulan Peraturan-Peraturan untuk Pemilihan Konstituante. Jakarta: Kementerian Penerangan.
Matondang, Victor. 1997. Victor Matondang: Sahabat Semua Orang. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Suara Tani, Vol. 11, No. 10, Oktober 1960.
Urbanus, S.M. “Pulau2 Jang Menawan”, Suara Tani, Vol. 12, No. 1, hlm. 6, Januari 1960.
Van Klinken, Gerry (2014). The Making of Middle Indonesia: Middle Classes in Kupang Town, 1930s–1980s. Leiden: Brill.
Sumber Internet
“Nostis et Nobiscum: On the Church in the Pontifical States”, Papal Encyclicals Online, 23 Desember 2024 (terakhir disunting). Diakses pada tanggal 24 Desember 2024.
“Rerum Novarum: On Capital and Labor”, Papal Encyclicals Online, 24 Desember 2024 (terakhir disunting). Diakses pada tanggal 24 Desember 2024.
Hidayat, Syahrul, dan Kevin W. Fogg. “Profil Anggota: Ekhjopas Uktolseja,” Konstituante.Net, 1 Januari 2018. Diakses pada tanggal 24 Desember 2024.
Tinungki, Iverdixon. “Hendrik Daandel, Kiprah Putra Siau Lepasan Stovil 1932”, Barta1.com, 13 Agustus 2019. Diakses pada tanggal 31 Desember 2024.
M. Jaris Almazani adalah mahasiswa S1 Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menaruh minat besar pada sejarah gerakan kiri di Indonesia