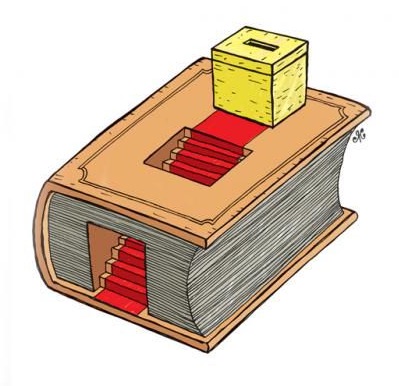POLITISASI SARA (suku-agama-ras) jelas telah memengaruhi proses hasil pilkada DKI 2017. Itu memang fakta terlepas bagaimana ia diperdebatkan, termasuk oleh beberapa tulisan di media kita ini. Berbagai diskusi publik dan tulisan akademisi segera meramalkan bahwa ketegangan sosial dan hasil pilkada dki 2017 ini akan berlanjut dan menjadi faktor menentukan situasi politik Indonesia, setidaknya hingga pemilu 2019.
Perdebatan soal politisasi SARA dan meningkatnya suasana sektarian berlangsung panas bahkan cenderung kacau balau (chaos) di berbagai media sosial yang kini menjadi sarana komunikasi mudah dan massal. Sementara ketakutan akan terjadinya kerusuhan di jalanan hingga potensi kudeta menjadi trauma sekaligus intimidasi bagi banyak kalangan di masyarakat kita. Sejauh ini mungkin kita bisa bersukur bahwa potensi kerusuhan masih terkendali. Tapi seharusnya kita memperlakukan kondisi saat ini sebagai peringatan keras bagi kalangan progresif dan pendukung demokrasi tentang perlunya mengevaluasi kelemahan analisa sosial kita sejauh ini.
Kegagalan analisa
Kegagalan penjelasan atas realitas politik tak pelak turut berpengaruh pada kegagalan mengantisipasi meruncingnya ketegangan sosial yang manifes dalam pembelahan posisi politik di tengah masyarakat saat ini. Fenomena politisasi SARA yang sangat kental dan brutal di pilkada DKI ini telah gagal diprediksi, salah satunya, oleh analisa politik pluralis. Pendekatan pluralis ini berpengaruh kuat di berbagai kajian yang mengamati perilaku pemilih.
Analisa pluralis dijejalkan oleh para pengamat dan media arus utama secara berlebihan dengan memamerkan adu versi lembaga survey pemilu. Pendekatan analisa ini terlalu dangkal karena mengandaikan kekuatan itu tersebar meluas di kalangan masyarakat. Siapa yang berkuasa adalah yang paling banyak disukai di antara aktor sosial yang disangka punya kekuasaan menyebar acak tersebut. Metode utama pendekatan ini adalah memotret dan mengukur persepsi (pendapat) masyarakat dengan keyakinan bisa menunjukkan perilaku individu-individu yang diandaikan memiliki kekuasaan rasional atas pilihannya.
Nyatanya para pendukung ilmu pengukuran perilaku pasca kekalahan Ahok mengaku kebingungan. Sebab, sebagaimana terekam oleh berbagai survey warga berulangkali konsisten menjawab memiliki tingkat kepuasan yang sangat tinggi terhadap kinerja petahana. Sebuah studi dengan argumen kelas[1] sebagai aktor dalam masyarakat menjadi mitra debat analisa kubu pluralis dan memengaruhi munculnya argumen interseksi. [2] Analisa studi ini melaporkan bahwa sentimen sektarian dan politisasi SARA oleh kelompok sektarian punya titik temu (interseksi) dengan rasa frustasi dan harapan perubahan terkait kesenjangan sosial yang dirasakan beberapa kelompok miskin kota.
Yang banyak menjadi sorotan dalam argumen interseksi/titik temu ini adalah peranan aktif dan destruktif dari kelompok-kelompok sektarian Islam garis keras. Mereka aktif melakukan mobilisasi massa di jalanan dan ruang hidup masyarakat (pemukiman, sekolah, tempat ibadah). Mobilisasi dan propaganda konfrontatif juga berlimpah di media sosial sejak akhir tahun lalu — bahkan sebetulnya bila mau ditarik lebih jauh sebagai keberlanjutan dari kontes pilpres 2014. Beberapa artikel di media kita sejak akhir tahun pun telah membahas dan berpolemik soal strategi mobilisasi massa “populisme” dan kebangkitan berbahaya dari sektarianisme.[3]
Kesadaran pragmatis menggunakan momen pilkada DKI menurut kajian ini terkait kebijakan cenderung intimidatif dari petahana yang mengincar berbagai kelompok miskin kota di DKI — terutama sejak gelombang penggusuran bantaran kali sekitar dua tahun lalu. Pilihan strategi pemprov DKI oleh petahana juga cenderung mengabaikan partisipasi dan dialog demokratis demi pembersihan cepat dan teknokratis atas masalah-masalah sosial yang ruwet di Jakarta. Strategi ini sempat berhasil dan menuai popularitas yang tinggi di kalangan publik yang sudah sangat frustasi dengan kelambanan birokrasi dan juga penguasa illegal di kehidupan jalanan keseharian Jakarta.
Sementara itu kita juga bisa menemukan analisa lain soal titik temu. Kecaman ditujukan berbagai kalangan terdidik kepada beberapa tokoh intelektual dan politik yang semula dikenal sebagai kalangan Islam moderat yang dianggap lawan dari kalangan Islam garis keras. Gubernur terpilih Anis Baswedan adalah tokoh yang dulu digadang-gadang sebagai salah satu simbol tokoh Islam moderat. Ia dibanggakan para penggemar Jokowi karena pilihannya bergabung sejak masa kampanye pemilu 2014. Nyatanya agenda berkuasa secara politik setelah dipecat dari kabinet Jokowi lebih penting buat tokoh yang dulu terkenal “menjual” retorika pentingnya pluralisme dengan jargon “tenun kebangsaan” ini.
Belakangan kritik tentang tokoh yang selama ini pamer citra moderat juga menyasar Wapres Jusuf Kalla, yang terungkap mendukung kandidat lawan petahana dan sekaligus punya banyak kepentingan ekonomi politik di pembangunan infrastruktur, termasuk di DKI.[4] Sementara itu Eep Saifulah Fatah sebagai tim sukses kandidat Anis-Sandi, juga sejak lama dikenal publik dengan citra sebagai tokoh intelektual muslim yang moderat dan diharapkan menjadi pemikir demokrasi yang sehat. Tapi pilkada DKI ini mengungkap posisi Eep yang lebih mengutamakan kepentingan bisnis “political marketing”-nya di atas agenda apa pun lainnya.
Singkatnya, argumen “interseksi” seperti diuraikan dalam berbagai versi di atas, adalah soal titik temu antara politisasi SARA dan kepentingan oportunisme lewat medium pertarungan elit di pemilu. Ini dapat dilakukan siapa saja baik itu kalangan intelektual atau pun kelompok marjinal. Analisa ini umumnya mengedepankan bukti-bukti tentang mereka yang di suatu masa mengaku moderat atau terkategori non elit (miskin kota, buruh) namun tak segan mendukung fanatisme SARA di momen pilkada kali ini.
Di sini lah analisa interseksi menjadi penjelasan yang sama buntu dan mengecohkannya dengan analisa pendekatan pluralis. Konsekwensi logis lanjutan dari analisa ini adalah semua aktor sosial bisa menjadi oportunis akibat pemilu. Oportunisme para aktor sosial yang ditunjukkan oleh argumen interseksi rentan terperangkap dalam perdebatan soal pengkhianatan moral versus komitmen terhadap kemajemukan semata. Perdebatan moral semacam ini melelahkan sekaligus minim penjelasan yang mencerahkan apalagi menawarkan solusi progresif. Argumen interseksi, karenanya juga, punya resiko semakin menyuburkan antipati pada demokrasi elektoral secara tidak kritis. Antipati yang sesungguhnya mengancam demokrasi sejati justru karena praktik demokrasi yang sejak lama diperjuangkan kalangan progresif sejak masa Orde Baru adalah melawan agenda pendukung otoriterisme dan oligarki: pemilihan umum secara langsung untuk posisi-posisi pejabat publik.
Kebutuhan analisa kelas marxis.
Sekali pun mengakui adanya titik temu dengan faktor keresahan sejumlah kelompok marjinal atas kecenderungan ketidakadilan sosial, namun pendukung pendekatan pluralis bersikukuh bahwa fakta-fakta yang terekam dari jajak pendapat (survey, exit poll, dll) mendukung tesis “faktor agama” sebagai yang lebih menentukan. Prediksinya, situasi politik Indonesia ke depan terkait kontestasi menuju pemilu 2019 akan ditentukan oleh faktor tersebut. Konsekwensi dari prediksi ini bisa memengaruhi kekisruhan lebih lanjut untuk memahami kompleksitas politisasi SARA dan juga strategi apa yang harusnya dikembangkan kalangan progresif. Kompleks karena diceraikannya hubungan antara fenomena yang terlihat kasat mata soal politisasi SARA dengan penjelasan analisa kelas yang mencoba mengungkap realitas di balik yang tampak kasat mata tersebut.
Argumen tentang “faktor agama dan ras” serta “interseksi” sebetulnya seolah mengakomodir adanya dimensi kelas oleh beberapa survey dan exit poll dengan menggunakan kelas sebagai kategori penduduk dengan latar belakang pendapatan dan pendidikan (tinggi-sedang-rendah).[5] Dengan menggunakan konsep kelas semacam itu mereka menunjukkan bahwa “faktor agama” lebih menentukan pilihan di pilkada DKI. Tentu saja itu bukan lah analisa kelas marxis yang justru mesti membahas kelas dalam kaitannya dengan kapitalisme sebagai relasi dan proses produksi serta perjuangan kelas yang nyata dan berlangsung menyejarah hingga saat ini di masyarakat.
Sangat jelas bahwa mereka yang terlibat dalam titik temu oportunisme lewat arena elektoral/pemilu langsung semuanya menyadari bahwa sentimen sektarian dan politisasi SARA adalah bahan baku yang sejalan dengan penataan kompetisi ekonomi politik di era kapitalisme agresif yang berlaku secara global saat ini. Analisa kelas yang kritis tidak akan mengabaikan kepentingan dan kekuatan mereka yang terlibat signifikan dalam menentukan jalannya kapitalisme di Indonesia. Dalam hal ini, kita berbeda dengan analisa pluralis karena kita tidak bisa mengabaikan faktor yang menentukan jalannya kapitalisme di Indonesia sepanjang sejarah, yaitu kekuatan militer dan imperialis yang sudah terkenal dengan keahliannya dalam menyuburkan dan mengorkestrasi sektarianisme SARA.
Perlu dijernihkan bahwa editorial ini tidak menyarankan agar data dan informasi yang diungkap berbagai analisa non-marxis itu harus dibuang jauh-jauh. Akan tetapi untuk memahami realitas politisasi SARA yang tidak terpisah dari dinamika kapitalisme maka kita harus membacanya dalam kerangka ekonomi politik dan analisa pertentangan kelas. Data dan informasi yang sudah ada harus didorong untuk dianalisa lebih mendalam lagi dalam konteks ruang, relasi, dan proses yang dimungkinkan oleh logika keutamaan persaingan pasar dan produksi kapitalis yang aktual di Jakarta dan Indonesia saat ini.
Kita tentu sadar analisa marxis tidak punya ruang bergerak yang leluasa di kalangan akademisi Indonesia, salah satunya karena langgengnya pelarangan oleh Negara hingga saat ini. Akan tetapi justru momen meningkatnya potensi ketegangan dan ledakan sosial pasca pilkada DKI 2017 membuat analisa kelas marxis yang kritis, tajam, dan tepat sangat mendesak dan relevan sampai ke kesadaran kaum progresif dan tentu saja massa secara luas. Evaluasi atas kelemahan analisa politik guna memahami realitas politik seharusnya terkait dengan kebutuhan menyusun strategi dan pengorganisasian perjuangan kelas ke depan. Tentu tidak akan dibahas di editorial kali ini, tapi harapannya perdebatan tentang strategi dan pengorganisasian akan banyak muncul lebih banyak dalam berbagai tulisan IndoPROGRESS ke depannya.***
————–
[1] http://www.newmandala.org/making-enemies-friends/
[2] http://www.newmandala.org/economic-injustice-identity-politics-indonesia/
[3] https://indoprogress.com/2017/01/merebut-populisme/, https://indoprogress.com/2017/01/menguatnya-populisme-trump-brexit-hingga-fpi/, https://indoprogress.com/2017/02/yang-patut-dikhawatirkan-adalah-politik-yang-rasis-bukan-populisme-islam/
[4] https://indoprogress.com/2017/04/sisi-lain-pilkada-jakarta-kembali-surutnya-kapitalisme-negara/
[5] http://www.newmandala.org/economic-injustice-identity-politics-indonesia/ dimana kalau kita memblejeti secara kritis data statistik yang dipaparkan dalam artikel ini kita sebetulnya bisa mengajukan interpretasi yang berbeda sama sekali dan justru mendukung arti siginifikan dari dimensi kelas secara kritis.