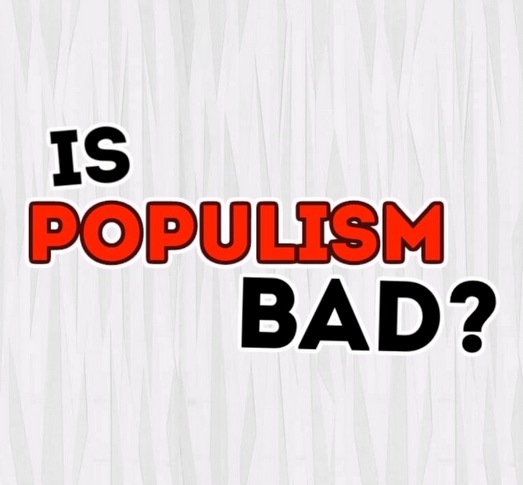DALAM beberapa masa ke depan, politik Indonesia akan tetap berada dalam bayang-bayang kebangkitan populisme. Dari konteks nasional, efek dari mobilisasi populisme Islam (baca: kanan) 411 dan 212, masih akan mewarnai dinamika politik yang ada melalui balutan artikulasi Islam Politik yang sangat rasis, bahkan memiliki kecenderungan fasis. Sementara dari faktor internasional, retorika dan kebijakan politik anti imigrasi dari pemerintahan Donald Trump di AS, serta kelanjutan dari sentimen politik Brexit akan mengamplifikasi rasisme dan sektarianisme di tingkatan global. Situasi yang tentu memperdalam karakter illiberal dalam demokrasi Indonesia, dimana demokrasi kita bukan hanya ditandai dengan supremasi kekuasaan kelas pemodal, namun juga diiringi dengan menguatnya kondisi politik yang semakin hari semakin berkecenderungan rasis.
Situasi ini tentu berbahaya. Karena itu gerakan rakyat memerlukan perspektif atas situasi yang ada. Ada beberapa proposal mengenai bagaimana sebaiknya kita melihat perkembangan yang ada. Pandangan pertama muncul dari argumen bahaya populisme itu sendiri. Argumen ini tampak pada artikel Ari A. Perdana yang beranggapan bahwa populisme merupakan ancaman bagi demokrasi sekarang. Oleh karenanya populisme dilihat sebagai penyakit dari dinamika politik kontemporer yang semakin mengglobal . Mengulang posisi Huntington tentang “Benturan Peradaban”, Ari berpendapat bahwa keterbukaan global sekarang (atau disebutnya sebagai “kosmopolitan liberal”) menciptakan ketidakamanan nilai-nilai lama. Masuknya identitas dan kebudayaan baru menyerang keberadaan nilai-nilai lama yang dianut oleh mayoritas warga. Hal ini kemudian menciptakan respon balik yang reaksioner, dimana warga mayoritas ini merasa bahwa mereka harus mengklaim ulang kepemilikan nilai-nilai masyarakat yang ada melalui penolakan terhadap identitas baru yang dianggap liyan oleh mayoritas tersebut.
Sementara perspektif yang lain mencoba menempatkan kebangkitan populisme dari masalah pertarungan kepentingan dalam ranah ekonomi-politik. Di sini kalangan populis dianggap sebagai bagian dari kekuatan lama yang hendak melawan dominasi elit baru. Hal ini, setidaknya, secara implisit disampaikan oleh Bonnie Setiawan. Bonnie menganggap bahwa elit baru (yang disebutnya sebagai “borjuis putih”) hendak mendorong agenda kapitalisme modern yang berimplikasi pada peminggiran elit-elit lama yang selama ini diuntungkan dengan modus akumulasi rente.
Walau terlihat berbeda, dua perspektif ini setidaknya berangkat dari asumsi yang sama, bahwasannya artikulasi populis yang berkembang sekarang adalah suatu kondisi patologi dari perkembangan demokrasi liberal. Bedanya terletak pada penekanan. Bagi Ari patologi ini berasal dari ketidaksiapan sistem demokrasi terhadap perubahan relasi budaya karena globalisasi, sementara menurut Bonnie masalahnya terletak pada ‘kanker’ kekuatan lama yang masih bercokol dalam lingkar kekuasaan yang ada.
Dua argumen ini berada dalam posisi “dua sisi dari satu koin yang sama”, yakni sama-sama memiliki keterbatasan epistemologi. Observasi Ari secara sengaja mengabaikan peminggiran sistematis kekuatan sosial dalam masyarakat yang ada yang difasilitasi oleh institusi demokrasi itu sendiri. Peminggiran yang difasilitasi oleh kombinasi antara dominasi pengelolaan ekonomi (kapitalisme) neoliberal yang disertai dengan depolitisasi demokrasi liberal melalui pengerdilan ruang politik sebatas politik formal (pemilu dll). Peminggiran ini yang kemudian dimanfaatkan oleh elit-elit politik yang sedang bertarung dengan menggunakan retorika populistis dalam rangka mendapatkan dukungan dalam ruang demokrasi yang ada. Oleh karenanya, tidak ada yang alamiah (baca: esensial) dari identitas atau kebudayaan suatu masyarakat. Asumsi Huntingtonian yang diusung Ari perlu untuk dikubur selama-lamanya karena asumsi esensialis ini.
Sementara argumen Bonnie keliru untuk mengidentifikasi pola pertempuran politik yang ada. Apa yang yang disebutnya sebagai ‘borjuasi putih’ adalah angan-angan karena, ia bukanlah kategori sosial yang dapat secara distingtif dipisahkan dari kekuatan yang lama. Kekuasaan elit baru, seperti Ahok atau Jokowi, misalnya, masih sangat tergantung dengan topangan elit lama tertentu. Oleh karenanya, walau mereka terlihat mengusung agenda “modernisasi”, namun agenda ini tidak serta merta akan menantang kekuatan politik lama. Selama agenda ini tidak bertentangan dengan kepentingan langsung elit lama, agenda-agenda tersebut tentu dipersilahkan untuk diimplementasikan.[1] Disinilah tawaran Bonnie secara implisit justru membuat kita harus pula mendukung kekuatan lama yang ikut dalam gerbong “borjuasi putih” ini, yang dengannya justru menciptakan pertanyaan mengenai perubahan relasi kuasa.
Untuk itu, alih-alih dilihat sebagai patologi, populisme perlu ditempatkan sebagai gejala dari problem internal ekonomi-politik demokrasi yang berlaku sekarang. Karena kepentingan untuk menciptakan masyarakat pasar yang kompetitif, neoliberalisme menciptakan masyarakat yang sangat rentan karena minimalnya perlindungan Negara. Hidup yang rentan ini semakin diperparah ketika masyarakat tidak memiliki kanal ke politik Negara. Struktur Negara yang ada sudah semakin kebas dari kepentingan masyarakat yang terkena dampak kerentanan itu sendiri. Oleh karenanya politik serta capaian Negara yang ada menjadi sekadar sarana penguasaan segelintir kelompok elit. Hal inilah yang kemudian menciptakan kondisi material bagi perasaan marah dari mereka yang terpinggirkan yang menjadi bahan bakar bagi pemberontakan terhadap sistem politik yang elitis.
Yang diperlukan kemudian adalah menyasar problem strutkural yang dikritik dalam populisme mengenai sistem demokrasi. Depolitisasi demokrasi liberal yang membatasi proses politik pada sebatas institusi formal tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya bentuk demokrasi. Mobilisasi politik populis membuka kemungkinan untuk melawan dominasi politik elit yang secara strutkural diuntungkan oleh pola pengaturan formal demokrasi liberal. Untuk itu politisasi lebih dalam menjadi krusial dalam perkembangan populisme sekarang.
Akan tetapi politisasi untuk politisasi itu sendiri tidak mencukupi. Kita juga harus sadar bahwa populisme yang muncul sekarang adalah buah dari politisasi faksi elit tertentu yang telah terpinggirkan dalam pertarungan politik formal. Pertanyaannya kemudian, apa agenda politik yang harus diusung agar populisme memiliki kapasitas emansipatif? Jawabannya terletak pada perjuangan politik anti kapitalisme neoliberal itu sendiri. Kerentanan sosial yang dihadapi oleh mayoritas populasi harus diatasi dengan menciptakan agenda kesejahteraan sosial yang universal atau biasa disebut dengan politik sosialis.
Perspektif ini penting karena kerentanan sosial di era neoliberal sekarang bukan hanya sekedar dialami oleh kelas pekerja, tapi juga kelas menengah. Karena terpaan kompetisi bebas yang diciptakan oleh kebijakan neoliberal, kelas menengah yang ada sekarang memiliki resiko yang sama untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Di sini kita menemukan karakter lintas kelas dari politik populis versi kiri. Mungkin selama proses pengorganisiran kita akan menemukan aspirasi yang berbeda (karena posisi kelasnya tentunya!), namun hal ini dapat diantisipasi selama artikulasi politik sosialis dibangun secara inklusif dan menyasar musuh politiknya secara konsisten, yakni kalangan elit berkuasa. Pengalaman kampanye Bernie Sanders di AS dan Jeremy Corbyn di Inggris menunjukan bahwa metode seperti ini dapat dilakukan.
Dalam salah satu karya lawas yang sempat terlupakan, Politics and Ideology in Marxist Theory, Ernesto Laclau sempat berujar tentang “sosialisme sebagai tahapan tertinggi dari populisme.” Di era ketika populisme semakin memasuki relung percakapan publik kita, ujaran ini semakin kuat relevansinya sebagai agenda politik gerakan sosialis Indonesia. Untuk itu, daripada kita menghindari masalah populisme, lebih bermakna bagi kita untuk segera merebut populisme!***
Penulis adalah anggota Partai Rakyat Pekerja (PRP)
—————
[1] Tidak heran jika yang disebut dengan agenda ‘modernisasi’ ini sendiri bekerja secara selektif; misalnya bisa kita lihat pada bagaimana Ahok mengangkangi proses hukum dalam kasus penggusuran Bukit Duri, walau ia sendiri selalu gencar mempromosikan agenda penegakan hukum. Hal ini mengingat agenda penggusuran yang sangat krusial bagi kepentingan elit Jakarta itu sendiri, terlepas apakah elit tersebut berasal dari kekuatan lama atau bukan.