Judul : The Contours of Mass Violence in Indonesia, 1965-68
Editor : Douglas Kammen dan Katharine McGregor
Penerbit : Honolulu, Asian Studies Association of Australia dan University of Hawai’i Press
Tahun : 2012
PEMBANTAIAN massal tahun 1965 adalah peristiwa yang paling gelap dalam sejarah republik ini. Kira-kira setengah hingga sejuta orang mati terbunuh dalam peristiwa mengerikan tersebut. Dari segi kuantitas, pembantaian ini bahkan menyamai jumlah yang terbunuh saat genosida di Rwanda tahun 1994. Namun, tidak seperti genosida di Rwanda, dunia internasional tampaknya tidak peduli untuk mengungkit hal ihwal pembantaian di Indonesia ini.
Hingga kini pembantaian itu lebih banyak menyisakan pertanyaan daripada jawaban. Bahkan kita gagap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling umum seperti: Mengapa pembunuhan itu terjadi? Dimana saja terjadinya? Siapa yang melakukannya? Siapa yang menjadi korban? Dimana para korban dikuburkan?
Usaha-usaha untuk menyelidikinya pun tidaklah mudah. Selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru, pemerintah Indonesia menutup semua celah untuk melakukan penelitian mendalam soal pembantaian ini. Ironisnya, setelah Orde Baru tumbang sekali pun, kesulitan-kesulitan untuk menyelidikinya tetap ada. Tantangan datang tidak saja dari negara – khususnya dari militer Indonesia – namun juga dari masyarakat sipil. Sebagian dari kelompok masyarakat sipil ini diperalat oleh militer dan negara. Sebagian lainnya memang murni lahir dari ‘komunisto-phobia’ yang melanda (khususnya) golongan agama.
Kekurangan informasi dan kajian tentang pembantaian 1965 itulah yang ingin dilengkapi oleh buku ini. Pembuatannya diawali dengan sebuah konferensi ilmiah tiga hari di National University of Singapore. Para editor memilih sembilan tulisan dari peserta konferensi itu yang kemudian dikompilasikan dalam sebuah buku. Tulisan-tulisan tersebut dianggap mewakili beragam pikiran yang muncul dalam konferensi tersebut.
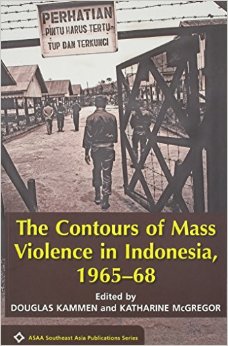
***
Pada bagian awal, dua editor dari buku ini menulis sebuah Pengantar yang membawa pemahaman baru terhadap pembantaian massal ini. Pertanyaan yang mereka ajukan mendasar: mengapa pembunuhan massal ini terjadi? Kedua editor ini sepintas menyinggung beberapa teori yang menyebutkan mengapa pembantaian massal ini terjadi, misalnya perbedaan ideologi yang sangat ekstrem, kompetisi tajam antar partai politik, soal perebutan tanah di pedesaan, ekonomi yang memburuk karena hiper-inflasi, kekurangan pangan, dan lain sebagainya. Sekalipun penjelasan-penjelasan ini tampak meyakinkan, namun tidak seluruhnya benar. Mungkin satu sebab itu bisa menjelaskan satu keadaan khusus di tingkat lokal. Namun sulit untuk dipakai dalam menganalisa keseluruhan pembunuhan massal.
Banyak ahli yang memusatkan kajian pada korban menyebutkan bahwa pembantaian massal ini adalah sebuah usaha untuk mengeliminasi PKI dari panggung politik Indonesia. Editor buku ini mengkritik pandangan tersebut, dimana menurut keduanya terlalu oversimplikasi. Mereka berargumen bahwa usaha pemberantasan terhadap PKI sesungguhnya sedikit banyak telah dituntaskan pada bulan Desember 1965. Sejak saat itulah saingan politik utama TNI-Angkatan Darat sudah habis. Langkah Angkatan Darat berikutnya adalah membabat kekuasaan Soekarno yang pada ujungnya menjungkalkannya dari kekuasaan pada bulan Maret tahun 1966. TNI-Angkatan Darat tidak berhenti sampai disana. Mereka mulai membersihkan tubuh tentara dan birokrasi dari orang-orang Kiri. Mereka kemudian juga membersihkan partai-partai politik.
Semua ini dilakukan oleh TNI-Angkatan Darat dengan kecepatan dan efisiensi yang sangat mengagumkan. Mereka menunggangi kondisi sosial yang memang sudah matang karena persaingan politik dan ideologis yang telah ada sebelumnya. Menurut kedua editor ini, pandangan yang mengatakan bahwa pembantaian massal adalah bentuk penghancuran PKI dalam konteks perang dingin sesungguhnya penjelasan yang mengabaikan dimensi politik dari kekerasan ini. Pembantaian massal tahun 1965 tidak hanya berhenti pada penumpasan kekuatan politik Kiri dan pembantain kaum Kiri. Namun, demikian argumen mereka, pembantaian massal ini adalah “sebuah reorganisasi segenap kekuatan sosial dan reintegrasi Indonesia ke dalam ekonomi dunia kapitalis” (cetak miring dari saya). Singkatnya, pembantaian massal ini adalah sebuah kontra-revolusi (hal. 11).
***
Tulisan-tulisan dalam buku ini berusaha untuk mengkaji pembantaian massal 1965 dari berbagai aspek. John Roosa, misalnya, mencoba mencari titik terang dari bagian yang paling gelap dan paling sering diklaim sebagai alasan untuk melakukan pembantaian massal, yakni Gerakan 30 September. Roosa mengelaborasi argumen-argumen yang pernah ditulis dalam bukunya, ‘Dalih Pembunuhan Massal’ (Pretext to Mass Murder) itu. Dia menelaah argumen resmi pemerintah Orde Baru yang mengkaitkan Gerakan 30 September dengan PKI, dan kemudian dengan pembantaian massal. Roosa memakai konsep ‘aporia,’ yakni hal yang secara individual kelihatan masuk akal namun secara keseluruhan jalinan logikanya akan berantakan, untuk menelaah argumen resmi Orde Baru tersebut. Alhasil, John Roosa menyimpulkan bahwa Gerakan 30 September memang hasil kerjaan Biro Chusus Politbiro PKI, namun sangat sulit untuk menghubungkannya dengan PKI secara keseluruhan. Apalagi dipakai untuk menjustifikasi pembantaian massal.
Pada bagian yang lain, Brad Simpson berusaha mengungkap dimensi internasional dari pembantaian massal ini. Dari riset mendalam terhadap dokumen-dokumen sejarah yang tersedia, Simpson berpendapat bahwa Amerika dan negara-negara Barat memang dari sejak awal menginginkan Indonesia diperintah oleh penguasa otoriter. Ini dilakukan lewat kerjasama dengan militer dan intelektual sipil pro-Barat yang jengah dengan sistem demokrasi parlementer yang tidak bisa membawa stabilitas dan pembangunan ekonomi. Dari sinilah lahir ‘proyek PRRI’ – pemberontakan di daerah-daerah yang ditulang punggungi oleh militer.
Namun, hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat memburuk karena konfrontasi dengan Malaysia. Sementara itu, setelah kegagalan proyek PRRI, kekuatan PKI malah makin meningkat. Hingga muncullah percobaan kudeta G30S yang kemudian terbukti membawa berkah untuk Amerika dan negara-negara Barat.
Dalam artikelnya, Simpson merinci bagaimana Amerika dan sekutu-sekutunya membantu militer Indonesia. Sekalipun usaha kudeta ini cukup mengejutkan bagi Amerika, namun mereka bertindak cepat untuk membantu militer Indonesia. Dalam beberapa jam setelah mendengar berita usaha kudeta gagal itu, Amerika sudah menyiapkan daftar bantuan untuk militer Indonesia. Beberapa minggu setelah kudeta, tentara menghubungi kedutaan besar Amerika di Jakarta untuk meminta bantuan.
Amerika dan para sekutunya tahu persis akan pembantaian terhadap anggota-anggota PKI dan organisasi afiliasinya, namun mereka tidak mengambil tindakan apapun. Tetapi Simpson tidak beranjak lebih jauh dengan mempersoalkan hal yang paling sering menjadi kontroversi, yakni pemberian daftar elit PKI yang harus dibunuh.
Hal yang paling penting dari kajian Simpson adalah bantuan besar-besaran yang diberikan Amerika kepada regim Soeharto yang baru berkuasa. Sebagai balasan, Soeharto dan para teknokratnya pun menuruti apapun yang dikehendaki oleh Amerika. Sebagai contoh, Simpson menyebutkan bagaimana Rancangan Undang-undang Penanaman Modal Asing dibikin oleh perusahan konsultan bernama Van Sickel Associates yang bekerjasama dengan Widjojo Nitisastro (arsitek utama ekonomi Orde Baru, sering disebut sebagai ‘tetua’ Mafia Berkeley). Rancangan Undang-undang itu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak Kedutaan Besar Amerika. Dari situ pulalah, Amerika bisa mendapatkan akses untuk mengeksploitasi sumber mineral Indonesia, termasuk Freeport.
***
Tulisan-tulisan selanjutnya membahas dinamika pembantaian di daerah-daerah. Mungkin bagian inilah yang paling menarik dari buku ini. Pembantaian di setiap daerah memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Variasi itulah yang memberikan banyak nuansa. Seperti misalnya, mengapa di satu daerah jumlah korban pembantaian rendah sementara sangat tinggi di daerah lain? Taruhlah misalnya pembantaian di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Jumlah korban yang dibantai di Jawa Tengah mencapai ratusan ribu jiwa, sementara di Jawa Barat hanya sekitar sepuluh ribu. Padahal jumlah anggota PKI di kedua daerah itu tidak jauh berbeda. Ternyata, perbedaan itu terjadi karena latar belakang sejarah di kedua daerah tersebut dan kemauan militer mempersenjatai rakyat sipil untuk melakukan pembunuhan. Di daerah-daerah dimana terjadi pemberontakan Darul Islam (seperti di Jawa Barat) tentara tidak mempersenjatai milisi sipil untuk melakukan pembantaian.
Ini jelas terlihat dari tulisan Douglas Kammen dan David Jenkins yang membahas peranan RPKAD (Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat) dalam pembantaian di Jawa Tengah dan Bali. RPKAD (yang sekarang menjadi Kopassus) benar-benar merupakan mesin pembunuh. Karena militer lokal (seperti Kodam Diponegoro di Jawa Tengah atau Brawijaya di Jawa Timur) memiliki banyak tentara yang menjadi simpatisan PKI, maka tugas RPKAD adalah membersihkan tubuh militer. Selain itu, mereka memobilisasi rakyat sipil untuk melakukan pembunuhan. Sehingga, bagaikan malaikat maut, kemana saja pasukan RPKAD melangkahkan kakinya pada saat itu maka hampir pasti ribuan nyawa tercabut.
Soal pembunuhan oleh rakyat sipil itulah yang menjadi subyek bahasan Greg Fealy dan Katharine McGregor. Mereka berupaya mengupas peranan jaringan Nahdlatul Ulama (terutama sayap organisasinya seperti Ansor dan Banser) dalam hubungannya dengan komandan-komandan militer di Jawa Timur. Hal yang penting untuk dicatat dalam bab ini adalah bahwa dalam hubungannya dengan militer, NU tidak hanya dipakai untuk melakukan pembunuhan, namun juga, dalam beberapa kasus, mencegah terjadinya pembantaian yang lebih luas.
Kekerasan tahun 1965 tidak hanya berhenti pada pembantaian. Dia juga merambah ke bidang lain yakni penahanan, pemenjaraan, dan kerja paksa. Kasus etnik Tionghoa di Sumatra Utara dan para tahanan PKI di Sulawesi Selatan menjadi contoh nyata. Dalam kasus etnik Tionghoa di Sumatera Utara, sekalipun mereka bukan sasaran utama dari kekerasan anti-komunis, namun mereka mengalami masa penahanan yang lebih lama. Penyebabnya adalah adanya negosiasi dan pertentangan di kalangan kelompok-kelompok anti-komunis di Sumatera Utara yang kemudian menjadikan etnik Tionghoa sebagai sasaran. Sementara, di Sulawesi Selatan para tahanan politik Kiri selain dipenjara juga harus melakukan kerja paksa. Dalam bab yang ditulis oleh Taufik Ahmad jelas sekali tampak bahwa perwira-perwira militer mengambil keuntungan dari kerja paksa para tahanan tersebut.
Salah satu aspek yang jarang diperhartikan menyusul pembantaian tahun 1965 dan penghancuran PKI adalah reaksi para kader PKI itu sendiri. Satu studi yang ditulis oleh Vannessa Hearman persis menelaah soal ini dengan studi kasus Blitar Selatan. Menurutnya, sisa-sisa kader PKI berusaha bertahan di perbukitan kapur Blitar Selatan. Berlawanan dengan anggapan tentara Indonesia yang mengklaim ‘basis PKI’ di Blitar Selatan adalah kelompok bersenjata, Vannessa Hearman menunjukkan bahwa tujuan utama para kader ini ke Blitar Selatan adalah untuk mengungsi. Kesulitan persenjataan dan ketatnya kontrol oleh tentara mengakibatkan tidak mungkinnya dibentuk kelompok gerilya. Vannessa menggambarkan teknik-teknik ‘penumpasan’ sisa-sisa Komunis di Blitar Selatan yang brutal, yang mana akibatnya lebih banyak mengenai kaum perempuan dan anak-anak.
Dua tulisan berikutnya adalah tentang dinamika di Jembrana, Bali, dan tentang kuburan massal. Penelusuran lebih jauh oleh Mary Ida Bagus di Jembrana memperlihatkan bahwa politik lokal didominasi oleh dua klan aristokrasi yang saling beradu dalam pembunuhan massal. Yang pertama adalah klan yang dipimpin oleh Anak Agung Sutedja, gubernur Bali pertama, sementara yang kedua adalah klan Guru Wedastra Suyasa. Sutedja adalah gubernur yang sangat dekat dengan Soekarno. Sementara Suyasa adalah pemimpin PNI (Partai Nasional Indonesia). Sutedja menghilang (tepatnya: dihilangkan) saat dia berkunjung ke Jakarta karena dipanggil presiden Soekarno. Hingga kini nasibnya tidak diketahui. Sementara, Suyasa memimpin Tameng, milisi PNI yang menjadi ujung tombak pembantaian di Bali. Namun setelah Soeharto berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya, PNI pun ditindas habis.
Pembantaian besar-besaran tidak pelak membuat persoalan tentang kuburan. Sementara banyak terdengar bahwa mayat-mayat korban pembantaian dibuang di sungai atau di luweng-luweng (sumur yang sangat dalam yang terdapat di gua pegunungan, atau bisa juga lubang yang dalam), banyak juga yang dikubur begitu saja dalam satu lubang. Tulisan dari Katharine McGregor mengulas persoalan ini, khususnya seputar kontroversi untuk memberi penghormatan yang layak kepada mereka yang dikuburkan secara massal.
***
Buku ini dengan tepat mencatat bahwa pembantaian 1965 adalah sebuah bentuk kontra-revolusi. Lewat pembantaian tersebut, militer Indonesia berusaha mengembalikan tatanan lama yang berusaha dihancurkan pada Revolusi 1945. Sejarah Indonesia – khususnya yang dinarasikan oleh Orde Baru – tidak terlalu memberi perhatian terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat Indonesia pada periode 1945-1949. Periode ini adalah periode revolusi sosial dimana rakyat biasa berusaha menjungkirkan tatanan lama. Petani, buruh, pemuda, santri, pelajar, hingga ke preman berusaha mengorganisasikan diri untuk menjadi bagian dari revolusi sosial ini. Sebagaimana halnya revolusi, tidak terlalu mengherankan bila kekerasan terjadi dimana-mana.
Namun, revolusi sosial ini tidak pernah selesai dengan tuntas. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda, kekuatan-kekuatan lama tampil kembali. Tentara melakukan apa yang dinamakan ‘ReRa’ atau rekonstruksi dan rasionalisasi. Pada hakekatnya, ini adalah program untuk membikin sebuah tentara yang ‘profesional.’ Namun ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Profesionalisasi ini mengeluarkan banyak sekali anak-anak muda dari kelas bawah yang tidak memiliki pendidikan memadai untuk memenuhi syarat menjadi tentara. Secara kelas, pimpinan tentara pun menjadi beralih dari komandan-komandan kelas bawah ke kelas menengah terdidik. Tidak ada lagi tentara yang tipenya seperti Sudirman yang memimpin TNI pada saat revolusi. Yang muncul adalah tentara sejenis Nasution dan Simatupang yang fasih berbahasa Belanda dan dididik sebentar di akademi militer Hindia Belanda.
Indonesia kemudian dijejali dengan berbagai kekuatan politik dengan ideologinya masing-masing. Tentara, sekalipun resminya adalah organ negara, juga mulai menjadi kekuatan politik. Persis pada titik inilah, Amerika dan negara-negara Barat melihat celah untuk mengamankan kepentingan strategis mereka dalam hal ekonomi maupun pertahanan. Banyak investasi Amerika dan negara-negara Barat di Indonesia hilang atau dirampas pada saat revolusi terjadi. Satu-satunya harapan dan jalan masuk adalah lewat militer Indonesia – sebuah organisasi yang memerlukan kemodernan dan bisa menjadi kekuatan untuk mengontrol semua wilayah Indonesia.
Tidak terlalu lama kemudian tentara juga menjadi kekuatan ekonomi. Program nasionalisasi perusahan-perusahan asing yang dilakukan Soekarno menguntungkan militer. Banyak tentara mulai menguasai perkebunan, pertambangan, dan perusahan-perusahan lain yang semula dikuasai oleh asing. Dalam situasi ini, tidak terlalu mengherankan bahwa ketika berhasil mengkonsolidasikan dirinya, tentara kemudian menjadi benteng konservatisme dan kapitalisme. Hanya ada satu kekuatan yang bisa menyaingi tentara sebagai kekuatan politik dan ekonomi. Gesekan mulai terjadi ketika tentara mulai menguasai perusahan-perusahan asing. Tentara harus berhadapan dengan serikat-serikat buruh dan serikat tani yang berafiliasi ke PKI.
Harus diakui, tidak ada organisasi yang paling berhasil untuk mengorganisasikan kekuatan massa yang biasanya disingkirkan dari proses politik selain PKI. Partai ini tumbuh dengan pesat sesudah dihancurkan karena percobaan melakukan ‘revolusi ala Bolshevik’ di Madiun tahun 1948 (masih dalam periode revolusi sosial). Salah satu kekuatan partai ini adalah kemampuannya untuk memberikan suara dan akses ke kekuasaan kepada mereka yang sebelumnya tidak dipandang sebelah mata dalam proses kekuasaan. Contoh yang paling sederhana adalah nama-nama pemimpin partai ini, semisal Rewang, Nyono, Nyoto, Sudisman, dan lain-lain, yang mengindikasikan kuatnya akar kelas bawah mereka. Hampir tidak ada nama-nama pimpinan PKI yang mengindikasikan mereka datang dari kelas aristokrat atau kelas yang biasa dianggap berkuasa.
Itulah sumbangan terbesar dari buku ini. Secara garis besar, buku ini menunjukkan kepada kita bagaimana gerakan kontra-revolusioner yang dimotori oleh militer bekerja. Namun sayangnya, argumen yang paling penting ini justru yang paling diabaikan dalam buku. Tidak ada elaborasi lebih lanjut dari ‘kontra-revolusioner’ yang dilakukan lewat pembantaian besar-besaran pada tahun 1965 itu. Itu terjadi mungkin karena buku ini hanya berpusat pada pembantaian tahun 1965 dan harus mengakomodasi berbagai pikiran dan temuan dari daerah yang disampaikan oleh banyak peneliti.
Dengan demikian, studi tentang gerakan kontra-revolusioner ini tentu bisa menjadi agenda riset tersendiri. Orde Baru mengambalikan tatanan masyarakat kepada tatanan masyarakat ‘rust en orde’ yang pernah ada pada zaman kolonial. Dengan menumpahkan darah jutaan orang dan dengan menciptakan kaum Kiri sebagai kelas pariah dalam masyarakat, Orde Baru menjungkirkan semua ide dan tatanan masyarakat yang pernah dicita-citakan oleh Revolusi 1945. Di dunia internasional, Indonesia kembali ke tatanan kapitalis dunia dan membuka diri untuk eksploitasi berkelanjutan. Di dalam negeri, Indonesia pada masa Orde Baru menciptakan pasar dan membesarkan kelas konsumen – yang sebagian besar berasal dari kelas sosial menengah ke atas – yang juga mengisi lapisan-lapisan birokrasi dan militer Indonesia. Bahkan setelah Orde Baru tumbang sekali pun orientasi ini tidak menghilang, dan justru bertambah kuat.
Tugas lain dari agenda riset gerakan kontra-revolusioner ini adalah juga untuk mengidentifikasikan aktor-aktornya dan dari kelas sosial mana mereka berasal. Perbandingan dengan kelas yang menghidupi masyarakat kolonial (yang sebagian besar dibangun dari kelas pegawai itu) akan semakin memperjelas posisi aktor-aktor pendukung Orde Baru, yang didukung oleh kelas menengah terdidik, birokrat, dan aristrokrat.
Dengan melihat pembantaian massal tahun 1965 sebagai gerakan kontra-revolusioner juga akan mempermudah kita untuk mengerti bahwa gerakan ini adalah revolusi pada dirinya sendiri. Artinya, sekalipun merupakan ‘kontra-revolusi,’ pembantaian ini adalah sebuah revolusi. Dia melakukan reorganisasi kekuatan kelas sosial yang memiliki ideologinya sendiri. Semua kekuatan yang tidak berada dalam gerbong kelas dan ideologi kontra-revolusi yang diciptakan oleh militer Orde Baru harus diberangus dan diberantas habis.
Demikianlah kita lihat bahwa kekuatan-kekuatan sosial dan politik yang dipakai dan diperalat untuk membantai oleh militer kemudian satu per satu dipungkas dan dibabat habis. Itu pulalah yang dialami oleh kaum Nasionalis dan kaum Islam. Ketika Orde Baru mengkonsolidasi kekuasaannya, dengan segera dia menyasar kekuatan politik Nasionalis dan Islam. Regim Orde Baru menyingkirkan sama sekali mereka dari kekuasaan. Dalam hal ini, dilihat dari perspektif pembantaian massal, para korban dan para jagal mengalami nasib yang sama: tergilas oleh tank-tank militer. ***






