Daya Cipta S, mahasiswi tingkat akhir Ilmu Politik Universitas Indonesia
Judul : Take Back Higher Education: Race, Youth and Democracy in Post Civil Era
Penulis : Henry Giroux dan Susan Searl Giroux
Penerbit : Basingstoke, Palgrave Macmillan
Tahun : 2004
Tebal : 324 halaman
PEKAN lalu, John Cassidy, seorang kolumnis di New Yorker, menulis sebuah artikel di kolom In Depth Critics yang berjudul College Calculus. Dalam artikel tersebut, Cassidy mempertanyakan tujuan sebenarnya dari pendidikan tinggi yang diprivatisasi –khususnya di Amerika Serikat (AS). Menurutnya, biaya untuk mengenyam pendidikan tinggi belum tentu sebanding dengan penghasilan yang kelak akan didapatkan. Jawaban atas pertanyaan Cassidy di muka sebetulnya sudah termuat di pertanyaannya sendiri, saat ia mengatakan bahwa penghasilan yang kelak didapat belum tentu sebanding dengan ongkos yang dikeluarkan: bahwa pendidikan tinggi sebetulnya hanya diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan industri, untuk mendapat pekerjaan dengan penghasilan di atas rata-rata.
Fenomena privatisasi yang diulas Cassidy bukanlah hal yang baru di AS, bahkan dunia. Apa yang disebut dengan privatisasi dalam konteks ini adalah pengalihan kepemilikan universitas yang tadinya milik publik menjadi privat, dan dengan demikian dikelola secara privat pula. Privatisasi pendidikan tinggi kemudian menjadi tren global setelah tahun 1990an, khususnya ketika pendidikan tinggi itu disepakati oleh institusi perdagangan global, World Trade Organization (WTO), sebagai sebuah jasa. Sebagaimana jasa, maka perlu pengorbanan tertentu untuk mendapatkannya, sehingga tidak semua orang bisa menikmatinya.
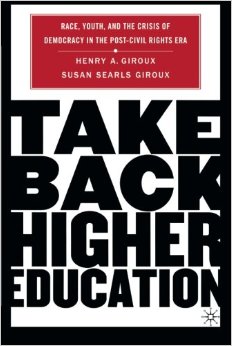
Fenomena privatisasi kampus ini kemudian mendapat tanggapan kritis, dan bahkan sanggahan, dari banyak akademisi. Salah dua di antaranya adalah Henry Giroux dan Susan Searls Giroux (Giroux&Giroux). Dalam karya Take Back Higher Education (selanjutnya disebut TBHE) yang akan diulas pada kesempatan kali ini, kedua orang itu mempromosikan critical pedagogy theory, yaitu sebuah wacana yang menolak neoliberalisme dipraktikkan dalam pengelolaan institusi pendidikan. Sebaliknya, wacana critical pedagogy theory bercita-cita untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan dan kesetaraan. TBHE juga menarasikan pendidikan tinggi di AS di era post civil rights, yang menurut keduanya sudah terstrukturisasi dengan paradigma-paradigma corporate culture.
Pendidikan Tinggi dan Pewujudan Demokrasi Partisipatoris
Dalam karya yang terbit di tahun 2004 ini, Giroux&Giroux mengenalkan istilah yang dikembangkan dari teori critical pedagogy, yaitu korporatisasi universitas. Istilah ini merujuk pada fenomena perubahan pengelolaan pendidikan tinggi dari yang tadinya bersifat publik, menjadi privat. Korporatisasi universitas ini disebabkan karena neoliberalisme, dimana dalam logika ekonomi tersebut, kultur korporasi dipenetrasikan ke berbagai institusi pubik, termasuk kampus. Dengan ini, institusi pendidikan tinggi berjalan dengan logika korporat, dimana pada saat yang bersamaan tujuan dari pendidikan tinggi juga berubah menjadi sebatas pada lembaga pencipta tenaga kerja.
Dalam logika neoliberalisme, Giroux&Giroux yakin bahwa posisi universitas tidak akan pernah ideal. Kecuali, logika tersebut diganti sama sekali, sehingga tiap aktivitas dalam universitas dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat. Untuk sampai pada idealita ini, universitas disyaratkan menjadi sebuah institusi publik terlebih dulu.
Pada intinya, bagian-bagian awal buku ini memang menjelaskan urgensi untuk mendefinisikan kembali posisi dan bentuk universitas di dalam sebuah masyarakat, dimana saat ini sudah terkooptasi dengan corporate culture yang telah dijelaskan.
Giroux&Giroux kemudian menjelaskan, bagaimana logik korporasi ikut berkontribusi terhadap cara pandang masyarakat umum dalam memandang fenomena secara tidak kritis. Ia menjelaskan hal ini dengan memberikan contoh peristiwa 9/11. Pasca penyerangan menara kembar, para akademisi (dan tentu saja, media arus utama) universitas mengeluarka opini dengan nada seragam. Menurut mereka, aksi teror itu adalah bagian dari perang antara Barat dan Timur. Pandangan yang oversimplikasi tentu, jika tidak mau dikatakan asal bicara. Opini-opini ini senada dengan tesis Samuel Huntington yang berpendapat bahwa segala bentuk teror, kekerasan dan perang, adalah semata benturan budaya antar bangsa. Memerangi dan membenci kelompok teroris ‘Timur’ tersebut, menurut Giroux&Giroux, adalah bentuk ‘patriotisme’ yang ditanamkan ke dalam benak masyarakat AS sedari dini.
‘Patriotisme’ ini kemudian membuat pandangan-pandangan yang lebih kritis mengenai peristiwa teror menjadi terpinggirkan. Pandangan-pandangan kritis dari beberapa kalangan akademisi disebut tidak ada gunanya, bahkan dalam beberapa kasus dianggap membela pelaku teror. Anggapan ini terutama berlaku bagi opini yang mengaitkan antara peristiwa teror, dengan imperialisme AS ke negara-negara dunia ketiga.
Lalu, apa kaitan pandangan tentang terorisme tersebut dengan pendidikan, terutama pendidikan tinggi? Menurut Giroux&Giroux, diskursus yang seragam adalah wujud dari demokrasi prosedural yang tidak mengakomodir pandangan-pandangan lain di luar diskursus arus utama. Lebih jauh, diskursus mengenai peristiwa teror yang seragam adalah bentuk dari government harassment dan hegemoni media arus utama.
TBHE secara vulgar mengaitkan lumpuhnya daya kritis para akademisi korporat ini dengan masuknya agenda neoliberal ke dalam institusi mereka sendiri. Para neoliberal warriors beranggapan bahwa nilai-nilai demokrasi haruslah menjadi subordinat dari pertimbangan ekonomi. Dalam kerangka ini, menciptakan universitas yang efisien dan menghasilkan profit besar adalah pilihan yang lebih menarik ketimbang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mempromosikan nilai-nilai demokrasi, serta berusaha untuk memunculkan berbagai diskursus alternatif atas sesuatu.
Bergeraknya pengelolaan dengan mekanisme korporasi tidak terlepas pula dari prioritas pemerintah AS yang notabene neoliberal, yang tidak memprioritaskan pelayanan-pelayanan publik, termasuk pendidikan. Anggaran yang besar justru dilimpahkan untuk pos-pos belanja militer, seperti invansi ke Irak, dengan dalil justru untuk mewujudkan sistem demokrasi di negara yang dianggap otoriter (tetapi kaya minyak) tersebut. Anggaran-anggaran pelayanan publik, justru dipotong dan pengelolaannya diserahkan kepada mekanisme pasar sebagaimana prinsip neoliberalisme bekerja.
Lumpuhnya demokrasi partisipatoris di AS, bagi Giroux&Giroux, harus dimunculkan dan dikembangkan kembali dengan membuka ruang-ruang publik agar segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat memicu doubt (keraguan, istilah Giroux). Doubt tersebut yang akan membuka berbagai perdebatan sehingga kebijakan yang diambil tidak bernuansa elitis. Sebab demokrasi yang partisipatoris, menurut Giroux&Giroux, haruslah dapat membuat isu-isu dan permasalahan yang menyangkut kepentingan orang banyak dapat diperdebatkan oleh orang banyak itu sendiri.
Ruang-ruang publik yang dimaksud itu salah satunya adalah universitas. Sebab pada universitas tersebut terdapat intelektual (pengajar dan mahasiswa) yang mempunyai tanggung jawab keilmuan terhadap isu-isu dan permasalahan politik yang muncul. Intelektual dapat berpartisipasi untuk ‘menjaga’ diskursus-diskursus kritis agar tercipta demokrasi yang partisipatoris, melalui sumbangan-sumbangan teoretik dan praktik. Universitas yang ideal, ujar Giroux&Giroux, seharusnya tidak resisten dengan dialog-dialog multikultural, dan tidak terbatas pada produksi teknologi atau hal-hal yang bersifat entrepreneurial saja.
TBHE membuka perdebatan bahwa pendidikan tentang demokrasi harus diinstitusionalisasikan, dikarenakan media arus utama dalam konstruksi neoliberal kini sifatnya sangat bias dan sarat dengan berbagai kepentingan segelintir elit, alih-alih untuk kepentingan publik. Rezim demokrasi, menurut Giroux&Giroux, membutuhkan masyarakat yang teredukasi, dalam artian dapat memberikan alternatif gagasan kritis sehingga dapat menciptakan dasar bagi terbangunnya nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial di masyarakat.
Korporatisasi Universitas Publik dan Peran Intelektual dalam Konstruk Neoliberal
Di bagian ketiga TBHE, Giroux&Giroux mengulas bagaimana institusi pendidikan tinggi di AS bertransformasi untuk menyesuaikan diri dengan sistem neoliberalisme. Giroux&Giroux kemudian mengabstraksikannya dengan konsep ruang dan waktu, yang dapat digunakan untuk memaknai transformasi peranan universitas dari yang tadinya publik menjadi privat.
Waktu, menurut Giroux&Giroux, adalah sebuah proses dimana universitas membentuk diskursus tentang kepentingan publik, yang di dalamnya terdapat peranan sivitas dalam memanfaatkan ruang pendidikan tinggi, akses ke ruang tersebut untuk calon sivitas, dan pengorganisiran relasi sosial dan klaim tertentu terhadap manusia (Giroux, 2004). Waktu yang dimaksud Giroux&Giroux ini tidak hanya sebagai relasi di antara ruang institusi, administrator, dosen ataupun mahasiswa saja, tapi juga bagaimana pengalokasian kekuasaan, identitas, dan ruang, melalui seperangkat norma dan kepentingan.
Giroux&Giroux berposisi bahwa waktu pada ruang universitas haruslah digunakan untuk aktivisme yang lebih partisipatoris dengan tidak hanya memenuhi digunakan untuk memenuhi kepentingan ekonomi saja, tetapi juga untuk mengarahkan dan menumbuhkan pemikiran-pemikiran kritis. Ketika waktu berubah pemaknaannya menjadi komoditas, ia akan menjadi lawan dari tumbuhnya budaya politik yang kritis dan nilai-nilai pembebasan. Transformasi waktu dalam aras neoliberalisme kemudian disebut sebagai perubahan dari public time menjadi corporate time.
Public time adalah tentang bagaimana politik dapat memainkan peranannya dalam akses, kekuasaan, dan kelompok yang posisinya tidak setara untuk mendistribusikan institusi, barang, jasa, sumber daya dan pengetahuan. Public time akan membentuk universitas sebagai ruang publik, yang mempromosikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan individu. Dengan kata lain, public time yang kemudian membangun ruang publik dalam bentuk nyata akan memberikan ruang agar ilmu pengetahuan dapat berkontribusi dalam persoalan masyarakat.
Logika neoliberalisme kemudian mengubah konsep public time menjadi corporate time. Pemaknaan universitas dalam corporate time menjadikan segala aktivitas institusi tersebut didasarkan pada pertimbangan pasar. Di AS, bentuk corporate time dapat dilihat dari produksi ilmu pengetahuan semisal riset, serta relasi yang seharusnya pedagogis menjadi berorientasikan profit. Corporate time pun dapat dimaknai sebagai aktivitas intelektual yang sifatnya lebih privat dan kompetitif.
Corporate time menciptakan ruang bernama corporate university, dimana relasi-relasi politik dalam universitas, antara pejabat administratif universitas, pengajar dan mahasiswa didasarkan pada prinsip-prinsip yang materialistik. Corporate time mengarahkan orientasi universitas tidak lagi sebagai institusi pencipta nilai-nilai demokrasi dan pembebasan, tetapi sebatas sebagai tempat untuk melatih calon-calon tenaga kerja. Corporate time mengukur hubungan produktivitas space dan pengetahuan pada efisiensi biaya, keuntungan yang didapatkan, dan rasionalitas pasar.
Institusi pendidikan tinggi yang telah bertransformasi menjadi corporate university ini berorientasi tidak lebih untuk menjual brand dari corporate university itu sendiri, semisal untuk menyewakan space, investasi di gedung-gedung tertentu, atau bahkan posisi untuk para donor, ketimbang pengadaan dan peningkatan fungsi pendidikan tinggi itu sendiri.
Tentu perubahan universitas sebagai ruang corporate university juga diiringi perubahan pada struktur tata kelola universitas itu sendiri. Pengelolaan universitas tidak lagi dipimpin oleh pengajar yang mempunyai latar belakang intelektual yang mapan, tetapi kemampuan enterpreneurial dan administrator lah yang menjadi pertimbangan utama. Universitas tidak lagi dikelola oleh dewan pengajar, tetapi oleh board of trustees dan pejabat universitas yang menjalankan fungsi birokrasi. Board of trustees inilah yang bertugas untuk mengelola universitas, serta pasti dibayar tinggi untuk itu. Dari fenomena ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengajar sebagai salah satu entitas utama universitas, atau inteletual yang berperan untuk melaksanakan fungsi dari universitas, justru dipinggirkan dalam pengambilan keputusan di universitasnya sendiri.
Intelektual Part Time
Telah dijelaskan, fenomena bertansformasinya universitas publik menjadi universitas privat tidak hanya dalam bentuk kepemilikannya saja, tetapi juga dalam hal pengelolaan. Pun dalam pengelolaan para pekerjanya, sistem kerja yang dibangun di corporate university akan selalu mengarahkannya pada agenda pasar dan kepentingan individual. Dengan bahasa yang lebih vulgar, sistem kerja fleksibel telah terinstitusionalisasi pada sebuah corporate university.
Apa turunan dari transformasi ini? Pengajar universitas misalnya, akan mengampu kelas yang lebih besar jumlah mahasiswanya dan menghasilkan profit yang lebih. Universitas korporasi akan merekrut mahasiswa sebanyak-banyaknya karena merekalah sumber pendanaan utama kampus. Apalagi, dalam corporate university, universitas harus mencari dana sendiri layaknya sebuah perusahaan tanpa (atau minimal dalam jangka panjang) bantuan biaya dari negara. Dalam konteks demikian, posisi pengajar tidak lain adalah alat dari ideologi bisnis universitas itu sendiri.
Posisi pengajar ini kemudian disesuaikan dengan keuangan universitas. Giroux&Giroux memberikan contoh melalui kasus yang paling ekstrem di universitas-universitas AS. Di sana, sering kali keberadaan pengajar ditentukan berdasarkan ‘permintaan’ calon mahasiswa program tertentu. Dengan kata lain, universitas mempunyai keleluasaan untuk hiring dan firing, tentu, tanpa dibebankan oleh tanggung jawab memenuhi hak-hak yang seharusnya diterima pengajar tersebut.
Menurut Giroux&Giroux, kondisi seperti ini membawa situasi beban kerja yang berlebih untuk para pengajar. Beban kerja yang berlebih ditimbulkan karena banyaknya kelas yang harus diampu oleh pengajar, sementara jumlah mahasiswanya terus meningkat dan jumlah pengajarnya tidak. Aktivitas intelektual pengajar di universitas kemudian diukur berdasarkan kemampuan untuk bertransaksi dan menarik ‘konsumen’.
Pengajar-pengajar dibuat bekerja paruh waktu (fleksibel), dikarenakan sistem kerja tersebutlah yang lebih efisien dari segi anggaran. Pekerjaan akademis kemudian tidak lagi menjadi pekerjaan dengan komitmen penuh waktu dan jenjang karir yang jelas. Hal ini membawa implikasi lanjutan, salah satunya adalah solidaritas di antara pengajar universitas menjadi lemah. Lebih jauh, relasi kerja yang fleksibel ini juga dapat menghasilkan interaksi di antara pengajar yang tidak lagi solid yang dan mempraktikkan hubungan yang produktif demi kepentingan publik. Para pengajar malah akan terjebak dalam budaya kompetisi pribadi yang seragam. Interaksi yang renggang ini juga membuat ruang-ruang dialog kritis menjadi kosong. Pun dalam aktivitas mengajar, pengajar tidak lagi tampil sebagai seorang intelektual, tapi seorang teknisi yang menggunakan berbagai metode atau teknologi tertentu untuk menarik sebanyak mungkin mahasiswa.
Bukan hanya kerugian yang sifatnya mental saja implikasi dari corpotare university ini, melainkan juga hal-hal yang sifatnya konkret, nyata. Misalnya, pengajar tidak dibayar dengan insentif yang memadai, padahal beban kerja mereka berlebih; kekurangan tunjangan tertentu seperti kesehatan; dan dideprivasi oleh kekuasaan yang membentuk struktur tempat pengajar bekerja. Pada titik ini kita melihat bagaimana pergeseran pengelolaan universitas yang tadinya menjadi tanggung jawab pengajar yang mempunyai latar belakang intelektual, menjadi dipegang oleh pejabat yang berlatar belakang administrasi dan bisnis.
Apabila kita melihat kasus di Indonesia, misalnya di Universitas Indonesia (UI) yang notabene pengelolaannya adalah otonom (privat), posisi kerja pengajar yang fleksibel tersebut dapat dilihat melalui fenomena dosen yang harus mengampu banyak kelas dalam seminggu (bisa mencapai empat kelas) di samping peranan lainnya yang harus dipenuhi, misalnya penelitian dan pengabdian masyarakat. Banyaknya kelas yang harus diampu dosen adalah implikasi dari meningkatnya jumlah mahasiswa setiap tahunnya, yang mana disebabkan karena universitas harus menambah fundingnya secara otonom. Beban kerja yang berlebih ini tidak diiringi dengan insentif yang memadai. Masih di UI sebagai pemisalan, dosen dengan status part time hanya dibayar paling banyak enam juta rupiah persemester. Sementara dosen tetap pendapatannya hanya empat hingga lima juta rupiah setiap bulannya. Minimnya insentif ini membuat dosen terpaksa untuk menjalani ‘peran’ lainnya di luar pekerjaannya di kampus, atau juga mengajar di kampus-kampus lainnya.
Lebih jauh, duo Giroux mengungkapkan bahwa perubahan relasi kerja universitas yang dilatar belakangi oleh pertimbangan eifisensi biaya dan memperluas kontrol manajemen universitas tidak hanya berdampak pada pengajar universitas, melainkan pada proses pendidikan itu sendiri yang semakin terdegradasi.
Berubahnya Relasi Pengajar dengan Mahasiswa
Karena universitas berubah orientasi menjadi lembaga funding, dengan serta merta mahasiswa menjadi subyek konsumen. Universitas yang menerapkan pengelolaan dengan model bisnis, mengontrak pengajar sebagai buruh, sehingga mahasiswa yang posisinya adalah membayar untuk mendapatkan jasa pendidikan tinggi diperlakukan sebagai konsumen. Di sisi lain, pengajar dengan konstruksi ‘pemberi jasa’ di corporate university diharapkan sebagai academic entrepreneur yang berorientasi agar sebanyak mungkin menghasilkan uang dan prestise, ketimbang pengajaran yang bernas dan riset yang bermanfaat untuk publik.
Universitas berperan melakukan proses ‘vokasionalisasi’, dimana term-term seperti fleksibilitas, kompetisi, atau produksi dirasionalisasi. Menurut Giroux&Giroux, semakin sedikit peluang kerja di masa depan untuk program studi tertentu, maka akan semakin sedikit pula calon mahasiswa yang akan mendaftar. Dalam hal ini, departemen dan program studi tertentu yang tidak ‘komersil’ akan kesulitan untuk mengejawantahkan studi mereka ke perolehan komersial, karena memang tidak diminati dalam lingkup pasar kerja. Bahkan, keberadaan program studi itu sendiri terancam (Beberapa waktu yang lalu bahkan beredar kabar bahwa jurusan di UI yang tidak ‘menjual’ akan ditutup, -Ed).
Persoalan penggunaan tenaga pengajar dengan status paruh waktu—tetapi dengan beban kerja penuh waktu—dilatar belakangi oleh itikad universitas untuk memotong biaya pengeluaran seefisien mungkin. Persoalan ini selain berdampak pada tenaga pengajar itu sendiri, juga berpengaruh pada kualitas pendidikan yang diterima oleh mahasiswa. Universitas kerap kali mengadakan kelas dengan kuota yang berlebih, karena kuantitas pengajar yang minim. Peran pengajar yang seharusnya adalah seorang intelektual diproletarisasi sesuai dengan demand universitas yang bergerak dengan logika perusahaan, sehingga relasi pengajar dan mahasiswa pun berubah hanya sebagai pemberi jasa dan konsumen, tidak lagi sebagai intelektual universitas yang dapat memberikan solusi dari permasalahan sosial masyarakat serta membuka jalan demokrasi yang lebih partisipatoris.
Penutup dan Hikmah Ajar
Sebelum masuk ke bagian akhir, perlu dijelaskan disini bahwa TBHE tidaklah dimaksudkan untuk mempropagandakan ideologi politik tertentu untuk merebut tatanan struktur universitas yang sudah ada, dan menggantinya dengan bentuk yang diyakini benar. TBHE dimaksudkan penulisnya sebagai ‘panggilan etis’ untuk para akademisi universitas agar dapat memberikan tanggung jawab keilmuan dan membawa misi peradaban yang bertitik berat pada kepentingan publik. Akademisi seharusnya tidak netral dari politik, akademisi justru harus dapat membawa persoalan politik ke ruang-ruang publik sehingga kebijakan yang tercipta dapat mengakomodir kepentingan masyarakat, atau dengan kata lain: berpihak pada yang termarjinalkan.
Kemudian, Pada bagian penutup ini saya akan menjabarkan poin-poin mengganjal yang dapat dijadikan kritik atas buku, serta menarik hikmah ajar yang dapat diambil untuk pendidikan tinggi yang lebih baik.
Bagi saya, TBHE tidak secara tajam dan tuntas mengulas bagaimana peranan akademisi di era neoliberalisme dewasa ini. Memang, dinarasikan secara panjang lebar bahwa dalam universitas privat peran pengajar sebagai intelektual menjadi terdegradasi, dan hanya sekadar menjadi ‘pekerja’ yang sama dengan faktor produksi lainnya di universitas. Tetapi, narasi tersebut hanya disampaikan secara umum tanpa data-data yang tajam. Pun, Giroux&Giroux terlalu banyak mengulas tentang yang ‘seharusnya’. Kritik yang dilancarkan atas demokrasi yang sedang berlangsung di AS memang sangat bernas, tetapi pada buku setebal tiga ratus halaman lebih ini sedikitpun tidak menyinggung tentang ‘mengapa’ yang ‘seharusnya’ itu menjadi alternatif yang harus dipilih. Semisal, di buku ini selalu disebutkan bahwa akademisi haruslah mempunyai tanggung jawab dan dedikasi terhadap permasalahan-permasalahan politik, tapi tidak diulas lebih lanjut mengapa akademisi mempunyai peran strategis tersebut.
TBHE bagi saya terlalu mengeneralisir akademisi; dalam artian tidak mengkategorisasikan secara lebih eksplisit mengenai ragam akademisi dan peran yang ‘seharusnya’ diharapkan. Gagasan yang terkandung dalam buku ini begitu terasa vis a vis antara akademisi universitas liberal yang resisten terhadap gagasan-gagasan kritis dan akademisi ‘yang seharusnya’, yang memberikan dan terbuka terhadap diskursus gagasan-gagasan kritis. Meskipun memang, Giroux&Giroux berhasil membangun narasi bahwa jika nilai-nilai demokrasi partisipatoris tercerabut dari ruang-ruang publik, maka hasilnya adalah kebijakan-kebijakan elitis yang mengurangi akses masyarakat miskin dan tertindas terhadap sumber daya publik.
Sebagaimana narasi critical pedagogy theory, Giroux&Giroux dalam TBHE juga menawarkan beberapa strategi politik untuk mengatasi apa yang mereka sebut dengan krisis pendidikan tinggi. Pertama, isu pendidikan tinggi harus dilihat dalam konteks politik dan ekonomi suatu negara yang lebih luas. Giroux&Giroux berpendapat konsepsi ideal mengenai pendidikan tinggi harus dikembalikan pada pemaknaan demokrasi yang ideal pula, yakni demokrasi yang partisipatoris, yang mengutamakan kepentingan-kepentingan publik. Hal ini membawa konsekuensi logis pada strategi kedua, yakni universitas harus direvitalisasi kembali sebagaimana layaknya public sphere dengan mengoptimalkan pembelajaran yang dialogis antara mahasiswa dengan pengajar. Strategi terakhir yang dapat ditarik dari TBHE adalah: perlawanan. Mahasiswa dan pengajar harus diorganisir dalam sebuah kesatuan untuk melawan korporatisasi pendidikan tinggi. Tetapi, perlawanan ini harus disertai dengan adanya job security dan terpenuhinya hak-hak normatif untuk para pengajar.
Terakhir, hikmah ajar yang dapat diambil dari buku ini adalah bahwa perjuangan untuk menciptakan pendidikan tinggi yang dapat membuka ruang-ruang publik yang kritis haruslah dilaksanakan secara terus menerus. TBHE seperti yang sempat sedikit disinggung di atas adalah panggilan etis bagi intelektual untuk mewujudkan demokrasi, kesetaraan dan keadilan sosial. Sebuah kritik yang keras untuk universitas yang kini hanya menjadi pencetak tenaga kerja dan semakin menghilangkan nilai-nilai humanis dari ruang pendidikan tinggi tersebut. Sebuah ajakan yang sangat bersemangat untuk merebut kembali universitas publik!
Daftar Pustaka
- Morrow, Raymond eds. 2006. The University, State and The Markets. California: Stanford University Press.
Saad Filho, Alfredo dan Deborah Johnston. 2005. Neoliberalism: A Critical Reader. London: Pluto Press.
Jhon Fitz dan Bryan Beers “Education Management Organisations and The Privatisation of Public Education: A Cross National Comparation of the USA and Britain” Comparative Education, Vol. 38 No. 2, 2002.
Laleh Jamshidi, dkk, “Developmental Patterns of Privatization In Higher Education: A Comparative Study”, Higher Education, Volume 68.
Lloyd Armstrong dan Douglas Becker “Higher Education and Global Marketplace”, artikel US Center For Higher Education Policy Analysis, 2004
Margaret Thornton, “The Evisceration of Equal Employment Opportunity in Higher Education”, Volume 50 No.8, 2008.
Reed Kharaim “Expanding Higher Education”, CQ Global Researcher, Volume 5 No. 22, 2011.
Sheila Slaughter, “Problems in Comparative Higher Education: Political Economy, Political Sciology and Postmodernism”, Higher Education, Volume 41 No. 4.






