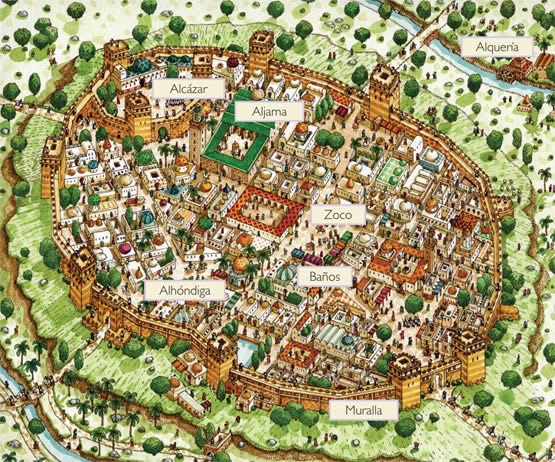KALAU ingat-ingat masa lalu, ambil saja rentang era 1980 hingga 1990-an, pesona Islam di ruang publik Indonesia tak sekuat dan tak seseram seperti sekarang ini. Di masa itu, suasana perkotaan nampak ‘sekular’ sementara di desa-desa pesona agama tampak teduh tanpa banyak kegaduhan isu-isu keagamaan.
Dimulai dari era reformasi 1998 yang menampilkan wajah Islam-politik simbolis dengan isu penegakan syariat Islam -yang sebagian telah memudar, sekarang bergeser ide tentang Khilafah Islamiyah dari kelompok Hizbuttahrir dan Daulah Islamiyah di Syiria dan Irak—yang keduanya mendapatkan resistensi arus utama Islam Indonesia. Di luar isu politik, nampak wajah Islam budaya, lebih tepatnya budaya pop dengan isu hijab/jilbab.
Realitas itu merupakan dinamika zaman, tetapi dinamika tak selalu produktif untuk dinilai dari paradigma peradaban Islam. Upaya penegakan syariat Islam sudah terbukti hanya perdagangan isu untuk kepentingan politik kekuasaan semata, bukan kepentingan esensial dari misi Islam.
Lorong Gelap Islamisme
Jika ditelisik lebih mendalam tentang Islam-politik tersebut, kita perlu menengok basis-basis gerakan pengusung ideologi Islamisme ini. Islamisme adalah paham serba Islam yang punya keyakinan Islam (dipersempit) menjadi ideologi politik, ditegakkan oleh organisasi Islam, dan impian idealnya mendirikan negara Islam.
Oleh kalangan cendekiawan dan ulama-ulama yang rasional, keyakinan seperti itu bukanlah prinsip baku dalam Islam karena Nabi Muhammad Saw., tidak mengharuskan formalitas dalam sistem politik. Apa yang paling penting bagi Rasulullah adalah mengutamakan terwujudnya Etik-Islam (Akhlakul Karimah) dengan model empirik berupa masyarakat madani, yang secara umum saripatinya bisa mendasarkan pada lima tujuan universal, yakni Hifdz al-‘aql, menjamin kreativitas berpikir dan kebebasan berekspresi serta mengeluarkan pendapat; Hifdz al-dien, menjamin kebebasan beragama; Hifdz al-nafs, memelihara kelangsungan hidup; Hifdz al-mal, menjamin pemilikan harta dan property; dan Hifdz al-nasl wal-‘irdl, menjamin kelangsungan keturunan, kehormatan, dan profesi.
Gerakan politik Islamisme tak memiliki komitmen untuk untuk itu, melainkan lebih menekankan tercapainya kemenangan Islam (baca kemenangan golongan) terhadap pihak lain yang dianggap musuh. Celakanya, musuh itu adalah setiap kelompok yang berbeda pandangan dengan kelompoknya sendiri.
Efek ideologisasi Islam dengan gerakan bermerek ‘dakwah’ dan ‘tarbiyah’ tersebut memang melahirkan generasi Islam ideologis, tetapi ideologi dalam pengertian negatif karena faktanya banyak menimbulkan egoisme individual. Itulah kenapa sering terjadi fenomena bullying dalam perdebatan tanpa mengenal etika keilmuan lagi. Sedikit berbeda pandangan secepat itu tuduhan-tuduhan muncul menyertainya. Jika berpikir rasional sedikit dianggap liberal, jika rasional sedikit dianggap kafir.
Kota-kota besar dan metropolitan menampakkan wajah ‘Islamisasi’ (tentu dalam artian simbolik), sementara di daerah-daerah –sekalipun terseok-seok dalam modernisasi– justru mengalami sekularisasi. Islam di perkotaan yang muncul di media massa, termasuk media sosial, yang seharusnya menjadi teladan lahirnya Civic dan Civil Islam, justru menampakkan wajah Islam yang tak substansial; sarat simbol-simbol Arab, sloganistis, dan pada saat-saat situasi politik tertentu menampilkan ekspresi politik yang menyeramkan.
Islam menjadi tren, tetapi tren itu justru sering diambil orang-orang narsisus untuk menengak keuntungan sebagai sarana eksistensi diri. Misalnya, banyak muncul ustad dan ustadah instan yang pemahaman agamanya kurang mumpuni, tetapi hasrat dakwahnya begitu tinggi, melontarkan statemen-stemenen yang klise dan tak jarang ngawur. Jika muncul kritik, yang terjadi bukan perdebatan keilmiahan, melainkan saling serang dengan melibatkan pendukung-pendukungnya.
Menelisik lebih mendalam, ternyata sebagian generasi muslim di perkotaan yang terislamisasi itu –lari ke agama melewati jalur gerakan politik Islamisme– berasal dari desa-desa, mayoritas lahir dari keluarga agraris/petani. Mereka bermigrasi untuk belajar atau bekerja, tetapi silau oleh gemerlapnya kehidupan kota, lalu mencari jalan lain di ‘lorong-lorong keagamaan’ untuk menghindari gemerlapnya keduniawian.
Sayangnya ruang-ruang gerakan Islam tak menyediakan cahaya yang baik. Atas nama aqidah didakwahkan untuk taat organisasi, taat imamah, menyempitkan pergaulan, membatasi literatur di luar petunjuk seniornya, bahkan urusan perkawinan pun di arahkan untuk memilih dari golongan mereka.
Mencari terobosan
Jalan pembaruan gerakan Islam mesti digemakan kembali dengan lebih nyaring. Perlu kiranya agar pola-pola pengkaderan yang dogmatis itu kembali dibuka, dengan cara pengembangan pemikiran yang lebih terbuka dan ilmiah serta kemauan untuk mendengarkan pemahaman Islam dari kelompok lain.
Di Salman ITB (Institut Teknologi Bandung), misalnya, sekarang ada upaya untuk itu. Laporan Harian Umum Pikiran Rakyat (5/1/2015) merupakan upaya ‘Islami’ yang patut ditiru kampus lain. Ada kursus sinema, ada diskusi dengan tema nasionalisme, ada upaya mengurangi kegiatan politik yang kelewat memperhatikan isu internasional tanpa peduli lingkungan sekitar.
Nilai-nilai gerakan Islam yang positif seperti di Salman ITB itu, yang mengembangkan gerakan inklusif dan transformatif tersebut, memiliki nilai-nilai gerakan kenabian karena sangat peduli lingkungan sekitar secara sektoral. Itulah gerakan profetik, itulah gerakan intelektual organik yang bisa menjadi modal terbentuknya masyarakat civic-virtue atau (dalam konteks keislaman) bisa disebut civic-Islam.
Generasi Islam kota mestinya semakin memahami secara komprehensif arus kehidupan nasional dan berpikir lebih kreatif dengan kreasi-kreasi keilmuan di masing-masing bidang yang digeluti dan kemudian berupaya membumikan semangat kenabian dalam konteks sektoral tempat kita berdomisili. Mengambil jalan dakwah politis dengan sebatas menduplikasi atau mengcopy-paste paham/ideologi sekadar untuk mengajak orang ‘berislam’ adalah bukti kekolotan berpikir.
Ada ilustrasi sejarah menarik. Di Arab dulu, ada istilah kafir (kuffar) yang secara harafiah berarti petani. Pada esensi literalnya, kuffar adalah kebiasaan petani memasukkan (menanam) benih ke tanah lalu menutupnya. Tetapi juga sering dimaknai secara simbolis sebagai keadaan (sosiologi) di mana petani-petani di pedalaman Arab (badui pedalaman) itu punya tradisi berpikir tertutup, kolot, sulit diajak terbuka dalam pergaulan, sulit menerima pengetahuan baru dan pola pikirnya selalu resisten terhadap kemajuan.
Ada pula kafr yang artinya gelapnya malam. Itulah sebabnya kata kafir itu lebih tepat untuk orang-orang yang terkunci akalbudinya, terjebak pada lorong gelap dogmatisme kepercayaan lama– dan sungguh bukanlah orang-orang yang memiliki paham berbeda dengan golongan tertentu.***
Penulis adalah Kolumnis dan Pemimpin Redaksi Penerbit Nuansa Cendekia
Artikel ini sebelumnya telah dipublikasikan di www.katakini.com. Dipublikasikan ulang di sini untuk tujuan Pendidikan.