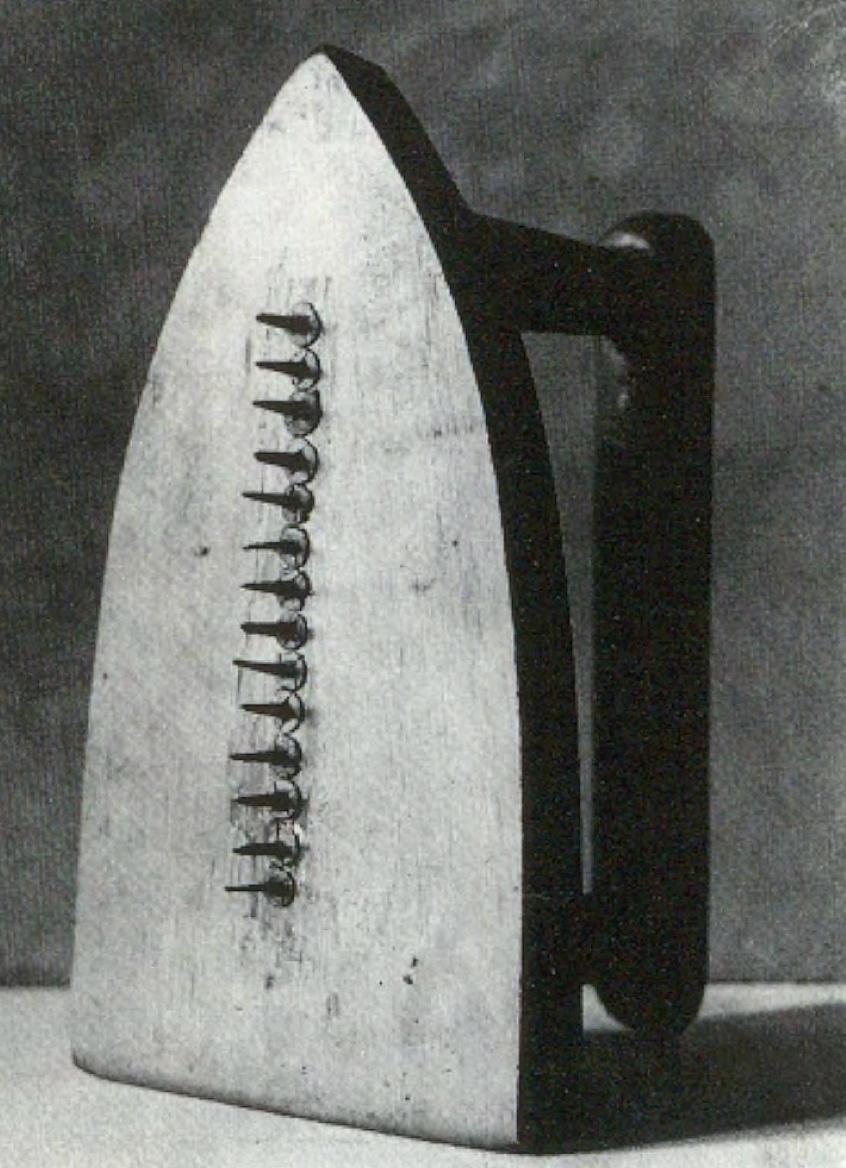Perdana Putri, kuliah sastra Rusia UI tingkat akhir, bekerja di Remotivi. Anggota SEMAR UI & Komune Rakapare.
Judul buku : Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis
Penulis : Nancy Fraser
Penerbit : Verso Books, 2013
Tebal buku : 243 halaman
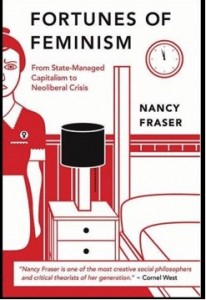
You might not see things yet on the surface, but underground, it’s already on fire.
– Y.B. Mangunwijaya
SAYA pernah terlibat dalam sebuah diskusi sengit antara perempuan patriarkis dan seorang teman yang bermetamorfosis menjadi feminis. Dalam argumen yang timpang tersebut, perempuan yang patriarkis ini berkata, “Saya rasa feminisme itu egois, karena tidak semua perempuan ingin disetarakan,” atau semacam itu. Intinya, ia berbicara seolah feminisme adalah semacam Nazi berbasis gender yang berusaha menaikkan harkat martabat perempuan semata. Ia melanjutkan argumennya dengan, “Toh, saya sudah hidup selama ini, merasa masyarakat adil kepada saya.” Sekedar memberi latar belakang, ia adalah perempuan kelas menengah atas dengan akses pendidikan dan ekonomi yang baik. Bukan Marsinah, bukan buruh yang meninggal karena tidak dapat izin padahal ia sedang sakit.
Namun yang paling penting dalam kasus menggelikan di atas, bagi saya itu juga tanggung jawab para feminis untuk mendistribusikan lagi apa itu pengetahuan akan feminisme. Sejak kapan feminisme dibaca sebagai pilihan individual semata dan hanya berfokus pada perempuan saja dan abai terhadap permasalahan lain? Sebab, sepanjang saya mempelajari feminisme bahkan dari yang liberal dan radikal sekalipun, feminisme adalah persoalan bersama karena posisi perempuan yang (dibuat secara ironis oleh patriarki) terpinggirkan di dalam struktur masyarakat kapitalis.
Situasi seperti di atas yang saya alami, hemat kata, adalah kegagalan para feminis untuk merumuskan lagi permasalahan perempuan. Ada patahan dalam linimasa sejarah feminisme, khususnya di gelombang kedua feminisme, yang menurut Nancy Fraser (dan saya amini) belum selesai dan tak ditemukan pecahannya. Namun, sebelum itu selesai, permasalahan feminisme yang pada dasarnya adalah persamaan hak sosial, ekonomi politik, kemudian langsung dikerucutkan menjadi permasalahan budaya. Dimana hal tersebut di bawa ke dalam konteks aksi di jalan dan tercitrakan kepada masyarakat lain yang sinis terhadap gerakan perempuan dan feminisme. Tentu, tak ada yang salah dengan budaya (malah sangat krusial), tapi yang sering luput adalah, jika variabel seperti ekonomi, politik dan kehidupan sosial saja diabaikan dalam kerangka pemikiran, bagaimana kita bisa loncat ke sesuatu yang sifatnya lebih besar.
Aneh, jika berbicara feminisme tapi tidak berbicara mengenai kebebasan hak politik, hak ekonomi dan hak sosial. Sebab feminisme, berlawanan dari konsepsi umum yang merugikan gerakan perempuan, bukanlah masalah pilihan semata. (Bowden & Mummery, 2009) Feminisme bukan hanya masalah “gue perempuan, gue tertindas, makanya masyarakat harus berubah.” Ia bukan persoalan identitas gender semata. Ia adalah benang-benang relasi kuasa politik, ekonomi dan sosial, lalu termaktub di dalam kebudayaan. Ibaratnya, feminisme adalah tujuan bersama, yang berlandaskan dari impian kita semua: keadilan sosial. (Bowden & Mummery, 2009: 164-165)
Untuk sekadar kita sama-sama mengingat, sejarah feminisme dimulai dari perjuangan akan hak-hak politik (hak untuk bersuara), dilanjutkan dengan hak ekonomi pasca Perang Dunia II yang mengurangi jumlah laki-laki secara signifikan (Kottak, 2011: 228-229). Saat itu, perempuan masuk ke ruang publik, tapi ia tidak mendapatkan akses ekonomi yang sama dan bahkan diskriminatif. Jadi, naif rasanya jika bicara feminisme, tapi tidak menyinggung hak politik dan ekonomi, di berbagai kontur masyarakat yang berbeda-beda. Artinya, membicarakan feminisme tidak seharusnya abai terhadap hal-hal fundamental seperti ekonomi dan politik. Namun, keadaan itu dapat kita lihat sekarang, bagaimana perlahan gerakan feminis banyak mengerucut hanya kepada perayaan perbedaan dan identitas mereka terhadap lelaki, lalu mengaburkan masalah sosial yang lebih luas seperti kemiskinan, atau ketimpangan pendapatan, yang semuanya berdasarkan diskriminasi terhadap perempuan.
Berangkat dari keadaan mendesak tersebut, Nancy Fraser membuka tabir permasalahan dengan pertanyaan, relevankah pemikiran feminisme yang ada saat ini untuk menjawab tantangan patriarki di masa depan? Apakah artinya menjadi feminis dan hubungannya di dalam gerakan sosial sekarang? Nancy Fraser, yang juga , dalam kumpulan esainya sejak tahun 1985 hingga 2010 yang dijadikan antologi Fortunes of Feminism (FOF) ini memunculkan pertanyaan di atas, berdasarkan runutan sejarah. Membaca karya Fraser ini menuntut kita, khususnya kaum feminis, untuk memikirkan ulang runut sejarah gelombang feminisme: apa yang menjadi tuntutan dan bagaimana nasib tuntutan itu, agar dari kita sendirilah yang dapat menjawab pertanyaan di atas.
Banalitas Feminisme Saat Ini
Fraser membagi gelombang kedua feminisme menjadi tiga babak berdasarkan tuntutannya, antara lain (1) the personal is political, (2) Arah redistribusi sosial-politis yang bergerak menjadi penyadaran identitas, dan (3) hubungan berbahaya (dangerous liaison) antara feminisme dan neoliberalisme (Fraser, 2013: 1-2). Fraser mengkritik bahwa akar keadaan ini terjadi ketika “the personal is political” tidak dilanjutkan dalam konteks sosio-ekonomi, melainkan hanya berlandaskan pada kultural, dan lebih spesifik ke permasalahan identitas. Akibatnya, agenda gelombang feminisme kedua yang menuntut keadilan dalam permasalahan sosio-ekonomi belum selesai, tapi didahului oleh agenda kultural, yang bermain dalam kerangka identitas.
Fraser tidak serta merta meninggalkan kultural, tapi yang ia tanyakan adalah genealogi permasalahan kultural itu sendiri. Jika feminisme abai pada permasalahan sosio-ekonomi mereka, maka penindasan akan selalu terjadi dan justru membuat terpecah-pecahnya gerakan perempuan, termasuk pemisahannya dari gerakan sosial lain—suatu hal yang diinginkan oleh patriarki. Permasalahan identitas yang penting seperti kritik Bell Hooks[1] direduksi menjadi sekadar pembenaran perbedaan perempuan dari laki-laki. Ini akan menjadi gerakan perempuan yang tidak bernas, sebab memahami perempuan berarti juga memahami laki-laki dan subjek-subjek sosial lainnya di masyarakat.
Akibat dari gerakan ini adalah banyaknya feminis yang mengeksklusikan isu perempuan dan menyalahkan patriarki semata, tanpa tahu darimana datangnya patriarki. Hal ini dapat dilihat dari minimnya pembahasan kemiskinan berbasis gender pada gerakan feminisme “kekinian”. Bahkan tak jarang banyak feminis yang tidak peduli pada isu seperti kemiskinan ataupun ekonomi perempuan dalam kerangka globalisasi. Reduksi masalah menjadi kultural (yang juga banal) semata membuat gerakan perempuan lupa apa masalah sebenarnya dan perlahan memisahkan feminisme dari gerakan-gerakan sosial lainnya yang beririsan. Belum lagi, dalam kerangka pasar neo-liberalisme, inilah yang diinginkan, ketika permasalahan perempuan hanya permasalahan afirmasi identitas, permasalahan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang harusnya menjadi agenda menjadi tidak dibawa, dan justru membantu penyerangan neoliberalisme terhadap bentuk-bentuk kesejahteraan sosial.
Fraser tidak berusaha melupakan kultural, melainkan ia mempertanyakan isu kebudayaan di dalam feminisme yang mana hanya disempitkan menjadi problem identitas semata dan bagaimana para feminis sekarang memaknai gender. Di sini, Fraser menyorot kritiknya kepada Lacanianism, atau bagaimana pemikiran Lacan diterjemahkan oleh para feminis. Para perempuan feminis yang gandrung kepada pemikiran (pseudo) pascamodernis khususnya Lacan, mengamini gender sebagai konstruksi diskursif (discursive construction) dan pemisahan gender tidak lagi dikaitkan dengan fungsi biologisnya, melainkan pada proses identifikasi, bahasa dan sosialisasi ketika anak belajar di tengah-tengah lingkungannya. Setelahnya, anak tunduk pada peraturan di masyarakat. Namun, argumen ini dianggap Fraser tidak terlalu akurat secara historis dan bahkan kultural. Sebab, pembacaan Lacanianism terhadap gender hanya berorientasi pada simbol-simbol, tapi abai pada struktur yang telah menghasilkan simbol-simbol tersebut.
Memang benar, bahwa ada suatu konstruksi yang bermain di gender, layaknya pemikiran Lacanianism. Bukankah Simone de Beauvoir dalam The Second Sex mengatakan hal serupa? Bahwa one is not born woman, but instead becoming. Maksudnya, Perempuan memang berbeda secara biologis dengan laki-laki, tapi sejarah panjang patriarki, sejak pemisahan kerja (division of labor) dalam sistem ekonomi kapitalistik, berangkat dari pemisahan biologis ini, sebagai argumen dasar dalam penindasan perempuan.[2]
Pada pembacaan atas Lacan, bagi Fraser permasalahan terletak pada karakter “diskursif” yang diberikan. Karakter “diskursif” pada persoalan gender mewajibkan seseorang memahami sejarah panjang pemisahan dan bahkan penciptaan konsep gender sendiri, l Ketidakjelian dalam membangun argumen dasar tentang kelahiran gender, membuat permasalahan yang mengikutinya semakin tidak dapat dipecahkan. Jika memang gender hanya masalah kontruksi diskursif dalam bahasa dan simbol semata, lalu bagaimana teori tersebut melihat diskriminasi pada buruh perempuan yang tidak boleh cuti hamil dan tidak mendapatkan cuti menstruasi? Idealnya adalah, memang tak seharusnya perbedaan biologis menimbulkan penindasan, tapi kondisi objektif yang terjadi adalah sebaliknya. Kebutuhan biologis perempuan justru menjadikan salah satu alasan di diskriminasikannya perempuan di dalam masyarakat.
Feminisme dalam Pasar yang Berubah
Sebab, berkutat pada masalah upah semata tanpa memikirkan lagi masalah di dalam “kerja”,[5] dan kembali mencampurkan dikotomi antara yang domestik dan publik tidak akan menyelesaikan apapun. Hanya dengan memberikan upah semata kepada perempuan, di tengah benang kusut kehadiran perempuan di ruang publik dan/atau domestik, hanya akan memunculkan masalah baru seperti “ketergantungan” dan “kebutuhan” yang diciptakan dari wacana politik ekonomi perempuan sebagai caregiver[6] dan juga breadwinner pasca penolakan terhadap family wage (Fraser, 2013: 54).
Jargon-jargon upah semata tanpa memikirkan nilai kerja itu sendiri akan membenturkan kondisi objektif perempuan kelas pekerja (non-kerah putih) seperti buruh-buruh perempuan, dengan keadaan yang lebih kompleks dan terbatas terhadap akses, tidak seperti perempuan pekerja kerah putih – seperti perempuan karir yang dielu-elukan sebagai tokoh perempuan di korporat. Sebab, sebagaimana menurut Fraser, upah yang diberikan kepada perempuan pasca babak pertama feminisme gelombang kedua membuat kapitalisme beradaptasi dengan mengurangi variabel tertentu seperti jaminan kerja (job security) di dalam proses kerja agar profit tetap terjaga.
Penurunan nilai (devaluation) terhadap konsep kerja adalah kerangka utama yang menjadi dasar kritik Fraser, terlebih lagi dia memang berfokus pada ekonomi politik. Bagi Fraser, setiap kali gerakan perempuan memberikan kontribusi langsung kepada permasalahan, seperti dengan melahirkan peraturan-peraturan yang lebih ramah kepada perempuan, sistem kerja kapitalisme langsung beradaptasi untuk melawannya. Ini akan menyulitkan gerakan perempuan yang pada dasarnya berjuang dalam persoalan “kerja”.
Artinya, jika berangkat dari alur kerja, maka sebenarnya para feminis harus berpikir lebih lanjut tentang gerakannya. Sebab, pasar terus berubah berusaha memperbaiki kontradiksi yang inheren dalam sistem kapitalisme. Para feminis harus kembali mengingat bahwa agenda pendahulunya di babak pertama dari gelombang kedua feminisme tentang pembebasan perempuan di ruang ekonomi politik belum selesai, dan berarti permasalahan kolektif juga belum selesai. Untuk hanya mengerdilkan feminisme sebagai gerakan identitas semata di luar konteks ekonomi-politik-sosialnya berarti telah meninggalkan cita-cita yang belum selesai. Hanya dengan kembali secara prinsipil ke agenda feminisme yang awal, gerakan perempuan tidak akan terkecoh lagi dalam melihat pasar yang beradaptasi dan berubah.
Meskipun menitikberatkan pada pembacaan terhadap ekonomi, bukan berarti Fraser meninggalkan pertanyaan akan identitas dan budaya. Tetapi menurut Fraser, pembacaan yang lebih menitikberatkan pada faktor identitas dan budaya serta mengabaikan ekonomi di sisi lainnya, justru akan menimbulkan hierarki yang disebarkan dalam kehidupan sehari-hari dan budaya populer. Penyebaran ini menimbulkan pemisahan juga dalam sektor ekonomi; pekerjaan berbayar (seperti kantor, pabrik) dan tidak berbayar (pekerjaan yang dianggap domestik/household activities). Di sinilah tautan yang hilang ketika feminisme gelombang ketiga (atau bagi yang menolak, gelombang kedua feminisme di fase ketiganya) membicarakan budaya. Ia hanya berbicara mengenai representasi (simbolik), tapi tidak membicarakan efek di dalam diskriminasi dengan motif ekonomi tadi.
Pada kasus yang lebih lanjut dan sering terjadi, feminisme akhirnya hanya dimaknai sebagai pilihan hidup individual untuk menghargai kebebasan semata. Padahal, kembali lagi ditekankan, feminisme tidak hanya permasalahan “saya” saja, tapi merupakan usaha untuk melakukan perubahan radikal di keseluruhan struktur sosial.
Dalam memberikan kritik terhadap perkembangan feminisme dalam kondisi pasar yang terus berubah, ada empat hal yang menjadi pemikiran Fraser untuk melihat relasi berbahaya (dangerous liaison) yang terjadi antara feminisme dan neoliberalisme: (Fraser, 2013: 219-223)
- Anti-ekonomisme, seperti yang pernah disebutkan sebelumnya, feminisme pasca babak pertama gelombang keduanya terjebak pada persoalan identitas dan perayaan perbedaan semata, dan mulai menjauhi permasalahan ekonomi, sosial dan politik yang menjadi urusan di babak pertama. Fraser berpendapat bahwa harusnya pembenturan masalah ke kebudayaan juga harus dikorelasikan dengan ekonomi, sosial dan politik dan bukan hanya masalah identitas tadi (tidak one-side culturalism). Hanya dengan mempersoalkan identitas berarti sudah mengamini cetak biru neoliberalisme yang berusaha menghapus permasalahan egalitarian sosial yang harusnya juga menjadi agenda feminisme.
- Anti-androsentrisme, ini berhubungan dengan romantisasi brand wajah-wajah perempuan di ruang publik yang memiliki posisi penting (seperti perempuan pekerja kerah putih). Padahal, neoliberalisme membantu penindasan perempuan dengan berusaha menyembunyikan permasalahan asli di ruang kerja perempuan. Gaji dan posisi tinggi tak serta merta mengindikasikan kesejahteraan gender secara utuh. Seperti tanya Fraser: bagaimana dengan jaminan kerja, ruang-ruangnya serta standar kehidupan layak yang masih berlandaskan pada imaji maskulin, seperti dalam sektor IT (Fraser memberi contoh dengan grup Lembah Silikon di Amerika Serikat) – terlepas dari kampanye keluarga dengan dua tulang punggung? (two-earner family).
- Anti-etatisme, neoliberalisme berusaha mengalihkan agenda fundamental feminisme dengan semakin meminggirkan kehadiran negara dalam pelayanan di ruang publik. Akibatnya, semakin banyak mekanisme di tingkat lokal dan membantu di tingkat ekonomi mikro, namun juga abai terhadap konteks makro dalam melawan kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial. Fraser memberi contoh dengan adanya kebijakan kredit mikro. Neoliberalisme berusaha menghadirkan wajah masyarakat yang terpecah di tataran paling kecil, untuk menghilangkan imaji kehadiran otoritas yang harusnya hadir untuk membantu permasalahan gender (pelayanan day care misalnya, atau di Perancis memberi potongan harga untuk binatu bagi ibu-ibu yang baru selesai melahirkan).
- Pro-kontra Westphalian, bagian ini berusaha menjelaskan tantangan feminis di era globalisasi. Ekspansi pasar menuntut feminisme untuk semakin terintegrasi dengan berbagai isu lainnya (lingkungan, HAM dan lain-lain). Walau di beberapa sisi ini menguntungkan dan memberi akses baru bagi feminis untuk melihatkan masalahnya, tapi ini tidak serta merta menyentuh permasalahan fundamental pada gender. Contoh yang diberikan Fraser sangat menarik dan dapat dilihat bahkan di tingkat mahasiswa sekarang, yakni konferensi transnasional. Kampanye tentang gender di wajah konferensi semisal PBB berkisar antara identitas perempuan, kekerasan terhadap perempuan, heteronormativitas dan reproduksi, untuk menampilkan wajah masalah yang urgen di dalam suatu entitas baru bernama “masyarakat sipil global”, tapi luput dari masalah, misalnya kemiskinan dan permasalahan sosio-ekonomi perempuan. Ini banyak terjadi pada para feminis. Gerakan transnasional yang awalnya dipakai untuk menyuarakan permasalahan berbagai masyarakat, rupanya tidak membawa semangat akar rumput.[7] Jadi, permasalahan identitas ditransformasikan menjadi diskursus global dan membuat kita lupa bahwa landasan feminisme sesungguhnya terletak pada sosial, ekonomi dan politik, dan setelah ketiganya dapat dicapai, barulah kanal kebudayaan dapat dicapai dan diolah secara sempurna.
Salah satu contoh yang dikemukakan Freser adalah mengenai jaminan sosial (social protection). Di sini, Fraser melanjutkan tesis Karl Polanyi mengenai pergerakan ganda (double movement) di dalam karnya The Great Transformation. Menurut Polanyi, jika pasar bebas berusaha memisahkan dirinya dari struktur masyarakat, maka jaminan sosial menjadi suatu yang niscaya untuk menimbulkan efek proteksi terhadap pasarnya, atau justu semakin membebaskan pasar itu sendiri. Permasalahan yang ditangkap oleh Fraser adalah bahwa tak selamanya jaminan sosial bermakna keadilan sosial yang sesungguhnya, dan di dalamnya bisa saja mengandung dominasi serta menempatkan masyarakat (khususnya perempuan) sebagai entitas yang lebih lemah daripada pasar (Fraser, 2013: 232-233).
Penutup
Sebenarnya, buku Fraser ini lebih memberikan pertanyaan daripada jawaban. Permodelan yang ia tawarkan pun sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan feminis sosialis lainnya, yakni dengan model caregiver di mana laki-laki pun turut serta dalam mengurus rumah tangga (anak, rumah dan seterusnya). Jadi, permasalahan tidak lagi masalah upah dengan keduanya menjadi breadwinner, tapi keduanya pun hadir sebagai caregiver. Dengan permodelan ini, maka secara langsung konsep kerja pun akan berubah – terjadi restrukturisasi akan konsep waktu dan kebutuhan baik perempuan dan laki-laki (Fraser, 2013: 128-130).
Usulan ini juga sejalan dengan keadilan gender yang diusung Fraser. Bagi Fraser, keadilan gender adalah suatu konsep yang rumit, dan sebaiknya, karena disesuaikan dengan agenda yang belum selesai tadi dalam feminisme, maka ini bukan hanya masalah perempuan. Keadilan perempuan berarti melibatkan keadilan bagi subjek-subjek yang lain (Fraser, 2013: 116-117). Artinya, keadilan gender tidak dapat dilihat dari satu norma ataupun nilai tertentu saja. Mengenai hal ini, Fraser memberikan tujuh prinsip yang bersifat normatif keadilan gender di negara pascaindustrial, antara lain:
- Anti-kemiskinan, khususnya dalam melihat berkembangnya ibu tunggal di dalam keluarga yang sering mendapat stigma dan kesulitan dalam menjaga keluarga.
- Anti-eksploitasi, agenda ini berbarengan dengan anti-kemiskinan. Sebab, terkait dengan sisi buruk dari proteksi sosial yang hierarkis, akan ada kelas-kelas yang dieksploitasi hanya karena kemiskinannya
- Kesetaraan pendapatan, salah satu yang penting dalam prinsip gerakan perempuan adalah distribusi pendapatan per kapita. Walau nampaknya sekarang perempuan punya akses, namun pada kenyataannya, . Ketidaksetaraan pendapatan dan minimnya kompensasi perempuan, sejatinya terdapat kemiskinan terselubung (hidden poverty) dalam masyarakat. Walaupun di awal Fraser menyatakan diskriminasi gender tidak semata bisa diselesaikan dengan upah, tapi kesetaraan upah adalah salah satu agenda dalam rumusan solusi yang ia berikan. Yang ia tolak adalah bagaimana kesetaraan upah menjadi satu-satunya solusi di dalam penumpasan patriarki dan mewujudkan keadilan sosial.
- Kesetaraan waktu luang (leisure time), perempuan bekerja di sektor berbayar (paid work) dan yang tidak (unpaid work) seperti merawat anak, merawat suami dan lain-lain. Namun, ia tidak memiliki waktu senggang yang sama untuk pria, dalam artian ia bekerja lebih produktif karena ada di dua sektor tersebut.
- Kesetaraan dalam penghormatan, hal ini merupakan tuntutan paling besar yang selama ini feminis pada umumnya tuntut, sebab perempuan masih dijadikan sebatas objek seksual di masyarakat dan tidak dilihat sebagai manusia dengan kehendak (will) masing-masing. Penghormatan ini juga bergerakan dalam mengubah paradigma dengan menghormati kontribusi perempuan, karena selama ini tugas perempuan di ranah publik maupun domestik, dianggap natural, walaupun nanti memunculkan paradoks tersendiri.
- Anti-marjinalisasi, maksudnya perempuan tidak boleh menjadi marjinal di berbagai sektor (politik, ekonomi, dan sipil). Artinya, permodelan negara kesejahteraan (welfare-state) yang didukung oleh Fraser dituntut agar membantu mobilitas perempuan, seperti penyediaan day-care, dan yang lain-lain.
- Anti-androsentrisme, berarti tidak memposisikan perempuan harus mengikuti standar yang ditentukan laki-laki, atau mengukur ketangguhannya dari standar laki-laki hanya untuk diterima secara adil di dalam masyarakat, juga menolak nilai-nilai maskulin yang dijadikan untuk menandai tipe-tipe perempuan.
Bagi saya, buku Nancy Fraser ini terbilang sulit dibaca karena ia merupakan rangkaian teks selama hampir dua puluh tahun. Untuk membaca teks Fraser berikut, diperlukan pengetahuan lebih mendalam tak hanya mengenai feminisme, tapi seluruh rangkaian teori kritis lainnya. Banyak juga repetisi ide dan penyampaian yang bagi saya berputar-putar dalam mengkritik keadaan feminisme saat ini, sehingga akan menyulitkan pembaca. Salah satu kritik yang juga diberikan kepada teks Fraser adalah ia dianggap terlalu ekonomi deterministik. Namun, sejak awal Fraser memiliki stand-point yang jelas dalam memberikan argumennya terhadap gerakan perempuan (khususnya feminisme), yakni feminisme harus kembali ke akarnya dan menyentuh agenda yang belum selesai dari pendahulunya di gelombang kedua feminisme babak pertama, yaitu hak-hak politik, sosial dan ekonomi. Fraser memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk perumusan gerakan feminis dan gender saat ini. Fraser seolah bersejalan dengan Maria Mies yang mengatakan bahwa semakin berkembangnya gerakan feminis, maka semakin berkembang pula manifesto-manifesto dari patriarki (Mies, 1999: ix). Untuk itu, menurut Fraser para perempuan yang bergerak di isu kesetaraan gender dan feminisme, harus “think big” dan kalau boleh saya tambahkan “think ontologically”.
Pada akhirnya, gerakan perempuan dan feminis harus jeli dalam melihat konteks, tanpa meninggalkan perangkat dasar keadilan sosial sebagai akar dan tujuan feminisme. Fraser menegaskan kebingungan feminis yang tidak kembali pada hakikat keadilan sosial di seluruh sektor masyarakat dengan pertanyaan, “Just about everyone claims to be feminist now, but what does that mean? And what does that have to do with the social movement that I was part of?” (Di saat semuanya mengaku menjadi feminis, tapi apa artinya (menjadi feminis) itu? Apa hubungannya menjadi feminis dengan gerakan sosial lainnya yang saya perjuangkan?”
Referensi Tambahan
Hooks, Bell. 1984. Feminist Theory: From Margin to Center. Boston: South End Press.
Foucault, Michel. 1996. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences.
Haslanger, Sally. 2012. Resisting Reality: Social Construction and Social Critique.
Mies, Maria. 1998. Patriarchy & Accumulation on a World Scale :
Women in the Internasional Division of Labour (New Edition). Zed Book Ltd.
Millets, Kate. 1970. Sexual Politics.
Okin, Susan Moller. 1989. Justice, Gender and the Family. Basic Books, Inc.: New York.
Weeks, Kathi. 2011. The Problem with Work :Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries. Duke University Press.
—
[1] Bell Hooks, seorang feminis afro-Amerika mengkritik gerakan feminisme kulit putih yang melihat keluarga adalah sentral dari masalah gender, keluarga sebagai sosok opresif. Padahal, di beberapa masyarakat (khususnya non-Eropa/Amerika), keluarga berfungsi sebagai pelindung perempuan. Hooks juga mengkritik Betty Friedan karena terlalu fokus terhadap domestifikasi perempuan kulit putih dan abai melihat isu rasial di dalamnya. Lihat Feminist Theory: From Margin to Center (1984)
[2] Lihat Kate Millets, Sexual Politics (1970) dan Sally Haslanger, Resisting Reality: Social Construction and Social Critique (2012).
[3] Lihat karya Foucault The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences (1966)
[4] Lihat Okin, Susan Moller (1989). Justice, Gender and the Family. Basic Books: New York.
[5] Lihat Kathi Weeks, The Problem With Work (2011).
[6] Dengan ekspektasi yang sama dengan nilai-nilai tradisional, bahwa perempuan tetap harus memiliki anak dan bersuami, lalu merawat mereka. Asumsinya, kehidupan domestik tetaplah azas kehidupan perempuannya.
[7] Pada kasus konkretnya, saya pernah bertemu dengan “feminis” yang semangat menyuarakan LGBT (tidak ada yang salah soal pilihan topik ini) di forum-forum internasional yang ia ikuti, tapi mengaku tidak tertarik untuk membawa isu kemiskinan berbasis gender.