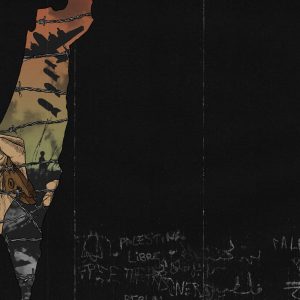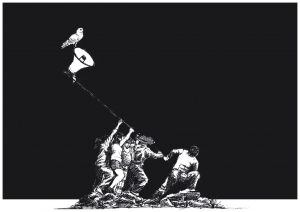Ilustrasi: Bruno Ferreira/eltecolote.org
PETANG perlahan menggulung kehidupan di Universitas Hasanuddin (Unhas). Pada waktu yang syahdu itu saya membuka percakapan dengan seorang kawan. Kami merefleksikan pengalaman menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan (ormawa) selama kurang lebih delapan bulan. Tujuannya tentu bukan untuk menenggelamkan diri dalam nostalgia atau euforia, tapi demi memetakan langkah selanjutnya yang harus diambil. Pendek cerita, berdasarkan pertimbangan yang hati-hati, saya menjatuhkan vonis: gerakan di kampus (saya) sudah mampus.
Sebelum membedah rasionalisasi yang melandasi kesimpulan tersebut, saya mau menjelaskan sedikit latar belakang. Saya merupakan demisioner presidium senat mahasiswa tingkat fakultas. Tahun ini saya akan menyelesaikan masa studi setelah menempuh perkuliahan selama tiga setengah tahun. Bagi sebagian orang, pengurus organisasi yang kuliahnya sesingkat itu adalah anomali. Karena anomali, vonis saya mungkin akan dituding tidak valid sebab kontribusi untuk gerakan mahasiswa tidak semaksimal (mereka yang mengaku) aktivis yang menghabiskan waktu lebih lama di kampus. Alasan saya mengakhiri kuliah dengan cepat adalah karena kampus hari ini, khususnya Unhas, sudah sangat minim menyediakan ruang gerak bagi aktivisme mahasiswa. Aktivisme dalam arti konvensional bukan lagi alasan untuk berlama-lama di kampus, sebab kampus sendiri sudah bertransformasi menjadi ladang subur orang-orang pasif dan apolitis.
Tidak hanya itu, keputusan tak berlama-lama di kampus saya landaskan pada keyakinan bahwa menanggalkan status mahasiswa tidak sama dengan meninggalkan perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial.
Kepercayaan bahwa hanya mahasiswalah yang bisa mendesak perubahan sebaiknya dibuang jauh-jauh. Sudah banyak literatur yang secara gamblang mengutuk narasi eksklusivitas gerakan mahasiswa. Dalam sejarah, itu adalah mitos yang diproduksi oleh Orde Baru dengan tujuan memecah belah gerakan politik rakyat.
Sebelum Orde Baru, sejak merdeka sampai 1965, politik menjalar ke seluruh sendi kehidupan sampai-sampai tidak ada ruang untuk tidak berpolitik. Pembantaian pasca-peristiwa 1965 mengubah itu semua. Semua kekuatan politik diberangus dan hal tersebut terus dipelihara. Seluruh elemen rakyat, dari mulai buruh, tani, miskin kota, aparatur sipil negara, sampai agamawan difragmentasi agar terisolasi di “sektor”-nya masing-masing. Sekat dibangun dan kesadaran palsu ditanamkan. Watak politis rakyat pun akhirnya jadi kabur. Semua ini dilakukan sebab Orde Baru melihat rakyat yang “melek” politik sebagai ancaman. Mereka tidak menghendaki terwujudnya kesadaran dan konsolidasi politik besar-besaran sebab berpotensi menghadirkan front politik tandingan.
Salah satu kesadaran palsu yang berhasil ditanamkan oleh rezim Orde Baru adalah heroisme mahasiswa dengan dasar bahwa mereka “menurunkan” rezim Sukarno. Ini dalam rangka mengisolir elemen mahasiswa dari totalitas sosial-politik rakyat pada saat itu. Doktrin ini menanamkan kepercayaan bahwa mahasiswa adalah unsur yang terpisah dari rakyat, yang diberi tugas khusus untuk mencerdaskan dan membela rakyat dari segala macam ketidakadilan. Layaknya para resi di epos Mahabharata, mitos ini menggambarkan mahasiswa sebagai intelektual yang tinggal di menara universitas; tidak terjangkau oleh rakyat biasa. Mereka hanya akan “turun gunung” apabila keadaan rakyat benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Di satu sisi, mitos ini membungkus “rakyat” layaknya anak kecil yang tidak bisa apa-apa, yang harus berpangku tangan menunggu ubermensch-nya Nietzsche menyelamatkan mereka dari kezaliman penguasa. Mitos ini semakin paripurna dengan dilekatkannya simbol-simbol eksklusif kepada mahasiswa, misalnya agen kontrol sosial, agen perubahan, moral forces, iron stock, dan seterusnya. Alhasil, jurang pembatas antara mahasiswa dan rakyat kian melebar.
Dampaknya, gerakan yang dibangun oleh mahasiswa sering kali tidak menyentuh persoalan yang hadir di grass root. Pun apabila mahasiswa ikut bersuara terkait persoalan “rakyat”, tuntutan tersebut kerap kali berakhir sebagai aksi simbolik semata seperti bakar ban, teater, orasi, menabur bunga, dan bagi-bagi pamflet. Akibatnya, gerakan mahasiswa menjelma sebagai ruang masturbasi intelektual yang becek oleh retorika dan simbol.
Mitologi “mahasiswa super” ini diturunkan dari generasi ke generasi, angkatan ke angkatan, kemudian menjadi dosa turunan yang sukses menjangkiti banyak universitas, termasuk Unhas. Entah bagaimana di kampus lain, tapi Unhas fenomena ini indikatornya dapat dilihat di dua aspek yang saling berkesinambungan, yakni degradasi peran lembaga kemahasiswaan, lalu kemudian diikuti oleh depolitisasi gerakan mahasiswa.
Saya akan membahas terlebih dulu degradasi peran lembaga kemahasiswaan. Tereksklusi dari basis massa rakyat membuat mahasiswa lebih sibuk dengan kehidupan lembaga intrakampus masing-masing. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), senat, himpunan, dan apa pun namanya itu larut dalam dinamika internalnya sendiri. Politik direduksi menjadi “politik kampus”, yang kemudian dipersempit lagi menjadi “politik kemahasiswaan”: dinamika eksklusif yang mencerminkan tarik menarik kepentingan antarmahasiswa semata. Para stakeholder organisasi intrakampus sibuk memenangkan calon presiden/calon ketua umum sokongan kubu masing-masing meskipun program kerja yang ditawarkan itu-itu saja: pengaderan, seminar self-development, bedah buku, family gathering, dan seterusnya. Tidak lagi terpikir apalagi menjalankan kegiatan turun ke bawah (turba/live in), tidak ada lagi pelaksanaan riset strategis, pendidikan politik kritis, apalagi pengorganisiran bersama rakyat. Ironisnya, meski interaksi dengan rakyat yang sangat minim, para “resi” inilah yang nantinya akan menutup jalan, membakar ban, dan bergiliran orasi atas nama rakyat.
Kondisi di atas diperparah oleh mewabahnya berbagai organisasi eksternal yang turut mengokupasi ruang gerak di kampus, dari mulai organisasi nonpemerintahan (ornop), organisasi kemasyarakatan (ormas), dan organisasai kedaerahan (organda). Organisasi ekstrakampus menggeser peran dan fungsi lembaga kemahasiswaan dengan corak politik elitis yang dibawa mereka. Di Makassar umumnya, dan Unhas khususnya, organda dan ormas umumnya dilandasi oleh politik identitas yang sering kali memikul doktrin etnosentris. Selain itu, organda dan ormas juga menjadi pintu masuk bagi politik praktis ke kampus. Di hadapan organda dan ormas, lembaga kemahasiswaan tak ubahnya tambang bagi elite politik untuk mendulang suara dan menggaet popularitas guna memenangkan politik elektoral yang zalimnya naudzubillah.
Sebagian mahasiswa yang menyadari penyelewengan fungsi lembaga kemahasiswaan oleh organda dan ormas memilih menjadi apolitis. Sementara sebagian yang lain, yang lebih oportunis, memanfaatkan “kendaraan” ini untuk ikut terjun ke lahan basah politik elite.
Ornop juga tidak bebas dari dosa. Ornop umumnya hadir di universitas untuk membersihkan tangan kotor korporasi dari dosa lingkungan dan sosial yang telah dilakukan atas nama profit. Cara yang paling umum ditempuh oleh ornop adalah menjadi penyokong dan donatur bagi kegiatan kemahasiswaan, serta menyediakan beasiswa dan pelatihan. Apabila dicermati, selain untuk menciptakan generasi tenaga kerja terampil, langkah ini dapat dimaknai sebagai strategi bagi korporasi untuk menciptakan ketergantungan dan meninabobokan gerakan mahasiswa agar akumulasi tetap terjaga.
Di sisi lain, mereka yang masih aktif mengorganisir (baca: aktivis) kerap kali kebingungan sendiri melanjutkan gerakan mereka. Ketika ban habis terbakar, semua koordinator kebagian berorasi, dan iring-iringan aparat datang membubarkan aksi, suara kritis serentak padam melempem. Tapi tak berapa lama kemudian siklus itu dimulai lagi dari awal. Semua inilah yang saya sebut sebagai depolitisasi gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa kehilangan trajektori politiknya. Hal ini jugalah yang membuat saya menjatuhkan tuduhan: perjuangan akan ditinggalkan tepat setelah status mahasiswa ditanggalkan.
Hal-hal di atas seharusnya menjadi renungan bagi mereka yang ada di lembaga kemahasiswaan hari ini. Gerakan mahasiswa hari ini telah menderita krisis politik akut dengan gejala berupa eksklusivitas, ketergantungan, elitis, reaksioner, dan oportunis. Ini pada akhirnya membuat gerakan kampus mampus.
Kemarin bergeliat di politik elektoral untuk memenangkan elite tertentu, hari ini berdiri menolak penggusuran, besok mengupayakan uang kuliah (UKT) murah, lusa berteriak menolak kenaikan harga minyak. Berapa banyak medan perjuangan, berapa banyak waktu dan tenaga, dan berapa banyak martir yang harus kena skors dan bahkan drop out agar gerakan mahasiswa memperoleh kemenangan sejati? Atau pertanyaannya saya ubah menjadi lebih mendasar: apa itu menang? Apakah keberhasilan elite di kontestasi politik elektoral merupakan kemenangan mahasiswa? Apakah membatalkan penggusuran merupakan kemenangan mahasiswa? Apakah UKT murah merupakan kemenangan mahasiswa? Kalau memang iya, berapa banyak penggusuran yang harus kita gagalkan? Berapa banyak elite politik yang harus kita menangkan? Sampai di angka berapa UKT agar gerakan kita ini menjadi paripurna? Singkatnya, perjuangan mana yang akan memenangkan mahasiswa di panggung sejarah? Atau, bahkan, adakah kemenangan mahasiswa itu?
Jadi, meminjam perkataan kata Lenin, “what is to be done?” Bagi saya, gerakan mahasiswa harus kembali pada poros perjuangan politik yang seharusnya, dan untuk itu marxisme dapat menjadi alat bantu. Pendekatan ekonomi-politik marxis membagi masyarakat ke dalam dua kelas yang saling bertentangan: (1) kelompok yang memiliki kuasa atas sarana produksi tapi tidak mencurahkan tenaganya untuk menggarap sarana tersebut sehingga memerlukan curahan kerja dari kelompok lain; (2) mereka yang tidak memiliki sarana produksi sehingga harus menjual tenaganya kepada kelompok yang pertama dan memperoleh balas jasa berupa upah yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kelas yang pertama diberi nama pemodal/kapitalis dan yang mengikuti disebut pekerja/proletar.
Mengadopsi kerangka berpikir marxis ke dalam gerakan mahasiswa berarti pertama-tama melacak posisi mahasiswa dalam pertentangan tersebut. Mahasiswa jelas bukan pemilik sarana produksi, tapi dia juga belum bekerja untuk orang lain. Namun, melihat situasi perguruan tinggi hari ini yang telah bertransformasi sekadar menjadi pemasok tenaga kerja bagi industri, maka posisi mahasiswa dalam antagonisme kelas adalah calon pekerja/proletar. Oleh karena itu, alih-alih terus mengidentifikasi diri sebagai iron stock, mahasiswa seharusnya mulai melihat diri mereka sebagai sekumpulan labour stock, atau yang Marx sebut sebagai “reserve army of labour”.
Konsekuensi dan pandangan tersebut adalah, mahasiswa tidak perlu lagi merasa terlalu sibuk, atau mungkin terlalu suci, untuk terjun membangun aliansi dengan buruh/pekerja di sektor apa pun: buruh pabrik, buruh tani, buruh pemerintahan (ASN), buruh akademik, dan buruh-buruh lainnya—sebab mahasiswa pada akhirnya akan menjadi buruh. Mahasiswa harus siap meninggalkan menara kampusnya dan turun berjuang dan berserikat bersama pekerja. Seluruh agenda lembaga kemahasiswaan, mulai dari ideologisasi, riset, hingga advokasi, sudah seharusnya mulai diorientasikan untuk kepentingan kelas pekerja. Selain itu,, mahasiswa sudah seharusnya mulai mawas diri dan memilah segala atribut kelembagaan yang mengaburkan identitas sejatinya sebagai calon pekerja. Baik itu ormas, ornop, dan organda yang tidak melandaskan diri pada analisis kelas marxis atau setidaknya tidak pro terhadap kaum buruh harus segera dieliminasi dari daftar aliansi.
Dengan terangnya posisi mahasiswa dalam rakyat hari ini, terjawablah pertanyaan sebelumnya: kemenangan sejati mahasiswa adalah kemenangan kelas pekerja. Menang tidak boleh lagi dimaknai secara parsial dan terisolir. Tidak ada kemenangan bagi mahasiswa secara khusus; tidak ada kemenangan bagi tani secara khusus; tidak ada kemenangan bagi kerah biru secara khusus. Saya kutip pernyataan Yosie Polimpung: “menang itu hanya satu, dan cuma satu: kapitalisme runtuh.” Itulah kemenangan total dan universal, kemenangan yang akan melepaskan belenggu kerja upahan dan memenangkan massa rakyat pekerja di panggung sejarah.
Seiring dengan terjelaskannya trajektori politik gerakan mahasiswa ini, yakni politik kelas pekerja, tidak ada lagi keraguan untuk apa yang harus dilakukan setelah status mahasiswa ditanggalkan. Pada akhirnya, dalam rangka mengalahkan totalitas ekonomi-politik dengan corak eksploitatif ini, roda perjuangan harus terus bergulir, baik itu sebagai mahasiswa atau sebagai pekerja.
Gerakan mahasiswa belum akan mampus. Tidak akan mampus, selama ia mampu mematahkan mitos, keluar dari keterasingan dan keterisolasian, kemudian bergabung ke medan perjuangan yang lebih nyata: perjuangan politik massa rakyat pekerja. Kalau tidak? “Mampus kau (gerakan mahasiswa) dikoyak-koyak sepi.”
A. Fadhil Aprilyandi Sultan adalah mahasiswa Unhas