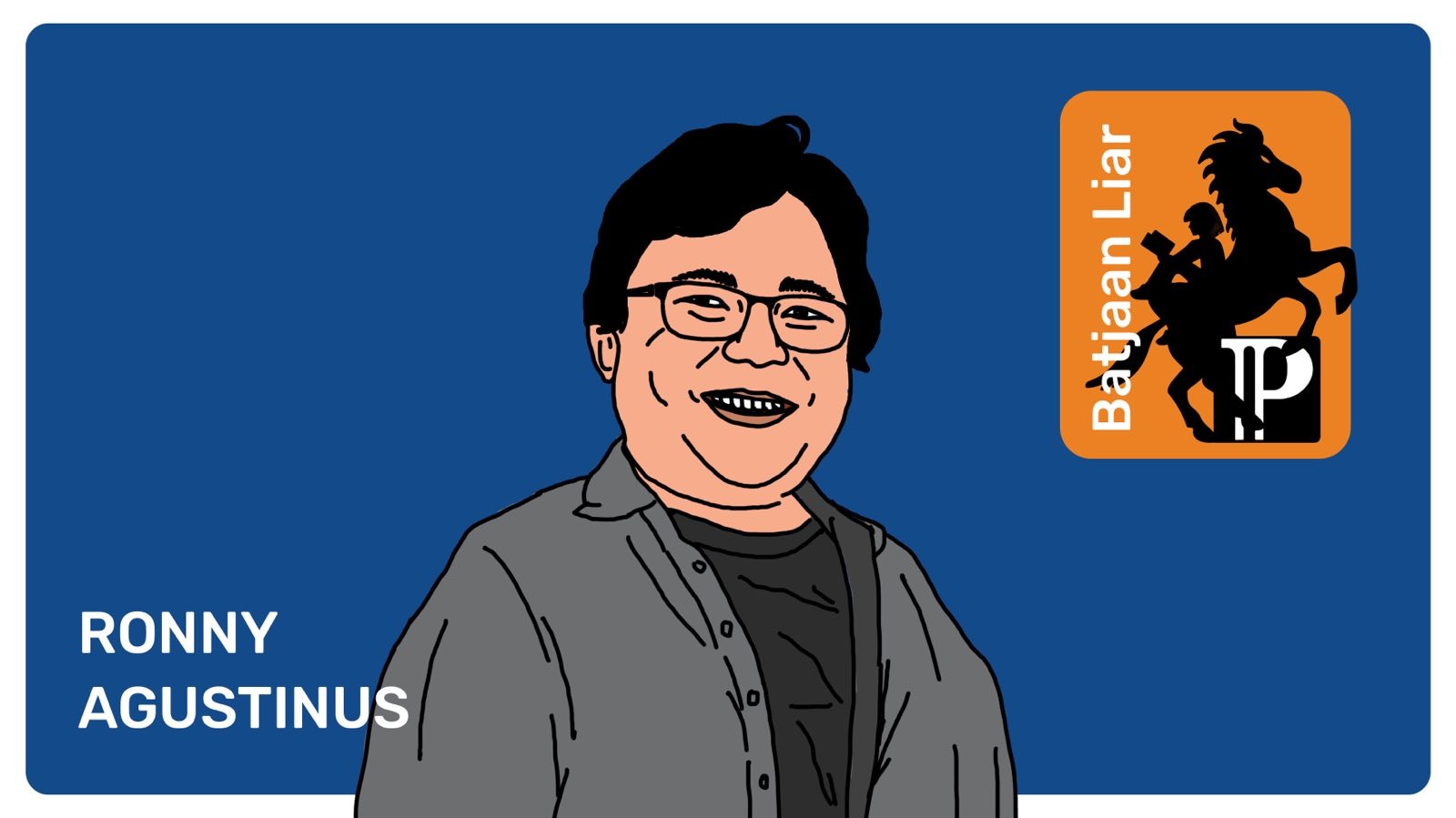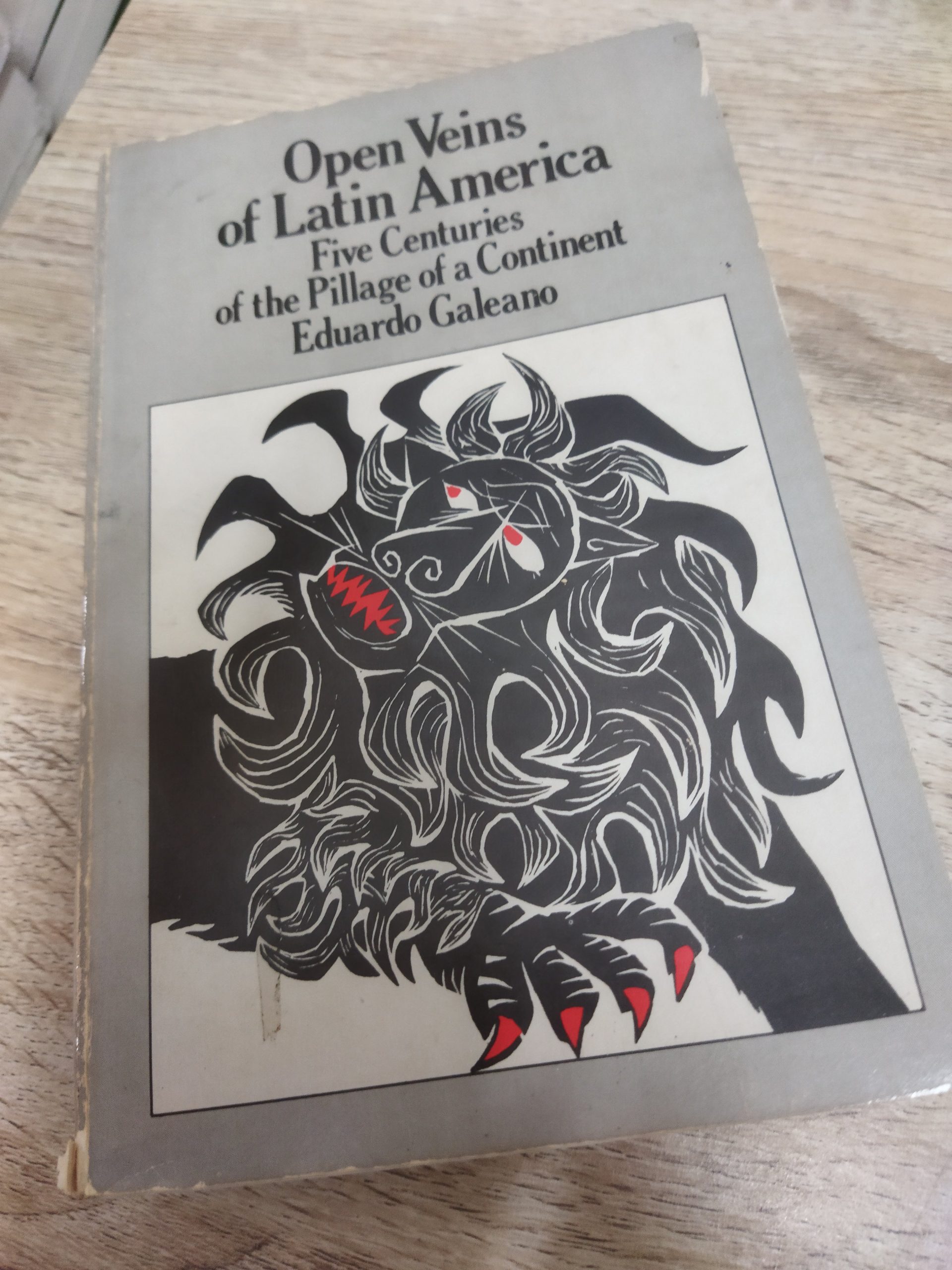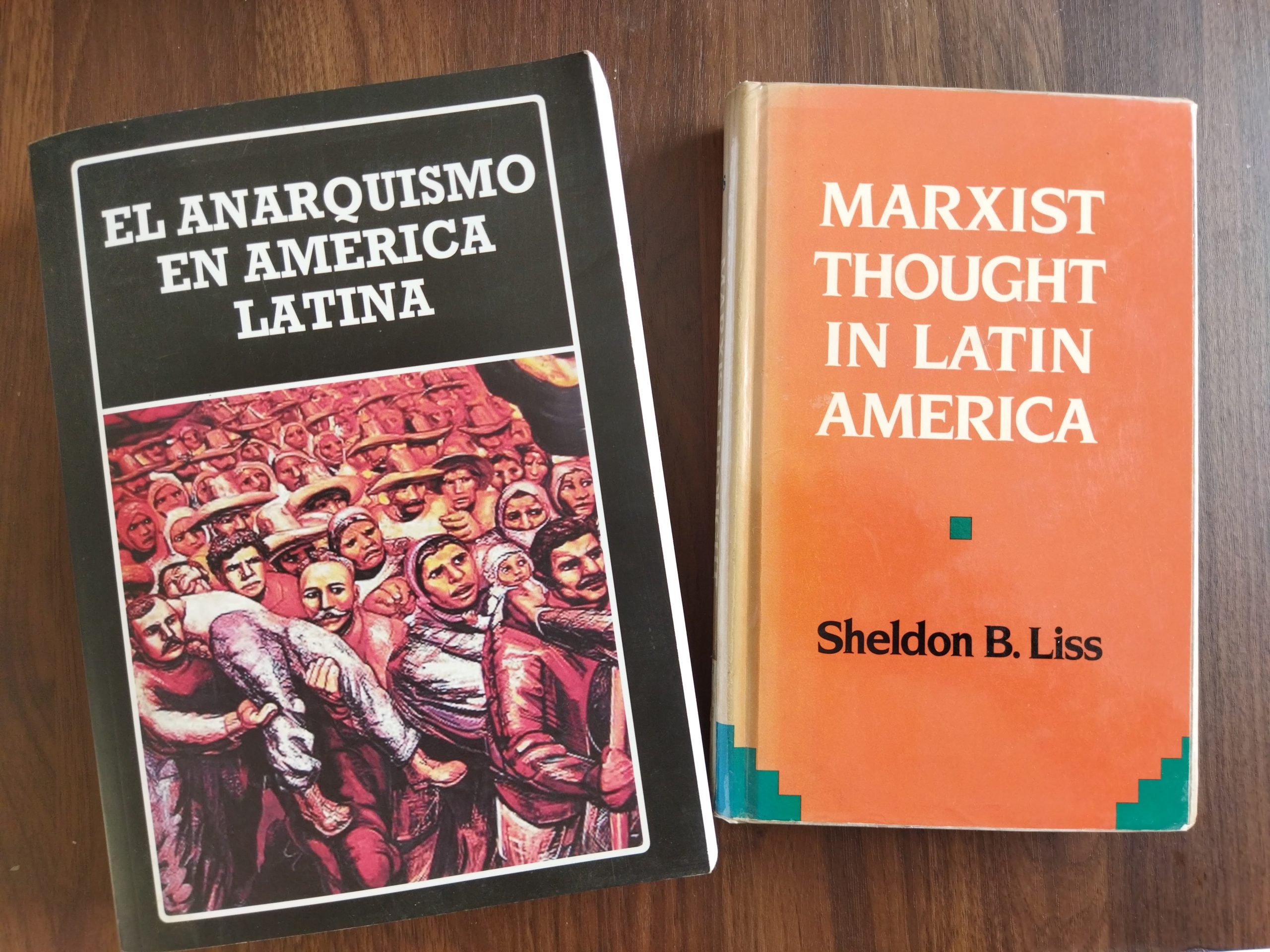Ilustrasi: Jonpey
“SEMUA jalan mengarah ke sasaran yang sama: menyampaikan kepada yang lain apakah kita ini.” Demikian penyair Cile Pablo Neruda pernah berkata mengenai kerja para penulis Amerika Latin seperti dirinya. Lalu apa yang telah disampaikan para penulis Amerika Latin kepada dunia, termasuk kita di Indonesia, tentang sub-benua mereka selama bertahun-tahun ini? Banyak sekali, tentunya. Dan saking banyaknya, maka tugas yang diberikan oleh redaksi rubrik “Batjaan Liar” IndoProgress kepada saya untuk memilih rekomendasi bacaan tentang Amerika Latin ini, khususnya terkait gerakan-gerakan progresifnya, terasa sungguh tidak mudah.
Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan pemilihan ini tidak mudah: Pertama, di Amerika Latin, politik, filsafat, seni, dan sastra berkelindan dan saling memengaruhi satu sama lain dengan amat erat. Sulit memilah-milahnya. Revolusi Meksiko, misalnya, tak bisa dipahami secara utuh tanpa menghitung peran muralis Diego Rivera dalam memopulerkan dan mengomunikasikannya kepada rakyat banyak, sebagaimana karya-karya Rivera tidak bisa dipahami tanpa meletakkannya dalam konteks Revolusi Meksiko. Di Brasil akhir 1990-an, wacana ketimpangan redistribusi lahan dan reforma agraria didorong paling kencang oleh telenovela O Rei do Gado. Saking kencangnya, O Rei do Gado menjadi pembicaraan publik sampai-sampai para tuan tanah berencana menuntut penulis telenovela itu ke pengadilan dan Kongres akhirnya bertindak menjatuhkan pajak tinggi bagi lahan tidak produktif. Sastrawan-sastrawati seperti Roque Dalton, Gioconda Belli, Sergio Ramírez bukan cuma mengangkat pena tetapi juga senjata sebagai prajurit gerilya. Begitu pun Rafael Guillén—jauh sebelum dikenal dunia sebagai Subcomandante Marcos—memasuki rimba Lacandon menggotong seransel penuh buku-buku puisi dan fiksi, bukan teori politik, untuk memulai pasukan gerilyanya. Dari sekilas contoh-contoh ini jelas, pembeda-bedaan kajian serius dan karya pop, atau fiksi dan non-fiksi dalam mengurai dan memahami realitas—topik yang sempat meramaikan jagat twitter kita tempo hari—sungguh tak relevan di Amerika Latin.
Kedua, Amerika Latin sangat luas dan beragam. Memandangnya sebagai monolit yang homogen dari ujung ke ujung hanya akan menghasilkan simplifikasi bahkan kekeliruan pemahaman. Ras, misalnya, yang masih menjadi isu penting di negara-negara seperti Bolivia atau Peru bisa dibilang bukan isu di Argentina yang sangat “putih”. Ketimpangan mencolok di Cile tidaklah didapati di Uruguay, dan rezim-rezim militer yang menjadi persoalan kambuhan di banyak negara Amerika Latin sama sekali bukan soal di Costa Rica yang sudah membubarkan tentaranya sejak 1948. Maka dari itu, akan keliru misalnya untuk menyamaratakan program dan fokus kelompok-kelompok progresif di negara yang berbeda-beda di Amerika Latin.
Namun demikian, pilihan harus dibuat. Mau tak mau, memilih berarti pula memadatkan, menyederhanakan, dan membuang. Saya pertama-tama akan memilih tema-tema terkait Amerika Latin yang sekiranya menarik dan relevan buat pembaca IndoProgress (misalnya: “Zapatisme”, “arus pasang merah jambu” dll), baru sesudahnya memilih buku-buku rekomendasi terkait tema bersangkutan. Meskipun tadi telah dibahas bagaimana pembedaan-pembedaan fiksi dan non-fiksi tidak relevan di Amerika Latin, namun dalam daftar ini saya membatasi diri pada non-fiksi hanya karena pilihan akan menjadi terlampau luas bila fiksi diikutsertakan. Batasan lain yang saya buat adalah bahasa—saya sebisa mungkin mencari buku-buku yang ditulis (atau diterjemahkan) dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Bila tidak tersedia, barulah saya merekomendasikan buku berbahasa Spanyol.
Kolonialisme, eksploitasi, dan warisan imperialis di Amerika Latin
The Broken Spears: The Aztec Account of the Conquest of Mexico (Beacon Press, 1962) karya sejarawan dan antropolog Meksiko Miguel León-Portilla dalam terjemahan Inggris oleh Lysander Kemp adalah bacaan wajib untuk mengetahui masa Penaklukan awal bangsa Indian Amerika Latin oleh kaum conquistadores Spanyol yang berlangsung sejak akhir abad ke-15. Para penakluk Spanyol sendiri serta pastor-pastor Katolik yang datang mengiringi maupun sesudahnya memang telah banyak menulis kronik tentang masa-masa itu dan mendokumentasikan kehidupan bangsa Indian, tetapi yang membuat buku León-Portilla berbeda dan menonjol adalah karena ia ditulis dari suara pihak yang dikalahkan. Miguel León-Portilla mengabadikan kerja intelektualnya meneliti kebudayaan Aztec pra-Kolombus, dan bisa dibilang sebagai perintis gerakan merevitalisasi bahasa Nahuatl. The Broken Spears adalah yang paling populer di antara puluhan buku hasil karyanya. Dia melacak cerita-cerita orang Aztec sendiri tentang masa Penaklukan dari peninggalan tertulis, ditambah dengan cerita-cerita lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi.
Hanya berselang sekitar satu dasawarsa sejak buku León-Portilla terbit, penulis Uruguay Eduardo Galeano merilis bukunya yang dalam bahasa Inggris berjudul Open Veins of Latin America: Five Centuries of the Pilage of a Continent (Monthly Review Press, 1973; terjemahan Inggris oleh Cedric Belfrage). Buku ini juga langsung menjadi klasik, dan dicekal di beberapa negara Amerika Latin yang pada dasawarsa 1970-an sedang dikuasai rezim-rezim sayap kanan. Dengan gaya penulisan sastrawi, cakupan yang sangat luas, serta pemahaman sejarah yang mumpuni (meski penulisnya resminya bukan sejarawan), Galeano berhasil menjelaskan bagaimana Amerika Latin menjadi “pembuluh nadi terbuka” yang darahnya terus-menerus disedot keluar—bukan hanya pada masa kolonial, tetapi juga pada era keuangan dan perekonomian internasional kontemporer yang bagi Galeano hanya melanjutkan sistem imperialis yang telah dibangun sejak masa kolonial.
“Sejarah adalah nabi yang melihat ke belakang,” tulis Galeano. Artinya: ia menubuatkan apa yang akan terjadi dengan melihat apa yang sudah terjadi. Maka buku ini “yang berusaha menyusun kronik perampokan kita dan sekaligus menjelaskan bagaimana mekanisme penjarahan terkini beroperasi, akan menyajikan secara berdekatan kaum conquistadores yang datang dengan kapal-kapal kerakah dan para teknokrat yang datang dengan pesawat jet; Hernán Cortés dan Marinir; agen-agen Takhta Spanyol dan misi Dana Moneter Internasional; dividen dari perdagangan budak dan laba General Motors.” (hlm. 18)
Foto: Ronny Agustinus
Buku ketiga adalah I, Rigoberta Menchú: An Indian Woman in Guatemala (Verso, 1983; terjemahan Inggris oleh Ann Wright) karya Rigoberta Menchú Tum, aktivis HAM dan masyarakat adat Guatemala peraih Hadiah Nobel Perdamaian 1992, yang disusun bersama Elisabeth Burgos-Debray. Buku ini bergenre testimonio, yang dalam kajian Amerika Latin berarti narasi biografis dari sudut pandang orang pertama (baik tunggal maupun jamak) yang berisi kesaksian atas suatu situasi ketidakadilan atau penindasan. Meski tulisan jenis “kesaksian” bukan hal baru, testimonio mulai dipandang sebagai genre tersendiri di Amerika Latin, beserta perdebatan teoretis mengenainya, seiring merebaknya kesaksian-kesaksian perlawanan terhadap penindasan kelompok-kelompok marginal oleh negara dan militer sejak 1970-an. Dalam konteks itulah testimonio Menchú, seorang Indian Quiche, ditulis: bagaimana sebuah negara nasional pascakolonial Amerika Latin menindas rakyatnya sendiri, terutama masyarakat adatnya. Konteksnya adalah masa pemerintahan Lucas Garcia, yang dipandang sebagai rezim paling berdarah dan korup sepanjang sejarah Guatemala. “Pada 1978-lah, ketika Lucas Garcia mulai berkuasa dengan nafsu untuk membunuh, represi sebenar-benarnya bermula di El Quiche. Wilayah ini cuma seperti potongan kain gombal di tangan Garcia. Ia mendirikan markas-markas militer di banyak desa dan terjadilah perkosaan, penyiksaan, penculikan. Serta pembantaian.” (hlm. 161) Meski bertolak dari kisah hidupnya pribadi, testimonio Menchú berfungsi sebagai cerminan atas apa yang jamak dialami oleh komunitas-komunitas masyarakat adat di wilayah Amerika Tengah.
Gagasan kiri progresif di Amerika Latin dan pengusungnya
Memang bagus kiranya bila kita mau mempelajari para pemikir kiri Amerika Latin satu per satu, tetapi bila kita tidak bermaksud menjadi spesialis soal ini, tak perlu juga rasanya membuang-buang umur untuk itu. Pakar seperti Sheldon B. Liss telah menyusun ekstraknya yang bisa kita baca dengan asyik Marxist Thought in Latin America (University of California Press, 1984). Buku ini padat tanpa kehilangan kompleksitas. Liss memetakan pemikiran per negara, per tokoh, memberi konteks bagi kemunculan tiap-tiap pemikiran. Problemnya hanya satu: buku Liss ini cukup tua, tidak pernah dimutakhirkan hingga ia wafat pada 1994, sehingga para pemikir yang mulai menonjol sejak era 1980-an pun seperti Marta Harnecker (Cile) atau Álvaro García Linera (Bolivia) belum tercakup di dalamnya. Buku Liss yang lebih baru (ditulis dua tahun sebelum wafat) terbit secara anumerta, Radical Thought in Central America (Routledge, 2020), dengan cakupan kawasan yang jauh lebih sempit (hanya lima negara) tetapi rentang pemikiran yang lebih luas, meliputi pemikiran-pemikiran radikal non-Marxis.
Foto: Ronny Agustinus
Bicara tentang pemikiran radikal non-Marxis, maka anarkisme tak boleh dilupakan peran, pengaruh, dan warisannya dalam gerakan-gerakan progresif Amerika Latin. Sebagai pemikiran sosial yang berasal dari Eropa, anarkisme memasuki Amerika Latin mulai sekitar 1860-an dengan puncaknya para pelarian Komune Paris 1871 (meski tentunya bentuk-bentuk indigenous dari “anarkisme” bisa didapati dalam berbagai praktik masyarakat adat), dan dalam banyak konteks, misalnya serikat-serikat buruh Argentina, Meksiko, Peru, atau Cile, anarko-sindikalisme menjadi ilham dan mode pengorganisasian yang jauh lebih kuat. Represi yang luar biasa brutal oleh negara mulai menyurutkan anarkisme sebagai gerakan massa pada dekade 1930-an. Angel de Cappelletti dan Carlos M. Rama telah menyusun buku legendaris yang sampai sejauh ini merupakan yang paling komprehensif mengenai anarkisme di Amerika Latin, El anarquismo en America Latina (Biblioteca Ayacucho, 1990). Buku ini terbit pada masa-masa runtuhnya Blok Timur dan sosialisme-komunisme dipertanyakan sebagai model yang mungkin bagi pengorganisasian politik progresif, sehingga melecut minat banyak pihak untuk menengok kembali ke anarkisme. Cappelletti sendiri wafat sebelum sempat melihat bukunya mencetuskan revivalisme anasir anarkis di banyak serikat buruh Amerika Latin.
Zapatisme, Awal dan Akhir Abad ke-20
Bicara Zapatista, pikiran kita mungkin langsung tertuju kepada pasukan gerilya bertopeng yang menghebohkan dunia pada akhir 1990-an. Namun sebelum itu, ada baiknya kita kembali ke Zapata yang ori, Emiliano Zapata di Morelos, beserta gerakan petani desa dan program reforma agrarianya yang meletuskan Revolusi Meksiko meski terus-menerus juga berusaha dihabisi oleh berbagai pemerintahan yang terbentuk dari hasil revolusi. Namun warisan Zapata jelas: rumusan pasal 27 UUD Meksiko 1917 adalah hasil tuntutan dan perjuangan gerakan petani. Bunyi dan kandungannya sesungguhnya mirip dengan pasal 33 UUD kita, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara, dan negara berhak mengolahnya untuk kepentingan rakyat.
Pasal 27 merinci bahwa negara berhak mengambil lahan dan menggusur bila ada “kepentingan publik”. Tuntutan atas rumusan macam ini harus dibaca dalam konteks saat itu ketika kapitalis dan tuan-tuan tanah perorangan bisa menguasai lahan dalam jumlah sangat besar, dan visi yang mendasari rumusan itu adalah bahwa negara harus bisa mengambil lahan swasta dan perorangan tersebut dan memberikannya untuk kepentingan publik, yakni para petani kecil. Mungkin tidak atau belum terbayang oleh Zapata dan pengikutnya bahwa pemaknaan “kepentingan publik” bisa dibelokkan oleh negara (“komite pengelola urusan borjuis” itu, menurut Marx) menjadi “kepentingan kelas pengusaha dan penguasa” dan berbalik merugikan kepentingan petani kecil. Sekarang kita tahu ini dengan jelas (di Chiapas, di Wadas, dll). Jadi, meski partai yang puluhan tahun berkuasa di Meksiko adalah partai yang punya nama dan sejarah “revolusioner”, proses revolusi itu sendiri berhenti, dan akhirnya lahirlah pemberontakan neo-Zapatisme pada tahun baru 1994.
Karya sejarah John Womack, Jr., Zapata and the Mexican Revolution (Vintage Books, 1968) belum ada duanya dalam mengkaji Emiliano Zapata dan gerakannya, serta konteks Revolusi Meksiko yang melatarinya. Penulis Meksiko seperti Carlos Fuentes pun memuji kemampuan Womack yang sanggup memahami luar biasa peliknya Meksiko sebagai sebuah peradaban, sehingga pemberontakan petani ini diletakkan dalam jalinan kompleks peristiwa dan sebab-musabab yang tidak tunggal dan simplistis. Untuk gerakan Zapatista 1994, izinkan saya merekomendasikan buku-buku yang saya susun dan terjemahkan sendiri, Bayang Tak Berwajah (Insist Press, 2003) dan Kata Adalah Senjata (Resist Book, 2005).
Revolusi Kuba
Revolusi Kuba bisa dibilang sebagai revolusi terpenting di Amerika Latin, bahkan dunia, pada abad ke-20 yang layak disorot tersendiri. Sebagai sebuah eksperimen sosialis ia mengubah bukan hanya geopolitik Amerika Latin, tetapi juga lanskap pemikiran dan kulturalnya. Ia juga sebuah sumbangan penting bagi dunia secara luas dan proyek-proyek pembebasan nasional serta dekolonisasi negara-negara Selatan. Kemampuannya bertahan selama puluhan tahun padahal diembargo oleh negara adidaya yang besarnya 89 kali lipat dirinya adalah juga sebuah pelajaran penting tentang kemandirian nasional.
Jika untuk topik ini saya hanya boleh mengusulkan satu rekomendasi, maka buku itu adalah A History of Cuban Revolution ed. 2 (Wiley-Blackwell, 2015). Buku karya Aviva Chomsky ini adalah buku yang paling mudah dibaca—lengkap tapi tak berkepanjangan—tentang keseluruhan aspek revolusi Kuba: bagaimana ia mengubah manusia, mengubah hubungan-hubungan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Namun perlu diingat, buku ini ditulis dengan pembayangan pembaca yang spesifik: mahasiswa-mahasiswi AS. Penulisnya berulang kali terlihat berusaha menyapih terlebih dulu pembacanya dari konsep-konsep yang mungkin bagi mereka taken for granted akibat proses pendidikan/indoktrinasi selama ini, dengan menjelaskan bahwa bagi orang Amerika Latin (baca: orang-orang di luar AS), konsep-konsep ini bisa punya pengertian yang berbeda. Misalnya, buku dibuka dengan bahasan soal “kebebasan”. Benarkah di Kuba tidak ada kebebasan? Apa yang dimaksud dengan kebebasan? Bagi banyak orang di Kuba atau Amerika Latin, kebebasan berarti “bebas dari eksploitasi kapitalis internasional”—hal yang mungkin tidak dipahami oleh anak muda AS.
Arus Pasang Merah Jambu
“Marea rosa” atau “arus pasang merah jambu” adalah istilah populer untuk menyebut kebangkitan politik kiri di Amerika Latin memasuki abad ke-21. Setelah kebijakan neoliberal era 1980-an hingga 1990-an, satu demi satu presiden berhaluan kiri—dimulai oleh Hugo Chávez (Venezuela)—merebut suara rakyat lewat demokrasi elektoral dan naik menduduki tampuk kekuasaan. Beberapa di antaranya bahkan berlatar belakang mantan gerilyawan kiri, seperti José Mujica (Uruguay) dan Dilma Rousseff (Brasil)—sesuatu yang tak terbayangkan bisa terjadi bahkan satu dekade sebelumnya.
Mengapa merah jambu? Awalnya, pada 2006 istilah ini dimaksudkan sebagai ejekan peyoratif oleh wartawan New York Times untuk menyebut bahwa “pemerintahan kiri” Amerika Latin saat itu cuma tong kosong nyaring bunyinya. Gahar dalam retorika, tapi kosong isi. Namun kemudian, beberapa pengamat lain mulai memberinya makna yang lebih positif. Ada yang menuliskan bahwa ini adalah bentuk lebih kalem dari “merah” yang selama ini diasosiasikan dengan komunisme (artinya pemerintahan kiri abad ke-21 dicapai melalui jalur demokratis tanpa senjata). Ada juga yang melihatnya sebagai kiri yang sudah diimbuhi dengan wawasan-wawasan lain yang dulu belum menjadi pertimbangan kaum komunis jadul, seperti feminisme, hak-hak minoritas seksual dll. Namun, perlu diingat juga bahwa merah jambu telah lama menjadi warna bendera partai revolusioner Bolivia Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) saat Víctor Paz Estenssoro dan Hernán Siles Zuazo mendirikannya pada 1942.
Mike Gonzalez dalam The Ebb of the Pink Tide: The Decline of the Left in Latin America (Pluto Press, 2019) menyajikan suatu overview yang padat dan sangat tajam tanpa menggampangkan mengenai gelombang naik (sekaligus turun) ini. Memang, memasuki tengah 2010-an, pemerintahan-pemerintahan kiri ini tampak pudar, dan sebagai respons muncullah kembali golongan-golongan konservatif reaksioner atau ola conservadora (arus konservatif). Gonzalez menganalisis sebab-sebabnya, dan dengan jujur melancarkan otokritik terhadap strategi pemerintahan-pemerintahan ini yang menurutnya hanya mengambil jarak dari modal AS tapi mendekat ke modal Tiongkok dan Rusia. Sosialisme sejati tidak bisa dibangun dengan cara seperti itu.
Meski analisis Gonzalez penting dan wajib dibaca, tetapi dalam beberapa hal dia juga tampak terlalu pesimistis, semisal yang terlihat dari judul bukunya. Seakan-akan decline (penurunan) akan berlangsung terus tanpa titik balik. Padahal, memasuki 2020-an dan di masa pandemi, kita menyaksikan kembalinya marea rosa melalui, misalnya, Pedro Castillo (Peru), Xiomara Castro (Honduras), dan Gabriel Boric (Cile), yang didahului oleh protes-protes sosial-ekonomi skala besar.
Tentu terpilihnya Boric adalah peristiwa paling menarik dan menimbulkan keingintahuan kita di sini. Bagaimana kubu kiri yang sudah hancur digerus kudeta dan militerisme Pinochet selama berpuluh tahun bisa kembali menguat dan menyebar ke kalangan mudanya, melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang mampu merebut dukungan rakyat. Kita semua berharap bisa belajar darinya dan mengidamkan sesuatu yang sama bisa terjadi di sini. Masalahnya, belum ada satu buku utuh yang mengulas keberlangsungan gerakan kiri di Cile sesudah pemerintahan kiri Unidad Popular Salvador Allende dikudeta hingga bangkitnya aktivisme kiri-kiri muda yang nantinya menjadi basis dukungan Boric. Saya sendiri sangat menantikan adanya buku seperti itu.
Dari sepengetahuan saya, setelah Unidad Popular kena gebuk telak, aktivis kiri Cile menyebar ke banyak tempat. Dari banyak tempat pulalah, serta banyak medium, perlawanan terhadap rezim dilancarkan: dari aliansi partai-partai politik yang masih diizinkan ada, ketidakpuasan terhadap rezim akhirnya menjadi wadah bagi bibit-bibit oposisi bagi sisa-sisa kiri Cile di bawah Pinochet; dari para aktivis dan intelektual eksil yang menulis dan berkampanye soal pelanggaran HAM di Cile, serta—dalam banyak kasus—membentuk partai-partai kiri baru di pengasingan; dari gerakan gerilya dan serikat-serikat buruh terutama di wilayah selatan; dari media massa dalam negeri yang terus-menerus menegosiasikan sensor; dari aktivisme Gereja Katolik yang melakukan pendampingan dan tuntutan atas nama korban rezim. Sisa-sisa kiri Cile tidak sepenuhnya hilang tetapi menyebar ke semua unsur tadi dan menjadi basis bagi revitalisasi gerakan pasca referendum yang menurunkan Pinochet dari kekuasaan. Maka membaca banyak aspek yang terpencar ini bisa memberi kita pemahaman yang lebih utuh tentang strategi membangun kembali gerakan kiri Cile.
Ada beberapa buku yang bisa saya rekomendasikan untuk itu. Dari sang legenda sendiri, Salvador Allende, presiden sosialis pertama di dunia yang terpilih secara demokratis: Salvador Allende Reader: Chile’s Voice of Democracy (Ocean Press, 2000). Kumpulan artikel dan wawancara Allende ini menunjukkan dengan jelas visinya sebagai politikus kharismatik yang masih terus menjadi pegangan dan ikon gerakan kiri Cile saat ini. Karya Katherine Hite, When the Romance Ended: Leaders of the Chilean Left, 1968-1998 (Columbia University Press, 2000) bersumber dari 100-an wawancara dengan tokoh-tokoh Cile di pengasingan. Di antara tokoh-tokoh ini, Hite membedakan antara “loyalis partai” (yang setia kepada komunisme sebagai partai) dan “loyalis sosok” (yang setia kepada Allende lebih sebagai pribadi). Bahasan buku ini lagi-lagi penuh dengan detail yang mungkin lebih cocok bagi mereka yang ingin menjadi spesialis; ia bisa jadi tidak inspiratif bagi kita yang ingin mencari inspirasi tentang apa yang bisa dipetik oleh Indonesia. Namun inilah satu-satunya buku yang bisa menjadi penghubung antara kiri Unidad Popular dengan berbagai penerusnya pada 1980-an. Ia bisa menjelaskan mengapa kiri Cile bisa bangkit lagi—karena memang ia tak pernah sepenuhnya mati (berbeda dengan PKI).
Foto: Ronny Agustinus
Dua buku berikut ini Podemos cambiar el mundo (Ocean Sur, 2012) karya Camila Vallejo dan No lo vieron venir: Columnas, 2005-2020 (LOM Ediciones, 2021) karya Daniel Jadue sesungguhnya tak perlu-perlu amat dibaca, tetapi menarik karena keduanya adalah pelaku langsung dari aktivisme kiri dalam satu-dua dekade terakhir yang berujung kepada kemenangan Gabriel Boric. Vallejo—yang kini diangkat sebagai Menteri Sekretaris Negara—adalah teman Boric sejak masa-masa aktivis mahasiswa, dan bukunya berisi pidato serta wawancaranya selama memimpin demo-demo mahasiswa menuntut reformasi pendidikan (yang dikenal sebagai “revolusi penguin” 2006) dan memberi kita akses langsung untuk melihat permasalahan yang dihadapi kaum muda Cile yang lantas dijadikan fokus perubahan oleh Partai Komunis. Sementara Jadue, yang sempat digadang-dagang sebagai kandidat presiden—sebelum kalah oleh Boric dalam pemilihan internal Partai—sudah punya prestasi yang menarik sejak masih jadi walikota di municipal Recoleta. Dia berhasil memangkas biaya obat untuk warga kebanyakan turun sampai 30% dengan membuka apotek-apotek di kampung, yang lalu diperluasnya jadi buka optik tingkat kampung, dan rencananya juga toko buku tingkat kampung. Kumpulan kolomnya juga memberi wawasan langsung mengenai masalah kesenjangan yang amat parah di Cile, yang pada akhirnya menyulut demo-demo besar “estallido social” (letupan sosial).***