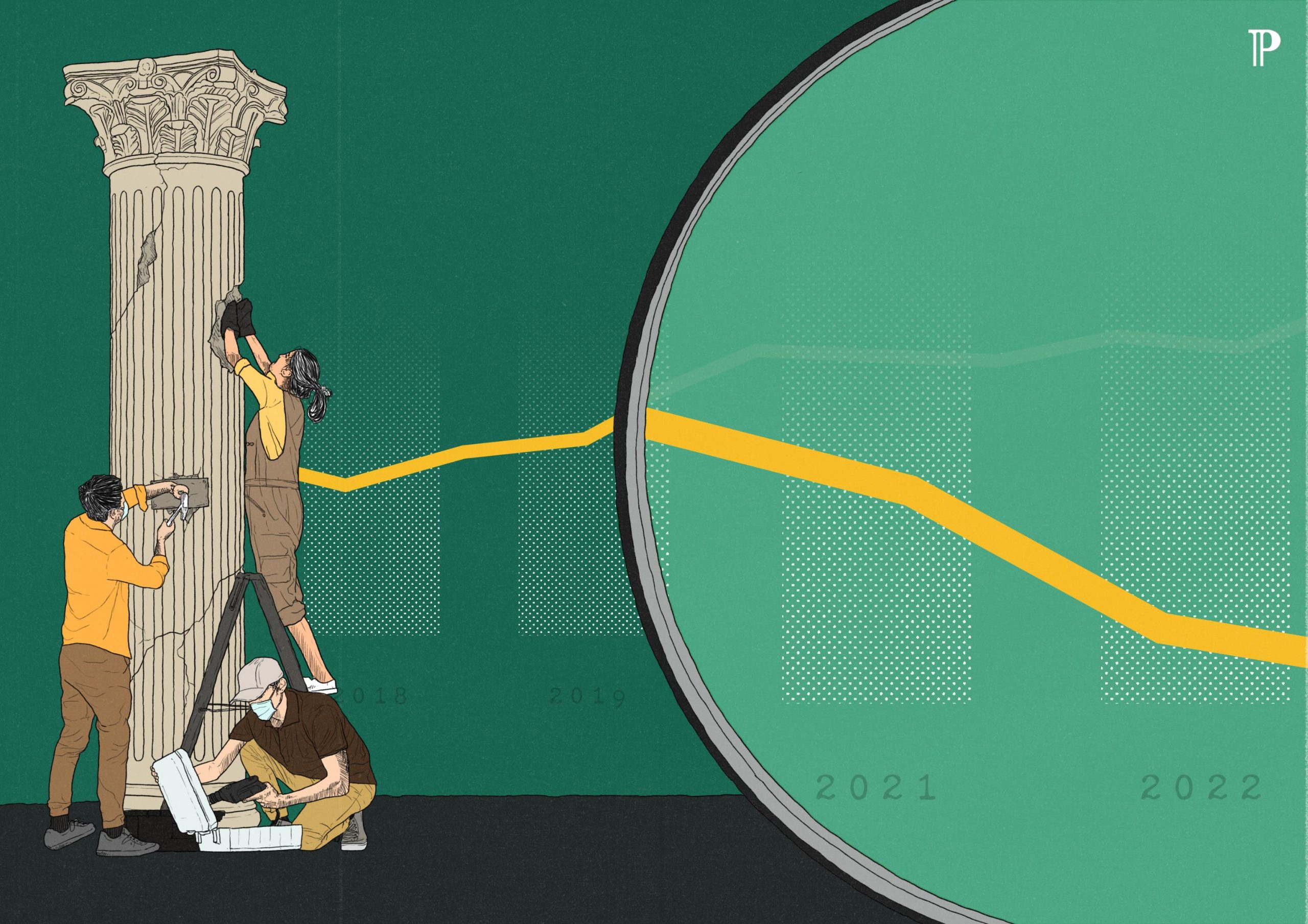Ilustrasi: Illustruth
BEBERAPA minggu terakhir surat kabar terkemuka Kompas menerbitkan laporan mengenai membaiknya kualitas demokrasi di Indonesia serta tingginya tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintah. Laporan ini mengundang perdebatan di ruang publik karena dianggap mengandung bias, tapi sekaligus menegaskan posisi dan watak Kompas sebagai produk jurnalisme pelat merah.
Publik telah jamak mengetahui posisi Kompas yang cenderung mendekat kepada penguasa sejak ia didirikan sebagai bagian dari strategi surat kabar ini untuk bertahan hidup, juga sebagai respons atas sindrom double minority complex yang diidapnya. Laporan Kompas tentang membaiknya skor indeks demokrasi di Indonesia sepanjang tahun 2021 yang merujuk pada The Economist Intelligence Unit (EIU), dengan demikian, dapat dilihat sebagai bagian dari narasi tandingan yang menilai adanya tren penurunan kualitas demokrasi dalam beberapa tahun terakhir. Kompas bisa saja mengelak tuduhan itu dengan berlindung di balik klaim objektivitas lembaga pengindeks EIU.
Pertanyaannya, sejauh apa klaim objektivitas lembaga pengindeks demokrasi dapat dipercaya? Apa kepentingan lembaga-lembaga pembuat rangking demokrasi seperti EIU, Freedom House dan V-Dem? siapa yang diuntungkan darinya?
EIU menyebutkan bahwa dari lima indikator, ada tiga aspek yang mengalami peningkatan yang berkontribusi meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia sepanjang tahun 2021: keberfungsian pemerintah, kebebasan sipil dan partisipasi politik. Padahal, sepanjang tahun itu, seperti juga tahun-tahun sebelumnya, kualitas dari aspek-aspek itu sangat buruk. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, misalnya, pemerintah cenderung abai menanganinya secara serius dan lebih berkepentingan mengeksploitasi krisis kesehatan publik yang terjadi untuk memperbesar kekuasaan dan peluang pencarian rente. Penangkapan, pembungkaman dan represi terhadap para pengkritik pemerintah juga terus terjadi. Partisipasi politik dalam pembuatan kebijakan juga terbatas. Namun demikian, bagaimana EIU dapat memberi penilaian positif pada aspek-aspek itu?
Sebenarnya banyak studi telah mengulas kelemahan model-model pemeringkatan demokrasi. Peter Tasker (2016), misalnya, menilai pemeringkatan itu berpijak pada ilmu yang cacat dan karena itu secara metodologis layak dipersoalkan. Dalam mengomentari EIU, Tasker mengatakan: “terlepas dari tampilan objektivitas saintifiknya, pemeringkatan kualitas demokrasi suatu negara penuh dengan bias, penilaian [subjektif] serta agenda tersembunyi seperti pemberian Oscar untuk film atau bintang Michelin untuk restoran—yang juga diputuskan oleh sekelompok ahli yang misterius menggunakan kriteria yang hanya diketahui di kalangan mereka sendiri”.
Sarah Bush (2017) dalam artikelnya yang diterbitkan oleh jurnal Perspectives on Politics mengatakan bahwa skor-skor indeks itu tidak hanya membuat peringkat-peringkat kualitas demokrasi tapi juga mendefinisikan demokrasi untuk audiens tertentu. Menurutnya, negara-negara dan organisasi-organisasi internasional tertentu menggunakan pemeringkatan-pemeringkatan demokrasi untuk menentukan ke mana jutaan dolar bantuan pembangunan akan diberikan serta sejauh apa keberhasilan program-program itu.
Ada banyak lembaga pemeringkat demokrasi yang membuat definisi dan ukuran yang berbeda-beda, tapi menurut Bush, Amerika Serikat hampir selalu menggunakan indeks Freedom in the World yang dibuat oleh Freedom House sejak 1972. Pemerintah AS menggunakan indeks ini untuk menentukan target negara yang dapat menerima bantuan pembangunan serta untuk mengevaluasi capaian upaya-upaya promosi demokrasi di sana. Sebaliknya, negara resipien juga dapat menggunakan indeks itu; mengunggulkan skor positif untuk memperkuat legitimasi kekuasaan, serta mengapitalisasi skor negatif untuk memperoleh bantuan pembangunan.
Bush juga menerangkan bahwa pemeringkatan itu tampak saintifik, tapi sebenarnya sangat subjektif, terutama yang sumber pengukurannya dari pandangan para ahli dan in-house coding. Artinya, pemeringkatan ini bukan semata soal metodologi, tapi juga memuat problem ideologis.
Hal itu bisa diamati, misalnya, dari indikator yang secara umum digunakan yang lebih berfokus pada aspek liberalisme dalam demokrasi. Freedom House, misalnya, menggunakan indikator yang terbatas pada hak-hak politik dan kebebasan sipil. Sementara itu, EIU menggunakan lima indikator yang meliputi proses elektoral dan pluralisme, kebebasan sipil, keberfungsian pemerintah, partisipasi politik dan budaya politik. Indikator-indikator ini tentu saja tidak menjangkau terutama aspek-aspek yang berkaitan dengan keadilan sosial dan ekonomi serta tingkat kualitas jaminan kesejahteraan sosial dari negara kepada warganya.
Tapi persoalannya bukan semata bagaimana memuat indikator selengkap mungkin dalam penyusunan indeks. Sebab, menurut Bush (2017), Meskipun tampak netral, penentuan indikator kunci peringkat-peringkat demokrasi itu melibatkan pengambilan keputusan yang subjektif. Pemeringkatan yang paling berpengaruh, menurutnya, seringkali adalah “karena ia merefleksikan penilaian dari mereka yang berkuasa”.
Yang juga penting untuk dicatat adalah, dalam kajian akademik, para pakar penganut teori modernisasi dan pluralisme liberal adalah mereka yang paling gandrung menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif yang dibuat oleh lembaga-lembaga pengindeks itu dalam menilai dan menganalisis kualitas demokrasi suatu negara. Sebagaimana para pemakainya dari kalangan ilmuwan, ukuran-ukuran kuantitatif tentang kualitas demokrasi ini berpijak pada paradigma transisional dalam memahami perkembangan demokrasi. Perkembangan ini dilihat secara linear yang membentang dari periode transisi, konsolidasi ke periode demokrasi yang telah berfungsi secara penuh. Stagnasi, penurunan kualitas atau dekonsolidasi demokrasi juga diukur dari trek yang sama.
Penilaian mengenai tren negatif kualitas demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sebagian besar juga dibuat dengan mengacu pada skor-skor indeks itu. Jika konsisten, dengan bertolak dari skor EIU, para pakar penganut paradigma transisi demokrasi semestinya mulai mengoreksi penilaian mereka dan mengapresiasi capaian positif pemerintah sebagaimana dilakukan Kompas. Tapi itu jika kita percaya pada indeks-indeks demokrasi tanpa memeriksa kepentingan apa dan siapa yang diuntungkan dari skor penilaian tertentu.
Sebagaimana telah saya ulas pada artikel sebelumnya, problem konseptual dari penjelasan yang berpijak pada paradigma transisi demokrasi itu punya implikasi praktis yang cukup serius. Persoalan paling mendasar adalah skor-skor indeks demokrasi yang ada tidak dapat menggambarkan secara utuh kondisi sosial-politik yang sebenarnya. Demokrasi di Indonesia, misalnya, pernah dikategorikan sebagai yang telah terkonsolidasi terutama karena ditopang oleh adanya elemen masyarakat sipil yang kuat.
Padahal, elemen masyarakat sipil cenderung terfragmentasi dan tak memiliki agenda politik yang koheren bahkan dalam mempertahankan demokrasi. Kebebasan sipil dan partisipasi politik juga terbatas, sementara korupsi menjadi masalah yang endemis. Namun, masalah-masalah ini cenderung diabaikan, bahkan dinormalisasi oleh lembaga-lembaga pengindeks itu serta para pakar transisi demokrasi.***