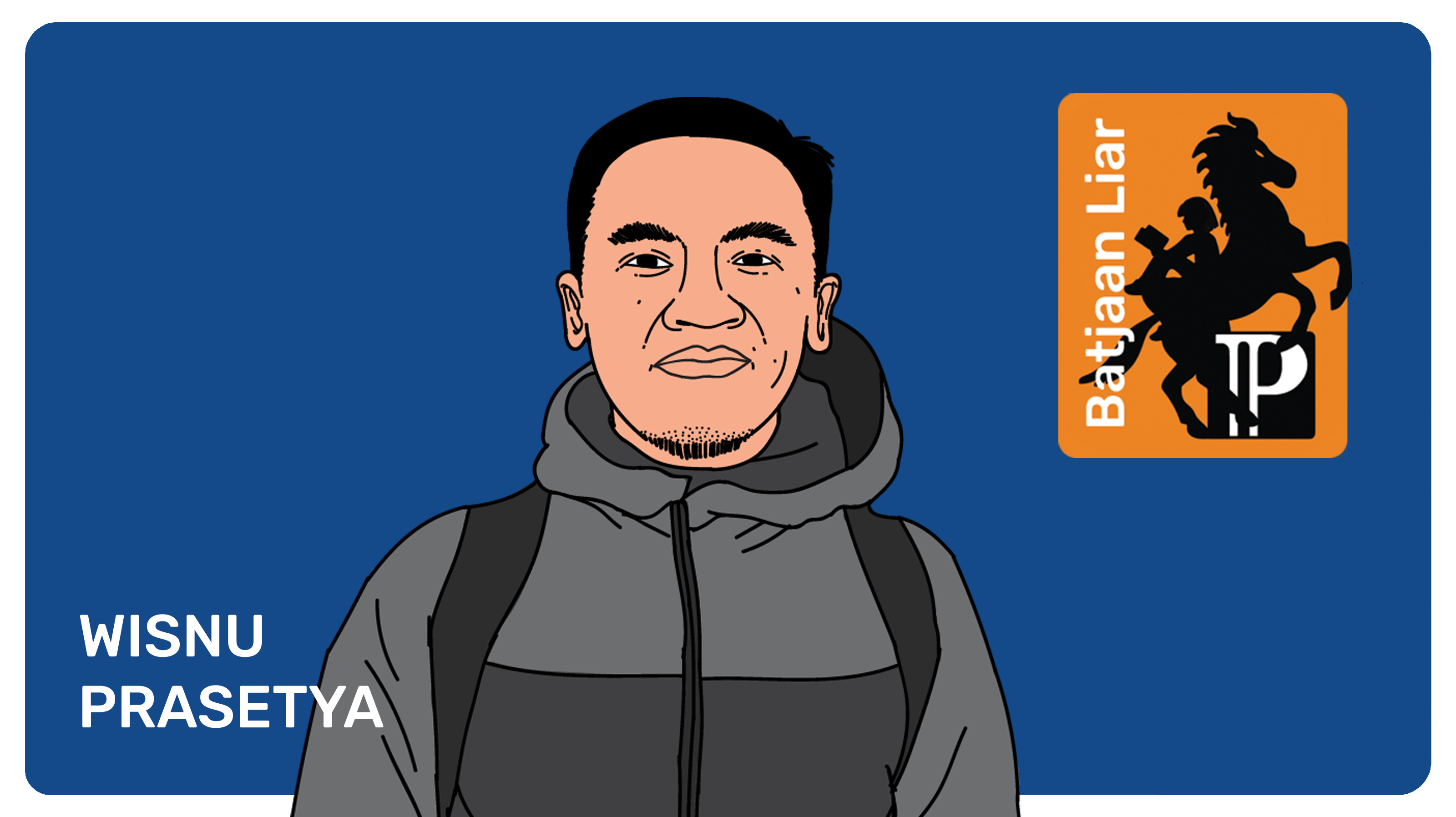Ilustrasi: Illustruth
SALAH SATU topik yang meresahkan ketika mendiskusikan jurnalisme adalah konvensi arus utama yang memfatwakan bahwa media harus netral. Pasalnya, anggapan semacam itu sering digunakan untuk mendelegitimasi media-media yang liputannya kritis. Semua berangkat dari asumsi bahwa media harus netral, tak boleh punya sikap, apalagi oposan terhadap kekuasaan elite.
Dalam konteks tertentu, netralitas juga kemudian mengurung posisi jurnalis. Saya pernah mendengar cerita dari seorang teman jurnalis yang memutuskan mundur dari organisasi profesi jurnalis karena tidak boleh mengekspresikan sikap politiknya di media sosial. Padahal, menurutnya, sikap politiknya tetap tidak mengurangi standar jurnalistik yang ia lakukan ketika menulis berita.
Teman yang lain, juga seorang jurnalis, mengeluh tentang standar ganda saat dirinya mengekspresikan sikap, bersamaan dengan jejaring politik yang dimiliki atasannya.Banyak kasus saat ia dilarang menyampaikan pandangan politik tertentu di media sosial, tetapi nyatanya banyak atasannya yang diam-diam menjadi tim sukses kandidat politisi dan menerima berita pesanan.
Tentu saja, cerita-cerita tersebut merupakan ilustrasi yang tidak bisa digunakan untuk melakukan generalisasi atas kondisi media di Indonesia saat ini. Namun, ia setidaknya bisa dipakai untuk memulai diskusi lebih serius tentang netralitas media dan jurnalis. Di Project Multatuli, saya menulis bahwa “netralitas dalam jurnalisme adalah hal yang secara teori dan praktik tidak mungkin dicapai.”
Bagi saya, persoalannya memang bukan pada apakah sebuah media netral atau tidak, atau partisan dan berpihak atau tidak. Persoalannya—karena hampir tidak mungkin media bisa bersikap netral—adalah kepada siapa keberpihakan itu diarahkan dan bagaimana ia dilakukan. Ini yang mestinya bisa dieksplorasi lebih jauh kalau ingin membicarakan kondisi media di Indonesia dengan jujur.
Saya punya delapan buku untuk direkomendasikan agar bisa membantu mendiskusikan isu tersebut lebih jauh. Menurut saya, ia tidak hanya penting untuk wartawan dan juga akademisi atau peneliti media, melainkan juga mahasiswa yang kelak ingin masuk ke industri media. Dengan begitu, ketika mendiskusikan tentang netralitas media, kita bisa berangkat dari realitas dan bukan pada teori-teori normatif yang semakin berjarak.
Tidak semua buku-buku yang saya rekomendasikan di bawah ini khusus membahas media. Namun ia bisa memberikan kita konteks yang lebih luas untuk sampai pada kesimpulan kenapa netralitas media itu pada dasarnya adalah sebuah mitos.
- Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (Edward S. Herman dan Noam Chomsky, 1994)
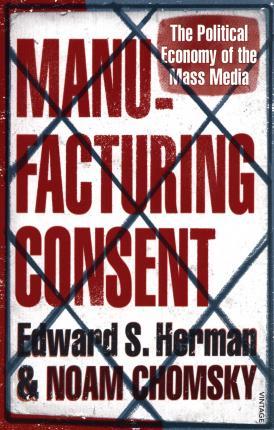
Dalam kajian tentang ekonomi politik media, buku ini tak bisa diabaikan. Untuk menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar demokrasi, teori-teori normatif kajian media menilai bahwa media tak boleh menjadi megafon bagi kelompok kepentingan yang berkuasa. Ia harus bisa objektif dan tidak berpihak. Herman dan Chomsky menyebut bahwa pandangan tersebut justru berjarak dengan realitas.
Melalui model propaganda yang mereka jelaskan dalam buku ini, Herman dan Chomsky menyebut ada lima filter yang memastikan media pada dasarnya hanya melayani elite. Lima filter tersebut adalah kepemilikan, iklan, sumber, flak (respon negatif terhadap media dari respon individual sampai regulasi), dan anti-komunisme. Anti-komunisme sebagai filter tentu tidak bisa dilupakan dalam kerangka Perang Dingin dan politik luar negeri Amerika Serikat—yang menjadi salah satu objek kritik Herman dan Chomsky. Lima filter tersebut, selain melayani elite, juga menjelaskan bagaimana media memproduksi persetujuan (manufacturing consent) publik.
Hal lain yang perlu diperhatikan dari Herman dan Chomsky adalah pendapat mereka bahwa sebagai bagian dari sistem pasar, media tidak hanya berbagi kepentingan yang sama dengan bisnis lain yang berorientasi profit, tapi juga berbagi kepentingan yang sama dengan negara yang punya kemampuan untuk mempengaruhi cara pasar media bekerja dengan kebijakan-kebijakannya.
Latar belakang ekonomi politik ini yang mesti dipahami ketika ingin mendiskusikan tentang “netralitas.”
- The Political Economy of Communication (Vincent Mosco, 2006)
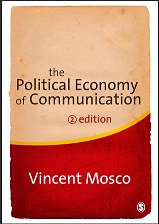
Buku ini juga sudah menjadi salah satu rujukan utama ketika mendiskusikan tentang ekonomi politik komunikasi. Pisau analisis yang diajukan Mosco—komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi—penting untuk melihat gerak laju industri media, khususnya terkait dengan konsentrasi kepemilikan.
Komodifikasi—proses mengubah nilai guna menjadi nilai tukar—dalam industri media berkaitan dengan tiga hal: konten, audiens, dan pekerja. Spasialisasi merupakan proses untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam mekanisme produksi. Proses ini dilakukan dengan dua cara, horizontal dan vertikal. Spasialisasi horizontal muncul ketika pemilik modal menggabungkan berbagai jenis media dalam satu kontrol kepemilikan. Sedangkan spasialisasi vertikal berjalan ketika pemilik media menggabungkan perusahaan dari berbagai jenis industri untuk mendapatkan kontrol atas proses produksi.
Sedangkan strukturisasi menjelaskan proses pembentukan struktur sosial oleh agen, di mana bagian-bagian dalam struktur tersebut saling mempengaruhi masing-masing bagian, serta struktur secara keseluruhan. Strukturisasi menghasilkan serangkaian relasi kuasa maupun hubungan sosial. Dalam pembahasan terkait netralitas, pisau analisis itu bisa kita pakai untuk membedah lapis demi lapis bias yang mempengaruhi cara media bekerja.
- Media and Power (James Curran, 2002)

Buku berikutnya adalah karya dari James Curran, professor komunikasi di Goldsmiths College University of London. Ada tiga pertanyaan yang ia ajukan dan coba dijawab dalam buku ini: Sebesar apa kuasa dan pengaruh yang dimiliki media? Siapa yang sebenarnya mengontrol media? Apa dan bagaimana relasi antara kekuasaan dan media di masyarakat?
Curran menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan memberikan berbagai studi kasus di media di Inggris. Salah satu yang ia ceritakan, misalnya, terkait dengan penelusurannya atas kontrol media dari sisi sejarah. Berdasarkan konvensi arus utama, media-media di Inggris punya kebebasan yang besar karena sejak dulu mereka bekerja keras untuk lepas dari jeratan kontrol pemerintah dan partai politik.
Salah satu caranya, dengan independen secara finansial yang akhirnya membuat media bisa bebas memberitakan apa saja. Ia berargumen bahwa independensi finansial ini pada dasarnya adalah media kemudian bergantung pada pasar. Kekuatan pasar kemudian secara efektif menjadikan media di Inggris sebagai alat bagi kontrol sosial, sesuatu yang sulit dicapai dengan regulasi negara. Konsentrasi kepemilikan di industri media pelan-pelan menjadikan para pemilik media menjadi powerful.
Membesarnya kuasa media tidak bisa dilepaskan dari proses konsolidasi kekuasaan para elite. Kata Curran, menjadi wajar ketika media-media sayap kanan yang menguasai pasar kemudian punya kontribusi signifikan terhadap stabilnya konservatisme di masyarakat Inggris.
- Chavs: The Demonization of the Working Class (Owen Jones, 2016)
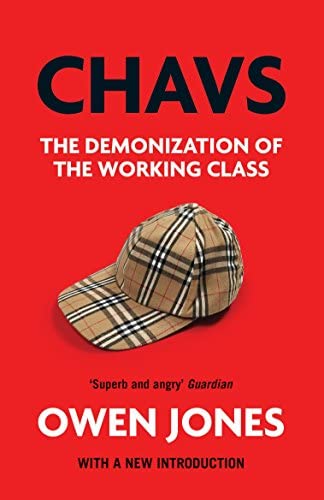
Buku yang ditulis oleh jurnalis The Guardian ini tidak secara spesifik mendiskusikan tentang jurnalisme. Owen coba membongkar bagaimana kaum elite yang mapan (establishment) di Inggris baik pengusaha, media, dan terutama politisi menggunakan berbagai cara untuk mendelegitimasi kelas pekerja.
Buku ini dibuka dengan cerita seorang ibu yang menculik anaknya sendiri dan memfabrikasi cerita penculikan untuk dijual secara ekslusif kepada media-media tabloid di Inggris yang suka dengan sensasi. Ada juga cerita bagaimana para penerima bantuan sosial dari negara, justru banyak yang melakukan aksi kriminal. Cerita semacam ini yang dipotret media bertaburan di dalam buku setebal 304 halaman tersebut.
Menurut Owen, cara media-media tabloid sayap kanan membingkai dan mengeksploitasi cerita tersebut bertujuan untuk memberikan ruang bagi kebencian dan kemarahan karena krisis ekonomi. Alih-alih diarahkan pada Partai Konservatif—yang ketika buku ini ditulis ada di dalam kekuasaan—yang melanjutkan Tatcherism, kemarahan karena krisis ekonomi diarahkan pada kelompok Chavs, kelas pekerja yang rentan.
Tepat pada titik itulah, buku ini menunjukkan bahwa media literally melanggengkan dan berpihak pada status quo.
- Losing Pravda: Ethics and the Press in Post-Truth Russia (Natalia Roudakova, 2017)
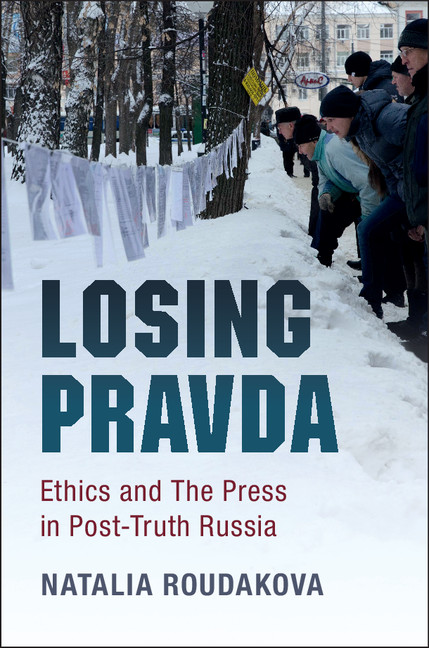
Buku nomor lima merupakan hasil dari penelitian Natalia Roudakova tentang perubahan dalam kultur politik dan jurnalisme di Rusia selama lebih dari tiga dekade terakhir. Ia lakukan penelitian arsip media, observasi etnografi di ruang redaksi media-media lokal, analisis konten, dan wawancara dengan puluhan jurnalis di Rusia.
Roudakova memotret kebingungan sebagian besar jurnalis, khususnya di masa transisi runtuhnya Uni Soviet di awal 1990-an. Kebingungan para jurnalis dan media itu berkaitan dengan: “siapa yang mereka representasikan, kepada siapa mereka harus memberikan loyalitas terkait pekerjaannya, dan bagaimana relasi antara informasi dan uang.”
Kebingungan itu yang membuat mereka terjebak pada relasi patron-klien dengan berbagai aktor politik. Tidak mengherankan bahwa, kata Roudakova, jurnalis di Rusia sering diidentikan dengan profesi prostitusi: rela menjual tubuhnya asalkan bisa mendapatkan akses terhadap informasi. Terkait dengan relasi patron-klien ini, Roudakova menyebut istilah kompromat—yang sering dipakai para aktor politik untuk mengunci satu sama lain.
Banyak jurnalis di Rusia yang kemudian mengambil langkah serupa sesuai dengan relasi patron-kliennya. Mereka menjalin relasi dengan politisi, mendapatkan akses dan informasi, dan di saat yang bersamaan punya ketergantungan dengan relasi itu—kondisi yang menegaskan ada di mana posisi dan keberpihakan jurnalis serta medianya.
- Comparing Media Systems Beyond the Western World (Editor Daniel C. Hallin and Paolo Mancini, 2012)

Buku yang saya rekomendasikan berikutnya adalah kumpulan tulisan sebagai respons atas buku Comparing Media Systems yang ditulis Hallin dan Mancini pada 2004 silam, yang mencoba membuat kategori-kategori dalam sistem media di berbagai negara—khususnya terkait relasi media dan sistem politik. Namun, buku tersebut dikritik terlalu western-centric (barat-sentris). 13 tulisan di buku ini mencoba memperluas sistem tersebut melampaui negara-negara barat.
Yang menurut saya menarik adalah tulisan Duncan McCargo di mana ia memperkenalkan istilah partisanship polyvalence. Dengan konsep ini, McCargo bilang bahwa alih-alih berafiliasi secara ideologis dengan partai politik sebagaimana media-media di barat, media di Asia lebih dekat hubungannya dengan berbagai aktor politik yang ada. Seperti yang dikatakan McCargo (2012: 208), “paralelisme politik dalam konteks Asia bukanlah tentang ikatan organisasi formal, melainkan segala sesuatu yang berkaitan dengan koneksi pribadi.”
Kategori kanan dan kiri—sebagaimana yang lazim digunakan untuk membaca media di barat—menjadi stidak relevan di Indonesia. Penjelasan tersebut penting untuk menjelaskan kondisi media di Indonesia yang dari sisi sejarah, yang memang tidak punya tradisi media sebagai pilar demokrasi yang netral dan nonpartisan. McCargo juga menjelaskan kenapa dalam kerangka politik elektoral, sebuah media sering berubah-ubah dalam menunjukkan dukungan politiknya.
Karena punya ikatan dengan berbagai kelompok tersebut dan berpengaruh terhadap bagaimana sebuah berita diberitakan, menyebut media netral adalah sebentuk penyangkalan terhadap kondisi yang ada.
- Politics and the Press in Indonesia: Understanding an Evolving Political Culture (Angela Romano, 2003)

Angela Romano menulis buku tentang bagaimana kultur politik dan nilai-nilai yang ditanamkan Orde Baru, dari paternalisme sampai korupsi, mempengaruhi cara jurnalis dan media di Indonesia memahami diri mereka sendiri.
Romano menyebut bahwa di negara berkembang seperti Indonesia, banyak wartawan yang mengimani ide bahwa media tidak boleh menjadi bagian yang merusak negara saat sedang dalam kondisi krisis. Media harus menjaga stabilitas karena itu harus menampilkan berita-berita yang “positif” dan mendukung agenda pemerintah. Berita harus “konstruktif dan korektif, tapi tidak destruktif,” kata Romano mengutip seorang wartawan senior.
Kultur semacam itu yang menjadi dasar bagi “kebebasan pers yang bertanggung jawab” di era Orde Baru.
Selain itu, Romano juga mengulas tentang kultur “amplop” dalam jurnalisme di Indonesia. Kultur amplop di mana berbagai instansi maupun aktor politik “mengamplopi” para jurnalis yang meliput mereka, menciptakan kondisi ketergantungan antara media dan sumbernya yang rentan dieksploitasi satu sama lain. Di satu sisi amplop bisa membuat sebuah berita bisa “dipesan,” di sisi lain ia menunjukkan kerentanan seorang jurnalis yang kondisi kesejahteraannya tidak terjamin.
Kondisi ketergantungan tersebut yang membuat dari buku ini saya belajar bahwa netralitas media itu mitos: karena setiap tindakan yang dilakukan oleh jurnalis dan media selalu dipengaruhi oleh berbagai bias, baik di level personal maupun di level sistem. Bias ini—yang tidak bisa disingkirkan begitu saja dengan berbagai perangkat dan teknik jurnalistik—tentu saja yang berpengaruh terhadap bagaimana sebuah berita dibingkai dan disajikan.
- Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital (Ross Tapsell, 2018)

Buku Ross Tapsell yang terbit pada 2018 ini mengonfirmasi dan mempertegas penelitian-penelitian yang ada sebelumnya tentang semakin terpusatnya kepemilikan media di Indonesia. Media tidak hanya semakin terpusat di mana media-media besar mengakuisisi media-media yang kalah modal, melainkan juga para pemiliknya semakin aktif masuk ke gelanggang politik. Mereka mendirikan organisasi masyarakat, membentuk partai politik dan menjadi ketuanya, juga ada yang bergabung dengan pemerintahan. Ciri-ciri yang bisa kita lihat dalam politik Indonesia dua dekade belakangan.
Ross menyinggung bahwa para oligark media ini bukanlah nama-nama baru. Mereka adalah kelompok yang dibesarkan oleh Orde Baru. Ketika Soeharto jatuh, mereka berhasil melakukan rekonsolidasi kekuasaan dengan cepat dan menguasai pasar media dan infrastruktur komunikasi di Indonesia.
Efeknya, nada pemberitaan sebuah media akan mengikuti ke mana bandul politik pemiliknya mengarah. Tentu saja, tidak ada netralitas di sana.***
Wisnu Prasetya Utomo, dosen di Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM
Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda melalui tangan Balai Poestaka berusaha membendung arus penerbitan buku dan artikel karya para aktivis anti-kapitalis dan anti-kolonialis. Barisan literatur yang berperan besar menyuburkan gerakan politik kelas di Indonesia ini dicap Belanda sebagai “batjaan liar”. Kami mengklaim kembali istilah tersebut untuk sebuah rubrik berisi rekomendasi bacaan yang disusun secara tematik untuk merespons berbagai macam isu. Haris Prabowo adalah editor tamu Batjaan Liar. Sehari-hari ia bekerja sebagai jurnalis Tirto.id.