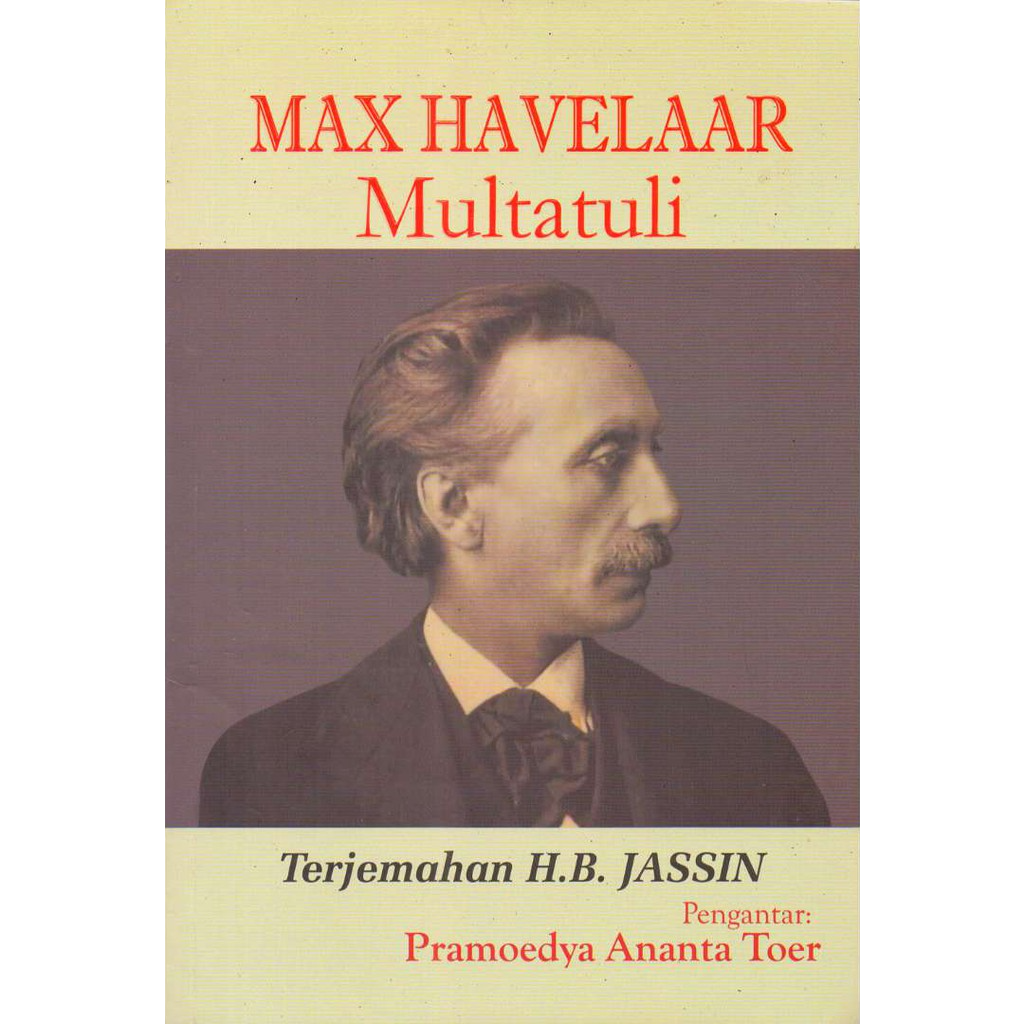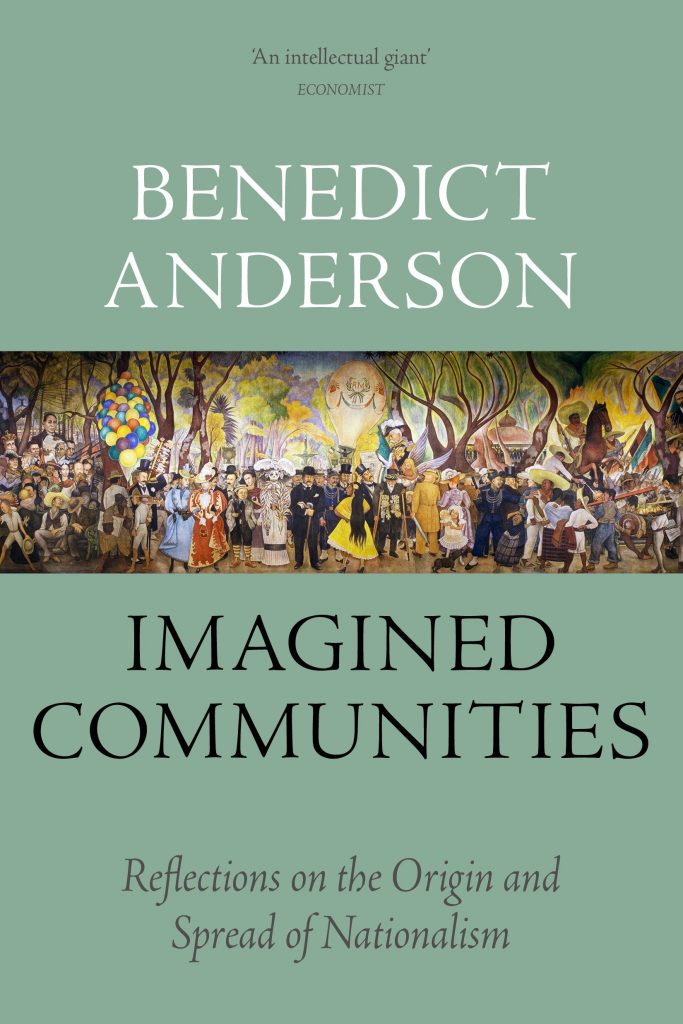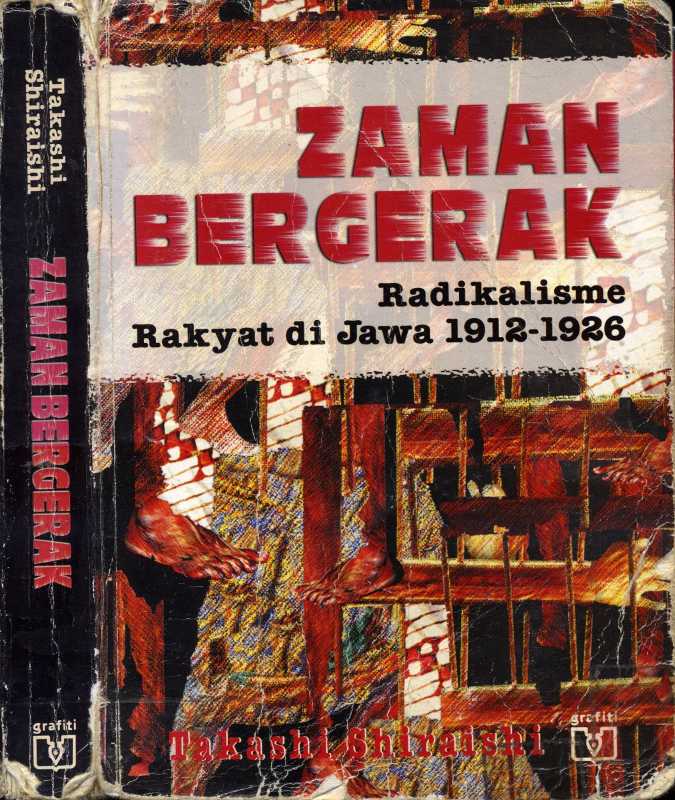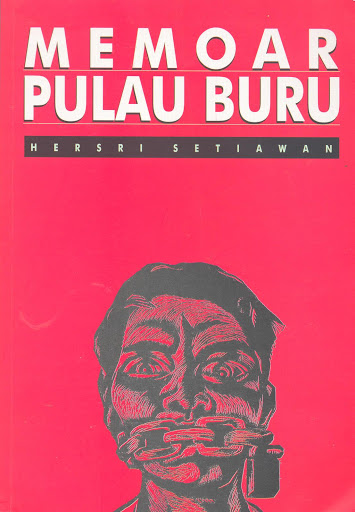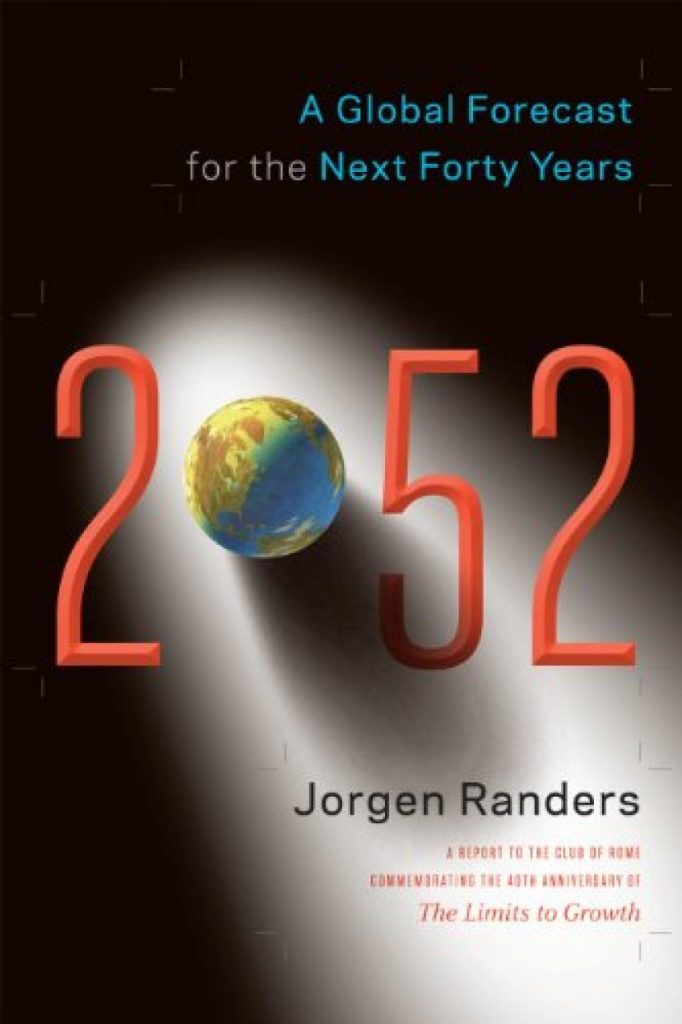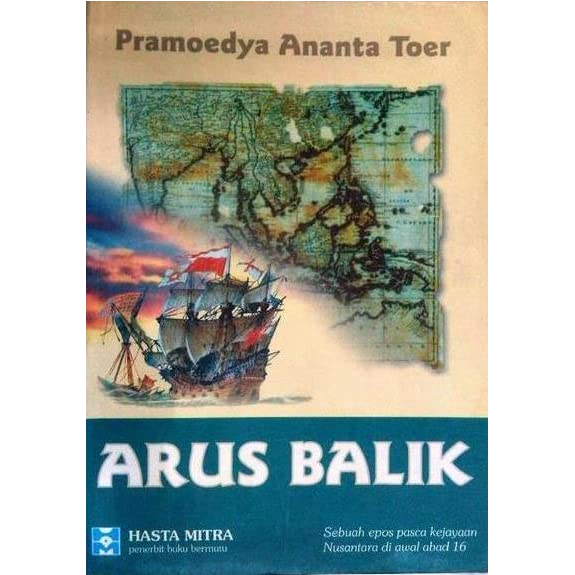Ilustrasi: Deadnauval
JIKA ADA yang perlu saya soroti dari sekian kebijakan pemerintahan Joko Widodo, hal itu tidak lain dari gagasannya tentang Indonesia jelang abad ke-22. Gagasan yang digadang-gadang menjadi peta besar Indonesia tersebut kerap diklaim sebagai “Indonesia Emas 2045”. Alhasil, angkatan saya—yang saat tulisan ini dibuat berada di antara usia 15-25 tahun—disebut-sebut pula di dalamnya sebagai “Generasi Indonesia Emas.”
Gagasan itu pertama kali dituangkan Joko Widodo dalam sebuah catatan yang ditulisnya di Merauke, bertitimangsa 30 Desember 2015. Ia berisi tujuh butir impian yang isinya adalah akselerasi kualitas sumber daya manusia, kebhinekaan, mimpi menjadi pusat peradaban dunia, aparatur negara yang bersih dari korupsi, pemerataan pembangunan—astaga, istilah ciptaan Orde Baru ini ternyata masih laku dipakainya—didukung kemandirian bangsa yang akan mendongkrak Indonesia menjadi barometer ekonomi global.
Dari manuskrip itu, Menteri BPN/Kepala Bappenas menjabarkannya dalam makalah yang sudah dibekali berbagai grafik dan analisis data mutakhir lalu diberi judul “Visi Indonesia 2045.” Makalah ini dipaparkan pertama kali dalam sebuah orasi ilmiah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 26 September 2017 lalu.
Bagi segelintir orang, visi seratus tahun Indonesia mungkin akan dipandang visioner. Pandangan seperti itu didorong oleh fakta sejarah bahwa presiden terakhir Indonesia yang berani merencanakan peta jalan Indonesia hingga seabad hanya Sukarno. Sesudah beliau dikudeta jenderalnya sendiri—dengan dukungan penuh modal multinasional—visi besar itu dilenyapkan. Tak tanggung-tanggung, ongkos yang mesti dibayar untuk melenyapkan visi itu adalah eksekusi atas satu juta anak bangsa sendiri—sonder pengadilan.
Lebih dari setengah abad kemudian, tak heran kembalinya visi 100 Tahun Indonesia buatan Jokowi dinilai sebagai kebangkitan Indonesia yang kembali bergairah, setelah melalui bertahun-tahun dininabobokkan jargon pembangunan berselubung fasisme para serdadu, konflik-konflik komunal, hingga pemerintahan korup.
Tak salah jika Jokowi memberi judul manuskrip itu sebagai “impian,” bukan “cita-cita.” Setiap orang bisa saja bermimpi, tetapi tidak semua mimpi dapat menjadi cita-cita. Dalam kasus ini, istilah “impian” sudah tepat diletakkan. Ia memanglah mimpi—atau lebih tepatnya mimpi basah yang cukup membuat dahi berkerut.
Para penggerak utama mimpi itu adalah generasi saya. Tak sedikit dari kami yang masih terlena dalam prinsip keniscayaan dan keyakinan goodwill pemerintah hari ini. Dua belas tahun ditempa pendidikan Indonesia—termasuk empat kali pergantian kurikulum, apa yang telah saya dapat dari negara boleh diibaratkan sebagai bekal sebatang galah untuk cita-cita menjolok rembulan. Uraian lebih lengkap dapat dibaca pada serial “catatan empiris” yang telah saya tulis beberapa waktu lalu.
Dengan bekal tersebut—termasuk yang teranyar berupa program pendekatan pendidikan dengan dunia industri yang disebut “Merdeka Belajar” dan “Kampus Merdeka,” saya tak perlu ragu-ragu mengamini metafora seorang kawan bahwa generasi “Tiktoker-Youtuber-Influencer” yang dinisbatkan sebagai “Generasi Indonesia Emas” ini nyatanya hanyalah “Generasi Kaleng-Rombeng.”
“Generasi Kaleng Rombeng” yang dimiliki Indonesia saat ini mungkin terasa hanya sebuah ungkapan gejolak darah muda yang labil. Namun nyatanya, optimisme delusional golongan tua yang mengagul-agulkan generasi kami sebagai juru selamat dan hanya menjadi penerus, bukan pengubah, Indonesia itu sering terdengar dongkol. Tak jarang saya mengumpat dalam hati: “Wahai bapak-ibu guru, bukankah kalian yang mengajarkan pada kami, bagaimana kalian memamah biak informasi sampah, mencontohkan “budaya” hipokrit- korup-manipulatif, dan yang paling menjadi bencana adalah menjauhkan kami dari buku?”
Dari kejengkelan itu, tak terhitung berapa kali saya kecewa karena perpustakaan sekolah tidak memiliki buku-buku bagus yang perlu dibaca sehingga kami tak gampang menelan informasi sampah—apalagi menjadikannya suatu tataran aksioma. Seruan pejabat angkuh yang mengimbau anak-anak muda agar mampu menangkal hoaks sejak dini sungguh ironis: bagaimana generasi muda mampu membedakan informasi sampah dan informasi bermutu, jika membaca dan memilih buku bacaan yang bagus saja harus diajari?
Saya merekomendasikan tujuh buku yang wajib dibaca dan dibedah, agar sedapat mungkin mengubah pandangan yang bias dan kabur menjadi kokoh dan fokus. Saya kira tujuh buku ini kiranya menjadi moda terakhir yang dapat menjadi senjata agar generasi “Indonesia Emas” tidak benar-benar menjadi kaleng rombeng.
1. Max Havelaar atau Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda (Multatuli, 2018)
Buku pertama, dan yang saya camkan paling mendasar, adalah Max Havelaar. Kendati buku ini telah disinggung berulang kali dalam buku sejarah sebagai buku yang ditulis “Belanda baik,” tetapi bagi yang benar-benar paham isi dan konteks penulisannya, penjelasan buku Max Havelaar di dalam skripta sejarah resmi adalah kekeliruan besar. Buku sejarah secara sembarang menyebut bahwa Max Havelaar, roman yang pertama kali terbit 160 tahun silam ini, berisi kritik atas sistem tanam paksa yang menyengsarakan rakyat. Bodohnya, istilah “Belanda baik” kerap dinisbatkan kepada penulisnya sebagai antitesis “Belanda jahat” dalam bab-bab sejarah lainnya.
Kesalahan ini membikin saya bilang dengan terus terang di banyak kesempatan bahwa roman Max Havelaar sama sekali tidak mengkritik sistem tanam paksa yang menimpa rakyat Jawa, namun mengkritik habis-habisan penyalahgunaan kekuasaan pejabat bumiputra—dalam konteks buku adalah Bupati Lebak dan Demang Parangkudjang—yang berlaku korup, represif, serta acap memanipulasi kenyataan pahit dengan kebohongan-kebohongan dan dalih-dalih.
Implikasi langsung dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan ini dikisahkan sangat baik dan jujur oleh Havelaar, asisten residen yang baru bertugas sebulan di Lebak. Ia mengambil contoh bagaimana dari banyak laporan aduan dari penduduk setempat yang diterimanya, sangat sedikit yang kembali untuk mengusut lanjutan perkaranya. Maksud Havelaar, sebelum mengusut jauh permasalahan yang diadukannya, orang-orang ini telah lebih dulu “dibereskan” oleh kaki tangan Bupati yang berkuasa di atas rasa takut rakyatnya sendiri.
Karena itu pula, dalam suratnya terakhirnya kepada Gubernur Jenderal, Havelaar meraung keras-keras: “Yang Mulia mempersalahkan saya atas dasar-dasar yang samasekali isapan jempol dan bohong [….] Tapi Yang Mulia telah membenarkan sistem penyalahgunaan kekuasaan, sistem perampokan dan pembunuhan yang memberati pundak orang Jawa yang malang dan karena itulah saya mengeluh!”
Urgensi Max Havelaar dalam hal ini jelas: semboyan-semboyan kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan yang diagul-agulkan Eropa nyatalah hanya riak kecil di alam penindasan yang sungguh mencekik bagi rakyat di Dunia Ketiga—yang sekian abad menjadi sumber kemakmuran dan pemasukan utama Eropa. Karenanya, berkaca pada praktik penindasan itu, Max Havelaar bukan saja mengimbau makna kebebasan dan hak-hak asasi manusia, namun juga mengajarkan pembacanya untuk menggugat secara kritis asal-usul akumulasi kekayaan sejumlah pihak yang ternyata berasal dari hasil keringat pihak lain yang mengalami eksploitasi tak berkesudahan.
2. Imagined Communities: Reflection on The Origins and Spread of Nationalism (Ben Anderson, 2006)
Buku kedua—dan yang paling berkesan ketika saya membaca dan mendalaminya—tiada lain dari pemikiran otentik Oom Benedict Anderson ini. Bagi generasi saya, yang sejak mula telah dibesarkan dalam kerangka pikir nasionalisme chauvinistik, buku ini akan merombak cara berpikir itu dengan pertanyaan yang sangat sederhana: “apa itu nasion?”
Jika selama kita belajar di sekolah dikisahkan bangsa Indonesia lahir serta-merta dari rasa benci yang membukit terhadap penjajahan, maka buat saya buku inilah yang pertama kali memperkenalkan suatu konsep hakiki bahwa bangsa Indonesia sebagai suatu entitas terlebih dulu ada dalam imajinasi dan bayangan orang-orang yang merasa (kelak) akan menjadi bagian di dalamnya. Di dalam aspek yang lebih mendalam lagi, buku ini turut menelaah konstruksi sebuah masyarakat juga turut terbentuk karena peran media cetak. Bagaimana media di dalam masyarakat yang mula-mula mengenal surat kabar mendapatkan kesamaan pengertian, memiliki kesamaan bahasa dan membentuk gramatika, yang pada akhirnya melahirkan identitas pertama dan paling menonjol tentang sebuah bangsa: yaitu bahasa.
Dengan bekal akan suatu “komunitas terbayang” itu pula, sejarah tercipta. Tak kurang dari jutaan orang mati untuk mendirikan dan mempertahankan eksistensi “komunitas terbayang” itu. Berbagai perang kemerdekaan sejatinya dilakukan untuk suatu imajinasi terbatas yang bernama bangsa. Ada orang-orang besar yang menjadi simbol “komunitas terbayang” itu, namun sejatinya ia bukan siapa-siapa tanpa orang-orang kecil yang akhirnya berguguran demi menegakkan sang pemimpin besar.
Cara berpikir ini memberi saya perspektif baru tentang Indonesia 2045: apakah dalam waktu yang pasti akan datang itu, Indonesia tetap ada seperti hari ini? Ataukah Indonesia sudah bubar dan ditertawakan bangsa-bangsa lain, karena Indonesia yang konon gagah itu dihancurkan oleh masyarakatnya sendiri yang terpolarisasi kepentingan politik para penguasa dan mau-maunya dihasut isu-isu kepicikan pemuka agama? Bangsa seperti apa yang dikehendaki Indonesia hari ini?
Idealisme tinggal idealisme. Kenyataan yang ada jauh lebih kejam daripada bayang-bayang siapapun mengenai suatu tatanan komunitas yang kini rapuh dan tertatih-tatih diterjang zaman. Akankah Indonesia 2045 tetap menjadi komunitas terbayang? Atau tinggal sekadar menjadi bayang-bayang kejayaan masa lalu namun nyatanya tinggal tulang-belulang kegagalan yang dia ciptakan sendiri?
3. Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (Takashi Shiraishi, 1997)
Untuk buku nomor tiga, saya tidak bisa jika tidak merekomendasikan karya penting tentang zaman pergerakan Indonesia ini. Dengan membaca Zaman Bergerak ini, kita bisa menemukan keterkaitan antara gagasan-gagasan besar Multatuli mengenai ketertindasan orang Jawa yang tak sanggup melawan dengan bibit-bibit pergerakan yang diinisiasi kaum intelektual.
Pondasi pergerakan mula-mula memang dan tidak dapat dilepaskan dari para cerdik cendekia dan insan pers yang merintis surat-surat kabar berbahasa Melayu. Namun, bagi kalangan rakyat jelata—dalam buku ini spesifik di Surakarta, Semarang, dan Yogyakarta—apa-apa yang menyangkut pergerakan tidak bisa tidak dilakukan secara radikal. Bukti konkret dan yang paling berpengaruh adalah wahana Sarekat Islam yang kemudian mengalami gejolak dan pertentangan Islamisme dan pemikiran sosial-revolusioner Karl Marx dan Bolsyewik.
Pertentangan-pertentangan yang kemudian melahirkan gejala baru dalam mengonsolidasi pergerakan dan pemikiran rakyat melalui surat kabar, kemudian menyulut gambaran ihwal cikal bakal lahirnya Partai Komunis Indonesia (PKI) yang membidani kebulatan identitas politik Hindia dan menjadi organisasi revolusioner mula-mula. Haji Misbach, tokoh Islam berhaluan komunis yang jamak dibicarakan dalam buku ini, kiranya menjadi gambaran irisan kedua gagasan besar yang acap dipertentangkan diametral itu.
Saat ini, ketika semua pemikiran yang bertentangan dengan kehendak dan keinginan para penguasa akan dicap “radikal” dan dikutuk, bukan salah jika buku ini wajib kembali dibaca dan dipatrikan dalam ingatan: Indonesia tidak akan pernah ada di muka bumi, jika kaum radikal tidak bergerak menuntut perbaikan nasib. Dengan kata lain, jika pemerintah sekarang mengutuk “radikalisme” sebagai belenggu, samalah dia dengan anak yang mengutuk dan memaki rahim ibunya sebagai belenggu.
4. Memoar Pulau Buru (Hersri Setiawan, 2004)
Sejalan dengan ide menapis sejarah gerakan kiri dan peranannya dari historiografi resmi, maka pembinasaan lebih dari 500.000 orang tertuduh komunis tanpa peradilan dalam bulan-bulan sesudah Oktober 1965-1966 acap disingkirkan dari ingatan. Yang selamat dari pembinasaan namun harus dibusukkan dalam berbagai penjara dan akhirnya kerja paksa selama bertahun-tahun tanpa upah, bernasib setali tiga uang. Buku nomor empat menggambarkan keadaan itu.
Pengalaman saya yang terakhir, kurikulum sejarah menyajikan peristiwa dalam hari-hari sesudah Gerakan 30 September 1965 dengan berkisar pada peralihan kekuasaan: rakyat marah atas terbunuhnya jenderal-jenderal (sesuatu yang hingga tulisan ini dibuat tidak terasa masuk di akal saya); rakyat menuntut dibubarkannya PKI; hingga rakyat juga yang menuntut Presiden Sukarno agar menyerahkan kekuasaan bulat kepada Jenderal Soeharto yang “dipercaya rakyat.” Semuanya menggunakan kata “rakyat,” tanpa dijelaskan kepada siswa, “rakyat” mana yang dimaksud itu.
Secara personal, saya merekomendasikan buku Hersri Setiawan ini karena buku ini—yang saya pinjam dari perpustakaan SMP dalam edisi yang diterbitkan IndonesiaTera sebelum dicetak ulang Kepustakaan Populer Gramedia—adalah buku pertama yang mendobrak benteng antikomunis yang dibangun dalam teks buku PPKN. Buku ini memberi saya pengertian bahwa Tragedi 1965 bukan hanya drama terbunuhnya enam petinggi Angkatan Darat di Jakarta, namun juga serangkaian aksi teror dalam rangka balas dendam yang dilakukan Angkatan Darat di luar nalar kemanusiaan. Pendeknya, tanpa memoar ini, saya mungkin akan tetap menyebut 1965 di dalam satu rangkaian kata made in Orde Baru, G-30-S/PKI.
Bagian yang menurut saya paling memikat dari Memoar Pulau Buru ini terletak pada penggambaran setiap kisah yang ringkas namun detail. Dalam 572 halaman, memoar ini tidak menaruh pretensi korban yang mempahlawankan diri. Pengisahan yang jujur tentang kepahitan yang dialami pengarangnya, pertama-tama memang membuat saya bertanya: “Masa iya, sih?”
Pertanyaan itu dengan sendirinya terjawab ketika pengelanaan saya terhadap rumpun bacaan dalam dan luar negeri seputar tragedi kemanusiaan 1965 berkembang dan mempertemukan saya dengan para peneliti dan sejarawan yang menaruh minat serupa. Stimulus yang diberikan Memoar Pulau Buru bagi saya tak tergantikan. Memoar ini pula, saya yakin, dapat membantu menjawab teka-teki bangsa yang kadang ditinggalkan, dan sering kali dilupakan di antara baris-baris buku petunjuk masalah eksak dan teknik yang menggejala.
5. Unfinished Nation: Indonesia Before and After Soeharto (Max Lane, 2016)
Jika dinilai tak berlebihan—dan harapannya tidak—bolehlah jika saya mendaku buku ini telah menjawab satu lagi missing link ihwal sejarah sebuah bangsa bernama Indonesia yang lama menjadi kabut dalam buku sejarah: pergerakan dan aktivisme warga.
Diterbitkan pertama kali oleh Verso pada 2008, buku karya Max Lane—mantan staff Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia dan penerjemah beberapa roman Pramoedya Ananta Toer—ini akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerbit Djaman Baroe pada 2016. Di dalamnya, dengan narasi bertutur yang cukup memikat, tergambar jelas watak dari pergerakan bangsa Indonesia sejatinya terletak pada gerakan massa—sejak awal zaman Politik Etis di Hindia hingga tergulingnya kediktatoran Soeharto.
Massa pekerja dan buruh tani—dua basis kelompok gerakan rakyat yang sayangnya sangat sayup terdengar di buku-buku sejarah—ditekankan dalam buku ini sebagai kelompok yang memiliki andil luar biasa besar dalam menggerakkan perubahan sejarah. Perlawanan yang jelas tertuju untuk mengakhiri riwayat Orde Baru di Indonesia secara jeli tergambarkan dalam buku ini sebagai perlawanan berdarah, penuh bahaya, namun menampakkan hasil yang tidak sedikit.
Dengan konsentrasi pada peran besar massa pekerja dan buruh tani, tak salah jika banyak pembaca—termasuk saya—sepakat bila pemikiran kiri adalah motor utama dalam berbagai fragmen sejarah. Orang-orang kiri yang selama ini disingkirkan dari sejarah dan distigma sebagai pengkhianat, sebagaimana ditulis Max Lane, adalah aktor sejarah yang sejati. Karenanya pula, siapapun yang hendak mempelajari sejarah perubahan Indonesia, buku ini wajib dimasukkan masuk ke dalamnya.
6. 2052: A Global Forecast for The Next Forty Years (Jørgen Randers, 2012)
Dalam esai saya yang kedua, buku ini sedikit saya singgung dalam beberapa alinea jelang penutup. Sejatinya, buku ini merupakan suatu perkembangan atas buku serupa yang pernah ditulis Club of Rome pada 1972 dan dievaluasi sesudah 40 tahun. Analisis Randers ini tajam, faktual, dan yang paling saya sukai, diperkaya dengan statistik dan data kiwari. Jelas, buku yang memberi gambaran kepada kita tentang planet bumi tahun 2052 ini bukan sekadar isapan jempol.
Buku yang pertama kali terbit pada 2012 dan telah diterjemahkan dalam 6 bahasa (Jerman, Polandia, Jepang, Korea, Mandarin, dan Italia) ini, Randers menitikberatkan permasalahan dunia kontemporer dalam tiga aspek: keberlanjutan; prakiraan populasi dan dampaknya; serta analisis tren ekonomi yang ditelaah dari lebih 30 buku karya ekonom, futuris, dan ilmuwan. Pendek kata, Randers mengemas semua gambaran tentang ketahanan manusia di muka bumi dalam kacamata generalis.
Randers menganalisis antara lain bagaimana populasi dunia mengalami puncak pada 2030 dan menurun dalam dekade berikutnya. Dengan demikian, perlambatan ekonomi yang diawali penurunan konsumsi akan susul-menyusul dengan gelombang baru investasi yang dipaksakan maupun yang dilakukan secara sukarela. Lebih jauh, Randers menjabarkan efek domino inklinasi ini, yaitu eksploitasi terhadap kapasitas lingkungan hidup dunia yang bisa membuat perkotaan lokasi dijadikan areal pertambangan baru!
Di luar masalah pemenuhan kebutuhan fisik, akses terhadap ilmu pengetahuan akan membaik dan jagad internet akan dengan sendirinya memisahkan ranah publik atas privat. Keadaan ini akan berimbas pada pilihan yang akan diambil spesies manusia: tetap bersaing atau memilih bekerja sama mempertahankan eksistensi spesiesnya?
Meski tidak membahas spesifik mengenai negara per negara, namun tinjauan singkat yang komprehensif ini akan menjadi peta jalan yang memadai untuk memprediksi wajah Indonesia 2045. Situasi yang digambarkan Randers mungkin tidak terbayangkan hari ini. Akan tetapi, bila nyatanya situasi tersebut bukan mustahil terjadi, pertanyaan yang masih mengganjal dalam benak saya: “mengapa buku sepenting ini tak terdengar bahkan belum lagi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia?”
7. Arus Balik (Pramoedya Ananta Toer, 2002)
Roman legendaris yang terakhir dicetak ulang Hasta Mitra pada 2002 ini menyuguhkan gambaran transisi Hindu menuju Islam, kedatangan bangsa Portugis, invasi Malaka, hingga kedaulatan Portugis yang berhasil mencengkeram pelabuhan utama dan paling berpengaruh di Jawa, Tuban.
Roman ini saya rekomendasikan, terutama karena kekayaan pengetahuan Pramoedya ihwal penaklukkan dan penguasaan laut yang sejak mula ditekankan sebagai kunci kedigdayaan semua kerajaan. Laut dan kelautan dipermuliakan dan diunggulkan sebagai potensi pendapatan, simbol kejayaan, serta pemersatu pulau-pulau yang terpisah. Dengan demikian, Jalesveva Jayamahe tak sekadar pemanis bibir.
Keadaan ini nyata bertentangan dengan situasi hari ini, ketika dominasi Angkatan Darat di Indonesia mengungguli matra-matra angkatan lainnya. Secara tidak langsung, dalam dominasi itu terkandung implikasi yang menjadikan laut sebagai pemisah daratan. Pengetahuan mengenai kelautan sangat kecil diberikan dalam kurikulum. Akibatnya, laut Indonesia pun menjadi ladang bancakan perusahaan-perusahaan minyak dan tambang pasir yang mengakibatkan nelayan kecil semakin mudah dikriminalisasi.
Pengetahuan tentang laut menjadi semakin mendesak, selagi pengenalan lebih dalam dan menyeluruh tentang seluk-beluk Indonesia tidak lain merupakan satu-satunya jalan paling cepat saat ini, agar “Generasi Indonesia Emas” tidak merasa terasing dari tanahnya sendiri.
Semoga!***
Chris Wibisana, pelajar dan peneliti sejarah independen
Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda melalui tangan Balai Poestaka berusaha membendung arus penerbitan buku dan artikel karya para aktivis anti-kapitalis dan anti-kolonialis. Barisan literatur yang berperan besar menyuburkan gerakan politik kelas di Indonesia ini dicap Belanda sebagai “batjaan liar”. Kami mengklaim kembali istilah tersebut untuk sebuah rubrik berisi rekomendasi bacaan yang disusun secara tematik untuk merespons berbagai macam isu. Haris Prabowo adalah editor tamu Batjaan Liar. Sehari-hari ia bekerja sebagai jurnalis Tirto.id.