Ilustrasi: Deadnauval
UNDANG-UNDANG Cipta Kerja, sebuah produk legislasi yang dibentuk menggunakan metode omnibus dan disahkan baru-baru ini, telah menjadi wajah teranyar rezim hukum yang mengabdi kepada akumulasi kapital dan menindas rakyat kecil. Ia dibentuk oleh kaum oligark tanpa transparansi, tanpa partisipasi publik, menerabas aturan yang berlaku, dan menganut paradigma neoliberal yang hanya menguntungkan orang-orang kaya .
Beragam cara penolakan, termasuk turun ke jalan, telah direspons dengan represi dari aparatus negara. Tak ada upaya pemerintah untuk mendengar keluhan rakyat dengan lebih jernih. Omnibus Law semakin menegaskan bagaimana hukum hanya menjadi instrumen kelas kapitalis dan borjuasi nasional di Indonesia.
Penolakan besar-besaran atas sebuah produk legislasi yang bermasalah, cacat, dan hanya merugikan rakyat, bukan terjadi kali ini saja. Kita tahu bagaimana tahun lalu penolakan besar oleh mahasiswa dan gerakan sosial secara masif dikumandangkan lewat gerakan #ReformasiDikorupsi. Mereka juga menuntut pembatalan ragam rancangan undang-undang yang bermasalah.
Jika sudah seperti itu, satu pertanyaan yang seharusnya mulai kita ajukan bersama: apa yang salah dari ruang hukum di Indonesia?
Sebelum berbicara mengenai sistem dan produk hukum yang sudah kadung terstruktur begitu kuatnya menindas rakyat kecil, mungkin kita bisa mulai dari pendidikan hukum itu sendiri. Sudah berpuluh-puluh tahun pendidikan hukum di Indonesia hanya menghasilkan lulusan yang buta atas ketidakadilan, abai terhadap pelanggaran HAM, hingga mereka yang hanya mengejar keuntungan dan kekuasaan.
Pendiri Pusat Studi Hak Asasi Manusia Univesitas Islam Indonesia Pusham UII) Eko Prasetyo menyebut pendidikan hukum di Indonesia hanya menghasilkan lulusan “kaum fundamentalis undang-undang, yang sama berbahayanya dengan kaum fasis: mereka merasa paling benar dan paling mengerti hukum.”
Ia menilai pendidikan hukum di Indonesia “sangat brengsek”, karena hanya mereproduksi algojo-algojo—entah itu hakim, jaksa, pengacara, maupun politikus pembuat regulasi—yang doyan menggunakan hukum untuk menindas orang yang lemah dan terpinggirkan.
Semua bermula dari pendidikan hukum di Indonesia yang tidak mengajarkan cara berpikir kritis dan keberpihakan kepada orang-orang yang lemah. Pendidikan hukum di Indonesia hanya mengajarkan mahasiswanya untuk menjadi praktisi-praktisi hukum yang hanya membaca, menghafal, dan mengeksekusi ragam instrumen hukum, tanpa menyentuh nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
Sejujurnya, selama tujuh tahun kuliah di fakultas hukum, tak banyak buku dan modul hukum yang saya baca. Saya lebih senang membaca kajian-kajian di luar hukum, seperti politik, sejarah, sastra, hingga teori kritis, untuk membaca hukum dari sisi yang lain. Saya selalu mengambil jarak dari praktik “penyembahan” undang-undang, pasal-pasal, hingga ragam regulasi—seolah-olah semua itu suci tanpa ada noda—tanpa melakukan interpretasi kritis sebelumnya. Padahal, kita semua tahu, ragam aturan itu dibentuk oleh manusia dengan segala kepentingan politik dan ideologinya.
Berikut ini saya coba merekomendasikan sebelas buku yang setidaknya bisa menjadi bacaan bagi para mahasiswa hukum sebelum lulus. Daftar buku ini, bisa jadi, sangat jarang masuk ke dalam kurikulum pendidikan hukum di fakultas-fakultas hukum di Indonesia—kecuali jika ada inisiatif pribadi dari sang dosen. Menurut saya, daftar buku ini bisa menjadi bacaan alternatif mahasiswa hukum untuk bisa memperkaya diskursus ilmu hukum di Indonesia, melihat hukum dari sisi kritis, dan akhirnya memiliki empati ke orang-orang kecil.
Saya membagi daftar bacaan ini menjadi tiga kategori: sejarah, pemikiran, dan litigasi. Ketiga kategori ini bisa dibaca secara berurutan, namun bisa juga secara acak. Pemilihan buku-buku ini juga dilakukan mengandalkan batas maksimal referensi saya dan upaya mencari relevansi dengan masalah-masalah hari ini.
Sejarah
1. Bukan 350 Tahun Dijajah (2012)
“Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun!”
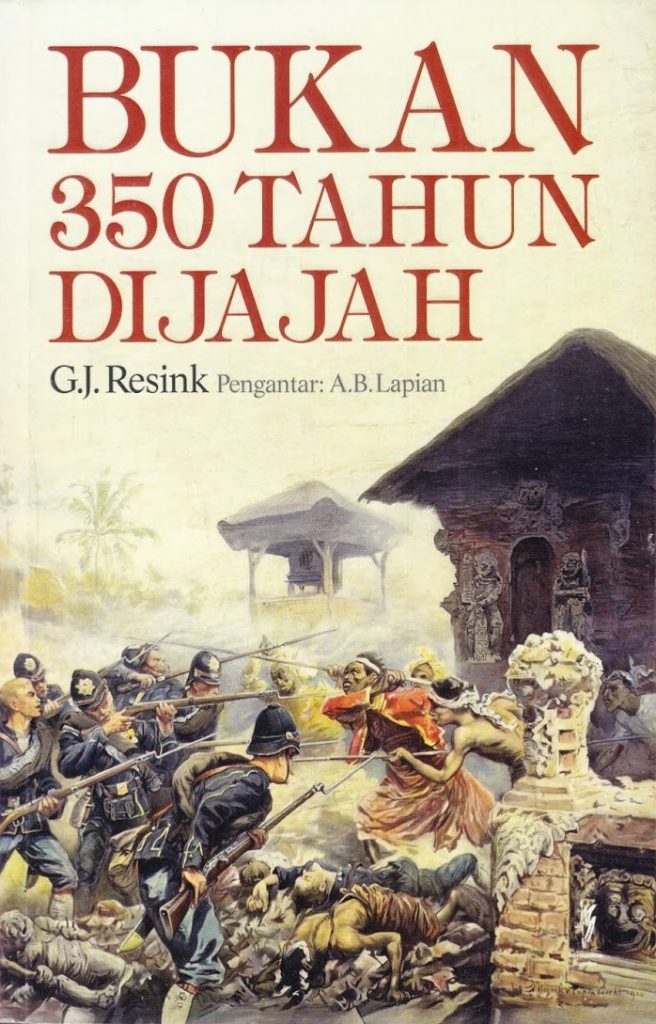
Kalimat itu kerap kita dengar saat belajar Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), salah satu mata pelajaran Sekolah Dasar (SD) di dalam kurikulum pendidikan Orde Baru. Kendati kalimat itu pernah digaungkan oleh Soekarno sebagai bentuk penyemangat saat masa kemerdekaan, namun Orde Baru akhirnya mengkristalisasi hal tersebut lewat kurikulum selama puluhan tahun. Akhirnya, ia menjadi sakral: Indonesia pernah dijajah Belanda selama 350 tahun.
Namun benarkah Indonesia dijajah selama itu?
Narasi itu yang coba dibongkar oleh Gertrudes Johannes (G.J.) Resink—ahli hukum internasional dan sastrawan berdarah Belanda-Indonesia—lewat bukunya ini. Kumpulan esai sejarah karya G.J. Resink ini mencoba membongkar mitos penjajahan Belanda terhadap Indonesia selama 350 tahun, dengan menggunakan pendekatan studi hukum internasional dalam membedah ragam dokumen hukum serta perjanjian kerajaan-kerajaan di Nusantara.
Kesimpulan dia: Indonesia tidak benar-benar dijajah selama tiga setengah abad.
Buku ini menunjukkan kalau narasi Indonesia dijajah selama 350 tahun adalah bentuk generalisasi sejarah yang Jawa-sentris, bahkan cenderung menyesatkan. Tentu kita tidak bisa semata-mata menyimpulkan bahwa terbentuknya Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada 1602 adalah awal mula penjajahan, karena VOC hanyalah sebuah kongsi dagang yang tak pernah merepresentasikan kerajaan Belanda—apalagi lokasinya di Kota Jayakarta, bukan di seluruh Nusantara. Jika mitos tersebut terus dilanggengkan, tentu kita mendiskreditkan perjuangan kerajaan-kerajaan kecil, seperti Aceh dan Bali, yang terus mempertahankan kedaulatan tanahnya melawan kolonial Belanda hingga awal abad ke-20. Selama beratus-ratus tahun sejak VOC dibentuk, Aceh dan Bali masih belum juga berhasil dikuasai oleh Belanda.
Lewat buku ini, G.J. Resink berusaha mengubah cara pandangan kita tentang masa lalu, khususnya mengenai keadaan hukum internasional, di Kepulauan Nusantara.
2. Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional (2014)
Sejauh ini, baru dalam buku inilah saya menemukan penjelasan runut dan komprehensif tentang bagaimana perubahan sosial-politik hukum Indonesia sejak era kolonial (1840an) hingga akhir Orde Baru (1990an) terjadi—kurang lebih selama satu setengah abad. Buku ini merupakan karya guru besar emeritus Universitas Airlangga, Soetandyo Wignjosoebroto.
Dalam salah satu babnya, Soetandyo menjelaskan dengan rinci pembentukan awal pengadilan-pengadilan yang kita kenal saat ini, tentu dengan paradigma hukum kolonial di atas tanah jajahan: districtsgerecht (pengadilan di wilayah kawedanan untuk orang pribumi), regentschapsgerecht (pengadilan di tingkat kabupaten untuk orang pribumi), hingga landraad (pengadilan untuk orang biasa sehari-hari urusan remeh temeh)—pengadilan yang mendakwa makar Soekarno pada 18 Agustus 1930 di mana ia membacakan pleidoi terkenalnya, Indonesia Menggugat.
Di dalam buku ini juga kita bisa menemukan akar konsep “negara hukum” (rechtsstaat), yang untuk pertama kalinya coba diterapkan oleh Hindia Belanda lewat Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1848 dan Regeringsreglement tahun 1854, setelah melepaskan konsep “negara kekuasaan” (machtsstaat)—kendati masih secara yuridis-normatif, karena dalam praktiknya tidak demikian. Di kemudian hari konsep ini akhirnya menjadi dasar negara Indonesia pasca-kemerdekaan.
Soetandyo menggunakan sumber-sumber primer yang melimpah—kebanyakan dokumen-dokumen berbahasa Belanda—untuk membedah sejarah hukum Indonesia yang sebenarnya tak pernah terlepas dari kekuasaan yang menindas rakyat kecil.
3. Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959 (1995)

Buku setebal 583 halaman ini merupakan hasil disertasi doktoral Adnan Buyung Nasution di Utrecht, Belanda, yang membahas perjalanan sebuah dewan perwakilan bernama Badan Konstituante. Badan ini bertugas untuk membentuk undang-undang dasar baru menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. Badan ini berumur pendek: bekerja hanya kurang dari tiga tahun, sebelum dibubarkan Soekarno lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan akhirnya tak menghasilkan apa-apa.
Lewat disertasinya ini, Adnan Buyung berhasil menghadirkan gambaran tentang perdebatan-perdebatan yang berkualitas dari para intelektual di masa itu guna membentuk sebuah konstitusi baru.
Lewat buku ini pun, kita juga bisa membaca bagaimana kelompok Islamis, untuk kedua kalinya, berusaha mengusulkan konsep “Negara Islam” sebagai dasar negara yang sebelumnya gagal dicoba lewat Piagam Jakarta pada 1945—sebuah konsep yang belakangan kerap dimunculkan kembali dan menguatkan sentimen intoleransi di Indonesia.
4. Teror Orde Baru: Penyelewengan Hukum & Propaganda 1965-1981 (2013)
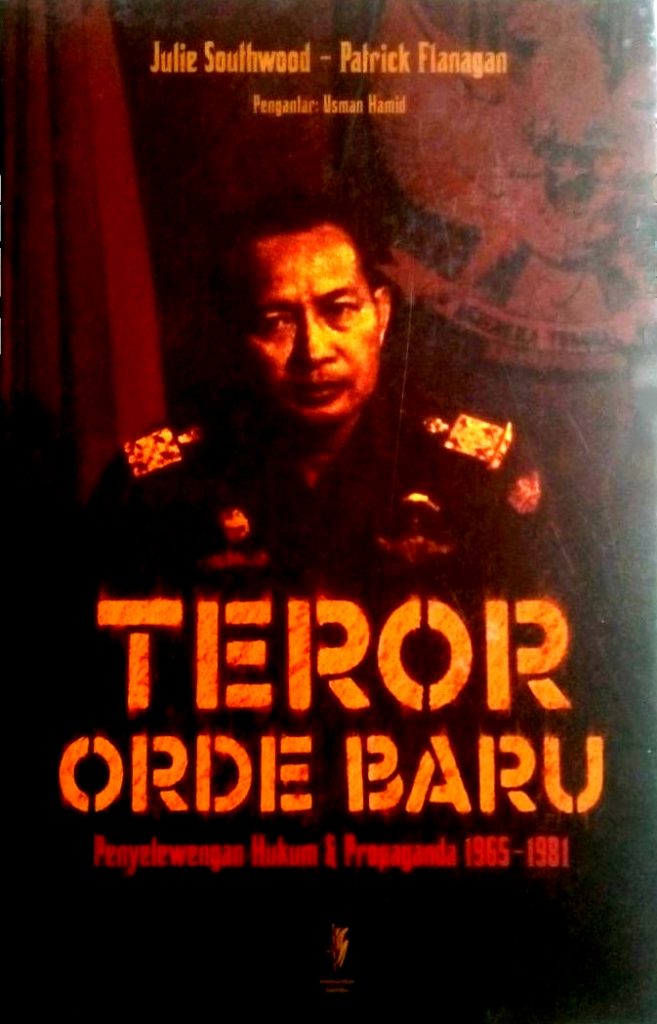
Kabarnya, buku yang terbit pada tahun 1983 ini sempat dilarang beredar saat Presiden Soeharto berkuasa, karena dianggap berhasil membongkar modus operandi Orde Baru dalam membangun negara hukum ala kolonial, yang efeknya bahkan bisa kita rasakan sampai sekarang. Dalam buku tersebut, Julie Southwood dan Patrick Flanagan menganalisis bagaimana 16 tahun pertama rezim Soeharto dibangun di atas darah, penindasan, dan tentu saja, ketidakadilan.
Salah satu tema yang paling disorot dalam buku ini adalah bagaimana rezim Orde Baru memiliki sebuah lembaga superpower bernama Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), yang bekerja sebagai pelaku teror, agen propaganda, hingga penegakan hukum ke ranah privat sekalipun. Lewat persetujuan Soeharto, lembaga itu boleh membuat aturan, tidak bertanggungjawab kepada parlemen, dan mudah mengangkangi produk hukum lainnya.
Lembaga ini bisa mengawasi warga hingga ke ruang lingkup terkecil. Dengan demikian, ada ketakutan dan paranoia yang dilanggengkan. Kopkamtib menjadi salah satu instrumen Soeharto untuk membentuk cara pandang masyarakat bahwa: negara tak pernah salah. Sebaliknya, warga yang akan merasa selalu salah. Tak heran jika salah satu pengacara HAM yang terkenal saat itu, Yap Thiam Hien, pernah berkelakar: “Bahkan bernafas pun bisa salah.”
Contoh lainnya adalah ketika rezim Soeharto memaksimalkan Penpres (yang kemudian menjadi Undang-Undang) Antisubversi 1963 yang sangat represif kepada rakyatnya sendiri. Banyak pasal karet yang ada di dalam UU itu rentan mengkriminalisasi warga. Dengan aturan ini, negara memiliki kewenangan untuk mendakwa siapa pun yang melakukan tindakan yang tidak disukai rezim. Efeknya, mayoritas masyarakat kehilangan daya kritis dan tak berani beropini beda. Regulasi yang sangat berbahaya!
Pemikiran
5. Pandangan Negara Integralistik (1994)
Buku ini adalah karya dari Marsillam Simanjuntak, aktivis gerakan mahasiswa tahun 1960-an, pegiat Forum Demokrasi (Fordem) di masa Orde Baru, yang di kemudian hari menjadi Jaksa Agung di era Presiden Gus Dur. Dalam buku ini, Marsillam mencoba menganalisis Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang sedikit banyak mengacu pada pidato perumusan hukum dasar (konstitusi) yang disampaikan oleh Soepomo dalam Sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945.
Dalam sidang itu, Soepomo mengusulkan suatu konsep negara hukum bernama “negara integralistik” (NI). Intinya: suatu paham di mana “negara” dan “warga” menjadi manunggal. Posisi individu, rakyat, atau warga—di dalam konsep negara itu—melebur atau menyatu ke dalam negara. Tak ada namanya kepentingan individu, yang ada hanyalah kepentingan negara. Soepomo mengambil saripati pemikiran “negara integralistik” dari tiga filsuf asal Barat: Baruch Spinoza, Adam Müller, dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
Konsep negara inilah yang dikritik oleh Marsillam di dalam bukunya. Bagi Marsillam, “negara integralistik” cenderung membawa negara ke arah otoriter dan tidak menghargai martabat warga negaranya. Karena dalam konsep negara itu, tak ada pemisahan antara “negara” dengan “warga/individu”. Dua entitas itu melebur jadi satu, sehingga tidak diperlukan aturan yang melindungi atau menjamin hak-hak kebebasan dasar manusia—khas filsafat politik Hegel yang kerap mengagungkan “negara”. Asumsi dalam pandangan “negara integralistik”: segala aturan yang baik bagi negara, sudah pasti baik bagi warganya.
Marsillam mengambil contoh rezim yang sudah mengoperasikan “negara integralistik”: Orde Baru-nya Soeharto. Ia tak hanya mengkritik Soepomo, tapi juga Spinoza, Müller, hingga Hegel, yang dianggap menjadi dasar pemikiran rezim otoriter Orde Baru. Buku ini akhirnya menjadi acuan banyak aktivis untuk menganalisis ideologi khas Orde Baru yang meleburkan “negara” dan “warga” sehingga menjadi “sebuah keluarga”. Ideologi itu bernama “bapakisme”: Soeharto sebagai “bapak” dan warga sebagai “anak”.
Buku ini merupakan hasil dari skripsi kedua Marsillam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1989. Skripsi pertamanya dirampungkan di Fakultas Kedokteran di kampus yang sama, pada 1971.
6. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (2009)
Buku berikutnya adalah karya Satjipto Rahardjo, guru besar emeritus Universitas Diponegoro. Ia adalah akademisi yang terkenal dengan teorinya yang kerap digunakan oleh gerakan sosial: hukum progresif. Secara umum, hukum progresif adalah sebuah cara pandang hukum yang bertolak belakang dengan paradigma konvensional dan positivistik.
Diskursus studi ilmu hukum di Indonesia, beserta segala praktik beracaranya, sudah puluhan tahun mandek, karena hanya mengandalkan pasal, regulasi, hingga undang-undang. Semua itu dianggap suci, saklek, tak bisa dikritik, dan harus selalu ditaati oleh rakyat yang awam hukum ketika tersandung kasus. Padahal kita sama-sama tahu, produk-produk hukum tersebut tidak dibentuk dalam ruang hampa. Semuanya dirancang oleh manusia—lebih tepatnya penguasa dan politikus—dengan segala selubung kepentingan ideologi dan politiknya.
Kata Satjipto, ilmu hukum tak boleh melepaskan diri dari studi ilmu pengetahuan sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, sejarah, hingga filsafat. Tak heran jika dalam bukunya ini, Satjipto banyak mengupas perkembangan dan revolusi ilmu pengetahuan dari Rene Descartes, Francis Bacon, hingga “the turning point”-nya Fritjof Capra.
Pemikiran hukum progresif, menurut Satjipto, membuat hukum harus mengikuti perkembangan zaman dan keadaan masyarakatnya. Setiap ada pertentangan antara hukum dan manusia, produk hukumlah yang seharusnya ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa agar masuk ke dalam skema hukum. Bagi hukum progresif: hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya.
Hukum progresif tidak bergerak mengandalkan kesakralan dogma legalistik dan positivistik—pasal, regulasi, dan undang-undang—tapi lebih mengedepankan keadaan sosiologis masyarakatnya. Di ranah peradilan, contohnya, seorang hakim harusnya bisa membedah secara struktural masalah yang sedang disidangkan sebelum akhirnya memutuskan sebuah perkara, ketimbang hanya menggunakan produk hukum yang rentan menindas rakyat kecil. Apa yang membuat seorang nenek bisa mencuri kayu di lahan milik negara sehingga harus dikriminalisasi? Keadaan sosiologis seperti apa yang mendesak masyarakat adat akhirnya berani menyita alat tebang milik korporasi multinasional yang akan menggunduli hutan tempat mereka tinggal? Hakim harusnya bisa lebih banyak menyelami seluk-beluk permasalahan dalam kasus-kasus seperti ini, sebelum memutuskan sebuah perkara.
Kata Satjipto, hukum progresif memang dimaksudkan untuk mengoreksi sistem hukum modern yang sarat birokrasi dan prosedur, yang akhirnya rentan meminggirkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Apalagi, keadaan hukum modern tersebut tak bisa dilepaskan dari keadaan negara modernnya yang dibangun oleh industrialisasi, kapitalisme, dan oligarki.
Satjipto tak menampik jika teori hukum progresifnya kerap disandingkan dengan Critical Legal Studies (CLS), sebuah mazhab hukum yang muncul di Amerika Serikat pada tahun 1977 karena ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan hukum di negeri itu. Pada awal perkembangannya, CLS banyak dipengaruhi oleh gerakan kiri dan sangat membuka kemungkinan untuk membedah hukum dengan ragam pisau pemikiran kritis—mulai dari Friedrich Engels, Antonio Gramsci, Michel Foucault, hingga Jacques Derrida.
Jika Anda tak ingin menjadi mahasiswa hukum yang dekaden, bacalah buku ini!
7. Hukum & Masyarakat: Sejarah, Politik, dan Perkembangannya (2018)

Mungkin buku karya Bakrul Amal ini sekilas akan terlihat biasa saja dan tidak segarang buku lainnya yang ada di dalam daftar ini. Jika dibaca hanya dari judulnya, kita akan mengira buku ini akan sama seperti buku-buku pengantar lainnya untuk mahasiswa semester satu di fakultas hukum. Dan memang demikian, buku ini dimaksudkan sebagai pengantar untuk memahami apa itu “hukum”.
Yang membuat buku ini berbeda adalah niat Bakhrul untuk mencari definisi alternatif dari berbagai elemen ilmu hukum, dengan menggunakan referensi yang berani keluar dari jalur mainstream. Ia seperti mendobrak pendekatan lawas dalam ilmu hukum dengan menggunakan kajian-kajian kritis.
Di dalam buku ini, tentu kita akan menemukan ragam penjelasan mengenai: apa itu hukum, dari mana saja sumber hukum, macam-macam ideologi hukum, hingga apa itu negara. Namun yang menarik dari buku ini adalah bagaimana Bakhrul mau mengajak pembaca untuk membaca definisi-definisi alternatif yang lebih baru dan segar, daripada terlalu lama berkutat ke teks-teks lawas macam Pengantar Ilmu Hukum-nya Sudarsono (1991) atau bahkan Ilmu Negara-nya Abu Daud Busroh (2001).
Salah satu contohnya adalah bagaimana Bakhrul tak sungkan untuk menceritakan bagaimana pengertian dan kemunculan awal “hukum” menurut Slavoj Žižek—filsuf Marxis asal Slovenia. Begitu juga saat ia membahas konsep “negara” dan “kewarganegaraan” yang lebih baru dan progresif, seperti “kewarganegaraan global” ala gerakan anarkis Zapatista di Chiapas, “kewarganegaraan kosmopolitan”-nya David Held, hingga konsep orang-orang yang kehilangan kewarganegaraan ala homo sacer-nya Giorgio Agamben, ketimbang berpatokan pada definisi-definisi lawas yang cenderung nasionalistik dan dogmatik.
Di dalam salah satu babnya, Bakhrul juga sedikit membahas perkembangan hukum kiwari di Indonesia dengan beberapa tema yang masih hangat diperbincangkan, seperti lingkungan, internet, kesetaraan gender, hingga pemilu, dengan perspektif yang lebih progresif. Setidaknya buku ini bisa memberikan pandangan baru dan wacana alternatif bagi para mahasiswa untuk memahami apa itu hukum, ketimbang terjebak dengan definisi-definisi lawas yang membosankan.
Litigasi
8. Verboden Voor Honden En Inlanders dan Lahirlah LBH (2012)

Buku ini membahas perjalanan panjang Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang bisa dibilang merupakan salah satu organisasi paling progresif yang pernah dimiliki Indonesia. Ini adalah organisasi bantuan hukum pro bono yang memiliki rekam jejak panjang membantu rakyat miskin, buta hukum, korban kekerasan negara, mereka yang distigma komunis, kaum LGBTQ, hingga orang-orang konservatif kanan yang mendapat perlakuan tidak adil dari negara.
Dengan menggunakan pendekatan bantuan hukum struktural (BHS)—yang tak hanya melakukan advokasi proses hukum, tapi juga konsolidasi gerakan sosial dan strategi perlawanan non-litigasi—YLBHI menjadi salah satu motor penggerak perlawanan ketidakadilan di berbagai rezim.
Buku ini banyak bercerita tentang bagaimana Adnan Buyung Nasution membentuk lembaga ini dan membantu korban-korban penggusuran di masa awal rezim Soeharto, kisah Bambang Widjajanto yang membentuk LBH Papua dan menjadi satu-satunya kuasa hukum Thomas Wanggai, hingga strategi bantuan hukum terkini yang harus terus diperbarui karena beradaptasi dengan rezim yang berbeda.
9. Negara ini Tanpa Hukum: Catatan Pengacara Jalanan (2000)
Ini adalah buku kumpulan esai dari Artidjo Alkotsar, mantan Hakim Agung yang terkenal karena putusan-putusannya yang memberatkan koruptor kelas kakap di Indonesia. Lewat buku ini, kita akan paham bagaimana sikapnya yang keras kepala atas kasus-kasus korupsi yang ia tangani—kasus-kasus yang secara struktural membuat Indonesia terpuruk dalam kubangan kemiskinan dan ketidakadilan—tak bisa dilepas dari kisah masa lalunya yang ditempa sebagai pengacara orang-orang kecil korban ketidakadilan selama Orde Baru.
Kasus-kasus pelanggaran HAM dan manipulasi hukum saat Orde Baru berkuasa yang kerap kita dengar selama ini, seperti penembakan misterius (petrus) di Yogyakarta dan penembakan bromocorah di Jawa Timur pada tahun 1980-an, tragedi pembantaian di Santa Cruz pada tahun 1991, pembunuhan wartawan Udin di Yogyakarta pada tahun 1996, kecurangan pemilu 1997 di Madura, hingga tewasnya Moses Gatot—mahasiswa Yogyakarta yang mati saat aksi di Gejayaan jelang reformasi 1998, adalah sederet kasus saat Artidjo berdiri di garis terdepan dalam memberikan bantuan hukum pro bono kepada para korban. Semua kasus itu ia hadapi saat bergiat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.
Lewat catatan-catatan ini, kita akan menemukan gambaran ideal sosok pengacara dengan spirit altruisme: berani membela orang-orang yang tertindas oleh sistem hukum yang bobrok dan manipulatif, yang puluhan tahun dibangun oleh rezim Soeharto. Ia adalah gambaran paling tepat dari apa yang disebut oleh Michel Foucault sebagai “parrhesia”—berani berkata benar, kendati berada di bawah ancaman kekuasaan. Kampus-kampus fakultas hukum di Indonesia harus banyak melahirkan calon pengacara seperti dia!
10. Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (2008)
Buku ini merupakan hasil penelitian Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia terhadap 40 kasus perempuan saat berhadapan dengan aparat penegak hukum di Indonesia. Penelitian ini membedah dokumen-dokumen risalah dan putusan pengadilan 40 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rentang waktu 1955 sampai 2003. Artinya, penelitian ini mencoba membaca bagaimana pergulatan perempuan melawan rezim hukum di tiga era berbeda: Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Buku ini ditulis oleh Antonius Cahyadi dan Sulistyowati Irianto—yang dikenal sebagai Guru Besar Antropologi Hukum yang feminis.
Yang menarik dari buku ini adalah kedua penulis berani menggunakan pendekatan socio-legal studies ketimbang positivisme hukum yang sudah kadung mengakar di Indonesia. Lewat socio-legal studies, sangat memungkinkan untuk menganalisis sebuah kasus peradilan—khususnya ketika subjeknya adalah perempuan—dengan pendekatan sosiologi, analisis wacana, studi budaya, feminist legal theory, hingga posmodernisme.
Sulis dan Antonius mencoba membaca setiap putusan pengadilan tersebut dengan pendekatan-pendekatan di atas: apakah para perempuan tersebut sudah diberikan ruang yang aman untuk bersuara saat bersidang? Bagaimana komposisi para hakim yang menyidangkan kasus kekerasan terhadap perempuan itu? Apakah para hakim sudah berikhtiar menggali pengalaman dan sisi kemanusiaan perempuan untuk menimbang dan memutuskan suatu perkara, ketimbang hanya mengandalkan paradigma “benar-salah” sesuai peraturan yang ada?
Posisi perempuan di dalam masyarakat yang sangat patriarkal membuat perempuan rentan menjadi korban ganda dalam sebuah perkara. Semisal, ketika ada kasus perceraian yang dibalut dengan kekerasan sang suami terhadap sang istri. Perceraian dan kekerasan adalah dua dunia yang berbeda di ranah hukum: perceraian masuk ke ranah hukum perdata, sedangkan kekerasan masuk ke ranah hukum pidana. Namun, dalam banyak kasus, kejadian seperti ini hanya akan diselesaikan di Pengadilan Agama—yang memang hanya mengurusi ranah perdata. Ragam bentuk kekerasan yang dilakukan sang suami tak akan diadili di pengadilan itu, karena memang bukan kewenangannya—tentu ini akan menguntungkan posisi sang suami.
Contoh seperti itulah yang dimaksud Sulis dan Antonius sebagai “runtuhnya sekat perdata dan pidana”, karena perempuan mudah menjadi korban ganda akibat kaburnya dikotomi perdata dan pidana dalam kasus-kasus kekerasan.
Colongan H̶o̶n̶o̶u̶r̶a̶b̶l̶e̶ ̶M̶e̶n̶t̶i̶o̶n̶
[Daftar dalam rubrik Batjaan Liar dibatasi maksimal 10 buku. Buku berikut terlalu penting untuk dimasukkan ke dalam kategori “Honourable Mention”, jadi saya sebut saja “colongan”]
11. Final Report of The International People’s Tribunal on Crimes Against Humanity in Indonesia 1965 (2017)
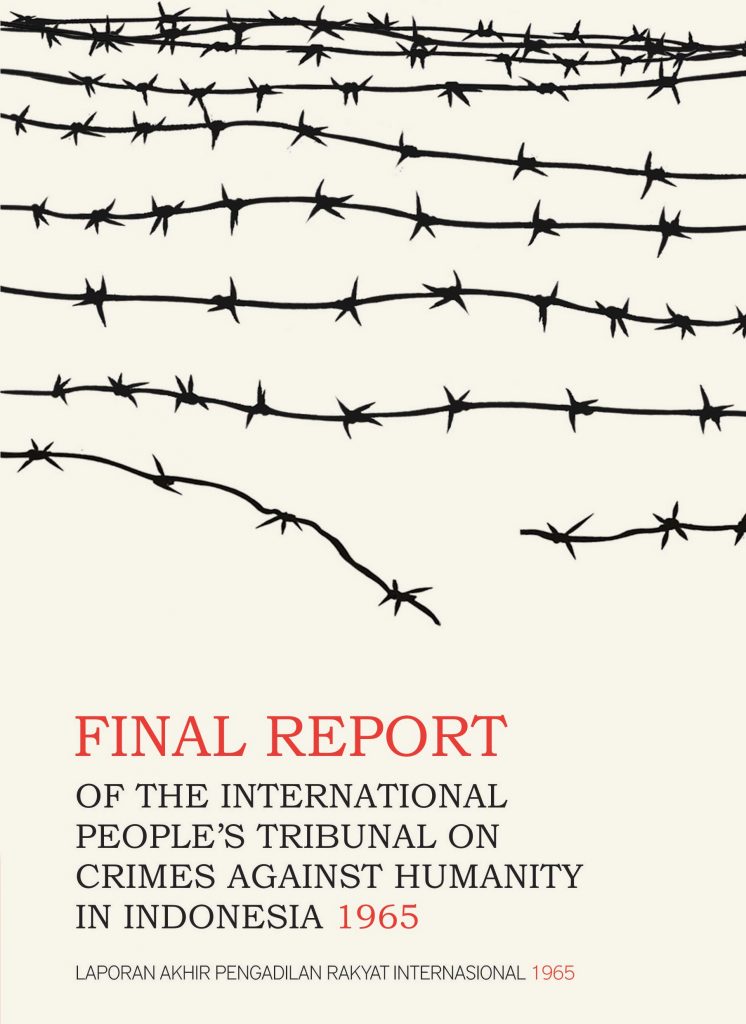
Buku ini merupakan hasil laporan pengadilan rakyat (people’s tribunal) yang digelar di Den Haag, Belanda, pada 2015 silam. Pengadilan ini adalah sebuah langkah inisiatif yang dilakukan masyarakat sipil atas nama Yayasan IPT 65, karena kecewa atas pengabaian negara terhadap para korban dan keluarga yang tidak merasakan keadilan pada kasus pembantaian 1965-1966.
Pengadilan ini dibentuk sebagai upaya kritik dan koreksi terhadap penyelenggara negara yang enggan membentuk pengadilan resmi untuk membela rasa keadilan korban. Hasil pengadilan ini menunjukkan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan massal, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan, hingga genosida, berkaitan dengan peristiwa 1965—hasil yang tak jauh beda dengan investigasi Komnas HAM tiga tahun sebelumnya.
Pengadilan ini merekomendasikan agar negara Indonesia melakukan permintaan maaf dan memberikan kompensasi kepada korban, penyintas, dan keluarga, serta menuntut semua pelaku ke ranah hukum.***
Haris Prabowo baru saja lulus dari jurusan Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Aktif di pers mahasiswa ASPIRASI (2013-2017). Wartawan harian di Tirto.id sejak 2018. Editor tamu IndoPROGRESS untuk rubrik Batjaan Liar.
Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda melalui tangan Balai Poestaka berusaha membendung arus penerbitan buku dan artikel karya para aktivis anti-kapitalis dan anti-kolonialis. Barisan literatur yang berperan besar menyuburkan gerakan politik kelas di Indonesia ini dicap Belanda sebagai “batjaan liar”. Kami mengklaim kembali istilah tersebut untuk sebuah rubrik berisi rekomendasi bacaan yang disusun secara tematik untuk merespons berbagai macam isu. Haris Prabowo adalah editor tamu Batjaan Liar. Sehari-hari ia bekerja sebagai jurnalis Tirto.id.






