Ilustrasi: Deadnauval
Mitos Pendidikan Netral
JALAN panjang merealisasikan pendidikan yang lebih kritis nyatanya tak semudah yang kami kira. Terutama ketika narasi dominan tentang pendidikan yang ada dan terus bertumbuh di dalam masyarakat lekat dengan logika kapitalisme, kompetisi, individualisme, dan depolitisasi institusi pendidikan—kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) pada era Orde Baru menjadi salah satu contohnya.
Contoh lainnya, kami teringat bagaimana tahun lalu ketika kami menulis sedikit mengenai hubungan antara pendidikan dan Revolusi Industri 4.0—yang kerap diagungkan oleh para pejabat negara. Salah seorang kawan mengutarakan ketidaksetujuannya. Alasanya, pendidikan adalah suatu hal yang netral. Jika ada yang salah,maka yang salah bukan sistem pendidikannya, namun individu yang menjalaninya. “Tergantung ke individu masing-masing bagaimana mereka menanggapinya dan menggunakan pendidikannya untuk apa,” kata dia.
Sebenarnya, pernyataan dan cara pandang seperti ini cukup sering kami temui. Memang mungkin ada benarnya apabila pembacaan seperti itu berhenti di ranah personal. Namun, yang ingin kami garisbawahi adalah bagaimana pandangan masyarakat tentang pendidikan seringkali begitu naif: pendidikan dan proses pendidikan dilakukan tanpa intervensi pihak lain, tanpa upaya terselubung oleh kekuasaan sosio-politis di sekitarnya, pendidikan pada dasarnya murni ada untuk kesejahteraan para peserta didiknya. Itu saja.
Namun benarkah demikian? Benarkah tidak ada intervensi sosio-politis atau tujuan-tujuan sosio-politis dari pendidikan?
Kami jadi teringat kata-kata Karl Marx dan Friedrich Engels, sekitar 170 tahun yang lalu dalam bukunya Communist Manifesto (1888), tentang peran pendidikan untuk masyarakat.
“Dan pendidikan Anda! Bukankah itu juga sosial, dan ditentukan oleh kondisi sosial di mana Anda mendidik, oleh intervensi langsung atau tidak langsung, dari masyarakat, melalui sekolah? Kaum Komunis belum menciptakan campur tangan masyarakat dalam pendidikan; akan tetapi mereka berusaha untuk mengubah karakter intervensi itu, dan untuk menyelamatkan pendidikan dari pengaruh kelas penguasa.” (hal. 28).
Dalam konteks dan zaman yang berbeda, jika kita renungi lebih dalam lagi, apakah benar pendidikan kita hari ini tidak ingin membentuk kita menjadi warga negara dengan modal pengetahuan tertentu, karakter tertentu, atau berpihak pada kepentingan-kepentingan kelompok tertentu?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kami ingin sedikit berbagi rekomendasi beberapa buku terkait pendidikan. Harus diakui buku-buku telah membuka cara pandang, sekaligus menjadi pintu masuk kami, untuk mendalami dan memeriksa lebih jauh sistem pendidikan kita yang problematis. Harapannya, daftar bacaan ini dapat dijadikan pintu masuk juga untuk teman-teman pendidik, peserta didik, aktivis, orang tua, anak muda, atau siapa pun yang ingin mulai untuk memahami lebih dalam lagi hubungan pendidikan dengan kehidupan sosial kita.
Sebagai catatan, kami sadar bahwa daftar bacaan ini tak cukup inklusif dan representatif terhadap pemikir pendidikan dari berbagai latar belakang. Tak ada niat dari kami untuk menasbihkan penulis atau karya tulis di dalam daftar ini sebagai kanon. Bagi kami, buku-buku ini menjadi gerbang utama kami mendalami isu pendidikan secara lebih kritis dan reflektif. Daftar ini akan terus bertambah, dan tentunya kami sangat terbuka pada masukan dari teman-teman sekalian.
Untuk mempermudah, kami akan membagi daftar bacaan referensi pendidikan ini menjadi tiga bagi yang kami rasa sangat saling terikat satu sama lain. Pertama, memahami tujuan pendidikan sebagai alat reproduksi sosial. Kedua, memahami tujuan pendidikan sebagai alat kendali sosial (education for social control). Dan ketiga, membahas pendidikan sebagai kesempatan memerdekakan masyarakat (education for liberation), sebuah upaya agar kami tidak dituduh terus menerus sebagai manusia-manusia yang tidak memberikan alternatif dan hanya berkubang di dalam pesimisme.
Pendidikan sebagai Alat Reproduksi Sosial
Tujuan pendidikan sebagai alat reproduksi sosial dapat diartikan bagaimana pendidikan digunakan sebagai alat untuk mempertahankan, serta menciptakan kembali, berbagai hierarki sosial serta relasi-relasi kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh yang ada di masyarakat saat ini. Kita bisa ambil contoh bagaimana pendidikan mempertahankan—atau bahkan menciptakan kembali—ketimpangan-ketimpangan sosial yang diakibatkan dari struktur masyarakat yang hierarkis. Beberapa contohnya seperti hierarki gender, hierarki ras “pribumi-non-pribumi”, hierarki kelas sosial orang kaya dengan orang miskin, bahkan hierarki orang kota-orang desa.
Sebagai alat reproduksi sosial, pendidikan justru berkontribusi untuk membuat yang miskin tetap miskin, perempuan dilihat sebagai makhluk yang berada di bawah laki-laki, masyarakat adat sebagai masyarakat yang ‘tak berpendidikan’ dan ‘tak modern’, dan sebagainya.
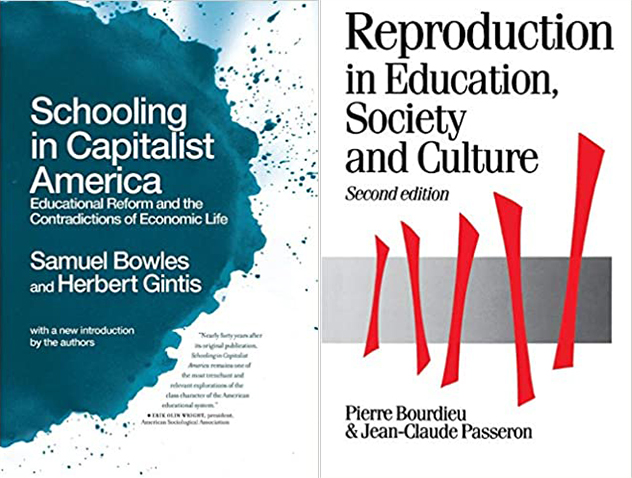
1. Schooling in Capitalist America (1976)
Untuk menjawab permasalahan di atas, buku pertama yang kami rekomendasikan adalah Schooling in Capitalist America karya Samuel Bowles dan Herbert Gintis. Kedua penulis itu menekankan bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk mereproduksi kelas sosial. Mereka menemukan apa yang mereka sebut sebagai “prinsip korespondensi” (correspondence principle). Mereka menjelaskan bagaimana pengaturan internal sebuah institusi pendidikan disesuaikan dengan pengaturan aspek ketenagakerjaan, terutama dalam perihal struktur institusinya, norma, maupun nilai-nilai yang dirangkul institusi pendidikan tersebut. Bowles dan Gintis menambahkan bahwa hal tersebut akan disesuaikan dengan latar belakang ekonomi para peserta didik di dalam institusi pendidikannya.
Misalnya, sekolah kelas menengah-bawah akan mencerminkan struktur sebuah tempat kerja yang sangat hierarkis seperti pabrik. Dengan seorang kepala sekolah sebagai direktur pelaksana, dan para siswa ada di posisi bawah dalam hierarki tersebut. Mereka kerap diminta untuk tunduk terhadap apa yang diminta sekolah, menyiratkan bahwa kepatuhan merupakan kemampuan (skill)yang penting untuk dimiliki. Begitu pula dengan pengetahuan yang diajarkan, yang sangat fokus ke kemampuan-kemampuan teknis seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Yang terpenting adalah agar peserta didik lekas mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari sekolah.
Keadaan di atas sangat kontras dengan mereka yang bersekolah di sekolah-sekolah elite, pada umumnya datang dari latar belakang yang mampu serta memiliki pengaruh dan kuasa. Dalam rangka mempertahankan kemampuan ekonomi, pengaruh dan kuasa yang dimiliki keluarga dari mana siswa/siswi tersebut berasal, sekolah elite harus turut mereproduksi kemampuan, pengetahuan, norma, serta nilai-nilai yang dibutuhkan.
Maka sangat wajar ketika sekolah elite—entah itu negeri atau swasta—mendorong pelajar yang otonom, mandiri, dan memiliki keterampilan manajerial yang baik ketimbang fokus ke pendidikan yang sifatnya hal-hal teknis. Tujuannya tak lain agar para peserta didik kelak mendapatkan pekerjaan yang mampu mempertahankan atau bahkan memperbesar kemampuan ekonomi, pengaruh, dan kuasa yang dimilikinya.
2. Reproduction in Education, Society and Culture (1990)
Kedua ini membahas pengembangan yang lebih dalam lagi dari reproduksi sosial ala Bowles dan Gintis. Dalam Reproduction in Education, Society and Culture,dua sosiolog radikal asal Prancis, Pierre Bourdieu dan Jean-Claude Passeron, menemukan bahwa dalam mereproduksi sebuah struktur sosial yang timpang, hubungan sekolah dan keluarga sangatlah erat. Bourdieu menjelaskan bagaimana sekolah dan modal sosial, serta budaya dan ekonomi keluarga, berkontribusi untuk memperkuat dan mereproduksi ketimpangan sosial serta privilese suatu kelas.
Bourdieu mendefinisikan “modal budaya” sebagai pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang diperoleh orang melalui pendidikan formal/informal; “modal sosial” sebagai jumlah hubungan dan hubungan sosial yang diperoleh individu atau kelompok; lalu “modal ekonomi” sebagai kekayaan, serta aset yang dimilikinya. Ketika menelusuri sekolah-sekolah di Perancis, Bourdieu menemukan bahwa nilai dan pengetahuan yang diajarkan di sekolah mencerminkan budaya yang dominan di mana sekolah tersebut berada.
Lalu apa masalahnya?
Bagi mereka yang tidak datang dari budaya dominan—tidak memiliki modal budaya, sosial, atau ekonomi yang serupa atau setara—akan sangat sulit untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh sekolah tersebut, atau bahkan untuk sebatas membangun hubungan sosial. Mereka yang sudah tertinggal akan tetap semakin tertinggal. Ketimbang mengurangi ketimpangan dalam masyarakat, sekolah malah menciptakan ulang ketimpangan yang ada, atau bahkan memperparah keadaan itu.
Contoh yang paling nyata di masa pandemi ini adalah ketika dalam satu sekolah ada siswa yang memiliki akses ke sarana telekomunikasi—berkat privilese keluarganya—dan ada siswa yang tidak memilikinya, atau terbatas aksesnya. Mereka yang memiliki akses akan lebih mudah mengikuti proses belajar dan tentu akan lebih maju dalam pembelajarannya.
Lalu, bagaimana caranya agar para siswa menyetujui proses pendidikan yang mereproduksi ketimpangan sosial ini? Bagaimana agar para siswa menginternalisasi dan melihat semua hal ini sebagai hal yang lumrah dan “biasa-biasa saja”? Siswa diajarkan bahwa ketimpangan kelas sosial terjadi bukan karena struktur sosial yang menindas, tapi karena orang tersebut “mungkin kurang kerja keras saja”.
Untuk memahami hal ini kami masuk ke tema berikutnya, yaitu, bagaimana memahami pendidikan sebagai alat kendali sosial.
Pendidikan sebagai Alat Kendali Sosial
Pengendalian sosial, singkatnya, dapat diartikan sebagai strategi dan proses yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku individu dan kelompok yang mengarah pada kepatuhan. Hal ini bisa dilakukan melalui cara yang terbuka dan mudah dilihat, seperti peraturan, produk hukum, dan pedoman—contoh: bel masuk sekolah atau kelas, aturan akan seragam sekolah, hingga potongan rambut. Atau bisa juga melalui kontrol tersembunyi, seperti bagaimana kita harus berperilaku atau bertindak sebagaimana yang diterima secara umum, meski tidak ada aturan resmi yang tertulis. Contoh: pemahaman akan kesejahteraan, kesuksesan, dan kerja keras, peran dan perilaku yang terkait dengan gender dan lain-lain.
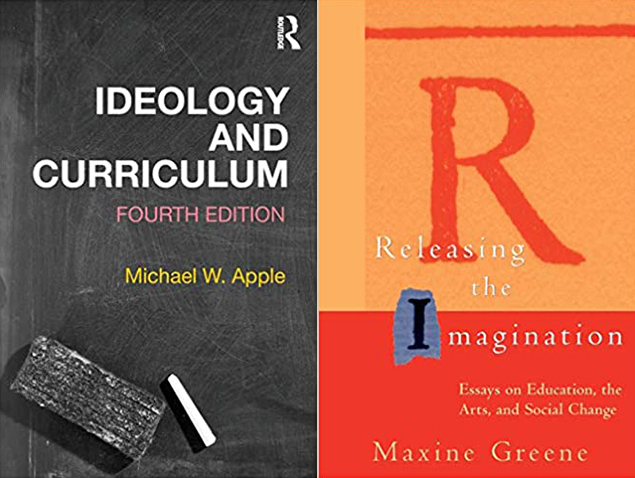
3. Ideology and Curriculum (1979)
4. Releasing the Imagination: Essays on Education, the Arts, and Social Change (1995)
Salah satu cara pengendalian sosial yang paling efektif adalah melalui kebijakan pendidikan yang dinamakan kurikulum. Melalui buku-bukunya karya Michael W. Apple dan Maxine Greene, mereka membahas bagaimana sekolah tidak hanya secara langsung mengendalikan orang seperti melalui peraturan pakaian, tapi juga mengendalikan orang melalui pengendalian pengetahuan.
Melalui penelusuran mereka lewat kurikulum resmi negara, Apple dan Greene berargumen bahwa sekolah melestarikan dan mendistribusikan apa yang dianggap sebagai “pengetahuan yang sah” (legitimate knowledge)—sebuah pengetahuan yang kita semua harus miliki versi negara. Kurikulum, menurut Apple dan Greene, adalah sebuah produk kontestasi kekuasaan: siapa yang memiliki kuasa paling besar akan menentukan kurikulum dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Itu artinya, ragam pengetahuan lain di luar kurikulum itu dianggap tidak sah.
Melalui kedua buku ini, kita dapat memahami bahwa pengetahuan yang didapat di sekolah dapat menjadi bentuk kontrol sosial dan ekonomi kita. Maka dengan ini, kita dapat mempertanyakan mengapa ada pengetahuan-pengetahuan tertentu yang tidak kita pelajari? Mengapa pengetahuan tersebut penting untuk kita pelajari? Jika pengetahuan dan kekuasaan sangat erat hubungannya, kekuasaan siapa yang kita pertahankan, ketika kita menganggap pengetahuan dalam kurikulum tertentu sebagai pengetahuan yang paling sah dan layak untuk dipelajari?
Lewat buku karya Greene akan peran kritis dari seni, kita dapat mengambil contoh pendidikan sebagai kendali sosial dalam konteks Indonesia. Salah satunya perihal hierarki pengetahuan dalam pendidikan kita. Kita tahu bagaimana jurusan IPA seringkali dilihat sebagai jurusan berada di puncak hierarki, diikuti oleh IPS lalu diakhiri oleh seni/bahasa. Adakah hubungan hierarki ini dengan hubungan pendidikan, dengan tenaga kerja dan dengan ekonomi kita? Adakah hubungan “pengetahuan sah” yang kerap mengesampingkan peran kritis seni dan mengerdilkan ilmu sosial, dengan pengendalian imajinasi kita agar tidak mampu mengimanjinasikan dunia melampaui kapitalisme?
Buku-buku Apple dan Greene layak dibaca lebih dalam jika kita ingin memahami pertanyaan-pertanyaan ini.
Mungkin, kedua tema yang sejauh ini telah kita bahas memberi kesan bahwa tidak ada harapan atau ruang untuk melakukan perlawanan dalam pendidikan. Bagaimana mungkin? Negara begitu mendominasi, begitu menghegemoni pendidikan, dan menggunakannya sebagai alat kendali serta mereproduksi ketimpangan-ketimpangan yang ada.
Namun, setiap dihadapkan dengan situasi seperti ini, kami selalu teringat kata-kata ahli pedagog kritis Peter Mayo: hegemoni tidak pernah sempurna. Akan selalu ada ruang dan kesempatan untuk melawan. Namun apa yang bisa kita lakukan dalam celah-celah dan kesempatan melakukan perlawanan ini? Bagian terakhir yang ingin kami ajukan adalah beberapa buku sebagai referensi pendidikan sebagai alat yang memerdekakan.
Pendidikan yang Memerdekakan
Sejauh pengamatan kami, ruang kelas adalah satu-satunya ruang yang belum dikendalikan dan diawasi secara ‘penuh’ oleh institusi pendidikan atau negara (atau kita hanya tinggal menunggu teknologi surveillance terkini?). Maka celah-celah menantang hegemoni yang kerap digunakan oleh mereka yang mengupayakan perlawanan kontra-hegemoni terletak pada guru/tenaga pendidik dan proses pengajaran dalam kelas—atau apa yang kita kenal sebagai pedagogi.
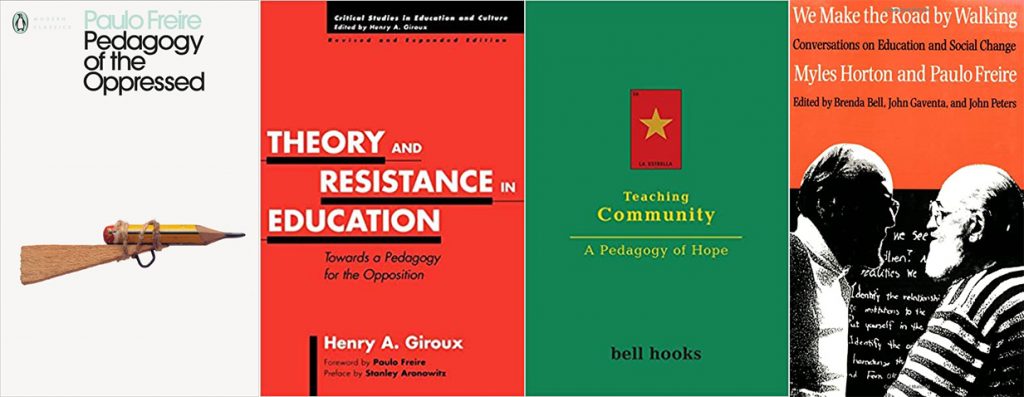
5. Pedagogy of the Oppressed (1992)
Buku kelima adalah karya terbaiknya Paulo Freire, filsuf sekaligus tokoh pendidikan kritis asal Brazil: Pedagogy of the Oppressed. Buku ini pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan makin terkenal dengan judul Pendidikan Kaum Tertindas. Kendati Freire bukan orang pertama yang melihat bagaimana pendidikan tidak hanya dapat menindas, namun juga memerdekakan kita, dialah yang memulai penggunaan istilah “pedagogi kritis” dalam bukunya ini.
Pedagogi kritis adalah suatu bentuk belajar-mengajar yang ditanamkan dengan ide-ide yang diambil dari teori kritis. Teori kritis sendiri, singkatnya, berusaha memeriksa bagaimana kekuasaan dipertahankan dan dikendalikan dalam masyarakat, serta mencari cara agar kelompok yang terpinggirkan mendapatkan akses ke kekuasaan ini. Maka, tujuan pedagogi kritis menurut Freire adalah agar proses belajar mengajar dapat memerdekakan, berjuang menuju keadilan sosial, dan kesetaraan, serta berbasis pada inklusi semua anggota masyarakat—tidak hanya elite atau kelompok yang dominan. Semua itu diharapkan munculnya sebuah ‘kesadaran kritis’ dalam diri peserta didik.
Namun, proses pedagogi kritis tidak hanya dapat dilakukan dalam tataran teoretik atau refleksi semata. Dibutuhkan pula intervensi kritis atau aksi pada dunia kita. Kombinasi aksi dan refleksi ini dia sebut ‘praxis’, refleksi dan aksi atas dunia dengan tujuan untuk mengubahnya.
6. Theory and Resistance in Education (1983)
Yang keenam adalah bukunya Henry Giroux, Theory and Resistance in Education. Selain Freire, nama Giroux cukup dikenal di Indonesia. Di dalam buku ini, ia semacam meneruskan dan mengembangkan pedagogi kritis-nya Freire. Namun, letak perbedaan Giroux dengan Freire adalah konteks sosial di mana ia mengupayakan pedagogi kritisinya: Freire fokus pada konteks pedesaan, sedangkan Giroux pada konteks urban.
Giroux juga lebih menekankan fokus diskursusnya pada agency atau keberdayaan kita sebagai peserta didik atau tenaga pendidik. Ia menolak ide-ide pendidik Marxis sebelumnya, seperti Gintis dan Bowles, yang terlalu menempatkan orang sebagai subjek yang seakan-akan tidak punya pilihan selain pasrah untuk diatur sistem reproduksi dan kendali sosial. Menurut Giroux, pendekatan tersebut terlalu deterministik. Tidak ada ruang untuk harapan. Sebaliknya, Giroux menyerukan teori perlawanan atau agensi atau keberdayaan yang menyeimbangkan aspek deterministik berlebihan dari teori-teori tersebut. Dia berpendapat bahwa manusia turut mengubah dan mereproduksi struktur sosialnya.
7. Teaching Community: Pedagogy of Hope (2003)
Selanjutnya, terinspirasi oleh Freire dan para pedagog kritis, serta para pemikir feminis, bell hooks dalam bukunya, Teaching Community: Pedagogy of Hope, menawarkan rekomendasi bagaimana kita dapat membuat ruang kelas menjadi tempat yang menopang kehidupan dan pikiran berkembang. Ruang kelas harus menjadi tempat kebersamaan yang membebaskan di mana guru dan siswa bekerja sama sebagai mitra dalam solidaritas.
hooks menulis bahwa pendidikan sebagai praktik kebebasan, dan institusi pendidikan sebagai ruang praktik kebebasan tersebut, mengajari kita cara menciptakan komunitas dan solidaritas. Bagi hooks, walaupun pedagogi harus selalu mengupayakan kesadaran kritis, pedagogi kritis juga harus berakar pada harapan. Ia menempatkan harapan sebagai hal yang sentral dalam proses belajar-mengajar karena pendidikan yang mengklaim dirinya memerdekakan, namun tidak memberikan harapan, akan sangat mudah jatuh ke dalam keputusasaan.
Tak akan ada dunia yang baru dan tak akan ada yang merdeka, jika kita hanya berkubang dalam keputusasaan.
8. We Make the Road by Walking: Conversations on Education and Social Change (1990)
Sebagai penutup, jika ada satu buku lama yang kami rasa penting untuk dibaca para pendidik, atau siapapun yang bergerak di bidang pendidikan kritis dan ingin merawat harapan, maka buku nomor delapan ini, We Make the Road by Walking: Conversations on Education and Social Change, adalah buku yang tepat. Buku ini berusaha mencatat mencatat—dalam format dialog—perbincangan yang kritis, dalam, sangat reflektif, dan jujur, antara dua pendidik kritis, yaitu Myles Horton dan Paulo Freire.
Perbincangan di antara keduanya menyadarkan kami betapa pendidikan adalah perjalanan praxis panjang dari satu harapan dan satu kemerdekaan kecil ke harapan dan kemerdekaan kecil berikutnya. Sedikit demi sedikit, jalan itu terbentang karena kita terus berjalan: semakin dekat pada pendidikan yang memerdekakan. Semoga.***
Ben K. C. Laksana, pendidik serta peneliti lepas dan dosen paruh waktu di jurusan Hubungan Internasional, International University Liaison Indonesia
Rara Sekar Larasati, musisi independen, pendidik dan peneliti di bidang antropologi budaya lulusan Victoria University of Wellington, Selandia Baru.
Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda melalui tangan Balai Poestaka berusaha membendung arus penerbitan buku dan artikel karya para aktivis anti-kapitalis dan anti-kolonialis. Barisan literatur yang berperan besar menyuburkan gerakan politik kelas di Indonesia ini dicap Belanda sebagai “batjaan liar”. Kami mengklaim kembali istilah tersebut untuk sebuah rubrik berisi rekomendasi bacaan yang disusun secara tematik untuk merespons berbagai macam isu. Haris Prabowo adalah editor tamu Batjaan Liar. Sehari-hari ia bekerja sebagai jurnalis Tirto.id.
Kepustakaan
Apple, M. W. (1979). Ideology and Curriculum (Third). New York: RoutledgeFalmer.
Bourdieu, P., & Passeron, J. (1990). Reproduction in education, culture and society. London: Sage Publication.
Bowles, S., & Gintis, H. (1976). Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life. Chicago: Haymarket Books.
Freire, P. (1992). Pedagogy of Hope: Reliving Pedagogy of the Oppressed. Bloomsbury Publishing.
Giroux, H. (1983). Theory and Resistance in Education: A Pedagogy for the Opposition. South Hadley: Bergin & Garvey Publishers.
Greene, M. (1995). Releasing the imagination: Essays in education, the Arts and social change. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
hooks, B. (2003). Teaching Community: A Pedagogy of Hope. New York: Routledge.
Horton, M., & Freire, P. (1990). We Make the Road by Walking: Conversations on Education and Social Change (B. Bell, J. Gaventa, & J. M. Peters, eds.). Temple University Press.
Marx, K., & Engels, F. (1888). The Communist Manifesto: Penguin Classics. Penguin Books Limited.






