Anggota perempuan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Sarekat Rakyat (SR). Di tengah-tengah adalah tanda, dengan tulisan tangan, “ “P.K.I” and “S.R” Bersama simbol komunis palu arit. (Foto diambil di Marx-Engels Forum di Berlin).
100 tahun kelahiran Partai Komunis Indonesia
Seratus tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 23 Mei 1920 Perhimpunan Komunis di Hindia (nantinya, Partai Komunis Indonesia/PKI) didirikan di Semarang. Pada masa ini, gerakan komunis berperan penting mengubah karakter perlawanan terhadap penjajahan Belanda di awal abad kedua puluh. Pada masa-masa sebelumnya, pemberontakan terhadap negara kolonial dilakukan secara sporadis dan tradisional dengan senjata. Pada 1920-an, gerakan antikolonial diorganisir dengan alat komunikasi modern dengan mendirikan sekolah-sekolah bagi rakyat kelas bawah, penerbitan koran dan media cetak lainnya, serta mengadakan rapat-rapat umum baik di kota, desa, maupun daerah pertambangan dan perkebunan. Melalui alat komunikasi yang demokratis dan revolusioner, perjuangan antikolonial yang dipimpin oleh gerakan komunis pada masa ini berhasil untuk pertama kalinya memobilisasi gerakan yang populer yang dipimpin oleh rakyat kelas bawah dan mengikutsertakan masyarakat dari berbagai latar belakang baik suku bangsa, agama, maupun gender. Gerakan komunis ini mewarisi tradisi gerakan revolusioner yang demokratis dan global dan menciptakan budaya perlawanan yang dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari rakyat kelas bawah.
PKI berdiri di masa ketika negara kolonial Hindia sedang bergejolak. Dalam dua dekade sebelumnya, perhimpunan-perhimpunan politik dan sosial yang peduli pada kepentingan bumiputra mulai berdiri seperti Budi Utomo dan Indische Partij. Namun kebanyakan perhimpunan ini mewakili segmen masyarakat kelas atas dan berpendidikan. Suara kromo atau rakyat kelas bawah baru mendapatkan tempat ketika Sarekat Islam (SI) berdiri di tahun 1912. Sarekat Islam yang awalnya bergerak untuk kepentingan para pedagang batik bumiputra di Surakarta, di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto, menjadi gerakan yang secara terang-terangan melawan penjajahan. Bendera Islam digunakan untuk membangun identitas yang berbeda dari identitas kaum Belanda. Petani dan rakyat kecil berbondong-bondong menjadi anggota SI. Di tahun 1914, Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (Perhimpunan Sosial Demokrat Hindia, ISDV) didirikan di Surabaya oleh Henk Sneevliet dan kaum sosialis Belanda lainnya. Perhimpunan ini bertujuan untuk menyebarkan pendidikan Marxis tentang ide-ide anti kapitalis dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Walaupun fokus mereka adalah menggerakkan kaum bumiputra yang menjadi korban penjajahan Belanda, mereka kesulitan untuk masuk ke dalam kelompok-kelompok bumiputra karena kebanyakan anggota ISDV adalah orang Belanda. Untuk menyebarkan ajaran sosialisme, ISDV melancarkan strategi “bloc within” yaitu dengan membuat aliansi dengan perhimpunan populer yang ada.[i] Anggota ISDV seperti Semaun—yang juga seorang pemimpin serikat buruh yang cerdas dan mumpuni—dan Baars—yang fasih berbahasa Indonesia—kemudian ikut serta dalam kepemimpinan organisasi SI. Mereka memperkenalkan pendidikan anti kapitalisme dan bahasa perlawanan Marxis dan mentransformasikan SI menjadi radikal dan revolusioner. Dua tahun setelah Sneevliet diasingkan oleh pemerintah kolonial dari Hindia Belanda, di tahun 1920 ISDV diubah namanya menjadi Perhimpunan Komunis di Hindia dan dipimpin oleh Semaun dan kader-kader komunis bumiputra lainnya. Di tengah-tengah krisis ekonomi setelah Perang Dunia I dan wabah Flu Spanyol, PKI berperan sebagai salah satu mesin penggerak gerakan antikolonial yang paling besar dan sukses di masanya.
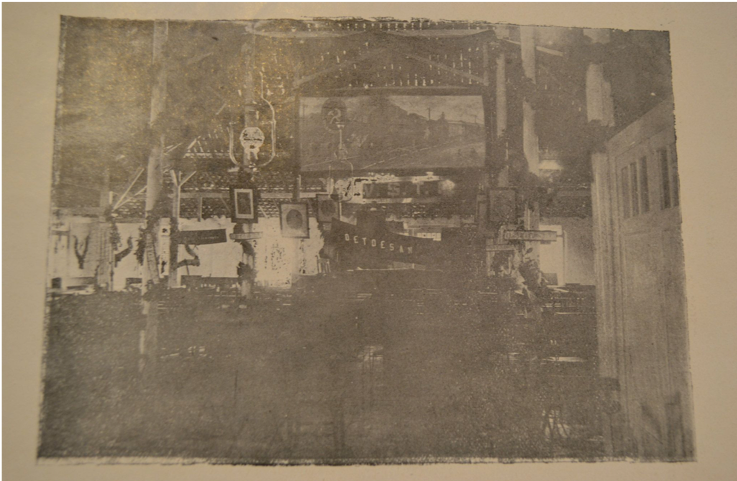
Penting sekali melihat “zaman bergerak”[ii] di tahun 1920an sebagai “gerakan komunis” dan bukan hanya sebagai gerakan PKI. Gerakan ini dilancarkan melalui aliansi PKI dan SI dengan berbagai organisasi termasuk di antaranya sarekat-sarekat buruh seperti Sarekat Postel, perhimpunan buruh kereta api Vereeniging voor Spoor-en Tramweg Personeel, Sarekat Pegawai Laoet Indonesia, and Sarekat Pegawei Pelabuhan dan Lautan. Walaupun SI sudah mulai memobilisasi gerakan kelas bawah sejak 1913, pada masa gerakan komunis, PKI membentuk gerakan antikolonial dengan organisasi politik dan pendidikan politik yang modern[iii] serta bahasa perlawanan yang universal dan global. Ketika Sarekat Islam diubah menjadi Sarekat Islam Merah (versus SI Putih yang anti komunis) dan lalu Sarekat Rakyat, identitas gerakan diubah dari berdasarkan “Islam” menjadi identitas inklusif yaitu “rakyat”. Gerakan semakin meluas dan mengikutsertakan rakyat berbagai latar belakang. Ini dapat dilihat jelas melalui perubahan slogan organ Sinar Hindia ketika berubah namanya menjadi API di tahun 1924, yaitu dari“Surat kabar bagi kaum kromo di Hindia”, menjadi “Suara kaum proletar dari segala bangsa dan igama.”[iv] Perubahan ini menjadikan gerakan yang awalnya berdasar pada kepentingan rakyat kromodi Jawa menjadi kepentingan yang lebih luas lagi yaitu kelas buruh atau proletar di Hindia Belanda. Namun, tentu penting sekali untuk tidak melihat gerakan ini sebagai gerakan yang homogen yang digerakkan hanya oleh kelompok buruh. Gerakan komunis berhasil menjadi gerakan populer karena mengikutsertakan kepemimpinan aktif buruh, tani, kaum perempuan, kaum Tionghoa, India, dan Eropa serta anak-anak.

Paling tidak ada tiga warisan penting gerakan komunis seratus tahun silam. Yang pertama adalah pembentukan budaya perlawanan. Pada masa ini, ide-ide antikolonial dicurahkan melalui kesenian seperti lagu-lagu, seni teater traditional ketoprak, dan fesyen. Ketika openbare vergaderingen (rapat-rapat umum atau “begandringan”) diadakan di rumah-rumah penduduk, ruang rapat didekorasikan dengan tanaman, bunga-bunga dan bendera berwarna merah dilengkapi dengan foto ukuran besar para pemimpin komunis seperti Lenin, Marx, Tan Malaka, Semaun, dan Rosa Luxemburg. Rapat diawali dan diakhiri dengan lagu-lagu perjuangan, “Internationale”, “Darah Ra’jat”, “Sair Kemerdikaan”, “Bendera Merah”, “Perlawanan”, “Barisan Moeda”, “Enam Djam Bekerja”, dan “Marianna” yang dinyanyikan dengan sangat bersemangat oleh anak-anak Sekolah Rakyat yang menggunakan baju putih dan celana merah.[v] Rapat umum dapat dilihat sebagai hiburan untuk para buruh tani dan keluarganya. Setelah seharian bekerja di perkebunan atau sawah, mereka berkumpul untuk mendiskusikan sistem kapitalisme dan kolonialisme yang eksploitatif dan membahas strategi perlawanan. Hal ini memberikan harapan dan antusiasme bagi mereka setelah lama hidup dalam penjajahan. Pembahasan ini tidaklah abstrak. Seringkali tuntutan yang dibangun berkenaan dengan kondisi setempat, misalnya perbaikan jembatan, pengembalian lahan sawah ke tangan masyarakat, penolakan pembangunan pabrik gula, dan pendirian sekolah untuk anak-anak bumiputra kelas bawah (kebanyakan sekolah hanya dapat diakses oleh kelas priyayi). Tradisi openbare vergaderingen berkembang dan menyebar di dapur-dapur rumah dan dipimpin oleh kaum perempuan dan juga di bioskop-bioskop yang dimiliki oleh kaum Tionghoa yang dapat diisi ratusan bahkan ribuan peserta rapat. Dengan partisipasi aktif massa kelas bawah dalam rapat-rapat ini, tuntutan antikapitalis dan antikolonial pun meluas memasukkan tuntutan pembebasan perempuan dan pembebasan praktik-praktik tertentu dari agama Islam yang dipandang tidak demokratis dalam agendanya.

Walaupun radikal dan revolusioner, gerakan komunis ini sangat menjunjung metode perlawanan dengan cara “bersenjata rukun”,[vi] artinya dengan tidak menggunakan kekerasan seperti senjata dan peperangan. Para perempuan komunis seperti woro Djoienah misalnya dengan gencar mengajak masyarakat untuk bergerak secara rukun melalui organisasi politik dan dengan berpartisipasi dalam vergaderingen serta berdebat tulis di koran-koran revolusioner. Gerakan ini menciptakan tradisi komunikasi revolusioner yang diciptakan dengan mengalihfungsikan secara kreatif alat-alat komunikasi yang ada. Pada 1901, Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan sistem Politik Etis (Ethical Policy). Kaum bumiputra dapat mengenyam pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah Belanda. Mereka juga dapat mencetak koran-korannya sendiri dan diperbolehkan membangun perhimpunan sosial dan mengadakan rapat-rapat umum untuk berdiskusi. Namun, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, hanya penduduk bumiputra priyayiyang dapat menikmati keistimewaan ini. Priyayi saat itu mencakup bukan hanya keturunan bangsawan tapi juga orang-orang yang bekerja untuk pemerintah kolonial dan anak-anaknya seperti bupati dan mantri polisi (90% pegawai pemerintahan di Hindia Belanda pada 1931 adalah orang bumiputra).[vii] Kaum bumiputra kelas kromo tetap tidak mendapatkan tempat dalam ranah publik. Oleh karena itu, gerakan komunis masa ini menjadikan openbare vergaderingen sebagai alat utama memobilisasi rakyat. Rapat-rapat ini diadakan di rumah-rumah penduduk, bioskop, kantor, lapangan luas dan dipimpin oleh masyarakat lokal, perempuan dan kaum Eropa dan Tionghoa. Gerakan komunis juga menciptakan tradisi pers revolusioner.[viii] Hasil rapat dari berbagai penjuru baik daerah terpencil di pegunungan maupun di kota-kota besar di Jawa, Sumatra, Timor, maupun Sulawesi dilaporkan di koran-koran pergerakan ini seperti Sinar Hindia (Semarang), Neratja (Batavia), Oetoesan Hindia (Surabaya), Sri Djojobojo (Kediri), Benih-Mardeka (Medan), Hindia-Sepakat (Sibolga), Heroe-Tjokro (Kediri), Matahari (Bandung), Ra’jat Bergerak (Solo), Halilintar (Pontianak), Djago-Djago (West Sumatra) dan banyak lagi lainnya.[ix]
Begitu pun Sekolah SI yang kemudian berubah nama menjadi Sekolah Rakyat menjadi tempat anak-anak kelas bawah mengenyam pendidikan dasar seperti pelajaran Matematika, Bahasa Belanda, baca tulis, dan olahraga selain pendidikan politik. Dari alat komunikasi revolusioner ini kita belajar bahwa pendidikan modern dan akses ke media tidak disajikan oleh negara kolonial kepada kaum bumiputra di atas piring perak. Kaum bumiputra harus membuat alat komunikasi tadi dengan tangannya sendiri sebagai bagian dari perjuangannya melawan penjajahan Belanda. Mereka mengubah alat komunikasi kolonial menjadi alat komunikasi revolusioner yang berlawan.
Warisan kedua dari gerakan ini adalah dibangunnya gerakan rakyat yang demokratis. Gerakan komunis bukanlah buah tangan Semaun, Sneevliet, atau Tan Malaka semata, gerakan ini adalah perjuangan hasil kerja keras banyak orang. Termasuk misalnya, para perempuan yang mengadakan rapat umum di dapur-dapur untuk membangun kesadaran akan kebutuhan ilmu pengetahuan kesehatan modern, dan juga anak-anak yang dengan semangat menyanyikan lagu-lagu revolusioner sambil berbaris rapi keliling kampung. Dalam menuntut kebebasan dari kolonialisme, gerakan ini membayangkan emansipasi yang universal atas nama kemanusiaan. Seperti kata Djoeinah, editor perempuan pertama Sinar Hindia, “…hidoep bersaudara dengan sekalian sifat manoesia, dengan tiada memandang bangsa, bahasa dan agama itoelah tjita tjita kita…”[x] Karena sifatnya yang inklusif dan egaliter dan menjunjung tinggi emansipasi sosial yang universal, gerakan ini berhasil membangun sebuah front persatuan berbagai kalangan baik buruh, tani, pemuka agama, gerakan perempuan, dan mendapat simpati dan dukungan dari organisasi non-komunis seperti Budi Utomo.
Warisan ketiga yang sering luput dari pembahasan sejarah di masa ini adalah karakternya yang kosmopolitan. Kosmopolitan di sini artinya gerakan dibuat dengan membangun solidaritas dengan sesama kelas buruh di berbagai belahan dunia. Melalui organisasi Communist International (Comintern) di Rusia, gerakan komunis Hindia Belanda membayangkan dirinya sebagai bagian dari gerakan global yang menentang penjajahan dan kapitalisme. Ini adalah kosmopolitanisme yang dibentuk melalui bahasa perlawanan yang universal seperti kebebasan, hak kemanusiaan, sama rata, sama rasa, dan keadilan sosial. Penting sekali untuk tidak melihat gerakan ini semata-mata hanya dalam bingkai kepentingan nasionalis. Mereka memperjuangan kemerdekaan bangsa sebagai bagian dari perjuangan kelas. Bagi mereka, keikutsertaan dalam perjuangan proletariat internasional tidak berarti mengkhianati kepentingan lokal. Mereka melihat kepentingan lokal tidak terlepas dari kepentingan bersama yaitu pembebasan manusia dari eksploitasi kapitalisme yang mengekang. Melalui solidaritas internasional ini kaum revolusioner Indonesia mencari dan menemukan tempatnya dalam kancah perjuangan kemanusiaan global baik di masa lalu maupun di masanya. Bersama Marx, Lenin, dan Rosa Luxemburg, Djoienah, Semaun, Darsono, dan para revolusioner lainnya mengepalkan tangannya berjuang bersama melawan kapitalisme dan imperialisme global.

Gerakan ini mungkin pendek masanya tetapi memberikan sumbangsih besar dalam sejarah Indonesia. Ketika kebanyakan para pemimpin partai sudah ditangkap dan diasingkan dari Hindia Belanda, periode 1923-1925 adalah tahun-tahun ketika pergerakan sangat aktif. Masyarakat biasa turun ke jalan dan hampir tiap hari openbare vergaderingen diadakan. Tanggal 1 Mei dan 17 November diadakan pesta meriah untuk merayakan hari buruh dan Revolusi Rusia. Dengan meningkatnya jumlah rapat-rapat ini secara pesat, pemerintah kolonial pun meningkatkan represinya terhadap gerakan komunis. Periode 1923-1924 yang penuh perayaan dan antusiasme berubah menjadi tahun panas pada 1925. Konflik antara polisi dan peserta gerakan meningkat tajam. Pembunuhan dan teror dialami peserta rapat dan terjadi bukan hanya dalam konflik dengan polisi Hindia tetapi juga dengan kelompok anti-komunis bernama Sarekat Hidjo. Rumah masyarakat biasa yang ikut rapat umum dibakar atau dilempari batu; perempuan diteror. Pemerintah Belanda untuk pertama kalinya mengeluarkan aturan dan kebijakan yang mengekang di ranah komunikasi, baik koran, rapat umum, maupun “sekolah liar.”[xi] Pengekangan dan teror yang dirasakan rakyat biasa di tahun ini menjelaskan sikap ekstrem pemerintah merespons pemberontakan komunis 1926-1927. Walaupun dilakukan oleh hanya segelintir orang, pemerintah Belanda menangkap ribuan orang. Sebagian dihukum mati, sementara sekitar 3.000 orang dibuang ke Digoel.
Walaupun berakhir dengan dilarangnya PKI dan organisasi komunis lainnya, perjuangan para revolusioner pada masa ini merupakan benih penting bagi terbentuknya gerakan kemerdekaan Indonesia dua dekade setelahnya. Mereka yang turut berjuang di dalam revolusi nasional adalah para angkatan 1926 dan juga anak-anak muda yang tumbuh dan dibesarkan dalam tradisi komunikasi revolusioner dan budaya perlawanan yang difasilitasinya.
Rianne Subijanto adalah editor IndoProgress dan dosen di jurusan komunikasi Baruch College, City University of New York.
[i] Ruth T. McVey, The Rise of Indonesian Communism (Ithaca, N.Y: Cornell University Press, 1965), 82-3.
[ii] Takashi Shiraishi, An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926 (Ithaca: Cornell University Press, 1990).
[iii] Ruth McVey, “Teaching Modernity: The PKI As an Educational Institution,” Indonesia 50 (1990): 5-27, dan McVey, The Rise of Indonesian Communism.
[iv] Rianne Subijanto, “Enlightenment and the Revolutionary Press in Colonial Indonesia” in International Journal of Communication (11), 1357-1377 (akses dalam bahasa Belanda, “Verlichtingsidealen en de Revolutionaire Pers in Koloniaal Indonesië: De Inhoud, Productie en Distributie van Sinar Hindia,” Tijdschrift voor Geschiedenis, 130(3) (2017), 449-466).
[v] Rianne Subijanto, “Communist Openbare Vergaderingen and an Indonesian Revolutionary Public Sphere” in The Global Impacts of Russia’s Great War and Revolution Book 2: The Wider Arc of Revolution, Part 2 eds. Choi Chatterjee et.al. (Bloomington, IN: Slavica Publishers Indian University, 2019), 277-297.
[vi] “Pemimpin Istri dalam vergadering (Oengaran),” Sinar Hindia, 2 October 1920.
[vii] Benedict Anderson, Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia (Ithaca: Cornell University Press, 1990), 98.
[viii] Tentang media perlawanan di masa ini, lihat Rianne Subijanto, “Media of Resistance: A Communication History of the Communist Movement in the Dutch East Indies, 1920-1926” (Ph.D. diss., University of Colorado Boulder, 2016).
[ix] Subijanto, “Enlightenment and the Revolutionary Press,” 1365.
[x] Djoeinah, “Zaman Ini,” Sinar Hindia, 7 December, 1920.
[xi] Mirjam Maters, Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial antara Kebebasan dan Pemberangusan 1906-1942 (trans. Mien Joebhaar) (Jakarta: Hasta Mitra & KITLV, 1998).






