Kredit ilustrasi: massappeal.com
APABILA dilihat dari perspektif yang meletakkan sentralitas pekerja dalam perkembangan sejarah, maka secanggih apapun teknologi akan berkembang ke depannya, tetap saja ia berwatak primitif. Maksudnya, dari standpoint pekerja, dan khususnya yang melihatnya secara materialis dan historis, seluruh perkembangan teknologi dalam kapitalisme akan selalu mensyaratkan proses akumulasi primitif. Tulisan singkat ini akan menjelaskan argumen “aneh” ini dengan meminjam dokumentasi pembuatan robot joget alias Tw3rk-Bot.
Tentu saja terasa aneh apabila dikunyah oleh kita yang melihat akumulasi primitif secara esensialis dan terfiksasi pada bentuk-bentuk konvensionalnya. Pertaruhan saya, dengan melihat senarai revolusi teknologi secara akumulasi primitif, bukan hanya kita bisa melihat gambar besar kapitalistik dari seluruh perkembangan teknologi sejak mesin pemintal sampai mesin pengunggah kesadaran, namun kita bisa mempertimbangkan relasi baru terhadap teknologi, dan mulai memikirkan strategi untuk merebutnya dan meletakkannya ke kendali pekerja.
Euforia dan Panik
Sampai hari ini saya yakin kita semua bisa memetakan secara sederhana bahwa terdapat dua pengutuban terkait reaksi terhadap perkembangan teknologi yang konon, menurut historiografi arus utama, sudah berada dalam versinya yang ke 4.0 ini. Kutub yang pertama umumnya sangat optimis dan cenderung euforis dalam menanggapinya. Revolusi Industri 4.0 (IR4—untuk menggunakan singkatan resmi pemerintah tercinta) memungkinkan kerja-kerja yang tadinya mensyaratkan tangan dan peluh manusia, kini bisa terotomasi: mulai prosedur dan perintah pengerjaannya (yi. secara algoritmis) sampai bahkan peggantian total tubuh sang pekerja (yi. melalui robotisasi). Kutub yang pertama ini umumnya kita dengar dari pemerintah, kawula muda optimis pelaku startup, dan perusahaan konsultan kelas kakap (seperti McKinsey dan PwC, dst.), untuk menyebut beberapa.
Kutub yang kedua umumnya disuarakan oleh romantisis kemanusiaan dan, yang akan menjadi perhatian kita, kaum pekerja. Romantisis kemanusiaan umumnya bernostalgia tentang hubungan tatap muka langsung seperti di zaman mereka masih ababil; menyayangkan intimitas yang kini termediasi layar dan mesin; dan bahkan ketakutan membuat Tuhan marah karena perbuatan “makar” teknologis kita umat manusia tak tahu diri. Saya akan mengabaikan ratapan mengenaskan kaum ini, karena yang terlebih penting adalah bagian berikutnya.
R&D vs. D&R
Dominan di kalangan pekerja adalah kepanikan dan ketakutan akan pengurangan bahkan penggantian (replacement) total pekerja, perlahan-lahan dengan teknologi otomasi dan sampai nantinya dengan robot-robot cerdas. Pengurangan kerja karena otomasi berpotensi memindahkan (displace) para pekerja ke pos-pos pekerjaan yang sangat menjemukan dan sudah tentu dihargai murah. Kecerdasan buatan pun perlahan-tapi-pasti mengotomasi mulai dari pekerja manufaktur, bahkan sampai pekerjaan peneliti! Sesempit pengamatan saya akan sirkulasi wacana di ruang publik, sayangnya belum saya temukan narasi pekerja (baik dari serikat maupun cendekiawan yang “mewakilinya”) yang tidak 11-12 dengan narasi ini. Saya memformulasikan perangkat mnemonik (penyederhana untuk mengingat) untuk narasi ini sebagai berikut: R&D (research & development) teknologi industri vs. D&R (displacement & replacement) pekerja.
Turunan dari wacana “R&D vs. D&R” ini pun kebanyakan normatif dan masih tidak berperspektif sentralitas pekerja karena masih melulu mengandalkan pemerintah. “Negara harus.. pemerintah harus.. blabla”; seolah-olah tanpa pemerintah, rakyat pekerja tidak mampu berbuat apa-apa. Respon pekerja pun umumya sangat personal: mereka cenderung mengambil inisiatif sendiri untuk meningkatkan kemampuannya masing-masing.[1] Sungguh memprihatinkan di sini bagaimana persoalan yang sifatnya sistemik justru direspon tidak secara sistemik, melainkan secara sukarela di-outsource ke diri mereka sendiri sebagai pekerja (sekaligus menunjukkan bagaimana cengkeraman logika privatisasi kehidupan ala neoliberalisme telah berhasil secara total!; dan sekaligus bahwa dalam neoliberalisme, persoalan outsourcing ternyata lebih “intim” dari yang umumnya dipahami).[2]
Bahkan, apabila serius dilihat dari perspektif kelas pekerja, lebih parah lagi: ratapan dan celaan bahwa IR4 adalah mengkhawatirkan karena mengancam pekerjaan rakyat pekerja, sedikit banyak, mengandung bias borjuasi. Bagaimana tidak, bukankah asumsi ini menormalkan kenyataan bahwa ‘kerja’ adalah selalu melemparkan diri ke rezim upahan yang pada hakikatnya adalah kapitalistik, dan seolah tidak ada konsepsi kerja lain yang di luar relasi buruh dan modal? Rezim upahan adalah sesuatu yang dilazimkan dan sama sekali tidak dipermasalahkan di sini; begitu pula etos kerja kapitalis yang menjadi moralitas universal yang tak terbantahkan. Kasihan Karl Marx, sudah jauh-jauh hari ia memperingatkan bahwa adalah relasi upah yang menjadi alat untuk menata masyarakat ke dalam kelas (borjuis dan proletar). Begitu pula Silvia Federici dan para feminis WfH (Wages for Housework) yang sejak puluhan tahun lalu sudah menunjukkan bahwa mengukur kerja dengan upah adalah upaya kapitalisme untuk menyembunyikan dan bahkan mengeksploitasi lebih jauh kerja-kerja domestik dan reproduktif yang umumnya tak berupah.[3]
Tapi baiklah, mungkin jam kerja kita para pekerja semakin meningkat dan relasi kerja yang makin rentan (precarious) gara-gara digitalisasi dan otomasi telah merampas waktu baca kita sehingga peringatan-peringatan ini lewat kita baca. Namun tetap saja, seruan dan tuntutan normatif di atas tidak akan membawa kita, kelas pekerja, kemana-mana. Karena dengan kerangka pikir keborjuis-borjuisan seperti ini, kemanapun kita melangkah tetap saja akan meniscayakan “mutasi” teknologi industri, dan bahwa teknologi adalah selalu “milik” kapitalisme. Kita perlu agenda baru kelas pekerja terhadap mutasi teknologi ini; dan untuknya, kita juga perlu memiliki paradigma dan bahkan relasi baru dengan teknologi “kapitalis” ini.
Teori Umum Akumulasi Primitif
Paradigma baru yang coba saya usulkan melalui tulisan ini adalah akumulasi primitif—namun dalam versinya yang non-esensialis. Pandangan yang non-esensialis akan menarik pola-pola umum dari fenomena yang dilabeli sebagai ‘akumulasi primitif’ dan, pada akhirnya, memampukan kita untuk keluar dari gambaran-gambaran tradisional yang secara dogmatik menancap di otak “progresif” kita.
Silakan dicoba: masukkan frasa “akumulasi primitif” di mesin pencari kesayangan kita, dan coba cek pada laman-laman temuan teratasnya (10-20, misalnya); atau coba masukkan frasa tersebut di mesin pencari di situs IndoPROGRESS ini. Berani taruhan potong leher, Anda akan temukan dominasi (jika bukan monopoli absolut) penggunaan kata itu untuk mengacu hal-hal seputar: perampasan lahan, masalah agraria, penguasaan SDA, penggusuran, kolonialisme, imperialisme, dan tema-tema sebangsanya. Persis seperti deskripsi Marx, akumulasi primitif dilihatnya sebagai “fakta mengerikan tentang penguasaan, perbudakan, perampasan, pembunuhan,” yang dalam sejarah, ia ditulis dengan “tinta darah dan api.” Itulah mengapa tentunya adalah aneh dan awkward apabila terma akumulasi primitif ini dipakai untuk memahami proses revolusi teknologi, boro-boro kecerdasan buatan (AI).
Tulisan ini tidak hendak menyalahkan penggunaan akumulasi primitif seperti di atas. Namun apabila konsep ini hanya dikerangkeng sedemikian rupa, maka kita akan kehilangan kerangka yang amat berguna untuk melihat persoalan teknologi, dan bahkan membayangkan visi teknologis ke depannya secara perspektif pekerja, yaitu non-kapitalis.
(Karena keterbatasan tempat, tulisan ini hanya akan memberikan rangkuman umum teorisasi akumulasi primitif, sehingga tentu saja kutipan dan elaborasi mendetil tidak akan pembaca dapatkan di sini.)[4]
Secara minimal, akumulasi primitif bisa kita definisikan proses pemisahan (severe) manusia-pekerja dari kondisi kerjanya (conditions of labor), yaitu kondisi-kondisi terberi yang memungkinkannya untuk bekerja dan berproduksi: seperti lahan, alam, tempat tinggal, dan—yang terpenting—relasi sosialnya. Pemisahan ini tentu saja dilakukan secara sepihak oleh mereka yang pasca akumulasi primitif ini menyandang predikat kapitalis. Lalu apa yang terjadi di sisi manusia-pekerja tadi?
Kronologi umumnya sbb.: pertama, mereka menjadi tersingkir dari kondisi kerjanya; lalu kedua, kondisi kerja tadi bertransformasi menjadi modal yang dikuasai/monopoli oleh kapitalis, dan para manusia tersingkir tadi kini tidak memiliki akses ke milik-mereka-yang-kini-menjadi-modal kapitalis; ketiga, para manusia ini tidak akan hidup tentunya tanpa kondisi kerja yang kini tidak dapat mereka akses, alhasil satu-satunya cara mengaksesnya adalah dengan menjadi buruh yang bekerja kepada kapitalis; dan keempat, hasil kerja para manusia-buruh ini diambil oleh kapitalis dan digantikan dengan upah, dan hasil-kerja itu bertransformasi menjadi komoditas. Untuk mengakses komoditas ini, para buruh tentunya harus membayar dengan uang yang didapat dari upah kerjanya.
Secara teoritis, bisa kita identifikasi empat operasi umum yang terjadi mengiringi drama akumulasi primitif dalam pemikiran Marx: 1) separasi pekerja dari kondisi kerjanya; 2) kapitalisasi, yaitu transformasi rampasan kondisi kerja menjadi kapital; 3) proletarianisasi, yaitu transformasi manusia-pekerja menjadi manusia-buruh yang bekerja berbasis relasi upah; dan 4) komodifikasi, yaitu transformasi hasil kerja manusia-buruh menjadi barang komoditas yang ditujukan bukan untuk dikonsumsi langsung, melainkan untuk disirkulasikan di suatu arena bernama pasar demi mengakumulasi keuntungan bagi kapitalis.[5]
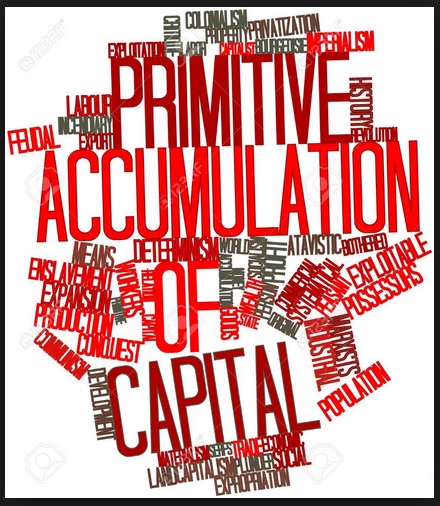
Kredit ilustrasi: 123RF.com
Aspek Primitif dari AI
Cukup sudah teori. Apabila keempat variabel ini kita pakai untuk melihat, misalnya, perampasan lahan, maka kita akan dapatkan penjelasan sbb.: perampasan lahan terjadi melalui proses separasi masyarakat dari lahan tinggalnya selama ini, yang kemudian lahan itu dijadikan properti sang perampas untuk dibangun, misalnya, pabrik; masyarakat dapat mengakses lahan rampasan tersebut hanya dengan menjadi buruh pabrik upahan, yang mana ia akan bekerja dan menghasilkan komoditas sebagaimana “diminta” pasar, yang hasil keuntungan penjualannya semakin memperkaya sang perampas lahan. Saya yakin narasi seperti ini tidak asing bagi kita tentunya. Tapi, bagaimana dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI)?
Untuk ini, saya minta pembaca meluangkan waktu 5:58 menit melihat video klip di bawah ini. Tugas Anda adalah mendeteksi keempat operasi umum akumulasi primitif sebagaimana yang saya gariskan barusan: separasi, kapitalisasi, proletarianisasi, dan komodifikasi. Video klip ini adalah tentang kisah pembuatan sebuah robot joget twerk, yaitu TW3RK-BOT®. Perlu diketahui, robot ini fiktif (bukan dalam artian “akal-akalan” sebagaimana Rocky Gerung, melainkan) dalam artian ia hanya kisah belaka; jika ada kesamaan nama tokoh, tempat, kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Namun demikian, sekalipun fiktif, saya berani bertaruh bahwa video klip ini adalah pengantar populer paling efektif di seantero jagad untuk menjelaskan proses akumulasi primitif sebagaimana diteorisasikan oleh Marx.
Kita bisa skip dulu untuk sementara alibi bahwa tanpa perjogetan maka tidak akan ada kemanusiaan, yang entah dengan penalaran seperti apa lantas solusinya adalah robot twerk. (Saya tidak sampai hati menjelaskan apa dan bagaimana itu joget twerking, silahkan pembaca mencari tahu sendiri). Pembaca bisa ikuti alur proses penciptaan Twerk-Bot yang menariknya benar-benar mirip dengan alur kronologis akumulasi primitif di atas. Awalnya, keterampilan dan kapasitas berjoget twerk adalah melekat di tubuh manusia. Adalah keterampilan twerking ini yang hendak diseparasi dari tubuh manusia-pekerja-twerk (twerking adalah kerja; mana mau Miley Cyrus twerking di depan Anda secara gratis?!). Lalu bagaimana menyeparasinya? Tidak lain dengan sains dan teknologi: pertama-tama gerakan sang manusia pekerja-twerk diamati, lalu dimodel, dan kemudian ditransformasikan ke dalam bit-bit informasi melalui piranti lunak pengkodean; luarannya adalah model rancang-bangun, desain atau cetak biru teknologi. Lalu berikutnya model tadi diberi tubuh berupa rakitan bahan-bahan material (besi, baja, serat, eter, karet, lem, silikon, dst.). Perlu diperhatikan di sini bahwa proses pemodelan morfologi “tubuh” dari Twerk-Bot ini juga turut menyeparasi citra tubuh dari sang pekerja-twerk, walau cuma bagian bawah, bahkan spesifiknya pantatnya saja. Citra tubuh pun menjadi obyek akumulasi primitif di sini. Pelajaran pertama Twerk-Bot: pemodelan digital (CAD—computer-aided design dan 3D modeling) adalah modus operandi apa yang bisa kita sebut ‘akumulasi primitif teknosains’ dalam merenggut, meringkus, dan kemudian (menggunakan kata favorit para esensialis) “merampas” kondisi kerja kognitif dan citra tubuh.[6]
Berikutnya, bisa kita tebak, data keterampilan twerking—yang terkodekan dalam bit-bit informasi digital—kemudian menjadi aset kapital perusahaan tak terlihat (intangible asset). Keterampilan kerja-twerk kini menjadi terpisahkan, teralienasi, terobyektifikasi menjauh dari tubuh asalnya dan kini menjadi suatu enititas kapital kognitif—di Grundrisse, Marx menyebut kapital ini sebagai general intellect. Pelajaran kedua Twerk-Bot: kapitalisasi keterampilan twerking dilakukan dengan cara-cara informasionalisasi, atau dengan kosakata yang lebih kontemporer, dengan datafikasi. Jika David Harvey mengutarakan tentang akumulasi melalui perampasan (accumulation by dispossession), mari kita namai ini sebagai ‘akumulasi melalui datafikasi’ (accumulation by datafication).
Lalu kemudian proletarianisasi. Jelas, mungkin bisa kita tebak para pekerja di riset yang menurut klip video berjumlah 118 orang tersebut adalah pekerja riset dengan kontrak dan waktu kerja tidak jelas. Tapi bukan itu: mereka adalah hasil akumulasi primitif di bidang lain. Di bidang per-twerk-an ini, adalah para penjoget twerk, yang adalah manusia-manusia, yang merupakan proletar di sini. Lalu, sebagai buruh, apa yang mereka kerjakan? Di sini poin menariknya: buruh twerk ini bekerja dengan cara “mengajari” robot bagaimana twerking dengan benar, secara berulang-ulang sampai sang robot bisa melakukannya (bahkan) secara lebih baik (baca: cerdas) dari sang penjoget twerk yang adalah gurunya. Pelajaran ketiga Twerk-Bot tentang akumulasi primitif: dalam alam kecerdasan buatan (AI), kita dibuat menjadi buruh dengan mengajari, menginformasikan, membagikan, dan mentransferkan keterampilan kita untuk dipelajari oleh mesin dengan algoritma machine learning (mis. artificial neural network) sedemikian rupa sampai akhirnya ia bisa independen sepenuhnya dari guru-gurunya. Simpulan lainnya, dalam alam AI, batasan antara separasi dan proletarianisasi menjadi terkaburkan; seakan-akan para manusia-pekerja rela untuk dirampas kondisi kerja kognitifnya dan menyerahkannya pada para Twerk-Bot yang adalah mesin-kapital. (Familiar bukan dengan kebiasaan kita sehari-hari dalam “mengajari” mesin pencari Google dan Facebook, dan juga ojek/taksi online?).
Terakhir, komodifikasi terpampang jelas di bagian akhir video klip ini. Twerk-Bot yang sudah selesai dibuat dan digandakan kemudian dikemas, diberi label harga, masuk ke pasaran, dan akhirnya terdistribusikan kepada para konsumen. Ada dua hal yang menarik terkait komoditas AI dengan melihat video klip Twerk-Bot ini. Pertama, jika kita perhatikan tagline jualannya, tertulis “learn to dance this holiday season” (belajar berjoget di musim liburan ini). Artinya, robot ini, yang adalah akumulasi dari intelijensia twerking para buruh-twerk sebelumnya, kini berbalik mengajari kita bagaimana twerk yang baik. Dengan kata lain, ia mentransferkan kembali intelijensia yang terkandung di dalamnya ke para konsumen! Kedua, ia tidak mengenal finalitas. Di tagline lain jualannya tertulis, “teach her new songs and moves” (ajari dia lagu dan gerakan baru). Karena ia cerdas, maka ia akan selalu belajar, belajar, dan belajar. (Saya yakin Lenin akan suka dengan AI jika ia masih hidup). Dan kini, konsumen dan buruh menjadi kabur: karena dengan mengonsumsi produk AI, kita pun menjadi para buruh-buruh pengajar mesin pembelajar! Masih mending para pengajar di video klip itu dibayar, dengan menjadi konsumen komoditas AI, kerja-kerja kita mengajari mesin adalah kerja-kerja gratisan alias tak berbayar!
Penutup
Sampai sini saya harap Anda bersepakat dengan judul artikel saya ini: secanggih-canggihnya teknologi kecerdasan buatan, apabila dilihat dari perspektif pekerja, ia tetap saja sebentuk akumulasi primitif. Anda benar jika Anda lantas berpikir bahwa hari ini, dengan mengemukanya imperatif untuk selalu berinovasi, maka akumulasi primitif (yang senantiasa menyertai setiap inovasi teknologi) menjadi turut mengemuka pula. Bahkan perlombaan startup harus kita lihat sebagai perlomba-lombaan dalam melakukan akumulasi primitif yang techy.
Beberapa takeaways yang bisa kita tarik di sini akan mengonfirmasi ambisi artikel ini untuk menceritakan narasi lain dalam proses penciptaan teknologi, yaitu dengan menekankan sentralitas pekerja. Pertama, subjek revolusi teknologi adalah manusia-manusia pekerja yang hidup, yang kreatif, yang intelijen—dan bukan para saintis dan asesoris perkabelannya.[7] Aspek revolusioner dari teknologi “disruptif” bersumber seluruhnya dari tubuh manusia dan seisinya: mulai citranya, geraknya, polanya, kreativitasnya, cara kerjanya, biologi dan metabolismenya, cara berpikirnya, dst. Hal-hal inilah yang dimodel dan diperangkap oleh kapitalis melalui trik-trik pengkodean dan datafikasi.
Kedua, kondisi kerja (conditions of labor), yaitu prasyarat yang dibutuhkan agar tubuh hidup manusia-pekerja bisa melakukan proses kerja, tidaklah terbatas pada hal-hal tradisional yang kita rujuk saat berbicara akumulasi primitif seperti tanah dan SDA. Dilihat per definisi, maka kondisi kerja dapat mengacu pada seluruh aspek kehidupan manusia yang memungkinkannya untuk bekerja: ia bisa berupa sesuatu yang obyektif dalam artian geografis-spasial (tanah dan SDA), melainkan bisa juga dalam artian biologis (metabolisme tubuh dan morfologi pantat untuk twerking), kimiawi (hormonal dan unsur-unsur kimia dasar yang mewarnai kulit pantat dan membentuk kekenyalan pantat Twerk-Bot), bahkan juga temporal[8]! Namun demikian, kondisi kerja tidak hanya berupa fakta objektif yang terberi saja, melainkan ia bisa juga sesuatu yang subjektif, misalnya seperti yang terdapat dalam video klip, seperti keterampilan dan jam terbang pengalaman twerking para pengajar-twerk dan pemaknaan akan joget yang akan punah dalam 15 tahun ke depan (yang menjustifikasi kebutuhan pasar akan Twerk-Bot). Kondisi kerja juga ada yang bersifat intersubyektif, misalnya konsepsi kemanusiaan yang coba dijadikan justifikasi komodifikasi twerking melalui Twerk-Bot dengan cara menghubungkannya dengan kelestarian jogetan. Perhatikan narasi di awal video klip: “Without dance there is no love. Without love there is no passion. Without passion there are no humans… Then what are we?”. Dengan cara pandang ini, maka bisa kita lihat bahwa seluruh aspek yang diburu oleh akumulasi primitif tidak lain tidak bukan adalah hidup itu sendiri. Adalah hidup dan hal-hal yang mengondisikannya yang selalu menjadi target akumulasi primitif.[9] Tanpa kehidupan, tidak akan ada sumber-sumber inspirasi untuk diotomasi, untuk didigitalisasi, dimodel algoritmanya, didesain citraannya, dan ditransfer ke dalam mesin. Menggunakan terma Marx, tanpa pekerja hidup (living labor) tidak akan ada kerja mati (dead labor) dan avatar-avatarnya mulai dari mesin pintal sampai Twerk-Bot, mulai dari cetak biru model 3D sampai general intellect.
Akhir kata, dengan menunjukkan aspek primitif dari kecanggihan terobosan-terobosan teknologi ini, penulis berharap kita, pekerja hidup, bisa memutakhirkan cara pandang kita terhadap teknologi. Kepanikan D&R terhadap R&D teknologis jelas adalah sesuatu yang teramat reaktif, belum lagi justru mereproduksi idiologi kerja borjuis. Permasalahan mendasar perkembangan teknologi hari ini sebenarnya BUKANLAH persoalan tergantikannya pekerja oleh robot. Pasalnya hal ini sebenarnya dan seharusnya adalah hal yang menggembirakan: kita bisa terbebas dari kerja-kerja monoton dan waktu luang kita bisa menjadi lebih banyak untuk, misalnya, membaca sastra dan filsafat (dan menghabiskan buku-buku Marx), untuk berorganisasi dalam serikat dan koperasi, untuk berdebat dalam wacana politik, dst.
Namun demikian, apabila ternyata perkembangan teknologi justru mengakibatkan pekerja menjadi tidak memiliki penghidupan, maka jangan serta-merta kita simpulkan bahwa adalah teknologi yang menjadi musuh pekerja. Sama sekali bukan. Karena sebenarnya, adalah pengusaan teknologi secara kapitalis dan penentuan perkembangannya untuk penguatan industri penghisapan nilai lebih di segala sektor yang harus kita perangi. Seluruh teknologi memiliki asal-usulnya dari tubuh hidup kita para pekerja. Memusuhi teknologi, berarti memusuhi “ekstensi” tubuh kita sendiri. Sebaliknya yang diperlukan pekerja adalah strategi untuk merebut seluruh teknologi yang saat ini dikendalikan dan dikuasai para pemodal, dan juga memikirkan perencanaan sistem pengelolaan dan pengembangan teknologi di masa yang akan datang kelak saat kapitalisme sudah dimuseumkan. Tanpa strategi dan perencanaan, maka pekerja harus berpuas diri dengan kepanikan borjuistik ini. Taruhannya cukup besar, sebagaimana Leopoldina Fortunati: “Robot mampu untuk membebaskan waktu kita dari kerja, namun, jika ternyata ketimbang memiliki waktu luang yang lebih banyak, kita malah menjadi penganggur atau menjadi lebih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan tak berupah lainnya, maka tepat di situlah robot berbalik menyerang kita.”[10]***
Penulis adalah peneliti di Koperasi Riset Purusha
————–
[1] Sebagaimana data sementara dari riset Dampak Transformasi Digital pada Pekerjaan Jurnalistik (Federasi Serikat Pekerja Media Independen dan Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia, 2018). Kontak riset ini: Gema Ramadhan Bastari, gemarbastari@gmail.com.
[2] Ekonom Neoliberal awal—seperti Gary Becker dan Theodore Schultz—melihat bahwa suatu ekonomi akan maju apabila para masyarakat-pekerjanya melihat partisipasinya pada ekonomi (yi. sebagai pekerja) sebagai suatu hal yang intim dan personal. Alhasil, kerja perlu dilihat sebagai karir, keterampilan kerja perlu dilihat sebagai modal manusia (human capital), ongkos pengembangan sebagai investasi; dan riwayat banting tulang cari penghidupan dilihat sebagai curriculum vitae. Lih. Michel Foucault, The Birth of Biopolitics (Palgrave, 2008).
[3] Silvia Federici & Nicole Fox, “Counterplanning from the Kitchen (1975),” dlm. S. Federici, Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle (PM Press, 2012).
[4] Paparan berikut ini merupakan petikan dari hasil refleksi teoritis yang saya lakukan bersama Cecil Mariani dalam riset kami Logic of Primitive Accumulation in Cultural Field (and literally elsewhere), (Tranzit Czech, 2017).
[5] Aspek pasar sengaja tidak dibahas di sini karena keterbatasan. Penciptaan pasar (baik dalam artiannya guru-guru manajemen, yi. market creation, maupun dalam artian sosiolog/antropolog, yi. marketization) juga memiliki struktur sebagaimana yang kita dapati dalam apa yang disebut di sini dengan akumulasi primitif. Penciptaan alibi nilai guna (menggunakan frasa Baudrillard) yang baru, platform sirkulasi, jejaring informasi melalui periklanan, rezim pengukuran nilai/harga, dst., yang termasuk dalam apa yang disebut ‘pasar’ telah selalu mensyaratkan perampasan lahan sosial-kognitif kolektif—yang juga adalah kondisi kerja masing-masing individu manusia-pekerja—dan seluruh operasi akumulasi primitif lainnya (kapitalisasi, proletarianisasi dan komidifikasi). Elaborasi lebih jauh pada kesempatan lainnya.
[6] Jangan remehkan citra tubuh. Tanpa citra tubuh manusia, Gregor Samsa yang berubah menjadi kecoak dalam novel Metamorfosis-nya Kafka tidak bisa bekerja! Citra tubuh, dalam psikoanalisis Lacanian, juga berbicara mengenai identitas. Label dan narasi identitas, tetap harus memiliki kontainernya berupa citra imajiner.
[7] Contoh buruk yang sama sekali buta perspektif pekerja, lih. Budiman Sudjatmiko, Hidup Bersama Robot Cerdas, Kompas, 16 Desember 2017. Versi panjang, yang tetap saja misleading, di sini.
[8] Dicky Ermandara, “Ekonomi Waktu,” IndoProgress, 12 Juli 2017. Tulisan ini menunjukkan dengan baik untuk poin temporal ini.
[9] Seluruh aspek kehidupan, atau yang kami sebut ‘life-common’ ini sebenarnya bisa terkategorikan ke dalam empat aksis: objektif, subjektif, intersubjektif dan interobjektif. Kapitalisme dikatakan berkembang tepat saat semakin banyak aspek-aspek life-common ini sukses terakumulasi primitif. Konsep awal diagram yang saya dan Cecil Mariani kembangkan mengenai ini, bisa dilihat di sini: https://postfordisthighway.com/diagram-life-common/.
[10] Leopoldina Fortunati, “Robotization and the domestic sphere,” New Media & Society, OnlineFirst, 2017.






