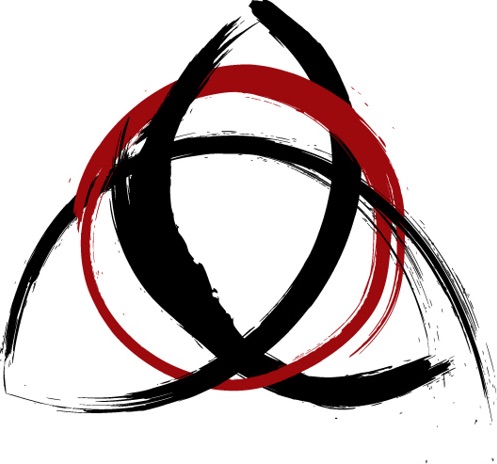Kredit ilustrasi: sevenmileroadphilly.org
KONTROVERSI ucapan Eggi Sudjana terkait ke-esa-an Tuhan, berikut semua drama yang mengiringinya (lapor-melapor ke pihak kepolisian, hingga penggunaan pasal karet ‘Penistaan Agama’) yang mengisi tajuk utama pemberitaan dan linimasa media sosial belakangan ini, rupanya tidak hanya menjadi bahan obrolan masyarakat awam, netizen, dan pengamat politik saja. Kalangan teolog, khususnya dari kalangan non-muslim, turut angkat bicara mengenai topik ini, bahkan menjabarkan konsep ke-Tuhan-an menurut teologinya masing-masing. Sebuah hal yang menarik tentunya, karena amat jarang publik diperkenalkan kepada diskursus yang bersifat teologis di luar keyakinannya. Di sisi lain, khususnya bagi umat kristiani, fenomena ini juga menggambarkan ironi: betapa gagapnya korelasi teologi kristen Indonesia di ranah publik, seolah-olah teologi hanya bisa bersuara terkait isu ajaran dan spiritual belaka.Hal ini bisa dilihat dalam keseharian kita, ketika mimbar gereja dipenuhi hanya oleh khotbah seputar spiritualitas, kesalehan, dan motivasi diri, seolah-olah iman kristen hanya berurusan dengan hal-hal yang bersifat abstrak belaka. Maka pertanyaannya adalah adakah dimensi material dari kekristenan? Apabila Allah itu transenden dan melampaui yang material, lantas bagaimana mungkin ia terhubung dengan yang material? Dalam hal inilah konsep trinitas menjadi jawaban dan melalui tulisan singkat ini, saya hendak memberikan pengantar singkat mengenai konsep trinitas melalui sejarah bapa–bapa gereja kapadokia.
Bapa-Bapa Kapadokia: Menjembatani Dua Ekstrim
Sejarah terbentuknya ajaran trinitas bermula dari usaha umat kristen abad perdana untuk menjelaskan posisi dan signifikansi sosok bernama Yesus dari Nazaret dalam kepercayaan mereka. Mengapa hal ini penting? Karena bagi umat kristen abad perdana, agama tidak hanya berperan sebagai kompas moral pribadi semata. Narasi agama juga menjadi semacam ‘kacamata’ atau worldview yang dipakai umatnya untuk memandang dan mengambil sikap dalam seluruh aspek hidup, termasuk politik, sosial, ekonomi, dll. Kita tahu bahwa Yesus dan sebagian besar umat kristen abad perdana adalah orang Yahudi dan menganut Yudaisme (agama Yahudi) yang berasaskan monoteisme, sebagaimana tertulis dalam Ulangan 6:4 atau yang juga dikenal dengan Shema Yisrael. Shema Yisrael adalah doa yang senantiasa diucapkan dalam ibadah Yudaisme setiap pagi dan petang hari. Bagi orang Yahudi, Shema Yisrael memiliki peran sentral, bukan hanya dalam ibadah dan liturgi saja, melainkan menjadi dasar nasionalisme Yahudi sebagai bangsa, suatu penanda identitas yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Kembali ke persoalan posisi Yesus, pada satu sisi, tradisi monoteisme Yahudi mensyaratkan mutlak hanya ada satu Allah yang patut disembah, yaitu YHWH, Allah Israel yang disembah oleh Musa, Ishak, dan Yakub. Di sisi lain, umat kristen abad-abad awal menilai bahwa perkataan dan klaim-klaim Yesus memiliki nilai otoritas yang lebih, bahkan dibandingkan dengan para nabi pendahulunya. Sebagai contoh, para nabi dalam Perjanjian Lama senantiasa memulai pesannya dengan titah ‘beginilah Firman Tuhan’, ‘demikianlah Firman Tuhan’, dan semacamnya. Dengan kata lain nabi hanyalah penyampai pesan Tuhan dan sama sekali tidak memegang otoritas atasnya. Sedangkan Yesus, alih-alih bertindak sebagai penyampai pesan, ia malahan berulang kali mengucap ‘kamu telah mendengar Firman…., tetapi Aku berkata kepadamu’. Bahkan dalam surat-suratnya, rasul Paulus dengan jelas menempatkan Yesus di posisi YHWH dalam formula Shema Yisrael. Seperti dalam surat 1 Korintus 8:3-6, berbunyi demikian:
8:3 Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah.
8:4 Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu: “tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain dari pada Allah yang esa.”
8:5 Sebab sungguhpun ada apa yang disebut “allah”, baik di sorga, maupun di bumi–dan memang benar ada banyak “allah” dan banyak “tuhan” yang demikian
8:6 namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari pada-Nya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh-Nya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup.
Selain dua hal tersebut, jemaat kristen perdana juga harus berhadapan dengan ideologi dominan saat itu, yaitu filsafat dan agama-agama Yunani, seperti gnostisisme yang perlahan mencoba memengaruhi pola pikir masyarakat awam. Gnostisisme berasal dari kata gnostic yang berarti rahasia, artinya pengetahuan tertinggi yang ‘rahasia’ hanya dapat diakses oleh segelintir orang. Gnostisisme juga menekankan bahwa tubuh atau yang material hanyalah cangkang dari jiwa atau ide yang dianggap lebih superior secara substansi. Dalam situasi inilah, gereja-gereja perdana mencoba merumuskan kaitan antara sentralitas figur Yesus dari Nazaret dan monoteisme Yahudi.
Usaha ini tentunya tidak mudah dan menimbulkan perbedaan pendapat yang sengit bahkan memengaruhi kehidupan bermasyarakat di zamannya (sebagaimana uraian di atas bahwa agama berperan sebagai worldview). Salah satu perdebatan besar yang terjadi pada abad ke 3 dan 4 masehi, adalah perdebatan menanggapi Arianisme, suatu ajaran yang dicetuskan oleh Arius (256-336 M), dimana Yesus adalah ciptaan Allah (Bapa), dan oleh karenanya, Yesus berbeda secara substansi dan lebih rendah derajatnya dibanding Allah (Bapa). Yang menjadi masalah dari konsep ini adalah apabila Yesus itu ciptaan belaka, maka Yesus (yang disebut sebagai Firman dalam Alkitab), tidak dapat menjalankan perannya sebagai Firman. Dalam terminologi agama-agama samawi, firman adalah objek yang menjembatani antara yang transenden dan imanen, antara yang immaterial dan material, karena bagi agama-agama abrahamik (Yudaisme, Kristen, dan Islam), tanpa melalui firman, adalah mustahil bagi manusia yang fana untuk bisa memahami Tuhan yang kekal dan tak terpahami.
Pasca Konsili Nicea Pertama, dimana salah satu pernyataan pentingnya adalah “Putra Allah (dan Roh Kudus) adalah se-hakikat (homoousios) dengan Allah (Bapa)”, perdebatan mengenai Arianisme tidak serta-merta surut. Bahkan di tahun 377 M, setelah wafatnya kaisar Constantine, kontroversi Arianisme meluas dalam konflik gereja barat (gereja-gereja berbahasa Latin) dan gereja timur (gereja-gereja berbahasa Yunani) mengenai dominannya pengaruh Romawi yang pro gereja barat dan penggunaan istilah ‘hipostasis’ ala pemikiran Yunani yang dianggap ambigu. Di sinilah tiga pemikir yang begitu dihormati, baik di kalangan barat dan timur, mengambil peran untuk merekonsiliasikan perbedaan pendapat di kedua ekstrim. Tiga sekawan inilah (Basil dari Caesarea, Gregory dari Nyssa, dan Gregory dari Nazianzus) yang disebut sebagai Bapa-Bapa Kapadokia.
Melalui kemampuan penulisan dan argumentasinya, Bapa-Bapa Kapadokia mencetuskan rumusan yang mengafirmasi ‘hipostasis’ sebagai yang plural dalam ke-Tuhan-an sekaligus menekankan kembali kesamaan hakikat (homoousios) Allah. Rumusan inilah yang dikenal luas hari ini dengan konsep trinitas atau Allah Tritunggal. Bahwa ada tiga pribadi dan satu Allah.
“Singkatnya, Saya katakan bahwa esensi (ousia) senantiasa terkait dengan pribadi (hypostasis) sebagaimana yang umum terkait dengan yang partikular. Setiap kita punya bagian dalam eksistensi karena Dia (Allah) berbagian dalam ousia sementara karena Dia adalah pribadi, maka Dia adalah A atau B. Jadi, ousia mengacu kepada konsepsi yang lebih umum, seperti kebajikan, ketuhanan, dan semacamnya, sementara hypostasis dijumpai dalam atribut yang lebih partikular seperti ke-bapa-an, ke-putra-an, and kuasa pengudusan. Adalah mustahil membicarakan pribadi tanpa hypostasis; Tetapi jika mereka mengakui bahwa yang berpribadi hadir dalam hypostasis, sebagaimana yang mereka akui saat ini, itu pun adalah bagian dari menjaga prinsip kesatuan esensi dalam ketuhanan, sekaligus menyatakan kekaguman mereka kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam hypostasis yang lengkap dan sempurna dari tiap pribadi.” [1]
Trinitas dan Implikasinya
Tak diragukan lagi, ajaran mengenai trinitas adalah salah satu ajaran fundamental dalam teologi Kristen. Signifikansi trinitas tidak hanya berperan sebagai abstraksi dari yang imaniah, lebih dari itu, pemahaman akan trinitas juga menjadi kacamata yang melaluinya, seluruh umat kristiani melihat seluruh aspek hidup. Dalam kacamata trinitas, Tuhan memilih dikenali secara personal melalui yang material dan menubuh, dan implikasinya jelas bahwa yang material dan menubuh adalah penting dan bukan sekadar ekstensi dari yang ideal. Hari-hari ini, ketika ada sistem tertentu yang secara objektif dan kasat mata menindas manusia dan melecehkan tubuh, maka kekristenan wajib hadir secara konkrit menjawab permasalahan tersebut.
Dalam kacamata trinitas pula, Allah yang dihayati umat kristen senantiasa dikenali melalui dan di dalam relasinya dengan Firmannya dan Rohnya. Gagasan ini pun turut mewarnai percakapan teologi kristen hari ini dalam kajian bernama Social Trinitarianism[2]. Dalam kerangka Social Trinitarianism, karena Allah bersifat relasional, maka segenap realitas senantiasa mengacu kepada model relasional, oleh karena itu Allah secara inheren senantiasa berdimensi sosial. Allah yang esa di dalam kerangka trinitas tidak dapat dipahami sebagai objek ontologis. Bapa dapat dikenal melalui Firman berimplikasi bahwa Allah bukanlah pribadi yang netral dan bebas kepentingan. Di tengah kenaifan liberalisme hari ini, yang percaya bahwa seseorang bisa bebas dari keberpihakan, narasi trinitas bahwa Allah adalah pribadi yang relasional, mendorong orang kristen untuk secara sadar berpihak kepada yang dipihaki oleh Kerajaan Allah, yaitu mereka yang miskin, tertindas, dan tak bisa bersuara.
Cara pandang trinitarian juga punya implikasi bahwa ideologi/narasi besar senantiasa dipahami melalui yang konkrit dari ideologi itu sendiri, sebagaimana Allah yang hanya bisa dipahami melalui Firman yang se-hakikat dengan Allah sekaligus konkrit. Ketika pemerintah hari ini berupaya menggaungkan ide ‘Kesaktian Pancasila’ maupun ‘NKRI Harga Mati’ yang seolah-olah ‘mutlak dari sononya’, maka cara pandang trinitarian mengajak kita untuk kritis dan curiga terhadap sebentuk ide besar yang tidak memiliki basis material dan tidak bisa dipertanggungjawabkan historisitasnya. Kekristenan yang trinitarian menolak percaya begitu saja pada suatu ideologi tanpa melihat genealoginya.
Maka dari itu, kemendesakan akan kerangka teologi yang lebih material sama sekali bukan tindakan reaksioner yang lahir karena satu-dua isu semata, melainkan konsekuensi logis dari cara pandang trinitarian. Bahwa dari hal yang fundamental pun, kekristenan tidak diam menjadi penonton dari sejarah dunia. Kekristenan senantiasa memanggil umat untuk turut bergerak, untuk terjun bersama Allah mewujudkan tatanan dunia yang berkeadilan dan mendatangkan shalom, damai sejahtera bagi seluruh umat manusia.***
Penulis adalah aktivis Diskusi Selasaan, sebuah kegiatan diskusi teologi yang diadakan rutin setiap Selasa malam pukul 19:00 WIB di Jl. Guntur No. 15, Jakarta Selatan.
————
[1] Basil of Caesarea Epistles. 214.4.
[2] Bandingkan Moltmann, Jürgen (1981). The Trinity and the Kingdom: The Doctrine of God. Fortress Press. ISBN 978-1-4514-1206-2.