KINI Indonesia kembali dipimpin oleh rezim developmentalis, yang mengingatkan kita pada masa-masa-masa Orde Baru, tentu dengan varian yang berbeda. Kata ‘Pembangunan’, semenjak rezim Jokowi, kembali mengemuka sebagai sebuah wacana dominan. Pemerintahan Jokowi terlihat bergairah sekali untuk melaksanakan pembangunan ini. Kita dapat melihat, salah satunya dari anggaran APBN, di mana pada tahun 2017 anggaran infrastruktur akan mencapai Rp387.3 triliun[1]. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp70,2 triliun dari tahun sebelumnya. Jika membandingkan dengan rezim sebelumnya, ini merupakan sebuah angka yang memiliki peningkatan relatif besar. Lebih lanjut, dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016[2], dicanangkan terdapat 225 proyek strategis nasional. Menyebut beberapa dari proyek-proyek pembangunan tersebut: 47 pembangunan ruas jalan tol, 11 pembangunan sarana dan pra sarana kereta api antar kota, 6 pembangunan infrastruktur kereta api dalam kota, 10 proyek revitalisasi bandar udara, 4 pembangunan bandar udara baru, 12 pembangunan pelabuhan, 59 pembangunan bendungan, 24 pembangunan kawasan industri, dan beberapa proyek lainnya.
Tidak berhenti di situ, pada tahun ini diwacanakan akan ditambah 78 proyek strategis nasional baru[3]. Tidak boleh pula dilupakan bagaimana Presiden Jokowi bahkan hingga begitu sering turun langsung ke lapangan untuk mengecek pembangunan proyek-proyek tersebut dan memastikan semua berjalan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan, mengindikasikan betapa pembangunan-pembangunan ini menjadi perhatian serius presiden. Berbagai proyek-proyek pembangunan tersebut ini—jika berhasil terimplementasi, dan karenanya nampak penting sekali bagi pemerintah untuk menyingkirkan segala “hambatan”—akan menjadi sebuah legacy dari Presiden Jokowi yang luar biasa, setidaknya secara kuantitatif. Namun, benarkah pembangunan selalu akan membawa kemaslahatan? Atau, dalam konteks tertentu, justru bisa sebaliknya?
Pertama-tama klaim kemaslahatan tersebut akan dapat dibantah jika kita merujuk kepada data Konsorsium Agraria Nasional (2016)[4], yang pada tahun 2016 saja terdapat sebanyak 450 konflik agraria, yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan ekses dari pembangunan tersebut. Tetapi bukan perihal ini yang akan menjadi fokus bahasan pada artikel ini.
Saya akan mencoba mendalami pertanyaan di atas dengan melihat dari perspektif lain yang jarang disentuh oleh para ekonom arus utama. Dalam hal ini, ilmuan politik James C. Scott[5] memberikan sebuah perspektif yang penting namun seringkali terlupakan: perspektif mereka-mereka yang tinggal jauh dari pusat-pusat kekuasaan negara, mereka-mereka yang berada di “pelosok”[6] negeri. Scott menelusuri kehidupan dan sejarah beberapa kelompok masyarakat yang tinggal di pelosok Asia Tenggara daratan—yang ia katakan bahwa corak yang sama juga akan ditemukan di tempat lain, termasuk Indonesia—dan menemukan bahwa kelompok masyarakat lokal tersebut bukan hanya memiliki corak sosial-budaya tersendiri yang unik seperti yang jamak diketahui. Tetapi mereka juga memiliki suatu sistem ekonomi sendiri, yang berbeda dengan sistem ekonomi yang dominan yang berlaku.
Kalimat terakhir ini perlu untuk digarisbawahi, yakni bahwa beberapa kelompok masyarakat pada tingkat lokal memiliki “suatu sistem ekonomi sendiri”, dan ia berbeda dengan sistem ekonomi yang dominan yang mana pada hari ini, dalam konteks Indonesia dan dunia pada umumnya, adalah ekonomi pasar. Untuk itu saya perlu menggunakan sebuah terma untuk keperluan analisis pada artikel ini, yang akan dinamakan ‘ekonomi “yang lain”’ (dan kita akan sering menggunakan bentuk jamak ‘ekonomi-ekonomi “yang lain”’ karena keberadaannya yang bervariasi pada berbagai kelompok masyarakat lokal), yang dapat didefinisikan sebagai “suatu sistem ekonomi yang hidup dan bekerja pada masyarakat di tingkat lokal yang menggunakna rasionalitas serta sistem kerja yang berbeda dengan sistem ekonomi dominan yang berlaku”. Perlu diberi catatan di sini, bahwa ekonomi dominan yang dimaksud tidak hanya bisa merujuk kepada ekonomi pasar semata, ekonomi komando pada negara-negara komunis di masa sebelum akhir Perang Dingin juga dapat dikategorikan ke dalam ekonomi dominan tersebut, yang mana pada negara-negara tersebut sistem ekonomi komando yang menempati posisi dominan di atas ekonomi-ekonomi “yang lain” yang ada pada kelompok-kelompok masyarakat lokal. Sedangkan penggunaan kata “yang lain” bukan untuk menempatkan sistem-sistem ekonomi tersebut pada posisi yang tingkat kepentingannya lebih rendah, melainkan untuk membangun pemahaman bahwa sistem ekonomi yang dominan berlaku pada hari ini bukanlah satu-satunya, tetapi sesungguhnya eksis (dengan berbagai variasinya dan spekturm perbedaan) sistem-sistem ekonomi di samping yang dominan itu, yang hidup dan bekerja pada kelompok-kelompok masyarakat di tingkat lokal (karenanya menggunakan tanda “..”). Oleh karena itu terma ini menjadi penting karena ekonomi-ekonomi “yang lain” tersebut sungguh jarang—jika tidak sama sekali—disadari terlebih dicoba dipahami oleh pemerintah ataupun akadamisi ekonomi kebanyakan. Dengan terma ini maka kini dapat dibangun pembedaan antara ‘ekonomi dominan’ dan ‘ekonomi-ekonomi “yang lain”’ tersebut untuk memahami eksistensi sistem-sistem ekonomi di luar sistem ekonomi dominan (pasar).
Absennya kajian terhadap keberadaan dan juga cara kerja dari sistem-sistem ekonomi “yang lain” dalam literatur-literatur ekonomi pada umumnya dapat dipahami karena ilmu ekonomi menganggap dirinya sebagai sebuah ilmu yang saintifik, dan karenanya beranggapan bahwa apa yang kini disebut ‘ekonomi’ adalah sesuatu yang mengandung kebenaran objektif dan bebas nilai. Begitulah yang dijelaskan oleh Arturo Escobar (1994)[7], dan karenanya ia membangun kritikan terhadap itu dengan berargumen bahwa kelahiran ilmu ekonomi sendiri sesungguhnya merupakan hasil dari suatu diskursus wacana. Untuk memahaminya, Escobar menelusuri sejarah perkembangan ilmu ekonomi dan menyatakan bahwa ilmu ekonomi sendiri adalah sebuah wacana yang mulai dikembangkan pasca berakhirnya Perang Dunia Ke-2[8], bermula dari dunia Barat setelah berakhirnya era kolonialisme atas berbagai jajahannya, dan kemudian disebarkan dengan berbagai cara seperti dengan institutionalisasi ilmu ekonomi dengan pembentukan berbagai institusi ekonomi global ataupun pada level nasional di negara-negara berkembang dengan asistensi negara-negara Barat. Dengan jalan menempatkan ekonomi sebagai sebuah wacana ini[9], maka konsekuensinya adalah dapat terbuka pemahaman-pemahaman baru atas apa yang kita kenal sebagai ‘ekonomi’, yang jarang terbahas dalam literatur-literatur utama ekonomi yang beranggapan ekonomi adalah objektif dan bebas nilai. Dengan begitu etidaknya dua konsekuensi pemahaman yang dapat ditarik dari sini.
Pertama, dengan menempatkan ekonomi sebagai wacana, maka (ilmu) ekononomi yang kita kenal sekarang sesungguhnya adalah sebuah wacana yang sedang mendominasi saja; dengan kata lain—mengutip Escobar[10]—“sesungguhnya di dunia ini eksis dan terus eksis model-model ekonomi yang lain” dan dengan menambahkan catatan: “yang tidak kalah saintifik” dibandingkan model ekonomi yang saat ini mendominasi. Dengan begitu, terbuka pintu bagi kita untuk menulusuri, menganalisis, hingga membangun model-model serta teori-teori dari ilmu ekonomi “yang lain” tersebut.
Konsekuensi kedua, dengan menempatkan ekonomi sebagai wacana, maka kita akan dapat melihat bahwa terdapat kontestasi antara wacana-wacana ekonomi yang ada, yang mana kekuatan atau kekuasaan (power) yang akan menentukan siapa yang akan mendominasi dan siapa yang harus menyingkir. Dengan begitu ekonomi pasar yang kini dominan merupakan wacana yang sedang “menang” dalam kontestasi tersebut, dan wacana ekonomi-ekonomi “yang lain” adalah wacana yang sedang harus menyingkir dan hanya hidup di pelosok-pelososk negerti yang jauh dari pengaruh kekuasaan. Maka pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan perspektif ini dapat dipandang sebagai perluasan pengaruh penguasaan dari wacana ekonomi pemenang tersebut.
Kedua poin konsekuensi dari pewacanaan ekonomi tersebutlah yang akan menjadi pembahasan pada dua bagian berikutnya: Yaitu, apa dan bagaimana sesungguhnya sistem ekonomi-ekonomi “yang lain” tersebut? Dan bagaimana menyikapi pembangunan dari pemerintah (yang berarti perluasan ekonomi dominan) dengan menempatkan diri dari perspektif ekonomi “yang lain”?
Memahami Keberadaan Ekonomi “Yang Lain”
Mencari seperti apa dan bagaimana rasionalitas dan sistem kerja (terlebih model dan teori) dari ekonomi-ekonomi “yang lain” pada buku-buku teks ekonomi arus utama akan sangatlah sulit—jika tidak mengatakan tidak ada. Namun penjelasan atas sistem-sistem ekonomi tersebut bukannya tidak ada, praktik ekonomi “yang lain” pada kelompok-kelompok masyarakat lokal dalam batas tertentu bisa kita dapatkan dalam karya-karya penelitian antropologi. Penelusuran kehidupan dari budaya lokal dalam penelitian etnografi mereka, sedikit banyak membuka pula penjelasan akan praktik-praktik ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat lokal, yang dapat dipahami perbedaannya dengan praktik yang berlaku pada ekonomi dominan; meski memang sulit atau belum dapat ditemukan model-model atau teori yang menjelaskan sistem-sistem ekonomi tersebut sebagaimana yang telah begitu banyak tersedia dan matang pada sistem ekonomi dominan. Meski begitu ada pula penelitian antropologi yang berfokus kepada perihal kehidupan ekonomi “yang lain” dari masyarakat lokal, yang dapat kita ambil sebagai contoh untuk gambaran praktik ekonomi “yang lain” ini.
Salah satu contoh tersebut adalah dari antropolog Belanda Jacqueline Vel, dalam bukunya “Ekonomi-Uma: Penerapan adat dalam dinamika ekonomi berbasis kekerabatan[11]”, yang melakukan penelitian terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Desa Lawonda di Sumba, Nusa Tenggara TImur. ‘Uma’ berarti “rumah-rumah [tradisional] yang menunjuk pada kelompok-kelompok sosial keturunan dari pasangan suami-istri yang telah mendirikan ‘rumah induk’ (uma kalada)[12]”, tetapi di samping itu uma juga merujuk kepada kesatuan sosial yang bersifat komunal. Di atas uma, terdapat kabihu yang bisa diartikan sebagai klan. Dalam sistem ekonomi “yang lain” di sana, tanah dan sumber dayanya dimiliki secara kolektif oleh tiap-tiap kabihu yang akan dimanfaatkan secara kolektif oleh tiap kabihu[13]. Oleh para tetua adat melalui musyawarah, kemudian ditentukan pembagian tanah untuk usaha pertanian dan mengatur tugas bagi masing-masing anggota uma. Pembagian tugas tersebut didasarkan pada pembedaan menurut gender, generasi, dan status sosial secara tradisional[14]. Dengan tanah yang dimiliki secara kolektif oleh kabihu atau uma, yang kemudian digarap dengan pembagian kerja kolektif dari para anggota, roda ekonomi-uma dari masyarakat Lawonda berputar untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Namun di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh uma dan kabihu, atau pertukaran kebutuhan-kebutuhan pribadi di dalam kabihu, masyarakat Lawonda akan melakukan pertukaran. Akan tetapi pertukaran yang dilakukan berbeda dengan paradigma pertukaran yang biasa dilakukan dalam ekonomi pasar. Mereka melakukan pertukaran berdasarkan apa yang dinamakan oleh Vel sebagai “moralitas pertukaran[15]”, di mana tata cara serta tingkatan (level) pertukaran akan berbeda ditentukan berdasarkan jarak sosial, yang oleh Vel diidentifikasi ke dalam tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah ‘kita-kita’ untuk pertukaran kepada sesama anggota kabihu. Pada tingkat ini mereka melakukan transaksi dengan cara saling berhutang secara umum; sebuah cara transaksi yang sangat tidak wajar bagi orang luar Lawonda. Tetapi di sana, saling berhutang ini justru menjadi suatu simbol ikatan yang sangat dalam antara kedua orang yang bertransaksi dan transaksi dilakukan bukan sekadar untuk mencari keuntungan, tetapi menjadi ”jaminan terbaik bagi keterjaminan sosial seseorang dan bagi kelangsungan hidup dari unit sosial yang lebih luas (dimana) orang itu terhisab”[16]. Dalam suatu cerita yang dikutip Vel, bahkan orang Lawonda berterimakasih kepada orang yang telah menolongnya dalam suatu kesulitan dengan cara meminta uang untuk berhutang kepada nya, bukan dengan ucapan terimakasih[17]. Pada tingkat kedua, terdapat jarak sosial ‘bukan orang lain’ yang biasanya terjadi antara orang pada kabihu yang berbeda, tetapi telah ada ikatan-ikatan khusus seperti melalui pernikahan antara anggotanya. Pada tingkat ini, mereka melakukan transaksi dengan pinjaman terperinci atau barter secara langsung. Adapun transaksi dengan menggunakan uang (jual-beli) seperti yang sangat umum pada ekonomi pasar, justru terjadi hanya kepada ‘orang lain’ atau bahkan ‘lawan’ (secara tradisional). Dalam hal ini mereka menggunakan uang, tetapi ini merupakan simbol ketiadaan ikatan sosial yang kuat atau bahkan pertentangan antara pihak yang bertransaksi. Karenanya transaksi ini hanya dilakukan kepada orang luar Lawonda (termasuk membayar pajak ke negara) serta kepada anggota kabihu lain yang bertikai dan bukan menjadi aktivitas ekonomi yang utama.
Contoh dari ekonomi “yang lain” atas masyarakat Lawonda memberikan kita sebuah gambaran bagaimana sesungguhnya eksis suatu sistem ekonomi yang bekerja berdasarkan rasionalitas dan sistem kerja yang berbeda, yang mungkin sulit dipahami oleh orang yang terbiasa hidup dalam lingkungan ekonomi pasar. Hal-hal yang dianggap “rasional” dan “sudah semestinya” pada masyarakat yang hidup dalam lingkungan ekonomi pasar, seperti rasionalitas akumulasi kekayaan, komodifikasi sumber daya alam dan tenaga kerja, transaksi dengan menggunakan uang, atau kepemilikan pribadi atas properti, ternyata tidak berlaku bagi mereka. Tetapi itu bukan berarti menandakan bahwa mereka terbelakang dengannya (mengenai terbelakang atau tidak ini tentu dibutuhkan kesepakatan indikator), jika dilihat dari keberlanjutan kehidupan, dengan sistem seperti itu terbukti mereka dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya dan dengan sifat komunalitasnya tidak ada anggota yang akan dibiarkan tidak berdaya. Dan sistem-sistem ekonomi “yang lain” seperti contoh pada Lawonda itu dapat diperkirakan eksis pula pada masyarakat-masyarakat lokal lainnya, tentu dengan keunikannya masing-masing, yang sesungguhnya dapat kita katakan sebagai sebuah “kemajemukan ekonomi”.
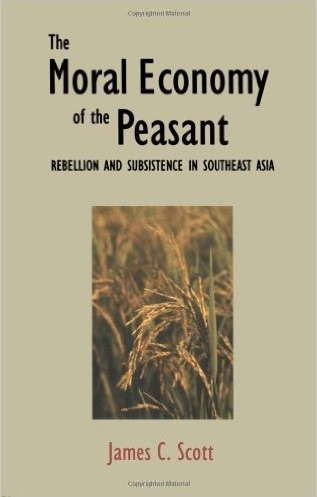
Namun bagaimana dan bisakah pola-pola perekonomian “yang lain” tersebut dijelaskan dalam analisis-analisis ekonomi? Upaya untuk memodelkan ekonomi “yang lain”, yang berbeda dengan ekonomi pasar yang dominan telah diupayakan oleh beberapa kalangan, meski belum seluas ekonomi dominan. Yang cukup berpengaruh dari situ dapat kita sebut James C. Scott dengan bukunya yang menjadi klasik, “The Moral Economy of the Peasant” (1976)[18]. Analisis yang lebih sophisticated oleh Elinor Ostrom[19], yang berhasil membawa terma the commons (atau sumber daya yang dimiliki secara kolektif oleh suatu kelompok masyarakat) yang banyak ditemui pada sistem-sistem ekonomi “yang lain” pada masyarakat lokal ke dalam diskusi ekonomi formal. Scott dan Ostrom secara kebetulan berlatar belakang ilmuan politik, bukan ekonomi.
Scott membangun model argumen tentang ekonomi moral yang bekerja pada petani-petani di perdesaan. Menurutnya, perekonomian mereka bekerja bukan atas keinginan untuk “mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya”, seperti yang seringkali dijadikan asumsi dasar yang menjadi fondasi teori-teori ekonomi pasar (dan karenanya ia menyebut banyak perilaku ekonomi petani yang sulit dipahamai dengan pisau analisis ekonomi pasar), tetapi mereka menjalankan ekonominya berdasarkan apa yang ia sebut moralitas subsisten dan resiprokal. Menurutnya, petani lebih mementingkan kehidupan subsistennya, yakni keterjaminan pemenuhan kebutuhan hidup dengan resiko minimal ketimbang berupaya mencari keuntungan sebesar-besarnya tetapi mengandung resiko yang membawa mereka ke bawah garis subsisten untuk bertahan. Dan karena itu pula, mereka juga membangun hubungan resiprokal (timbal balik) di antara sesama untuk suatu jaminan kehidupan untuk saling membantu di saat masa-masa sulit (menghilangkan resiko). Penjelasan ini secara terbatas dapat menjelaskan sistem transaksi berhutang dan barter yang berdasarkan kekerabatan yang ada pada contoh masyarakat Lawonda di atas.
Sedangkan Ostrom berkontribusi dalam membangun penjelasan ekonomi atas kepemilikan sumberdaya secara kolektif oleh masyarakat. Dengan menggunakan perangkat analisis game theory dan analisis institusi, Ostrom membangun argumen bahwa untuk menghindari the tragedy of commons dalam penggunaan sumber daya alam, solusi terbaik bukan terdapat pada hak kepemilikan (property rights) model ekonomi pasar yang individual, pun juga bukan pada model hak kepemilikan oleh negara seperti pada negara-negara sosialis dan komunis. Keberlanjutan (sustainability) atas pemanfaatan sumberdaya alam justru dapat tercapai dengan model hak kepemilikan secara kolektif oleh masyarakat, seperti yang dianut oleh masyarakat-masyarakat tradisional lokal dengan ekonomi “yang lain” nya, termasuk contoh masyarakat Lawonda di atas. Ostorm melanjutkan bahwa hal tersebut dapat terjadi dengan persyaratan: adanya institusi lokal yang bekerja dengan baik. ‘Baik’ di sini didefinisikan sebagai institusi yang memenuhi prinsip-prinsip desain institusi yang ia identifikasi, yaitu sumberdaya yang batas-batasnya terdefinisi dengan jelas, pemanfaatan yang sesuai dengan kondisi lokal, adanya pilihan kolektif melalui partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan, monitoring yang efektif, sanksi gradual atas pelanggaran kesepakatan (aturan), mekanisme konflik resolusi, dan self-determination atas kelompok masyarakat pemilik sumberdaya tersebut yang diakui oleh otoritas. Maka masyarakat-masyarakat lokal yang telah memiliki institusi (adat) yang matang dan memenuhi prinsip-prinsip di atas, secara teoritis sesungguhnya sanggup mengelola, memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya alam secara lebih efisien dan sustainable.
Akan tetapi meski telah terdapat upaya-upaya, pemahaman terhadap ekonomi-ekonomi “yang lain” tersebut masih sangat minim dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan terhadap ekonomi-ekonomi yang dominan (entah kiri atau kanan). Ketidakpahaman akan sistem perekonomian yang eksis pada masyarakat-masyarat lokal tersebut, membuat berbagai kebijakan dan aksi yang diambil oleh rezim hanya berdasarkan pertimbangan dari perspektif ekonomi dominan (dalam konteks Indonesia: pasar) yang bisa jadi bukan membawa maslahat melainkan merusak tatanan lokal yang telah ada, karena sesungguhnya—dengan mewacanakan ekonomi—wacanan-wacana ekonomi tersebut berkontestasi satu sama lainnya, kontestasi yang seringkali tidak seimbang.
Menyikapi Pembangunan
Maka dari itu kita perlu untuk melihat konsekuensi pemahaman yang kedua dari menempatkan ekonomi sebagai wacana ini, yaitu bahwa “kemajemukan ekonomi” atau keberadaan ekonomi-ekonomi “yang lain” dengan segala kekayaan variasinya tersebut yang ada pada masyarakat-masyarakat lokal seperti yang dijelaskan di atas, sesungguhnya berada dalam kontestasi wacana ekonomi secara tidak seimbang dengan wacana ekonomi “raksasa” yang dominan saat ini, yakni ekonomi pasar. Dan pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pintu masuknya: pembangunan berarti perluasan lingkup pengaruh (kekuasaan) ekonomi dominan terhadap ekonomi-ekonomi “yang lain” yang masih hidup di berbagai pelosok negeri, di saat kelompok masyarakat di pelosok-pelosok tersebut bisa jadi telah memiliki institusi ekonominya tersendiri (yang bekerja berdasarkan model dan teori dari ekonomi “yang lain”) dan hidup bersahaja dengannya. Pembangunan yang membawa serta wacana ekonomi pasar akan menekan keruntuhan sistem-sistem ekonomi “yang lain” dengan segala institusi pendukungnya dan menyerap mereka ke dalam sistem ekonomi dominan (pasar) tersebut. Masyarakat lokal yang mungkin selama ini hidup berkecukupan secara bersahaja bisa jadi justru mengalami kesukaran luar biasa karena tidak dapat survive pada lingkungan sistem ekonomi yang baru (pasar) dan harus mengikuti logika-logika nya. Maka menjawab pertanyaan yang diajukan di awal, pembangunan menurut perspektif orang-orang “pelosok” tidak selalu membawa kemaslahatan, dan justru bisa jadi sebaliknya.
Meski begitu, saya tidak ingin membawa kepada romantisme ekonomi lokal. Kita harus memahami pula bahwa ekonomi “yang lain” pada masyarakat lokal bukan berarti pasti merupakan sistem yang terbaik yang menjamin kesejahteraan kepada seluruh masyarakatnya dan membawa keadilan sosial. Kembali mengambil contoh masyarakat Lawonda dari Jacqueline Val, dalam sistem ekonomi-uma mereka, ada kelas-kelas sosial yang mana dalam strutkur ekonomi politiknya terdapat juga golongan bangsawan yang tidak bekerja secara nyata[20] tetapi menjadi pemilik, sedangkan orang-orang golongan bawah yang bekerja membajak sawah dan mengurus ternak untuk kemudian hasil-hasilnya dibagi berdasarkan aturan-aturan kolektif untuk “kesejahteraan bersama”. Maka dalam sistem ekonomi-ekonomi “yang lain” bisa jadi pula terdapat ketidakadilan sosial dan eksploitasi suatu kelas terhadap kelas lainnya.
Adanya kontestasi dan penekanan terhadap ekonomi-ekonomi “yang lain” melalui pembangunan, juga tidak lantas membawa kita kepada kesimpulan bahwa pembangunan adalah tidak perlu dan harus dihentikan, ini akan menjadi kesimpulan yang terburu-buru. Pembangunan dapat pula membawa kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak dapat diberikan oleh sistem ekonomi lokal mereka seperti fasilitas-fasilitas sosial, kesehatan, atau pendidikan, juga infrastrutur-infrastruktur untuk menunjang dan memudahkan kehidupan. Juga merupakan kekeliruan berdasarkan romantisme jika kita menganggap bahwa pada masyarakat lokal tersebut dengan sistem ekonomi “yang lain” nya dianggap statis dan tidak mengalami perubahan. Mereka juga mengalami perubahan dan karenanya juga berhak untuk menikmati kemajuan-kemajuan yang telah diciptakan oleh peradaban manusia. Maka ini sesungguhnya menjadi suatu dilema yang tidak sederhana, dan menjadi perdebatan pada tataran filosofis (yang tidak dimaksudkan diselesaikan pada artikel singkat ini).
Namun dengan demikian, lantas bagaimana kita menyikapi pembangunan? Inilah yang menjadi tantangan yang harus dijawab. Karenanya pemahaman atas keberadaan ekonomi-ekonomi “yang lain” tersebut harus dilanjutkan dengan perumusan model-model dan teori-teori ekonomi yang bekerja dalam wacana ekonomi-ekonomi lokal tersebut; atau dengan kata lain, model dan teori yang tidak bias ekonomi dominan (pasar). Dan dengan begitu kemudian dapat dirumuskan model pembangunan yang tepat, yang membawa kemaslahatan dan peningkatan kualitas hidup tanpa merusak tatanan-tananan ekonomi lokal yang telah bekerja dengan dan mesti dipertahankan, sembari mengubah tatanan-tananan ekonomi lokal yang merugikan kehidupan masyarakat lokal di sana. Ini perlu menjadi agenda penelitian-penelitian ke depannya.
Tetapi untuk saat ini, di tengah keterbatasan pemahaman atas ekonomi-ekonomi “yang lain” tersebut, jawaban terbaik sejauh ini yang dapat diberikan oleh teori-teori perencanaan pembangunan adalah dengan menerapkan “communicative turn” dalam pembangunan melalui model-model pembangunan partisipatif—dengan segala variannya[21]. Pendekatan ini berusaha mengurangi ekses negatif dari pembangunan dan berusaha melestarikan sistem-sistem yang ada pada masyarakat dengan cara melibatkan mereka dalam pembangunan: masyarakat lokal menjadi subjek atas pembangunan. Pendekatan ini menghargai masyarakat sebagai subjek yang dinamis, bukan statis, tetapi perubahan tersebut bukan dengan penekanan dari atas yang mana justru membawa serta merta sistem dominan dan menekan sistem-sistem lokal yang telah bekerja. Yang dilakukan adalah masyarakat lokal menentukan nasibnya sendiri mengenai apa, bagaimana, dan seberapa besar perubahan akan dilakukan melalui pembangunan tersebut. Model pembangunan seperti inilah yang sesungguhnya telah coba diupayakan melalui program-program seperti PNPM Mandiri dan UU Desa. Tetapi sepertinya Presiden Jokowi lebih menyukai pembangunan melalui projek-projek besar secara langsung oleh pemerintah yang hasilnya dapat terlihat langsung. Maka keberadaan ekonomi-ekonomi “yang lain” dan kehidupan masyarakat lokal yang bergantung kepadanya patut untuk dikhawatirkan.***
Penulis adalah Peneliti tamu di Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University
———–
[1] http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017, diakses pada 2 Maret 2017
[2] PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
[3] http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170210120827-78-192592/pemerintah-tambah-78-proyek-strategis-nasional/, di akses pada 26 Februari 2017.
[4] http://www.kpa.or.id/news/blog/kpa-launching-catatan-akhir-tahun-2016/, diakses pada 2 Maret 2017. Angka ini meningkat drastis dari jumlah konflik tahun lalu yang sejumlah 252 konflik agraria (sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria. Catatan Akhir Tahun 2015. 2015)
[5] Lihat Scott, James C.. The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia. 2009. Yale University Press.
[6] Pelosok di sini dalam artian jarak pengaruh dari pusat-pusat kekuasaan ekonomi politik negara, bukan jarak geografi. Meski begitu jarak geografi tentu akan berkolerasi dengan penyebaran pengaruh.
[7]Escobar, Arturo. Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. 1994. New Jersey: Princeton University Press
[8] sebelumnya yang lebih berkembang adalah ilmu ekonomi politik.
[9] Yang Esobar terhadap ilmu ekonomi, khusunya ekonomi pembangunan (berdasarkan paparan Esobar sendiri dalam bukunya) adalah mirip dengan apa yang dilakukan oleh Edward Said terhadap “ilmu” orientalisme (lihat Said, Edward. Orientalism.1978. New York: Random House, Inc.), yang dengan menempatkan Orientalisme sebagai wacana, sehingga dapat disadari bahwa orientalisme bukanlah sebuah ilmu yang objektif dan bebas nilai, tetapi sarat dengan nilai-nilai dominasi Barat terhadap belahan dunia lainnya.
[10] Escobar (1976), hlm. 62
[11] Vel, Jacqueline. Ekonomi-Uma: Penerapan adat dalam dinamika ekonomi berbasis kekerabatan. 2010. Jakarta: HuMa-Jakarta; Van Vollenhoven Institute, Leiden University; KITLV-Jakarta
[12] Id., hlm. 68; lihat juga hlm. 12
[13] Id., hlm. 175
[14] Id., hlm. 140
[15] Id., hlm. 67; lihat juga hlm. 88
[16] Id., hlm. 15
[17] Id., hlm. 65
[18] Scott, James C.. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. 1976. New Haven and London: Yale University Press
[19]Ostrom, Elinor. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. 1990. Cambridge: Cambridge University Press. Untuk penjelasan-penjelasan lainnya dari Ostorm mengenai the commons, lihat: Ostrom dkk (1994) Rules, Game, and Common-pool Resources; Ostrom, E. And Ostrom, E. (2005) Understandng Institutional Diversity; Dolsak, N. dan E. Ostrom (edt.) (2003) The Commons in the New Millennium; Ostrom, E. (2012) The Future of the Commons
[20] Lihat: Vel (2010), hlm. 77 dan 145.
[21] Lihat misalnya: Healey, P. Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies. 1997. Vancouver: UBC Press; Woltjer, J. Consensus Planning: The relevance of communicative planning theory in Dutch infrastructure development. 2000. Ashgate Pub Ltd dan lain-lain; juga dalam beberapa artikel jurnal seperti: Baiocchi, G. (2001) Participation, Activism, and Politics: The Porto Alegre Experiment and Deliberative Democratic Theory; Fischer, F. (2006) Participatory Governance as Deliberative Empowerment: the Cultural Politics of Discursive Space; Gupta, M.D., dkk (2006) State-Community Synergies in Community-Driven Development; dan lain-lain.






