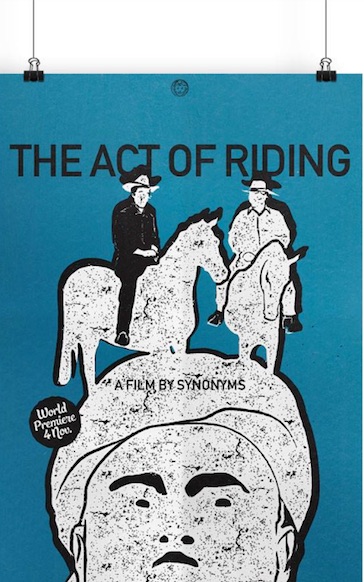Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)
DALAM artikel Merebut Populisme tanggal 30 Januari 2017, Muhammad Ridha menanggapi artikel saya Menguatnya Populisme: Trump, Brexit hingga FPI sekaligus artikel Bonnie Setiawan Ahok Melawan: Apa yang Sebenarnya Terjadi?. Tanggapan saya di artikel ini terbatas pada komentar Ridha pada artikel saya; komentar untuk Bonnie tentu lebih tepat dijawab oleh Bonnie sendiri.
Saya dan Ridha sepakat pada satu hal besar: bahwa retorika populis kanan yang sekarang berkembang memiliki karakter rasis dan bisa mengarah ke fasisme. Pada akhirnya, ini adalah bahaya bagi demokrasi. Tulisan Ridha sudah maju beberapa langkah dengan mengajukan solusi dan agenda aksi. Intinya adalah bagaimana gerakan sosialisme harus merebut narasi populisme.
Ada beberapa hal dari artikel Ridha yang akan saya tanggapi balik.
Pertama, Ridha melihat artikel saya memiliki keterbatasan epistemologi. Saya sepakat dengan penilaian ini. Meski pertanyaanya adalah, adakah tulisan – apalagi dalam format artikel – yang tidak memiliki keterbatasan epistemologi. Bagi saya, sebuah artikel adalah satu dari banyak titik, atau satu keping dari gambar acak. Hanya setelah kita menghubungkan titik-titik itu atau menyusun kepingan-kepingan, barulah gambaran yang utuh akan didapat.
Artikel saya adalah satu dari banyak cara pandang dalam melihat fenomena seperti kemenangan Brexit, Trump. Dari cara pandang yang spesifik itu saya coba melihat kesamaan dengan apa yang terjadi di Indonesia, dengan bungkus yang berbeda tapi punya isi yang sama. Ketika saya memilih sebuah cara pandang, itu seperti pilihan tempat duduk di konser dimana panggung berada di tengah. Saya yang duduk di dekat pemain drum bisa menjelaskan dengan fasih seperti apa penampilan si pemain drum. Namun perspektif saya terhadap pemain gitar menjadi terbatas. Ini bukanlah perkara sengaja atau tidak, tapi konsekuensi dari posisi yang saya pilih.
Oleh karena itu, bahwa artikel saya “mengabaikan peminggiran sistematis kekuatan sosial dalam masyarakat yang ada yang difasilitasi oleh institusi demokrasi itu sendiri” seperti Ridha katakan, bukan masalah sengaja atau tidak. Ini adalah bagaimana kita melihat satu fenomena dari berbagai sudut pandang, dan bagaimana kita membandingkan berbagai sudut itu.
Kedua, Ridha memberi catatan bahwa tesis cultural backlash yang saya ajukan sebagai bingkai dalam menjelaskan menguatnya populisme adalah “mengulang posisi Huntington tentang Benturan Peradaban.” Ini tidak sepenuhnya akurat.
Kalau kita ingat, konstruksi tesis Benturan Peradaban dimulai dari preposisi bahwa ‘kultur itu penting’ (culture matters). Sampai di sini, dan hanya sampai di sini, artikel saya sejalan dengan Huntington. Selanjutnya Huntington berpendapat bahwa pola konflik pasca Perang Dingin akan diwarnai oleh konflik terkait kultur atau nilai-nilai. Peradaban, lanjutnya, adalah bentuk agregasi dari kultur.
Lewat beberapa eksposisi, ia lalu mengajukan tesis bahwa nilai-nilai demokrasi yang dibawa oleh peradaban Barat-Judeo-Kristen akan mengalami benturan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh peradaban lain. Secara spesifik Huntington menyebut konflik antara peradaban Barat dan Islam akan menjadi arena konflik yang baru.
Ada banyak dukungan dan sanggahan atas tesis Huntington, yang di luar lingkup artikel saya. Tapi secara implisit, artikel saya justru menunjukkan keterbatasan dari tesis Huntington: ia mengesampingkan faktor benturan internal di dalam satu peradaban (clash within civilization). Di peradaban Barat sendiri, seperti saya tulis, masih ada pertentangan antara nilai-nilai konservatif dan kosmopolitan liberal. Terlihat dari perdebatan soal imigrasi, LGBT, feminisme, perubahan iklim, untuk menyebut beberapa isu.
Benturan nilai-nilai juga terjadi di dalam dunia Islam, meski untuk memetakan itu agak lebih rumit. Ada perseteruan abadi Sunni dan Syiah. Di dalam Sunni dan Syiah juga ada pertarungan sendiri antara liberal dan konservatif. Di Indonesia ada diskursus soal Islam kultural dan Islam politik.
Singkatnya, tidak tepat untuk menggunakan bingkai benturan peradaban untuk melihat argumen di artikel.
Meski demikian, menarik untuk mengaitkan menguatnya populisme ala Brexit dan Trump dengan buku Huntington tahun 2004, “Who Are We?” Di situ Huntington berpendapat bahwa Amerika adalah sebuah kuali (melting pot) dimana berbagai kultur bertemu. Tapi di dalam kuali berbagai kultur berbeda itu melebur dengan kultur yang selama ini menjadi penyangga identitas masyarakat Amerika yaitu Anglo Saxon Protestan. Huntington mengutarakan kekuatirannya bahwa identitas itu semakin tergerus oleh arus imigran yang mempertahankan kultur yang dibawa dan tidak berusaha melebur di kuali identitas.
Buku ini mendapat reaksi keras terutama dari kelompok liberal yang pro-imigrasi. Menurut mereka, konsep melting pot perlu dipertanyakan relevansinya dan Amerika mungkin lebih menyerupai mangkuk salad dimana berbagai kultur menyatu tanpa kehilangan identitas masing-masing. Saya masih tidak bisa setuju dengan pendapat Huntington. Tapi di sisi lain perdebatan yang terjadi di tahun 2004 itu ternyata masih terus terjadi. Bahkan menangnya Trump yang membawa ide kebijakan anti imigran bisa dibilang menjadi serangan balik atas gagasan ‘Amerika sebagai mangkuk salad’ yang terbuka pada imigran dan multikulturalisme.
Ketiga, Ridha menulis, “tidak ada yang alamiah (baca: esensial) dari identitas atau kebudayaan suatu masyarakat. Asumsi Huntingtonian yang diusung Ari perlu untuk dikubur selama-lamanya karena asumsi esensialis ini.” Ini perlu penjelasan lebih jauh. Asumsi (atau maksudnya tesis?) Huntingtonian mana yang dimaksud? Jika yang dimaksud adalah tesis terkait benturan peradaban, seperti saya jelaskan sebelum ini, artikel saya justru menunjukkan keterbatasan dari tesis itu.
Atau yang ditolak adalah asumsi Huntingtonian bahwa culture matters? Saya tidak ingin berspekulasi tentang apa yang Ridha maksudkan, jadi saya akan membiarkan ini sebagai sebuah pertanyaan. Hanya satu hal. Klaim bahwa sebuah asumsi atau tesis “perlu dikubur selama-lamanya” menyiratkan sebuah arogansi intelektual; atau bahkan sikap anti intelektual. Sebuah teori, hipotesis, asumsi, bahkan spekulasi, tidak perlu dikubur. Jika ia tidak relevan atau tidak teruji, ia akan terpinggirkan dengan sendirinya. Sebaliknya jika ia masih dianggap relevan, ia akan terus dibicarakan.
Yang membuat Huntington masih relevan bukanlah kebenaran prediksinya. Tapi ia memberi sebuah bangunan hipotesis yang mendorong orang terus mempertanyakan dan mengujinya. Dalam banyak hal ia keliru. Tapi kita tidak bisa tahu dia keliru atau tidak jika sejak awal kita memilih untuk mengubur pemikirannya ketimbang mempertanyakan.
Keempat, harus saya akui, artikel saya belum masuk ke tawaran solusi. Di sini saya sangat mengapresiasi Ridha yang sudah coba menawarkan solusi dan agenda ke depan. Ridha menyerukan untuk merebut populisme, dan mengisinya dengan artikulasi politik sosialis yang lebih inklusif.
Saya tidak dalam posisi untuk mendukung atau menyanggah tawaran itu. Tapi jika populisme hendak direbut, tentu kita perlu paham: dari siapa ia direbut, siapa yang akan merebut, dan untuk siapa? Jika ditarik ke kondisi Indonesia, kita perlu pemetaan yang lebih jelas, siapa saja yang mengusung narasi populis Islam-kanan; kelompok mana yang mendukung, dan mengapa?
Ridha merujuk pengalaman kampanye Bernie Sanders di AS dan Jeremy Corbyn di Inggris sebagai contoh penerapan artikulasi politik sosialis. Ini bisa diperluas dengan melihat bagaimana partai kiri Eropa seperti Syriza di Yunani dan Podemos di Spanyol menjadi seperti anomali tengah menguatnya populisme kanan. Apakah mereka konsiten dan cukup berhasil membawa agenda-agenda sosialis, atau menjadi lebih pragmatis.
Jangan lupakan juga Amerika Latin. Kondisi Venezuela sekarang perlu dikaji dengan kepala dingin, apakah itu menunjukkan keberhasilan atau kegagalan eksperimen populisme kiri Chavez. Bandingkan juga dengan Michelle Bachelet di Chile dan Lula Brazil yang bisa menggabungkan retorika kiri dengan manajemen makroekonomi yang disiplin.
Artikel saya, sekali lagi, lebih merupakan observasi awal. Ada banyak perkembangan yang perlu kita ikuti ke depan untuk kita bisa lebih memahami ke mana arah menguatnya populisme kanan. Di bagian akhir artikel, saya menuliskan tiga hal yang bisa ditindaklanjuti oleh studi yang lebih mendalam. Tentu ada banyak lagi pertanyaan yang bisa diajukan.
Untuk itulah kita perlu perspektif yang cukup beragam, tidak tunggal, untuk melihat fenomena ini.***
Penulis adalah mantan pengajar FEUI, sekarang tinggal di Manila, Filipina