Mitrardi Sangkoyo, Mahasiswa Ilmu Politik UI dan anggota Serikat Mahasiswa Progresif (SEMAR) UI
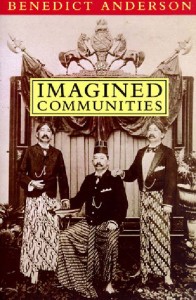
Judul Buku : Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism [revised, extended edition]
Penulis : Benedict Richard O’Gorman Anderson
Penerbit : Verso
Kota Terbit : London
Tahun Terbit : 1983, 1991
Tebal : xvi + 224 halaman
Pendahuluan: “…ingat apa yang telah dikorbankan…”
If you’re going to be killed you invent some kind of flag and country to fight for, and if you survive you get to love the thing.
—Franklin P. Scudder kepada Richard Hannay. John Buchan, The Thirty-Nine Steps (1915).
DALAM kurang dari tiga abad terakhir, keberadaan bangsa, dan belakangan negara-bangsa; istilah, relasi, dan konflik berbasis ke-bangsa-an; serta kekuatan perekat misterius yang mudah terbakar yang dinamakan nasionalisme, semakin merajalela. Kesulitan dan ambiguitas analitis kerap menghantui proses mendefinisikan dan menganalisis fenomena-fenomena di atas. Selain itu, terdapat perbedaan-perbedaan sikap dan posisi ideologis dalam upaya memahami dan menempatkan masing-masing dalam dinamika (dan pertarungan) sosial menyejarah. Kendati demikian, tak dapat diragukan bahwa masing-masing posisi dan sikap berhasil memperoleh tempat penting sebagai diskursus, entitas politis, unit analisis, maupun nilai universal yang tak terpisahkan dari disiplin-disiplin ilmu dan realitas sosial-politis.
Realitas-realitas tersebut tak hidup dan berkembang secara ‘kering’ pada ranah intelektual dan akademis semata. Perkembangan material menyejarah dari hal-ihwal nasion dan nasionalisme turut mencengkeramkan cakar-cakarnya pada ruang-ruang kesadaran, imajinasi, dan emosi kolektif manusia yang terdalam, sehingga—kendati sering tertempa dalam kondisi-kondisi yang sarat-penderitaan, kebengisan, dan eksploitasi—mampu memanifestasikan diri dalam ekspresi-ekspresi romantisme dan kecintaan yang terkandung dalam beragam produk budaya, dan, secara mengherankan serta kadang tak masuk akal, pengorbanan jiwa.
Ekspresi-ekspresi tersebut, dalam spektrumnya yang majemuk, tak sulit untuk kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu contoh yang menarik, mutakhir, dan cukup representatif untuk keperluan analisis kita: pada tanggal 10 November 2015, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan-cum-Jenderal TNI (Purnawirawan) dan mantan anggota Kopassus, Luhut Binsar Pandjaitan, menulis sebuah renungan dalam akun Facebook-nya perihal pertempuran yang dahulu dialaminya di Timor Timur, antara Kopassus dan pasukan Timor Timur. Berikut cuplikannya:
Di hari Pahlawan ini, saya teringat kejadian di tanggal 7 Desember 1975. Waktu itu saya bersama dengan anak buah saya diterjunkan di Timor-Timur. Kami adalah prajurit-prajurit Detasemen Tempur Kopassandha (sekarang Kopassus) … Hari itu, 8 anak buah saya gugur hanya dalam 2 jam pertempuran.…
Itulah pengorbanan-pengorbanan mereka untuk bangsa dan negara ini. Mereka tidak pernah tanya untuk apa ini. Saya dan Anda bisa menjadi seperti ini sekarang, menikmati ini semua, itu karena pengorbanan pahlawan-pahlawan kita. Maka dari itu, saya dan Anda harus ingat apa yang telah dikorbankan oleh mereka.
Saat itu kita tidak pernah bertanya kau dari mana, suku apa kamu, agama apa kamu. Yang selalu saya tanyakan kepada mereka adalah “kau siap atau tidak ?”. Pertanyaan ini juga terus mewarnai perjalanan hidup saya. Saya tidak pernah bertanya kau dari mana, sukumu apa, agamamu apa.…
Melalui kesempatan ini, ijinkan saya sekali lagi bertanya kepada Anda: Indonesia akan menjadi Negara yang besar, Kau siap atau tidak?[1]
Renungan tersebut tentu mengacu pada terapan doktrin-komando angkatan bersenjata dalam konteks historis Orde Baru yang militeristik dan, terkait Operasi Seroja, imperialis, sehingga mustahil kita samaratakan sebagai ‘bentuk nasionalisme’ yang setiap orang Indonesia ‘miliki’ secara seragam. Kendati demikian, di dalamnya tertera dengan terang-benderan beberapa elemen yang simtomatis dari logika yang secara inheren dapat hadir dalam nasionalisme: tumpah-ruah dengan pengorbanan-diri untuk bangsa(-)dan(-)negara (“itulah pengorbanan-pengorbanan mereka untuk bangsa dan negara ini”) dalam bentuk elan yang tak kenal kompromi (“Mereka tidak pernah tanya untuk apa ini”; “Melalui kesempatan ini, ijinkan saya sekali lagi bertanya kepada Anda: Indonesia akan menjadi Negara yang besar, Kau siap atau tidak?”); konstruksi kesatuan narasi sejarah-kolektif dalam tuturan ke-bangsa-an, yang terdenileasi melalui kematian (“Saya dan Anda bisa menjadi seperti ini sekarang, menikmati ini semua, itu karena pengorbanan pahlawan-pahlawan kita. Maka dari itu, saya dan Anda harus ingat apa yang telah dikorbankan oleh mereka”); serta konsepsi identitas diri yang mampu melampaui konsepsi-konsepsi identitas menyejarah lainnya (“Saat itu kita tidak pernah bertanya kau dari mana, suku apa kamu, agama apa kamu”)—seluruhnya dibungkus secara khidmat dengan nuansa romantisme yang kental, meluap-luap dengan emosi.[2]
Lantas, apa sebenarnya makhluk yang bernama bangsa dan nasionalisme, dan bagaimana wujud logikanya? Mengapa hanya dalam beberapa abad terakhir, tercermin melalui perang dan pembunuhan, jutaan manusia rela mengorbankan nyawa demi bangsa, tanah air, zǔguó (Cina), sokoku (Jepang), Eretz Ha’Avot (Yahudi), Patrie (Perancis), heimat, Vaterland (Jerman), dan sebagainya? Mengapa, dalam elan kesinisan maupun perlawanan terhadap rezim pemerintah yang dirasakan tak adil, seseorang bisa saja mengucap ‘negara tidak ada’—namun, orang yang sama dapat riang-ria manakala menyaksikan tim nasional sepakbola mengalahkan lawan mancanegara, bahkan ketika dia sebelumnya tak pernah peduli dengan olahraga tersebut (tentunya diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan)? Apakah ada korelasi positif antara nasionalisme dan rasisme? Apakah betul bahwa nasionalisme merupakan produk tunggal Eropa, dan muncul karena adanya “pola pikir yang khas Eropa”? Bagaimana basis material dari proses-proses terbentuknya bangsa dan nasionalisme dalam konteks ruang-waktu yang beragam namun spesifik-konteks? Bagaimana kedudukan (gerakan-gerakan) nasionalisme vis-à-vis relasi (dan kontradiksi) kelas dalam perkembangan kapitalisme?
Subjek-subjek pembahasan dari pendahuluan di muka—termasuk proses penulisan ulang narasi sejarah nasional yang turut mengonsolidasi identitas dan kesadaran nasional; kekuatan yang dimiliki nasionalisme untuk dapat menggugah jiwa-raga penganutnya; posisinya sebagai inovasi historis yang unik; serta inti bahasan pertanyaan-pertanyaan di paragraf sebelumnya—dikemukakan, dibedah, dan dituturkan secara memeka dan didaktik oleh almarhum Benedict Richard O’Gorman Anderson, profesor emeritus di Cornell University yang mengajar Kajian Internasional, Pemerintahan (termasuk disiplin Pemerintahan Komparatif), dan Kajian Asia, dalam bukunya yang berjudul Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.
Pertama-tama, tinjauan ini berusaha menyajikan secara rinci tesis, argumen dan premis dari Imagined Communities, yang dibagi menjadi beberapa bagian tematik. Alih-alih hanya menyarikan secara padu beberapa abstraksi dan argumen paling pokok dari keseluruhan subjek pembahasan, tinjauan ini menyajikan alur berpikir dan proses terbentuknya argumen-argumen tersebut secara lebih mendalam. Pilihan format penulisan ini tidak tanpa pertimbangan: dalam refleksi yang dituliskannya pada tahun 2008, Anderson mengakui bahwa “banyak orang telah mengeluh kepada saya bahwa [Imagined Communities] merupakan buku yang sulit, dan terutama sangat sulit untuk diterjemahkan.”[3] Dalam pengantar untuk edisi revisi dari Imagined Communities, Anderson juga terkejut dan menyayangkan bahwa dalam banyak tanggapan terhadap buku tersebut, pembaca cenderung mengabaikan beberapa argumen dan penemuan penting (h. xiii). Harapan saya, tinjauan ini dapat membantu pembaca memahami secara lebih menyeluruh dan kohesif alur logika dari berbagai argumen dan sikap yang dituturkan, terutama pembaca yang belum pernah membaca Imagined Communities atau membaca tapi belum tuntas.
Bagian pertama tinjauan ini—tinjauan itu sendiri—terdiri dari ‘Relevansi dan Tujuan Pengkajian’, ‘Kerangka Ontologis’, ‘Perubahan Akar-akar Kultural-historis’, ‘Nasionalisme dan Perkembangan Kapitalisme-percetakan’, ‘Genealogi dan Perkembangan Empat Model Nasionalisme [nasionalisme-creole, nasionalisme-populer, nasionalisme-resmi, dan nasionalisme-kolonial]’, dan ‘Legitimasi Emosional’. Bagian tersebut dilanjutkan dengan bagian kedua, yang berisi saduran dari berbagai kritik, otokritik dan refleksi, serta tanggapan dan dialog intelektual tentang ke-bangsa-an menyusul terbitnya Imagined Communities, terutama yang dirangkum oleh Castells (refleksi terhadap kontekstualisasi kontemporer dari ke-bangsa-an di tengah perkembangan dan perubahan sosial-politis global, beserta tesis-tesis para pengomentar), Chatterjee (kritik terhadap tesis Anderson dalam semangat pascakolonial), Blaut (‘persoalan nasional (the national question)’ dalam kerangka teoritis Kiri serta berbagai permasalahan dan usulan teoritisnya), dan Anderson sendiri. Terakhir adalah komentar hasil bacaan pribadi, dan beberapa titik kontekstualisasi dan pertanyaan yang dianggap relevan.
Sebelumnya, izinkan saya menuliskan sepatah dua patah kata renungan pribadi.
Saya bersyukur punya kesempatan berkawan dan belajar secara langsung dengan Om Ben yang penyayang dan baik hati. Melalui kasih sayangnya, Om Ben melakukan ‘agitprop’ lunak pada semangat dan imajinasi anak kelas 1 SMP. Pada masa tersebut, Om Ben memperkenalkan saya pada Tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer, serta serial fiksi mata-mata Perang Dunia Pertama karya John Buchan.[4] Secara bersamaan, Om Ben mengajak saya melahap habis seluruh koleksi film anime karya Studio Ghibli (Om Ben terutama gemar My Neighbor Totoro dan Porco Rosso). Om Ben doyan memakan sayur kale, mie rebus instan bermerek Neoguri, nasi dengan teri goreng, dan roti bakar dengan selai jeruk.
Kendati pernah mengajar ilmu politik selama 35 tahun, saat saya mengabarkan padanya melalui surel pada tahun 2011 bahwa saya diterima di jurusan ilmu politik, tanggapan Om Ben menggambarkan secara paripurna selera humor, ketajaman berpikir, dan kerendahan hatinya: “Dear Mitra, Astagafirullah, Kok [m]asuk djurusan poli-tikus!! Alias sub-djurusan biologi! Untuk ber[s]ukses d[a]l[a]m ilmu ini, perlu sekali: humor, kepintaran d[a]l[a]m hal plesetan dan satir[,] optimism tjampur pesimisme!”
Tulisan ini diniatkan sebagai refleksi pembelajaran; panggilan untuk belajar bersama melawan perusakan, menolak lupa, serta memulihkan kerusakan. dan terakhir, wujud sulang kecil in memoriam orang besar. Semoga bermanfaat untuk manusia dan alam.
Relevansi dan Tujuan Pengkajian
Bagaimana Anderson mulai membayangkan struktur tulisan Imagined Communities? Apa yang telah dan tengah terjadi di dunia pada saat itu? Bagaimana rona dari lanskap intelektual dan akademis menjelang 1983 terkait subjek pembahasan buku tersebut, dan apakah ada korelasinya dengan terbentuknya rangkaian tesis dan argumen yang dituturkan?
Imagined Communities diawali dengan pengamatan terhadap beberapa rangkaian fenomena global perihal pentingnya menggugat ‘bangsa’ dan ‘nasionalisme’. Pertama, Anderson mengamati bahwa pada saat itu, tengah terjadi transformasi fundamental dalam sejarah Marxisme dan gerakan-gerakan Marxis, yang bermanifestasi dalam perang-perang di Indocina yang melibatkan Vietnam, Kamboja, dan Cina, mulai tahun 1978 dan 1979.[5] Bagi historiografi Marxis, perang-perang tersebut memiliki signifikansi historis yang meresahkan: masing-masing negara yang berperang adalah negara merdeka yang memiliki sejarah revolusioner, namun tak berupaya menjustifikasi agresi militer mereka berdasarkan perspektif teoritis Marxis (h. 1).
Kedua, perang-perang di Indocina mengonfirmasikan kekekalan kontemporer dari nasionalisme dalam paruh-akhir abad ke-20: Anderson mengamati bahwa sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, setiap revolusi yang berhasil dijalankan mendefinisikan diri melalui istilah-istilah nasional, dan para pelaku revolusi mengakarkan diri pada wilayah teritorial dan sosial yang diwarisi dari kondisi pra-revolusi.[6] Anderson mengutip Eric Hobsbawm, sejarawan Marxis berkebangsaan Inggris, bahwa gerakan dan negara Marxis kian berwujud dan bersubstansi nasionalis—“sebuah tren yang kemungkinan besar akan terus berlangsung.” Tren tersebut tak hanya berlaku pada konteks sosialis: Perserikatan Bangsa-Bangsa rutin mengakui dan menerima bangsa-bangsa baru, dan banyak ‘bangsa tua’ yang sebelumnya diperkirakan sudah terkonsolidasi secara mapan, kini ditantang oleh ‘sub’-nasionalisme dalam wilayahnya sendiri. Kesimpulan pertama Anderson perihal fenomena nasionalisme kontemporer adalah bahwa nasionalisme merupakan nilai yang secara universal paling sah dalam kehidupan politis dimasa hidup kita (h. 3).
Ketiga, Anderson menganalisis bahwa nasionalisme merupakan anomali dalam teori Marxis, yang sejauh itu belum benar-benar dikonfrontasi. Padahal, Anderson melihat bahwa Marx dan Engels secara implisit menyinggung perihal ‘persoalan nasional’ dalam Manifesto Komunis (1848), yang dikutip Anderson sebagai berikut: “Kaum proletar di tiap-tiap negara harus, tentunya, pertama-tama menyelesaikan urusannya dengan kaum borjuisnya sendiri.”[7] ‘Borjuasinya sendiri’ menurut Anderson merujuk pada konteks nasional. Kendati demikian, Anderson menyayangkan penggunaan konsep ‘borjuasi nasional’ tanpa upaya serius pada saat itu untuk menjustifikasi secara teoritis relevansi dari adjektiva ‘nasional’ tersebut.
Belakangan, pada tahun 2008, Anderson merangkai ulang tujuan penulisan Imagined Communities menjadi tiga kontra-argumen:
- menyanggah Eurosentrisme yang berasumsi bahwa nasionalisme lahir di Eropa, lalu bergerak menyebar ke segala penjuru dunia (seperti yang nanti akan dijelaskan, Anderson melacak asal-usul gerakan nasionalisme pertama ke Amerika Utara dan Selatan dan Haiti);
- mengkritik tradisi Marxisme klasik yang gagal menerapkan pendekatan Marxis dalam melihat fenomena berkembangnya nasionalisme, serta mengkritik liberalisme klasik yang gagal pula secara serupa (Anderson menerapkan pendekatan materialis dalam melihat implikasi dari kapitalisme-percetakan sebagai salah satu basis material dalam proses diseminasi kesadaran nasional); dan
- menolak bahwa nasionalisme hanya merupakan sebuah ‘-isme’: murni sebagai suatu rangkaian ide, atau ideologi (penjelasan tersebut gagal menjelaskan mengapa dan bagaimana nasionalisme mampu memiliki ‘legitimasi emosional’ yang begitu menggigit hingga menyebabkan manusia rela mengorbankan nyawa).[8]
Kerangka Ontologis
Bagaimana mendefinisikan dan mengabstraksikan bangsa dan relasi-relasinya? Jika menurut Anderson nasionalisme bukanlah laksana ‘-isme’ lain, apakah ada penjelasan definitif yang dapat memuaskan dahaga analitis kita?
Berdasarkan berbagai pengamatan dan keresahan di muka, Anderson menuturkan kerangka ontologisnya sendiri untuk bangsa dan nasionalisme, dalam rangka mengajukan usulan alternatif bagi ‘anomali-anomali’ tersebut. Pertama, Anderson mengusulkan titik-berangkat tipologis: nasionalitas, ke-bangsa-an, dan nasionalisme merupakan artefak-artefak kultural yang spesifik.
Dalam rangka memahaminya, kita perlu:
- mempertimbangkan secara teliti proses pembentukan historisnya, serta bagaimana terjadinya perubahan makna darinya seiring berjalannya waktu; dan
- mempertanyakan mengapa artefak-artefak tersebut kini memiliki kekuatan dominatif, yang oleh Anderson dinamakan ‘legitimasi emosional’.
Secara umum, artefak-artefak kultural tersebut terbentuk menjelang akhir abad ke-18, diakibatkan oleh “distilasi spontan dari persilangan kekuatan-kekuatan historis yang kompleks, yang, begitu terwujud, menjadi ‘modular’, mampu ditransplantasikan dengan beragam tingkatan kesadaran-diri ke lanskap-lanskap sosial yang beraneka ragam”, untuk kemudian “melebur dan dileburkan dengan beragam konstelasi politis dan ideologi” (h. 4).
Kedua, Anderson menuturkan tiga paradoks inheren dalam nasionalisme yang senantiasa menghantui:
- dalam pandangan sejarawan, bangsa memiliki sifat modernitas yang objektif, sedangkan dalam mata nasionalis, bangsa memiliki sifat kekunoan yang subjektif;
- sebagai konsep sosio-kultural, nasionalitas memiliki universalitas formal (setiap manusia modern ‘memiliki’ nasionalitas, sebagaimana ‘memiliki’ gender), sedangkan sebagai manifestasi konkret, nasionalitas memiliki partikularitas mutlak (sui generis pada tiap-tiap bangsa);
- kendati memiliki kekuatan politis, nasionalisme juga mengendapkan kemiskinan-dan-ketakjelasaan filosofis.
Terkait tiga paradoks tersebut, Anderson menulis bahwa kesalahan ontologis yang fatal pada masanya adalah upaya membayangkan nasionalisme sebagai ‘Nasionalisme-dengan-N-besar’, dan kemudian mengklasifikasikannya sebagai suatu ideologi; menurutnya, nasionalisme lebih dekat dengan ‘kekerabatan’ dan ‘religi’ alih-alih ‘liberalisme’ atau ‘fasisme’ (h. 5).
Ketiga, Anderson menawarkan definisi bangsa sebagai komunitas politis-terbayang (“an imagined political community”), dan terbayang sebagai hal-ihwal yang secara inheren terbatas dan berdaulat. Alur logika argumennya dapat dituturkan sebagai berikut:
- bangsa terbayangkan karena anggota sebuah bangsa, bahkan bangsa terkecil sekalipun, mustahil mengenal, bertemu, atau mengetahui kabar seluruh anggota lainnya—kendati demikian, dalam kesadaran setiap anggota bangsa tersebut terdapat imaji dari persatuan mereka;[9]
- bangsa terbayangkan sebagai hal-ihwal terbatas karena setiap bangsa memiliki perbatasan yang terbatas (kendati elastis), yang memisahkannya dengan bangsa-bangsa lain;
- bangsa terbayangkan sebagai hal-ihwal berdaulat karena konsep bangsa lahir dalam konteks Abad Pencerahan dan Revolusi, yang tengah mencabik-cabik legitimasi wilayah dinasti-hierarkis berbasis keilahian, dengan kedaulatan sebagai lambang kebebasan baru pada masa tersebut;
- bangsa terbayangkan sebagai komunitas karena, kendati realitas ketimpangan dan eksploitasi yang hadir di dalamnya, bangsa selalu dibayangkan sebagai kekerabatan-horizontal yang mendalam (h. 5–7).
Perubahan Akar-akar Kultural-historis
Jika, sebagaimana dinyatakan dalam pendahuluan, bangsa dan nasionalisme baru merebak dalam tiga abad terakhir, apakah ia lahir spontan dan manasuka pada abad ke-18, ataukah ada konteks dan faktor lebih kuno yang mengakar dan melatarbelakangi kemunculannya? Sejauh mana kita perlu menarik mundur pandangan dalam lintasan sejarah?
Nasionalisme tak terbentuk dalam ruang hampa, alih-alih lahir di tengah proses transformasi dan antagonisme dalam relasi sosial dan kuasa yang berlaku pada dua sistem kultural terdahulu—komunitas religius dan dunia dinastik—akibat perubahan ekonomi, ‘penemuan-penemuan’ sosial dan ilmiah, serta kemajuan dalam bidang komunikasi yang ritmenya bertambah cepat (h. 36). Anderson menganalisis bahwa nasionalisme dikondisikan untuk berkembang manakala tiga konsepsi kultural yang fundamental dan kuno mengalami perubahan dan kehilangan ‘cengkeraman aksiomatis’-nya pada kesadaran manusia, seiring terbenamnya rezim mode-berpikir berbasis Agama di Eropa Barat pada Abad Pencerahan dan Revolusi, serta lahirnya mode-berpikir rasionalitas-sekuler (‘penemuan’ sosial), yang berkulminasi pada abad ke-18 (h. 11).[10] (Perlu dicatat bahwa perubahan tersebut tidak deterministik-absolut: nasionalisme tidak secara kausal dihasilkan oleh (perubahan pada) faktor-faktor di atas, melainkan secara parsial dikondisikan untuk dapat lahir dari proses transformasi pada relasi kuasa masyarakat yang secara historis menyanggahnya.)
Konsepsi pertama adalah ide bahwa sebuah bahasa-teks memberikan akses eksklusif-cum-sahih terhadap kebenaran ontologis, sebagai kesatuan yang tak terpisahkan dari kebenaran tersebut (ketakmanasukaan lambang; ideografis). Mendasari konsepsi tersebut adalah konsepsi tentang yang bersifat sentripetal dan hierarkis, alih-alih horizontal dan berorientasi pada batas. Anderson mengamati bahwa komunitas-komunitas religius pada era klasik—Ummat Islam yang terbentang dari Maroko hingga Kepulauan Sulu, Ummat Nasrani dari Paraguay hingga Jepang, dan dunia Buddha dari Sri Lanka hingga semenanjung Korea—secara kosmologis menganggap diri masing-masing sebagai titik-pusat, dan keberadaan mereka dapat terbayangkan melalui medium bahasa dan teks tertulis yang sakral. Bahasa-kebenaran (truth language) sebagai sistem representasi hadir melalui bahasa Latin Gereja, bahasa Arab Klasik Qur’an, dan bahasa Cina Eksaminasi (h. 12–16).
Kedua adalah kepercayaan bahwa masyarakat terorganisir mengelilingi, dan berada di bawah bayang-bayang dari, titik-titik pusat dalam rupa monarki yang berkuasa melalui dispensasi ilahi. Monarki-dinastik memiliki watak relasi kuasa sebagai berikut, yang menurut Anderson bertolak belakang dengan konsepsi modern tentang kehidupan berpolitik:
- mode spasialitas politis yang mana wilayah-kuasa didefinisikan oleh titik-pusat, perbatasan bersifat berpori dan kabur, dan wilayah-wilayah secara tak kasatmata saling melebur satu sama lain;
- legitimasi politis yang bersumber dari keilahian, alih-alih rakyat;
- konsepsi keanggotaan yang bersifat penghambaan (subjects) alih-alih kewarganegaraan; dan
- ekspansi politis yang dioperasikan tak hanya melalui perang, tetapi juga melalui politik seksual (kawin-mawin antardinasti untuk tujuan berekspansi, mempertahankan relasi kuasa) (h. 19–21).
Konsepsi ketiga, yang menurut Anderson paling signifikan dan fundamental di antara yang lain terhadap dimungkinkannya membayangkan sebuah bangsa, adalah perihal temporalitas yang berakar pada doktrin agama, di mana kosmologi dan sejarah tak dapat dibedakan satu sama lain, dan asal-usul dunia dan manusia secara esensial serupa: bentuk keserentakan antara masa lalu dan masa depan yang hadir dalam masa kini yang acap, atau, dalam bahasa Walter Benjamin, ‘waktu-Messianic’. Konsepsi temporalitas tersebut kemudian tergantikan oleh (lagi-lagi memakai istilah Walter Benjamin) ‘waktu homogen-kosong (homogenous, empty time)’. Keserentakan menjadi bersifat lintang-waktu; alih-alih ditakdirkan, kini merupakan kebetulan-temporal yang terukur melalui jam dan kalender, dan tercermin dalam dua komoditas kapitalisme-percetakan, yakni novel[11] dan koran,[12] yang merupakan cara-cara teknis untuk merepresentasikan bangsa sebagai bentuk komunitas-terbayang (h. 22–32).
Pada akhirnya, koherensi komunitas religius mulai membenam sejak akhir Abad Pertengahan akibat:
- efek penjelajahan ke dunia non-Eropa, yang menambah luas cakrawala kultural, geografis, dan imajinasi manusia perihal bentuk-bentuk kehidupan, serta menanamkan benih-benih relativitas dan pengavelingan kepercayaan; dan
- terpuruknya bahasa sakral secara bertahap akibat muncul dan berkembangnya kapitalisme-percetakan, yang pada akhirnya menjadikan bahasa-bahasa sakral Kuno—terutama Latin—mengalami fragmentasi, pluralisasi, dan pengavelingan, antara lain akibat konfrontasi dengan berbagai bahasa-rakyat (vernacular) di Eropa.
Sementara itu, kendati—di tengah merebaknya gerakan-gerakan nasionalis pada abad ke-18—dunia dinastik mampu menangguhkan kematian ‘formal’-nya hingga memasuki abad ke-20, berbagai perubahan relasi sosial masyarakat akibat berkembangnya kapitalisme dan lahirnya mode-mode berpikir yang baru menyebabkan diskursus dan logika nasionalisme mampu meresap dan menginfiltrasi logika dinastik (h. 16–19, 21–22).
Nasionalisme dan Perkembangan Kapitalisme-percetakan
Sejauh mana perkembangan kapitalisme berdampak pada tumbuhnya nasionalisme? Bagaimana relasi tersebut dioperasikan, dan melalui instrumen-instrumen apa saja?
Teknologi percetakan pertama kali muncul di Cina, sekira lima ratus tahun sebelum mulai berkembang di Eropa pada paruh-akhir abad ke-15.[13] Kendati demikian, percetakan di Cina tak memiliki dampak revolusioner sebagaimana di Eropa, karena tidak dibarengi dengan mode produksi kapitalis. Terdorong oleh logika akumulasi dan ekspansi kapital, kapitalisme-percetakan (print-capitalism) di Eropa mengalami pertumbuhan pesat di bawah kuasa dan kepemilikan kapital para pemodal kaya.[14] Pertumbuhan tersebut tercermin baik dari jumlah produk yang dimanufaktur, pasar-cetak dan konsumennya yang secara perlahan terkonsolidasi dalam 150 tahun, maupun pertumbuhan dan persebaran perkakas-perkakas produksi dan sirkulasi pendukungnya (seperti jumlah percetakan, serta munculnya perpustakaan-perpustakaan pertama di pusat-pusat urban); Anderson mengutip istilah Walter Benjamin bahwa masa tersebut merupakan penanda mulainya ‘zaman reproduksi mekanis (age of mechanical reproduction)’.[15]
Menurut Anderson, salah satu produk kapitalisme-percetakan, buku, merupakan komoditas industrial tipe-modern pertama yang diproduksi secara massal. Buku memiliki sifat yang berbeda dengan produk-produk industrial awal lainnya, seperti tekstil, batu bata, atau gula: produk-produk lain tersebut terkuantifikasi berdasarkan jumlah matematis (sekian pound gula, dan sebagainya), dan tak merupakan objek secara inheren. Sebaliknya, buku merupakan objek paripurna dan unik, yang direproduksi secara identik dalam skala besar. Terakhir dan terpenting, buku mengandung kapasitas dahsyat untuk mendiseminasi pemikiran, emosi dan imajinasi, yang produk-produk lain tak punya, dan yang—mengikuti berkembangnya rasionalitas-sekuler—turut mempengaruhi pembentukan kesadaran nasional seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang mampu membaca (h. 34).
Sebagai penegasan, seperti yang telah dibahas di muka, salah satu produk kapitalisme-percetakan yang paling laku dan berpengaruh pada pembentukan kesadaran nasional—oleh Anderson dikategorikan sebagai ‘bentuk ekstrim dari buku’ dan ‘one-day bestsellers’—adalah koran. Unsur ritualitas dari keserentakan pembacaannya—Anderson: “pengonsumsian (‘pembayangan’) koran-sebagai-fiksi” yang, secara bersamaan, meyakinkan pembaca bahwa “dunia yang terbayang terakar secara kasatmata pada realitas keseharian”—oleh Hegel digambarkan “melayani manusia modern sebagai substitusi untuk doa modern” (h. 35).
Kemampuan ekspansif dari kapitalisme-percetakan didorong oleh tiga faktor:
- perubahan pada sifat bahasa Latin, yang menjadi semakin esoteris dan tercerabut dari kehidupan gerejawi maupun kehidupan sehari-hari;
- dampak Reformasi Protestan, yang ‘berutang budi pada kapitalisme-percetakan’ dalam mendiseminasi pemikiran melalui karya-karya murah, dan turut menciptakan pasar dan komunitas pembaca baru (gerakan Protestan memahami pentingnya bahasa-rakyat,dan menggunakan pasar-cetak yang dihasilkan kapitalisme-percetakan untuk menyerang pihak Gereja yang berupaya mempertahankan kedudukan bahasa Latin); dan
- persebaran beberapa bahasa-rakyat tertentu sebagai instrumen sentralisasi administratif yang diterapkan beberapa monarki absolutis (universalitas bahasa Latin di Eropa Barat tak pernah bermanifestasi dalam bentuk sistem politis universal, sehingga, tak seperti Cina pada masa Imperial, otoritas religius Gereja tak memiliki padanan politis) (h. 39–44).
Sementara itu, pengaruh bahasa-cetak (print-languages), yang dikondisikan oleh kapitalisme-percetakan, pada terbentuknya basis kesadaran nasional hadir dalam tiga cara berbeda:
- bahasa-cetak menciptakan ruang pertukaran dan komunikasi terpadu; berposisi di bawah bahasa Latin, namun di atas bahasa-rakyat lisan (beraneka ragam dialek bahasa Perancis, Inggris, atau Spanyol—yang sebelumnya tak dapat dipahami dalam percakapan oleh penutur dialek lain—kini dapat dipahami bersama melalui percetakan dan kertas);
- kapitalisme-percetakan memberikan unsur ketetapan pada bahasa, yang dalam jangka panjang membantu menciptakan imaji kekunoan yang esensial bagi ide subjektif bangsa; dan
- kapitalisme-percetakan menciptakan bahasa-bahasa-kekuasaan (languages-of-power) yang berbeda dari bahasa-rakyat administratif terdahulu (h. 44–45).[16]
Genealogi dan Perkembangan Empat Model Nasionalisme
Kita sudah melihat beraneka ragam konteks dan faktor yang secara historis melatarbelakangi dan memengaruhi pembentukan nasionalisme. Lantas, bagaimana wujud nasionalisme dalam realitas global yang menyejarah, sehingga mengondisikan konstelasi politis global yang kita alami sekarang?
Anderson menuturkan adanya empat model nasionalisme: nasionalisme-creole, nasionalisme-populer, nasionalisme-resmi dan nasionalisme-kolonial. Kendati pada titik-titik historis tertentu terdapat kait-kelindan antara satu dengan yang lain, formasi empat model nasionalisme tersebut masing-masing berada dalam konteks yang unik. Berdasarkan konteks ruang-waktu, nasionalisme-creole muncul lebih awal di benua Amerika dan sekitarnya, dan terkonsolidasi dalam bentuk gerakan-gerakan kemerdekaan pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19; nasionalisme-populer muncul hampir langsung setelahnya di Eropa; nasionalisme-resmi muncul pada pertengahan abad ke-19 di Eropa, kemudian dipelajari, dibajak, dan berkembang di Jepang dan Indocina dengan variasi tersendiri; terakhir, nasionalisme-kolonial muncul sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua sebagai ‘gelombang terakhir nasionalisme’ dalam proses dekolonisasi di berbagai wilayah jajahan imperialis, terutama di Afrika dan Asia, termasuk di Indonesia.
Nasionalisme-creole[17]
Model pertama dikondisikan oleh beberapa faktor sosial-historis di benua Amerika (baik Utara maupun Selatan) dan Kepulauan Karibia (terutama Haiti), dalam konteks sebagai koloni-koloni Eropa. Wilayah-wilayah tersebut mengalami dinamika konflik dengan kekuatan-kekuatan negara-induk yang bertangan panjang dan bertengger dari seberang Samudera Atlantik. Menurut Anderson, ditilik menggunakan analisis kelas, fenomena nasionalisme-creole merupakan realitas yang secara kontekstual tak cocok dengan tesis Tom Nairn, teoretisi ilmu politik berkebangsaan Skotlandia, bahwa nasionalisme terbentuk melalui “pembaptisan politis kelas-kelas bawah”, memiliki sikap yang “populis dan berkehendak melantik kelas-kelas bawah ke dalam kehidupan berpolitik”, dan terbentuk dari “kelas menengah resah” serta “kepemimpinan inteligensia” yang berupaya “mengarahkan strategi-strategi kelas yang populer dalam rangka meraih dukungan bagi negara-negara baru” (h. 47–48).
Sebaliknya, Anderson berargumen bahwa:
- setidaknya di Amerika Selatan dan Amerika Tengah, keberadaan ‘kelas menengah’ ala Eropa belum signifikan hingga akhir abad ke-18, dan hampir belum ada kaum inteligensia; kepemimpinan berada di genggaman pemilik-pemilik tanah (yang beraliansi dengan pedagang-pedagang yang lebih kecil) serta berbagai kalangan profesional (pengacara, militer, pejabat lokal dan provinsi); dan
- alih-alih berpihak pada kelas-kelas bawah, apa yang terjadi di Amerika—terutama Venezuela, Meksiko, dan Peru—menunjukkan bahwa ketakutan terhadap mobilisasi politis kelas bawah (pemberontakan budak-Negro atau kaum Indian, laksana yang berhasil di Haiti[18]) justru merupakan salah satu faktor determinan dalam memantik perlawanan dan semangat kemerdekaan terhadap imperialisme Spanyol yang berpusat di Madrid. Relasi kelas yang eksploitatif dan antagonistis terhadap kelas bawah, terutama para budak, juga dapat dilihat dari kepemilikan budak para pemimpin Tiga Belas Koloni (yang kelak terkonsolidasi menjadi Amerika Serikat).[19]
Terdapat dua faktor pendukung (yang tak sepenuhnya cukup untuk menjelaskan fenomena) serta dua faktor utama yang menurut Anderson menjelaskan latar belakang terkonsolidasinya nasionalisme-creole. Dua faktor pendukung tersebut adalah:
- kebijakan imperial Spanyol yang semakin ketat terhadap koloni-koloninya (di bawah rezim Carlos III Spanyol menerapkan pajak-pajak baru, mengefisienkan mekanisme pengambilan pajak, menerapkan monopoli komersial, membatasi perdagangan lintas-Samudera untuk kepentingannya sendiri, menyentralisasi hierarki-hierarki administratif, dan mempromosikan imigrasi peninsulares); dan
- percepatan ide-ide liberal Abad Pencerahan pada paruh-akhir abad ke-18 (suatu ‘revolusi kultural’ yang terkonfirmasi dengan merebaknya ide dan bentuk republikanisme dari komunitas-komunitas yang baru independen) (h. 50–51).
Selanjutnya, dua faktor utama adalah:
- evolusi dari, dan pembubuhan makna pada, wilayah-kuasa administratif menjadi tanah air, sebagai hasil proses berkepanjangan dari penciptaan-makna dan pembentukan kesadaran kolektif (melibatkan siklus hidup pejabat-pejabat creole yang bekerja untuk Spanyol vis-à-vis ketimpangan kesempatan-hidup, status, dan wewenang birokratis antara pejabat creole dan pejabat peninsulares berprivilese elit, yang didasari oleh praktik realpolitik Machiavellian serta diskriminasi biologis/ekologis-rasial[20]); dan
- terkonsolidasinya relasi-relasi produksi dari kapitalisme-percetakan—terutama melalui koran—secara pesat di Amerika Utara dan secara lebih lambat di Amerika Selatan (antara tahun 1691 dan 1820, 2.120 merek koran tercetak di Tiga Belas Koloni, yang mana 461 merek bertahan lebih dari sepuluh tahun; di Amerika Selatan, percetakan lokal baru muncul pada paruh-akhir abad ke-18) (h. 53–64).[21]
Pada akhirnya, proses panjang dari pembentukan nasionalisme-creole berhasil, untuk pertama kalinya di dunia, menghasilkan kemerdekaan dan kedaulatan, dan mengonsolidasikan entitas politis yang berbasis ke-bangsa-an; kendati demikian, Anderson mengomentari bahwa nasionalisme-creole di Amerika Selatan ‘gagal’ menciptakan nasionalisme permanen yang mencakup seluruh wilayah Amerika-Spanyol, akibat keterbelakangan ‘lokal’ dari kapitalisme dan teknologi Spanyol vis-à-vis wilayah geografis yang begitu luas, dibarengi kondisi isolatif dari komponen-komponen wilayah-kuasanya (h. 62–63).
Nasionalisme-populer[22]
Secara historis, berakhirnya era keberhasilan nasionalisme-creole di Amerika tak terpaut jauh dengan awal kemunculan gerakan nasionalisme-populer di Eropa, yang lahir, tumbuh, dan menyebar antara tahun 1820 dan 1920. Selain letak geografis, terdapat dua karakteristik yang membedakan nasionalisme-populer dengan nasionalisme-creole:
- perbedaan pembubuhan signifikansi pada bahasa: berbeda dengan bangsa-bangsa creole di Amerika yang tak pernah menjadikan bahasa sebagai persoalan atau pun elemen penting yang membedakan mereka dengan negara-induk, bagi bangsa-bangsa balita Eropa, bahasa-cetak nasional memiliki signifikansi ideologis dan politis besar;
- nasionalisme-populer mempelajari dan meniru contoh-contoh yang sebelumnya diberikan oleh nasionalisme-creole dan Revolusi Perancis pada tahun 1789. Dalam hal ini, Anderson mendeskripsikan bangsa sebagai ‘penemuan yang tak dapat diberikan paten’ yang rawan terhadap ‘pembajakan (piracy)’ oleh berbagai pihak (h. 67).
Proses panjang pengonsolidasian bahasa-cetak nasional difasilitasi oleh proses yang dinamakan Anderson ‘revolusi filologis-leksikografis (philological-lexicographical revolution)’; revolusi tersebut berakar pada penjelajahan dan penemuan Eropa pada abad ke-16 ke Cina, Asia Tenggara, sub-kontinen India, Meksiko-Aztec, dan Peru-Inca, yang membawa kembali pemikiran perihal pluralisme manusia dan ‘sejarah komparatif’, sebagai refleksi terhadap pertemuan dengan ‘mereka’ yang berada di ‘Luar’ keseluruhan konstruksi sejarah Eropa, Gereja maupun Abad Kuno. Dari penjelajahan dan penjajahan, lahirlah revolusi pada ide-ide di Eropa perihal bahasa, yang lambat laun berkembang menjadi kajian komparatif ilmiah tentang bahasa yang memuncak pada abad ke-18 (h. 67–70).
Penemuan-penemuan tersebut pada akhirnya membentuk disiplin ilmu filologi—mempelajari gramatika komparatif, mengklasifikasi bahasa berdasarkan famili, dan merekonstruksi ‘protobahasa’ menggunakan akal budi ilmiah—yang turut melahirkan disiplin ilmu leksikografi (perihal penyusunan kamus). Menurut Anderson, kamus, terutama kamus bilingual, merupakan alat instrumental dalam mematahkan ketimpangan relasi kuasa linguistik dari bahasa-bahasa kuno yang sakral, seperti Latin, Yunani, dan Ibrani. Melalui kamus bilingual, bahasa-bahasa tersebut terpaksa mengalami proses keseukuran ontologis melalui jukstaposisi padanan kata dengan beraneka ragam bahasa-rakyat—proses yang melengkapi penggerusan yang sebelumnya dilakukan oleh kapitalisme-percetakan. Revolusi filologis-leksikografis—difasilitasi oleh para cendekiawan dan mahasiswa di Jerman, Inggris, dan Perancis—melahirkan penerjemahan dan penemuan kembali literatur-literatur Helenistik, serta memantik ketertarikan dan kepedulian pada sejarah dan bahasa-rakyat bangsa masing-masing, yang turut mendorong pemekaran kesadaran dan gerakan nasional (h. 70–75).
Sebagaimana buku memerlukan pembaca, revolusi filologis-leksikografis memerlukan pasar. Anderson menjelaskan bahwa yang menikmati produk-produk revolusi filologis-leksikografis adalah kaum melek-huruf yang jumlahnya lambat laun meningkat, terdiri dari kelas aristokrat-penguasa lama, golongan pembantu istana dan gereja, strata menengah dari pejabat kelas bawah, golongan profesional, serta borjuasi komersial dan industrial.[23] Perihal pembentukan nasionalisme-populer, transformasi linguistik terakhir adalah unifikasi bahasa-rakyat pada wilayah-kuasa dinastik, yang muncul dari konteks masyarakat Eropa yang umumnya menguasai lebih dari satu bahasa-rakyat (polyvernacular). Impuls bagi proses unifikasi (dan pengenyahan) bahasa-rakyat tersebut didorong oleh pertumbuhan dan kemajuan pada angka kemelekan huruf, perdagangan, industri, komunikasi dan perangkat-mesin negara pada abad ke-19 (h. 75–80).
Perihal modularitas (kesifatstandaran) nasionalisme, Anderson menulis bahwa, manakala diliput, dituturkan, dan disebarluaskan dalam bentuk cetak, keberhasilan nasionalisme-creole dan gerakan kemerdekaan di Amerika, serta Revolusi Perancis, dipahami dan dimaknai sebagai ‘konsep’, ‘model’, dan ‘cetak biru’ untuk dipelajari, dibajak dan digandakan. Keberhasilan masa silam memunculkan kosakata politis (atau ‘realitas-realitas terbayang’ dalam bahasa Anderson) berupa ‘negara-bangsa’, ‘institusi republikan’, ‘kewarganegaraan setara’, ‘kedaulatan populer’, ‘bendera dan lagu kebangsaan nasional’, dan sebagainya. Validitas dan keterapan dari bentuk-bentuk tersebut terkonfirmasi oleh pluralitas negara-negara independen yang muncul. Merujuk pada model asli, proses pembajakan tersebut juga menyaksikan penerapan ‘standar’ etis yang berkarakter ‘populis’, yang melampaui apa yang telah dicapai sebelumnya di Amerika: contohnya, relasi kerja feodal (serfdom) dan perbudakan legal kemudian menjadi relasi kerja yang wajib dienyahkan (h. 80–82).
Nasionalisme-resmi
Sejak pertengahan abad ke-19, muncul model nasionalisme yang dinamakan nasionalisme-resmi (official nationalism), yang tak hanya mencengkeram di Eropa dan Syam, tapi juga wilayah-wilayah Asia (termasuk Jepang dan Siam) dan Afrika akibat ekspansi imperialis. Logika dari nasionalisme-resmi adalah amalgamasi dari bangsa, yang berumur baru, dan dinasti, yang bersejarah kuno; contohnya, Imperium (dinastik) Britania (ke-bangsa-an) atau Kekaisaran Jepang (serupa). Nasionalisme-resmi hanya muncul setelah kehadiran nasionalisme-populer, karena pada dasarnya merupakan bentuk respons dari kelompok-kelompok kekuasaan, yang utamanya bersifat dinastik dan aristokratis, yang terancam dienyahkan dari, atau pun mengalami marginalisasi dalam, ‘komunitas-terbayang-populer’ yang telah muncul. Dalam kata lain, nasionalisme-resmi merupakan kebijakan-kebijakan konservatif dan, terlebih, reaksionis, yang diadaptasi dari model nasionalisme-populer yang silam. Adjektiva ‘resmi’ di sini menggambarkan “sesuatu yang berasal dari negara” dan “lebih dulu melayani kepentingan negara” (h. 86, 109–111, 159).
Anderson secara rinci membahas nasionalisme-resmi berwatak imperialis yang bermanifestasi dalam Kekaisaran Rusia, Imperium Britania, dan Kekaisaran Jepang.[24] Selain itu, dibahas pula nasionalisme-resmi di Siam dan Hungaria-di-dalam-Austro-Hungaria yang, kendati tak ekspansionis-imperialis, memiliki logika yang sama dengan yang lain, dan—kendati tentunya memiliki konteks sosial-politis spesifik—sama-sama lahir dari respons terhadap pengancaman kekuasaan.[25] Masing-masing contoh nasionalisme-resmi tersebut memiliki rangkaian kebijakan yang sama: pendidikan utama yang dikontrol negara, propaganda yang diorganisir negara, penulisan ulang narasi sejarah secara resmi, militerisme, dan afirmasi terhadap identitas dinasti dan bangsa (h. 101).
Kebijakan pertama—pendidikan—memiliki signifikansi fundamental pada setiap contoh nasionalisme-resmi, sebagai instrumen penyeragaman bahasa dalam rangka mereproduksi kader-kader subordinat untuk menjalankan roda administrasi dan birokrasi negara. Di bawah kepemimpinan Alexander III, Kekaisaran Rusia, melalui slogan ‘Ortodoksi, Autokrasi, Nasionalisme (Pravoslaviye, Samoderzhaviye, Narodnost)’ yang diprakarsai Sergey Uvarov pada tahun 1832, melancarkan proses penyeragaman bahasa Rusia yang dikenal sebagai ‘Russifikasi’;[26] pada 1834 Imperium Britania melakukan ‘Anglicisasi’ (penyeragaman bahasa Inggris) di bawah komando Thomas Babington Macaulay, selaku ketua Komite Pengajaran Publik di Bengal, India Kolonial; setelah tahun 1900, menyusul ekspansi Kekaisaran, Jepang menerapkan kebijakan-kebijakan yang mencontoh Eropa, di wilayah jajahannya di Indocina dan Asia Tenggara; Siam di bawah kepemimpinan Wachirawut melakukan hal serupa dengan slogan ‘Bangsa, Agama, Raja (Chat, Sasana, Kasat)’, yang merupakan bentuk persis dari slogan Uvarov, kendati dalam urutan berbeda (h. 87–101).
Penerapan nasionalisme-resmi dalam beberapa contoh imperialis di muka juga mirip dengan proses pembentukan nasionalisme-creole, yakni ‘perjalanan’ birokratis dan pendidikan yang memekarkan kesadaran kolektif. Hanya saja, dalam konteks nasionalisme-resmi, posisinya terbalik: bila dianalogikan dengan nasionalisme-creole, posisi negara penganut nasionalisme-resmi adalah Imperium Spanyol alih-alih pejabat creole. Alih-alih pejabat creole yang mengalami ketimpangan, nasionalisme-resmi imperialis justru mengoperasikan logika birokrasi negara dinastik, dan mengekang mobilitas birokratis pejabat-pejabat tersebut, baik secara horizontal (wilayah dinas) maupun vertikal (anak tangga jabatan) (h. 98–99).
Sebagai contoh, kendati ada pejabat Indonesia yang bekerja untuk pemerintah kolonial Jepang serta mahir berbahasa Jepang, dia tak mungkin dimutasi ke Kyoto untuk bekerja di sana sebagai pejabat tinggi. Hal tersebut tak hanya dilatarbelakangi oleh rasisme, tetapi juga merupakan cerminan logika nasionalis bangsa-bangsa baru—seperti Hungaria, Jepang, dan Inggris—yang tak sudi dikuasai kekuatan ‘asing’.[27] Ironisnya, serupa dengan ‘perjalanan’ pada masa nasionalisme-creole, logika tersebut kelak turut memekarkan kesadaran dan gerakan nasionalisme-kolonial di bekas-bekas jajahan imperialis (h. 92–93, 110–111).
Nasionalisme-kolonial
Perang Dunia Pertama menandakan berakhirnya era dinasti-tinggi (high dynasticism), seperti dinasti Habsburg, Hohenzollern, Romanov, dan Ottoman; sejak saat itu, norma internasional yang sah adalah negara-bangsa, yang mencapai kulminasinya pasca-Perang Dunia Kedua hingga memasuki paruh-akhir abad ke-20. Anderson memposisikan munculnya nasionalisme-kolonial sebagai ‘gelombang terakhir nasionalisme (the last wave of nationalism)’, yang sebagian besar terjadi di wilayah-kuasa kekuatan-kekuatan kolonial di Asia dan Afrika, namun juga mencakup bangsa di Eropa seperti Swiss. Nasionalisme-kolonial mulanya merupakan respons terhadap imperialisme global gaya baru, yang secara material dimungkinkan oleh perkembangan kapitalisme industrial yang didorong oleh logika akumulasi dan ekspansi kapital, sebagaimana dikutip Anderson dari Manifesto Komunis: “kebutuhan terhadap pasar yang terus-berkembang untuk kebutuhan produk-produknya, mengejar kelas borjuasi hingga ke seluruh permukaan bumi.”[28]
Bersamaan dengan kapitalisme, negara kolonial juga secara pesat memperkembangkan dan mereproduksi aparatus-aparatusnya, baik di koloni maupun di negara-induk, akibat luas geografis wilayah-kuasa yang memerlukan kekuatan administrasi maupun militer yang signifikan untuk mempertahankannya. Seperti yang telah dijelaskan, kebutuhan mereproduksi aparatus negara, yang dikondisikan program pendidikan dan penyeragaman bahasa, turut menciptakan ‘perjalanan’ untuk memperoleh pendidikan resmi (bahkan sampai ke negara-induk) dan memasuki dan menjelajahi mesin-birokrasi sipil maupun militer untuk memperoleh jabatan lebih tinggi. Menurut Anderson, ‘perjalanan’ tersebut mengondisikan terciptanya basis wilayah-kuasa ‘komunitas-komunitas-terbayang’ baru, di mana orang lokal dapat melihat diri mereka sendiri sebagai kaum ‘nasional (nationals)’—dengan kata lain, munculnya nasionalisme-kolonial (h. 140).
Pasca pertengahan abad ke-19, dan terlebih pada abad ke-20, ‘perjalanan’ di negara-negara kolonial menyaksikan pertumbuhan dan diversifikasi pesat dari para ‘pejalannya’. Fenomena tersebut dijelaskan Anderson sebagai akibat dari tiga faktor:
- peningkatan yang luar biasa dalam kapasitas mobilitas fisik yang diakibatkan oleh penemuan-penemuan kapitalisme industrial (rel kereta api, kapal uap, transportasi berbasis motor, pesawat terbang);
- diversifikasi (jenis pos birokrasi sipil-militer) dan intensifikasi (jumlah aparat yang dibutuhkan) yang disebabkan kebijakan ala ’Russifikasi’ yang diterapkan negara kolonial, dan menciptakan kebutuhan terhadap pejabat negara bilingual sebagai jembatan bagi negara-induk dan negara kolonial (muncul lowongan-lowongan baru seperti pekerja medis, insinyur irigasi, pekerja pertanian, guru sekolah, polisi, dan sebagainya); dan
- pertumbuhan dan persebaran sistem pendidikan modern (baik yang diselenggarakan negara kolonial, maupun organisasi-organisasi religius dan sekuler privat) (h. 115–116).[29]
Anderson mengamati, kolonialisme memastikan bahwa relatif sedikit orang lokal berprofesi sebagai tuan tanah besar, pedagang besar, pengusaha industrial, atau pun golongan profesional. Hampir di mana-mana, kekuasaan termonopoli di antara para penjajah, atau pun terdistribusi secara tak merata pada ‘kelas pengusaha (non-lokal) yang mandul-politik’, yakni bangsa Lebanon, India dan Arab di koloni Afrika; dan bangsa Cina, India, dan Arab di koloni Asia. Relasi dan komposisi kelas tersebut ditempa dengan persetubuhan antara logika negara kolonial (mengajak orang lokal masuk ke sekolah dan perkantoran) dan logika kapitalisme kolonial (mengenyahkan orang lokal dari direksi perusahaan), mengondisikan munculnya juru bicara pertama untuk nasionalisme-kolonial, dengan profil yang khas: ‘inteligensia yang bilingual dan kesepian, yang tak terikat pada borjuasi lokal yang kukuh’. Di dalam maupun di luar ruang kelas, kaum inteligensia memiliki akses terhadap berbagai model bangsa, ke-bangsa-an, dan nasionalisme, yang “terdistilasi dari pengalaman-pengalaman sejarah Amerika dan Eropa selama lebih dari satu abad, yang bergejolak dan kaotis” (h. 116, 140).
Model-model tersebut turut menjadi faktor penting bagi pembentukan mimpi dan visi nasionalis. Nasionalisme-kolonial mengambil model-model nasionalisme sebelumnya dan, dalam tingkatan dan variasi yang berbeda-beda sesuai konteks lokal, mempelajarinya, membajaknya, dan menggandakannya. Pada akhirnya, baik pada tahap perkembangannya maupun pada tahap pasca terkonsolidasinya kemerdekaan, nasionalisme-kolonial merupakan sejenis amalgamasi dari unsur-unsur nasionalisme-creole (kesepadanan antara cakupan wilayah-kuasa masing-masing kekuatan nasionalisme dan wilayah-kuasa unit-unit administrasi negara kolonial), nasionalisme-populer (populisme yang berapi-api), dan nasionalisme-resmi (orientasi kebijakan berprinsip ‘Russifikasi’, dalam wujud menyuntikkan ‘ideologi’ nasionalis melalui media massa, sistem pendidikan, regulasi administrasi, dan sebagainya) (h. 140).
Legitimasi Emosional
Bentuk nasionalisme dan bangsa di muka tak lahir dalam keadaan fisik yang bersih dan tak bernoda; laksana manusia manakala keluar dari rahim Ibu, kita dan mereka lahir bersimbah darah, dan terkadang, lahir berkat pengorbanan nyawa. Jika upaya menuturkan dan menjelaskan kekuatan emosional Ibu tampak sebagai proyek mustahil, dapatkah kita bernasib lebih baik dalam menjelaskan kekuatan emosional dari nasionalisme, serta implikasi-implikasinya?
Anderson merefleksi bahwa nasionalisme memiliki ‘legitimasi emosional’ yang dapat menggugah rasa kecintaan dan pengorbanan. Sepanjang teks Imagined Communities, Anderson kerap mengilustrasikan beragam manifestasi legitimasi emosional di tengah proses perkembangan nasionalisme. Tak sekadar berurusan dengan ‘cinta’ dan ‘pengorbanan’, legitimasi emosional memiliki cakupan yang lebih luas dan dalam, perihal proses pemaknaan dan penciptaan-makna terkait bahasan-bahasan seperti ingatan, bahasa, simbol, kekerabatan, dan kesadaran eksistensi-diri manusia di hadapan narasi sejarah yang tampak kukuh, namun sejatinya rawan terhadap pengubahan. Anderson membedah dan menuturkan permasalahan, implikasi realitas politis, dan tanggapan intelektual terhadap berbagai faktor yang membentuk maupun berasal dari legitimasi emosional tersebut. Tuturan tersebut antara lain mencakup:
- pengamatan terhadap pengalaman dan pemaknaan kematian dalam pertempuran berbasis ke-bangsa-an dalam beberapa abad terakhir;
- argumen bahwa nasionalisme tak berkorelasi positif terhadap rasisme, dan keduanya memiliki akar-logika yang berbeda;
- proses penciptaan-makna kesadaran ke-bangsa-an melalui evolusi dan manipulasi pemaknaan terhadap lambang dan klasifikasi sosio-spasial, khususnya melalui instrumen sensus, peta, dan museum;
- analisis terhadap ‘romantisme’ warisan politis yang hadir dalam logika ‘negara lama, bangsa baru’, dalam rangka menjelaskan anomali (pada saat itu) seperti perang-perang antarnegara (yang secara formal) Marxis di Indocina; dan
- analisis terhadap ‘penulisan ulang’ narasi historis ke-bangsa-an, baik sadar dan terencana maupun bawah-sadar, yang turut mengukuhkan kesadaran dan konsepsi identitas nasional.
Pertama, salah satu unsur terpenting dan termisterius dari nasionalisme adalah kematian, dan, dalam konteks ke-bangsa-an, kerelaan untuk mendekapnya dengan elan yang berkobar-kobar. Menurut Anderson, kematian dapat dilacak kesakralannya pada akar-akar kultural-historis-religius, sebagai ‘jawaban’ bagi permasalahan dan interogasi manusia berkenaan dengan fatalitas nasib—jawaban yang kelak berpindah tangan pada ‘bangsa’ sebagai titik bertumpu. Anderson menuturkan bahwa mode-mode berpikir yang evolusioner atau progresif, tak terkecuali Marxisme, gagal membedah dan menanggapi secara memuaskan fenomena-fenomena fatalistis, seperti ‘kematian’ dan ‘keabadian’. Tentu saja, kita mengerti bahwa mode-mode berpikir tersebut, setidaknya dalam kasus Marxisme, merupakan disiplin ilmu, mode, dan praktik berpikir ilmiah yang tak berpretensi melampaui cakupan epistemologisnya, sejauh ia diterapkan dengan logika yang ilmiah pula. Anderson tak berusaha menyangkal realitas logis tersebut, alih-alih memperlihatkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat menjelaskan absennya kesamaan legitimasi emosional pada mode-mode berpikir tersebut dengan yang ada pada nasionalisme.[30]
Kedua, Anderson memasang badan terhadap pemikiran beberapa intelektual ‘progresif dan kosmopolitan’, terutama di Eropa, yang menekankan bahwa nasionalisme memiliki karakter yang ‘mirip dengan patologi’, berakar pada ‘ketakutan dan kebencian terhadap yang-Lain’, dan ‘memiliki afinitas dengan rasisme’. Anderson menyangkal tesis-tesis tersebut dan berargumen sebaliknya bahwa nasionalisme “menginspirasi cinta, dan, seringnya, yang sarat pengorbanan-diri mendalam”, yang terekspresi dalam beragam produk budaya seperti puisi, prosa fiksi, musik, maupun seni rupa, secara “terang-benderang dalam ribuan jenis wujud dan gaya yang berbeda.” Sebaliknya, menurut Anderson, jarang kita menemukan produk-produk budaya nasionalis yang, secara analogis, mengekspresikan ketakutan dan kebencian.[31] Menolak bahwa rasisme muncul dari nasionalisme, Anderson kemudian menunjukkan perbedaan logika di antara keduanya: “nasionalisme berpikir berkenaan dengan takdir-takdir menyejarah” yang terbayangkan melalui bahasa, sementara rasisme “bermimpi perihal kontaminasi-kontaminasi abadi” yang “berada di luar sejarah”, bersifat domestik (dalam bentuk represi dan dominasi) alih-alih perihal perang-perang internasional, dan bermanifestasi dalam bahasa.[32] Dalam kacamata rasisme, sekali ‘nigger (orang kulit-hitam)’ tetap nigger, dan sekali Yahudi tetap Yahudi, kendati paspor apa pun yang dimilikinya. Penghinaan seperti ‘slant-eyed (sipit)’, dalam konteks rasisme orang kulit-putih terhadap orang Asia, tak hanya mengandung kebencian politis biasa, melainkan menghilangkan unsur ke-bangsa-an dan menggantikannya dengan fisiognomi (ilmu wajah) biologis; secara bersamaan, rasisme justru mengagregasi bangsa-bangsa seperti ‘Vietnam’, ‘Cina’, ‘Korea’, ‘Jepang’ menjadi satu kategori. Anderson menutup analisisnya dengan tesis bahwa rasisme berpangkal dari ideologi kelas, alih-alih nasionalisme (h. 141–150).
Ketiga, sensus, peta, dan museum merupakan tiga ‘institusi kekuasaan’ yang ditemukan sebelum pertengahan abad ke-19, namun mengalami perubahan bentuk dan fungsi manakala wilayah-wilayah koloni memasuki era reproduksi mekanis.[33] Secara terpadu, dengan drastis mereka mengubah cara negara kolonial membayangkan wilayah-kuasanya, yang meliputi sifat manusia yang dikuasainya (‘kuantifikasi/serialisasi orang secara manasuka’), geografi wilayah-kuasanya (‘logoisasi ruang-politis’), dan legitimasi silsilahnya (‘genealogisasi secara profan’). Proses perkembangan tiga instrumen di muka adalah sebagai berikut: sepanjang periode kolonial, kategori sensus semakin terlihat rasial dan eksklusif, sementara identitas religius secara perlahan hilang sebagai bentuk klasifikasi primer. (Anderson: “Fiksi dari sensus adalah bahwa setiap orang berada di dalamnya, dan setiap orang memiliki satu—dan hanya satu—tempat yang benar-benar jelas. Tak ada pecahan”.) Kemudian, melalui peta dan kartografi, muncul fenomena ‘peta historis (historical map)’, yang mampu merombak narasi politis-biografis dari wilayah-kuasa negara koloni, yang kelak diwariskan kepada negara bekas koloni; serta ‘peta-sebagai-logo (map-as-logo)’, yakni bentuk kartografis spesifik dari wilayah-kuasa yang didemarkasi oleh garis perbatasan (dalam kata lain, bentuk negara pada peta) yang mampu diekstraksi dan direproduksi sebagai ‘logo’ dari identitas negara tersebut.[34] Terakhir, situs-situs kuno berubah fungsi sebagai ‘museum’ yang mengalami serialisasi: diamati, difoto, dan direproduksi sebagai bagian dari ‘album para leluhur’, yang turut mengapropriasi dan merekonstruksi narasi identitas historis kuno berdasarkan identitas ke-bangsa-an baru. Melalui tiga instrumen di muka, negara kolonial abad ke-19, beserta kebijakan-kebijakannya, secara dialektis dan tak sadar menelurkan ‘gramatika dari nasionalisme yang kelak bangkit untuk melawannya (h. xiv, 163–185).
Keempat, Anderson mencoba menjelaskan paradoks fenomena perang-perang antarnegara Marxis di Indocina yang melibatkan Cina, Vietnam dan Kamboja, menggunakan logika ‘negara lama, bangsa baru (old state, new society)’:[35] setelah berhasil merebut negara, rezim ‘pascarevolusioner’ baru diresapi logika dan elan nasionalisme-resmi dinastik yang sebelumnya ada, dan mewarisi aparatus-aparatus negara lama—“terkadang [mewarisi] para pejabat dan informan, namun selalu [mewarisi] berkas, dosir, arsip, hukum, catatan finansial, sensus, peta, perjanjian, korespondensi, memorandum dan sebagainya”. Logika tersebut juga sering muncul secara simbolis, seperti tindakan memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi pusat pemerintahan lama (contohnya Uni Soviet yang memilih Moskow sebagai pusat, kendati Moskow merupakan pusat pemerintahan Tsar yang lampau), dan memasang atau menggunakan simbol pemimpin, pahlawan, dan negara era dinastik terdahulu. Proses pengakomodasian tersebut juga dinamakan Anderson sebagai ‘Machiavellisme ‘negara’ (‘state’ Machiavellism)’. Pada akhirnya, logika pascarevolusioner tersebut dioperasikan oleh konfigurasi ‘kepemimpinan (leaderships)’ alih-alih massa rakyat, yang mana, pasca menguasai negara ‘lama’, dapat menggunakan kekuatan negara yang ada di tangan untuk mengejar visi-visinya (h. 155–162).
Kelima, dalam bab terakhir Imagined Communities, Anderson menuturkan signifikansi ‘ingatan’ dan ‘kelupaan’ secara spasio-temporal dalam mewujudkan legitimasi emosional dalam konteks ke-bangsa-an dan nasionalisme. Poin pertama adalah munculnya konsepsi keserentakan yang mutakhir pada peradaban kolonial di benua Amerika dalam bentuk penamaan kota sebagai kota ‘Baru’ (seperti New York, Nouvelle Orléans, Niew Amsterdam, dan sebagainya), yang kehadirannya serentak dengan padanan ‘kota lama’ (York, Orléans, Amsterdam) di seberang lautan.[36] Konsepsi tersebut mensinyalir bahwa pada dasarnya, tak ada motif politis untuk menghancurkan dan menggantikan imperium lama dengan imperium baru, alih-alih keinginan untuk mempertahankan keserentakan di muka. Anderson juga menjelaskan bahwa kendati terjadi perang melawan imperium, bangsa creole di Amerika memiliki ‘rasa aman’ berbasis genalogi biologis, yang berakar pada pengakuan ‘kekerabatan (kinship)’ dengan masyarakat Eropa di seberang lautan. Anderson kemudian menjelaskan perubahan pada pemaknaan bangsa terhadap konsepsi waktu pasca terkonsolidasinya nasionalisme dan kemerdekaan, yakni sebagai pencapaian dan pembukaan ‘era baru’ yang revolusioner dalam lintasan sejarah. Terakhir, tak kalah signifikan adalah apropriasi, pembajakan dan penulisan ulang narasi historis melalui tindakan ‘mewakili yang-meninggal’, seperti San Martín di Peru yang mendeklarasikan pada tahun 1821 bahwa para Indian adalah sesama ‘orang Peru’; pemaknaan bahwa orang-orang yang sudah mati adalah ‘saudara’ dan ‘bagian dari kita’, laksana ‘Perang Saudara’ Amerika Serikat yang, seiring perkembangan sejarah, dimaknai oleh warga Amerika Serikat sebagai perang antarsaudara (‘brothers’), kendati realitas politis saat itu adalah perang antara dua negara berbeda yang sama-sama berdaulat; serta anggapan orang Inggris bahwa William Sang Penakluk, ‘raja’ di (wilayah yang kini disebut sebagai) Inggris pada abad ke-11, adalah orang Inggris, kendati William bahkan tak mampu berbahasa Inggris. “Pertama sebagai tragedi, kedua sebagai lelucon” (h. 187–206).[37]
Dialog, Kritik, Otokritik: Diskursus dan Realitas Ke-bangsa-an Pasca-Imagined Communites
Selama lebih dari tiga puluh tahun pasca terbitnya Imagined Communities, dunia berganti rupa dengan pesat. Bagaimana kedudukan tesis-tesis Anderson di hadapan perkembangan sosial, politik, kebudayaan dan teknologi? Bagaimana tanggapan intelektual terhadap permasalahan bangsa, ke-bangsa-an, dan nasionalisme, baik berdasarkan argumen dalam Imagined Communities maupun dalam tradisi pemikiran lain?
Dalam edisi revisi Imagined Communities yang terbit pada tahun 1991, Anderson mengamati perkembangan dunia dalam delapan tahun sejak pertama terbitnya buku tersebut. ”Tak hanya dunia yang berganti wujud”, tulis Anderson. “Kajian nasionalisme secara tersentak mengalami transformasi dalam metode, skala, kecanggihan, dan kuantitas. “Kajian tersebut mengalami pemekaran yang begitu pesat, yang kemudian mengaitkan diri pada kajian-kajian lain seperti sejarah, sastra, antropologi, sosiologi, feminisme dan bahasan-bahasan lain yang “menghubungkan objek dari bidang penyelidikan tersebut pada nasionalisme dan bangsa.” Menariknya, dalam edisi revisi ini, Anderson mengambil sikap untuk tidak merombak atau memperbarui tesis-tesis utamanya, dan ‘hanya’ menambahkan dua bab baru di akhir buku mengenai sensus, peta dan museum, serta polemik ‘ingatan nasional’ dalam narasi historis. Dalam kata lain, Anderson memilih membiarkan Imagined Communities sebagai ‘karya-periode yang ‘tak dipulihkan’, dengan gaya, siluet, dan gairah yang khas’. Kendati teks Imagined Communities per se relatif tak tergerus oleh gejolak perubahan dunia, subjek-subjek pembahasannya serta bidang penyelidikannya menjadi fokus diskusi dan perdebatan di kalangan akademisi, serta menjadi realitas yang dialami langsung oleh orang-orang biasa di seluruh dunia, yang berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa tak semua perubahan membawa kebaikan alih-alih perusakan dan ketimpangan yang semakin besar (h. xii–xv).[38]
Manuel Castells: Pemosisian Bangsa, Ke-bangsa-an dan Nasionalisme dalam Konteks Kontemporer
Salah satu pemikir dan pengamat yang paling berpengaruh dalam merangkum perubahan-perubahan global menjelang akhir abad ke-20 adalah Manuel Castells. Seorang sosiolog Kiri berkebangsaan Spanyol, pada dasawarsa 1990-an Castells menulis proyek trilogi buku berjudul The Information Age: Economy, Society and Culture. Serial tersebut mengamati dan menganalisis proses perubahan sosial, politis, ekonomi, teknologi dan kultural, yang melanda dunia sejak paruh-akhir abad ke-20 hingga penghujungnya, melalui tiga dimensi sosiologis: produksi, kekuasaan, dan pengalaman. Volume kedua dari trilogi tersebut, The Power of Identity (1997), membahas perubahan-perubahan pada pola pembentukan identitas dalam berbagai tingkatan analitis yang berbeda, mulai dari identitas komunitas urban di tengah penistaan urban, munculnya gerakan fundamentalisme agama,[39] hingga berbagai wujud pemaknaan terhadap identitas bangsa dalam konteks keterbenturan ‘Diri’ dengan ‘Net’ di era ‘kapitalisme informatif’, yang ditandai oleh “transformasi dari fondasi-fondasi material dari kehidupan, ruang, dan waktu, melalui pembentukan ruang-arus dan waktu-abadi, sebagai ekspresi-ekspresi dari aktivitas-aktivitas dominan dan elit-elit yang memegang kendali.”[40]
Menurut Castells, masa globalisasi juga merupakan masa kebangkitan nasionalis, yang ditandai oleh munculnya tantangan terhadap negara-bangsa yang terkonsolidasi, serta tersebar luasnya rekonstruksi identitas atas basis kebangsaan. Fenomena tersebut hadir di tengah seruan bahwa ‘nasionalisme telah mati’—kematian yang (seharusnya) diakibatkan oleh:
- globalisasi ekonomi dan internasionalisasi institusi-institusi politis;
- universalisme budaya yang tersebar oleh media elektronik, pendidikan, keaksaraan, urbanisasi dan modernisasi; serta
- serangan akademis terhadap konsep bangsa (terutama oleh Gellner dan Hobsbawm).[41]
Menjelang tutup abad, Castells mengamati adanya dua fenomena yang khas dari periode sejarah mutakhir:
- disintegrasi negara bangsa-majemuk yang berusaha tetap berdaulat secara penuh, atau menolak pluralitas dari konstituen nasionalnya (‘quasi-negara-bangsa (quasi-nation-states)’ yang berbagi kedaulatan dengan bekas negaranya atau dengan konfigurasi politis yang lebih luas); dan
- pembentukan dari bangsa yang berhenti tepat di ambang kenegaraan, namun memaksa negara-induknya untuk beradaptasi dan menyerahkan kedaulatan (‘bangsa quasi-negara/national quasi-states’) yang berhasil memenangkan sebagian otonomi politis atas dasar basis identitas nasional).
Castells lantas menunjukkan bahwa fenomena meledaknya berbagai corak nasionalisme di akhir milenium—berkaitan dengan pelemahan negara-bangsa—tak sesuai dengan model teoritis yang mengasimilasikan bangsa dan nasionalisme dengan kemunculan dan terkonsolidasinya negara-bangsa modern pasca-Revolusi Perancis, yang ia akui, memang berlaku pada sebagian besar dunia sebagai cetakan awalnya. Menurut Castells, ketaksesuaian antara beberapa teori sosial dan praktik kontemporer berakar pada fakta bahwa nasionalisme dan bangsa memiliki logikanya sendiri yang terlepas dari logika kenegaraan, kendati tertancap pada konstruksi-konstruksi kultural dan proyek-proyek politik. Selanjutnya Castells menuturkan beberapa contoh konfigurasi bangsa dan negara yang mencerminkan ketakterkaitan antarlogika tersebut:
- bangsa tanpa negara (Catalunya, Basque, Kurdistan, Skotlandia, atau Quebec);
- negara tanpa bangsa (Singapura, Taiwan, atau Afrika Selatan);
- negara majemuk-bangsa (bekas Uni Soviet, Belgia, Spanyol, atau Inggris Raya);
- negara bangsa-tunggal (Jepang);
- negara bangsa-bersama (Korea Selatan dan Korea Utara); dan
- bangsa berbagi negara (orang Swedia di Swedia dan Finlandia, orang Irlandia di Irlandia dan Inggris Raya).[42]
Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa kewarganegaraan tak serupa dengan kebangsaan yang eksklusif. Berdasarkan pengamatannya, Castells menuturkan empat poin analitis yang perlu ditekankan manakala membahas nasionalisme kontemporer vis-à-vis teori-teori sosial tentang nasionalisme:
- nasionalisme kontemporer mungkin atau mungkin tidak berorientasi pada pembentukan negara-bangsa yang berdaulat;
- bangsa dan negara-bangsa tak terbatas secara historis pada negara-bangsa modern, sebagaimana terbentuk di Eropa dalam dua ratus tahun setelah Revolusi Perancis;
- nasionalisme belum tentu merupakan fenomena elit, dan nasionalisme masa sekarang lebih sering merupakan respons terhadap elit-elit global; dan
- karena nasionalisme kontemporer lebih bersifat reaktif alih-alih proaktif, ia cenderung lebih kultural alih-alih politis, dan lebih berorientasi pada pertahanan budaya yang telah terinstitusionalisasi alih-alih pembentukan atau pertahanan negara.[43]
Berhubungan dengan Imagined Communites, Castells mempersoalkan definisi Anderson tentang bangsa sebagai ‘komunitas-terbayang’ sebagai definisi yang secara analitis tak terlalu relevan. Namun lebih dari itu, tafsir Castells mengkritik analisis Anderson dan Hobsbawm tentang nasionalisme sebagai sumber identitas yang direduksi pada periode historis yang spesifik dan pada logika kerja internal dari negara-bangsa modern. Menurut Castells, pereduksian tersebut mustahil untuk menjelaskan keserentakan antara kebangkitan nasionalisme ‘pascamodern’ dan kemerosotan negara modern. Sebaliknya, Castells menawarkan beberapa tesis berikut:
- bangsa adalah komune-komune kultural yang terkonstruksi dalam pikiran dan ingatan kolektif orang melalui sejarah dan proyek-proyek politis bersama;
- alih-alih komunitas-terbayang yang dikonstruksikan melalui aparatus-aparatus kekuasaan, bangsa diproduksi melalui pengalaman historis bersama, dan dituturkan dalam imaji dari bahasa-bahasa komunal;
- bahasa, khususnya bahasa yang telah terbentuk secara lengkap, merupakan atribut fundamental dari pengakuan-diri, dan dari ditegakkannya suatu perbatasan nasional yang tak kasatmata, yang tak semanasuka kewilayahan, dan tak seeksklusif etnisitas;[44]
- etnisitas, agama, bahasa, dan wilayah per se tak sanggup untuk membangun bangsa dan memantik munculnya nasionalisme—yang sanggup adalah pengalaman bersama.[45]
Chatterjee dan Kedaulatan Imajinasi Pascakolonial
Salah satu kritik yang paling eksplisit dan tajam terhadap tesis-tesis Anderson dalam Imagined Communities datang dari pemikiran dan tulisan Partha Chatterjee, seorang intelektual multidisiplin berkebangsaan India, yang utamanya bergerak di kajian subaltern dan pascakolonial. Chatterjee menulis dalam bukunya yang berjudul The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories (1993) bahwa:
Saya memiliki satu keberatan utama dengan argumennya Anderson. Jika nasionalisme-nasionalisme di sisa belahan dunia harus memilih komunitas-terbayangnya dari bentuk-bentuk ‘modular’ tertentu yang terlebih dahulu disediakan untuk mereka oleh Eropa dan Amerika, apa yang tersisa untuk dapat mereka bayangkan? Tampaknya, sejarah telah menetapkan bahwa kami yang berada di dunia pascakolonial hanya akan menjadi konsumen-abadi dari modernitas. Eropa dan Amerika, subjek-subjek sejatinya sejarah, telah, atas nama kami, memikirkan tak hanya tentang naskah dari pencerahan dan eksploitasi kolonial, tetapi juga tentang perlawanan antikolonial dan penderitaan pascakolonial kami. Bahkan imajinasi-imajinasi kami harus tetap terkolonisasi untuk selama-lamanya.[46]
Chatterjee melihat bahwa terdapat beberapa bentuk imajinasi nasionalis di Asia dan Afrika yang justru berbeda dengan bentuk-bentuk ‘modular’ dari masyarakat nasional yang dikembangkan oleh dunia Barat. Menurut Chatterjee, kelemahan Anderson dan pemikir-pemikir lainnya adalah bahwa mereka terlalu cenderung dalam melihat nasionalisme sebagai gerakan politis semata.[47] Chatterjee melihat kehadiran dimensi-dimensi lain dalam nasionalisme antikolonial yang tak dapat direduksi sebatas pada perjuangan politis. Nasionalisme antikolonial menciptakan ranah-kedaulatannya sendiri dalam masyarakat kolonial, jauh sebelum memulai pertarungan politis dengan kekuatan imperialis.
Chatterjee mengusulkan bahwa nasionalisme antikolonial membagi dunia institusi dan praktik sosial menjadi dua ranah:
- ranah material, yang merupakan ranah sisi-luar (outside) dari ekonomi, kenegaraan (statecraft), dan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang tampak lebih diungguli oleh dunia Barat ketimbang dunia Timur. Di ranah ini, keunggulan dunia Barat perlu diakui dan keberhasilan-keberhasilannya dipelajari dan digandakan; dan
- ranah spiritual, yang merupakan ranah sisi-dalam (inside) yang mengandung tanda-tanda ‘esensial’ dari identitas kultural. Semakin besar kesuksesan dalam meniru keterampilan dunia Barat, semakin besar kebutuhan untuk mempertahankan kekhasan dari suatu budaya spiritual.
Menurut Chatterjee, ‘formula’ dalam kedua ranah tersebut merupakan ciri fundamental dari nasionalisme-nasionalisme antikolonial di Afrika dan Asia. Logika dari dua ranah tersebut berimplikasi bahwa nasionalisme terlebih dahulu mendeklarasikan ranah spiritual sebagai wilayah kedaulatannya, dan melarang kekuatan (negara) kolonial untuk dapat mengakses dan berintervensi dalam ranah tersebut. Kendati demikian, alih-alih terhindar dari perubahan, ranah spiritual tersebut tetap mengalami perubahan melalui proyek nasionalisme untuk membentuk suatu budaya nasional ‘modern’ yang tetap bukan-Barat (non-Western). Di sinilah tempat kelahiran bangsa sebagai komunitas-terbayang.[48] Lantas, dalam ranahnya yang ‘sejati’ dan ‘esensial’, sebuah bangsa tetap berdaulat, kendati ranah material atau sisi-luarnya (negara) berada di tangan kekuasaan kolonial. Chatterjee melihat bahwa dinamika dari proyek historis tersebut sama sekali luput dari sejarah-sejarah konvensional, yang mana cerita nasionalisme bermula dengan kontestasi kekuasaan politis. Dengan demikian, menurut Chatterjee, upaya mendemarkasi dan mengidentifikasi dua ranah berbeda dalam dinamika masyarakat nasional merupakan upaya untuk “meruntuhkan klaim-klaim memutlakkan dari suatu historiografi nasionalis.”[49]
James Morris Blaut: Persoalan Kolonialisme dan Nasionalisme dalam Teori Marxis
Melalui pendekatan materialisme-historis, Marxisme hendak menjelaskan sejarah perkembangan masyarakat berdasarkan kondisi material dari moda produksi masyarakat, yang tercermin dari terbentuknya kelas-kelas sosial dan kontradiksi antaranya. Lantas, bagaimana Marxisme melihat ‘persoalan nasional’, seperti ketika soal unik ini muncul di awal abad ke-20, dan terlebih di tengah berbagai perkembangan dari perjuangan nasional yang juga diresahkan oleh Anderson? Pemikiran dan tulisan James Morris Blaut, profesor antropologi dan geografi dari Amerika Serikat, dapat membantu. Kendati Blaut tidak mengkritik Imagined Communities atau Anderson secara langsung, rangkaian pemikirannya berguna untuk memahami posisi ke-bangsa-an dan nasionalisme dalam perspektif Kiri yang lebih luas.
Blaut adalah salah satu intelektual yang paling bergairah dalam kajian Marxis mengenai nasionalisme dan kolonialisme, dan juga merupakan aktivis dalam gerakan kemerdekaan Puerto Rico. Dalam bukunya yang berjudul The National Question: Decolonizing the Theory of Nationalism (1987), Blaut secara tegas berposisi bahwa perjuangan nasional merupakan bentuk perjuangan kelas, dan menuturkan tujuan dari proyek intelektualnya sebagai upaya untuk “menggeneralisasi teori Marxis tentang perjuangan nasional; membenamkannya erat-erat dalam kerangka materialisme-historis yang lebih luas.” Blaut membatasi cakupan analitis dari pemikirannya pada perjuangan-perjuangan pembebasan nasional melawan kolonialisme dan neokolonialisme, yang menurutnya secara mendasar merupakan perjuangan-perjuangan yang progresif.[50]
Pertama, Blaut menyadurkan tiga posisi dan pandangan dari teori Marxis tentang nasionalisme atau perjuangan nasional yang muncul secara historis; dua pandangan pertama disebutkan oleh Blaut sebagai pandangan-pandangan yang ‘menyimpang’, sementara posisi sentral Marxisme berada pada poin nomor tiga, yang dibingkai oleh Marx dan Engels dan kemudian dikembangkan oleh Lenin:
- nasionalisme pada akarnya merupakan ide Eropa yang menyebar ke luar dari Eropa bagian barat-laut ke dunia kolonial. Dengan demikian, gerakan-gerakan pembebasan nasional tidak mencerminkan tanggapan masyarakat kolonial terhadap penindasasn dan supereksploitasi, melainkan merefleksikan penyebaran dari ‘ide tentang negara-bangsa’, atau ‘ide tentang kebebasan’;
- perjuangan-perjuangan nasional secara inheren bersifat borjuis, yang muncul serentak dengan kebangkitan borjuasi Eropa dan lahir di tempat-tempat lain sebagai bentuk revolusi borjuis atau kemunculan kapitalisme yang tertunda; signifikansi perjuangan nasional pasti menurut atau menjadi irasional, seiring dengan wujud kapitalisme yang mengalami internasionalisasi secara paripurna dan tak lagi memerlukan negara-bangsa; perjuangan-perjuangan nasional tak memiliki posisi yang signifikan dalam perjuangan-perjuangan kelas pekerja melawan borjuasi;[51]
- perjuangan nasional secara spesifik merupakan bentuk perjuangan kelas (yang tidak Eurosentris) untuk merebut kekuasaan negara, yang dapat diterapkan oleh kelas sosial manapun, termasuk kelas pekerja, dan merupakan arena kontestasi yang sentral dalam Dunia Ketiga sebagai respons terhadap penindasan-dari-luar dan supereksploitasi kolonial.
Menurut Blaut, permasalahan mendasar yang menghantui kajian Marxis, terutama dalam konteks pembahasan tentang perjuangan bangsa dan ke-bangsa-an, dapat dikatakan sebagai ‘difusiisme Eurosentris (Eurocentric diffusionism)’. Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan pendapat Blaut tentang ‘titik terlemah’ dari teori Marxis secara keseluruhan, yakni bagian yang hendak menjelaskan evolusi sosial pada skala yang terbesar, yang meliputi rangkaian sejarah manusia sejak terbitnya masyarakat kelas. Titik tersebut dianggap Blaut lemah karena secara relatif, kaum Marxis lantas mengetahui sangat sedikit tentang mode-mode produksi pra-kapitalis di manapun, dan tentang bentuk-bentuk perjuangan kelas pra-kapitalis. Blaut menjelaskan kritiknya dalam tiga poin utama yang menurutnya kerap dimiliki oleh kaum Marxis (dan yang, menurut Blaut, tumpah-ruah pula dalam kajian tentang nasionalisme dan perjuangan nasional):
- ‘kacamata kuda-historis (historical tunnel vision)’ tentang mode-mode produksi pra-kapitalis, yang melihat rangkaian mode dalam kolom ruang-waktu historis yang mencakup Eropa dan Timur Dekat, namun gagal untuk memiliki pemahaman yang layak tentang mode-mode produksi di belahan lain dunia pada titik sejarah tertentu, serta gagal untuk memiliki metodologi yang layak untuk komparasi antardaerah dan budaya. Kacamata kuda-historis membuat gagal upaya untuk mempertimbangkan kejadian-kejadian historis ekstra-Eropa sebagai data untuk generalisasi evolusioner historis;[52]
- ‘difusiisme geografis (geographical diffusionism)’ yang merupakan saudara dekat dari poin pertama, yang mengasumsikan bahwa peristiwa-peristiwa yang secara historis signifikan (inovatif dan memiliki konsekuensi evolusioner) terjadi hanya di tanah Eropa (dan, dalam konteks pra-Nasrani, di Timur Dekat dan Tanah-tanah Injil), kemudian menyebar ke seluruh dunia. Menurut Blaut, kedua proses berpikir di muka hanya menemukan penyebab-penyebab evolusioner di sektor Eropa, dan gagal melihat proses-proses yang terjadi di luar sektor tersebut, dan lantas gagal melihat proses-proses yang lebih besar yang membentuk evolusi sosial pada skala global;
- ‘keterkekangan-waktu (time-boundedness)’, yang menurut Blaut membentuk salah satu kontradiksi yang paling besar dalam praktik Marxis: di satu sisi, teori Marxis tentang evolusi sosial, yang didasari atas perjuangan kelas dan mode-mode produksi, memiliki semesta-diskursus yang mencakup keseluruhan sejarah dan geografi masyarakat manusia sejak kemunculan pertama mode produksi berbasis-kelas, bahkan lebih awal lagi; di sisi lain, kaum Marxis mengamati mode kapitalis secara miopik, sehingga mengasumsikan atribut-atribut utama dari mode kapitalis sebagai hal-ihwal yang khas pada mode tersebut saja, atau hanya pada fase kapitalisme industrial. Sebaliknya, menurut Blaut, berbagai ciri fundamental dari mode kapitalis tentunya merupakan ciri dari mode-mode berbasis-kelas terlampau, dan terkadang merupakan ciri dari masyarakat kelas secara umum.[53]
Selanjutnya, Blaut menyumbang pendekatan teoritis dalam melihat perjuangan nasional sebagai perjuangan kelas yang dalam konteks modern memiliki klasifikasi dan dimensi yang lebih beragam ketimbang dikotomi proletariat/borjuasi. Alur logika dari pendekatannya Blaut dapat diringkas sebagai berikut:
- sejarah perjuangan masyarakat kelas senantiasa berakar pada perjuangan kelas, terutama ketegangan dinamis antara kelas-kelas penguasa—mereka yang mengendalikan alat-alat produksi dan menuntut hasil produksi yang kian membesar—dan kelas-kelas pemroduksi;
- perjuangan tersebut sebagian besar telah melintasi batas-batas kultural dan politis, dan melibatkan perjuangan kelas pekerja dalam (atau dari) suatu masyarakat melawan dua kelompok-kelas pengisap: mereka yang datang dari masyarakat mereka sendiri (eksploitasi internal), dan yang datang dari masyarakat luar (eksploitasi eksternal);
- dari waktu ke waktu, muncul pula perjuangan-perjuangan kelas antarkelas penguasa, yakni antara kelas penguasa internal dan kelas penguasa eksternal;
- eksploitasi eksternal cenderung jauh lebih intens (supereksploitasi) ketimbang eksploitasi internal;
- secara historis, di era kapitalisme modern, signifikansi dari eksploitasi eksternal mengambil dua wujud yang berbeda:
- eksploitasi pekerja di wilayah-wilayah kolonial dan neokolonial yang jauh semakin intensif, diiringi oleh peningkatan proletarisasi; dan
- pengimporan pekerja dalam skala masif dari wilayah-wilayah tersebut ke dalam negara-negara kapitalis-maju;
- dalam dunia modern, politik dari perjuangan kelas eksternal menjadi apa yang disebut sebagai perjuangan nasional;
- perjuangan nasional—’nasionalisme’ dalam pengertiannya yang terluas—adalah bentuk kontemporer dari suatu proses mendasar yang hadir dalam masyarakat kelas secara keseluruhan, yang telah terjadi sejak zaman dahulu kala, yakni perjuangan kelas eksternal, atau lebih khususnya, perjuangan kelas untuk merebut kekuasaan negara manakala kelas penguasa bersifat eksternal atau ‘asing’, kendati sifat ke-kelas-annya dapat dikaburkan oleh etnisitas dan kerumitan-kerumitan lainnya;
- perjuangan nasional ditempuh oleh kelompok-kelompok kelas yang berbeda dalam mode-mode produksi yang berbeda, baik kelompok-kelompok pengisap maupun kelompok-kelompok terisap;
- kontradiksi pokoknya adalah kontradiksi antara kelas-kelas pengisap dan terisap yang saling berkontestasi;
- gerakan-gerakan nasional bersifat progresif dan signifikan sejauh kekuatan-kekuatan kelas utamanya adalah proletariat dan kelas-kelas tereksploitasi dan marginal, seperti yang tampak dalam perjuangan-perjuangan melawan kolonialisme.[54]
Anderson: Refleksi dan Otokritik
Beberapa hari sebelum meninggal dunia, Anderson tengah mengoreksi naskah dari memoarnya yang berjudul A Life beyond the Boundaries, yang diterbitkan di Jepang pada tahun 2008, dan sedang dipersiapkan untuk diterbitkan oleh Verso pada bulan Maret depan. Salah satu penyarian dari refleksi tersebut diterbitkan dalam bentuk esai di London Review of Books, yang berjudul ‘Frameworks of Comparison’. Dalam tulisan tersebut, Anderson menuturkan tentang pasang-surut dan dinamika perjalanan intelektualnya, dan juga lingkungan-lingkungan akademis maupun keseharian yang berkontribusi pada pola pikir dan tulisannya, tak terkecuali sebagai ‘medan perang’ untuk argumen-argumen dari berbagai karyanya.
Dalam ‘Frameworks of Comparison’, terdapat tiga kontra-argumen utama yang menjadi fondasi keresahan dalam menuliskan Imagined Communities, yang telah disebutkan di muka di bagian ‘Relevansi dan Tujuan Pengkajian’. Selain itu, Anderson juga mengakui bahwa golongan pembaca yang awalnya dituju oleh Imagined Communities adalah inteligensia Inggris, yang menjelaskan banyaknya kutipan dan rujukan pada legenda, sejarah, esai dan puisi Inggris, yang mungkin tak mudah dipahami konteksnya oleh pembaca yang bukan orang Inggris.
Anderson juga merefleksikan metode komparatifnya dalam menganalisis dan menjelaskan proses dan fenomena. Dalam Imagined Communities, Anderson mampu mengaitkan Amerika Serikat dengan bangsa-bangsa di Amerika Selatan. Rusia di masa Tsar dengan India di masa kolonial Inggris, Hungaria dengan Siam dan Jepang, Indonesia dengan Switzerland dan Vietnam dengan Afrika Barat milik Perancis. Perbandingan-perbandingan tersebut diakui oleh Anderson sebagai upaya untuk “mengagetkan dan mengguncangkan.” tetapi juga untuk ”mengglobalisasi kajian tentang sejarah dan nasionalisme.” Kendati mengajar di bidang ilmu politik/pemerintahan, Anderson menyebutkan bahwa jenis-jenis perbandingan tersebut jauh berbeda dengan yang biasa dilakukan di kajian pemerintahan komparatif, yang berbasiskan statistik dan survey.[55]
Anderson tentu mengetahui dan membaca berbagai kritik dan masukan akademis yang dilontarkan kepadanya. Pengantar untuk edisi revisi 1991 pun mengakui dan menyebutkan beberapa di antaranya secara eksplisit, termasuk Nationalist Thought and the Colonial World (1986) karya Partha Chatterjee yang memuat kritik awalnya terhadap Anderson dan pemikir-pemikir ‘nasionalis’ lainnya. Dalam beberapa kalimat dalam ‘Frameworks of Comparison’, Anderson kemudian tak hanya menuturkan otokritiknya terhadap kelemahan-kelemahan teoritisnya yang terkandung dalam Imagined Communities, tetapi juga mengakui lebarnya spektrum kritik yang menyusul terbitnya buku tersebut (perhatikan pilihan kata-katanya), serta menunjukkan pula kesadarannya terhadap kontekstualisasi kontemporer serta perkembangan kematangan cakupan intelektualnya pasca-Imagined Communities:
Baru setelah lama kemudian, bahkan setelah saya pensiun, saya mulai menyadari kekurangan fundamental dari tipe perbandingan tersebut: bahwa menggunakan bangsa dan negara-bangsa sebagai unit analisis dasar, secara fatal mengabaikan fakta yang kentara, bahwa dalam kenyataannya, unit-unit tersebut terikat satu sama lain dan terlintasi oleh arus-arus politis-intelektual global seperti liberalisme, fasisme, komunisme dan sosialisme, serta jaringan-jaringan religius yang luas dan kekuatan-kekuatan ekonomi dan teknologi. Saya juga jadinya harus menanggapi dengan serius realitas bahwa sedikit sekali orang yang pernah semata-mata menjadi nasionalis belaka. Kendati betapa kuatnya nasionalisme mereka, mereka juga dapat terjangkit oleh film-film Hollywood, neoliberalisme, selera terhadap manga, Hak Asasi Manusia, bencana-bencana ekologis yang akan terjadi, mode busana, ilmu pengetahuan, anarkisme, pascakolonialitas, ‘demokrasi’, gerakan-gerakan masyarakat adat, ruang-ruang chat, astrologi, bahasa-bahasa supranasional seperti Spanyol dan bahasa Arab dan sebagainya.[56]
Komentar Bacaan: Imagined Communities dan Realitas Perubahan
Membaca Imagined Communities terasa seperti tengah membaca novel yang menggigit—hampir-hampir setara dengan denyut-pikir yang dirasakan saat membaca serial Game of Thrones karya George R. R. Martin: penuh-sesak dengan nama-nama aneh, kejadian-kejadian masa lampau, plot twist, dan kebiasaan naratif yang hobi memindahkan pembaca dari satu sudut pandang ke sudut pandang berlawanan: halaman sekarang tangisan darah Stark, halaman berikutnya canda tawa Lannister; kini Rama V (Chulalongkorn) dari Siam pada akhir abad ke-18 mengirim anak-anaknya untuk mencari ilmu di St. Petersburg, London, dan Berlin, berikutnya pelantikan anaknya menjadi Rama VI yang dihadiri oleh pangeran-pangeran dari Inggris, Rusia, Yunani, Swedia, Denmark, dan Jepang; kini Imperium Britania melebarkan sayap-sayap imperialis-hibridanya di koloni India, berikutnya fakta bahwa belum pernah ada raja atau ratu Inggris yang berasal dari dinasti ‘Inggris’ sejak abad ke-11. Perbandingan-perbandingan yang dituturkan tampak menegaskan posisi Anderson tak hanya sebagai akademisi yang bergelut dalam ‘kajian komparatif’, melainkan intelektual yang turut merevolusionerkan disiplin kajian komparatif itu sendiri, yang oleh Anderson disebut sebagai suatu ‘strategi diskursif’.[57]
Anderson menulis Imagined Communities dengan gaya yang mengalir, legit dan gurih, memukau, dan sarat-humor, dengan penggunaan visualisasi dan analogi yang kerap kali membuat kita tercengang: kekhidmatan dan kesakralan dari kehadiran kuburan tentara nasional tak bernama vis-à-vis ketakmasukakalan hipotetis dari fenomena kuburan kaum Marxis atau Liberal yang tak bernama pula; bagaimana Soekarno ‘mengingatkan’ rakyatnya bahwa Indonesia telah dijajah Belanda selama 350 tahun, kendati ‘Indonesia’ sendiri adalah penemuan abad ke-20, dan mayoritas wilayah-kuasa ‘Indonesia’ baru dikuasai oleh Belanda antara tahun 1850 dan 1910; atau bagaimana Pangeran Diponegoro mengakui ingin ‘menguasai Jawa’ alih-alih ‘membebaskannya’ atau ‘mengusir Belanda’. Selera humornya Anderson terlihat dalam pengakuannya bahwa dirinya menulis nama-nama monarki Inggris dengan nama aslinya sebagaimana orang-orang biasa (Charles Stuart untuk Charles I), namun tetap menggunakan format penamaan standar untuk pemimpin-pemimpin asing (Louis XIV), hanya sebagai plesetan untuk para pembaca Inggris (Anderson sendiri berkebangsaan Irlandia!), yang kendati demikian menjadi masuk akal ketika kita pertimbangkan kritik Anderson terhadap Eurosentrisme sebagai salah satu tujuan penulisan Imagined Communities.[58]
Selain itu, Imagined Communities memperlihatkan serat-serat humanisme dan keberpihakan Anderson pada kaum yang lemah, dan terlebih, kaum yang kalah: kutipan-kutipan sastra—salah satu metode komparatif yang paling diandalkan oleh Anderson, yang mencerminkan pendidikan sastra klasiknya saat menjadi mahasiswa di Cambridge—kerap kali menunjukkan konteks sosial yang sarat dengan ketimpangan kuasa dan perjuangan melawan status quo, yang tampak dari pilihan penulis yang mewarnai narasi tentang perkembangan nasionalisme: contohnya, José Rizal dan Último Adiós (puisi terakhirnya yang ditulis saat menunggu dihukum mati oleh imperialisme Spanyol), serta Mas Marco Kartodikromo dan Semarang Hitam (yang salah satu adegannya secara tajam menggambarkan penderitaan kaum papa). Tampak pula kesinisan Anderson pada relasi kuasa monarki dan dinastik, terutama dalam konteks Inggris, seperti ketika Anderson dengan cemerlang menunjukkan bagaimana lagu kebangsaan Inggris, God Save the Queen, sarat dengan unsur-unsur kebencian dan ketakutan terhadap musuh dari Luar, yang bertumpu pada konsepsi penghambaan pada ratu atau raja.
Sebagai ilmuwan sosial, tulisan Anderson sama sekali tak mencerminkan modus kerja yang nomotetik (deduktif). Gaya penulisan Anderon berbeda jauh dengan model-model sosiologis-cum-taksonomis ala Manuel Castells, yang cenderung mengabstraksikan fenomena ke dalam taksonomi-taksonomi teoritis; Anderson menuliskan fenomena dengan apa adanya, dengan gaya yang naratif dan komparatif. Sebagai gambaran, Anderson bahkan tak pernah memberikan penamaan yang jumud dan taat asas perihal ‘nasionalisme-populer (popular nationalism)’—terkadang Anderson menggunakan istilah tersebut, terkadang Anderson menggunakan istilah ‘nasionalisme-bahasa-rakyat (vernacular nationalism)’, ‘nasionalisme-linguistik (linguistic nationalism)’, atau berbagai variasi dari yang di muka, seperti ‘nasionalisme-linguistik populer (popular linguistic nationalism)’ dan ‘nasionalisme-bahasa-rakyat populer (popular vernacular nationalism)’. Serupa, beberapa istilah yang digunakan dalam tinjauan ini, seperti ‘legitimasi emosional’, tak pernah dieksplisitkan oleh Anderson sebagai klasifikasi terminologi baku alih-alih en passant.[59]
Perihal tanggapan-tanggapan akademis, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari kritik-kritik Castells dan Chatterjee, sumbangan perspektifnya Blaut, dan otokritik serta refleksinya Anderson. Kritik Castells terhadap Anderson perihal pengonsolidasian negara-bangsa sebagai parameter keberhasilan dari nasionalisme, serta sebagai satu-satunya unit analisis politis, relevan dalam mengamati ketidakmampuan dari parameter dan unit analisis tersebut untuk menjelaskan beberapa fenomena ke-negara-an dan ke-bangsa-an yang mutakhir, seperti munculnya ISIS/ISIL yang keanggotaannya berbasiskan identitas religius alih-alih terbentuk oleh identitas kebangsaan; bangsa tanpa negara seperti Kurdistan; dan lain-lain. Selain itu, tampak ada persamaan antara kritik Castells dan kritik Chatterjee, terutama perihal implikasi dari logika nasionalisme yang tak melulu berkaitan dengan proses dan institusi politis. Sebenarnya, apa yang digambarkan oleh Chatterjee sebagai ranah ‘spiritual’ dari masyarakat memiliki persamaan dengan legitimasi emosional dari nasionalisme yang dijelaskan oleh Anderson—bedanya, Anderson tidak mengontekstualisasikan legitimasi emosional secara spesifik pada pemaknaan kultural dalam konteks pascakolonial. Di sisi lain, sumbangan teoritis Blaut mengenai materialitas dari perjuangan nasional sebagai bentuk perjuangan kelas yang dapat diterapkan oleh kelas manapun, tampak menguatkan analisis kelasnya Anderson terkait faktor-faktor kemunculan nasionalisme-creole, yang justru dimotori oleh para pemilik budak dan tuan tanah alih-alih kelas pekerja yang tertindas. Dari refleksinya Anderson dalam ‘Frameworks of Comparison’, Anderson mengakui keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam Imagined Communitiesvis-à-vis kontekstualisasi dari realitas pasca-1983, terlebih pada abad ke-21; kendati nasionalisme bukanlah laksana ‘-isme’ yang lain, dirinya tak dapat berdiri sendiri dan terbebaskan dari ‘arus-arus politis-intelektual’ yang lain.
Dari awal, Anderson memang tak pernah berpretensi untuk menulis kitab mutlak perihal nasionalisme (the final word on nationalism). Justru, di bagian ‘Pengakuan (Acknowledgements)’ dari edisi revisinya Imagined Communities, Anderson menulis secara rendah hati bahwa profesinya sebagai spesialis Asia Tenggara dapat menjelaskan bias-bias dan pilihan contoh yang ada dalam teks, serta mengempiskan pretensi-pretensi global yang tampaknya ada. Anderson menulis sumbangan bagi kajian ke-bangsa-an, dan mengakui keberadaan tepi-tepi penyelidikan (margins of inquiry) yang, secara alamiah serta sebagai konsekuensi logis, tentunya melahirkan kajian-kajian komplementer (bahkan kontradiktif) yang, dilihat secara keseluruhan, menengarai munculnya ruang-ruang penyelidikan tandingan yang semakin membangun dan mengasah konstruksi analitis dari keseluruhan kajian tersebut.
Sebagai tambahan, terdapat beberapa pengamatan dan titik kontekstualisasi yang dapat kita bangun antara argumen-argumen serta premis-premis Imagined Communities dan realitas yang kini kita alami—selain dari yang sudah dieksplisitkan oleh Castells, Chatterjee, Blaut, dan Anderson sendiri—lebih dari 30 tahun kemudian. Di awal buku, Anderson memberikan gambaran yang murung bahwa bangsa dibayangkan sebagai komunitas karena terdapat kekerabatan yang mendalam antar anggotanya, kendati realitas ketimpangan dan eksploitasi yang hadir di dalamnya. ‘Ketimpangan dan eksploitasi’ di muka secara ringkas tampak cocok untuk menggambarkan kondisi Indonesia saat ini dalam jeratan logika dan praktik neo-liberalisme dan jaringan oligarkis: perusakan sosial-ekologis melanda hampir seluruh wilayah kepulauan di bawah logika pengkavlingan spasial untuk melayani industri neo-ekstraktif;[60] kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga meningkat—termasuk pencabutan hak-hak politik, penggusuran, kekerasan dan pembunuhan—baik atas nama identitas politis, etnis dan agama, maupun atas nama peningkatan laba bisnis dan pembangunan negara yang difasilitasi oleh aparat negara;[61] jubah pragmatisme partai-partai politik membungkusi logika dan praktik predatorisnya;[62] korupsi dan ketimpangan alokasi sumber daya meningkat dan merajalela;[63] dan sebagainya.
Menariknya, penderitaan dan perusakan yang menimpa dan dialami oleh warga negara justru beriringan dengan inisiasi program bela negara yang secara masif difasilitasi oleh negara, yang bertujuan menanamkan lima nilai dasar, yakni “cinta Tanah Air, rela berkorban, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin dengan ideologi Pancasila dan UUD 45, serta Bhinneka Tunggal Ika.”[64] Dalam kata lain, kesadaran, identitas dan esprit de corps nasional sebagai ‘bangsa’ hendak didongkrak—’kekerabatan yang mendalam’—yang sayangnya, membunyikan lonceng di kepala tentang ingatan (sosial) kita terhadap rezim Orde Baru dan kooptasi dan korupsi ideologisnya terhadap pemaknaan dari ‘bangsa’ dan ‘warga’ itu sendiri.
Penting untuk menganalisis pernyataan dari Kepala Badiklat Kemenhan, Mayjen Hartind Asrin: “Anak kecil ditanamkan kebanggaan kepada negaranya. Makanya kita sasar anak PAUD karena anak usia dini lima sampai sembilan tahun itu long term memory-nya sangat bagus. Kemarin sudah dicoba sehari anak-anak diminta menggambar bendera Merah Putih, pulau-pulau di Indonesia.”[65] Yang patut menjadi perhatian adalah pemosisian konstruksi ingatan jangka-panjang anak-anak melalui simbol-simbol ke-bangsa-an (ingatan palsu?)—serupa dengan yang ditulis Anderson mengenai praktik ‘penulisan ulang narasi historis’—di hadapan realitas ingatan sosial warga, yang, baik secara jangka panjang maupun jangka pendek, mengalami perusakan dan kerusakan dalam segala sendi kehidupan, tak terkecuali oleh mereka yang justru diamanatkan sebagai pelayan publik.
Poin kontekstualisasi kedua yang dapat ditarik adalah mengenai fungsi dan signifikansi novel dan koran sebagai produk-produk unggulan kapitalisme-percetakan vis-à-vis perubahan mode temporalitas sosial, ritme masyarakat dan implikasi revolusi teknologi informasi. Anderson menuturkan bahwa novel dan koran memiliki peran dan fungsi yang signifikan dalam proses pembentukan kesadaran nasional, terutama dalam (namun tak terbatas pada) model nasionalisme-creole dan nasionalisme-populer. (Anderson lantas secara cemerlang mengutip Hegel yang mengomentari bahwa Koran “melayani manusia modern sebagai substitusi untuk doa modern.”) Pertanyaannya: bagaimana posisi novel dan koran sekarang—’doa modern’—di hadapan perubahan-perubahan teknologi dan kapitalisme-media, yang instrumennya kini tak lagi sekadar tinta dan kertas alih-alih layar dan laman? T. J. Clark memberikan pengamatan yang tajam terhadap titik kontekstualisasi tersebut dalam tinjauannya yang berjudul ‘In a Pomegranate Chandelier’:
…koran semakin tak menjadi substitusi untuk apapun, dan di sebagian besar dunia, doa-doa pagi tak lagi dapat tersubstitusi oleh bentuk representasi privat (publik) seperti di muka. Kapitalisme-layar tengah melarutkan struktur dari kebersamaan privat (publik). [Kapitalisme-layar] tengah menghancurkan keserentakan sunyi dari waktu-jam … Acara di layar adalah unik dan abadi. Ia kembali menjadi milik Tuhan atau Iblis. Laman dan video telepon genggam merupakan jalur-jalur menuju yang-sakral. Doa pagi ada di mana-mana.[66]
Selain ancaman ketakrelevansian dari koran di hadapan banalitas dari perubahan pola diseminasi informasi dalam masyarakat, pembahasan Anderson mengenai perubahan mode temporalitas—bahasan yang implikasi dan manifestasinya kerap muncul di sepanjang Imagined Communities—tampak relevan dengan pembahasan Bender dan Wellbery mengenai ‘kronotipe’, yakni model atau pola yang: melaluinya, waktu memiliki signifikansi praktik atau konseptual; bersifat temporal dan majemuk; terus-menerus diproduksi dan direproduksi pada tingkatan-tingkatan individu, sosial, dan kultural yang berbeda; berinteraksi dan berubah kian kemari; dan memiliki sejarah yang penafsirannya merupakan konstruksi temporal. Terminologi Anderson yang meminjam dari Walter Benjamin, ‘waktu-Messianic’ dan ‘waktu homogen-kosong’, dapat diklasifikasikan sebagai jenis-jenis kronotipe tertentu. Waktu tidak diberikan alih-alih dirajut dalam proses yang berkepanjangan.
Pembahasan tersebut berkaitan erat dengan refleksinya Muhammad Al-Fayyadl, yang secara mencerahkan menunjukkan bagaimana Anderson berhasil menafsirkan materialitas dari waktu sebagai “kekuatan produksi dalam sejarah” dan “class struggle dalam ranah temporalitas,” dan bahwa “penyeragaman waktu, dengan demikian, bisa dibaca sebagai cara baru rezim-rezim politik untuk menundukkan dan menguasai orang-orang.” Pengamatan Al-Fayyadl menarik benang merah antara perubahan mode temporalitas kontemporer di era revolusi teknologi informasi dan upaya membangun perjuangan kelas yang melihat waktu sebagai arena kontestasi untuk direbut. Pertanyaannya kemudian: apakah perubahan yang dituturkan oleh Anderson, dari waktu-Messianic menjadi waktu-homogen-kosong, bersifat linier dan deterministik? Dalam konteks ke-bangsa-an, apakah mungkin terdapat kronotipe-kronotipe partikelir dalam konteks masyarakat intra-bangsa yang masih berpegang teguh pada konsepsi spasio-temporalitas lokal? Bagaimana wujud amalgamasi dari dua (atau lebih) kronotipe yang hadir secara serentak dalam masyarakat yang sama, dan bagaimana implikasinya pada mode produksi mereka?[67]
Penutup: Tempurung and its Discontents
Suara itu hanya terdengar beberapa detik saja dalam hidup. Getarannya sebentar berdengung, takkan terulangi lagi. Tapi seperti juga halnya dengan kali Lusi yang abadi menggarisi kota Blora, dan seperti kali itu juga, suara yang tersimpan menggarisi kenangan dan ingatan itu mengalir juga—mengalir kemuaranya, kelaut yang tak bertepi. Dan tak seorangpun tahu kapan laut itu akan kering dan berhenti berdeburan.
Hilang.
Semua itu sudah hilang dari jangkauan panca-indera.
—Pramoedya Ananta Toer, ‘Yang Sudah Hilang’ dalam Tjerita dari Blora (1952). Dikutip oleh Anderson dalam Imagined Communities, h. 147–148.
Om Ben pernah berefleksi perihal jenakanya iklim akademis di subbagian Pemerintahan Komparatif, bagian dari Departemen Ilmu Politik di Cornell University, yang condong fokus pada wilayah Eropa Barat dan tidak membahas negaranya sendiri (Pemerintahan Amerika menjadi subbagian tersendiri dan sarat dengan pragmatisme mahasiswa untuk memajukan karier politis domestiknya). Disiplin tersebut bahkan tak memiliki mata kuliah mengenai politik di dua negara tetangga terdekat, yakni Meksiko dan Kanada. Dengan selera humornya yang khas, Om Ben menggambarkan watak akademis tersebut sebagai mentalitas “frog under the coconut shell” (betapa jenakanya bunyi peribahasa manakala diterjemahkan). Tidak berhenti di situ, Anderson kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai katak tersebut:
Kendati bahasa Thai dan bahasa Indonesia tak memiliki keterkaitan dan tergolong dalam silsilah linguistik yang cukup berbeda, keduanya telah lama memiliki imaji fatalistis tentang seekor katak yang sepanjang hidupnya tinggal di bawah separuh tempurung kelapa—biasa digunakan sebagai mangkok di negara-negara tersebut. Duduk-diam di bawah tempurung, tak lama kemudian sang katak mulai merasa bahwa tempurung kelapa meliputi seluruh alam semesta. Kesimpulan moral dalam imaji tersebut adalah bahwa sang katak berpikiran sempit, lokal-dan-terkucil, diam-di-rumah, dan puas-diri tanpa alasan berarti. Dalam kasusku, aku tak cukup lama berdiam diri di satu tempat untuk dapat menetap di sana, tak seperti katak dalam peribahasa.[68]
Pengakuan Om Ben di akhir menggambarkan secara indah sosoknya sebagai pelajar seumur hidup: rendah hati, dan tak pernah berhenti melihat dunia dengan penuh rasa keingintahuan dan kekaguman. Tanggal 13 Desember silam, Om Ben meninggalkan dunia ini untuk selamanya, tetapi jangan pernah kita lupa: jauh sebelum hari tersebut tiba, Om Ben terlebih dahulu meretas jalan keluar dari tempurungnya dan berhasil lolos ke bentangan-pemikiran baru, tak lagi terkekang oleh sempit dan gelapnya tempurung-keserbapuasan. Om Ben menyaksikan matahari-pengetahuan terbit di ujung cakrawala-keingintahuan, lantas kembali terbenam dan menjelma menjadi malam-keresahan. Pemandangan dan rona-rona indah di sekelilingnya tak membuat Om Ben terlena dan lupa daratan. Di tanah barunya, Om Ben berkawan dengan orang-orang biasa, mereka yang lemah dan dinistakan, yang sepanjang hidupnya dibebankan dengan pemahaman bahwa bahasa ibu mereka tak mampu menuturkan makna yang berarti. Keresahannya lantas mendorongnya untuk terus mengetuk-pelan tempurung-tempurung lain yang berserakan di sekitarnya, dan, sambil tersenyum, mengajak katak-katak lain untuk berani memecahkan tempurungnya masing-masing.
Reruntuhan tempurungnya Om Ben masih dapat kita lihat pada permasalahan-permasalahan dalam setiap karya tulisannya, yang terlubangi oleh pertanyaan-pertanyaan tajam yang Om Ben ajukan. Om Ben tak pernah berpretensi mengetahui jawaban dari setiap pertanyaan yang dia ajukan—bukan itu intinya—tetapi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, katak-katak lain diharapkan tak dapat tidur nyenyak di malam hari, tertular oleh keresahan yang sama, lantas bergerak oleh keingintahuan yang sama dan mendobrak dengan semangat yang sama pula. Al-Fayyadl tak salah dalam menghormati Om Ben sebagai seorang filsuf—tetapi kita tentu tak lupa pada pernyataan Marx di ‘Tesis Kesebelas Tentang Feurbach’. Alih-alih sebatas menginterpretasi, melalui rangkaian tuturannya, Om Ben mengubah cara kita melihat dunia; alih-alih berdiam diri, Om Ben berpihak pada yang lemah dan yang kalah, mempertaruhkan karier akademisnya dan tempurung-tempurung-identitas lain yang terbayang—hingga sampai pada titik ini, hanya ada satu seruan yang patut digaungkan:
”Para katak seluruh dunia, bersatulah! Kalian hanya akan kehilangan tempurung!”
Kepustakaan
Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Edisi revisi. London: Verso, 1983.
————. ‘Old State, New Society: Indonesia’s New Order in Comparative Historical Perspective’. The Journal of Asian Studies. 42.3 (1983): 477–496. http://www.jstor.org/stable/2055514. Diakses 10 Juni 2015.
————. ‘Frameworks of Comparison’. London Review of Books. 38.2 (2016). http://www.lrb.co.uk/v38/n02/benedict-anderson/frameworks-of-comparison. Diakses 16 Januari 2016.
Bender, John dan David E. Wellbery, eds. Chronotypes: The Construction of Time. Stanford: Stanford University Press, 1991.
Blaut, James M. The National Question: Decolonizing the Theory of Nationalism. London: Zed Books, 1987.
Castells, Manuel. The Rise of the Network Society. Malden: Blackwell, 1996.
————. The Power of Identity. Malden: Blackwell, 1997.
Chatterjee, Partha. The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton: Princeton University Press, 1993.
Clark, T. J. ‘In a Pomegranate Chandelier’. London Review of Books. 28.18 (2006). http://www.lrb.co.uk/v28/n18/tj-clark/in-a-pomegranate-chandelier. Diakses 24 Januari 2016.
Fentress, James dan Chris Wickham. Social Memory. Oxford: Blackwell, 1992.
Harvey, David. Spaces of Capital: Towards a Critical Geography. New York: Routledge, 2001.
Herry-Priyono, B. ‘Kota dan Harta: Perihal Jarak antara Jakarta dan Indonesia’. Seri ke-5 dalam rangkaian Studium Generale mengenai Philosophy in the City. Jakarta: Goethe-Institut Jakarta, 15 Oktober 2009.
Marx, Karl. ‘Chapter I (Feb. 1848 to Dec. 1851)’. The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. Marx/Engels Internet Archive (marxists.org). 1999. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/. Diakses 21 Januari 2016.
Rachman, Noer Fauzi dan Dian Yanuardy, eds. MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2014.
Riaz, Ali. ‘Global Jihad, Sectarianism and the Madrassahs in Pakistan’. Working Paper. Institute of Defence and Strategic Studies, Singapore. Agustus 2005.
Robison, Richard dan Vedi R. Hadiz. Reorganising Power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. London: Routledge, 2004.
Berita dan media internet
Al-Fayyadl, Muhammad. ‘Benedict Anderson: Seorang Filsuf’. LSF Cogito. 14 Desember 2015. http://lsfcogito.org/benedict-anderson-seorang-filsuf/. Diakses 21 Januari 2016.
Boediwardhana, Wahyoe. ‘Antimining activist beaten to death in East Java’. Jakarta Post. 28 September 2015. http://www.thejakartapost.com/news/2015/09/28/antimining-activist-beaten-death-east-java.html. Diakses 25 Januari 2016.
Hussein, Mohamad Zaki. ‘Fakta Singkat Konflik Agraria di Indonesia’. Inkrispena. 17 Maret 2015. http://inkrispena.org/fakta-singkat-konflik-agraria-di-indonesia/. Diakses 24 Januari 2016.
‘Jenderal Luhut Kenang Pertempuran di Timor Timur’. Merah Putih. 10 November 2015. http://news.merahputih.com/peristiwa/2015/11/10/jenderal-luhut-kenang-pertempuran-di-timor-timur/32394/. Diakses 16 Januari 2015.
Kaiman, Jonathan. ‘Inside China’s ‘cancer villages’’. Guardian. 4 Juni 2013. http://www.theguardian.com/world/2013/jun/04/china-villages-cancer-deaths. Diakses 24 Januari 2016.
Nainggolan, Bestian. ‘Pergeseran Konfigurasi Penguasaan Partai’. Kompas.com. 11 Januari 2016. http://nasional.kompas.com/read/2016/01/11/15000051/Pergeseran.Konfigurasi.Penguasaan.Partai?page=all. Diakses 25 Januari 2016.
Nurdin, Endang. ‘Kisah para eksil 1965: Mereka yang ‘dibui tanpa jeruji’’. BBC Indonesia. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150928_indonesia_lapsus_eksil_bui. Diakses 25 Januari 2016.
Perkasa, Anugerah. ‘LAPORAN BANK DUNIA: Sebagian Orang Kaya Indonesia Koruptif’. Bisnis.com. 28 Desember 2015. http://finansial.bisnis.com/read/20151228/9/505201/laporan-bank-dunia-sebagian-orang-kaya-indonesia-koruptif. Diakses 25 Januari 2016.
Perkasa, Surya. ‘Dari Konflik Ambon hingga Pengusiran Ahmadiyah’. Metrotvnews.com. 28 Desember 2015. http://telusur.metrotvnews.com/read/2015/12/28/205693/dari-konflik-ambon-hingga-pengusiran-ahmadiyah. Diakses 24 Januari 2016.
Perlez, Jane dan Raymond Bonnder. ‘Below a Mountain of Wealth, a River of Waste’. New York Times. 27 Desember 2005. http://www.nytimes.com/2005/12/27/world/asia/below-a-mountain-of-wealth-a-river-of-waste.html?_r=1. Diakses 25 Januari 2016.
Putra, Erik Purnama. ‘Kemenhan Terinspirasi Obama Terapkan Program Bela Negara’. Republika. 6 Januari 2016. http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/06/o0ivpb334-kemenhan-terinspirasi-obama-terapkan-program-bela-negara. Diakses 25 Januari 2016.
Zuesse, Eric. ‘First-Ever Study of Global Economic Inequality: Richest 8% Earn 50% of Earth’s Incomes’. Huffington Post. 28 Mei 2013. http://www.huffingtonpost.com/eric-zuesse/firstever-study-of-global_b_3336962.html. Diakses 21 Januari 2016.
[1] “Jenderal Luhut Kenang Pertempuran di Timor Timur”, Merah Putih, 10 November 2015, diperoleh dari http://news.merahputih.com/peristiwa/2015/11/10/jenderal-luhut-kenang-pertempuran-di-timor-timur/32394/, diakses 16 Januari 2015.
[2] Tulisan ini tidak bermaksud merendahkan mereka yang gugur dalam perang. Kebrutalan tentara dan aparat di medan perang dan di kampung-kampung; doktrin militer-imperialis yang membantai kehidupan kelas-kelas tertindas demi kepentingan kelas penguasa; propaganda dan manipulasi narasi sejarah untuk mempertahankan legitimasi politis: semua hal tersebut wajib kita kutuk dan lawan, tetapi kematian—tirai hitam tak-berpihak yang penuh teka-teki itu—tetaplah kematian. Mengutip ukiran pada korek Zippo milik seorang tentara Amerika Serikat saat perang Vietnam: “We the unwilling / Led by the unqualified / To kill the unfortunate / Die for the ungrateful”.
[3] “Many people have complained that it is a difficult book and especially difficult to translate.” Benedict Anderson, “Frameworks of Comparison”, London Review of Books, 38.2 (2016), diperoleh dari http://www.lrb.co.uk/v38/n02/benedict-anderson/frameworks-of-comparison, diakses 16 Januari 2016.
[4] Tanpa saya sadari saat itu, karya kedua penulis tersebut merupakan penanda bagi proses pembentukan dua model nasionalisme dalam ruang-waktunya masing-masing: konstelasi politis pada saat Perang Dunia Pertama yang sebelumnya terbentuk oleh gerakan nasionalisme-populer berbasis bahasa-rakyat di Eropa, disusul oleh model nasionalisme-resmi berwatak imperialis (Buchan); dan perjalanan membentuk kesadaran nasional dalam konteks nasionalisme-kolonial di Indonesia (Pram).
[5] Anderson mencatat bahwa invasi dan pendudukan militer Vietnam terhadap Kamboja pada bulan Januari 1978 dan bulan Februari 1979 merupakan perang konvensional berskala-besar pertama antara sesama rezim Marxis-revolusioner (h. 1).
[6] Munculnya fenomena ISIS/ISIL (Islamic State of Iraq and Syria/the Levant) yang mengklaim sebagai negara dengan keanggotaan berbasis identitas religius alih-alih kebangsaan, serta ‘berhasil’ membentuk dan mempertahankan batas-batas wilayah-kuasa yang nyata, dapat dikatakan sebagai anomali jika disandingkan dengan pengamatan Anderson pada tahun 1983. Lihat subbagian “Manuel Castells…” di bawah.
[7] “The proletariat of each country must, of course, first of all settle matters with its own bourgeoisie”. Marx dan Engels, The Communist Manifesto dalam Selected Works, I, dikutip oleh Anderson di h. 4.
[8] Anderson 2016, op. cit.
[9] Argumen pertama tak sulit untuk kita pahami, terutama untuk konteks Indonesia. Kendati tak mungkin setiap penduduk Indonesia bersemuka dengan penduduk titik-titik tertimur dan terbarat, kesadaran nasional sebagai satu bangsa, yang mengemuka dalam pernyataan “dari Sabang sampai Merauke”, terpatri dalam benak setiap orang Indonesia. Gambaran tentang ‘anehnya’ realitas argumen ini dapat dibaca pada jukstaposisi yang dituturkan Anderson secara cemerlang, antara masyarakat pantai timur Sumatra, masyarakat pantai barat Semenanjung Malaya, dan masyarakat kepulauan Ambon (Maluku): kendati persamaan bahasa, agama, asal-usul etnis, dan kedekatan geografis antara masyarakat pantai timur Sumatra dan masyarakat pantai barat Semenanjung Malaya, serta kendati absennya semua persamaan tersebut antara masyarakat pantai timur Sumatra dan masyarakat kepulauan Ambon (Maluku), dalam kurun waktu abad ke-20, masyarakat pantai timur Sumatra mengenal masyarakat kepulauan Ambon (Maluku) sebagai sesama bangsa Indonesia, dan mengenal masyarakat pantai barat Semenanjung Malaya sebagai orang asing (h. 120–121).
[10] Implikasi aksiologisnya ada tiga:
- disintegrasi dari kepercayaan pada surga menyebabkan fatalitas menjadi lebih manasuka;
- kemustahilan dari kepercayaan pada keselamatan-ilahi (salvation) mengharuskan suatu mode kontinuitas yang baru; dan
- terjadinya transformasi sekuler dari fatalitas menjadi kontinuitas, dan dari kemungkinan menjadi kemaknaan.
Tiga perubahan di atas kemudian mensyaratkan bangsa sebagai entitas yang secara logis paling dapat mengemban nilai-nilai baru yang muncul (h. 11).
[11] Novel-novel tertentu memunculkan ‘imajinasi nasional’ dalam narasi yang alur penulisannya sarat dengan ‘diskontinuitas kesadaran’ sebagai penanda waktu homogen-kosong. Sebagai contoh, Anderon mengutip narasi dalam Noli Me Tángere (1887) karya José Rizal (‘Bapak Nasionalisme Filipina’); El Periquillo Samiento (1816) karya José Joaquín Fernandez de Lizardi (penulis dan wartawan-politis Meksiko yang resisten terhadap administrasi Spanyol); dan Semarang Hitam (1924) karya Mas Marco Kartodikromo (jurnalis radikal berideologi komunis-nasionalis, yang ditahan Belanda di Boven Digul dan meninggal pada tahun 1932).
[12] Membaca koran secara rutin dan serentak bermakna sebagai ritual baru masyarakat, yang mengondisikan munculnya kesadaran kolektif perihal keserentakan kejadian—jutaan orang membaca koran yang sama pada saat yang sama, membaca tentang kejadian-kejadian yang dihubungkan satu sama lain oleh tanggal yang tertera di atas koran—yang kelak mengarah pada pembentukan kesadaran nasional.
[13] Anderson merujuk pada Febvre dan Martin dalam The Coming of the Book (1976)—terjemahan dari L’Apparition du Livre (1958)—bahwa, kendati tampak kelas borjuasi di Eropa pada akhir abad ke-13, prasyarat material-teknis bagi munculnya industri percetakan di Eropa adalah kertas, yang baru lazim digunakan di Eropa pada akhir abad ke-14 dan masuk ke Eropa dari Cina melalui Dunia Islam (h. 43).
[14] Anderson mengutip Febvre dan Martin: “para penjual buku utamanya berkepentingan menciptakan keuntungan dan menjual produk-produk mereka. Alhasil, mereka pertama-tama mencari karya-karya yang diminati oleh sebanyak mungkin orang”. Book-sellers were primarily concerned to make a profit and to sell their products, and consequently they sought out first and foremost those works which were of interest to the largest possible number of their contemporaries (h. 38).
[15] Pada awal paruh-akhir abad ke-15—ditandai tercetaknya Injil Gutenberg—hingga menjelang abad ke-16, lebih dari 20.000.000 karya cetak diproduksi di Eropa. Antara tahun 1500 dan 1600, jumlah buku termanufaktur berada di antara 150.000.000 dan 200.000.000 (h. 33–34, 37).
[16] Kendati faktor-faktor yang telah dijelaskan, Anderson menolak menetapkan jangkauan kapitalisme-percetakan sebagai faktor determinan-absolut bagi pembentukan konkret dari negara-bangsa kontemporer yang lahir dari kesadarannya sendiri. Anderson berargumen bahwa, kendati kini terdapat banyak bangsa dan negara-bangsa modern yang memiliki ‘bahasa-cetak nasional’, tak semuanya menggunakan bahasa tersebut dalam keseharian; terdapat negara-bangsa yang memang menggunakan bahasa-cetak nasional (mereka yang tadinya bagian dari Amerika-Spanyol, atau menjadi bagian dari ‘keluarga Anglo-Saxon’), tetapi juga terdapat negara-bangsa yang tidak menggunakan bahasa-cetak nasional mereka dalam percakapan atau pun secara tertulis (berbagai negara bekas koloni, terutama di Afrika) (h. 46).
[17] Dalam catatan Anderson, creole (dari bahasa Spanyol criollo), adalah seseorang yang (setidaknya secara teoritis) berdarah Eropa-murni tetapi lahir di Amerika (dan, kelak sebagai tambahan, di mana pun di luar Eropa) (h. 47). Bandingkan dengan peninsulares, yakni orang Spanyol yang lahir di Spanyol namun tinggal di koloni Amerika. Pada akhir abad ke-18 terdapat 3.200.000 kaum creole dan 150.000 peninsulares di Amerika, dari total populasi 16.900.000 yang tinggal di koloni Spanyol di Amerika (h. 189).
[18] Secara historis, Haiti merupakan republik-merdeka kedua di belahan bumi Barat, yang berhasil meraih kemerdekaan pada tahun 1804. Kemerdekaannya diraih oleh mantan-mantan budak—satu-satunya bangsa di dunia yang lahir dari pemberontakan budak—pasca pemberontakan yang dimulai dan dipimpin oleh Toussaint Louverture pada tahun 1791, seorang mantan budak dan jendral kulit-hitam pertama di Angkatan Darat Perancis (h. 48, 193).
[19] Anderson menunjukkan bahwa ‘El Libertador’ sekalipun, Simón Bolívar, pada awalnya menyatakan bahwa “pemberontakan Negro seribu kali lebih buruk daripada serangan Spanyol”, walaupun kemudian dia berubah sikap dan memerdekakan budak-budaknya. Pada tahun 1789, kaum creole menolak undang-undang perbudakan baru dari Spanyol yang lebih humanis. Di Amerika Serikat, tokoh pendiri nasional sekaliber Thomas Jefferson juga merupakan pemilik budak yang kaya (h. 49).
[20] Proses tersebut diabstraksikan oleh antropolog Victor Turner sebagai ‘perjalanan (journey)’ untuk menaiki anak-tangga jabatan birokratis (mobilitas vertikal) selagi dimutasi ke wilayah-lokal dan provinsi lain (mobilitas horizontal). Secara vertikal maupun horizontal, perjalanan tersebut terantuk akibat keterbatasan inheren pada para pejabat creole: dari 170 penguasa-kolonial (viceroy) yang bertugas di koloni-koloni Spanyol di Amerika, hanya empat yang merupakan orang creole (pembatasan mobilitas vertikal); kendati seumur hidupnya digunakan untuk menaiki tangga jabatan birokratis, pejabat creole tak akan mungkin ditugaskan di tanah Spanyol (pembatasan mobilitas horizontal).
[21] Koran, baik di Amerika Utara maupun Amerika Selatan, pada awalnya berfungsi sebagai kepanjangan tangan pasar, namun berkembang hingga memuat berita dari negara-induk, berita dan pengumuman komersial (jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal, harga komoditas di berbagai pelabuhan), pengumuman pernikahan para orang kaya, dan sebagainya. Yang menyatukan semua berita tersebut adalah struktur dari administrasi kolonial, serta sistem pasar itu sendiri.
[22] Anderson tak pernah taat asas dalam menamakan model nasionalisme tersebut, alih-alih bervariasi menggunakan istilah ‘nasionalisme-populer (popular nationalism)’, ‘nasionalisme-bahasa-rakyat (vernacular nationalism)’, ‘nasionalisme-linguistik (linguistic nationalism)’, dan gabungan dari variasi-variasi tersebut: ‘nasionalisme-linguistik populer (popular linguistic nationalism)’, ‘nasionalisme-bahasa-rakyat populer (popular vernacular nationalism)’. Demi ketaatasasan, tulisan ini menggunakan istilah ‘nasionalisme-populer’.
[23] Anderson menjelaskan bagaimana kesadaran eksistensi-diri kelas borjuasi tumbuh melalui bahasa-cetak, mengikuti logika mutakhir yang berbeda dengan pembentukan kohesi kelas-kelas penguasa praborjuasi melalui politik seksual. “Dalam narasi sejarah dunia, kelas borjuasi merupakan kelas pertama yang meraih solidaritas melalui basis yang, pada dasarnya, terbayang.”
[24] Menurut Anderson, tiga faktor yang melancarkan proses konsolidasi nasionalisme-resmi di Jepang adalah:
- homogenitas etnokultural tinggi akibat dua-setengah abad isolasi dan pasifikasi internal oleh Bakufu (rezim Shogun Tokugawa);
- kekunoan dinasti imperial Jepang yang unik (Jepang merupakan satu-satunya negara yang, sepanjang sejarah, monarkinya dimonopoli dinasti tunggal), sehingga memudahkan eksploitasi Kaisar untuk kepentingan nasionalisme-resmi; dan
- penetrasi oleh para ‘barbar’ yang datang dari Eropa bersifat acap, berskala besar, masif, dan mengancam, sehingga populasi Jepang yang melek-politik lekas memberikan dukungan pada kebijakan bela-diri yang disusun berdasarkan istilah-istilah nasional (h. 95–96).
[25] Anderson menuturkan bahwa legitimasi fundamental dari sebagian besar dinasti-dinasti di Eropa justru tak ada hubungannya sama sekali dengan nasionalisme: dinasti Romanov berkuasa atas bangsa Tatar, Lett, Jerman, Armenia, Rusia, dan Finn; dinasti Habsburg berkuasa atas bangsa Magyar, Kroat, Slovak, Itali, Ukrania, dan Austro-Jerman; dinasti Hanover berkuasa atas bangsa Bengal, Québecois, Skotlandia, Irlandia, Inggris, dan Wales. Lebih menarik lagi, Anderson mencatat bahwa sejak abad ke-11, apa yang tadinya disebut sebagai Imperium Britania pada kenyataannya terakhir dipimpin oleh dinasti ‘Inggris’ pada abad ke-11; sisanya adalah ‘parade’ yang terdiri dari dinasti Plantagenet, Tudor, Stuart, Orange, dan Hanover (h. 83).
[26] Sebelumnya, pada abad ke-18, bahasa istana di St. Petersburg adalah Perancis, sedangkan bahasa bangsawan di level provinsi adalah Jerman. Pada saat itu, separuh ‘bangsa’ Rusia berstatus pekerja-feodal (serf), sementara lebih dari separuhnya berbahasa-ibu selain bahasa Rusia (h. 87).
[27] Anderson menunjukkan dua faktor yang menjelaskan mengapa Jepang menganut watak imperialisme ekstrim:
- warisan isolasi panjang, ditandai dengan absennya kesadaran terhadap kualitas hubungan internasional atau standar-standar normatif dalam bernegara; dan
- contoh-contoh nasionalisme-resmi yang ditiru dan dibajak, yakni para kekuatan imperialis di Eropa (h. 97–98).
[28] “The need of a constantly expanding market for its products chases the bourgeoisie over the whole face of the globe”. Marx dan Engels, The Communist Manifesto, dikutip oleh Anderson di h. 139.
[29] Anderson memberikan contoh Indonesia pada masa kolonial: pada tahun 1928, terdapat hampir 250.000 ‘inlander’ yang bekerja untuk, dan digaji oleh, pemerintah Hindia Belanda; jumlah tersebut merupakan 90% dari seluruh pejabat pemerintahan. Kendati demikian, pengeluaran negara Hindia Belanda untuk seluruh aparatus birokrasinya, termasuk gaji dan pensiun, mencakup 50% dari total pengeluaran.
[30] Anderson memberikan beberapa imaji perbandingan sebagai ilustrasi:
- kekhidmatan dan kesakralan yang dirasakan anggota bangsa di hadapan ‘kuburan dan makam tentara tanah air tak bernama (cenotaphs and tombs of Unknown Soldiers)’ vis-à-vis kejanggalan dan kesumbangan jika situasi yang sama dianalogikan dengan ideologi: ‘kuburan penganut Marxisme tak bernama (tomb of the Unknown Marxist)’ atau ‘makam untuk para penganut Liberal tak bernama (cenotaph for fallen Liberals)’;
- keagungan moral yang terkandung dalam tindakan mengorbankan-nyawa untuk bangsa—Anderson juga menarik padanan dengan tindakan mengorbankan-nyawa untuk revolusi, “sejauh revolusi tersebut dirasakan sebagai sesuatu yang, secara fundamental, murni”—yang tak tersaingi oleh tindakan mengorbankan-nyawa untuk (misalnya) Partai Buruh (Partai Perindo?), Asosiasi Kedokteran Amerika (Himpunan Penerjemah Indonesia?), atau Amnesty International (Gerakan Indonesia Mengajar?): lembaga-lembaga yang secara manasuka dapat diikuti atau ditinggalkan (h. 9–10, 144).
[31] Anderson melakukan analisis-konten pada beragam produk budaya, termasuk dua contoh berikut:
- lirik lagu kebangsaan Inggris, God Save the Queen, mengandung unsur kebencian dan ketakutan terhadap ‘musuh dari Luar’ yang mencengangkan. Secara bersamaan, lagu tersebut melambangkan secara sempurna logika monarki, alih-alih bangsa, karena subjek utama dalam lagu tersebut adalah ratu atau raja, bukan bangsa Inggris (yang bahkan tak muncul sekalipun dalam lirik); dan
- bait-bait pertama dan terakhir dari Último Adiós, puisi terakhir José Rizal saat dia menanti dihukum mati oleh imperialisme Spanyol, yang tumpah-ruah dengan kecintaan terhadap bangsa dan tanah air alih-alih kebencian terhadap mereka yang hendak membunuhnya (h. 141–142).
[32] Melalui analisis yang tampak pengaruh filologisnya, Anderson menegaskan dua unsur fundamental bahasa bagi penciptaan-makna:
- primordialisme (‘hari lahir’ bahasa yang tak terlacak dalam sejarah, kendati pada bahasa-bahasa yang tergolong modern); dan
- keserentakan (unisonance), yang terutama hadir dalam puisi dan tindakan menyanyi lagu kebangsaan (h. 144–145).
[33] Penjelasan Anderson perihal sensus, peta, dan museum secara historis dapat dikatakan sebagai jembatan antara penjelasan perihal kekuatan imperialis yang ‘menganut’ nasionalisme-resmi, dan negara-negara bekas koloni yang, dalam ukuran berbeda-beda, turut mewarisi konsepsi perihal kesadaran nasional dari bentuk negara yang sebelumnya berkuasa.
[34] Perlu dicatat bahwa selain proses pembentukan identitas nasional secara kartografis berdasarkan ‘logo’, secara sejajar, perkembangan kartografi dalam konteks kolonial menyandang logika kapitalisme (imperial). David Harvey menuturkan bahwa pada era imperialis, peletakan basis kartografis merupakan cara untuk memaksakan bentuk-bentuk hak teritorial kapitalis pada wilayah-wilayah jajahan. Definisi-definisi kartografis perihal kedaulatan membantu pembentukan negara dan pelaksanaan kekuasaan negara. Selain itu, kartografi meletakkan basis hak kepemilikan tanah berdasarkan kelas, serta hak mengapropriasi hasil alam dan kerja dalam ruang-ruang yang terdelineasi secara tegas. Terakhir, kartografi memungkinkan pengorganisasian ruang secara ‘rasional’ untuk kepentingan akumulasi kapital, serta pengkavlingan ruang dalam rangka administrasi efisien atau perencanaan rasional untuk memajukan kesehatan dan kesejahteraan. Lihat David Harvey, Spaces of Capital: Towards a Critical Geography (New York: Routledge, 2001), h. 220.
[35] Istilah tersebut tak muncul secara eksplisit di Imagined Communities, tetapi merupakan judul dan sebagian pembahasan dari tulisan Benedict Anderson, “Old State, New Society: Indonesia’s New Order in Comparative Historical Perspective” dalam The Journal of Asian Studies, 42.3 (1983): 477–496, diperoleh dari http://www.jstor.org/stable/2055514, diakses 10 Juni 2015.
[36] Fenomena ini dikontraskan dengan bentuk penamaan kota “Baru” di Asia Tenggara—seperti Chiang Mai (New City), Kota Bahru (New Town), dan Pekan Baru (New Market)—yang tidak menandakan keserentakan, alih-alih pergantian atau pewarisan kota baru terhadap yang lama (h. 187).
[37]Abstraksi dari contoh dan logika berpikir Anderson dalam topik pembahasan ini tampak memiliki unsur kesejajaran dengan ungkapan Marx di bab pertama dari The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. Berikut kutipan yang paling relevan: “Manusia membuat sejarahnya sendiri, tetapi mereka tidak membuatnya sesuka hati; mereka tidak membuatnya dalam situasi-situasi yang dipilih oleh mereka sendiri, alih-alih dalam situasi-situasi yang sebelumnya telah ada, yang ditentukan dan ditransmisikan dari masalalu. Tradisi dari semua generasiyang mati membeban bagaikan mimpi buruk atas benak yang hidup. Dan tepat manakala mereka tampak sibuk merevolusionerkan diri sendiri dan hal-hal, menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, justru pada periode-periode krisis revolusioner seperti itu mereka dengan cemas membangkitkan roh-roh masa lalu untuk melayani mereka, dan meminjam darinya nama-nama, teriakan-teriakan perang, dan kostum-kostum agar dapat menyajikan adegan baru sejarah dunia dalam samaran sepuh dan bahasa pinjaman”. Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, diperoleh dari https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/ch01.htm, diakses 21 Januari 2016; lihat juga pembahasan mengenai “ingatan-ingatan sosial dalam periode modern” di James Fentress dan Chris Wickham, Social Memory (Oxford: Blackwell, 1992), h. 127–137.
[38] Eric Zuesse, “First-Ever Study of Global Economic Inequality: Richest 8% Earn 50% of Earth’s Incomes”, Huffington Post, 28 Mei 2013, diperoleh dari http://www.huffingtonpost.com/eric-zuesse/firstever-study-of-global_b_3336962.html, diakses 21 Januari 2016; Jonathan Kaiman, “Inside China’s ‘cancer villages’”, Guardian, 4 Juni 2013, diperoleh dari http://www.theguardian.com/world/2013/jun/04/china-villages-cancer-deaths, diakses 24 Januari 2016.
[39] Castells membahas faktor kemunculan gerakan fundamentalisme agama ‘Islamis’ dan Kristen:
- fundamentalisme agama ‘Islamis’ (termasuk munculnya ISIS/ISIL) dapat dipahami sebagai kulminasi historis dari kemunculan fundamentalisme radikal dan identitas Islam kontemporer yang berakar pada permainan strategi geopolitis Perang Dingin, serta akumulasi dari respons terhadap globalisasi dan gagalnya proyek politis pascakolonial.
- mekarnya fundamentalisme agama Kristen di Amerika Serikat pada dasawarsa 1990-an merupakan bentuk oposisi terhadap pengendalian negara oleh ‘pemerintahan-dunia (world government)’, yang menggantikan pemerintahan federal Amerika Serikat (yang dianggap terlibat pula), dan dioperasikan melalui badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-bangsa, Dana Moneter Internasional, Organisasi Perdagangan Internasional, dan sebagainya. Selain itu, sumber utama dari fundamentalisme Kristen pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an adalah respons terhadap merapuhnya ‘keluarga Amerika Serikat yang patriarkis’ dan tantangan terhadap patriarki, yang bermanifestasi dalam protes-protes pada tahun 1960-an, gerakan-gerakan perempuan, lesbian, dan gay.
Lihat Manuel Castells, The Power of Identity (Malden: Blackwell, 1997), h. 18–19, 26; Ali Riaz, “Global Jihad, Sectarianism and the Madrassahs in Pakistan” (Working Paper, Institute of Defence and Strategic Studies, Singapore, Agustus 2005), h. 3–4.
[40]“…the transformation of material foundations of life, space adn time, through the constitution of a space of flows and of timeless time, as expressions of dominant activities and controlling elites.” Castells, op. cit., h. 1; untuk jukstaposisi dari “Diri” dan “Net”, lihat Manuel Castells, The Rise of the Network Society (Malden: Blackwell, 1996), h. 3.
[41] Serangan akademis tersebut memiliki tesis dasar bahwa gerakan-gerakan nasionalis, yang merasionalkan kepentingan-kepentingan elit tertentu, menciptakan identitas nasional yang, manakala berhasil, dikukuhkan melalui negara-bangsa. Identitas tersebut lantas disebarkan kepada massa melalui propaganda. Konsekuensinya, para ‘nasionalis (nationals)’ kemudian rela mati untuk bangsa. Hobsbawm mengakui adanya bukti-bukti historis bahwa nasionalisme dapat muncul dari akar rumput, namun mengklasifikasikan fenomena tersebut sebagai ‘proto-nasionalisme’. Kendati suatu masyarakat sama-sama memiliki atribut linguistik, wilayah, etnis, religius dan politis-historis, Hobsbawm berpendapat bahwa bangsa dan nasionalisme tercipta hanya ketika terkonsolidasi sebagai negara-bangsa, sebagai ekspresi dari negara-bangsa tersebut atau pun sebagai tantangan terhadapnya atas nama negara baru yang berpotensial muncul. Castells, op. cit., h. 27–28.
[42] Castells, op. cit., h. 51.
[43] Ibid.
[44] Menurut Castells, bahasa memberikan kaitan antara ranah publik dan privat dan antara masa lalu dan masa sekarang—terlepas dari pengakuan institusi negara terhadap komunitas kultural. Bahasa merupakan bentuk pertahanan kultural, pengendalian-diri dan tempat berlindung bagi makna yang dapat diidentifikasi.
[45] Castells, op. cit., h. 51–52.
[46] “I have one central objection to Anderson’s argument. If nationalisms in the rest of the world have to choose their imagined community from certain “modular” forms already made available to them by Europe and the Americas, what do they have left to imagine? History, it would seem, has decreed that we in the postcolonial world shall only be perpetual consumers of modernity. Europe and the Americas, the only true subjects of history, have thought out on our behalf not only the script of colonial enlightenment and exploitation, but also that of our anticolonial resistance and postcolonial misery. Even our imaginations must remain forever colonized.” Partha Chatterjee, The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories (Princeton: Princeton University Press, 1993), h. 5.
[47] Sebagai contoh, Chatterjee menyebutkan bahwa dalam pendidikan di India, awal mula nasionalisme India adalah tahun 1885 dengan dibentuknya Kongres Nasional India, yang didahului oleh sedasawarsa masa persiapan yang ditandai oleh dibentuknya beberapa asosiasi politis lokal. Sebelumnya, periode 1820-an hingga 1870-an merupakan masa ‘reformasi sosial’, ditandai oleh ‘pencerahan kolonial’ yang tengah ‘memodernisasi’ berbagai norma dan institusi masyarakat tradisional, namun memiliki jiwa politis yang masih kolaboratif alih-alih nasionalis. Menurut Chatterjee, narasi sejarah di muka tampak sangat cocok dengan model argumen Anderson. Ibid.
[48] Untuk menggambarkan argumennya, Chatterjee menganalisis perkembangan teater, novel, bahasa, institusi pendidikan dan institusi keluarga di India. Beriringan dengan mekarnya nasionalisme di India, produk-produk budaya dan institusi-institusi tersebut mengalami proses modifikasi yang sebagian besar didorong oleh elit inteligensia bilingual (dijuluki Anderson sebagai ‘juru bicara nasionalisme’ dalam tahap nasionalisme-kolonial). Hasil akhir dari proses modifikasi tersebut adalah bentuk yang ‘modern’, namun secara bersamaan tetap memisahkan diri sebagai sesuatu yang ‘non-Barat’. Ibid., h. 7–12.
[49] Ibid., h. 13.
[50] Kendati Blaut membahas teori umum yang mendasari segala bentuk perjuangan nasional, Blaut mengakui bahwa selain perjuangan pembebasan nasional di muka, terdapat pula bentuk-bentuk perjuangan nasional yang ‘reaksioner’ dan ‘taksa (ambiguous)’, yang tidak dibahas. James Morris Blaut, The National Question: Decolonizing the Theory of Nationalism (London: Zed Books, 1987), h. 5.
[51]Pandangan ini merupakan pandangan dominan Marxis pada tahun-tahun awal menjelang Perang Dunia Pertama, namun kemudian ditantang oleh Lenin dan diruntuhkan oleh realitas pembebasan nasional.
[52]Menurut Blaut, Marx dan Engels juga terjangkit penyakit yang sama, namun saat itu mereka tidak dalam posisi untuk dapat menghindar; pengetahuan-pengetahuan krusial mengenai dunia non-Eropa antara belum ada di masa hidup mereka, atau belum menyebar sampai Eropa, atau ditekan untuk alasan-alasan politis.
[53]Blaut, op. cit., h. 172–174.
[54] Ibid., h. 172–204.
[55] Anderson 2016, op. cit.
[56] “It was not until much later, in fact after I finally retired, that I began to recognise the fundamental drawback of this type of comparison: that using the nation and nation-states as the basic units of analysis fatally ignored the obvious fact that in reality these units were tied together and crosscut by global political-intellectual currents such as liberalism, fascism, communism and socialism, as well as vast religious networks and economic and technological forces. I had also to take seriously the reality that very few people have ever been solely nationalist. No matter how strong their nationalism, they may also be gripped by Hollywood movies, neoliberalism, a taste for manga, human rights, impending ecological disaster, fashion, science, anarchism, post-coloniality, ‘democracy’, indigenous peoples’ movements, chatrooms, astrology, supranational languages like Spanish and Arabic and so on.” Ibid.
[57] Kepiawaian Anderson dalam menuturkan metode perbandingan secara tajam, kritis dan tak standar, dapat dilihat dari publikasi-publikasi selanjutnya, terutama The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia and the World (1998) dan Under Three Flags: Anarchism and the Anti-Colonial Imagination (2007).
[58] Anderson 2016, op. cit.
[59] Dalam beberapa tempat di tulisan ini, pemikiran Anderson yang naratif disarikan menjadi klasifikasi tipologis, sebagai upaya untuk memudahkan pembaca memahami alur logika dari penulisannya. Lihat catatan kaki nomor 22.
[60] Lihat Noer Fauzi Rachman dan Dian Yanuardy, eds., MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2014), h. 3–10, 68–70; Jane Perlez dan Raymond Bonnder, “Below a Mountain of Wealth, a River of Waste”, New York Times, 27 Desember 2005, diperoleh dari http://www.nytimes.com/2005/12/27/world/asia/below-a-mountain-of-wealth-a-river-of-waste.html?_r=1, diakses 25 Januari 2016.
[61] B. Herry-Priyono, “Kota dan Harta: Perihal Jarak antara Jakarta dan Indonesia” dalam seri ke-5 dalam rangkaian Studium Generale mengenai Philosophy in the City (Jakarta: Goethe-InstitutJakarta, 15 Oktober 2009), h. 20; Endang Nurdin, “Kisah para eksil 1965: Mereka yang ‘dibui tanpa jeruji’”, BBC Indonesia, 29 September 2015, diperoleh dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150928_indonesia_lapsus_eksil_bui, diakses 25 Januari 2016; Surya Perkasa, “Dari Konflik Ambon hingga Pengusiran Ahmadiyah”, Metrotvnews.com, 28 Desember 2015, diperoleh dari http://telusur.metrotvnews.com/read/2015/12/28/205693/dari-konflik-ambon-hingga-pengusiran-ahmadiyah, diakses 24 Januari 2016; Mohamad Zaki Hussein, “Fakta Singkat Konflik Agraria di Indonesia”, Inkrispena, 17 Maret 2015, diperoleh dari http://inkrispena.org/fakta-singkat-konflik-agraria-di-indonesia/, diakses 24 Januari 2016; Wahyoe Boediwardhana, “Antimining activist beaten to death in East Java”, Jakarta Post, 28 September 2015, diperoleh dari http://www.thejakartapost.com/news/2015/09/28/antimining-activist-beaten-death-east-java.html, diakses 25 Januari 2016.
[62] Lihat Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, Reorganising Power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets (London: Routledge, 2004), h. 244–245; Bestian Nainggolan, “Pergeseran Konfigurasi Penguasaan Partai”, Kompas.com, 11 Januari 2016, diperoleh dari http://nasional.kompas.com/read/2016/01/11/15000051/Pergeseran.Konfigurasi.Penguasaan.Partai?page=all, diakses 25 Januari 2016.
[63] Anugerah Perkasa, “LAPORAN BANK DUNIA: Sebagian Orang Kaya Indonesia Koruptif”, Bisnis.com, 28 Desember 2015, diperoleh dari http://finansial.bisnis.com/read/20151228/9/505201/laporan-bank-dunia-sebagian-orang-kaya-indonesia-koruptif, diakses 25 Januari 2016.
[64] Erik Purnama Putra, “Kemenhan Terinspirasi Obama Terapkan Program Bela Negara”, Republika, 6 Januari 2016, diperoleh dari http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/06/o0ivpb334-kemenhan-terinspirasi-obama-terapkan-program-bela-negara, diakses 25 Januari 2016.
[65] Ibid.
[66] “For newspapers are less and less a substitute for anything, and in much of the world morning prayers are no longer to be substituted for by any such private (public) form of representation. Screen capitalism is dissolving the very structure of private (public) being-together. It is wrecking the quiet simultaneity of clock-time … The event on the screen is unique and eternal. It belongs again to God or Satan. The website and the cellphone video are paths to the sacred. Morning prayer is everywhere.” T.J. Clark, “In a Pomegranate Chandelier”, London Review of Books, 28.18 (2006), diperoleh darihttp://www.lrb.co.uk/v28/n18/tj-clark/in-a-pomegranate-chandelier,diakses 24 Januari 2016.
[67] Lihat John Bender dan David E. Wellbery, eds., Chronotypes: The Construction of Time (Stanford: Stanford University Press, 1991); Muhammad Al-Fayyadl, “Benedict Anderson: Seorang Filsuf”, LSF Cogito, diperoleh dari http://lsfcogito.org/benedict-anderson-seorang-filsuf/, diakses 21 Januari 2016.
[68] “Although the Thai and Indonesian languages have no linkages and belong to quite different linguistic ancestries, both have long had a fatalistic image of a frog who lives all its life under half a coconut shell – commonly used as a bowl in these countries. Sitting quietly under the shell, before long the frog begins to feel that the coconut bowl encloses the entire universe. The moral judgment in the image is that the frog is narrow-minded, provincial, stay-at-home and self-satisfied for no good reason. For my part, I stayed nowhere long enough to settle down in one place, unlike the proverbial frog.” Anderson 2016, op. cit.






