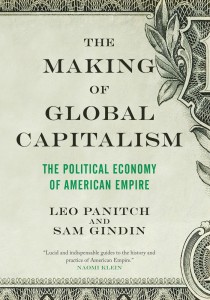Judul buku: The Making of Global Capitalism
Penulis: Leo Panitch dan Sam Gindin
Penerbit: Verso, London, 2012
Tebal: 447+vii
SIAPA tak kenal Kenichi Ohmae, ahli strategi manajemen dan politisi asal Jepang ini? Ketika rezim Orde Baru terpaksa harus semakin meliberalkan pasar domestiknya pada awal dekade 1980an, Ohmae adalah salah satu nama yang paling sering dikutip oleh para pejabat pemerintah, teknokrat, ekonom, manajer perusahaan, dosen-dosen sekolah bisnis, hingga media massa. Ohmae dibicarakan berkaitan dengan gagasannya mengenai semakin melumernya batas-batas negara (borderless state), di hadapan perkembangan pesat ekonomi Internasional.
Dekade 80an memang merupakan dekade dimana paham ekonomi neoliberal sedang mengalami pasang naiknya. Bangkrutnya sistem Bretton Woods pada akhir dekade 60an, dan proses deindustrialisasi yang menimpa negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat yang berpuncak pada krisis fiskal pada pertengahan 1970an, telah membuat para intelektual, teknokrat, dan politisi berpaling dari jalan Keynesianisme dan Sosial-demokrasi mengikuti jalan Kapitalisme-neoliberal. Di negara-negara berkembang, proyek industrialisasi berorientasi impor (Industrialisasi substitusi impor/ISI) mulai kehilangan popularitasnya sebagai solusi untuk memodernisasi keterbelakangan dan ketertinggalan ekonomi. Ketika terjadi krisis hutang luar negeri dari negara-negara Dunia Ketiga ini pada dekade 1908an, maka proyek ISI bangkrut dan diganti dengan proyek industrialisasi berorientasi ekspor (Industrialisasi Orientasi Ekspor/IOE).
Kembali kepada tesis Ohmae, katanya, dalam era baru ekonomi dunia ini, peran negara tidak lagi signifikan dalam mengatur jalannya perekonomian. Uang tidak punya nasionalisme, ia bisa datang setiap saat dari berbagai penjuru dunia, dan pergi sekejap mata ke penjuru dunia lainnya. Tak ada lagi kekuatan yang bisa menghadang pergerakan uang dan jasa ini. Jadi, pengaturan ekonomi oleh negara bukan saja buruk, tetapi sesungguhnya negara itu sendiri tidak memiliki daya untuk mengelolanya.
Keyakinan serupa Ohmae ini merupakan keyakinan mayoritas. Bahkan di kalangan kiri, keyakinan ini juga melekat kuat. Pertama, itu bisa dibuktikan dengan memudarnya studi-studi tentang Negara dan terutama imperialisme, dalam hubungannya dengan ekspansi dan akumulasi kapital sejak munculnya perdebatan legendaris tentang negara antara Ralph Miliband dan Nicos Poulantzas. Kedua, karena itu muncul teorisasi baru bahwa tidak penting lagi perjuangan rakyat pekerja dalam merebut kekuasaan negara, karena toh negara telah tak berdaya di hadapan kapital. Slogannya, kita bisa mengubah dunia tanpa harus merebut kekuasaan negara. Sebagai gantinya, apa yang paling populer sekarang ini adalah jaringan, karena kekuasaan itu ada dimana-mana (dispersed) sehingga tugas gerakan anti-kapitalisme adalah membangun jaringan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Ini berarti, sebagai konsekuensinya, rakyat pekerja bukan lagi motor penggerak kekuatan anti-kapitalisme, melainkan apa yang disebut oleh Michael Hardt dan Antonio Negri sebagai Multitude, kerumunan.
Buku yang ditulis Panitch dan Gindin ini datang untuk membongkar mitos yang telah menghunjam sanubari kita selama ini. Keduanya dengan lantang menentang tesis bahwa globalisasi ekonomi merupakan konsekuensi logis dari dinamika internal kapitalisme yang berwatak ekspansif, yang menjadikan negara tak lebih sebagai kendaraan pasifnya para kapitalis. Menurut keduanya, neoliberalisme justru tidak akan pernah sukses tanpa adanya peran negara yang besar dan kuat dalam memfasilitasi dan meregulasi berbagai bentuk perundang-undangan demi bekerjanya sistem ini. Oleh sebab itu, buku ini tidak saja sangat penting karena sumbangannya yang luar biasa bagi pemahaman kita atas negara dalam kaitannya dengan sistem kapitalisme-neoliberal, tapi juga merupakan abstraksi teoritik atas kecenderungan yang menguat dalam gerakan anti-kapitalisme saat ini bahwa ‘untuk bisa mengubah keadaan kita harus merebut kekuasaan negara.’

Negara kuat
Untuk membuktikan tesisnya itu, Panitch dan Gindin mengkhususkan studinya pada negara Amerika Serikat (AS). Alasannya karena ‘peran AS dalam menciptakan kapitalisme global tak terbantahkan’ (h. 25). Menurut keduanya, peran aktif AS ini bukan sesuatu yang kebetulan (accidental) melainkan melekat (built-in) dalam proses pembentukan negara tersebut. Ia tidak datang atau berasal dari tempat lain. Ini, misalnya, tampak dari kata-kata para pendiri AS, seperti George Washington, yang menggambarkan ambisi negara baru ini sebagai ‘a rising empire.’
Tetapi berbeda dengan kekaisaran lama (old empire) seperti Romawi dan Inggris yang ditegakkan melalui kolonisasi, kekaisaran AS (American empire) adalah kekaisaran tanpa koloni. Tipe baru kekaisaran ini kelak memunculkan konsekuensi politik, ekonomi dan juga teoritik ketika kita membahas watak Negara AS.
Lalu bagaimana cita-cita kekaisaran tersebut direalisasikan? Di sini, Panitch dan Gindin memulai pembahasannya tentang karakteristik kunci dari pembangunan ekonomi AS. Katanya, ekonomi AS bertumpu pada modernisasi teknologi yang berakar pada akumulasi kapital domestik melalui pertumbuhan yang intensif. Ketika pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ini tidak sanggup lagi difasilitasi oleh batas-batas wilayah domestiknya, maka para kapitalis ini membutuhkan wilayah baru untuk merealisasikan nilai-lebihnya (surplus-value). Di sinilah Negara berperan aktif dalam memfasilitasi ekspansi kapital tersebut baik melalui ekspansi teritorial maupun perluasan akses kepada pasar internasional yang tertutup dan jauh.
Perluasan ekspansi teritorial di sini berarti pembentukan wilayah-wilayah baru, pengusiran penduduk lokal dari tanahnya, penciptaan undang-undang yang memberikan kekuatan hukum bagi pengalihan tanah-tanah diam dan sumberdaya alam ke dalam pengusaan para kapitalis, eksploitasi budak kulit hitam yang sadis, hingga penghancuran gerakan rakyat pekerja. Dalam konteks AS abad ke-19, ekspansi teritorial itu berada dalam lingkup kontrol kedaulatan negara, yakni di dalam negeri AS sendiri, misalnya, ekspansi kapital ke Ohio, Texas, California, dan Oregon (h. 27).
Selain memfasilitasi ekspansi kapital, Negara juga menerapkan kebijakan perlindungan pasar nasional melalui kebijakan tarif tinggi bagi barang-barang produk asing. Hasilnya, pada abad ke-19, AS menjadi saksi bagi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa pesat. Jika pada 1870 tingkat produktivitasnya masih 14 persen lebih rendah dari Inggris, pada akhir abad ke-19 tingkat pertumbuhannya menjadi 7 persen lebih besar, dan pada 1913 meningkat lagi menjadi 20 persen lebih besar dari Inggris serta dua kali lebih besar ketimbang Jerman dan Prancis. Dalam hal sumbangan kepada produksi dunia, pada 1870 share AS sudah mencapai 23 persen, lalu mencapai 30 persen pada 1900, dan meningkat lagi menjadi 36 persen pada 1913. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan sumbangan Inggris dan Jerman dijadikan satu. Perusahaan-perusahaan berskala besar, juga lahir pada periode ini. Misalnya, hampir 30 persen dari 500 daftar perusahaan yang dirilis majalah Fortune pada 1990, didirikan antara tahun 1880 dan 1910 (h. 28).
Peningkatan ekonomi ini tentu saja beriringan dengan bertambah besarnya jumlah kelas pekerja baru di AS. Organisasi-organisasi serikat buruh mulai bermunculan dan makin militan. Begitu dramatisnya dinamika petumbuhan ekonomi AS tentu saja bersandar pada hubungan sosial yang eksploitatif antara kelas buruh dan borjuasi. Panitch dan Gindin menulis bahwa pada seperempat akhir abad ke-19, gerakan kelas pekerja AS tampak seperti pelopor (vanguard) bagi perjuangan kelas internasional (h. 33), karena kemampuan mobilisasi dan militansinya yang luar biasa. Keduanya mencatat, periode ini ditandai dengan terbentuknya Knight of Labor pada 1969, Great Railway Strike pada 1887, dan yang paling terkenal tentu saja adalah pemogokan massal menuntut 8 jam kerja sehari, yang berlangsung pada 1 Mei 1886 di Haymarket Square, Chicago. Pemogokan di Haymarket Square ini berlangsung selama beberapa hari. Pada tanggal 4 Mei, polisi secara brutal membubarkan aski ini dan kemudian menghukum mati tujuh orang pemimpin aksinya (h. 33).
Namun, represi brutal di Haymarket itu tak menyurutkan militansi rakyat pekerja. Aksi-aksi demonstrasi buruh dan organisasi-organisasi sosialis tidak berkurang, bahkan mencapai puncaknya pada awal tahun 1890an. Terhadap aksi-aksi ini, Negara melakukan tindakan yang sangat keras dalam memadamkan dan membungkam kemunculan aksi-aksi serupa. Pada saat yang sama, para kapitalis dalam menghadapi gelombang aksi pemogokan buruh yang terus berlangsung, juga melakukan pengelompokan-pengelompokan baru di kalangan mereka, baik melalui asosiasi-asosiasi bisnis di tingkat lokal maupun melalui organisasi-organisasi kebudayaan, serta lembaga-lembaga nasional yang sangat kuat seperti National Association of Manufacture, yang semula dibentuk untuk mendorong ekspor AS serta terkenal sangat anti serikat buruh. Menurut Panitch dan Gindin, pengelompokan baru yang paling penting adalah aliansi baru antara para pebisnis ini dengan Partai Republik (h. 34). Dalam menghadapi pemogokan-pemogokan itu, para kapitalis tersebut, sebagai sebuah kelas, untuk sementara melupakan kompetisi di antara mereka dalam pasar.
Internasionalisasi Negara AS
Pada dekade 1900an, setelah melalui serangkan tindakan represif untuk membungkam gerakan buruh, Negara kemudian meluncurkan serangkaian UU yang memproteksi hak kepemilikan dari gangguan kelas buruh. Keadaan ini menyebabkan militansi serikat buruh melemah, dan kemudian lebih mengandalkan strategi politik pragmatis di bawah naungan American Federation of Labor (AFL) yang anti politik.
Hasilnya, ekonomi AS melaju kencang. Pasar dalam negeri pun dirasa mulai terbatas, sehingga fokus kini dialihkan pada ekspansi ke pasar internasional. Ini tak berarti bahwa pasar dalam negeri telah jenuh, namun pasar luar negeri dijadikan sebagai peluang baru untuk ekspansi kapital. Di sini, lagi-lagi peran Negara sangat menentukan, dengan dirumuskannya fungsi baru Negara sebagai ‘promotional state’ yang tugas utamanya adalah ‘internasionalisasi tarif, yang mengubah peran Negara dari yang murni melindungi menjadi aktor penting dalam “bargaining” dengan negara-negara lain guna “membantu perluasan ekspor AS melalui reduksi selektif barang-barang material, sekalgius mengubah kebijakan dan tindakan negara-negara lain melalui manipulasi tarif.”’ Perubahan fungsi Negara menjadi promotional state tersebut dikukuhkan melalui sebuah UU yang bernama McKinley Tariff Act of 1980 (h. 35). Fleksibilitas ini kemudian mendasari terbentuknya kebijakan ‘Pintu Terbuka/Open Door policy,’ dimana tujuan utamanya adalah melindungi kesempatan yang sama dalam pasar internasional. Tak lama berselang, Departemen Luar Negeri menciptakan lembaga baru, yakni Bureau of Foregin Commerce pada 1899. Di sini, kita lihat bagaimana masalah ekonomi, dalam hal ini promosi kepentingan-kepentingan kapitalis AS dianggap sebagai sebuah tugas politik dari Departemen Luar Negeri. Tak lama sesudahnya, pemerintah membentuk Department of Commerce and Labor pada 1903, yang tugas khususnya adalah melaporkan situasi pasar dunia bagi barang-barang produk AS.
Jika kita pahami bahwa ekspansi pasar internasional itu tidak hanya berurusan dengan masalah dagang, maka peran Negara menjadi lebih krusial lagi. Ekspansi kapital ke luar negeri tidak akan berarti banyak jika itu hanya bermakna perpindahan barang, uang, dan jasa. Karena watak dasar kapital itu adalah akumulasi keuntungan tanpa batas, maka stabilitas dan keberlangsungan usaha lebih penting lagi. Itu sebabnya, ekspor kapital berarti juga mengekspor cara/metode kerja, ilmu pengetahuan, serta mentalitas dan budaya pasar ini ke luar negeri. Anda tidak bisa mengakumulasi kapital secara berkelanjutan di masyarakat yang struktur sosialnya mengandalkan mekanisme pertukaran barter, atau pada struktur masyarakat yang kelas buruhnya sangat kuat, atau pemerintahan nasionalnya anti-modal asing. Dan itu berarti, kapital membutuhkan tanah, tenaga kerja, dan penguasaan sumberdaya alam setempat, seperti baja, emas, pertambangan, hutan, sistem politik dan kultural, dsb. Di hadapkan pada situasi ini kapital mau tidak mau sangat mengandalkan Negara, tidak hanya untuk membuka pasar luar negeri terhadap produk-produk AS, tetapi juga menjamin kelangsungan akumulasi kapital di luar negeri.
Dalam proses menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan bagi ekspansi dan akumulasi kapital di pasar internasional tersebut, kita lihat bahwa kebijakan politik luar negeri AS sangatlah pragmatis. Secara retorik bisa saja mereka berkoar-koar bahwa seluruh bentuk intervensi politik luar negeri bertujuan untuk mempromosikan kebebasan (freedom) dan demokrasi (democracy), tetapi dalam prakteknya AS merupakan pendukung utama dari rezim-rezim kediktaroran militer paling berdarah di seluruh dunia, mulai dari rezim Orde Baru di Indonesia, rezim-rezim militer di Amerika Latin, para raja-raja keji di Timur Tengah, hingga pemerintahan apartheid di Afrika Selatan.
Ekspansi ke pasar internasional ini membuat perekonomian AS bertumbuh sangat pesat. Pada pertengahan tahun 1920an, ekspor barang-barang manufaktur betumbuh dua kali lipat dari yang mereka capai sebelum perang, dan sejak tahun 1922-1928, total ekspor bertumbuh hampir 50 persen lebih cepat dari pertumbuhan GDP domestik yang hanya mencapai 40 persen. Mata uang Dollar kemudian menjadi cadangan mata uang utama dalam sistem keuangan dunia saat itu. Lebih dari itu, aliran kapital swasta AS ke Eropa setelah Perang Dunia I diperkirakan lebih besar dari yang terjadi segera setelah PD II. Setelah dekade 1920an, nilai buku dari total investasi langsung AS mencapai 129 persen dalam bidang manufaktur, dan 95 persen secara keseluruhan. Di kawasan Amerika Latin, AS kemudian sukses mengalahkan Inggris dalam adu kuat perebutan pengaruh di kawasan tersebut (h.49).
Negara di Masa Krisis Ekonomi
Di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi tinggi itu, tiba-tiba perekonomian AS dilanda krisis parah yang berujung pada depresi ekonomi di dekade 1930an. Pada tahun 1932 tercatat perdagangan dunia jatuh sebesar 1/3 dari pencapaian sebelum tahun 1929. Akibatnya, banyak perusahaan tutup, pengangguran berlimpah, dan jumlah tenaga kerja yang di-PHK melonjak. Pada tahun 1933, jumlah buruh mencapai 3 juta orang dari yang lima tahun sebelumnya mencapai 5 juta orang.
Kondisi ini menyebabkan munculnya pemogokan di hampir seantero negeri. Ratusan ribu orang turun ke jalan-jalan menuntut agar mereka tidak dipaksa menanggung akibat dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh bangkrutnya sistem keuangan saat itu. Menghadapi demonstrasi buruh yang terus membesar dan semakin militan tersebut, Presiden F.D. Reosevelt terpaksa mengakomodasinya melalui penerapan kebijakan New Deal, yang mengikuti garis Keynesianisme. Dalam salah satu pernyataannya, Roosevelt mengatakan bahwa ‘hubungan antara negara juga harus direformasi untuk mencegah terjadinya revolusi dan perang’ (h. 56). Intervensi pemerintah dalam pasar ini dimulai dengan diundangkannya Glass-Steagall Act (1933) yang dimaksudkan untuk meregulasi sektor perbankan, dengan cara membatas aktivitas perbankan sekuritas serta memisahkan bank komersial dari bank investasi (h. 57). Selanjutnya, pemerintah mengundangkan The National Industrial Recovery Act/NIRA (1933) yang menjamin adanya tawar-menawar kolektif (collective bargaining) antara buruh dan manajemen. Tak lama berselang, pada 1935, atas inisiatif Senator Robert Wagner, pemerintah meloloskan National Labor Relations Act/NLRA (juga dikenal sebagai the Wagner Act) yang mewajibkan kapitalis untuk melakukan tawar-menawar dengan serikat buruh yang didukung oleh mayoritas anggotanya.
Namun konflik ideologi dan politik dalam internal gerakan buruh serta makin menurunnya jumlah anggota serikat buruh akibat pemecatan, menyebabkan kekuatan serikat buruh di hadapan kapitalis semakin melemah. Pada saat yang sama, kaum kapitalis pun terus menggencarkan penolakannya terhadap the Wagner Act. Pergeseran kekuatan kelas ini menyebabkan berakhirnya reformasi New Deal jilid II (h. 61). Keadaan ini membuktikan bahwa Negara sanggup menjadi benteng terakhir kapitalisme ketika gerakan buruh semakin militan di hadapan kelas kapitalis yang lemah akibat krisis. Dalam bahasa Panitch dan Gindin, Rosevelt sanggup membawa para banker, industrialis dan pemimpin-pemimpin serikat buruh moderat ke dalam apa yang disebut ‘grand truce/gencatan senjata’ pada bulan pertama tahun 1938 (h.62)
Negara Pasca Perang Dunia II
Setelah PD II, ekonomi AS tumbuh sebagai kekuatan terbesar di dunia. AS kini muncul sebagai satu-satunya kekuatan imperial, secara politik, militer, dan ekonomi. Untuk mencegah berulangnya krisis ekonomi dunia, AS lantas memelopori pembentukan Bank Dunia dan IMF mengikuti garis Keynesian. Prioritasnya adalah ‘mengorganisasikan sumberdaya-sumberdaya ekonomi dunia sehingga memungkinkan berlangsungnya kembali perdangan bebas di seluruh dunia’ (h. 67).
Peranan Negara AS pada masa perang ini semakin penting. Di satu sisi karena bangkrutnya negara-negara Eropa pasca PD II, di sisi lain karena adanya ketakutan terhadap ancaman dari gerakan kiri yang tengah menanjak popularitasnya di mata rakyat akibat perlawanannya yang gigih dan heroik terhadap fasisme Hitler. Di hadapan situasi ini, maka tujuan utama berupa perdagangan bebas harus segera direalisasikan, pertama-tama dengan meminta seluruh negara di dunia untuk tidak hanya mencabut penghalang tarif tetapi juga ‘subsidi, monopoli, aturan-aturan perburuhan yang ketat, pertanian feodal, keterbelakangan teknologi, hukum pajak yang telah usang, dan seluruh hambatan perdagangan lainnya harus dihapuskan’ (h. 67).
Tetapi di sini, ada hal yang berbeda dari kebijakan imperial AS dengan kebijakan negara-negara imperial sebelumnya, seperti Inggris dan Romawi. Di sini, AS, menurut Panitch dan Gindin, dalam proses pemulihan ekonomi Pasca PD II, tidak semata-mata mengedepankan kepentingan kapitalis AS di hadapan kapitalis-kapitalis negara lain. Jika ini yang dilakukan AS, maka kelak hanya akan memicu munculnya kembali perang dunia. Bagi AS, yang paling penting adalah mengintegrasikan seluruh negara di dunia ke dalam sirkuit kapital global tanpa harus menduduki wilayah dari negara-negara tersebut. Dalam perspektif ini, boleh jadi kebijakan AS itu menguntungkan kapitalis domestik dari negara-negara di luar AS dalam jangka pendek, atau bahkan secara ekonomi dalam jangka pendek tidak ada keuntungan signifikan yang diperoleh AS, tapi dalam jangka panjang hal itu penting bagi stabilitas kapitalisme secara global. Pandangan Panitch dan Gindin ini, secara teoritik jelas menolak definisi imperialisme lama, seperti yang dikemukakan Lenin, misalnya, yang melihat peran Negara semata-mata sebagai alatnya kelas kapitalis domestik untuk mengeksploitasi pasar dunia. Itu sebabnya, kesimpulan Lenin bahwa perang dunia bisa sewaktu-waktu meletus benar adanya.
Dengan kacamata inilah kita mesti melihat bantuan ekonomi besar-besaran terhadap Eropa Barat melalu kebijakan Marshall Plan, atau bantuan terhadap Jepang, Korea Selatan, juga Taiwan. Melalui serangkaian kebijakan itu, perekonomian negara-negara tersebut perlahan-lahan bangkit dari keterupurukannya dan korporasi-korporasi mereka pun kemudian muncul sebagai pesaing berat korporasi-korporasi AS. Pada dekade 1960an, sudah jelas tampak bahwa dominasi korporasi AS makin tergerus.
Tapi, itu tidak berarti bahwa peran Negara AS kemudian melemah. Justru sebaliknya, melalui integrasi yang semakin dalam ke sirkuit akmulasi kapital global, peran Negara AS menjadi penjamin terakhir, atau apa yang disebut Panitch dan Gindin sebagai ‘the commanding heights’ bagi stabilitas akumulasi global kapitalisme (h. 289). Dengan semakin terintegrasi ke dalam sirkuit kapital global, maka kompetisi di antara negara-negara tersebut juga semakin tinggi dalam memperebutkan pasar, tenaga kerja murah, dan kandungan sumberdaya alam yang semakin terbatas. Karena negara-negara tersebut (selain AS) memperjuangkan kepentingan borjuasi domestiknya masing-masing, maka potensi untuk meledak dalam perang militer terbuka semakin besar. Dalam konteks itulah keberadaan AS, menjadi penting, yakni mengelola kompetisi global itu agar tidak meledak menjadi perang militer terbuka. Itu sebabnya, ketika Irak di bawah Saddam Hussein menyerang Kuwait, maka AS dengan cepat meresponnya secara militer, dimana tujuan utamanya, selain untuk menjaga stabilitas di kawasan kaya minyak itu juga sekaligus memberi pelajaran kepada negara-negara yang tak mau tunduk pada logika akumulasi global tersebut.
Peran AS sebagai ‘the commanding heights’ bagi akumulasi kapital global ini semakin menguat ketika neoliberalisme muncul menggantikan Keynesianisme pasca krisis dekade 1970an. Meningkatnya kontribusi sektor finansial melampaui sektor industri, membuat ekonomi AS semakin rentan terhadap goncangan krisis karena fundamental ekonominya yang rapuh. Pada tingkat domestik, satu-satunya cara untuk membuat perekonomian tetap berputar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, adalah dengan ekspansi sektor konsumsi yang dibiayai melalui utang. Pada tingkat global, pasar global yang semakin terintegrasi merupakan kunci untuk meredam terjadinya krisis. Itu sebabnya AS, baik secara bilateral maupun multilateral semakin getol mendorong dan mempersuasi negara-negara di dunia agar semakin mengintegrasikan dirinya ke dalam sirkuit akumulasi global, melalui serangkaian kebijakan privatisasi, liberalisasi, deregulasi, dan pasar tenaga kerja yang fleksibel, serta peran negara yang kuat dalam memfasilitasi bekerjanya serangkaian kebijakan neoliberal tersebut. Bergabungnya Cina sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi dan paling stabil di dunia dalam dua dekade terakhir, merupakan sukses besar dalam integrasi pasar global tersebut.
Dengan semakin terintegrasinya pasar dunia, maka sebenarnya AS juga telah membagi resiko krisis ke negara-negara tersebut. Sedikit saja terjadi krisis dalam ekonomi AS, maka hal itu akan segera menyebar dan menjangkiti ekonomi negara-negara lain. Sehingga, satu-satunya jalan untuk mengatasi krisis global yang dipicu oleh krisis ekonomi AS, adalah dengan meminta tanggung jawab bersama dari negara-negara lain untuk mengatasinya. Melalu strategi ini, maka peran AS sebagai sebuah kekaisaran (empire) makin tak tergoyahkan. Sekali lagi, ini menunjukkan bagaimana peran Negara begitu vital dalam proses akumulasi kapital di tingkat global ini.
Tinjauan Kritis
Walaupun buku ini secara detil menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta empiris mengenai pentingnya peran Negara dalam globalisasi ekonomi, tak berarti buku ini lepas dari kritik. Kita tahu bahwa hubungan Negara dan ekonomi merupakan topik yang sangat penting dalam studi-studi Marxis. Salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah, bagaimana menjelaskan peran negara sebagai regulator dan penjamin kebijakan neoliberal? Apakah negara semata-mata bertindak sesuai dengan kepentingan kelas kapitalis? Atau negara memiliki otonomi relatif dalam hubunganya dengan kelas kapitalis?
Dalam buku ini, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini, Panitch dan Gindin pertama kali mencoba mengklarifikasi perbedaan hubungan antara negara dan ekonomi dalam masyarakat pra-kapitalisme serta masyarakat kapitalis. Menurut mereka, pada masa pra-kapitalis, tidak ada perbedaan legal antara negara dan ekonomi, sementara dalam masyarakat kapitalis, antara negara dan ekonomi perbedaan legal itu terjadi. Namun, Panitch dan Gindin kurang memberikan penjabaran mengenai adanya perbedaan dalam dua corak masyarakat tersebut, sehingga sebelum kita ikuti lebih jauh argumentasi keduanya, saya ingin mengajak pembaca untuk mengikuti pemikiran salah satu ilmuwan politik Marxis terkemuka saat ini, Ellen Meiksins Wood, yang juga berbicara mengenai topik ini.
Wood dalam bukunya Empire of Capital,[1] mengatakan bahwa dalam masyarakat berkelas yang non-kapitalis (non-capitalist class societies), biasanya tidak sulit untuk mengidenfikasi di mana lokus kekuasaan berada. Cukup bagi kita untuk mencari sumber-sumber kekerasan politik serta militer dan pada saat yang sama, kita temukan kekuasaan ekonominya. Di sini, kekuasaan ekonomi dari kelas-kelas dominan tergantung pada pemaksaan ‘extra-economic.’ Sederhananya, kalau Anda memiliki kekuasaan politik dan militer, maka anda juga adalah penguasa ekonomi; dan sebaliknya, penguasaan ekonomi itu dilakukan melalui pemaksaan militer dan politik. Seorang tuan tanah, pada masa feodal, adalah juga penguasa politik, militer, dan ekonomi sekaligus.
Tapi, tidak demikian pada era kapitalisme. Antara penguasa ekonomi (economic power) terpisah dari penguasa politik atau militer (political or military power). Dalam kapitalisme, segala sesuatunya tergantung pada pasar. Pasar memiliki kekuatannya sendiri untuk memaksakan kepada semua orang, baik kapitalis maupun buruh, hal-hal mendasar bagi bekerjanya sistem ini secara impersonal, misalnya, pemaksaan akan hukum kompetisi, akumulasi, dan maksimalisasi laba. Karena semua orang tergantung pada pasar, maka untuk bisa hidup, orang-orang ini harus menyesuaikan dirinya dengan hukum-hukum dasar kapitalisme tersebut. Itu sebabnya, kapitalisme tidak hanya berurusan dengan soal jual-beli, tapi lebih dari itu, ia berurusan dengan persoalan hubungan sosial masyarakat secara keseluruhan.
Hubungan buruh dan kapitalis, misalnya, dimediasi atau berlangsung di pasar. Dalam kapitalisme, keberadaan buruh adalah bebas ganda: selain ia adalah pemilik dirinya sendiri, ia juga tidak memiliki alat-alat produksi. Karena itu, tidak seperti pada masa pra-kapitalis dimana tuan feodal bisa memaksa petani (secara militer) untuk bekerja di tanahnya dan memiliki kontrol langsung atas tubuh si petani hamba, seorang kapitalis tidak bisa semena-mena menggunakan kekuasaan militer untuk memaksa orang bekerja di pabriknya. Apa yang terjadi adalah, baik si kapitalis dan si buruh sama-sama pergi ke pasar tenaga kerja untuk mencari pembeli dan penjual. Dengan demikian, eksploitasi kapital terhadap buruh tidak bergantung pada kekuatan ‘extra-economic’ seperti di era pra-kapitalis, sehingga konsekuensinya, hegemoni kekuasaan ekonomi pun bisa melampui batas-batas dominasi politik secara langsung.
Melalui pemisahan antara negara dan ekonomi ini, maka dalam masyarakat kapitalis, negara bekerja dengan logikanya sendiri, sementara ekonomi juga memiliki logika kerja sendiri. Lalu, apakah ekonomi tidak membutuhkan negara, karena melalui hukum pasar toh masyarakat bisa diorganisasikan? Atau sebaliknya, apakah negara bisa eksis tanpa adanya basis ekonomi yang menopangnya? Di sini, kita kembali kepada Panitch dan Gindin. Menurut keduanya, adanya pembedaan antara negara dan ekonomi itu tidak berarti negara dan ekonomi berjalan sendiri-sendiri. Namun berbeda dengan Wood yang mengatakan bahwa negara dan ekonomi adalah terpisah (separation), Panitch dan Gindin melihat hubungan itu berbeda (differentiation). Artinya, secara legal negara berbeda dari ekonomi tapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Sebagai contoh, dalam kasus negara-negara kapitalis maju, faktanya keterlibatan negara dalam urusan ekonomi justru lebih dalam ketimbang pada periode pra-kapitalisme, khususnya dalam soal penciptaan dan pengelolaan hukum, aturan, kerangka kerja infrastruktural bagi kepemilikan pribadi, kompetisi, dan kontrak-kontrak ketika ekonomi mulai beroperasi. Negara-negara kapitalis juga merupakan aktor utama dalam melindungi terjadinya krisis kapitalis, termasuk sebagai penjamin terakhir (lenders of the las resort). Dan sebaliknya, negara lalu semakin tergantung pada kesuksesan akumulasi kapital melalui penarikan pajak dan mempertahankan legitimasi rakyat (h. 3).[2]
Inilah dasarnya mengapa mereka mengatakan bahwa negara memiliki otonomi relatif terhadap ekonomi. Artinya, negara kapitalis bukannya tak berhubungan dengan kelas kapitalis, tetapi negara juga memiliki kemampuan untuk bertindak atas nama sistem itu secara keseluruhan, namun pada akhirnya, otonomi negara tersebut dalam merespon atau tidak tekanan masyarakat, dibatasi oleh ketergantungan mereka pada kesuksesan akumulasi kapital. Itu sebabnya, otonomi negara hanya bersifat relatif (h. 4). Dengan demikian, keduanya menolak gagasan bahwa Negara adalah kendaraan pasif bagi kelas kapitalis untuk merealisasikan dan mengawal kepentingannya.
Namun, berkaitan dengan tesis Otonomi Relatif Negara tersebut, muncul persoalan lain seperti yang dipertanyakan James Petras: ‘relatif terhadap apa? Di mana? Kapan? Di bawah kondisi dan kerangka waktu seperti apa?’ Pertanyaan lain yang muncul sehubungan dengan penggunaan istilah ‘otonomi’ ini adalah otonomi ‘dari apa?’ ‘Terhadap apa?’ ‘Kadang-kadang, sering sekali atau dalam keseluruhan waktu?’[3] Terhadap pertanyaan ini, Panitch dan Gindin tidak memberikan penjelasannya sama sekali.
Persoalan mendasar lainnya yang mengganjal dari buku ini adalah penekanannya yang sangat besar pada dimensi ekonomi dari kekaisaran AS ini. Panitch dan Gindin menunjukkan bahwa sukses AS sebagai ‘the commanding heights’ sangat ditentukan oleh kemampuan diplomasi ekonominya baik melalui departemen luar negeri, departemen perdagangan, maupun melalui forum-forum multilateral, seperti IMF, Bank Dunia, WTO, kerjasama-kerjasama ekonomi regional, maupun melalui pengelompokan negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi ke dalam G-20. Keduanya tidak sedikitpun menyentuh pembahasan soal dimensi politik-militer dari kekaisaran ini, dan juga tidak ada penjelasan kenapa aspek vital tersebut diabaikan.
Dengan demikian, buku ini gagal dalam menjelaskan serangkaian aksi-aksi politik-militer yang dilakukan oleh AS, baik secara terbuka maupun tertutup di berbagai negara dan kawasan di muka bumi ini. Misalnya, bagaimana menjelaskan dukungan AS atas kudeta militer terhadap Presiden Soekarno, operasi militer terbuka AS terhadap Panama, dukungan secara langsung melalui operasi intelijen terhadap penggulingan Presiden Salvador Allende di Chile, dan penggulingan pemerintahan Sandinista di Nicaragua. Atau dalam kasus terakhir, invasi militer terhadap Irak dan Afghanistan. Apakah aksi-aksi polisional AS tersebut memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan yang dikejar melalui aksi-aksi diplomasi ekonomi? Apakah kepentingan para pengambil kebijakan militer itu tidak sejalan dengan kepentingan ekonomi korporasi AS?
Penutup
Membaca buku ini, kita disadarkan bahwa dalam perjuangan melawan sistem kapitalisme-neoliberal, kita tak bisa mengabaikan peran Negara. Slogan-slogan lama gerakan, seperti ‘Emoh negara,’ ‘gerakan kita a-politis,’ ‘gerakan kita adalah gerakan moral,’ sudah kadaluwarsa. Slogan-slogan yang dicekokkan ke dalam batok kepala kita itu harus segera disingkirkan jauh-jauh sejak sekarang. Kini kita mesti berani berteriak lantang: ‘Untuk mengubah keadaan, kita mesti merebut kekuasaan negara.’
Melalui slogan ini, kita diharuskan untuk mengubah orientasi pergerakan kita, memperjelas dasar-dasar teoritik, memperbarui kembali bentuk organisasi, dan metode-metode pembangunan organisasi perjuangan tersebut. Di era kapitalisme-neoliberal yang dijaga oleh kekaisaran AS ini, perjuangan yang bersifat lokal, a-politis, dan sektarian sama sekali tidak banyak gunanya dalam perjuangan.
¶
[1] Ellen Meiksins Wood, Empire of Capital, Verso, London, 2005.
[2] Kesimpulan Panitch dan Gindin ini sama persis dengan kesimpulannya Wood, ‘While capital does require support by state coercion, the power of the state itself, or so it seems, circumscribed by capital.’ Ibid., h. 11.
[3] Lihat Coen Husain Pontoh, ‘Imperialisme, Motor Penggerak Sejarah Kontemporer Tinjauan Atas Pemikiran James Petras,’ Jurnal IndoPROGRESS III, Resist Boook, Yogyakarta, 2013.