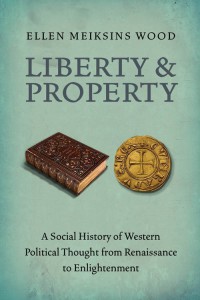Judul Buku: Liberty and Property: A Social History of Western Political Thought from Renaissance to Enlightenment Pengarang: Ellen Meiksins Wood Penerbit: Verso, London/New York, 2012 Tebal: x + 325 h. PEMIKIRAN politik Barat seringkali dipahami dan dipelajari secara parsial atau setengah-setengah. Baik dalam diskursus politik di tanah air maupun di kelas-kelas ilmu politik di negara industrialis maju, pemikiran politik Barat seringkali direduksi menjadi pengetahuan akan jargon-jargon belaka. Akibatnya, pemahaman kita menjadi jargonistik dan ahistoris, memakai istilah-istilah seperti ‘hak,’ ‘negara,’ ‘kedaulatan,’ ‘kebebasan’ dan ‘kapitalisme’ tanpa memahami konteks historis dari istilah-istilah tersebut. Di tengah-tengah kondisi tersebut, Ellen Meiksins Wood berusaha memberikan analisanya tentang Pemikiran Politik Barat melalui perspektif sejarah sosial dari Abad Renaisans hingga Abad Pencerahan. Buku ini, yang merupakan lanjutan dari buku Wood sebelumnya, yaitu Citizens to Lords, membahas berbagai pemikiran filsuf politik Barat, dari Machiavelli hingga Spinoza, dari Montesquieu hingga Locke dengan meletakkannya pada konteks sosio-historis pembentukan negara, perkembangan awal kapitalisme dan kelas borjuis, perebutan klaim kedaulatan, hingga benturan dan dialektika antara faktor-faktor ideasional dan material. Kali ini, Wood berusaha membongkar mitos “keterkaitan” antara modernitas, kapitalisme, dan demokrasi. Menurut Wood, kapitalisme perlu dipahami sebagai bentuk perkembangan unik dari fase perkembangan modernitas Barat. Wood juga berpendapat bahwa secara historis, ada ketegangan yang tak terelakkan antara demokrasi dan kapitalisme – sebuah ketegangan yang juga belum terselesaikan hingga sekarang. Transisi Historis Peradaban Barat: Menuju Modernitas atau Kapitalisme Wood membagi bukunya dalam delapan bab yang disusun kurang lebih secara kronologis. Bab pertama membahas tentang debat-debat dalam transisi feodalisme ke kapitalisme, metode penafsiran sejarah pemikiran politik Barat, dan pentingnya sejarah sosial dalam membahas filsafat politik Barat. Bab kedua hingga ketujuh masing-masing membahas tentang sejarah pemikiran politik mulai dari masa Negara Kota Renaisans, Reformasi Protestan, Kekaisaran Spanyol, Republik Komersial Belanda, Absolutisme Perancis hingga Revolusi di Inggris. Di bab terakhir, Wood kembali menegaskan argumennya tentang ketegangan antara modernitas, kapitalisme, dan demokrasi serta implikasinya terhadap konteks sekarang ini. Di bab pertama, Wood mengkritik dua tendensi dalam penulisan sejarah, yaitu pendekatan posmodernis dan revisionis. Dalam berbagai debat tentang penulisan sejarah, Wood menyadari bahwa ada sejumlah argumen yang menolak adanya sejarah dan karenanya mempertanyakan apa yang disebut sebagai modernitas. Wood mengritik tendensi tersebut karena menurutnya kesadaran historis itu penting untuk memahami kondisi masa kini yang bisa jadi merupakan hasil dari suatu proses sejarah yang panjang di masa lampau. Kesadaran akan proses dan konteks sejarah inilah yang digunakan Wood untuk membedah sejumlah pemikiran filsuf Barat dan meletakkannya pada konteks sosial di mana pemikiran-pemikiran tersebut lahir. Namun, Wood juga mengingatkan kita akan satu hal: pentingnya memperhatikan keragaman kondisi di tiap-tiap tempat dan perkembangan zaman. Sejumlah hal yang perlu kita perhatikan dalam memahami sejarah sosial pemikiran politik Barat antara lain adalah kondisi tatanan sosial di masing-masing tempat, pola hubungan antara institusi kerajaan, kaum bangsawan, tuan tanah, dan rakyat (petani, kaum perempuan, pekerja, dan lain sebagainya), perebutan klaim atas kedaulatan, definisi akan konsep-konsep kunci dalam diskursus politik pada masa itu seperti ‘kebebasan,’ ‘rakyat,’ ‘kedaulatan,’ dan lain sebagainya Bab kedua dibuka dengan pembahasan akan latar belakang sejarah Negara-Kota (City-State) di Italia. Di konteks Italia, sejumlah Negara-Kota Italia seperti Venesia dan Firenze menjadi pusat perdagangan dan juga kota penghubung jaringan perdagangan di Eropa pada masa itu. Namun, perlu diingat bahwa embrio kapitalisme modern sudah berkembang di Italia. Faktanya, sebagian besar pendapatan para penguasa seperti kaum bangsawan justru didapat dari kegiatan-kegiatan ‘ektra-ekonomi’ (‘extra-economic’ factors) seperti pajak dari para petani penggarap dan rakyat jelata serta fasilitas dan gaji dari jabatan negara. Kemudian, kota-kota seperti Venesia dan Firenze, karena kemajuan ekonominya, juga menghadapi tantangan militer dari negara-negara lain. Konteks inilah yang perlu dipahami dalam menganalisa pemikiran Machiavelli, terutama dalam dua karya utamanya yaitu The Prince dan The Discourses. Pertanyaan politik terpenting bagi Machiavelli kira-kira adalah sebagai berikut: bagaimana seorang penguasa bisa mewujudkan ketertiban (order) sosial dan politik sekaligus mempertahankan kedaulatannya dari serangan musuh dari luar. Terlepas dari berbagai perdebatan dan kontroversi di seputar penggambaran Machiavelli baik sebagai perintis nilai-nilai ‘republikan modern’ sekaligus seorang ‘Machiavellian’ yang menghalalkan segala cara, Wood mencoba menelaah dua wajah dari pemikiran Machiavelli. Menurut Wood, dalam konteks politik domestik, sesungguhnya konsepsi politik Republikan ala Machiavelli lebih condong kepada tatanan politik yang memberikan ruang lebih besar kepada para warga negara dan membatasi kekuasaan kaum bangsawan atau aristokrasi. Dengan kata lain, pemikiran kenegaraan Machiavelli cenderung lebih demokratis dibandingkan oligarkis. Namun, dalam konteks kebijakan luar negeri, Machiavelli berpendapat bahwa Negara-Kota Italia perlu memiliki pertahanan dan militer yang kuat untuk menghadapi musuh-musuhnya – sebuah pemikiran yang juga menjadi dasar pemikiran Realisme modern dalam disiplin Hubungan Internasional. Di Bab ketiga, Wood memfokuskan pembahasannya kepada pemikiran dua tokoh agama terkemuka di Eropa, Martin Luther dan John Calvin, dalam konteks Reformasi Protestan dan tantangan terhadap kekuasaan Gereja Katolik pada waktu itu. Dalam pemaparan kali ini, kita akan fokus kepada pemikiran Luther. Martin Luther, sang reformer Protestan itu, berusaha menantang legitimasi Gereja sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi. Menurut Luther, semua manusia, semua orang beriman, memiliki kesamaan derajat di depan Tuhan. Luther mengakui bahwa manusia memang cenderung akan tergelincir kepada perbuatan dosa, namun karena kesamaan derajat manusia dan kasih sayang serta pengampunan Tuhan yang universal, maka umat manusia akan diselematkan oleh Tuhan. Singkat kata, karena semua manusia sama derajatnya di depan Tuhan dan berhak mendapatkan ampunan-Nya, maka peranan Gereja sebagai perantara kehilangan legitimasinya. Inilah konsep teologi Luther yang terkenal dan kontroversial itu. Namun, ini baru sisi lain. Dalam kaitannya dengan hubungan antara Gereja, mereka yang beriman, dan kekuasaan negara yang sekuler, Luther justru berpendapat bahwa mereka yang beriman harus tunduk terhadap kekuasaan negara yang sekuler, betapapun kejam dan sewenang-wenangnya kekuasaan negara, karena hanya dengan negaralah sebuah ketertiban sosial dapat terwujud. Luther memang menyebutkan bahwa orang-orang Kristen memiliki hak untuk melanggar aturan-aturan negara tatkala kekuasaan negara itu menyimpang terlalu jauh dari ajaran Kristen, tetapi itu tidak melegitimasi hak untuk memberontak terhadap negara tersebut – Luther justru menganjurkan kaum Kristiani untuk menerima hukuman dari negara apabila mereka menolak mematuhi aturan-aturan yang dianggap bertentangan dengan prinsip ajaran Kristen. Tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, doktrin kesetaraan manusia di hadapan Tuhan dan ketaatan manusia pada Tuhan ala Luther justru menjadi justifikasi bagi berbagai pemberontakan petani di Eropa – suatu hal yang Luther sendiri tidak menghendakinya. Dalam bab ini, Wood juga mencoba membongkar persepsi populer akan tesis Weberian tentang kapitalisme: bahwa ide-ide Protestanisme mempromosikan perkembangan kapitalisme di Eropa. Meskipun Wood berbeda pendapat dengan Max Weber mengenai perkembangan awal kapitalisme di Eropa, menurut Wood, Weber sendiri tidak pernah mengatakan bahwa ide-ide Protestanisme per se lah yang mendorong perkembangan kapitalisme. Menurut Wood, Weber mengakui bahwa embrio berupa perkembangan politik dan ekonomi yang kondusif terhadap perkembangan kapitalisme di Eropa sudah ada sebelum munculnya Protestanisme. Ide-ide Protestan hanya menjadi katalisator bagi perkembangan dan penyebaran kapitalisme. Bab keempat membahas tentang Kekaisaran Spanyol dan kolonialismenya. Para pemikir dan filsuf politik di Spanyol pada waktu itu berusaha menjawab berbagai permasalahan di seputar praktek kolonialisme Spanyol di Amerika Latin dan berbagai macam dampaknya. Di satu sisi, perebutan klaim atas kekuasaan politik dan keagamaan antara Kekaisaran Spanyol, kaum bangsawan dan pihak Gereja mendorong Spanyol untuk memperluas Kekaisarannya. Ketergantungan ekonomi Spanyol dengan berbagai sumber daya di tanah jajahannya seperti emas dan perak juga semakin meneguhkan pentingnya kolonialisme bagi ekonomi Spanyol. Namun, di sisi lain, Kekaisaran Spanyol juga memiliki kesulitan untuk menjustifikasi praktek kolonialismenya terhadap bangsa Indian di Amerika Latin, yang menurut banyak pemikir politik di Spanyol, juga memiliki peradaban yang sangat maju. Dalam konteks inilah, berbagai pemikir dalam suatu aliran pemikiran yang disebut sebagai Mazhab Salamanca (Salamanca School) berusaha menanggapi berbagai dilema dalam praktek-praktek kolonialisme dan imperialisme Kekaisaran Spanyol. Mereka yang mendukung penjajahan Spanyol atas Amerika Latin mencetuskan doktrin ‘Perang Adil’ (Just War) sebagai dalilnya. Perang Adil berangkat dari asumsi bahwa Kekaisaran Spanyol memiliki misi untuk memajukan peradaban manusia dan menyebarkan agama Kristen. Bangsa Indian di Amerika Latin, betapapun majunya peradaban mereka, masih memeluk praktek-praktek ‘Pagan’ dan karenanya Kekaisaran Spanyol memiliki kewajiban untuk ‘menyebarkan’ agama Kristen dan membuat bangsa Indian menjadi ‘beradab’ – melalui praktek-praktek seperti pemindahan agama secara paksa, perampasan tanah-tanah adat bangsa Indian, dan eksploitasi tenaga kerja bangsa Indian di lahan-lahan pertanian dan tanah-tanah kaum penjajah Spanyol di Amerika Latin. Sebaliknya, mereka yang menentang praktek kolonialisme mengatakan bahwa sekalipun bangsa Indian bukanlah orang Kristen dan karenanya kaum ‘Pagan’ atau ‘Kafir’ (Heretic), peradaban Indian adalah peradaban yang maju dan karenanya Kekaisaran Spanyol tidak memiliki hak untuk menjajah mereka. Bab kelima membahas tentang Republik Belanda, kebijakan perdagangannya, dan pengaruh dua hal tersebut pada tatanan dan pemikiran politik pada masa itu. Pertumbuhan kota-kota di Republik Belanda menjadikannya sebagai pusat perdagangan di Eropa pada masa itu. Bahkan, pertumbuhannya jauh lebih pesat dibandingkan dengan berbagai Negara-Kota di Italia. Tetapi, aktivitas komersial di Belanda berkembang pesat bukan karena aktivitas ekonomi kapitalis yang merespon impuls pasar, namun karena akvitas ‘ekstra-ekonomi’ sebagai perantara perdagangan (commercial mediators), alih-alih produsen (producers). Selain perdagangan, berbagai aktivitas ‘ekstra-ekonomi’ yang lain adalah ekspansi militer, pajak yang tinggi yang diperoleh dari rakyat, dan fasilitas yang tersedia untuk jabatan-jabatan negara. Aktivitas-aktivitas komersial dan ‘ekstra-ekonomi’ di Belanda dan juga Italia pada masa itu bukanlah akvititas ekonomi yang bersifat (proto-)kapitalis, karena aktivitas-aktivitas ini pada dasarnya kurang merespon impuls pasar dan tidak didorong oleh prinsip produksi yang kompetitif.

Perubahan sosial ini, yang mengakibatkan bangkitnya sejumlah elit lokal, kemudian memunculkan persoalan baru: bagaimana ‘mendamaikan’ berbagai klaim atas kedaulatan negara dan hak-hak rakyat. Dalam konteks inilah, ide-ide resistensi dan tantangan terhadap kedaulatan dan kekuasaan institusi monarki atau kerajaan muncul. Tetapi, ide-ide resistensi ini bukan berarti melegitimasi usaha resistensi dari warga negara terhadap kekuasaan negara atau kerajaan. Bagi banyak filsuf politik pada masa itu, warga negara atau rakyat secara individual tidak memiliki legitimasi untuk mewakili dirinya sendiri dalam politik – ia harus direpresentasikan oleh institusi kolektif yang mewakili kekuatan politik lokal (lesser magistrates) seperti kaum bangsawan, badan-badan korporasi, maupun pejabat lokal. Implikasi perubahan sosial ini dalam tataran filsafat politik sangatlah menarik. Ada pemikir seperti Hugo Grotius misalnya, bapak hukum internasional, yang mencetuskan konsep tentang hak-hak korporasi internasional, dalam konteks ini yaitu East India Company atau VOC, sebagai individu di dalam hukum internasional. Grotius juga memberikan dalil-dalil yang melegitimasi kolonisasi sejumlah tanah dan sumber daya di negara-negara lain – yang nantinya menjadi tanah jajahan Belanda. Ada juga pemikir seperti Spinoza, yang mendobrak ‘transendensi’ dalam konsepsi kekuasaan politik. Ketika banyak filsuf politik berpendapat bahwa kekuasaan politik bersumber dari ‘luar’, dari institusi kerajaan, Tuhan, atau suatu tatanan hukum alam misalnya, dan karenanya meniscayakan kekuasaan yang absolutis, Spinoza berpendapat bahwa sumber kekuasaan berasal dari rakyat, warga negara, sebagai kumpulan individu yang menempati negara itu sendiri – dengan kata lain, sumber kekuasaan yang bersifat ‘imanen’, dari rakyat, alih-alih transenden. Terlepas dari kecenderungan Spinoza untuk membatasi implikasi transformatif dari konsepsinya tentang sumber kekuasaan yang imanen, ide imanensi kekuasaan ala Spinoza merupaka gebrakan yang radikal dan demokratis pada zamannya – dan menjadi sumber inspirasi bagi sejumlah pemikir Marxis kontemporer seperti Etienne Balibar, Michael Hardt, dan Antonio Negri. Bab keenam dan ketujuh membahas tentang sejumlah pemikir politik terkemuka dalam konteks Absolutisme Negara di Perancis dan Revolusi di Inggris. Kontras antara kondisi sosial-politik di Perancis dan Inggris dapat membantu kita memetakan perbedaan corak pemikiran politik di antara kedua negara tersebut. Di Perancis, terdapat ketegangan politik antara institusi negara atau monarki yang ingin memperbesar kekuasaan absolutisnya versus kaum bangsawan dan tuan tanah yang ingin melawan kecenderungan tersebut. Di Inggris, sebaliknya, terdapat institusi negara yang sudah kuat sebagai hasil kompromi dan kerja sama antara pihak monarki dan aristokrasi. Kemudian, di Perancis, kaum petani atau peasantry cenderung bebas, dan meskipun para tuan tanah serta negara tetap berusaha untuk mengeksploitasi kaum petani melalui pajak dan iuran, tuan tanah dan bangsawan di Perancis lebih tertarik untuk memperkaya diri mereka melalui jalur ‘ekstra-ekonomi’ yang disediakan oleh negara. Sebaliknya, di Inggris, sebagian besar tanah dikuasai oleh para tuan tanah dan para bangsawan yang merespon impuls pasar, impuls komersial di masa proto-kapitalisme. Persaingan antara para tuan tanah di Inggris dalam memperkaya diri mereka membuat para tuan tanah berusaha menerapkan strategi pertanian yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi produk pertanian – suatu strategi yang kemudian melahirkan kapitalisme agraria di Inggris. Sejumlah pemikir dibahas di dua bab ini, mulai dari Montesquieu, Jean Bodin, Rousseau, Hobbes, dan Locke. Namun kita hanya akan membahas Rousseau dan Locke kali ini, sekaligus membongkar persepsi populer atas karya-karya mereka. Rousseau yang seringkali dituduh memiliki kecenderungan totaliter dalam karya-karyanya, justru merupakan pemikir yang paling berani menggugat kecenderungan absolutisme negara di Perancis. Keunikan pemikiran Rousseau adalah analisanya yang jeli akan negara absolutis di Perancis sebagai bagian dari dan bukan solusi atas masalah eksploitasi terhadap rakyat terutama kaum petani penggarap. Meskipun solusi yang diajukan oleh Rousseau jelas adalah sebuah solusi utopis – komunitas petani yang bebas dari eksploitasi dan bebas menentukan proses produksi di antara mereka sendiri – Rousseau merupakan salah satu pemikir pertama yang menyadari persoalan eksploitasi dalam politik dan solusi atasnya. Sebaliknya, Locke, yang seringkali dianggap sebagai pencetus egalitarianisme dan konsep ‘pemerintahan yang terbatas’ (limited government) justru memiliki kecenderungan anti-demokratik. Ide kepemilikan pribadi sebagai hak alamiah (private property as natural rights) justru bersifat ahistoris, karena kepemilikan pribadi sesunguhnya merupakan produk sejarah dan kreasi institusional manusia, dan cenderung memarginalkan sejumlah kelompok masyarakat, seperti perempuan, pekerja, para petani penggarap dalam proses demokrasi yang lebih luas dan popular, atas nama ‘pemerintahan yang terbatas.’ Bab kedelapan atau yang terakhir merupakan ulasan singkat dan afirmasi Wood atas tesis utamanya: bahwa sejarah modernitas melahirkan kapitalisme, sebuah momen sejarah yang memiliki ketegangan yang inheren dengan demokrasi dan menghambat proses demokrasi yang lebih luas dan radikal. Ulasan Kritis Karya Wood kali ini, seperti karyanya yang sebelumnya, patut mendapatkan apresiasi. Pertama, pendekatan historiografi Wood atas pemikiran politik Barat perlu diacungi jempol. Kemampuannya untuk memberikan narasi yang lengkap dan utuh, tanpa terjebak dalam penulisan sejarah yang ‘teleologis’ dalam artinya yang simplistis dan normatif adalah keunggulan pendekatannya. Dalam hal ini, Wood menunjukkan keahliannya sebagai seorang ahli politik yang membahas sejarah sosial dari ide-ide politik. Kedua, Wood juga berhasil menunjukkan bahwa baik faktor ideasional maupun faktor material sama-sama penting dan keduanya sama-sama membentuk proses sejarah. Dari perspektif historiografi Marxis, Wood tentu ingin menunjukkan bagaimana faktor material terutama kontestasi kelas membentuk faktor-faktor ideasional yang mempengaruhi corak pemikiran berbagai filsuf politik di Eropa pada masa awal era modern. Namun, Wood juga tidak abai dengan kekuatan ide dalam menggerakkan aktor-aktor sejarah seperti para tuan tanah dan petani serta implikasi ide-ide tersebut dalam perkembangan sejarah. Dalam hal ini, Wood bisa dikatakan berhasil menyajikan suatu pendekatan sejarah sosial pemikiran politik Barat, suatu historiografi Marxis atas pemikiran politik Barat, tanpa terjebak dalam historisisme, idealisme, voluntarisme naïf, maupun partikularisme yang ahistoris. Ketiga, Wood juga berhasil membongkar mitos akan dua hal: pertama, persepsi populer atas karya-karya pemikiran politik Barat dan kedua, persepsi populer atas konsep-konsep politik modern. Dua persepsi ini cenderung tergelincir dalam pandangan-pandangan yang ahistoris. Pemikiran John Locke dan Montesequieu misalnya, dalam banyak hal justru tidak begitu demokratis karena keberpihakannya atas institusi-institusi serta kolektif-kolektif dan marginalisasinya atas hak-hak invidivual warga negara serta abainya dua pemikir tersebut atas eksploitasi politik, ekonomi, dan sosial. Konsep-konsep politik modern seperti “hak”, “kebebasan”, “rakyat” juga perlu diletakkan dalam konteks historis – apakah kita berbicara kebebasan bagi para pemilik modal dan tanah saja? Apakah kita akan menegasikan hak-hak politik yang bersifat ekstra-parlementer? Kesadaran historis akan konsep-konsep ini perlu dikembalikan dalam diskursus politik kita – satu hal yang berhasil dilakukan oleh Wood. Namun demikian, apresiasi ini tidak menghalangi kita untuk memberikan sejumlah kritik atas karyanya. Pertama, dalam hal metode, meskipun inovatif, metode sejarah sosial atas pemikiran politik Barat dapat membingungkan pembaca dan pengkaji ilmu sosial serta humaniora karena fokusnya yang terbelah: Apakah fokus karya ini ke konteks transisi feodalisme ke kapitalisme? Atau bagaimana ide-ide para filsuf politik berkembang dalam konteks tersebut? Di beberapa bagian, sepertinya penjelasan tentang bagaimana suatu pemikiran politik lahir dalam suatu konteks sosial-politik agak hilang atau kurang jelas. Ini tentu akan menyulitkan pembaca, tidak hanya bagi pembaca pemula, namun juga bagi para pengkaji yang sudah berkecimpung dengan isu-isu seperti ini setelah sekian lama. Kedua, metode ini sesungguhnya dapat dikembangkan lebih jauh lagi, menjadi semacam kajian sejarah komparasi atau sejarah konektif atas sejarah sosial pemikiran politik Barat di konteks Eropa. Bahkan, proyek intelektual ini dapat diteruskan dalam konteks interaksi antara masyarakat Barat dan non-Barat. Metode historiografi Wood yang memberikan porsi yang adil baik terhadap faktor-faktor ideasional maupun material sesungguhnya memiliki potensi untuk melakukan studi yang tersebut di atas. Ketiga, dan yang terakhir, lebih merupakan kritik yang sifatnya teknis. Beberapa penjelasan di dalam buku ini cenderung diulang-ulang, misalnya pembahasan tentang pertarungan antara berbagai klaim kedaulatan oleh berbagai entitas atau implikasi sosial politik dari konsep tentang hukum alam sebagai dalil atas kekuasaan dan kedaulatan. Kemudian, beberapa pemaparan Wood tentang transisi dari feodalisme ke kapitalisme bisa dikatakan tidak ada yang baru, kecuali dalam kaitannya dengan perkembangan pemikiran politik Barat. Kesimpulan Sebagaimana karya Wood yang sebelumnya, dapat dikatakan bahwa karya Wood patut dijadikan rujukan bagi para pengkaji dan penggerak gagasan Kiri dan ilmu sosial serta humaniora pada umumnya. Topik-topik yang dibahas Wood dalam bukunya kali ini juga merupakan topik-topik besar yang perlu dipelajari bagi para ilmuwan dan penggerak sosial, seperti persoalan negara, evolusi konsep kepemilikan pribadi, implikasi sosial politik dari perkembangan sebuah ide, pertautan antara hubungan tuan tanah dan kaum tani dengan ide-ide tentang kewarganegaraan dan proses-proses politik, dan lain sebagainya. Buku ini juga dapat dijadikan sebagai penangkal atas mitos bahwa modernitas, nilai-nilai borjuis, kapitalisme, dan demokrasi adalah hal-hal yang datang dalam satu paket. Buku ini juga mengingatkan kita bahwa ide-ide tidak muncul dari suatu kevakuman sejarah, namun merupakan hasil dari proses sejarah dan material yang membentuknya. ¶ Iqra Anugrah, mahasiswa doktoral ilmu politik di Northern Illinois University, AS. Penulis beredar di twitterland dengan id @libloc Bacaan tambahan: Althusser, L. (1972). Politics and History: Montesquieu, Rousseau, Hegel and Marx. London: New Left Books. McNally, D. (1994). Political Economy and the Rise of Capitalism. Berkeley, CA: University of California Press. Moore, B. (1966). The Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Boston, MA: Beacon Press. Wood, E. M. (1995). Democracy Against Capitalism: Renewing Historical Materialism. Cambridge: Cambridge University Press.