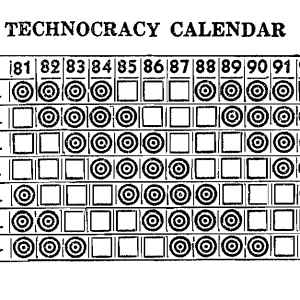Tanggapan dan Tambahan untuk Coen Husain Pontoh
DT TENGAH carut marut dan bobroknya negeri kita, rupa-rupanya ada semacam ‘angin segar’ yang berhembus di kancah politik tanah air. Ya, kita masih berbicara tentang ‘demam’ Jokowi-Ahok akhir-akhir ini yang melanda bukan hanya Jakarta dan sekitarnya tetapi juga seluruh negeri. Kelihatannya, ada semacam usaha menuju perubahan sosial dan politik yang betul-betul transformatif di Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi-Ahok – tapi benarkah? Patutkah kita ragu, apalagi di saat banyak orang begitu yakin dan menaruh harapan pada duet maut ini?
‘Tunggu dulu, jangan senang dulu, jangan-jangan ini cuma sekedar varian dari populisme!’ begitu kata kawan Coen, dalam artikelnya minggu lalu. Tanggapan seperti itu, saya pikir ada benarnya. Karenanya, saya ingin menanggapi dan menambahkan beberapa poin yang saya rasa perlu didiskusikan dalam kaitannya dengan fenomena Jokowi-Ahok dan populisme. Pertama, pada intinya saya menyetujui kritik dari kawan Coen, sekaligus tawarannya tentang Anggaran Partisipatif – yang tentu perlu kita akui merupakan sebuah tawaran yang tidak mudah untuk diwujudkan. Kedua, saya ingin menambal ‘gap’ yang belum ditutupi oleh pemaparan Coen, yaitu bagaimana kita, para warga, atau lebih tepatnya, para massa, musti menanggapi fenomena Jokowi-Ahok ini?
Sesudah Memilih, Sudah Itu Selesai: Sebuah Pertanda ‘Penyakit’ Individualisme Lockean
Adalah naif jikalau kita beranggapan bahwa setelah mengikuti pilkada Jakarta tempo hari lalu berhasil menaikkan Jokowi-Ahok ke kursi kekuasaan maka sim salabim, seluruh persoalan akan segera selesai – tapi, jangan-jangan kita mengidap penyaki seperti itu.
Mungkin observasi ini terlalu pribadi, bisa juga bias, tapi mungkin ada benarnya: di putaran pertama pilkada Jakarta, pasca pencoblosan di pagi hari, sisa hari digunakan oleh warga Jakarta untuk bersantai-santai atau berjalan-jalan. Warga kelas menengah ke atas kemudian membanjiri mall dan pusat perbelanjaan karena libur. Kita tidak menjadi seorang pengkhotbah atau mengajukan sebuah argumen normatif di sini, tetapi ini faktanya.
Dengan kata lain, demokrasi hanya menjadi sebuah ritual kosong, yang direduksi menjadi sebuah ritus tahunan yang bersifat individualistis. Ini mengingatkan saya akan konsepsi Lockean Liberalism di Amerika Serikat. Pada mulanya, Liberalisme Lockean adalah sebuah konsepsi tentang perlindungan kebebasan, yang pada perkembangannya dimanefestasikan oleh dua hal utama: pertama, sistem ekonomi pasar; dan kedua, pemerintahan yang ‘kecil’ dan ‘terbatas’ (limited government). Liberalisme Lockean juga merayakan ‘individualisme,’ saya beri tanda kutip karena individualisme yang dimaksud adalah konsepsi manusia yang bersifat ‘atomistis’ ala kaum Empirisis. Kesimpulan dari pemikiran-pemikiran ini adalah, negara yang ramping, pasar bebas, relasi antar manusia yang seakan-akan hanya bersifat ‘transaksional,’ plus masyarakat yang pasif atas nama stabilitas demokrasi.
Kembali dalam kaitannya dengan fenomena Jokowi-Ahok dan kualitas demokrasi kita, saya mulai curiga, jangan-jangan virus atau wabah individualisme Lockean mulai menyebar tanpa kita sadari di antara kita. Sesudah memilih habis itu selesai, lalu kita lupa pentingnya menjaga dan mengawal jalannya demokrasi. Jangankan memikirkan persoalan-persoalan seperti kesenjangan sosial ekonomi, maraknya kaum preman berjubah, hingga kualitas pendidikan di komunitas lokal kita; jangan-jangan kita sudah mulai enggan menyapa tetangga. Alih-alih semangat komunitarianisme kewargaan ala filsafat Republikanisme atau sikap progresif dalam menanggapi berbagai fenomena politik, kita dihadapka oleh sejumlah persoalan baru.
Pertama, kondisi massa, terutama rakyat dari latar belakang sosio-ekonomi yang termarginalkan. Senada dengan kritik Coen, saya khawatir: jangan sampai rakyat kita terjebak oleh Messianisme atau Ratu-Adil-isme dalam melihat Jokowi dan Ahok. Sosok pemimpin, terutama dengan kharisma, terkadang memang tetap perlu, bahkan di zaman modern seperti ini, tetapi jikalau berlebihan, ini hanya akan berujung pada kultus individu dan personalisasi potensi transformasi sosial dari massa. Tentu saya tidak berbicara mengenai kultus individu ala Suharto atau rejim otoriter dan totaliter lainnya, tetapi kultus individu, bahkan dalam bentuknya yang paling kecil, dapat pelan-pelan mengikis daya kritik dan praxis kita. Menjadi terpana, atau gumun dalam istilah Jawanya, tentu bukan pilihan bagi gerakan.
Kedua, adalah kebiasaan kritik ‘pepesan kosong’ ala kelas menengah Jakarta (yang dengan jujur musti saya akui bahwa saya adalah bagian di dalamnya, suka atau tidak suka). Sekedar mengritik keadaan sembari duduk-duduk di pusat perbelanjaan atau gerai kopi terkemuka di ibu kota tentu tidak akan mengubah keadaan – meskipun banyak yang merasa dengan melakukan itu mereka sudah mengubah keadaan.
Kedua hal ini, bisa berujung ke dua masalah yang serius, yaitu ketergantungan massa atau rakyat akan sosok atau figur pemimpin dan kepasifan atau sikap acuh tak acuh atas proses politik. Riset-riset dalam tradisi behavioralis dalam ilmu politik memang mengatakan bahwa dua hal ini ‘berpengaruh positif’ bagi ‘stabilitas demokrasi.’ Tetapi, tentu ini bukan jawaban yang memuaskan, apalagi dari perspektif progresif-kritis. Mengamini jawaban tersebut berarti mengamini bahwa kita musti ‘taking politics out of politics,’ mencabut elan partisipatoris dan radikal dari proses politik itu sendiri. Bila demokrasi hanya menjadi persoalan kampanye dan memilih kandidat A atau B lalu beres, maka itu laksana berbelanja di pasar atau toko: ada pilihan, tapi hanya yang itu-itu saja. Untuk membawa kembali politik ke dalam ranahnya yang betul-betul demokratis, partisipatoris, dan deliberatif, maka rakyat yang sadar akan hak-hak dan potensinya dan berkomitmen melakukan transformasi sosial menjadi suatu keniscayaan.
Menghindari Jebakan Populisme
Untuk Jokowi-Ahok, tantangan dan tugas terberat tentunya adalah menghindari jebakan kekuasan yang teknokratis dan populis dan mewujudkan kekuasaan yang merakyat dan transformatif. Yang ingin saya tekankan adalah tantangan dan tugas kita, bukan hanya sebagai bagian dari gerakan progresif, tetapi juga bagian dari massa rakyat, yaitu untuk membangun dan mempraktekkan demokrasi yang liberatif dan partisipatoris sedini mungkin, sekecil mungkin.
Pendidikan menjadi kunci. Ini penting, meskipun memang bukan hal yang seksi. Hanya dengan saling belajar, kita bisa ‘meruqyah’ atau mengusir hantu kegumunan, tendensi Messianik, dan sikap acuh tak acuh. Jangan lupa, seperti kata Paulo Freire, kita juga musti waspada akan kecenderungan otoriter dari tiap-tiap kita, yang mungkin bersemayam di dalam orang yang mengaku paling egaliter sekalipun.
‘Obat’ lain lagi yang bisa jadi mujarab adalah, meminjam slogan seorang ulama terkenal, yaitu memulai dari hal yang kecil, saat ini, dan dari diri sendiri. Kita bisa memulai dari membangun dan merawat suatu hal yang klise yaitu modal sosial (social capital) dengan cara-cara sederhana, seperti menjadi warga yang peduli dengan tetangga dan aktif dalam komunitas lokal – suatu hal yang mungkin juga semakin jarang di daerah perkotaan akhir-akhir ini. Untuk mewujudkan demokrasi dan transformasi sosial yang betul-betul partisipatoris, terkadang kita tidak perlu memulai dari hal-hal yang besar, atau gugusan istilah-istilah yang rumit, meringkus perlawanan hanya sekedar kata, kata, dan kata atau keren-kerenan belaka.
Ini memang tidak mudah, tetapi tidak ada perjuangan yang mudah. Skenario terburuk, jikalau Jokowi-Ahok tidak bisa menghindari jebakan populis yang teknokratis, minimal kita sebagai rakyat yang sadar bisa mengantisipasi persoalan tersebut, tanpa perlu menjadi anak ayam yang kehilangan induknya. Karena politik emansipasi dan realisasi aspirasi dari tiap-tiap individual menjadi mungkin apabila kita sebagai masyarakat ‘berlatih’ demokrasi sejati (partisipatif dan liberatif) sedini mungkin.***
Iqra Anugrah, mahasiswa doktoral ilmu politik di Northern Illinois University