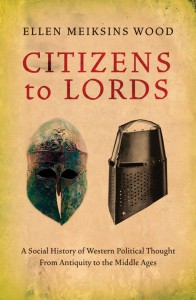Judul Buku: Citizens to Lords: A Social History of Western Political Thought from Antiquity to the Late Middle Ages
Pengarang: Ellen Meiksins Wood
Penerbit: Verso, London/New York, 2008
Tebal: ix + 245 h.
Membedah Pemikiran Politik Barat Melalui Sejarah Sosial
USAHA untuk membahas dasar-dasar pemikiran politik Barat, merupakan hal yang jarang dilakukan. Di tanah air, terdapat kecenderungan untuk ‘melupakan’ kanon-kanon teori politik klasik, apalagi membahas konteks sejarah dari pemikiran tersebut. Cap ‘kuno’ atau ‘tidak relevan’ sering menjadi alasan mengapa tidak banyak dari kita – pengkaji ilmu sosial dan filsafat, serta aktivis gerakan sosial – mau menekuni kajian pemikiran politik klasik Barat secara serius.
Di tengah-tengah kelangkaan kajian serius tentang filsafat politik klasik Barat, ahli ilmu politik Marxis terkemuka, Ellen Meiksins Wood, berusaha memberikan sebuah narasi lengkap tentang sejarah pemikiran politik. Yang menarik dari Wood, ia tidak hanya sekedar menarasikan sejarah intelektual atau history of ideas, melainkan berusaha membahas pemikiran politik Barat melalui pendekatan sejarah sosial (The Social History of Political Theory). Yang dimaksud dengan pendekatan sejarah sosial di sini adalah usaha untuk menempatkan para pemikir politik Barat klasik sebagai subyek yang terus-menerus berinteraksi dengan konteks politik, ekonomi dan sosial masyarakatnya, yang tertuang dalam pemikiran mereka. Oleh karena itu, selain membedah inti-inti gagasan para pemikir politik Barat klasik, Wood juga membahas latar belakang sosial mereka dan interaksinya dengan masyarakat dan kekuasaan pada masa itu – dari zaman Yunani Kuno hingga Abad Pertengahan.
Thesis utama Wood cukup jelas dan gamblang, yaitu sejarah pemikiran politik Barat dari zaman Yunani Kuno hingga Abad Pertengahan, didominasi oleh dua ketegangan: pertama, ketegangan antara kelas yang menguasai kepemilikan aset terutama tanah vis-à-vis demos – yaitu rakyat banyak yang rata-rata berprofesi sebagai petani penggarap; dan kedua, bagaimana menjustifikasi kekuasaan negara yang absolutis plus ketimpangan politik, ekonomi, sosial dan legal yang dilembagakan berdasarkan dalil ‘kesetaraan manusia’ menurut hukum alam (natural law). Ketegangan inilah yang menjadi pembahasan utama dalam buku Wood.
Dari Masa Yunani Kuno hingga Abad Pertengahan
Wood membagi bukunya dalam empat bab pembahasan: bab pertama tentang pendekatan sejarah sosial dalam filsafat politik, bab kedua hingga keempat masing-masing membahas tentang sejarah pemikiran politik mulai dari masa Yunani Kuno, Imperium Romawi, hingga Abad Pertengahan menjelang modernitas. Di bagian kesimpulan, Wood kemudian memaparkan dan menegaskan kembali argumennya tentang ketegangan dalam pemikiran politik Barat klasik dan implikasinya terhadap pemikiran politik Barat modern dan kontemporer.
Di bab pertama, Wood memberikan justifikasi tentang pentingnya memahami filsafat politik Barat dalam perspektif sejarah sosial. Metode penulisan Wood sesungguhnya merupakan gebrakan dalam penulisan sejarah filsafat politik Barat. Di Amerika Serikat, misalnya, pendekatan keilmuan dalam kajian filsafat politik di berbagai departemen ilmu politik cenderung dipengaruhi oleh pendekatan Straussian ala Leo Strauss. Menurut Leo Strauss, mengkaji filsafat dan teori politik berarti sekedar mengkaji pemikiran para pemikir besar politik Barat dengan cara membaca kanon-kanon pemikiran politik terkemuka tanpa berusaha untuk mengaitkannya dengan konteks sosio-historis pemikiran tersebut, atas nama ‘objektivitas ilmu pengetahuan’ dan karenanya memperjuangkan ‘anti-historisisme’ atau menghindari pembahasan konteks sosio-historis dalam mengkaji pemikiran politik Barat. Akibatnya, ide-ide pemikiran politik dibahas hanya secara normatif, seakan-akan muncul dengan sendirinya, dan karenanya bisa terjebak dalam solipsismenya sendiri. Di dalam ranah ilmu politik yang lebih ‘empirisis,’ pendekatan Straussian ini juga semakin melanggengkan hegemoni positivisme dalam ilmu politik, atas nama sains yang ‘objektif’ dan ‘bebas nilai dan kepentingan’ – suatu fenomena, yang sayangnya, sangat dominan dalam diskursus ilmu politik kita di tanah air.
Wood mengritik keras pendekatan semacam ini. Menurutnya, ide-ide filsafat politik Barat bukanlah gagasan yang muncul dalam konteks yang vakum, melainkan selalu berinteraksi dengan kenyataan sosial disekelilingnya. Konteks sosial inilah yang juga mempengaruhi bangunan argumentasi para filsuf politik Barat. Wood juga mengritik pendekatan dominan sejarah pemikiran politik Barat, yang selain terlalu menekankan pada aspek ide semata, juga cenderung abai terhadap berbagai proses sosial dan upaya berbagai elemen masyarakat, terutama mereka yang termarginalkan, seperti petani, perempuan, dan rakyat kebanyakan lainnya, dan karenanya, justru menjadi ahistoris. Selain memberikan konteks historis dari pemikiran politik Barat, pendekatan Wood juga bertujuan untuk menuliskan ‘history from below’ atau ‘sejarah dari bawah,’ yaitu sejarah filsafat politik dari kacamata rakyat biasa, terutama kaum petani penggarap.
Di dalam konteks inilah, Wood membuat gebrakan dan kritik tajam atas penulisan sejarah filsafat politik Barat, yang sekali lagi, cenderung menulis sejarah pemikiran politik dalam konteks yang vakum, ahistoris, atas nama ‘anti-historis.’
Berdasarkan perspektif inilah, Wood kemudian menganalisis secara cermat bagaimana ketegangan-ketegangan tersebut sudah ada dari masa awal perkembangan polis atau negara-kota di zaman Yunani Kuno dan masa awal perkembangan Imperium Romawi. Di masa Yunani Kuno, komunitas politik merupakan domain di luar negara, yang diwarnai bukan oleh interaksi antara penguasa dan rakyat jelata (rulers and subjects) tetapi merupakan hubungan yang setara antara warga negara (citizens). Namun demikian, pola relasi politik ini mengesampingkan pola relasi produksi antara para tuan tanah (appropriators, landlords) dan para produsen yaitu warga negara, yang rata-rata berprofesi sebagai petani penggarap (peasant-citizens). Pola relasi produksi antara tuan tanah dan petani penggarap inilah yang mewarnai ketegangan utama dalam pemikiran politik Barat. Tiap-tiap era menanggapinya dengan reaksi yang berbeda. Yunani Kuno menanggapinya dengan institusi demokrasi yang memungkinkan tuan tanah dan rakyat petani berkonfrontasi secara beradab dalam ranah politik sebagai warga negara yang setara. Imperium Romawi menempuh jalan yang jauh berbeda: berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam artian memberikan manusia hak sesuai kebijaksanaan dan kemampuannya, negara justru semakin memperkuat hierarkhi antara tuan tanah dan segenap penguasa lainnya (birokrat, pejabat negara dan militer) sebagai kelas yang berkuasa versus para rakyat petani melalui status hukum yang didasarkan atas status kepemilikan properti. Abad Pertengahan kemudian menjadi saksi di mana gereja dan negara menjadi semakin tidak berkuasa di hadapan kelas yang menguasai kepemilikan pribadi yang semakin menggerogoti kedaulatan negara.
Di Bab kedua, Wood berfokus kepada para pemikir politik Yunani terkemuka pada zamannya, yaitu Sokrates, Plato, Aristoteles, dan kaum Sofis, terutama Protagoras. Wood memulai pembahasannya dari kemajuan demokrasi di polis-polis Yunani yang dipelopori oleh Solon, sang reformer demokrasi di Athena. Yang dimaksud dengan ‘demokrasi’ di sini bukanlah demokrasi elektoral semata seperti yang sering menjadi penyakit di masa modern sekarang, tapi merupakan arena kontestasi politik di mana warga-petani (peasant-citizen) bisa memperjuangkan hak-haknya dalam polis. Pengaruh aristokrasi dan para penyokong oligarki memang masih ada, tetapi itu semua diimbangi oleh kekuatan politik para warga-petani. Memang, demokrasi Athena tidaklah sempurna. Dalam hal kebijakan luar negeri misalnya, Athena menerapkan kebijakan luar negeri yang justru ekpansionis, seperti digambarkan oleh Thukidedes, sejarawan Yunani, dalam karyanya Sejarah Perang Peloponnesos (History of the Peloponnesian War). Tetapi, demokrasi Athena dalam banyak hal merupakan kemenangan sejarah bagi kaum petani dan warga biasa.
Sejarah pemikiran politik Yunani Kuno, yang dimotori oleh filsuf-filsuf seperti Sokrates, Plato dan Aristoteles, sangat berkaitan dengan konteks ini. Pemikiran-pemikiran Sokrates, Plato dan Aristoteles dibangun berdasarkan interaksi dan refleksi mereka dengan kondisi sosial di sekitarnya. Yang menarik adalah, Wood lantas tidak berhenti di titik ini, melainkan bergerak lebih jauh lagi dengan menyodorkan sebuah argumen: Plato dan Aristoteles, yang memiliki latar belakang sebagai para pemikir yang dekat dengan kekuasaan dan golongan elit di Athena, sesungguhnya menawarkan pemikiran politik yang skeptis dengan kemampuan massa, yaitu petani dan warga biasa, untuk memerintah, jikalau tidak anti-demokrasi sama sekali. Terlepas dari berbagai perbedaan dari posisi filosofis para tiga filsuf tersebut, mereka semua mendasarkan filsafat politiknya dari argumen yang sama: bahwa terdapat perbedaan yang inheren dalam sifat dasar manusia (human nature), yang menjustifikasi perbedaan peranan dalam bentuk ketidaksetaraan (inequality) dalam kehidupan publik. Seorang budak atau petani, yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan menggarap tanah, tidak memiliki kemampuan untuk memikirkan persoalan publik dibandingkan dengan seorang aristokrat terdidik yang memiliki kemampuan dan waktu luang untuk memikirkan politik, dan karenanya, penegasan hierarkhi antara penguasa dan yang diperintah menjadi lebih baik untuk keduanya.
Yang menarik, para pembela demokrasi Athena dan kemampuan kelas petani dan produsen lainnya dalam memerintah dirinya sendiri justru adalah kaum Sofis, terutama Protagoras. Berbeda dengan para filsuf Yunani yang menekankan pada aspek hierarkhi alamiah (order), Protagoras justru berargumen tentang kesetaraan alamiah (equality) yang juga tercermin dalam praktek politik dan kehidupan publik, dalam bentuk demokrasi. Berdasarkan kesetaraan inilah, maka demokrasi Athena perlu menjadi instumen politik bagi kaum tani dan rakyat jelata dalam memperjuangkan haknya melawan dominasi para aristokrat dan oligark.
Di bab ketiga, Wood menjelaskan transisi dari kemunduran polis-polis Yunani ke kejayaan Imperium Romawi. Perubahan besar-besaran ini juga mempengaruhi corak filsafat politik yang berkembang di masa Romawi. Tantangan terbesar bagi filsafat politik dan politik itu sendiri di masa imperium Romawi adalah bagaiamana menjustifikasi pemerintahan yang absolutis dan imperium yang ekspansionis berdasarkan konsep kesetaraan manusia dan kosmopolitanisme yang menjadi tradisi filsafat dan politik Yunani. Persoalan ini menjadi semakin kompleks dengan semakin menguatnya legislasi yang melindungi kepemilikan properti pribadi dan munculnya gereja sebagai kekuatan baru, baik di bidang pemikiran, politik, maupun properti atau ekonomi.
Perubahan ini bermula dari mundurnya komunitas polis, bergeser menjadi imperium yang kosmopolis, meliputi dan memerintah berbagai jenis suku bangsa dan golongan masyarakat, di bawah pimpinan raja sebagai hukum yang hidup atau the living law. Mulai dari masa ini, pemikiran Yunani yang menjadi tren dan mewarnai pemikiran politik di era Romawi adalah Stoikisme yang dipelopori oleh Zeno dari Citium. Filsafat Stoikisme melahirkan berbagai macam konsep, tetapi konsep yang paling mempengaruhi corak filsafat politik di masa Romawi adalah konsep kesatuan antara akal pikiran (mind) dan badan atau aspek-aspek badaniah dari manusia (body), yang disebut dengan istilah logos, yang juga sering diterjemahkan sebagai ‘nalar universal.’ Konsepsi ini jelas berbeda dengan dualisme antara badan dan pikiran yang dirumuskan oleh Plato, yang konsekuensinya adalah justifikasi untuk hierarkhi yang tegas antara penguasa dan yang diperintah. Sepintas, pemikiran politik Stoik akan menguatkan tradisi demokratis a la Athena, tapi pada perkembangannya, filsafat Stoik mengalami evolusi konsep yang kelak dipakai untuk menjustifikasi kekuasaan yang absolut. Modifikasi atas Stoikisme dapat dilihat pada pemikiran Cicero, seorang negarawan Romawi kuno, dan Agustinus dari Hippo, seorang santo dan filsuf gereja di masa Romawi.
Cicero, yang menggunakan dalil Stoik tentang logos, pertama-tama bersentuhan dengan argumen kaum Stoik dari kacamata Plato. Dengan kata lain, Stoikisme Cicero sejatinya berbau Platonis, karena Cicero membaca Stoikisme melalui kritik tentangnya. Thesis utama dari pemikiran politik Cicero adalah pengakuan atas kemampuan akal budi manusia, kesetaraan dalam dimensi moral bagi seluruh manusia, penegakkan hukum dan perlindungan atas kepemilikan pribadi. Menariknya, berdasarkan atas prinsi-prinsip tersebut, Cicero melakukan pembelaan atas ketidaksetaraan dan hierarkhi sosial antara penguasa dan rakyat jelata, terutama kaum tani, yang dilembagakan melalui kedaulatan yang absolut dan sistem hukum, berdasarkan prinsip keadilan. Menurut Cicero, meskipun semua manusia setara dan memiliki kapasitas yang sama dalam menggunakan akal budinya dan memerintah, manusia juga memiliki potensi untuk mengabaikan akal budinya dan terjatuh dalam jurang kesalahan. Oleh karena itu, kekuasaan negara yang mutlak, jikalau tidak absolutis atau otoriter, dalam istilah yang lebih modern, diperlukan untuk menjaga manusia dari kecenderungannya untuk melakukan kesalahan. Kemudian, definisi keadilan Cicero berbeda dengan definisi keadilan ala masyarakat polis Yunani, yang menekankan pada kesetaraan kemampuan manusia, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonominya, dalam merumuskan kebijakan publik dan memerintah. Keadilan, menurut Cicero, adalah memberikan manusia tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Tidaklah adil, bagi Cicero, untuk memberikan bobot yang sama dalam kebijakan pemerintahan bagi manusia yang memiliki kemampuan terbaik dan mereka yang memiliki kemampuan terburuk, karena negara terbaik adalah negara yang dipimpin oleh para warga negara yang terbaik – kaum aristokrat, tuan tanah, dan oligark.
Santo Agustinus dari Hippo, yang menjadi salah satu pemikir Gereja terkemuka di era naiknya agama Kristen di Imperium Romawi, juga memiliki pemikiran serupa, yang digunakan sebagai dalil bagi pihak Gereja untuk mendukung sekaligus mengambil keuntungan dari semakin besarnya kekuasaan negara dan semakin terpinggirnya peranan para warga-petani. Agustinus, yang terkenal dengan karya utamanya Kota Tuhan (The City of God), berada di tengah-tengah dilema antara otoritas Gereja dan negara. Agustinus ingin meyakinkan bahwa KeKristenan bukanlah musuh para elit negara, dan sebalikya, Gereja tidak perlu takut dengan otoritas negara, sekalipun negara dipimpin oleh para elit yang sama sekali tidak Kristiani. Salah satu ide Agustinus untuk menjembatani ketegangan ini, sekaligus semakin menegaskan dukungannya untuk legitimasi negara yang mutlak, adalah doktrin tentang ‘dosa asal’ (original sin). Doktrin ini mengatakan,sekalipun manusia memiliki potensi untuk mengaktualisasikan potensi akal budinya untuk menjadi bijak, namun manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa dan menjauhi perintah Tuhan. Untuk itu, manusia, terutama umat Kristen, perlu mengikuti gereja sebagai otoritas spiritual demi menggapai kemenangan di bumi dan di hari akhir. Tetapi, institusi gereja memiliki keterbatasan dalam menegaskan kedaulatan temporal, kedaulatannya di bumi. Oleh karena itu, kedaulatan di bumi harus diserahkan kepada institusi negara, sekalipun negara tersebut sangat Pagan dan anti-Kristen, untuk menjaga manusia dari kecenderungannya untuk berdosa di bumi.

Perlu diingat bahwa baik pemikiran Cicero maupun Santo Agustinus merupakan reaksi atas munculnya tipe pemerintahan baru di masyarakat pada saat itu, yakni kekaisaran atau imperium yang bersifat ekspansif. Menariknya, pengalaman Imperium Romawi menunjukkan bahwa untuk semakin menguatkan otoritas dan jangkauan kekuasaannya, negara harus memperkuat rezim kepemilikan pribadi atas properti, terutama tanah, bagi para tuan tanah, pejabat publik, dan militer. Kedaulatan negara dan perluasan kekaisaran berkaitan erat dengan kekuatan para penguasa dan perlindungan atas rezim kepemilikan pribadi. Munculnya agama Kristen juga tidak terlepas dari konteks ini, yang akhirnya membuat Gereja harus mengambil suatu solusi yang bertujuan untuk melindungi penyebaran agama Kristen dan otoritas Gereja, yaitu mendukung rejim negara dan kepemilikan pribadi. Lagi-lagi, semua ini terjadi dengan mengorbankan hak-hak dan kontribusi produksi para warga, petani, dan budak.
Bab keempat menjelaskan tentang Abad Pertengahan dan transisi dari imperium Romawi ke feodalisme. Meskipun banyak sejarawan dan cendekiawan yang berfokus pada perubahan dan keterputusan sejarah antara era Romawi dan Abad Pertengahan, Wood justru menggarisbawahi kesinambungan (continuity) antara era Romawi dan Abad Pertengahan, terutama dari kacamata para petani yang semakin termarginalkan. Kesinambungan sejarah ini dapat terlihat pada hubungan yang makin pelik antara negara, Gereja dan kepemilikan pribadi dan batasan-batasan antara ruang sipil dan politik (civic and political spheres) versus ranah hukum (legality), yang menjadi fokus pembahasan para filsuf politik di masa itu, mulai dari Thomas Aquinas, John dari Paris, Marsilius dari Padua, William dari Ockham dan para filsuf Muslim klasik seperti Ibn Rushd (Averroes). Tantangan utama pada masa Abad Pertengahan adalah menyusutnya kedaulatan mutlak negara di hadapan menguatnya rejim kepemilikan properti yang memberikan posisi tawar yang lebih besar kepada para tuan tanah, yang berujung kepada dilema antara otoritas untuk menjalankan pemerintahan versus kekuatan kepemilikan pribadi.
Terlepas dari berbagai perbedaan di tingkat varian pemikiran yang berkaitan dengan konteks di negara masing-masing, para filsuf politik Eropa di Abad Pertengahan yang menghadapi dilema antara negara atau akumulasi tanah dan kapital, memilih ‘jalan tengah’ dengan mendukung status quo, yaitu pembelaan atas kekuasaan negara sekaligus rejim kepemilikan pribadi. Aquinas, misalnya, melakukan pembelaan atas kekuasaan negara yang temporal atau sekuler dan kekuasaan spiritual Gereja yang berdasarkan konsep hukum alam (natural law). Konsep ini berbeda, misalnya, dengan konsep Ibn Rushd yang meniadakan dikotomi antara agama dan filsafat sebagai jalan menuju Kebenaran, yang berimplikasi pada struktur politik yang lebih fleksibel di dunia Islam dibandingkan Eropa di Abad Pertengahan pada saat itu. Marsilius dari Padua, juga membela usaha negara untuk mengembalikan kedaulatannya sekaligus menguatnya kekuasan para tuan tanah berdasarkan dalil bahwa negara dan kekuasaan tuan tanah merupakan representasi dari ‘perkumpulan warga’ (the corporation of citizens). Sedangkan William dari Ockham berpendapat bahwa otoritas negara, Gereja dan kepemilikan pribadi merupakan gambaran dari kehendak-kehendak individu bebas dan perkumpulan warga di dalam masyarakat.
Terakhir, dalam kesimpulannya, Wood kembali menegaskan argumennya tentang ketegangan utama dalam filsafat politik Barat menurut analisis sejarah sosialnya: kesenjangan antara kelas yang menguasai aset, terutama tanah dan kelas produsen, terutama petani penggarap, yang dilembagakan oleh negara, gereja, dan hukum, berdasarkan dalil filosofis tentang kesetaraan manusia. Paradoks inilah, menurut Wood, yang mewarnai pemikiran politik Barat pasca-Abad Pertengahan dan seterusnya, termasuk derivasi modernnya yaitu ide tentang ‘demokrasi’ yang ditautkan dengan pemerintahan yang terbatas dan kepemilikan pribadi (limited government and private property).
Ulasan Kritis
Karya Wood patut diapresiasi sebagai sebuah upaya untuk membaca sejarah pemikiran politik Barat secara baru, yaitu melalui pendekatan sejarah sosial dan analisa Marxis – suatu hal yang jarang dilakukan ketika mempelajari sejarah pemikiran Barat. Namun demikian, setidaknya ada dua hal yang perlu menjadi perhatian sekaligus kritik untuk karya Wood.
Pertama, sebagaimana layaknya berbagai bentuk pemikiran, perlu ditegaskan bahwa filsafat politik dapat diinterpretasikan seluas-luasnya dalam berbagai cara. Dengan kata lain, dalam membaca karya Wood, kita tetap harus berhati-hati dalam menarik kesimpulan mengenai corak pemikiran politik Barat dari masa Yunani Kuno hingga Abad Pertengahan. Poin ini juga ditegaskan oleh Wood sendiri, yang menyebutkan bahwa analisis sejarah sosialnya tidak serta merta berpendapat bahwa seluruh bangunan pemikiran para filsuf politik Barat yang dikupas dalam buku Wood secara inheren anti-demokratik. Yang ditekankan oleh Wood adalah, ada elemen-elemen dari pemikiran Plato hingga Aquinas yang memang anti-demokratik, yang juga merupakan produk dari konteks sosial dan sejarah pada masa itu. Sebagai sebuah pemikiran, tentu saja pemikiran para filsuf Klasik tetap terbuka terhadap berbagai penafsiran. Yang ditekankan di sini adalah aspek keberkaitan antara pemikiran dan konteks sejarah sosialnya.
Kedua, Wood sudah mengerjakan tugasnya dengan baik dengan menyebutkan pengaruh masyarakat non-Barat atau yang liyan (the other) dalam pemikiran politik Barat, seperti pengaruh Ibn Rushd terhadap pemikiran Thomas Aquinas dalam mengkaji teks-teks politik Aristotelian.[1]
Namun, porsi yang diberikan dalam pembahasan Wood masih terbatas dan dapat dibilang kurang ekstensif. Tentu saja ini dapat dimaklumi karena memang fokus pembahasan Wood adalah sejarah pemikiran politik Barat. Namun, alangkah baiknya apabila porsi pembahasan tentang pengaruh pemikiran non-Barat terhadap filsafat politik Barat dapat ditambah – satu hal yang mungkin menjadi tugas kita di kalangan penggiat kajian dan gerakan Kiri untuk membahas persoalan serupa dalam konteks masyarakat kita.
Kesimpulan
Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa buku Wood merupakan terobosan baik dalam hal kajian pemikiran politik, sejarah sosial, dan analisa Marxis dalam ilmu-ilmu sosial. Tidak banyak ilmuwan politik maupun sejarawan yang berupaya melakukan analisis yang sifatnya sintesis dan eklektik dari berbagai disiplin ilmu. Dalam hal ini, karya Wood patut diapresiasi.
Dalam hal kajian keilmuan dan pengembangan gerakan, buku ini juga menjadi pengingat bagi para pengkaji dan penggerak gagasan Kiri maupun ilmu sosial dan humaniora pada umumnya, untuk kembali mempelajari ‘kitab-kitab’ atau kanon klasik pemikiran politik Barat secara serius, tanpa terjebak oleh label ‘kuno’ atau ‘sudah tidak relevan.’ Kita perlu membangkitkan budaya belajar teks-teks pemikiran politik secara serius, terutama sekali untuk mengerti situasi hari ini secara lebih komprehensif. Dan buku Wood adalah sebuah bacaan pengantar yang sangat berguna.
¶
Iqra Anugrah, mahasiswa doktoral ilmu politik di Northern Illinois University, AS. Penulis beredar di Twitterland dengan id@libloc
Bacaan Tambahan
Lefebvre, G. (1947). The Coming of the French Revolution. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Macpherson, C. B. (1962).The Political Theory of Possesive Individualism. Oxford: Oxford University Press.
Needham, J. (1954). Science and Civilisation in China. Cambridge: Cambridge University Press.
Skinner, Q. (1978). The Foundations of Modern Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press.
Wilson, S. (1962). Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought. Princeton, NJ: Princeton University Press.
[1] Salah satu contoh karya yang paling ekstensif mengulas tentang pengaruh pemikiran peradaban non-Barat terhadap peradaban Barat adalah Science and Civilisation in China karya Joseph Needham, sejarawan asal Inggris, yang terbit dalam 27 buku, selama 1954-2008, tentang sains dan teknologi di peradaban China.