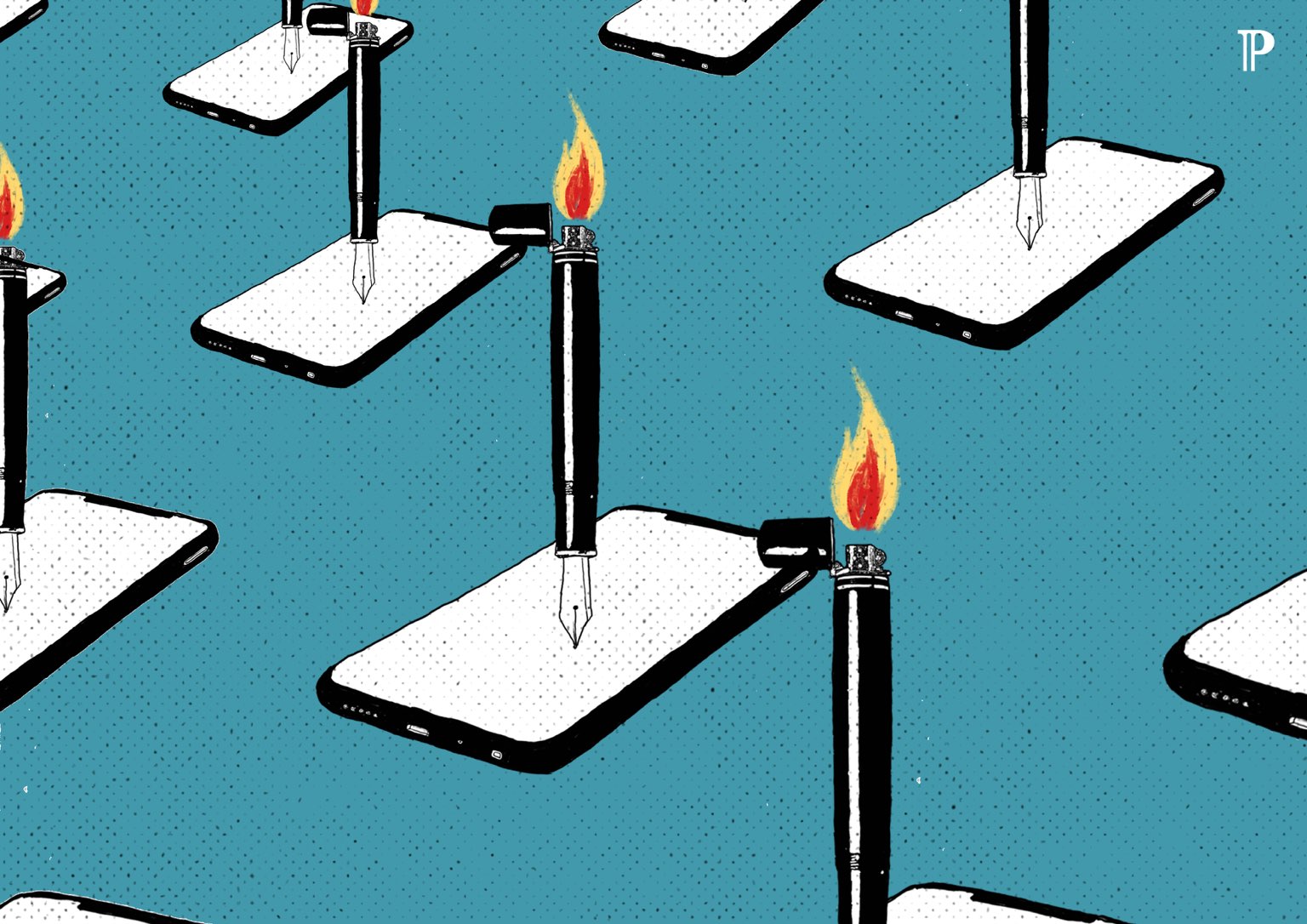Ilustrasi: Illustruth
“BU, KENAPA hutan masih saja habis padahal kami sudah sekolah?”
Pertanyaan anak-anak Orang Rimba kepada gurunya tersebut, seperti diceritakan Butet Manurung dalam buku Sokola Rimba (2015), kembali mengingatkan saya pada nasib pendidikan masyarakat adat. Pada tahun ajaran sekarang, sebagian besar sekolah di Indonesia akan melaksanakan kurikulum baru. Setidaknya kelas 1, 4, dan 7 akan mulai menggunakan Kurikulum Merdeka.
Lalu bagaimana dengan sekolah yang ada di wilayah masyarakat adat? Apakah juga akan menggunakan kurikulum tersebut begitu saja–seperti pada Kurikulum 2006 (KTSP) dan Kurikulum 2013 (K-13)–lengkap dengan buku pelajarannya, atau mandiri sesuai konteks bahasa, budaya, dan lingkungan, serta merespons kebutuhan atau permasalah yang sedang dihadapi?
Meskipun saat ini angka partisipasi sekolah di Indonesia sudah mencapai hampir 100 persen, namun masih banyak anak-anak SMP, khususnya di perdesaan, yang masih terbata atau belum bisa sama sekali membaca. “Kalau nilainya belum mencapai KKM, kami berikan remedial sampai nilainya mencukupi,” begitu umumnya jawaban guru ketika ditanya bagaimana mungkin anak yang belum lancar membaca bisa masuk SMP.
Saya juga banyak menemukan anak yang merasa minder dengan kampungnya; dengan identitas kulturalnya. Bahkan masyarakat umum di tempat saya bekerja, Sumba Barat dan Lombok Utara, juga kerap kali merasa lebih rendah dibandingkan orang Jawa yang dianggap lebih berpendidikan.
Situasi kian rumit karena diskusi tentang sekolah adat masih belum selesai di tingkat pusat, dalam hal ini Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada kesan bahwa sekolah adat adalah entitas yang berbeda dan bahkan tidak setara dengan sekolah formal. Oleh karena itu, anak-anak dari masyarakat adat harus menghabiskan waktu belajar di dua tempat.
Apakah masyarakat adat memang harus duduk di dua sekolah untuk berpendidikan? Jika demikian, kapan mereka dapat mengaktualisasikan diri dalam kehidupan? Orang tua juga menjadi serba salah. Jika tidak menyekolahkan anak ke sekolah formal, mereka akan dianggap melanggar hak anak untuk memperoleh pendidikan.
Pertanyaan lain yang juga krusial: apakah sekolah formal saat ini sudah menjawab kebutuhan masyarakat adat?
Sebelum menjawab hal tersebut, tentu harus diperjelas terlebih dulu apa itu masyarakat adat. Menurut PBB, masyarakat adat adalah pewaris dan praktisi dari budaya dan cara-cara unik dalam hubungan antara masyarakat dan lingkungan. Orang-orang adat mempertahankan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda dari masyarakat dominan di mana mereka tinggal.
Menurut World Bank (2022), meski jumlah masyarakat adat hanya 6 persen dari total populasi manusia saat ini, tetapi mereka tersebar di wilayah yang sangat luas luas, yaitu setara 25 persen teritori bumi. Mereka juga mengelola hingga 80 persen biodiversitas di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, mengutip Katadata, per 2020 lalu 57 juta dari 111,5 juta hektare hutan adalah wilayah masyarakat adat. Angkanya bisa jadi lebih karena faktanya masih banyak wilayah adat yang belum dipetakan.
Perubahan pada masyarakat adat, dengan demikian, akan mempengaruhi baik secara langsung atau tidak terhadap 25 persen wajah bumi, termasuk lebih dari setengah luasan hutan dan kekayaan biodiversitas Indonesia.
Dengan latar belakang tersebut, membicarakan pendidikan masyarakat adat semestinya menjadi sangat krusial bagi Indonesia.
Paradigma
Diskusi mengenai pendidikan masyarakat adat harus dimulai dari titik pijak yang tepat, yaitu cara pandang terhadap masyarakat adat itu sendiri–dengan berbagai aspek kehidupan mereka termasuk pengetahuan, keterampilan hidup, serta masalahnya.
Narasi pembangunan yang linear ala Walt Whitman Rostow (1959) memandang masyarakat adat yang hidup tradisional merupakan kelompok yang berada di urutan paling belakang dalam tahap pembangunan ekonomi. Pengetahuan mereka dianggap sebagai pengetahuan kuno, tertinggal, atau sekadar artefak masa lampau.
Mengikuti logika tersebut, maka masyarakat adat sudah seharusnya diseret untuk dapat maju; menjadi modern.
Pendidikan yang dirancang dengan cara pandang tersebut menjadi berbahaya karena bias urban, mendukung konsumsi massa yang tinggi, dan sangat industrialis. Apa yang dipelajari adalah subjek-subjek yang dianggap memiliki nilai ekonomi pada masyarakat industrialis berkonsumsi tinggi. Sistem pendidikan, sebagaimana industri, membutuhkan pabrikasi.
Dalam skema ini, pengetahuan adat yang tidak ada standar industrinya hanya akan menjadi dekorasi atau bersifat tambahan, tidak signifikan, apalagi wajib. Ini terlihat dari bagaimana sekolah adat lebih banyak bersifat informal atau sekadar tambahan seperti muatan lokal dengan jumlah waktu tidak sampai 20 persen dari total jam belajar di sekolah formal.
Dampak paling signifikan dari paradigma pendidikan seperti ini bagi anak-anak masyarakat adat adalah mereka harus menanggalkan atribut tradisinya–yang tidak sesuai standar pabrikasi tersebut–agar dapat disebut sebagai orang berpendidikan dan mampu masuk ke industri.
Sebaliknya, jika dilihat lewat narasi pembangunan berkelanjutan, cara hidup masyarakat adat yang penuh gotong royong, subsisten, menghasilkan emisi yang rendah, dan memanfaatkan alam secara berkelanjutan justru membuat kaum urban yang modern, individualis, dan mengonsumsi energi tinggi berada jauh di belakang. Pengetahuan masyarakat adat juga telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi kemajuan pengetahuan modern, terlebih dunia kesehatan dan ekologi. Sebut saja penggunaan kunyit sebagai obat pascaoperasi atau arsitektur tahan gempa dan tidak menggunakan unsur besi atau semen.
Bagi masyarakat adat, kesadaran menjaga lingkungan sudah jauh lebih dulu berkembang. Ketika orang-orang kota santai saja saat membuang limbah rumah dan pabrik ke sungai, Orang Rimba yang tinggal di Hutan Bukit Duabelas, Jambi, melarang anggotanya membuang hajat, sampah, juga menggunakan sabun di sungai. Mereka percaya bahwa sungai adalah jalur dewa sehingga harus dijaga kebersihannya.
Warisan terbesar dari proses belajar masyarakat adat selama ratusan tahun untuk warga dunia adalah budi daya tanaman pangan seperti padi-padian. Bahkan apa yang saat ini kita sebut superfood seperti madu, daun kelor, quinoa, dan masih banyak lagi sebagian besar adalah pola konsumsi tradisional yang sudah ratusan tahun dipraktikkan.
Lomawima (2015), seorang akademisi keturunan Indian (Muscogee), mengatakan bahwa pengetahuan adat seperti di atas terus berubah setiap generasi. Pengetahuan adat itu dinamis, selain juga tradisional, bukan statis atau tidak berubah. Pengetahuan adat juga beragam, unik, dan dirancang untuk menghadapi hal yang sangat fundamental, yaitu bertahan hidup.
Pendidikan yang Membebaskan
Meskipun pengetahuan masyarakat adat bersifat dinamis, adaptif, dan berkembang, bukan berarti pemiliknya tidak memiliki permasalahan. Salah satunya adalah tempat tinggal yang semakin panas. Kenaikan suhu bumi selama 50 tahun terakhir meningkat jauh lebih tajam dibanding ratusan tahun sebelumnya.
Ruang hidup masyarakat adat juga dipaksa menjadi semakin sempit. Para pemilik modal menggunakan cara-cara kolonial untuk memenuhi kebutuhan industri. Meskipun saat ini Indonesia telah merdeka, masyarakat adat masih sering mengalami perampasan lahan.
Lalu, seperti apa seharusnya pendidikan untuk masyarakat yang berpengetahuan, berdaya, dan memiliki kontribusi penting bagi kehidupan kita saat ini maupun masa depan namun sampai sekarang masih ditindas oleh banyak pihak?
Jika menggunakan cara pandang pembangunan berkelanjutan, pendidikan untuk masyarakat adat adalah pendidikan yang melihat mereka sebagai manusia yang merdeka, setara, memiliki pengetahuan, dan kemampuan. Oleh karena itu, mereka harus dapat ikut menentukan apa yang hendak dipelajari.
Sistem pendidikan ini tidak hanya kontekstual, melainkan juga partisipatif, kritis, dan otonom. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah pendidikan yang anti penindasan, bukan penundukan ke dalam sistem industri yang justru mendiskriminasi. Dalam hal ini, masyarakat adat harus diberikan kemampuan untuk melawan segala bentuk penindasan yang mengepung ruang hidup mereka.
Pendidikan untuk masyarakat adat, singkatnya, haruslah pendidikan yang membebaskan. Untuk itu kita harus membicarakan pemikiran Paulo Freire, tokoh penting dalam pendidikan kritis.
Freire menyatakan bahwa pendidikan yang sejati membutuhkan dialog. Tapi, dialog bukan sekadar dua orang atau lebih berkomunikasi dan berkompromi. Di dalamnya juga harus ada kesetaraan. Dalam pendidikan yang dialogis, guru, murid, dan masyarakat sekitar adalah subjek setara yang mendialogkan hal-hal yang konkret, eksistensial, dan merefleksikan aspirasi semua orang. Pengetahuan diproduksi bersama, dibicarakan, dan dikritisi untuk menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi subjek, bukan hal yang di luar subyek itu sendiri.
Dengan pendidikan dialogis ini, masyarakat adat tidak lagi dianggap tidak berpengetahuan. Selain itu, pendidikan akan dapat bermanfaat untuk menjawab permasalahan yang sedang atau akan mengancam kehidupannya.
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memang menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Peran mereka dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu individu, masyarakat sekitar termasuk orang tua murid dalam komite sekolah, dan masyarakat di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dalam dewan pendidikan.
Dalam praktiknya, pelibatan masyarakat sekitar sekolah baru terbatas pada aspek manajemen, pendanaan, atau aspek non-kurikuler lain. Sedangkan dalam kurikulum, partisipasi komunitas melalui komite sekolah hanya sebatas pembentukan visi, misi, dan tujuan sekolah, tidak pada perencanaan, penerapanan, dan evaluasi.
Banyak orang tua dari masyarakat adat tidak terlibat dalam pendidikan anak-anaknya di sekolah. Bukan tidak mau, tetapi karena institusi pendidikannya itu sendiri berwatak eksklusif. Besar kemungkinan ini terbentuk dari cara pandang yang menganggap masyarakat adat sebagai masyarakat yang lemah dan tertinggal. Dalam hal ini saja, sekolah sudah melanggar prinsip kesetaraan dalam pendidikan yang dialogis.
Cara pandang seperti ini tidak selalu berawal dari sekolah, namun sering datang dari para pejabat instansi pendidikan setempat yang berada di kota-kabupaten. Diskusi-diskusi tentang kurikulum tidak pernah dilakukan di tengah masyarakat, melainkan hanya sampai di guru. Itu juga umumnya sudah berbentuk instruksi-instruksi yang tidak partisipatif. Karena itu sekolah juga tidak dapat disalahkan jika tidak melibatkan masyarakat di sekitar sekolah. Mereka hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah.
Alih-alih publik, pemerintah melalui Kemdikbud lebih percaya pada Programme for International Student Assessment (PISA), penilaian pendidikan yang dilakukan lembaga ekonomi antarpemerintah yang bergabung dalam The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Pemerintah hendak mencetak anak sebagaimana yang dikehendaki PISA tanpa meleset sedikit pun.
Masalahnya adalah PISA tidak mampu mengukur kemahiran anak perempuan Kajang yang menenun tope le’leng dengan pewarna dari daun tarung, atau ketepatan anak-anak rimba memasang jerat sesuai dengan morfologi hewan buruan di hutan yang kompleks.
Selain itu, pendidikan yang terlalu berambisi mengejar PISA juga berdampak besar tapi tidak terlihat melalui angka, yaitu anak-anak masyarakat adat akan merasa semakin terpinggirkan dan rendah diri.
Minimnya partisipasi juga tercermin dari bahasa pengantar yang jauh berbeda dari konteks yang dipahami oleh masyarakat adat. Dalam praktiknya memang ada yang mendapatkan bahasa daerah sebagai muatan lokal, namun tidak sedikit yang terpaksa mempelajari bahasa daerah dari kultur yang lebih dominan. Misalnya SD di kawasan adat Kajang, Sulawesi Selatan. Para siswa mendapatkan muatan lokal bahasa Makassar, padahal bahasa masyarakat di sana adalah bahasa Konjo.
Sebenarnya Pasal 33 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan bahwa bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan. Dalam Bunga Rampai Pembelajaran Berbasis Bahasa Ibu di Kelas Awal (2021) yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Kemdikbud, pemerintah juga mengakui pentingnya membangun fondasi literasi melalui bahasa ibu. Hal ini juga telah diingatkan oleh UNESCO melalui dokumen kebijakan berjudul If You Don’t Understand How Can You Learn (2016).
Terputusnya penggunaan bahasa masyarakat setempat tentu patut dikritisi karena bahasa itu unik. Ia menyimpan kekayaan sosial dan ekologis masing-masing yang tidak dapat diwakili oleh bahasa lain dari mana pun. Banyak konteks kebudayaan dan pengetahuan tradisional yang tidak bisa diterjemahkan keluar dari bahasa di mana kebudayaan itu dipergunakan.
Kalender akademik yang digunakan di Indonesia saat ini juga belum berpihak pada anak-anak masyarakat adat. Kita mengikuti kalender akademik yang dipengaruhi kalender pertanian Barat. Kalender di sana disesuaikan dengan kebutuhan tenaga panen di musim panas. Karena itulah, kita mengenal libur musim panas. Tujuannya agar mereka dapat membantu orang tua di kebun.
Apa yang saya temukan di sini adalah kebalikannya. Justru orang tua yang meminta bantuan anak-anak di kebun saat panen akan dianggap mengabaikan hak pendidikan anak-anaknya. Padahal, keterlibatan anak dalam membantu orang tua adalah bagian dari banyak aspek pendidikan itu sendiri, mulai dari rasa tanggung jawab, gotong royong, belajar tentang alam, berhitung, dan masih banyak lagi.
Pengetahuan masyarakat adat saat ini lebih banyak dihadirkan secara ornamental sebagai muatan lokal seperti kerajinan tangan atau kesenian daerah. Hal ini membuat kebudayaan menjadi tidak visioner dan terkesan romantis. Padahal, melalui cara pandang pembangunan yang berkelanjutan, justru pengetahuan tradisional masyarakat adat-lah yang berada di garis depan.
Alih-alih melakukan refleksi kritis, setiap kali kabinet berganti, hadir pula kurikulum baru dengan jargon-jargon mutakhir di bidang pendidikan. Namun, sesungguhnya, tidak ada reformasi kurikulum yang signifikan, out of the box, dan tepat menyasar kebutuhan masyarakat adat. Semuanya cenderung mengikuti tren dan berorientasi ke Barat (eurosentris). Walaupun buku pelajaran dan metode berganti, tetapi jika paradigma dan visi masih sama, maka dampak di akar rumput juga tidak akan berubah: melemahkan, mendiskriminasi, dan mengalienasi.
Otonomi, Menghargai Kebinekaan
Konstruksi pengetahuan yang dimiliki masyarakat adat berbeda dengan Barat. Jika pengetahuan Barat sangat materialis, maka pengetahuan tradisional sangat spiritualis. Pengetahuan tradisional juga tidak memisahkan antara alam dengan budaya, semuanya kompleks dan terintegrasi menjadi satu. Misalnya saja pengetahuan tentang sungai pada orang rimba. Hal itu termasuk aspek perlindungan alam, hubungan sesama manusia, dan kepercayaan terhadap keberadaan dewa-dewa.
Sistem transmisi pengetahuan masyarakat adat pun tidak berbasiskan tulisan sehingga dapat dilakukan sendiri dengan membaca. Bagi masyarakat adat, pendidikan adalah pembelajaran dalam hidup. Oleh karena itu, proses pembelajaran umumnya berbasiskan pengalaman atau ‘learning by doing’, termasuk di dalamnya proses pengamatan, tindakan, sekaligus interaksi dengan alam secara langsung atau dengan orang dewasa seperti mendengarkan dongeng, cerita, mitos, metafora, atau lagu-lagu.
Pengetahuan pun terbagi menurut peran individu di dalam komunitasnya. Perempuan dan laki-laki menyimpan pengetahuan yang berbeda, demikian juga anak-anak. Dan, kembali lagi, setiap peran di komunitas adat tidak seragam.
Struktur pengetahuan masyarakat adat yang demikian kompleks tidak dapat masuk ke dalam templat persekolahan yang mengotak-ngotakkan pengetahuan. Di sekolah formal, misalnya, mata pelajaran agama berdiri sendiri di luar pelajaran seperti IPA dan IPS. Dalam pengetahuan adat semuanya berikatan. Aspek material tidak terpisahkan dari aspek spiritual, begitu pula antara aspek sosial dan alam.
Oleh karena itu, selain partisipatif dan kritis, memberikan otonomi pada masyarakat adat baik di sekolah formal maupun sekolah adat adalah kunci dari pendidikan yang membebaskan.
Masyarakat adat berhak menentukan proses dan arah pendidikannya. Ini tertuang dalam Pasal 14 Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Bahkan disebutkan bahwa negara-negara harus mengambil langkah-langkah efektif agar masyarakat adat, khususnya anak-anak, memiliki akses, bila mungkin, ke pendidikan dalam budaya dan dengan bahasa mereka sendiri. Pun Pasal 30 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa anak-anak masyarakat adat tidak boleh diingkari haknya untuk menikmati budayanya sendiri, menganut dan mengamalkan agamanya, atau menggunakan bahasanya.
Pertanyaannya: maukah kita membuat “mungkin” itu terwujud?
Jika kita membangun sekolah adat dengan standar yang sama untuk semua tempat alias templat, atau menyederhanakan dan mengintegrasikan sistem yang kompleks agar dapat diterima oleh sistem pendidikan yang seragam, maka kita akan banyak sekali kehilangan dan sepertinya justru pelan-pelan menundukkan masyarakat adat, bukan mendukungnya untuk berdaya.
Di tingkat nasional, mungkin masih sulitnya menjalankan pendidikan yang dialogis dan otonom bagi masyarakat adat disebabkan karena pemerintah masih enggan mengubah paradigma pendidikan. Masalahnya waktu semakin mendesak. Dampak ekologis karena pendidikan yang bias urban, mendukung konsumsi massa yang tinggi, dan sangat industrialis tidak hanya akan dirasakan masyarakat adat, melainkan kita semua.***
Fadilla M. Apristawijaya, aktivis pendidikan sekaligus spesialis kurikulum pada Sokola Institute (sokola.org)