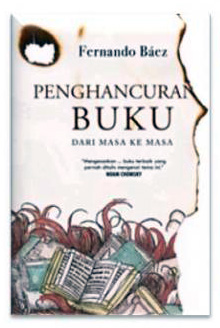Judul Buku: Penghancuran Buku dari Masa ke Masa
Penulis: Fernando Baez
Penerjemah: Lita Soerjadinata
Penerbit: Marjin Kiri, 2013
Tebal: vxiii+373 halaman
‘Dimanapun mereka membakar buku,
pada akhirnya mereka akan membakar manusia.’
-Heinrich Heine
‘MENGAPA manusia menghancurkan buku?’ Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang selalu hadir dalam setiap zaman, dalam setiap konteks sosial historis yang pernah ada, semenjak manusia mengenal cara merekam pengetahuan yang dimilikinya dalam media tertentu. Kini pertanyaan ini kembali mengemuka ketika beberapa waktu lalu terjadi peristiwa yang merupakan repetisi dari segala jaman yang merasa terganggu dengan lahirnya pengetahuan tertentu: pelarangan mendiskusikan buku tentang Tan Malaka oleh sekelompok ormas yang mengatasnamakan Pancasila dan Islam. Meskipun pelarangan mendiskusikan buku tersebut tidak diikuti dengan penghancuran buku dimaksud, tetapi pada akhirnya peristiwa tersebut adalah suatu contoh bagaimana buku menjadi arena kontestasi antara arus utama dan the others, antara kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai, antara keperluan untuk melanggengkan hegemoni dan upaya untuk menggugat status quo.
Dalam sejarahnya, penghancuran buku sama tuanya dengan ditemukannya buku itu sendiri (tentu bukan dalam bentuk yang kita ketahui sekarang). Merunut sejarah, penghancuran buku sudah terjadi di Sumeria Kuno, sekitar 4000 tahun sebelum masehi. Dalam konteks Indonesia, penghancuran buku telah ada semenjak masa kolonial, dan masih terjadi bahkan hingga hari ini. Kebencian terhadap buku ini seringkali diekspresikan dalam beragam bentuk, mulai dari pelarangan dan sensor hingga diekspresikan dengan cara langsung membakar buku, menghancurkan perpustakaannya, hingga membakar orang yang membuat buku tersebut bersama karyanya. Sejarah pembakaran buku dengan berbagai kompleksitasnya ini, yang tidak lain merupakan sejarah kebencian satu ke kebencian lainnya, direkam dengan baik dan amat lengkap oleh Fernando Baez, seorang kepala Perpustakaan Nasional Venezuela dalam bukunya Penghancuran Buku Dari masa Ke Masa. Buku ini menjadi penting sebab, selain karena merupakan kajian yang masih sedikit diangkat oleh para peneliti, juga bertentangan dengan pendapat umum bahwa para pelaku librisida (istilah untuk penghancuran buku) bukanlah vandalis yang bodoh, melainkan orang-orang terdidik dengan motif ideologis masing-masing.
Penghancuran Buku di Dunia Kuno
Mengapa orang menghancurkan buku? Jawabannya, demikian Baez, untuk menghabisi memori penyimpannya, artinya warisan gagasan-gagasan dari suatu kebudayaan secara keseluruhan. Buku sebagai media penyimpan gagasan si penulis sendiri pertama kali ditemukan di wilayah Sumeria, sekarang Irak Selatan, diantara aliran sungai Efrat dan Tigris sekitar 5.300 tahun yang lalu. Buku, dalam konteks ini, berbentuk tanah liat yang dikeringkan yang disebut ‘Tablet.’ Penghancuran buku pada waktu itu terjadi pada tahun 4000-an sebelum masehi (SM), yang dibuktikan dengan temuan arkeologis berupa banyaknya tablet yang ditemukan pecah atau hancur sama sekali.
Usaha untuk melestarikan ingatan melalui buku, selain mengganti bahan baku tanah liat menjadi kayu, juga dilakukan melalui merawat dan menyalin buku-buku oleh golongan tertentu yang disebut ‘para penyalin kitab,’ yang merupakan golongan fungsionaris istana. Perawatan serta penyalinan buku ini pada akhirnya menciptakan perpustakaan pertama kali dalam sejarah umat manusia, yaitu pada tahun 3300 SM dimasa raja Uruk III dari Sumeria. Buku ini sendiri terdiri dari buku tentang flora, fauna, mineral, puisi, pepatah, hingga mantra sihir. Pendirian perpustakaan pertama ini kemudian diikuti oleh pendirian perpustakaan-perpustakaan ditempat lain, seperti perpustakaan di Lasagh, Isin, Ur, dan Nippur. Ketika Sumeria runtuh dan digantikan dengan Babilonia (sekarang Baghdad), Sang penguasa baru, Hammurabi, kemudian mengambilalih koleksi-koleksi perpustakaan dan dikumpulkan dalam perpustakaan besar dalam istananya. Perpustakaan ini terkenal dengan nama Perpustakaan Babilonia.
Perkembangan media penyimpanan memori manusia terus berkembang di Mesir, yaitu melalui media bernama Papirus yang berasal dari alang-alang dan kemudian dikeringkan. Ketika itu, papirus hanya bisa dibaca oleh sekelompok pendeta karena dianggap memiliki kekuatan gaib. Papirus ini juga yang pertama kali menjadi media penyimpan memori yang dimusnahkan. Adalah Akhenaton, pelopor monoteisme, yang menjadi salah satu orang pertama yang membakar buku. Dia membakar naskah-naskah rahasia agar agama yang dianutnya menjadi unggul.
Papirus juga menjadi media penyimpanan di era Yunani Kuno, terutama pada abad ke-5 SM, ketika budaya tulisan mendominasi budaya lisan. Hal ini yang kemudian mendorong perdagangan buku untuk pertama kali. Meskipun demikian, diperkirakan hingga 75 persen karya sastra, filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani Kuno telah hilang (hlm 40). Adalah Aristoteles yang memberikan petunjuk pertama mengapa karya-karya, khususnya sastra, musnah pada zaman itu. Kesaksian yang didapat dari potongan buku Aristoteles berjudul Tentang Para Penyair, yang juga hilang, menunjukkan bahwa karya Empedokles yang merupakan penyair dibakar oleh saudara perempuannya sendiri. Menurut Baez, karya ini sendiri menyiratkan sentimen religius yang mendalam dan mungkin menjadi alasan penghancuran buku itu. Selain itu, musnahnya buku-buku Yunani klasik ini juga kemungkinan diakibatkan oleh kebakaran, gempa bumi serta mulai digunakannya bahasa latin sebagai teks yang menggeser peran bahasa Yunani. Adapun Aristoteles sendiri mengalami penghancuran atas buku-bukunya karena dituduh murtad oleh para pendeta, setelah muridnya yang sangat berkuasa Iskandar Agung, wafat. Karya Aristoteles dihancurkan dengan cara dibakar. Beberapa dugaan juga mengatakan bahwa karya-karya Aristoteles dilarikan jauh dari Athena untuk menghindari penghancuran yang lebih sadis.
Adalah perpustakaan Alexandria yang berada di Mesir Selatan, yang menjadi perpustakaan pertama yang penuh dengan tragedi-tragedi penghancuran akibat berbagai perang. Ketika perang saudara melanda Mesir akibat dari perebutan kekuasaan, Julius Caesar dari Romawi yang mendukung kekuasaan Cleopatra, membumihanguskan armada perang Mesir. Pembumihangusan inilah yang diindikasikan menghancurkan 40.000 buku yang disimpan dalam gudang pelabuhan. Perpustakaan Alexandria sendiri akhirnya hancur pada tahun 389 M akibat perang. Meskipun demikian, siapa dalang yang ada dibelakang penghancuran Perpustakaan Alexandria tersebut masih belum terpecahkan: antara orang Romawi, Kristen, atau Islam. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa hancurnya perpustakaan akibat dari bencana alam ataupun penelantaran karena konflik militer dan politik yang tak kunjung reda.
Penghancuran buku besar-besaran di era kuno juga dapat kita jumpai dalam sejarah Cina. Buku-buku yang dianggap mengritik kaisar dan proses penyatuan Cina pada abad ke-3 SM dibawah Zhao Zheng, pendiri dinasti Qin, dihancurkan. Selain itu, Zhao Zheng atau yang juga dikenal sebagai Shih Huang Ti menyetujui pembakaran semua buku, kecuali yang berkaitan dengan pertanian, kedokteran, dan ilmu nujum. Peristiwa ini terjadi pada tahun 213 SM, tahun dimana di Alexandria justru sedang terjadi usaha pengumpulan semua buku yang ada. Selain karena alasan politik, penghancuran buku juga terjadi dengan alasan agama, yaitu saat terjadi penghancuran terhadap teks-teks Buddhisme karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Konghucu.
Jika di Cina Kuno ada Zhao Zheng, si raja penghancur buku, di Romawi Kuno kita menemukan nama Kaisar Agustus yang memiliki tabiat yang serupa. Kaisar Agustus memusnahkan ribuan karya dengan alasan politik dan stabilitas negara. Diantara buku yang dimusnahkannya adalah Seni Bercinta karya Ovid dan Acta Caesaris Augusti karya Timagenes dari Alexandria, karena dianggap tidak menunjukkan rasa hormat yang cukup pada dirinya saat menuliskan karya ini, serta 2000 karya Romawi dan Yunani lain yang tidak dia sukai (hlm 84). Bangsa Barbar akhirnya menghancurkan Imperium Romawi Barat pada tahun 410. Bersamaan dengan itu, bangsa Barbar ini juga menghancurkan rekaman kebudayaan dalam bentuk apapun, termasuk papirus, tanpa ampun.
Kemudian, bersamaan dengan lahir dan berkembangnya Kristen pada abad ke 2 hingga ke-5, didapati pula motif penghancuran buku atas dasar agama. Inilah yang menimpa karya-karya para penganut Gnostik, yang merupakan campuran dari gagasan keagamaan orang Mesir, Hindu, Yunani, dan Babilonia. Penghancuran besar-besaran atas karya Gnostik dilakukan kekuasaan Gereja, karena kaum Gnostik ini menyerukan keselamatan akan hadir melalui pengetahuan (gnosis), bukan melalui iman. Selain memerangi Gnostik, Gereja juga harus memerangi serangkaian bidah lainnya yang berujung pada penghancuran buku. Diantara karya yang masuk daftar penghancuran adalah buku milik Uskup Macedonia, karya milik Eunomius, dan kitab-kitab sekte Nestorianisme.[1]
Byzantium Hingga Abad Ke-19: Penghancuran Buku Berlanjut
Penghancuran buku di zaman kuno menemui titik balik di era Byzantium, sebuah kekaisaran yang ibukotanya dibangun pada tahun 330 oleh Konstantin I dan merupakan kekaisaran yang melestarikan tradisi Yunani dan Romawi. Melalui kekaisaran yang memiliki ibukota Konstantinopel inilah kita berhutang. Tanpa kekaisaran ini, kita tidak akan pernah membaca karya-karya Plato, Aristoteles, Herodotus, Archimides, dan penulis Yunani Kuno lainnya. Gairah untuk menggali karya-karya kuno ini disebabkan kegandrungan yang besar akan buku, terutama yang dimotori oleh kaum terpelajar. Selain itu, media penyimpanan pun mengalami transformasi menjadi kodeks dan perkamen yang memungkinkan penulisan dikedua sisi, dan pada akhirnya kertas sebagaimana yang kita kenal sekarang pada masa pemerintahan Konstantin II.
Pada masa ini ratusan teks sejarah, filsafat, dan hukum disalin. Selain itu juga mulai dibangun perpustakaan yang merupakan usaha lain untuk melindungi buku-buku. Tetapi, toh semua peristiwa ini tidak menghalangi buku-buku hancur. Pada tahun 781, kebakaran hebat melanda istana yang mengakibatkan 120.00 buku terbakar. Pada masa ini juga beberapa kali penghancuran buku terjadi, yaitu yang menimpa buku karya Santo Sirilus karena dianggap mengandung bid’ah. Meskipun demikian, penghormatan terbesar tetap mereka berikan pada karya-karya para penulis klasik.
Di belahan dunia lain dimasa yang sama, berdiri juga kekhalifahan Abbasiyah yang berdasarkan Islam dan berpusat di Baghdad, Irak. Salah satu peristiwa penting dari kekhalifahan ini adalah penerjemahan karya-karya penulis Yunani Kuno yang didapat dari Byzantium dan pendirian perpustakaan terbesar dimasanya yang bernama Darul Hikmah (Rumah Kebijakan). Penerjemahan ini dimulai ketika Al-Ma’mun, khalifah keenam, bermimpi bertemu seorang sepuh dengan janggut rapi yang didaku sebagai Aristoteles dan memintanya untuk menerjemahkan semua karya Aristoteles agar tak lekang jaman (hlm 117).
Adalah perang salib yang menandai dimulainya kembali penghancuran atas buku-buku. Pada tahun 1108, pasukan Kristen menghancurkan pusat belajar di Damaskus dan memusnahkan lebih dari 3 juta buku. Kemudian pada tahun selanjutnya, pasukan Kristen yang berhasil memasuki Tripoli, kembali menghancurkan buku lebih dari 100.000 buah. Tahun 1204, dalam peran salib keempat, pasukan perang salib mencapai Konstantinopel yang berada di Byzantium dan menghancurkan ribuan manuskrip. Akhirnya, Konstantinopel benar-benar runtuh pada tahun 1453, setelah pasukan Turki di bawah komando Sultan Muhammad al-Fatih mengepung kota. Segera setelah itu seisi kota dihancurkan, termasuk perpustakaan bersama buku-bukunya. Selain perang salib, salah satu peristiwa yang menandai penghancuran besar-besaran atas buku, khususnya di Baghdad, adalah invasi bangsa Mongol yang dilakukan oleh Hulagu Khan, cucu Genghis Khan pada tahun 1257. Penyerangan yang mengorbankan 500.000 nyawa ini juga diikuti oleh penghancuran buku melalui metode menghanyutkannya ke Sungai Tigris.
Selain serangkaian penghancuran buku atas alasan politis sebagaimana yang telah dijabarkan, ada juga penghancuran buku dengan motif religius, yang dijumpai terutama pada Abad Pertengahan di Eropa, dimana kekuasaan Gereja sangat absolut. Beberapa karya yang dihancurkan pada zaman ini adalah karya Pierre Abelard berjudul Introductio ad Theologiam pada tahun 1120; Talmud, yang merupakan salah satu buku yang paling sering diberangus dalam sejarah dan berisi tentang kumpulan penjelasan dan penafsiran para rabi mengenai Alkitab dan sejarah Yahudi; karya-karya Musa bin Maimum; Khotbah-khotbah imam Arnaud de Bresse, pendiri sekte Almaricus;[2] karya guru besar teologi di Universitas Salamanca, Pedromartinez de Osma berjudul De Confessione; buku karya penyair Enriqe de Villena, dibakar karena tema-temanya mengandung ajaran pagan; buku karya Reginald Scott, seorang anggota parlemen Inggris berjudul A Discovery of Withcraft; Kitab Perjanjian Baru karena menggunakan bahasa lokal Inggris, dan masih banyak lagi. Sebagai salah satu upaya sistematisasi atas penghancuran buku, pada tahun 1559 Paus paulus IV menerbitkan Indeks Buku-Buku Terlarang yang berisi daftar buku yang paling membahayakan iman. Penghancuran buku dengan motif keagamaan, selain dilakukan oleh Gereja, ternyata juga dilakukan oleh kekhalifahan Islam. Diantara buku yang dihancurkan adalah buku-buku diperpustakaan Al-Hakam, Cordoba, Spanyol pada masa Khalifah Al-Mansur (938-1002), karena tidak dianggap suci dan seluruh karya Ibnu Hazm, seorang penyair. Selama masa perebutan kembali Spanyol pada tahun 1500-an, penghancuran buku kembali terjadi, kali ini korbannya adalah Al-Qur’an serta risalah keagamaan lainnya. Pemimpin penghancuran itu adalah Raja Ferdinand V dan Ratu Isabella I dengan alasan pemurnian religius.
Ketika Eropa mulai memasuki masa renaisance yang diikuti oleh Revolusi Prancis, tempat lahirnya paham kebebasan, penghancuran buku tidak juga berhenti. Justru, di Prancis inilah penghancuran buku mengalami transformasi metode: sensor. Sebelumnya, menjelang Revolusi Prancis, beberapa karya dihancurkan oleh Gereja seperti karya Voltaire berjudul Lettres Philosophiques (1734) karena dianggap menginspirasi kebejatan, berbahaya bagi agama dan tatanan sosial; Karya Denis Diderot Pensees Philosophiques (1746) juga disensor karena mengandung ajaran ateisme; Karya Montesquieu De l’esprit des loi (1748); hingga Emile (1762) karya Jean-Jacques Rousseau. Di masa Revolusi Perancis (1789), saat kekerasan menjadi peristiwa sehari-hari, perpustakaan juga terkena imbasnya. Menurut Baez, di Paris saja pada masa itu 8000 buku rusak, ditempat lainnya lebih dari 4 juta buku, yang mana 26.000 diantaranya adalah manuskrip kuno. Pada masa Komune Paris tahun 1871, kehancuran buku juga tidak terhindarkan dengan terbakarnya Perpustakaan Louvre, Paris.
Beberapa peristiwa penting lainnya tentang penghancuran buku, yang juga patut dicatat dipenghujung abad ke-19 ini adalah perang pembebasan Amerika Latin yang mengakibatkan perpustakaan, arsip, buku, serta monumen bersejarah lainnya dihancurkan. Salah satu contohnya adalah kekalahan Simon Bolivar dari Spanyol pada 1817. Karena kekalahan ini, semua buku yang awalnya dikumpulkan Simon Bolivar untuk perpustakaan umum di kota Caracas, dihancurkan oleh Spanyol. Selain itu, buku kontroversial dari Charles Darwin yang berjudul On The Origin of Species yang terbit pertama kali tahun 1859, juga menjadi buku penting yang masuk daftar penghancuran di ufuk barat abad ke-20.
Abad ke-20 Hingga Sekarang
Bab terakhir dari buku ini dimulai Baez dari epoh perang Spanyol, yang terjadi antara tahun 1936 sampai tahun 1939. Ketika itu, Spanyol dikuasai oleh Jendral Franco yang Fasis. Pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat dan menghasilkan sebuah komune disalah satu kota di Spanyol pada Oktober 1934, direspons dengan represi ganas dari Franco dan pendukungnya. Agen-agen polisi, dalam serangannya, menghancurkan buku dilebih dari 257 perpustakaan rakyat. Perpustakaan rakyat dimaksud adalah perpustakaan-perpustakaan yang ada dipemukiman warga dan basis serikat buruh. Setelah peristiwa ini, peristiwa bibliosida terus berlangsung. Kekuasaan fasis memberangus semua buku yang dianggap porno, antipatriotik, sektarian, bid’ah, revolusioner, atau merusak moral masyarakat. Selain penghancuran buku, kekuasaan fasis Franco juga melakukan sensor dengan cara membatasi peredaran buku-buku asing dan memerintahkan para penjual buku membersikan stok buku mereka. Semua ini dilakukan oleh badan khusus yang dibentuk bernama Badan Propaganda Nasional.
Setelah itu, Baez beranjak ke pembahasan selanjutnya: bibliocaust oleh Nazi. Sebagaimana diketahui, ketika Nazi berkuasa, mereka melakukan pembantaian massal kepada orang-orang Yahudi yang disebut dengan Holocaust. Sebagaimana yang dituturkan Baez, holocaust ini sebenarnya dimulai dengan sebuah aksi bibliocaust.[3] Gunungan buku yang dilalap api mengilhami tungku-tungku krematiorium kamp konsentrasi (hlm 217). Sebelum 1933, Nazi, yang kekuasaannya baru menggeliat, sebenarnya telah melakukan upaya-upaya bibliocaust. Mereka melakukan razia terhadap koleksi yang ada di toko buku dan meneror para penulisnya. Pada tanggal 30 Januari 1933, ketika Presiden Republik Weimar mengangkat Hitler sebagai kanselir, strategi intimidatif terhadap warga Yahudi, serikat buruh, dan anggota partai politik pesaing Hitler segera dilancarkan. Kantor Partai Komunis dan perpustakaannya dihancurkan, gedung parlemen Jerman diserang dan arsip-arsip yang ada di dalamnya dibakar. Bahkan, karena intimidasi dari satuan polisi sepperti SA, SS, dan Gestapo, pada penulis membakari buku-buku milik mereka sendiri. Otak dibalik penghancuran memori kolektif itu adalah Joseph Gobbels, yang merupakan tangan kanan dan pengikut setia Hitler. Penghancuran buku-buku ini juga mendapat restu serta justifikasi ideologis dari salah satu filsuf eksistensialis dan fenomenologis terkenal, Martin Heidegger.
Selain di Jerman, rezim fasis Hitler juga melakukan bibliocaust terhadap koleksi-koleksi yang berada di negara yang dikuasai Jerman, seperti Belanda, Belgia, Austria, Ceko. Selain itu, salah satu hal yang ‘menarik’ dari peristiwa bibliocaust oleh Nazi adalah bibliocaust diselenggarakan melalui upacara resmi yang jadwalnya telah disebarkan beberapa hari sebelumnya. Total, jutaan buku, perpustakaan, arsip, museum dan berbagai tempat memori kolektif hancur dan tidak bisa diselamatkan.
Selain itu, catatan penting tentang penghancuran buku di abad 21 juga terekam dalam kekuasaan militer di Spanyol, Cile dan Argentina. Di Spanyol ketika Jendral Franco berkuasa, buku-buku Marx, Engels, dan Mao dilarang keras selain karya-karya erotika. Di Cile, Jendral Pinochet yang mengkudeta pemerintaha sosialisme di bawah Salvador Allende, melakukan kontrol ketat atas terbitan-terbitan yang dalam pemerintahan sebelumnya mencoba menjangkau massa melalui terbitan-terbitan murah. Sedangkan di Argentina, penghancuran buku dilakukan dengan sasaran terbitan-terbitan yang membahas pemikiran seperti Marx, Hegel, Freud, Sartre, dan Camus. Selain kekuasaan militer, peristiwa penting tentang penghancuran buku juga terjadi dengan dalil kebencian etnis dan religius. Beberapa contoh dari kasus ini adalah kasus Bosnia dan Chechnya.
Beberapa Catatan
Membaca buku ini, bagi saya, adalah membaca kisah pilu sepanjang zaman yang bertubi-tubi. Baez berhasil membuat bulu kuduk bergidik membayangkan bagaimana buku-buku, dan dokumen lainnya, dihancurkan dengan dalih dan cara yang beragam. Tidak terhitung berapa jumlah buku, dan dengan demikian pengetahuan yang ada di dalamnya, tidak diketahui oleh generasi masa kini (dan tentu generasi masa mendatang). Ilmu pengetahuan yang tercipta di zaman Yunani Kuno adalah contoh kecil. Bagaimana saat ini, seberapapun luhur dan agungnya pengetahuan-pengetahuan yang tercipta melalui para pemikir yang lahir di zaman Yunani Kuno tersebut, nyatanya hanya sekitar 25 persen yang kita ketahui. Sisanya, bahkan tak pernah tersentuh oleh generasi penerus pertama dari para pemikir tersebut.
Di dalam buku ini, dapat disimpulkan bahwa hancurnya buku-buku adalah karena banyak hal. Bencana alam, musuh tradisional buku seperti serangga dan suhu udara, masalah politis, kebencian etnis dan religius adalah sebagian sebab dari hancurnya buku-buku. Tetapi, tidak diragukan lagi masalah politis dan religius adalah sebab yang paling dominan yang mewarnai eksekusi terhadap buku-buku. Masalah ‘politis’ dan ‘religius’ yang dimaksud sebenarnya dapat dikerucutkan kembali dalam terminologi ‘ideologis’ –dalam makna yang negatif, tentu. Dalam buku ini terlihat jelas bagaimana penghancuran buku bukan semata penghancuran materi, tetapi kandungan informasi yang ada di dalam buku. Api, yang menjadi senjata utama dalam menghancurkan buku, menguatkan simbol penghancuran tanpa sisa dari sisi fisik dan kandungan informasi tersebut.
Topik yang diangkat Baez dalam buku yang penelitiannya memakan waktu belasan tahun ini, merupakan buku yang penting. Selain karena masih sedikit yang mengangkat tema yang sama, buku ini juga bisa menjadi semacam ensiklopedia penghancuran buku sepanjang masa. Tetapi, karena menjadi semacam ensiklopedia itu pulalah terlihat kekurangan dari buku ini. Sebagaimana ensiklopedia, informasi yang diberikan sangat beragam dan dalam jangkauan yang juga sangat luas, tetapi sekaligus juga tidak mendalam. Begitu pula buku Baez ini, ia memang menjelaskan secara gamblang sejarah penghancuran buku bahkan semenjak manusia mengenal peradaban, tetapi karena jangkauan pembahasan yang teramat luas itulah, buku ini, bagi saya, tidak terlalu mendalam. Hal ini terlihat melalui beberapa pembahasan tentang penghancuran buku dalam konteks waktu tertentu, tetapi tidak dijelaskan mengapa dalam konteks waktu tersebut buku-buku dihancurkan. Mungkin, hal ini terjadi karena keterbatasan informasi yang didapatkan, dan itu adalah hal yang wajar dan justru seharusnya mendorong penelitian yang lebih spesifik baik dalam segi konteks waktu ataupun hal spesifik lainnya.
Dalam konteks Indonesia, buku Baez ini tidak akan cukup memuaskan untuk menjawab problem penghancuran buku yang pernah terjadi di Indonesia. Dalam buku ini, Baez hanya membahas bahwa pernah terjadi sensor terhadap buku-buku pelajaran yang tidak mencantumkan nama ‘PKI’ setelah kata ‘G30S’ dan pelarangan terhadap buku-buku yang menyebarluaskan gagasan marxisme-leninisme dalam beberapa kalimat saja. Padahal, sejarah penghancuran buku di Indonesia memiliki sejarah yang juga panjang, yaitu telah terjadi pada zaman kerajaan-kerajaan nusantara. Sebagaimana menurut Minanuddin (1992), sensor atau pelarangan buku lazimnya dilakukan dibawah perintah atau kuasa raja yang tercatat pertama kali pada abad ke 17, yang dilakukan oleh kerajaan Aceh atas karya Hamzah Fansuri, seorang ulama mistik.[4] Pelarangan, atau penghancuran, atau sensor terhadap buku terus terjadi seiring dengan pergantian corak pemerintahan: dari masa kerajaan, masa kolonialisme Belanda, masa pendudukan Jepang, Orde Lama, dan Orde Baru. Selain penelitian Minanuddin, penghancuran/pelarangan/sensor terhadap buku di Indonesia juga dibukukan melalui hasil penelitian Iwan Awaluddin Yusuf (et al) berjudul Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi, yang selain membahas sejarah pelarangan buku sejak zaman kerajaan hingga pasca orde baru, juga membahas bagaimana gerakan melawan pelarangan buku tersebut, baik dari jalur litigasi maupun non-litigasi. Kedua hasil penelitian ini dapat menjadi bacaan tambahan setelah membaca karya Baez.
Menanggapi kasus penghancuran buku sendiri, saya berpendapat bahwa, dengan alasan apapun, penghancuran buku merupakan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Dalam konteks kapitalisme saat ini, misalnya, apakah salah satu bentuk perlawanan terhadap kapitalisme adalah menghancurkan buku-buku yang menjustifikasi kapitalisme? Tentu tidak. Yang perlu dilakukan, meminjam istilah Gramsci, adalah melakukan counter-hegemony dengan cara mengeluarkan buku-buku yang melawan dan membuktikan bahwa kapitalisme adalah bermasalah (sehingga ia jahat) dan memberikan perspektif baru bahwa ada alternatif lain di luar kapitalisme. Tentu hal ini adalah salah satu contoh kecil disamping hal-hal lain yang bisa diimajinasikan dan dilakukan secara kolektif.
Penulis adalah Sekjend Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia (SEMAR UI)
Bacaan Tambahan
Minanuddin. (1992). Pelarangan Buku di Indonesia: disertai Bibliografi Beranotasi Buku Terlarang di Indonesia tahun 1966-1992. Skripsi Sarjana, Universitas Indonesia.
Iwan Awaluddin Yusuf. et al. (2010). Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi. Yogyakarta: PR2Media dan Friedrich Ebert Stiftung.
[1] Penganut Nestorianisme mempercayai Tuhan ganda dalam satu sosok yang ilahi dan satu sosok yang insani. Bagi mereka pemanggilan Maria, Ibu Yesus, sebagai ‘Bunda Tuhan’ sebagai sesuatu yang absurd. Mereka juga tidak mengakui supremasi Uskup Roma dan menganjurkan hidup sederhana sebagaimana yang dijalankan oleh para Rasul.
[2] Sekte Almaricus menganggap bahwa Tuhan dan segenap mahluk hanyalah strategi dari kemanunggalan Tuhan sebagai segala dan segalanya sebagai Tuhan.
[3] Istilah bibliocaus merujuk pada penghancuran buku –melalui berbagai cara, yang dilakukan oleh rezim Fasis Hitler.
[4] Minanuddin. (1992). Pelarangan Buku di Indonesia: disertai Bibliografi Beranotasi Buku Terlarang di Indonesia tahun 1966-1992. Skripsi Sarjana, Universitas Indonesia. Hlm 52-53.