MAX Lane[1] meramalkan bahwa, seperti pada pemilu 2009 lalu, pemilu legislatif 2014 juga kembali akan dimenangkan Golongan Putih. Ini memang bukan ramalan yang mengejutkan. Tetapi akan tetap mengherankan jika kita melihat beberapa kemungkinan statistik bahwa, meskipun kemenangan golput kali ini akan jauh lebih mutlak, namun fakta itu tetap tidak akan mengubah keadaan. Kemenangan golput tetap bukan sebuah kemenangan politik. Itu karena golongan ini masih akan merupakan ‘passive-abstentious-voters,’ pemilih pasif yang tak-hadir, atau yang keberadaannya tak punya signifikansi politik. Demokrasi kita masih akan tetap dikendalikan partai-partai elitis.
Pemilu 2014 adalah pemilu besar di antara pemilu-pemilu lain yang pernah diselenggarakan di seluruh dunia. Pemilu ini akan memilih sekitar 19.700 kandidat legislatif yang tersebar di 2.450 daerah pemilihan. Pemilu ini juga akan diikuti oleh sekitar 186 juta pemilih.[2]
Perludem (2014) menyebutkan kecenderungan naiknya jumlah pemilih yang tak mau menggunakan haknya sejak 1999 sampai 2009. Data KPU secara resmi juga memperlihatkan terus naiknya angka golongan putih, dari 8 persen (1999), 23 persen (2004), hingga 39 persen (2009). Beberapa pengamat memiliki proyeksi yang berbeda-beda mengenai angka golput pada 2014, yakni antara 40 persen hingga 70 persenan. Perkiraan tertinggi dikemukakan oleh Tamrin Amal Tomagola, hingga 75 persen.[3] Dengan mengambil angka moderat dari semua perkiraan itu, kita bisa menetapkan 57 persen sebagai proyeksi yang masuk akal.
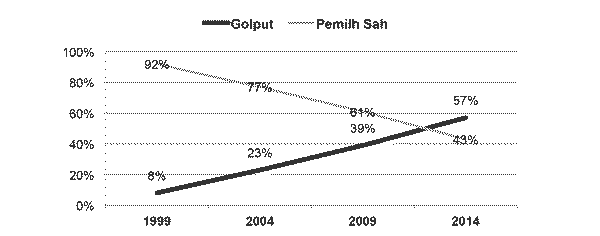
Perkiraan semacam ini yang mungkin membuat Max Lane mempunyai kesimpulan di atas. Pada pemilu 2009 lalu, angka golput melebihi perolehan suara di atas semua partai, termasuk Partai Demokrat yang mendapatkan suara paling unggul. Jadi, sejak lima tahun lalu golongan putih sebenarnya sudah ‘memenangkan pemilu.’
Perolehan Suara Pemilu 2009: Dua Versi Perhitungan
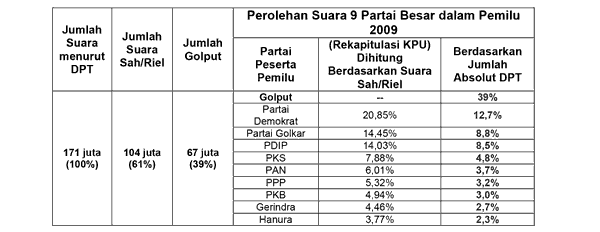
‘Kemenangan’ golput itu akan lebih terasa lagi jika kita melihat proyeksi berbagai pengamatan mengenai bakal merosotnya perolehan suara semua partai. Max Lane sendiri memprediksi, suara tertinggi pada pemilu 2014 akan diperoleh PDIP dengan angka sekitar 20 persen, merosot 14 persen dibanding perolehannya pada 1999; disusul Golkar yang merosot jadi 12 persen; lalu Partai Demokrat yang juga akan jeblok di bawah 10 persen.[4]
Proyeksi Enam Besar Perolehan Suara 2014
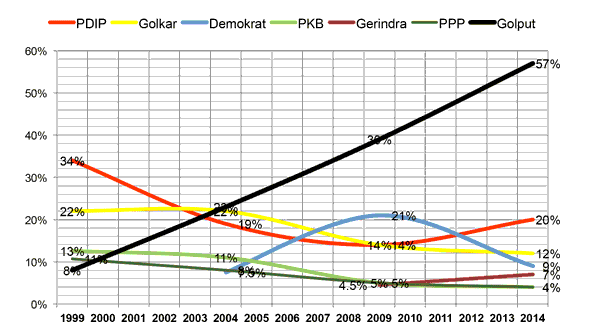
Dari 12 partai peserta pemilu, diperkirakan hanya separonya yang berhasil lolos ketentuan parliamentary treshold.[5] Di samping tiga partai besar di atas, PKB dan PPP diperkirakan masih bisa lolos karena basis dukungan tradisionalnya yang fanatik. Di pihak lain, seperti disebutkan dalam editorialnya baru-baru ini, The Jakarta Post menempatkan Gerindra di posisi empat besar perolehan suara, melejit melampaui suara PKB dan PPP, dengan perolehan suara sekitar 7 persen.[6] Jika proyeksi ini tepat, maka partai ini juga akan membenamkan PKS dan PAN yang selama ini berada pada posisi partai menengah. Mereka akan merosot jatuh bersama empat partai kecil lainnya, yakni Hanura, Nasdem, PBB, PND, dan PKPI. Kesemua partai ini menurut proyeksi SSS (Sugeng Saryadi Syndicate) tidak bakal bisa melampaui 3,5 persen parliamentary treshold.[7]
Keseluruhan proyeksi di atas tampaknya mengisyaratkan kenyataan yang tak terbantahkan, bahwa kompetisi politik pada periode elektoral keempat sejak jatuhnya Suharto itu adalah kompetisi yang terjadi di kalangan elite lama. Empat partai besar (Golkar, PD, Gerindra, dan PDIP) serta dua partai menengah (PKB dan PPP) sebenarnya masih mewarisi pemilahan politik kepartaian peninggalan Orde Baru: kuning, merah, dan hijau. PDIP adalah kubu yang masih solid, yang akan dibayang-bayangi oleh pecahan partai Golkar (Golkar dan Gerindra) plus partai Demokrat. Sedangkan PKB dan PKB yang mewakili kubu Islam berada di papan bawah.

Kompetisi Elite Ahli Waris Orde Baru
Mari kita lihat bagaimana partai-partai warisan Orde Baru itu merancang kandidasi untuk perebutan posisi kepresidenan. Golkar jelas sekali adalah pelanjut par excellence Orde Baru. Baru-baru ini Ketuanya, Abu Rizal Bakri, bahkan menegaskan agar kader-kadernya tidak perlu minder dan justru harus bangga dengan kenyataan itu. Di lain kesempatan, Ical juga pernah mengatakan akan melanjutkan ‘Trilogi Pembangunan’ jika ia terpilih jadi presiden.
Pendiri Partai Demokrat, Presiden SBY, juga adalah salah seorang jenderal Orde Baru. Di luar politisi Golkar yang pecah dan mendirikan partai-partai kecil – misalnya Hanura, Gerindra, PKPI, dan Nasdem – Partai Demokrat belakangan digunakan oleh SBY untuk membangun dinastinya sendiri. Ini terbukti ketika ia mencongkel Anas Urbaningrum dan merebut posisi sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina partai; serta menempatkan anaknya, Ibas, sebagai Sekjennya. Belakangan adik ipar SBY, Jenderal Edhie Pramono Wibowo, dianggap sebagai pilihan SBY untuk memenangkan konvensi partai dan menggantikannya jadi Presiden.
Dinasti lain ada di PDIP. Sejauh ini Megawati masih terus mempertimbangkan dirinya atau putrinya, Puan Maharani, untuk didampingi atau mendampingi Jokowi. Sebagai tokoh pengatrol suara partai, posisi Jokowi sangat menentukan untuk mencegah kemerosotan perolehan suara PDIP. Itulah yang membuat harga tawar Jokowi sangat tinggi untuk posisi sebagai calon Presiden. Tapi dalam dua kemungkinan, tidak ada jaminan bahwa jika Jokowi naik dinasti Soekarno akan tetap dipertahankan; begitu juga sebaliknya apakah Jokowi bisa didikte terus menerus oleh Megawati.
Di urutan berikutnya, Gerindra, sudah mencalonkan ketuanya Prabowo Subianto sebagai calon Presiden. Berbagai survei menyebutkan, dibandingkan Ical atau Edhie Pramono, Prabowo jauh lebih populer. Tetapi popularitas Prabowo yang didukung oleh mesin partai yang bekerja cepat, tetap akan dibayang-bayangi oleh masa-lalunya sebagai jenderal Orde Baru dengan berbagai kasus pelanggaran HAM.
Terakhir, PPP dan PKB adalah kekuatan politik yang terus mengalami kemerosotan sehingga manuvernya makin terbatas untuk berbagai bargaining. Kemungkinan besar mereka bahkan mengalami kesulitan dalam berbagai negosiasi koalisi karena suaranya yang kecil.
Alhasil, apa yang sesungguhnya terjadi adalah perebutan kekuasaan di kalangan elite lama. Kehilangan patron besar tunggal yang menjadi protektor mereka di masa lalu, kini mereka saling berlomba untuk merebut posisi tertinggi itu. Oligarki pasca Orde Baru sama sekali tidak mengubah dasar-dasar kehidupan politik patronase yang telah dibangun Suharto selama tiga dasawarsa.
Menuju Politisasi Gerakan Putih
Seperti disebutkan Max Lane, praktek politik demokrasi elitis yang sepenuhnya dikuasai elite lama itu telah membuat rakyat kebanyakan mengalami alienasi. Kenyataan ini bisa dilihat secara kasat mata. Masyarakat luas makin menyadari bahwa pemilu hanya menjadi ajang para politisi korup untuk mendulang suara. Selama tiga kali periode elektoral (1999-2004, 2004-2009, 2009-2014), mereka menyaksikan praktek demokrasi semakin elitis, semakin jauh dari kepentingan rakyat.
Dengan persepsi yang meluas ini, pemilu – bahkan demokrasi – dianggap tidak relevan dengan masalah kehidupan sehari-hari mereka. Mereka juga menyaksikan bahwa para politisi partai – yang berkolaborasi dengan birokrasi yang juga korup, dan kekuatan modal yang rakus dan agresif – ternyata hanya memanfaatkan demokrasi untuk menumpuk kekayaan dan menguber kekuasaan. Dalam pandangan mereka demokrasi mengalami malfungsi, karena telah disalahgunakan. Inilah yang bisa menjelaskan dua fenomena penting dalam demokratisasi Indonesia selama ini: pembajakannya oleh elite di satu pihak, dan apatisme publik di pihak lain.
Bagaimanakah mengubah agar alienasi ini tidak berlarut-larut menumpuk menjadi ledakan yang destruktif? Bagaimanakah membuat pasivisme politik yang melumpuhkan ini mengalami transformasi menjadi gerakan publik yang kreatif dan secara politik signifikan?
Merebut kembali demokrasi dari tangan elite oligarkis adalah skenario besar yang harus dipikirkan agar golongan putih punya imaginasi mengenai tujuan mereka melakukan politisasi gerakannya. Kita tidak boleh membiarkan demokrasi hanya dipakai sebagai sarana kompetisi elite untuk berebut kuasa sesama mereka sendiri. Demokrasi harus dikembalikan pada tujuan dasarnya untuk membangun sistem politik di mana rakyat menjadi berdaulat untuk mengurus dirinya sendiri; di mana kehidupan publik bisa dijaga dan dikembangkan oleh publik sendiri.
Imaginasi bahwa melalui demokrasi publik bisa bangkit itulah yang selama ini hilang dalam benak orang banyak. Menghidupkan kembali ruang publik untuk kepentingan publik menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali partisipasi publik. Partisipasi publik inilah persisnya yang selama ini absen dalam kehidupan demokrasi kita. Pada kenyataannya ruang-ruang publik kita justru telah dikuasai demi kepentingan mengejar profit atau memperbesar pengaruh politik oleh kepentingan-kepentingan yang sifat non-publik. Dengan kata lain, privatisasi ruang publik telah membuat publik terasing dari kehidupan publik.
Karena itu, bagaimana menjadikan kelompok-kelompok masyarakat mempunyai komunitas-publiknya masing-masing, berinteraksi dengan kelompok-kelompok lain di ruang-publik yang terbuka dan egaliter, untuk membahas isu-isu publik secara bersama, itulah yang perlu dirumuskan sebagai strategi politisasi gerakan politik putih.
Menolak pemilu adalah jalan pertama untuk membangun imaginasi baru mengenai demokrasi popular, demokrasi kerakyatan, demokrasi partisipatoris, demokrasi deliberatif. Apa yang kita kenal sekarang sebagai demokrasi elektoral-elitis itu pada hakikatnya bukan demokrasi, tetapi oligarki dan plutokrasi. Di banyak tempat lain, demokrasi model representatif yang diwakili partai-partai juga sedang mengalami krisis. Gagasan ‘perwakilan’ itu sendiri kini telah kehilangan makna karena partai-partai politik lama ternyata hanya bekerja demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kekuatan-kekuatan korporat yang berada di belakangnya. Semua praktek demokrasi yang seperti itu kini sedang digugat – sebuah gejala yang sebenarnya juga sedang menguat di di Indonesia.
Demikianlah, penguatan gerakan golongan putih harus diarahkan kembali untuk memperkuat keterlibatan dan partisipasi dalam kehidupan publik; dan dalam jangka panjang mentransformasikan demokrasi-representatif-elitis-yang-eksklusioner-dan-anti-publik menjadi demokrasi-delegatif-emansipatoris-yang-melibatkan-publik.
Dalam konteks itulah, adalah penting membangkitkan kesadaran publik untuk terus melakukan kontrol terhadap praktek politik demokrasi Indonesia. Dengan tema membongkar praktek demokrasi elektoral oligarkis, kelompok-kelompok democracy watch-dog itu harus bekerja ke arah tujuan-tujuan di atas, sambil: menciptakan imaginasi baru, diskursus baru, dan praktek alternatif untuk lahirnya demokrasi yang lebih susbstansial, yang melibatkan semua kekuatan sosial-politik yang tumbuh secara otentik dari kepentingan masyarakat banyak. Basisnya adalah delegasi-delegasi publik dengan kepentingan-kepentingan publiknya masing-masing.
Krisis Demokrasi Liberal di Tingkat Global: Relevansinya dengan Politisasi Golput
Eksperimen agar kekuatan publik bangkit dan menjadi basis politik baru dewasa ini sebenarnya juga sedang berlangsung di berbagai belahan dunia. Krisis demokrasi liberal bahkan sedang melanda negara-negara dengan sistem demokrasi yang sudah mapan. Demokrasi politik liberal yang bersekutu dengan ekonomi kapitalis neoliberal telah menciptakan krisis partisipasi publik. Diadopsinya ideologi neoliberal untuk mentransformasi seluruh bangunan relasi-relasi sosial menjadi pasar-bebas telah membuat warganegara mengalami depolitisasi, mengubah political-citizen menjadi sekadar economical-consumers. Peranan politik warganegara dengan sengaja dilucuti untuk mengeliminasi potensi kritisnya terhadap tatanan yang berlaku.[8]
Sementara itu persekutuan liberalisme politik dengan neoliberalisme ekonomi juga telah menciptakan akibat yang meluas di mana negara-negara dipreteli peran publiknya. Dalam doktrin politik demokrasi liberal, peran publik negara memang seharusnya diminalkan begitu rupa karena kepentingan publik akan diurus oleh mekanisme pasar. Tetapi doktrin ekonomi neoliberal yang dibangun dengan imaginasi bahwa dunia harus menjadi pasar-global telah membuat negara-negara akhirnya hanya menjadi agen-agen lokal bagi kepentingan korporasi-korporasi finansial global. Begitu krisis kapitalisme terjadi dalam skala dunia, maka akibat langsungnya secara telak juga akan menimpa setiap negara. Inilah yang menjelaskan mengapa krisis finansial global yang terjadi sejak 2008, telah membuat negara-negara demokrasi kapitalis juga langsung kolaps.
Di Eropa Selatan misalnya, tiga tahun lalu PM Yunani bahkan diganti oleh sebuah badan yang mewakili kepentingan IMF. Negara-negara nasional tunduk oleh dikte korporasi finansial global. Krisis ekonomi Spanyol dan Italia memaksa pemerintahnya menerapkan kebjakan ‘economic-austerity’ yang sangat ketat – meningkatkan pajak dan mencabut semua subsidi – di tengah-tengah bangkrutnya perusahaan-perusahaan dan meluasnya pengangguran. Semua ini membuat rakyat Eropa marah, sementara partai-partai politik tidak bisa melakukan apa-apa. Melalui apa yang disebut gerakan ‘indignados,’ masyarakat Eropa Selatan kini bangkit melawan demokrasi kapitalis. Mereka menginginkan terjadinya perombakan struktur ekonomi-politik yang selama ini didikte oleh lembaga-lembaga finanasial global. Gerakan seperti ini pula yang sedang terjadi di Irlandia, Ukraina, Bulgaria, Boznia-Herzegovina, dan lain-lain.
Di Timur Tengah, di mana otoritarianisme bersekutu dengan, atau didikte oleh, negara-negara kreditor Barat yang menjadi agen IMF atau Bank Dunia, krisis kapitalisme global yang sama telah melahirkan apa yang disebut ‘Arabellion’ – sebuah revolusi yang memuncak di lapangan Tahrir (Cairo) dan menjungkalkan Hosni Mubarak. Bahkan rezim-rezim di bawah partai Islam moderat seperti di Turki juga telah membuat rakyat marah di lapangan Taksim (Istanbul), karena kebijakan-kebijakan neoliberalnya. Hampir pada saat yang bersamaan, perlawanan publik seperti itu juga terjadi di Brazil atau Argentina, seperti pada gejolak yang disebut gerakan ‘horizontalidad.’ Gerakan ini meledak ketika rakyat berbondong-bondong untuk merebut kembali ruang-ruang publik dan menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan-kebijakan pasar bebas yang menyengsarakan.
Mengapa persekutuan demokrasi liberal di Indonesia dengan kebijakan ekonomi neoliberal yang bergitu agresif diterapkan sejak naiknya SBY, belum juga menimbulkan akibat yang sama dengan yang terjadi di tingkat global itu? Sampai kapan kita masih akan terus membiarkan rezim predatorial pasca Orde Baru ini menjadi makin destruktif dan menghancurkan lingkungan alam dan lingkungan kehidupan sosial kita? Sampai kapan kita akan bersikap apatis terhadap partai-partai korup yang bersekutu dengan birokrasi yang juga korup terus memfasilitas berbagai kejahatan korporatis di bawah dukungan negara neoliberal yang tak lain merupakan kaki tangan World Bank dan IMF ini? Apakah momentum perlawanan rakyat masih belum tiba?
Sambil menunggu matangnya situasi, ada baiknya kita memproyeksikan bahwa satu-satunya kemungkinan munculnya perlawanan itu akan datang dari korban, yakni publik politik Indonesia sendiri. Publik yang sadar politik harus dibangkitkan agar semakin tumbuh menguat. Dan seperti kita lihat pada semakin membesarnya jumlah golongan putih, modal politik kita adalah sikap oposisi mereka kepada partai-partai politik dan penyelenggara kekuasaan korup lainnya.
Dengan proyeksi seperti itu, kemungkinan-kemungkinan memperluas basis gerakan politik putih perlu mempertimbangkan agenda-agenda di bawah ini:
- Mengembangkan kekuatan publik melawan kelompok-kelompok plutokratik yang menguasai negara.
- Mencetuskan gerakan spontan solidaritas horisontal, bukan melalui komando hirarkis kepartaian yang bersifat vertikal
- Membangun eksperimen-eksperimen demokrasi langsung untuk menciptakan alternatif atas demokrasi representatif
- Memperluas eksperimen untuk terciptanya proses-proses politik deliberatif menyangkut berbagai isu publik, bersandar pada aspirasi lokal, otonomi publik, dan perluasan partisipasi lintas-sektoral
- Mengembangkan gerakan pengembangan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial lokal yang bersifat poliarkis.***
Penulis adalah peneliti dan pengamat masalah demokrasi dan kebijakan publik.
[1] Max Lane, ‘Who Will Be Indonesian President in 2014?,’ ISEAS Perspective, 18 July 2013, Singapore.
[2] Angka persis DPT 2014 yang ditetapkan KPU adalah 186.612.255 pemilih. Keputusan ini diumumkan KPU pada 4 November 2013.
[3] Perkiraan ini dikemukakan dalam sebuah diskusi di PVI (Jakarta), 1 Agustus 2013.
[4] Max Lane, op.cit, p. 4.
[5] Sebagai catatan, perlu disebutkan bahwa keseluruhan perhitungan di atas diasumsikan menggunakan model rekapitulasi KPU, yakni didasarkan pada jumlah suara sah. Jika digunakan persentase atas dasar jumlah total DPT (daftar pemilih tetap), maka perolehan riel partai-partai itu tentu lebih kecil daripada yang digambarkan.
[6] The Jakarta Post, ‘The Year Oligarchs try to Steal Democracy from the People,’ 27 January 2014.
[7] Suara Pembaruan, 23 Februari 2014.
[8] Charles Taylor, ‘The Depolitization of Politics,’ Eurozone, 2014 – http://www.eurozine.com/articles/2011-11-10-sierakowski-en.html





