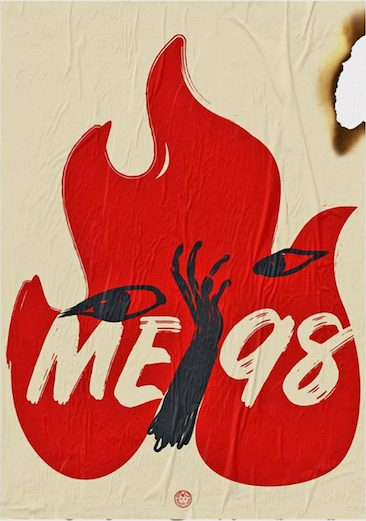Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)
LEDAKAN bom di Surabaya pada 13 Mei 2018 membuka kembali ingatan 20 tahun lalu di Jakarta. Persis 13-14 Mei 1998 api membara dan asapnya membumbung memenuhi udara Jakarta. Orang berteriak-teriak. Gaduh. Api penanda sebuah kekacauan massal sedang berlangsung sangat cepat dan massif. Di balik kekacauan massal itu terjadi kekerasan seksual secara massal pula terhadap perempuan-perempuan Tionghoa di Jakarta Barat dan Utara. Kejadian ini, yang didahului kejadian sebelumnya, yaitu krisis ekonomi, penculikan dan penembakan mahasiswa, dan kejadian-kejadian sesudahnya yang berwujud kekerasan, kiranya menjadi titik pijak konsolidasi gerakan perempuan di seluruh Indonesia.
Itu suasana duapuluh tahun yang lalu. Suasana dimana kebanyakan orang “menunggu” datangnya reformasi, dan pada sisi yang lain aktivis-aktivis berupaya untuk menggulingkan rezim otoritarian Orde Baru untuk menyingkap fajar reformasi. Duapuluh tahun kemudian, ada banyak kegiatan berupa diskusi dan seminar di Jakarta bertajuk “20 tahun reformasi” —-dimana narasumbernya adalah politisi-politisi laki-laki maupun pengamat politik laki-laki, dan tentu saja tidak ada yang mengaitkan reformasi dengan perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual pada Kerusuhan 13-14 Mei 1998. Memperbincangkan mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998 sebagai presiden dan gagasan reformasi untuk proyek demokrasi sangat terasa sebagai perbincangan patriarkis yang mengenyampingkan peranan perempuan dan ibu di dalamnya.
Dalam momen 20 tahun reformasi ini, ijinkan saya membuka kembali catatan tentang gerakan perempuan di Jakarta. Saya menegaskan konteks Jakarta agar tak mereduksi aksi-aksi gerakan perempuan di daerah-daerah di sekitar reformasi.
Reformasi Menurut Politik Perempuan
Kata reformasi tampaknya jarang ditelusuri kembali. Saya tidak tahu siapa yang pertama kali melontarkan kata reformasi massa pada saat itu. Yang jelas reformasi menjadi wacana dominan untuk membalik Soeharto dan Orde Barunya. Kalangan gerakan perempuan di Jakarta pun menggunakan kata reformasi —menurut tafsir saya– sebagai sarana untuk mengubah relasi perempuan dan negara. Telah banyak ulasan yang menunjukkan bapakisme-negara Orde Baru membungkam politik perempuan, dan menempatkan peran perempuan hanya sebagai koncowingking (pasangan bapak yang berperan di garis “belakang”, yaitu ranah dapur, kasur dan sumur) pendukung politik bapakisme-negara. Relasi perempuan dan negara seperti itu diwujudkan dalam organisasi isteri, yaitu Dharma Wanita (untuk isteri PNS), Dharma Pertiwi (untuk isteri ABRI) dan PKK (isteri non PNS dan nonABRI). Organisasi isteri ini tentu tidak mempunyai visi politik tentang pembebasan perempuan, kesetaraan dan keadilan.
Lalu apakah reformasi?
Merujuk pada tulisan Karlina Supelli 20 Tahun Reformasi: Majukah Rasionalitas dan Budaya Ilmiah Kita?[1], kiranya membantu pemahaman saya tentang reformasi. Dalam tulisannya itu Karlina Supelli menelusuri asal muasal dan perkembangan kata reformasi, yang mulanya diucapkan oleh Ovid, seorang penyair Romawi (43 SM – 17/18M) dalam karyanya Metamὁrphὂses. Ovid menggunakan kata reformatio untuk memaknai tindakan “membentuk ulang” segala sesuatu yang menjadi wujud yang sama sekali berbeda dari wujud semula. Lebih jauh, seperti ditulis oleh Karlina Supelli, Ovid memaknai “membentuk ulang” sebagai terjemahan dari Yunani metamὁrphὂsis (meta = sesudah atau melampaui, mὁrphẽ = bentuk). Artinya reformasi berarti perubahan ataupun peralihan bentuk. Ovid menggunakan kata reformatio untuk menceritakan tentang Narcissus yang konon tampan dan menolak setiap cinta yang datang padanya. Sikap Narcissus itu mungkin kurang menyenangkan dewa-dewa, sehingga Narcissus dikutuk berbalik jatuh cinta habis-habisan kepada dirinya sendiri setelah melihat wajahnya di permukaan air danau. Cerita Narcissus ini ditujukan sebagai kritik Ovid kepada kaisar Augustus (63 SM -14 M) yang melakukan perubahan tata hukum dan moral dengan menghidupkan kembali ritual keagamaan dan moralitas Romawi klasik[2].
Kata reformasi dalam perkembangannya banyak dipergunakan, termasuk Reformasi Protestan abad 16. Walau bertambah makna sejalan perkembangannya, substansi kata reformasi adalah kata re yang artinya kembali ke awal.[3] Maka saya bertanya: gerakan perempuan ingin kembali ke pijakan historis yang mana? Apakah mandat Kongres Perempuan 22 Desember 1928 atau Proklamasi 17 Agustus 1945?
Apabila gerakan perempuan ingin kembali pada pijakan historis 22 Desember 1928, maka saya akan merujuk pada pidato Siti Soendari mengenai “Kewajiban dan Tjita-tjita Poeteri Indonesia”. Diwarnai oleh semangat Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928, Siti Soendari mengimaginasikan Indonesia seperti sebidang taman bunga yang luas sekali.
Dalam pandangan kami tergambarlah Indonesia seperti sebidang taman boenga jang loewas sekali….Pandanglah Indonesia sebagai keboen yang ditjipta-tjiptakan. Ingat poelalah bahwa taman itoe tiada akan selamat sempoerna, kalau yang toemboeh hanja kembang melati….Boekankah yang kita kehendaki hendak memboeat boenga rampai jang haroem baoenya….?[4]
Pidato Soendari itu menegaskan bahwa rumah Indonesia itu memungkinkan semua yang bermukim di dalamnya tumbuh dan mekar bersama. Artinya perempuan pun berhak tumbuh bersama laki-laki. Adapun negara sebagai taman bunga menciptakan iklim egaliter agar perempuan dan laki dapat tumbuh bersama.
Maka politik gerakan perempuan mengenai reformasi adalah mengubah bapakisme-negara (bapak sebagai patriakh negara) menjadi taman bunga (fasilitator). Mengubah dominasi negara terhadap perempuan menjadi egaliter terhadap perempuan. Itu sebabnya gerakan perempuan mempunyai agenda sejalan dengan gerakan prodemokrasi untuk mengakhiri rezim otoritarian yang dipimpin oleh Soeharto.
Aksi-aksi Perempuan Pra-1998
Rekonstruksi gerakan perempuan pra-reformasi saya himpun berdasarkan penanda-penanda aksi perempuan lintas organisasi sebelum 1998. Gerakan perempuan pada masa itu terpusat pada NGO perempuan –sebagai wadah feminis generasi awal yang melawan Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi. Gerakan perempuan itu membentuk koalisi yang diberinama Koalisi Perempuan, lalu sesudah Soeharto turun pada 21 Mei 1998, nama Koalisi Perempuan diubah menjadi Koalisi Perempuan Indonesia untuk Demokrasi dan Keadilan (KIPD).
Konsolidasi gerakan perempuan ke dalam gerakan prodemokrasi diawali pada saat majalah Tempo, Editor dan tabloid Detik dibredel oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Menteri Penerangan Harmoko pada 1994. Pembredelan itu berkaitan dengan pemberitaan tentang pelipatgandaan harga pembelian kapal perang dari Jerman. Kejadian itu ternyata menghimpun solidaritas dan konsolidasi pelbagai macam organisasi prodemokrasi, termasuk NGO-NGO perempuan di Jakarta. Lalu menguatnya kontrol terhadap pers melahirkan pers alternatif yang saat itu berkembang subur sebagai media propaganda dan komunikasi. Kalyanamitra –salah satu NGO perempuan di Jakarta—juga menerbitkan pers alternatif khas feminis yang diberinama Mitra Media. Rupanya pers alternatif dianggap sebagai ancaman bagi rezim hingga Harmoko melakukan pembredelan terhadap pers alternatif, termasuk Mitra Media.
Sebagai penanda waktu dan kejadian, pembredelan pers berdampak mengonsolidasi NGO-NGO Perempuan, bahkan juga di luar Jakarta, untuk menuntut demokrasi. Kata demokrasi merdu dikumandangkan sebagai tuntutan bersama melawan patriarki militer di bawah pimpinan Presiden Soeharto.
Penanda kedua muncul di tengah krisis ekonomi yang popular disebut krisis moneter pada 1996. Bagi perempuan, suasana krisis ekonomi itu ditandai oleh beredarnya isu terhadap kelangkaan sembako. Hanya dalam sehari hampir semua ibu-ibu yang bekerja (juga bapak) meninggalkan kantor dan menyerbu supermarket untuk belanja sembako secara besar-besaran. Dalam satu hari itu pun supermarket kehabisan sembako. Tetapi rumah tangga-rumah tangga kelas “bawah” dan miskin kota tidak mampu belanja besar-besaran, hingga mereka tidak kebagian sembako, termasuk susu untuk anak-anak. Suasana itu mendorong aktivis perempuan membentuk Suara Ibu Peduli. Cukup menarik bahwa organisasi ini merupakan himpunan pelbagai perempuan dan aktivis NGO perempuan. Gerakan ini menanggapi krisis sembako dengan mengupayakan pengadaan susu murah. Sejalan dengan itu beberapa NGO perempuan, termasuk Kalyanamitra dan Tim Relawan untuk Kemanusiaan Jakarta (selanjutnya disebut TRK) membentuk koperasi sembako untuk rumah tangga miskin kota.[5] TRK berupaya memutus mata rantai distribusi sembako, belanja sembako langsung kepada petani, dan kemudian menjual dengan harga lebih murah kepada anggota dan keluarga miskin kota di Jakarta Selatan. TRK menjual minyak goring, beras, gula, dan lainnya.
Gerakan untuk memutus mata rantai distribusi sembako dan membentuk koperasi pangan ini cukup menarik. Gerakan perempuan yang didukung oleh gerakan umum ini sesungguhnya berusaha menjawab krisis dalam pemenuhan reproduksi sosial. Dalam pembagian kerja secara seksual dalam rumah tangga, pada umumnya ibu atau perempuan mendapat tanggungjawab sebagai penyedia kebutuhan reproduksi sosial. Maka pembentukan koperasi pangan itu merupakan ide yang sangat signifikan sebagai ekspresi politik perempuan.
Dalam perkembangannya gerakan Suara Ibu Peduli memobilisasi political emotion publik dengan menggunakan simbol susu. Kampanye ini sungguh menggalang solidaritas publik dan memperkuat gerakan melawan rezim otoriter di bawah pimpinan Soeharto. Meski belum ada data yang signifikan, pada saat Pemilu 1997 secara kualitatif ditemukan pernyataan ibu rumah tangga yang enggan memberikan suaranya kepada Golkar sebagai partai berkuasa.
Gerakan Suara Ibu Peduli dan gerakan koperasi sembako kemudian berkembang sebagai pusat-pusat dapur umum yang memproduksi nasi bungkus untuk gerakan mahasiswa, gerakan perempuan dan gerakan apapun untuk reformasi. Gerakan dapur umum (the public kitchen) ini didukung oleh para ibu di Jakarta. Di antara mereka ada yang menyumbangkan tenaganya untuk belanja, memasak, membungkus nasi bungkus, mengirim ke lapangan, termasuk DPR, menghimpun sumbangan dana, obat-obatan dan lainnya. Gerakan Dapur Umum ini sejalan dengan Koalisi Perempuan yang turut menduduki DPR bersama mahasiswa, atau mengadakan rally di jalan-jalan.
Penanda yang ketiga sebenarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan NGO perempuan menangani perempuan korban kekerasan seksual. Dalam catatan saya, NGO perempuan pernah mengusulkan draft RUU Anti Perkosaan pada 1994, dan draft itu tidak pernah digubris oleh pemerintah. Meski pun embrio pembangunan women’s crisis centre mulai tumbuh. Ketika terjadi penyerangan terhadap kantor PDI (27 Juli 1996) di Menteng dan banyak korban berjatuhan, termasuk warga miskin kota di sekitarnya, gerakan crisis centre ini berperan. Gerakan perempuan untuk healing crisis ini bahkan juga berperan menjadi teman (best buddies) bagi ibu-ibu aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang ditangkap dan dituduh sebagai pelaku penyerangan kantor PDI. Kegiatan healing crisis ini berlanjut pada ibu-ibu yang kehilangan anaknya akibat penembakan dalam peristiwa yang disebut Trisakti, Semanggi-1 dan Semanggi-2.
Penanda yang keempat adalah gerakan perempuan melawan militer dan rezim Orde Baru berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa 13-14 Mei 1998. Gerakan perempuan ini melawan pengingkaran militer terhadap fakta adanya tindak kekerasan seksual massal dan penghilangan paksa anggota keluarga miskin kota di mal-mal melalui modus pembakaran. Kejadian Kerusuhan 13-14 Mei 1998 itu memperbesar gerakan mahasiswa dan prodemokrasi hingga meluas ke seluruh Indonesia.
Keempat penanda aksi-aksi gerakan perempuan itu mengekspresikan politik perempuan yang khas, yaitu politik ibu yang melawan krisis ekonomi-politik berlandaskan pada etika kepedulian (ethic of care). Politik perempuan menanggapi krisis dengan kepedulian, dan melawan rezim kekerasan dengan kepedulian pula. Setelah Soeharto mundur pada 21 Mei 1998, KIPD mendesak Presiden Habibie untuk membentuk Komisi Nasional Anti-kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Selain itu juga mendesak Habibie agar meminta maaf kepada korban Kerusuhan Mei 1998, meski kata maaf itu tak pernah diucapkan. Lebih lanjut pada Desember 1998, KIPD menggelar kongres perempuan yang dihadiri 500-an orang di Yogyakarta (di UGM). Mereka yang hadir dalam kongres itu mewakili kelompok kepentingan perempuan seperti lansia, jompo dan penyandang cacat; profesional; pekerja sektor informal; miskin kota; miskin desa; pemuda, pelajar & mahasiswa; perempuan yang dilacurkan; buruh; janda, perempuan kepala rumah tangga & tidak menikah; anak marjinal; petani; nelayan; ibu rumah tangga; dan Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender (LGBT). Kongres itu membentuk wadah yang diberinama Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).
Maka terdapat dua agenda besar politik perempuan Indonesia pada masa itu, yaitu agenda melawan kekerasan terhadap perempuan sebagai agenda hak asasi perempuan, dan agenda kuota 30 persen untuk menaikkan keterwakilan perempuan di parlemen (juga eksekutif). Kedua agenda itu diterima oleh pemerintah. Lalu Kementrian Negara Urusan Peranan Wanita yang mengubah nama menjadi Kementrian Pemberdayaan Perempuan mendukung program women’s crisis centre dan pelayanan satu pintu bagi korban kekerasan seksual. Pelayanan satu pintu itu meliputi ruang perempuan di kepolisian (Polda DKI Jaya). Ruang perempuan di RS Cipto Mangunkusumo dan NGO women’s crisis centre untuk melayani healing crisis.
Apakah Reformasi Terwujud?
Pertanyaan sekarang: apakah reformasi yang diinginkan gerakan perempuan untuk mengubah relasi perempuan dan negara terwujud? Saya harus katakan bahwa reformasi itu terwujud, dalam arti politik rekognisi (pengakuan) negara terhadap agenda perempuan dan gerakan perempuan. Tetapi rekognisi itu belum disertai oleh redistribusi power dan kesejahteraan.
Rekognisi yang membentuk wacana dominan adalah kuota 30 persen bagi perempuan dalam pemilu legislatif. Wacana ini mendorong banyak perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tetapi menjadi aneh bahwa banyak perempuan kemudian menganggap berpolitik adalah ikut berkontestasi dalam pemilu legislatif dan menjadi anggota parlemen. Dalam hal ini saya tidak mempersoalkan jumlah perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif, melainkan wacana tentang representasi perempuan dalam politik itu saja. Dewasa ini sebanyak 30 perempuan terpilih sebagai kepala daerah tingkat 2 (kabupaten) dan walikota pada 2015. Meskipun angka itu belum mencapai kuota 30 persen perempuan, tetapi sekali lagi, ruang politik telah mengakui adanya perempuan.
Selain itu, masalah kekerasan terhadap perempuan juga mendapat pengakuan negara dengan diterbitkannya UU Anti-KDRT, meskipun kemudian kebebasan perempuan diikat kembali dalam UU Pornografi/Pornoaksi. Undang-undang yang terakhir itu bukan lahir dari agenda perempuan, melainkan dari kekuatan konservatif yang berupaya memasukkan norma “ekstremis” berdasarkan agama ke dalamnya.
Secara umum rekognisi terhadap perempuan setidaknya membuka ruang partisipasi kepada perempuan. Tetapi, rekognisi itu masih bersifat kuantitatif. Sebab, partisipasi perempuan dimaknai sebatas kehadiran (presence) tanpa disertai redistribusi power. Redistribusi power berarti perempuan itu mempunyai power untuk mewujudkan pemenuhan kepentingan politik perempuannya. Adapun redistribusi kesejahteraan telah diupayakan oleh negara dalam bentuk jaminan sosial “kartu kesejahteraan”, namun sekali lagi, hal itu belum memenuhi kriteria peningkatan kapabilitas perempuan. Apalagi kapabilitas dalam pengertian Martha Nussbaum yang meliputi 10 aspek, antara lain kehidupan, kesehatan, bodily integrity, senses-imagiantion-thouth, being able to laugh, control over one’s enviromentment, dan lainnya, masih jauh dirasakan perempuan.
Dengan demikian, reformasi itu baru terwujud pada tahap rekognisi politik formal, dan sedikit menggeser dominasi negara terhadap perempuan. Meskipun pergeseran itu terancam kembali oleh gejala menguatnya domestikasi terhadap perempuan oleh gerakan “Islam Politik” atau disebut juga “ekstrimisme Islam”. Adapun rekognisi tanpa redistribusi power dan kesejahteraan belum bermakna reformasi yang substansial, dan karena itu jalan menuju keadilan bagi perempuan masih berupa harapan.
Catatan ini menandaskan pula bahwa praktik demokrasi secara umum, selama 20 tahun, sebatas pengakuan tentang demokrasi tanpa terjadi redistribusi power. Adapun power itu digenggam oleh oligarki politik dan pemilik kapital yang menguasai industri-industri ekstraktif.***
—————
[1] Karlina Supelli, 20 Tahun Reformasi: Majukah Rasionalitas dan Budaya Ilmiah Kita?, sebuah makalah yang disampaikan pada 15 Mei 2018 di Komunitas Salihara, Jakarta Selatan
[2] Karlina Supelli, 20 Tahun Reformasi, ibid
[3] Siti Soendari, “Kewajiban dan Tjita-tjita Poeteri Indonesia”, Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang, Susan Blackburn (ed), (Jakarta: Yayasan Obor & KITLV, 2007)
[4] Siti Soendari, “Kewajiban dan Tjita-tjita Poeteri Indonesia”, ibid hal 56
[5] Cerita tentang gerakan koperasi sembako ini dapat pula dibaca pada Ruth Indiah Rahayu, “The Women’s Movement in Reformasi Indonesia”, dalam Indonesia Uncertain Transition, Damien Kingsbury & Arief Budiman (ed), (Adelaide: Crawford Pubishing, 2001)