Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)
PEMILIHAN gubernur DKI Jakarta 2017 menandakan sebuah perubahan yang signifikan dalam politik Indonesia. Pemilihan yang menghasilkan terpilihnya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI periode 2017-2022 itu, tidak saja memunculkan aktor-aktor dengan kekuatan politik barunya, namun juga mengindikasikan terjadinya perubahan mendasar dalam masyarakat Indonesia.
Pertarungan merebut kursi kekuasaan di DKI Jakarta itu diwarnai oleh pertarungan kampanye politik paling brutal dalam sejarah pemilihan di negeri ini. Taktik kampanye yang dipakai untuk mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang menjadi petahana, lebih tepat dikatakan politik bumi hangus (earth scorched politics). Hasilnya adalah pembelahan politik (political division) yang akan berlangsung sangat lama dan sulit untuk disembuhkan. Pertarungan ini akan membawa dampak sosial dan politik yang berkepanjangan.
Para ahli dan komentator politik mengatakan bahwa kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno terjadi karena munculnya politik populis. Memang, hal terpenting yang muncul dari pemilihan gubernur ini adalah bahwa dia memunculkan gerakan populis. Gerakan ini berkembang sangat cepat dalam masyarakat Indonesia, pun jika Anies Baswedan tidak terpilih menjadi gubernur.
Gerakan ini pulalah yang berhasil mengangkat organisasi-organisasi yang selama ini dianggap sebagai organisasi pinggiran (fringe organizations) menjadi kekuatan arus utama (mainstream). Front Pembela Islam (FPI), misalnya, sebelumnya dianggap sebagai organisasi marjinal, sekarang sudah diperhitungkan sebagai organisasi mapan. FPI adalah organisasi yang menjadi motor demonstrasi besar pada 4 November dan 2 Desember 2016.
Demikian pula organisasi semi resmi seperti Majelis Ulama Indonesia, yang pada awalnya hanya organisasi yang tugasnya menuntun umat Islam dengan fatwa, tiba-tiba menjadi sebuah kekuatan politik yang diperhitungkan. Fatwanya tidak lagi hanya sekadar tafsir teologis tentang moral dan hidup sehari-hari umat Islam. Fatwa-fatwa MUI memiliki bobot politis dan bahkan ideologis.
Adakah sesungguhnya gerakan populis ini? Apakah pemilihan gubernur DKI 2017 ini benar-benar menjadi penanda terjadinya perubahan sosial yang punya implikasi politik di Indonesia di masa depan? Apa yang menyebabkan bangkitnya populisme, yang dalam semua hal menunjukkan kecenderungan kanan dan konservatif ini?
Demo 212: Sebuah Awal?
Saya kebetulan hadir dan menyaksikan langsung demonstrasi besar 2 Desember 2016, yang sekarang terkenal dengan sebutan 212 itu. Satu hal yang paling mengesankan untuk saya adalah partisipan demo ini. Cukup banyak dari para peserta demo adalah kelas menengah Indoneesia. Dari gaya berpakaian dan perlengkapan yang mereka bawa, tampak jelas bahwa kebanyakan peserta bukanlah berasal dari kelas bawah masyarakat kita. Cukup banyak dari mereka adalah
kelas menengah professional Indonesia.
Mereka tidak canggung untuk masuk ke gerai kopi internasional Starbuck. Mereka juga memadati rumah makan cepat saji Amerika, McDonald’s. Telepon genggam mereka kebanyakan adalah Samsung atau iPhone dan umumnya keluaran terbaru. Banyak dari yang pria yang memelihara janggut, berbaju gamis dan bercelana di atas mata kaki. Seluruh perempuan berbusana muslim namun mereka memakai atribut-atribut khas yang menunjukkan kemakmuran kelas menengah perkotaan Indonesia.
Tidak sedikit dari mereka adalah para profesional seperti bankir dan pekerja sektor keuangan yang lain. Sebagian adalah para profesional dengan keahlian khusus yang sangat diperlukan dalam kehidupan mutakhir, seperti programer komputer dan para ahli informatika. Orang-orang seperti ini juga banyak bisa dijumpai di media-media sosial. Mereka adalah orang-orang yang punya kecerdasan memanfaatkan teknologi (tech-savvy).
Di media sosial, saya pernah berjumpa dengan seorang insinyur teknik yang bekerja di sebuah bank nasional. Dia sedang menyelesaikan studinya di program master of business administration (MBA) di sebuah universitas Katolik terkemuka di Amerika. Namun itu tidak menghalanginya untuk memuja Rizieq Shihab sebagai satu-satunya orang yang berani ‘membela Islam.’
Fenomena ini bukan sesuatu yang aneh. Seorang komikus yang bekerja untuk perusahan komik multinasional tidak bisa menyembunyikan ‘kekagumannya’ pada demonstrasi 212, sehingga menyisipkan pesan-pesannya ke dalam komik Marvel yang digambarnya. Seorang teknorat, yang juga seorang akademisi, yang terkenal tidak memiliki perhatian khusus kepada agama kemudian menjadi organisator untuk sebuah gerakan koperasi dengan nama Koperasi 212.
Kehadiran kelas bawah dalam Demo 212 memang tidak bisa dinafikan begitu saja. Mereka juga hadir. Namun, sangat tampak bahwa mereka hadir semata sebagai partisipan. Sangat kentara bahwa demo ini dikontrol oleh kelas menengah. Sangat jelas terlihat bahwa demo itu terorganisir dengan rapi. Semuanya direncanakan dengan baik.
Dalam banyak hal, Demo 212 tampak jauh lebih tertib dan rapi dibandingkan dengan demo tahun 1998 yang menjatuhkan Soeharto dan Orde Baru dari kekuasaan. Jalur logistik mengalir rapi. Tidak tampak peserta demo yang kelaparan atau kehabisan makanan. Nasi kotak dan minuman melimpah ruah. Demikian pula penganan, jajan, air minum kemasan, bahkan obat-obatan untuk sakit ringan.
Yang tentu juga mengesankan adalah soal kebersihan. Kantong plastik sampah berwarna hitam dengan ukuran seragam ada di mana-mana. Sungguh kontras dengan keseharian masyarakat Indonesia yang biasa saya lihat. Dalam Demo 212, orang sungguh mengamalkan kebersihan adalah bagian dari iman.
Tidak bisa disangkal bahwa Demo 212 adalah parade kecintaan pada agama. Mereka yang hadir benar-benar ingin mengekspresikan penolakan mereka terhadap Gubernur Basuki Tjahaya Purnama yang dianggap telah menghina Islam ketika mengutip surah Al Maidah 51. Mereka juga mengungkapkan penolakan untuk dipimpin oleh seorang gubernur yang tidak seiman dengan mereka. Apa yang terjadi dalam Demo 212 adalah sebuah pernyataan politik yang berdasarkan keyakinan keagamaan.
Dari Demo ke Kampanye
Yang juga tidak dapat disangkal adalah bahwa kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kemudian mampu mengkapitalisasi Demo 212 ini menjadi suara pemilih. Kampanye pasangan ini tampaknya disusun oleh strategi dua tombak (two-pronged strategy). Yang pertama adalah kampanye resmi. Di sini Anies-Sandi berusaha tampil bersih. Anies Baswedan berusaha tampil seperti apa yang sejak awal dicitrakan sebagai Anies Baswedan –pluralis, toleran, santun, dan jauh dari rasisme.
Tombak kedua adalah kampanye yang sangat terorganisir rapi lewat jaring-jaring kelompok-kelompok Islam. Kelompok-kelompok inilah yang melakukan semua pekerjaan, baik bersih maupun kotor, untuk melapangkan jalan Anies-Sandi ke kursi gubernur. Kelompok-kelompok ini melakukan mobilisasi lewat pengajian-pengajian serta pengorganisasian lewat mushala dan masjid-mesjid. Kelompok-kelompok ini juga aktif melakukan demonstrasi untuk menuntut agar gubernur petahana dijebloskan ke dalam penjara karena kasus penistaan agama.
Kelompok ini juga melakukan perisakan sosial (social bullying) dan intimidasi terhadap pemilih, khususnya terhadap pemilih Muslim. Kampanye yang memenangkan Anies Baswedan telah berhasil mendefinisikan antara ‘Muslim sejati’ versus ‘kaum munafik.’ Kaum Muslim yang memihak Basuki Tjahaja Purnama adalah kaum munafik. Di beberapa tempat bahkan terjadi insiden bahwa pengurus masjid menolak untuk menshalatkan mereka yang diidentifikasi sebagai pendukung gubernur Basuki.
Strategi seperti ini persis seperti yang disebutkan oleh ilmuwan sosial Uganda kelahiran India, Mahmood Mamdani dalam perang melawan terorisme. Negara-negara Barat, menurut Mamdani, berusaha untuk memisahkan antara ‘Muslim yang baik’ (good Muslims) dengan ‘Muslim yang buruk’ (bad Muslims) dan menciptakan kesan seolah-olah ada perang saudara di kalangan komunitas Muslim antara keduanya. Negara-negara Barat beserta sekutu-sekutunya memaksakan kategori yang mereka bikin sendiri terhadap kaum Muslimin. ‘Muslim yang baik’ adalah mereka yang menjadi Barat, berpikir ala Barat, dan mau menerima semua nilai-nilai Barat. Sementara ‘Muslim yang buruk’ adalah mereka yang menentang Barat dan tidak mau tunduk pada nilai dan kebudayaan Barat. Orang dalam kategori kedua inilah yang dicap sebagai orang yang berbeda (the other), sempalan (fringes), dan otomatis bukan kebanyakan (mainstream). Jika mereka dicap berbahaya maka mereka akan disebut sebagai teroris.
Tombak yang kedua inilah yang sesungguhnya sangat menentukan kemenangan kampanye Anies-Sandi. Kelompok-kelompok yang menjalankan strategi kedua ini lebih bebas melakukan aksi karena mereka seolah-olah partikel bebas yang tidak terkait dengan kampanye resmi. Sehingga kita melihat provokasi, intimidasi, hingga ke perisakan (bullying). Penolakan untuk menshalatkan jenasah mereka yang diketahui mendukung gubernur petahana, misalnya, dalam standar keadaban yang normal sangat sulit untuk diterima. Namun itulah yang terjadi.
Kampanye resmi Anies-Sandi tidak pernah mengutuk atau menyalahkan tindakan-tindakan seperti itu. Namun kampanye ini juga tidak pernah mengakuinya secara resmi bahwa kelompok-kelompok ini adalah bagian dari strategi pemenangan mereka. Sekalipun demikian, seorang pengatur strategi kampanye Anies toh mengakui pemakaian masjid untuk kampanye pemenangan dalam sebuah ceramah yang videonya beredar luas. Dia mengaku bahwa strategi ini dia tiru dari partai Front Islamique du Salut (FIS) atau Front Keselamatan Islam di Aljazair.
Strategi dua tombak ini juga membawa dua narasi berbeda. Yang satu narasi berbunga-bunga tenun kebangsaan. Ia bicara tentang pluralisme, toleransi, dan kemudian keadilan serta pemihakan kepada yang miskin. Sementara ujung tombak yang kedua lebih banyak berbicara tentang Jakarta yang eksklusif untuk Muslim. Dua hal yang sesungguhnya sangat kontradiktif ini bisa berjalan berdampingan sebagai sebuah strategi politik.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana Gubernur Anies Baswedan akan memenuhi janji-janji yang telah diucapkan kelompok-kelompok garis keras ini kepada konstituen yang memilihnya? Bagaimanapun juga, para pemilih ini memilih Anies Baswedan karena pertama-tama dia adalah ‘gubernur Muslim.’ Benarkah dia akan menjadi ‘gubernur Muslim’?
Pertanyaan ini membawa kita para persoalan hubungan antara Anies Baswedan dengan kelompok-kelompok Muslim ini. Anies Baswedan jelas bukan pencipta kelompok ini. Dia juga bukan “pemiliknya.” Dia hanya kebetulan berada di medan pertarungan persis ketika kekuatan ini bangkit. Anies juga tidak mengendalikan kelompok ini. Dia hanyalah seorang politisi yang melihat kesempatan dan memanfaatkannya.
Kekuatan yang menjadi tombak kedua dalam kemenangan kampanye Anies Baswedan ini adalah kekuatan yang saya sebut dengan istilah “populisme Muslim.” Mereka memang memakai Islam sebagai jargon untuk melakukan mobilisasi atau pengorganisasian. Islam juga dimunculkan sebagai alat untuk melakukan klaim politik. Namun, gerakan ini bukanlah gerakan Islam semata. Didalamnya memang ada kelompok seperti Hizbut Thahir Indonesia (HTI) dan beberapa kelompok lain yang ingin menegakkan kekhalifahan Islam. Namun jumlah mereka tidak demikian besar. Sehingga saya lebih suka menyebut seluruh gerakan ini sebagai gerakan populisme Muslim. Ini karena saya ingin menekankan bobot agency dari populisme ini.
Saya tidak menyebutnya sebagai populisme Islam karena alasan yang sederhana saja. Islam menawarkan sebuah ideologi, sama seperti ideologi-ideologi lainnya di dunia. Untuk mereka yang meyakininya, Islam menawarkan sebuah sistem kemasyarakatan dimana ekonomi, politik, dan hubungan sosial diatur. Sementara, populisme adalah sebuah gerakan yang sama sekali tidak ideologis. Kita akan mengkaji persoalan populisme ini lebih jauh di bawah.
Kita perlu menjernihkan terlebih dahulu pengertian populisme dan bagaimana kaum Muslim di Indonesia, khususnya kelas menengah profesional, mendukung gerakan ini. Apa yang terjadi pada kelas menengah Muslim Indonesia? Mengapa mereka mendukung gerakan populis ini?
Populisme: Tanpa Kelas, Tanpa Ideologi
Seperti di banyak negara, Indonesia juga mengalami pasang naik populisme. Pemilihan gubernur DKI Jakarta disinyalir menjadi awal dari sebuah keberhasilan politik dari gerakan populis ini. Keberhasilan ini mungkin akan secara signifikan memengaruhi politik Indonesia ke depan. Gerakan ini juga akan ditiru di daerah lain dan kemungkinan besar juga akan dipraktikkan dalam pemilihan presiden 2019 mendatang. Sangat jelas bahwa pemakaian gerakan populis sebagai sebuah strategi politik tidak akan berhenti di sini. Ia hanyalah sebuah awal.
Populisme bisa diartikan secara sederhana sebagai sebuah gerakan politik dari rakyat biasa untuk melawan kaum elite yang mapan (the establishment). John Judis menyebut populisme sebagai sebuah ‘logika politik,’ sebuah cara berpikir tentang politik, dan bukan sebuah ideologi. Dia mengutip sejarahwan Michael Kazin, yang menggambarkan populisme sebagai sebuah “bahasa yang pengujarnya adalah sekumpulan orang-orang biasa, yang tidak semata-mata diikat oleh solidaritas kelas; yang melihat para elite yang menjadi lawannya sebagai (golongan) yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak demokratis, serta berusaha memobilisasi yang pertama melawan yang kedua.”[1]
Dalam pengertian yang sederhana, populisme adalah gerakan massa-rakyat yang tidak berdasarkan kelas, melawan segelintir elite penguasa mapan dan korup. Penguasa yang tidak demokratis serta hanya mementingkan diri sendiri.
Dalam spektrum ideologis, populisme ada baik di kiri maupun di kanan. Populisme kiri, menurut John B. Judis, biasanya membenturkan rakyat dengan kaum elit. Politik mereka adalah politik vertikal, memainkan antagonism kelas bawah serta kelas menengah dengan kelas atas atau elite penguasa. Populisme kiri berbeda dengan sosialisme atau gerakan sosial demokratik karena tidak menganjurkan penghapusan kapitalisme. Dia juga berbeda dengan gerakan liberal kiri atau progresif yang biasanya berusaha menyelaraskan kepentingan berbagai kelas dan golongan. Judis menyebut populisme kiri sebagai dyadic karena hanya mengeksploitasi pertentangan antara antara massa-rakyat dengan kaum elite.
Sementara, populisme kanan lebih bersifat triadic karena disamping mengeksploitasi pertentangan antara massa-rakyat dengan elite, mereka juga menuduh para elite ini berkolusi dengan pihak ketiga. Para populis kanan membikin narasi bahwa pihak ketiga atau ‘the others’ sebagai pihak yang bertanggungjawab atas segala kesusahan dan kesulitan hidup yang menimpa rakyat kebanyakan. Pihak ketiga itu bisa imigran dan kalangan minoritas lainnya. Populis kanan ini disebut triadic karena “melawan ke atas, namun juga ke samping, ke kelompok-kelompok horisontal.”
Kadang ada juga yang menyamakan kaum populis kanan dengan kaum konservatif. Namun ada perbedaan besar antara keduanya. Konservatisme ada sebuah ideologi yang mendukung kebebasan pasar (kapitalisme) dan menentang peranan negara yang besar dalam mengatur kehidupan pribadi dan masyarakat. Populisme tidak keberatan dengan peranan negara – dan justru memandang bahwa negaralah yang harus direbut karena telah dikangkangi para elite. Populisme juga berbeda dengan konservatisme otoriter (seperti Naziisme) yang berusaha menelikung demokrasi secara subversif. Populisme selalu berjalan dalam kerangka demokrasi. Sekalipun hasilnya mungkin akan meruntuhkan demokrasi itu sendiri.
Populisme adalah gerakan yang ironis. Sementara ia mengutuki para elite mapan, gerakan ini biasanya dimotori oleh kaum elite juga. Mereka memobilisasi massa dengan janji-jani akan meruntuhkan kekuasaan kaum mapan. Mereka menuduh elite yang mapan itu sebagai penghisap kaum kebanyakan. Tidak jarang mereka menjanjikan sebuah ‘revolusi’ untuk menghancurkan kemapanan.
Tidak ada contoh yang paling baik untuk menggambarkan ini selain Donald J. Trump. Dia lahir dengan kelimpahruahan. Tidak pernah dalam hidupnya dia merasakan hidup sebagai rakyat biasa. Apalagi hidup dalam kemiskinan. Sungguh diragukan bahwa dia pernah mengetatkan sekrup atau mengerti bagaimana sebuah obeng berfungsi. Namun, dengan tiba-tiba dia menjadi pahlawan kelas buruh. Dia yang sama sekali buta bahwa roti yang disuap ke mulutnya itu perlu puluhan tahapan dari bibit gandum menjadi roti, mendadak menjadi pahlawan kaum tani.
Itu hanya bisa dilakukan dengan retorika dan janji-janji hebat seperti ‘mengeringkan rawa-rawa’ (draining the swamps) di Washington D.C., memberikan suara kepada kaum tak bersuara (the silent majority), atau mengenyahkan penyakit masyarakat dari penghisap-penghisap yang bercokol di Wall Street, pusat keuangan Amerika dan dunia. Mereka berjanji akan memberi keadilan bagi yang tertindas, pekerjaan untuk para pengangguran, dan tanah untuk petani tuna kisma.
Namun sebagian besar retorika-retorika dahsyat ini berhenti hanya sebagai retorika. Populisme adalah radikalisme tanpa ide-ide radikal. Kemarahan tanpa imajinasi. Ia berjanji untuk menghancurkan sistem yang ada. Namun dia tidak menawarkan sebuah bangunan yang lebih baik untuk menggantikannya. Ia adalah gerakan tanpa visi. Kampanye tanpa program. Atau, perang tanpa jalan keluar.
Tidak seperti sosialisme, populisme tidak menawarkan sebuah masyarakat tanpa kelas dimana semua orang bekerja sesuai dengan kemampuannya dan mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya. Juga dia tidak menawarkan semua orang punya hak untuk mengejar kebahagiaan (pursuing happiness) dengan bekerja secara giat dan kreatif seperti yang ditawarkan oleh kapitalisme. Tidak pula dia menawarkan sebuah masyarakat yang adil dan bahagia di dunia maupun akhirat seperti yang diberikan oleh ideologi agama-agama.
Itu semua terjadi karena populisme adalah gerakan tanpa ideologi. Ia tidak menawarkan ide atau imajinasi tentang bagaimana masyarakat yang sempurna itu. Lalu apa yang membuat orang-orang biasa tertarik pada jargon-jargon populis dan mau menjadi pengikut para pemimpin populis?
Populisme adalah tipuan yang tampak radikal namun tanpa isi dan visi sama sekali. Politisi populis dengan sangat cerdik mengeksploitasi kemarahan dan rasa frustasi dalam masyarakat tapi tidak mampu menawarkan solusi. Mereka menyalurkan kemarahan ini menjadi kebencian kepada ‘yang lain.’ Alih-alih memberikan imajinasi tentang kebahagian dari sebuah masyarakat ideal, para politisi populis memainkan perasaan terancam (insecurity) dari rakyat kebanyakan. Mereka menanamkan ketakutan, bukan harapan. Mereka menyemai kemarahan, bukan kemauan untuk berjuang secara serius. Orang seperti Donald Trump (Amerika Serikat), Neil Farrage (Inggris), atau Geert Wilders (Belanda) sangat pandai memprovokasi kemarahan dan rasa frustasi masyarakat namun tidak menawarkan ide apapun untuk keluar dari persoalan yang membuat rasa takut dan frustasi itu.
Satu-satunya yang mereka tawarkan adalah kebencian, terutama untuk membenci mereka yang berbeda. Itulah sebabnya, para politisi populis sangat mahir memainkan politik identitas. Sebagaimana kita lihat di Eropa, politisi populis menunggang gelombang anti-imigran yang berkembang di masyarakat. Di Amerika, Trump menang dengan jargon-jargon anti-Latino dan anti-Muslim.
Populisme adalah kuman yang menjadi penyakit untuk ideologi-ideologi besar. Ia menjadi kuman untuk kapitalisme seperti yang dilakukan Trump terhadap kapitalisme Amerika. Ia juga bisa menjadi penyakit untuk sosialisme seperti yang dilakukan oleh Jenderal Juan Peron di Argentina dan di beberapa negara Amerika Latin. Ia mencemari ideologi agama-agama seperti membangun semacam populisme Islam.
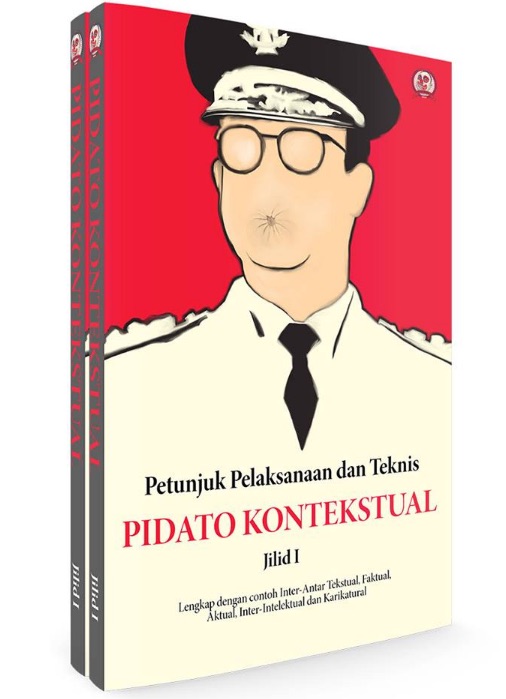 Kredit ilustrasi: Alit Ambara
Kredit ilustrasi: Alit Ambara
Mengapa Populisme Muncul?
Secara singkat, populisme muncul lebih karena perubahan-perubahan dalam hubungan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Tentu klaim seperti ini sangat umum, walaupun memiliki implikasi yang teramat luas. Namun, mau tidak mau, kita harus melihat bahwa perubahan-perubahan mendasar memang telah terjadi pada masyarakat, baik di negara-negara industri
maju dan akibatnya pada bagian dunia yang lain.
Ada beberapa hal yang mungkin harus digarisbawahi di sini. Pertama, sejak runtuhnya Uni Sovyet tahun 1989, ada klaim bahwa sejarah telah berakhir dan kapitalisme adalah pemenangnya. Deklarasi Francis Fukuyama tersebut ternyata membawa implikasi yang sama sekali lain. Uni Sovyet memang runtuh namun kapitalisme pun berubah karenanya.
Kapitalisme modern yang kita miliki saat ini sangat berbeda dengan kapitalisme yang kita kenal pada abad ke-20. Struktur kapitalisme saat ini sangat berbeda dengan yang ada pada abad-abad sebelumnya. Negara-negara yang kita kenal sebagai negara industri pada abad ke-20, telah kehilangan sebagian besar industri manufakturnya. Ekonomi negara-negara ini lebih bergerak ke arah jasa dan sektor keuangan.
Implikasi sosial dan politiknya sangat besar. Mereka yang dahulu bekerja di sektor-sektor manufaktur dengan tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Kota-kota industri, seperti Detroit, menjadi kota yang bangkrut. Pekerjaan manufaktur beralih ke negara-negara dengan upah buruh yang murah dan terus bergerak mencari cara berproduksi semurah-murahnya.
Kedua, akibat perubahan ini adalah menghilangnya kelas buruh dan, sebagai konsekuensinya, melemahnya serikat-serikat pekerja. Hal ini sangat tampak
di Amerika dan Inggris. Ketika kelas buruh menghilang maka kelas menengah pun menghilang. Amerika saat ini dipenuhi oleh cerita-cerita tentang hilangnya ‘the middle America’, yakni mereka yang dulu bekerja di sektor manufaktur dan industri ekstraktif (seperti misalnya pertambangan), menurunnya keanggotaan serikat buruh, dan kebingungan para pemilih partai Demokrat. Pada umumnya, yang terkena adalah mereka berkulit putih dan berdiam di wilayah tengah Amerika. Orang-orang inilah yang pada pemilihan presiden tahun 2016 lalu bertanggungjawab dalam menaikkan Donald Trump ke kekuasaan.
Ketiga, struktur perusahan pada kapitalisme m
odern tidak sama seperti perusahan abad ke-20. Jika dahulu modal dan produksi berjalan secara bersamaan, maka pada perusahan kapitalisme mutakhir modal dan produksi dijalankan secara terpisah. Model produksi seperti Fordisme, dimana pemodal juga menjadi pemilik pabrik, sudah tidak ada lagi. Modal saat ini dikendalikan oleh venture capitalists. Mereka yang memiliki modal, menyebar penanaman modalnya ke banyak tempat dan menuntut return yang setinggi-tingginya.
Dari model ini lahir kelas manajerial yang berusaha untuk berhemat sebesar-besarnya. Para manajer menjadi aset pemodal yang terpenting; bukan para buruh dengan segala macam ketrampilannya itu. Para manajer ini, dalam usahanya mengefisienkan produksi, mendorong investasi di bidang teknologi. Mereka juga memindahkan usaha ke wilayah-wilayah dimana ongkos produksi lebih rendah. Upah buruh dan regulasi (termasuk regulasi lingkungan) menjadi faktor penting dalam melakukan efisiensi. Sehingga tidak heran jika gaji manajer bisa berlipat ratusan kali, sementara upah buruh stagnan atau malah menurun dalam zaman kapitalisme mutakhir.
Semua perubahan ini tidak bisa dihindari di negara-negara maju, baik di Amerika maupun Eropa. Di samping upah yang stagnan, kelas buruh yang mengecil, serikat buruh yang melemah, kita juga melihat ketimpangan pendapatan (income inequality) yang semakin menganga.
Semua kondisi ini menyumbang pada lahirnya populisme. Mereka yang ‘kalah’ (the losers) pada perkembangan kapitalisme mutakhir sangat gampang menjadi man
gsa retorik dari para politisi populis. Pada awalnya, mereka mengarahkan kemarahannya kepada kaum elit, kepada kaum penguasa-penguasa modal di Wall Street, dan kepada para politisi yang berkolusi dengan pemodal. Namun kemarahan-kemarahan itu tidak menampakkan hasil yang nyata. Akibatnya, para politisi populis kemudian masuk dan mengisi kemarahan ini dengan menyasar kepada imigran atau kaum-kaum minoritas lainnya. Rasisme tumbuh dengan subur. Demikian pula narasi-narasi yang nativistik dan bahkan tribalistik. Pada titik inilah populisme kanan mendapatkan ruang gerak politiknya.
Populisme Kanan di Indonesia?
Pada titik ini kita perlu bertanya, apakah populisme dalam spektrumnya yang kanan telah bertumbuh di Indonesia? Secara samar-samar kita memang melihat karakter-karakter yang dimiliki oleh populisme kanan juga telah hadir di Indonesia. Retorika-retorika dengan nada yang sama, yang telah memunculkan populisme kanan di Amerika atau Eropa, juga telah muncul di Indonesia. Secara khusus, ide-ide nativistik seperti pemakaian jargon-jargon ‘pribumi’ dan anti- ‘asing dan aseng’ juga telah menguat.
Seperti yang telah kita lihat, pemilihan gubernur DKI Jakarta 2016 telah menyumbang secara siginifikan pada kemunculan populisme kanan ini. Namun, menurut saya, populisme kanan di Indonesia tidak muncul karena sebab-sebab yang terjadi di negara-negara maju. Kapitalisme Indonesia masihlah kapitalisme jenis erzats (semu), seperti yang pernah diulas oleh Kunio Yoshihara (1988). Kapitalisme jenis ini mengalami rintangan baik secara eksternal (keterbatasan transfer teknologi dan kapital) serta internal (lemahnya dukungan negara, kebijakan affirmative action, kroniisme, rent-seeking behavior, dan dominasi para spekulator). Akibatnya, Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara tidak mampu menjadi ‘negara pembangun’ (developmental states) seperti tetangganya di Asia Timur – terutama Jepang dan Korea.
Di sisi yang lain, Indonesia yang berkelimpahan tenaga kerja juga menjadi pemanfaat dari perpindahan industri-industri manufaktur dari negara-negara maju. Pada tahun 1980-90an, Indonesia menjadi negara indutri ‘tukang jahit’ dengan spesialisasi produksi menjahitkan tekstil serta perakitan aneka ragam produk. Sekarang pun Indonesia masih memiliki industri ini, sekalipun banyak industri sejenis yang membutuhkan teknologi lebih rendah telah pindah ke negara-negara yang menawarkan upah buruh lebih murah seperti Kamboja atau Bangladesh.
Indonesia juga tidak sepenuhnya bergantung pada industri jasa. Sementara, pola industri pun masih lebih ‘tradisional’ ketimbang di negara-negara maju. Venture capitalists memang sudah mulai hadir (ratusan, kalau tidak ribuan, nama pengusaha Indonesia bisa dijumpai dalam Panama Papers, bukan?). Namun ada kecenderungan tradisional bahwa perusahan atau konglomerasi perusahan tetap di tangan pemodal individual beserta keluarganya.
Seperti yang kita lihat bahwa populisme kanan di Indonesia digerakkan oleh kelas menengah bahkan oleh kelas menengah professional. Populisme ini tidak digerakkan oleh kelas buruh dan kelas menengah yang ‘kalah’ oleh bentuk baru industri seperti di negara-negara maju. Jelas kelas menengah Indonesia bukan kelas yang kalah. Populisme kanan justru didukung oleh kelas yang menang dalam ekonomi. Saya melihat tidak sedikit para pemain di sektor keuangan menjadi pendukung yang setia bahkan fanatik figur populis seperti Rizieq Shihab.
Mengapa ini terjadi?
Perlu penelitian yang mendalam untuk memahami tingkah laku politik kelas menengah Indonesia saat ini. Namun, saya kira kita bisa berspekulasi (atau: berhipotesa) tentang hal ini. Untuk saya, ini semua dimulai dengan pembentukan kelas menengah perkotaan dan professional di Indonesia.
Dugaan saya adalah bahwa kelas ini diciptakan oleh perguruan-perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengetahui latar belakang mereka yang masuk ke perguruan-perguruan tinggi terkemuka itu antara tahun 1970 hingga tahun 2000. Rentang waktu selama tiga puluh tahun ini cukup untuk mengetahui latar belakang sosiologis kelas menengah Indonesia.
Beberapa literatur tentang kelas menengah Indonesia selalu menunjukkan peran negara yang besar dalam menciptakan kelas menengah. Artinya, negaralah yang menciptakan kelas menengah. Hipotesis ini tidak pernah benar-benar diuji secara empirik. Namun, saya kira logika yang ada didalamnya tidak sepenuhnya salah. Saya memperkirakan sekitar 50-60 persen dari mereka yang memasuki perguruan tinggi terkemuka di Indonesia antara tahun 1970-2000 adalah anak-anak PNS atau ABRI (TNI/Polri) atau singkatnya pegawai negeri sipil atau PNS.
Jika dugaan ini benar, maka implikasi sosial dan politiknya sangat besar. Pegawai negeri adalah buruh negara. Di masa Orde Baru, buruh negara adalah buruh yang mendapatkan tunjangan (benefits) dan kesejahteraan (welfare) yang paling terjamin. Mereka mendapat asuransi kesehatan, pensiun, bahkan jatah beras dan uang lauk-pauk. Semua tunjangan dan kesejahteraan ini tidak dinikmati oleh buruh yang bekerja di sektor manufaktur, apalagi dinikmati oleh petani.
Namun pegawai negara ini adalah juga golongan yang paling dikontrol oleh Orde Baru. Mereka hanya boleh menjadi anggota satu partai politik (Golkar). Keanggotaan pegawai negeri sangat ketat diawasi. Para pegawai negeri ini tidak boleh memiliki ideologi yang berbeda dengan ideologi yang dimiliki oleh rezim Orde Baru. Sekalipun mereka dikontrol secara ketat, mereka memiliki akses langsung ke dalam kekuasaan lewat Golkar. Mereka bisa menduduki jabatan-jabatan politik (seorang kolonel bisa menjadi bupati; seorang Sekda bisa menjadi anggota DPR atau DPRD, dan lain sebagainya).
Para pegawai negeri inilah, yang jumlahnya bervariasi antara 4-6 juta orang, yang menjadi tulang punggung kelas menengah Indonesia. Sesungguhnya mereka adalah ‘the protected class.’ Negara Orde Baru memberikan kepada mereka semua jaminan sosial dan politik. Mereka harus loyal kepada ideologi Orde Baru dan loyalitas ini akan diganjar dengan aneka macam jabatan – dan dari jabatan-jabatan itulah mereka melakukan akumulasi kekayaan, seringkali dengan jalan illegal. Mereka juga dilindungi dari ancaman kelas bawah, khususnya kelas buruh, yang sering ‘memberontak’ untuk menuntut upah yang layak. Keanggotaan kelas menengah PNS ini diseleksi dengan ketat. Tidak ada orang dengan ide-ide revolusioner yang bisa masuk ke dalamnya. Setiap orang di-screen untuk mengetahui apakah dia ‘bersih lingkungan’ dan tidak ada keluarganya yang menjadi anggota atau simpatisan PKI. Kebijakan diskriminatif pun dilakukan. Tidak ada orang komunis yang boleh menjadi PNS. Demikian pula, tidak ada keturunan Cina yang bisa menjadi PNS.
Anak dan keturunan para pegawai negeri inilah yang sebagian besar masuk ke perguruan-perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Jaminan dan kesejahteraan dari negara telah memungkinan ‘kelas menengah PNS’ ini memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak ini pun mampu masuk ke perguruan-perguruan tinggi lewat persaingan ketat untuk masuk ke dalamnya.
Ketika tamat dari perguruan tinggi, anak-anak kelas menengah PNS ini telah dilempangkan jalannya entah dengan menjadi pegawai negeri atau menjadi professional di perusahan-perusahan nasional maupun asing. Status mereka tetaplah ‘protected class.’ Eksklusivisme keanggotaan mereka tetap terjamin.
Semuanya baik-baik saja hingga terjadi reformasi dan runtuhnya Orde Baru. Tentu, sebagian dari anggota ‘the protected class’ ini ikut serta dalam menjatuhkan Soeharto dan Orde Baru-nya. Namun segera setelah reformasi diinstitusionalisasikan dengan sistem demokrasi, para anggota kelas menengah PNS ini langsung merasakan bahwa proteksi yang selama ini mereka nikmati dari negara juga menghilang. Dulu, negara menjamin bahwa jika Anda bisa menjadi seorang kolonel di dalam ABRI, paling tidak karir Anda akan berakhir menjadi anggota DPRD. Kini, untuk menjadi anggota DPRD, Anda harus masuk partai dan harus mengumpulkan banyak uang untuk ‘membeli kendaraan’ partai.
Tidak terlalu mengherankan kelas menengah yang dulunya selalu dilindungi oleh negara ini dengan segera merasakan kebingungan sosial dan politik (social and political anxiety). Mereka dikalahkan oleh sistem politik demokratis ini. Merekalah yang paling rajin mengeluhkan kegaduhan dari sistem demokrasi ini. Namun mereka juga tidak berdaya untuk meruntuhkannya karena mereka tahu persis bahwa di dalam sistem ini, rakyat yang memiliki suara (sekalipun suara itu bisa dibeli!). Di samping itu, tidak ada yang mampu menyatukan mereka seperti dulu Soeharto memanipulasi militer untuk menjadi kekuatan perekat dan kontrol untuk rezim Orde Barunya.
Dalam kondisi ini, satu-satunya yang mereka andalkan adalah agama. Untuk para kelas menengah ini, agama tidak saja menjadi semacam pelarian (escapism) namun juga kekuatan. Seperti pernah dikatakan Presiden Obama tentang orang-orang ‘middle America’ yang mengalami kebingungan sosial sehingga mereka menjadi pemeluk teguh agama mereka (cling to their religion).
Untuk kasus Indonesia, masuk akal bahwa situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh politisi populis kanan. Merekalah yang mengisi kebingungan ini dengan kemarahan dan kefrustasian. Jika diperhatikan, sebagian besar retorika para agitator populis kanan ini selalu berusaha menumbuhkan perasaan sebagai korban dari para pendengarnya. Perasaan sebagai korban ini memperdalam kefrustasian dan kemarahan pendengarnya.
Sama seperti di tempat-tempat lain, para politisi dan agitator populis kanan tidak menawarkan ide atau imajinasi apapun untuk keluar dari rasa frustasi dan kemarahan ini. Jika diperhatikan dengan seksama, ada hal-hal mendasar yang hilang. Seperti misalnya, soal keadilan sosial sama sekali absen dari retorika kaum populis kanan.
Pada masa Orde Baru, misalnya, orang akan bicara keadilan sosial dengan berbicara tentang kekuasaan para konglomerat. Dari sini akan terbentuk pembicaraan tentang kolusi, korupsi, dan nepotisme yang menyekutukan para konglomerat ini dengan keluarga Soeharto. Di masa sekarang ini, yang muncul pada retorika para politisi dan agitator populis kanan adalah ‘aseng,’ sebuah sebutan yang sangat umum (general) dan menghina (derogative) kepada golongan Cina Indonesia.
Penutup
Akankah gerakan populisme kanan ini berhasil menjadi kekuatan politik arus utama di Indonesia? Saya tidak terlalu optimis. Kalau boleh membuat perkiraan, saya kira, persoalan kelas menengah PNS yang dulu sangat dilindungi ini adalah persoalan sebuah generasi. Sialnya, generasi itu adalah generasi saya – generasi yang lahir, besar, dididik, dan bekerja sepenuhnya di bawah perlindungan Orde Baru. Saya kira, problem ini akan menghilang seiring dengan punahnya generasi saya ini.
Ke depan yang muncul adalah sebuah generasi milennial dengan kehidupan sosial dan persoalan-persoalannya sendiri. Tentu mereka akan membikin landscape sosial dan politik yang berbeda.
Terakhir, apakah strategi populisme kanan seperti yang terlihat di Jakarta bisa direplikasi di tempat-tempat lain di Indonesia? Dalam hal ini, saya juga tidak terlalu optimis. Jakarta pada pemilihan umum tahun 1950an (periode Demokrasi Liberal) dikuasai oleh partai-partai Islam. Pada jaman Orde Baru, partai Islam yang berbendera PPP (Partai Persatuan Pembangunan) menang di Jakarta.
Namun bukan berarti populisme kanan akan enyah dari politik Indonesia. Saat ini, para politisi sedang mengasah isu-isu ‘pribumi’ sebagai isu politik masa depan. Tentu kita tunggu ‘kreativitas’ mereka dalam menggodok imajinasi pribumi dan menerjemahkannya menjadi isu politik. ***
—————
[1] Lihat juga John B. Judis (2016), The Populist Explosion. How the Great Recession Transformed American and European Politics, New York: Columbia Global Report. p. 14.






