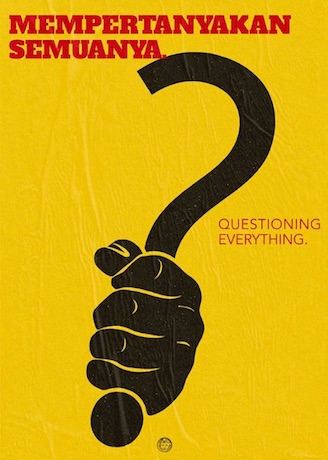Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)
PENGETAHUAN itu politis. Baik dari jalur Michel Foucault dan Georges Canguilhem (tradisi epistemologi kritis Prancis) maupun dari tradisi Sosiologi Pengetahuan Jerman (Karl Mannheim), kita mendapatkan tesis yang kebenaran historisnya nyaris tak terbantahkan itu: keterkaitan antara politik dan pengetahuan (knowledge) dan/atau ilmu-ilmu pengetahuan (sciences). Tak ada pengetahuan, a priori maupun a posteriori, teoretis maupun praktis yang tidak politis. Hal ini karena satu alasan: karena netralitas ilmu adalah ilusi. Sekali lagi, netralitas, bukan objektivitas. Ilmu dapat objektif, tetapi ia tidak pernah netral. Ia mesti berpihak, atau mengimplikasikan keberpihakan. Ilmu dapat dihasilkan dari proses-proses yang objektif, memenuhi standar penelitian tertentu yang memadai, atau merujuk kepada data-data tertentu yang dapat dikonfirmasi kebenarannya. Tetapi objektivitas itu tidaklah netral. Ia berpihak, secara langsung atau tak langsung.
***
Kepada apa, atau siapa, ilmu pengetahuan berpihak? Dalam teropong kekinian, jawabannya tak luput dari dua hal: kepada pihak yang berkuasa (ruling class) atau pihak yang dikuasai (the ruled). Dari Marxisme kita belajar bahwa pihak yang berkuasa merupakan kelas yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan corak produksinya di tengah masyarakat, yaitu corak produksi kapitalis (CmoP, capitalist mode of production). Pihak yang berkuasa bukan sekadar penguasa secara individual, tetapi sekumpulan agregat kepentingan dari kekuatan-kekuatan yang hidup dari diferensiasi kelas di tengah masyarakat, sekaligus yang menikmati penghisapan dan eksploitasi kerja dari kelas-kelas di bawahnya. Mereka, terlebih, adalah kekuatan kelas kapitalis. Kelas yang berkuasa ini, agar terus eksis, mensyaratkan skema reproduksi dalam segala lini: dari reproduksi barang (komoditas) hingga reproduksi relasi-relasi sosial (prestise/gengsi, gelar, dst.) yang penting untuk menjaga bangunan eksploitasi ini terus tegak.
Di mana ilmu pengetahuan terletak? Ilmu pengetahuan merupakan hasil dari produksi, yakni produksi ilmiah dari sekelompok ilmuwan tertentu dan kaum intelektual yang berkecimpung di dalamnya. Produksi ilmiah ini, di dalam masyarakat kapitalis, tentu berada di dalam skema reproduksi dari kelas yang berkuasa. Dalam hal ini, produksi ilmiah berada di antara reproduksi komoditas dan reproduksi relasi sosial. Ia memiliki dua-duanya, atau merupakan dua-duanya. Untuk itu, kelas kapitalis merekayasa suatu pola agar ilmu dapat menghidupi dan berkontribusi bagi kepentingan kelasnya, yaitu akumulasi nilai surplus (surplus value) yang memungkinkan kelas ini mendapatkan kenikmatan-kenikmatan hidup dalam bentuk uang, waktu senggang, dan kebebasan, sementara kelompok-kelompok lain bekerja untuknya – dan tentu saja memungkinkan kelas ini mempertahankan perusahaan atau lembaga-lembaga profitnya untuk tetap eksis. Ditemukanlah suatu pola yang dapat disebut “industri ilmu”, di mana pengetahuan merupakan komoditasnya, kaum ilmuwan sebagai tenaga kerjanya, dan relasi-relasi sosial di antara komunitas ilmiah sebagai relasi sosial untuk menaiki “tangga karier” di dalam industri ini. Inilah pabrik dari mana ilmu dihasilkan untuk menghasilkan profit, dan kaum ilmuwan dipaksa dan dikondisikan untuk berpihak kepada kepentingan kelas yang berkuasa.
***
M. Najib Yuliantoro dalam Ilmu dan Kapital (Kanisius, 2016: 70-71) memberi ilustrasi gamblang tentang cara kerja industri ini dalam konteks penelitian sains terapan:
“… Pada tahap ‘pra-penelitian’, seorang ilmuwan setidaknya perlu merumuskan dua hal, yakni menentukan objek penelitian dan membangun hipotesis penelitian berdasarkan objek penelitian dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Pada tahap ini … ilmuwan perlu membaca penelitian-penelitian paling mutakhir di bidangnya yang tersebar di berbagai jurnal, buku, majalah, dan proseding seminar dan konferensi. Permasalahannya, untuk mengakses sumber-sumber penelitian paling mutakhir itu … ilmuwan memerlukan kapital yang cukup besar. Beberapa universitas di negara berkembang, seperti Indonesia, perlu mengeluarkan ratusan juta supaya para peneliti, dosen, dan mahasiswa dapat mengakses jurnal internasional, menikmati buku-buku bermutu, dan mengikuti seminar penelitian di pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan … dan umumnya hal tersebut berbayar mahal. Demikian halnya ketika tiba pada tahap ‘proses-penelitian’, kondisinya sama dengan tahap sebelumnya. Ilmuwan memerlukan fasilitas-fasilitas utama, seperti sample penelitian dan alat-alat laboratorium, untuk mengerjakan eksperimentasi penelitiannya … dan celakanya, peralatan semacam itu sering kali hanya dimiliki oleh universitas-universitas terkemuka dan negara-negara maju, karena harganya yang cukup mahal …
Selanjutnya pada tahap ‘pasca-penelitian’, ketika suatu penelitian sudah menunjukkan ‘hasil’ dan menjadi ‘produk’, maka hal yang perlu dikerjakan oleh ilmuwan adalah melakukan ‘uji publik ilmiah’ melalui jurnal, buku, seminar, dan berbagai pertemuan ilmiah terdepan di bidangnya… Pada tahap ini, lagi-lagi, ilmuwan memerlukan kapital yang tidak kecil, karena umumnya jurnal-jurnal internasional yang diakui oleh komunitas ilmuwan terkemuka selalu berbayar mahal. Bukan hanya menerbitkan di jurnal, menghadirkan hasil penelitian di konferensi atau seminar saja sering juga berbayar. Jelaslah bahwa sejatinya tradisi peer-review di komunitas-komunitas ilmiah terkemuka ternyata bukan kegiatan yang dilaksanakan secara gratis. Pantas saja apabila banyak beasiswa dan perusahaan-perusahaan besar yang bersedia memfasilitasi ilmuwan agar menebitkan hasil-hasil risetnya di forum-forum ilmiah terkemuka. Bahkan, bukan hanya membantu membiayai publikasi, tetapi mereka juga membantu mengembangkan hasil penelitian itu menjadi produk komersial. Hal ini menegaskan bahwa kegiatan ilmiah saat ini sudah dimengerti sebagai kegiatan bisnis belaka, dan pemilik modal memanfaatkannya sebagai ‘komoditas’ untuk tujuan-tujuan kapital…”.
***
Kasus pelacuran intelektual sejumlah ilmuwan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, dalam melegitimasi penambangan bentang karst (kapur) di pegunungan Kendeng, dalam kasus Semen di Rembang beberapa waktu lalu, menunjukkan dinamika terkini dari “industri ilmiah” ini: bahwa industri ini telah mencapai batas terjauhnya sebagai garda depan pelindung kepentingan korporasi (perusahaan) yang membuatnya berhadapan secara langsung dengan masyarakat, korban terdampak. Kali ini, para ilmuwan tidak dapat lagi hanya bersembunyi “di balik layar”, atau berdiam di laboratoriumnya. Produksi ilmiah mereka telah langsung mempertemukan mereka dengan masyarakat yang terdampak oleh riset-riset atau pemikiran mereka. Di sinilah protes warga petani Rembang terhadap para ilmuwan UGM pro-tambang itu menjadi drama teatrikal di mana keberpihakan sedang dipertaruhkan. Dan ternyata, para ilmuwan UGM itu tetap memilih memihak perusahaan.
Apa pelajaran penting dari kasus intelektual vis-à-vis rakyat dan gerakan rakyat ini, dengan kepentingan kelas kapitalis di baliknya? Pelajaran terpenting yang perlu diambil dari kasus ini adalah bahwa ketiadaan kesadaran politis di lingkungan ilmuwan dan komunitas ilmiah yang ditetapkan dari awal berkorelasi dengan terseretnya kerja-kerja pengetahuan, terutama dalam ranah ilmu-ilmu empiris-positivis, ke dalam kepentingan kelas yang berkuasa. Ketiadaan kesadaran politis ini merujuk kepada dua faktor: lingkungan akademis yang semakin dinetralkan dari interaksi dengan lapisan-lapisan masyarakat yang tertindas, serta tidak adanya penggalian aspek pembebasan (emansipatoris) dari dalam ilmu pengetahuan itu sendiri yang memungkinkan ilmu dimaknai sebagai sarana pembebasan bagi lapisan-lapisan masyarakat yang tertindas dan terpinggirkan. Yang pertama merupakan “depolitisasi kampus”. Yang kedua merupakan “depolitisasi ilmu”. Keduanya berujung kepada demoralisasi ilmiah.
***
Tidak cukup bagi siapapun hari ini mengkritik relasi ilmu dan modal, karena kita memang sedang berada di dalamnya. Tugas terpenting saat ini adalah membongkar netralisasi lingkungan ilmiah dan menggali kembali aspek keberpihakan politis ilmu kepada mereka yang tertindas. Hal ini berarti melakukan repolitisasi kampus dan repolitisasi ilmu.
***
Bias liberalisme merupakan bias yang bekerja efektif dalam relasi antara ilmu, ilmuwan, dan modal hari ini. Bias ini hadir secara kelembagaan maupun secara ilmiah dalam lembaga-lembaga akademis dan ilmu pengetahuan yang digeluti oleh para ilmuwan. Apakah bias itu?
Individualisme epistemik, yaitu memperlakukan ilmuwan sebagai individu-individu yang terpisah dari masyarakatnya, dan memperlakukan ilmu sebagai produk dari proses individual yang tidak berurusan dengan kepentingan masyarakat. Bias ini otomatis mengabaikan relasi sosial-kolektif dari kerja ilmiah. Hasilnya, kerja-kerja yang dilakukan juga mengalami spesialisasi disiplin. Arsitek bekerja untuk mendesain bangunan hotel milik korporasi raksasa, tanpa peduli apakah hotel ini berdiri di atas lahan gusuran rakyat miskin kota. Arsitektur yang digelutinya bekerja terpisah dari ilmu agraria. Maka, dibutuhkan suatu langkah untuk men-de-disiplinarisasi ilmu, membongkar sekat-sekat disiplin ilmu sehingga tak hanya berkoneksi dengan yang lain, setiap ilmu secara fundamental dipengaruhi oleh isu politis yang dimunculkan oleh ilmu lain yang lebih politis.
Dalam hal ini, absennya Marxisme atau kritik ekonomi-politik (ekopol) dalam ranah ilmu-ilmu sosial-empiris kita merupakan suatu kehilangan besar yang harus segera direhabilitasi. Marxisme atau kritik ekopol harus masuk kembali secara terhormat dan mendapatkan tempatnya di dalam ilmu sosial. Hal ini akan memungkinkan relasi sosial-kolektif dari kerja ilmiah masuk kembali ke dalam lingkungan ilmu-ilmu sosial, dan meruntuhkan individualisme epistemik yang berlangsung.
Komunitas ilmiah di Indonesia hari ini bukannya tak mengakui Marxisme. Mereka mengetahuinya, tetapi sekadar menjadikannya opsi dalam analisis sosial, tetapi lebih sering, menyingkirkan dan mendiskreditkannya. Marxisme atau kritik ekopol akan memungkinkan ilmu sosial-empiris hari ini bekerja secara holistik untuk memperhitungkan dampak-dampak menyeluruh dari suatu kebijakan sosial (social policy) terhadap pergeseran kelas dan kekuasaan di dalamnya. Kita bisa bayangkan jika seorang pejabat pemerintah yang berurusan dengan tata-kota mempraktikkan analisis Marxis atas kota yang menjadi tanggung jawabnya, maka ia tidak mungkin menggusur rakyat miskin! Ia tidak akan melakukan rekayasa sosial “dari atas” atau sesuai selera korporasi, tetapi memperhitungkan keseimbangan, persebaran, dan kelangsungan kehidupan kota itu sehingga kalangan yang tertindas mendapatkan hak-haknya yang fundamental untuk dapat menghuni kota itu dengan nyaman dan mendapatkan hidup yang berkualitas.
***
Ada suatu paradoks yang mencolok pada komunitas ilmuwan ini: netralisasi dari interaksi dengan lapisan-lapisan masyarakat tertindas ternyata berlangsung seiring dengan ketergantungan yang tinggi dari komunitas tersebut kepada para pemodal (sponsor) atau korporasi yang mendanai kegiatan ilmiahnya. Dengan kata lain, netralitas itu ilusi, dan hanya merupakan fatamorgana dari ketergantungan kepada kekuatan pemodal.
Untuk melawan hal ini, dengan demikian, kita membutuhkan suatu gebrakan dari dalam: membangun otonomi aktivitas ilmiah, sehingga ketergantungan ini dapat terputus. Otonomi ini adalah kemandirian peneliti untuk membiayai dirinya. Otonomi ini juga berarti mengonversi komoditas ilmiah yang semula berorientasi kepada “nilai-tukar” (exchange value) menjadi “nilai-guna” (use value), sehingga hasil penelitiannya bermanfaat kepada pembelaan masyarakat yang tertindas.
Dalam kerjanya, otonomi ini dapat dikerjakan bila ia justru melibatkan sebanyak mungkin pihak—partisipatoris. Dengan demikian, masyarakat sendirilah yang mendanai, secara sukarela, hasil-hasil dari produksi dan kegiatan ilmiah. Kolaborasi intensif dengan kalangan masyarakat secara luas, dan kelompok masyarakat tertindas secara khusus, merupakan langkah yang strategis untuk membangun otonomi ini. Modal yang terakumulasi di tangan kelas pemodal, dengan demikian, dapat diganti dengan “modal sosial” masyarakat—yang akan memungkinkan para ilmuwan mandiri tanpa intervensi pemodal. “Modal sosial” inilah yang harus direbut, jika kultur keberpihakan kepada mereka yang tertindas ingin terbangun dari sekarang.***
Artikel ini sebelumnya adalah makalah yang disampaikan pada seminar FISIP DAY “Ketika Ilmu (Tak lagi) Sosial”, FISIP Universitas Hasanuddin Makassar, 5 Oktober 2017.