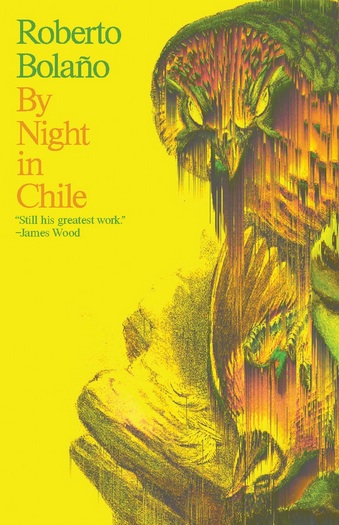DI AWAL abad ke-20, kesusastraan avant-garde adalah hamparan stepa luas, langit yang seperti selalu biru muda dan terbuka, pulau-pulau terpencil yang memikat siapa saja yang punya nyali untuk melenyapkan diri dalam petualangan tak berujung-pangkal. Di penghujung abad ke-20, apalagi di dekade kedua abad ke-21, kesusastraan avant-garde jadi semacam papan-papan reklame, materi-materi workshop penulisan kreatif dan senda-gurau di kafe-kafe unyu. Barangsiapa hendak menulis tentang kesusastraan avant-garde abad ke-21 tentulah akan mendapati dirinya menulis sebuah kisah sedih. Demikian halnya Marxisme.
Gerakan sastra avant-garde memang seperti saudara kandung gerakan Marxis. Keduanya didorong oleh impuls yang serupa, semacam dorongan liar untuk menjadi kontemporer. Dorongan ini terekam dengan baik dalam lirik lagu Internasionale yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Ki Hajar Dewantara: kesadaran untuk menggulung “adat dan faham tua” berkejaran dengan kesadaran bahwa “dunia telah berganti rupa”. Dalam lirik asli Internasionale karangan Eugène Pottier pun dapat kita kenali kekerabatan antara semangat avant-garde dan Marxisme. Lagu tersebut bersuara tentang kaum tertindas sebagai “kaum terkutuk” (les damnés de la terre). Imajinasi tentang subjek sebagai orang terkutuk semacam ini dapat pula kita temukan dalam riwayat kesusastraan avant-garde, khususnya tentang para “penyair terkutuk” (poète maudit) yang hidup terkatung-katung di jalanan, menyimpang dari adat-istiadat kesusastraan yang mapan, seringkali juga jauh dari kesuksesan (atau bahkan subsistensi) finansial. Dalam banyak hal, sastra avant-garde dan kemiskinan nyaris sinonim. Sastrawan avant-garde adalah “kaum yang lapar” (les forçats de la faim). Dorongan ke arah kebaruan dan kekinian juga membuat para sastrawan avant-garde kerapkali menjauhkan diri dari patokan-patokan agama. Mereka bertualang di dunia tanpa Tuhan dan Moralitas—mengembara lepas, bereksperimen dengan bahasa dan mencoba menciptakan tata dunia baru dalam kata-kata tanpa mengandalkan GPS teologis, ojek moralitas ataupun pemandu sorak adat-istiadat. Dengan kata lain, seperti dalam lirik Pottier: “Tiada juru selamat tertinggi / Tiada Tuhan, tiada kaisar, tiada hakim” (Il n’est pas de sauveurs suprêmes / Ni Dieu, ni César, ni tribun). Kesusastraan avant-garde, seperti halnya Marxisme, digerakkan oleh impuls untuk “menjebol dan membangun”.
Lebih dari semua itu, kesusastraan avant-garde dan gerakan Marxis mekar pada era yang kurang-lebih sama: akhir abad ke-19 sampai dengan akhir abad ke-20. Dalam rentang waktu itulah semua ini terjadi: Alfred Jarry menuliskan naskah drama dan novel eksperimentalnya, Friedrich Engels bergulat dengan naskah-naskah Marx yang penuh cakar ayam, petualangan Stephen Dedalus dan Leopold Bloom dimulai pada sebuah hari yang paling panjang dalam sejarah sastra, kapal Aurora melepaskan salvo pertamanya atas aba-aba Lenin dan meletuslah Revolusi Oktober, empat manifesto Stridentisme diterbitkan, Mao Tse-Tung bersama puluhan ribu komunis melakukan long march dari Jiangxi ke Shaanxi, Raymond Queneau mendirikan Oulipo sebagai subkomite dalam Collège de ‘Pataphysique, Jakarta Operation bergulir di Chile dan Allende dikudeta oleh semacam Suharto, kesusastraan avant-garde menyusut jadi sebuah tema dalam mata kuliah sejarah sastra, Uni Soviet runtuh. Literary dan political vanguardism tumbuh bersama dan sekarat bersama. Yang satu merupakan alegori dari yang lain. Kepeloporan partai dan kepeloporan sastra—keduanya kini menjadi bagian dari silabus sejarah dan gurauan singkat di tengah malam. Namun apa yang sebetulnya ikut lenyap dengan sekaratnya kedua aliran pemikiran itu? Sungguhkah tak ada yang bisa diselamatkan dari keduanya sebagai warisan bagi angkatan mendatang?
Jika saya kemudian bicara soal Roberto Bolaño, itu karena kekhasan sudut pandang yang ia gunakan dalam mengangkat tema Marxisme dan, terutama, sastra avant-garde. Alih-alih mengangkat tentang sastra avant-garde pada masa kejayaannya—katakanlah di era 1930-an—Bolaño memilih untuk menuturkannya dari sudut waktu yang lebih pelik, yakni antara akhir dekade 1970-an sampai dengan 1990-an. Ia berkisah tentang nasib kesusastraan avant-garde di tahun-tahun penghabisannya. Salah satu faktor yang membuat prosanya terasa mengejutkan, setidaknya buat saya, adalah karena kisah yang sebetulnya menyedihkan itu ia tuturkan dengan begitu riang, begitu polos, begitu sarat akan optimisme—dan dengan begitu memperparah kesedihan yang terpendam di balik semuanya. Ia bercerita tentang persaudaraan sastrawi di antara muda-mudi liar yang percaya pada kekuatan sastra untuk membikin rontok dunia dan mendesain ulang suatu dunia baru—kekuatan sastra untuk menjebol dan membangun—pada masa ketika hal-hal itu sudah dibuat jadi nyaris tak mungkin. Ia berkisah tentang les enfants terribles, anak-anak yang mengerikan, dari zamannya sendiri, yakni mereka yang percaya pada sosialisme, mendukung Allende, percaya pada kesusastraan Kiri eksperimental di luar pakem realisme sosialis, menyimpang dari pakem puisi lirik gaya Pablo Neruda dan Octavio Paz ataupun pakem prosa realisme magis yang sudah dipatenkan oleh Gabriel Garcia Marquez dan Isabel Allende, diasingkan oleh segenap literary establishment Amerika Latin, dikutuk untuk menjadi gelandangan sastra (sebelum akhirnya menjadi gelandangan betulan) dan mati sebagai “bukan siapa-siapa”, sebagai pengedar narkoba di perkampungan kumuh, sebagai buruh cuci-setrika di kota kecil, sebagai tukang palak di kota-kota asing, atau lenyap ditelan bumi.
Novel-novel Bolaño membentuk sebuah semesta rekaan bersama yang dihuni oleh tokoh-tokoh (atau setidaknya halusinasi) yang sama. Novela Amulet (1999) merupakan jalan paling mudah untuk memasuki semesta Bolaño (kecuali Anda mau segera mendaki ngarai-ngarai curam prosa-puisi Antwerp). Novela ini berkisah tentang Auxilio Lacouture, seorang perempuan paruh baya asal Uruguai yang menganggap dirinya sebagai “ibu puisi Mexico”. Dalam pendudukan Universitas Otonom Nasional Mexico (UNAM) oleh tentara pada 1968, ia sedang berada di toilet kampus itu dan karenanya mesti terus menyembunyikan diri di sana sampai 13 hari, ditemani buku puisi Pedro Garfias. Di sanalah ia mengenang pertemuan pertamanya dengan Arturo Belano, penyair muda Mexico asal Chile, ketika sang penyair masih culun dan belum akrab dengan miras. Auxilio lah yang mengajarinya wawasan kesusastraan dunia. Novela ini dituturkan dari sudut pandang pertama secara halusinatoris. Misalnya, Auxilio tengah berbicara tentang suatu peristiwa di tahun 1970-an lalu mendadak sudut pandangnya kembali ke hari-harinya di dalam toilet UNAM pada tahun 1968. Dalam narasi halusinatoris inilah sang “ibu puisi Mexico” itu memperoleh penglihatan tentang sekelompok anak muda—Arturo Belano, Ulises Lima dan kawan-kawannya—berbaris dengan gagah berani ke depan, tanpa mereka ketahui bahwa di depan sana hanya ada jurang gelap tanpa dasar. Mereka melangkah maju sambil menyanyikan lagu-lagu yang menebalkan semangat. Nyanyi-nyanyian itulah yang kemudian disebut sebagai “azimat” (amulet) oleh Auxilio—azimat masa muda, mantra petualangan menuju hari esok yang kosong, di mana gairah penciptaan gulung-menggulung dengan kekecewaan yang akan datang.
Suasana yang terbangun dalam novela itulah yang diwujudkan secara lebih kolosal dalam The Savage Detectives (1998). Novel setebal 600-an halaman ini bercerita tentang petualangan sastrawi tiga saudara seperguruan: Arturo Belano, Ulises Lima dan si anak baru, Juan Garcia Madero. Nama perguruan itu ialah “realisme jeroan” (visceral realism). Anggotanya sekitar belasan remaja yang gemar berbuat onar di acara-acara kesusastraan yang dibikin para ambtenaar sastra Amerika Latin era 1970-an. Yang paling radikal dari semua ababil itu ialah Belano dan Lima.
Novel itu terbagi ke dalam tiga bagian. Bagian pertama, bertajuk Orang-Orang Mexico Tersesat di Mexico, memuat narasi dari sudut pandang Madero pada tahun 1975 tentang inisiasinya ke dalam kelompok realis jeroan. Ia bertutur tentang kenakalan-kenakalan Belano dan Lima, serta diskusi tentang akar ideologis realisme jeroan pada gerakan kebudayaan Stridentisme di Mexico era 1930-an, khususnya tentang sosok penyair perempuan misterius bernama Cesárea Tinarejo yang sajaknya berisi gambar-gambar aneh, semacam puisi konkrit. Bersama Belano dan Lima, Madero memutuskan untuk mencari tahu keberadaan sang penyair avant-garde dari era 1930-an itu, pada suatu tempat di padang gurun Sonora. Pada saat yang bersamaan, mereka mesti menyelamatkan Lupe, seorang pelacur remaja, dari kejaran germo dengan kemaluan sebesar pisau komando, Alberto. Maka beranjaklah mereka berempat, menunggangi sedan Impala pinjaman, terseok-seok menyusuri padang gurun Sonora.
Bagian kedua yang begitu panjang, bertajuk Detektif-Detektif Liar, diisi dengan narasi dari sekurang-kurangnya 40 narator dengan suara yang khas seperti laiknya novel-novel William Faulkner (bandingkan As I Lay Dying dan The Sound and The Fury). Apabila bagian pertama tadi bertutur dalam lingkup tahun 1975, bagian kedua ini merentang dari tahun 1976 sampai dengan 1996 dan memuat kesaksian orang-orang tentang kembalinya Belano dan Lima dari padang gurun Sonora, pengembaraan mereka di Eropa, kepulangan mereka ke Mexico dan lenyapnya mereka dari skena kesusastraan Amerika Latin. Tak ada kabar sama sekali tentang Madero. Dari kesaksian 40-an orang itulah kita dapat merangkai suatu gambaran yang patah-patah tentang kehidupan dua tokoh realisme jeroan; Belano dan Lima sendiri tak pernah angkat bicara sebagai narator. Keduanya menggelandang di berbagai negeri di Eropa, masing-masing sendirian. Belano jadi tukang palak di Jerman, Lima jadi bandar narkoba kecil-kecilan, Belano jadi wartawan di daerah konflik Afrika, Lima terdampar di Tel Aviv. Beberapa waktu setelah kepulangannya ke Mexico, Lima diikutkan ke dalam kontingen sastrawan Mexico yang diberangkatkan ke Nikaragua sebagai tanda dukungan atas revolusi Sandinista. Sebagai seorang realis jeroan, ia asing terhadap kubu sastrawan Kiri tradisional—apa yang disebut di novel sebagai “para penyair petani”. Namun, pada tahap ini, Lima tak lagi peduli pada apapun, ia menjalani hari-harinya seperti orang yang baru saja dilobotomi. Menjelang kepulangan ke Mexico, para sastrawan itu baru menyadari bahwa Ulises Lima tidak lagi bersama mereka. Lima lenyap di Nikaragua. Sementara itu, di Barcelona, Belano menantang seorang kritikus dalam sebuah duel pedang di tepi pantai yang berakhir remis.
Pada bagian ketiga, berjudul Padang Gurun Sonora, peran narator kembali ke Juan Garcia Madero, kali ini dalam lingkup tahun 1976. Di sana Madero berkisah tentang petualangannya bersama Belano, Lima dan Lupe mencari Cesárea Tinarejo di kota-kota kecil sekitar Sonora. Setelah sekitar sebulan berkeliling padang gurun, mereka menemukannya: seorang nenek tua berbadan gemuk yang sedang berjongkok mencuci baju bersama dua buruh cuci lainnya. Sehari kemudian Alberto, si germo, beserta seorang polisi upahannya menemukan mereka. Belano berhasil membenamkan pisau ke dada si germo, tetapi Cesárea menerima peluru yang ditujukan sang polisi ke Ulises Lima. Cesárea mati, sang polisi mati. Kemudian yang hidup menguburkan yang mati dan berpisah di pagi buta: Belano dan Lima kembali ke Mexico, Madero dan Lupe memutuskan untuk tinggal di gurun Sonora. Pada entri-entri terakhir catatan hariannya, Madero menuliskan beberapa nama kota dan menggambar beberapa kotak yang tak jelas artinya.
Struktur cerita The Savage Detectives dengan begitu halus membingkai hikayat murung tentang avant-gardisme—kemubaziran sekaligus keniscayaannya. Kita memperoleh potret yang begitu jelas tentang degenerasi semangat muda, dari api pemberontakan yang meluluh-lantakkan segala kemapanan ke remah-remah abu yang dilupakan orang. Para sastrawan avant-garde macam Belano dan Lima dikutuk untuk menjalani kembali nasib Cesárea Tinarejo: mereka menggelandang lepas di negeri-negeri asing, dikucilkan oleh para ambtenaar sastra, terseok-seok mencari puisi. Dalam kumpulan draft cerita yang tak sempat diterbitkan sampai ajal menjemput Bolaño pada 2003, kita dapat menemukan sepotong cerpen berjudul Death of Ulises (dalam kumcer The Secret of Evil). Di sana dikisahkan kepulangan kesekian Belano ke kota Mexico, setelah 20 puluh tahun melanglang buana dan mulai memperoleh ketenaran sebagai penulis. Ia mengunjungi kosan lama Ulises Lima. Betapa terkejutnya ia ketika tiga pemuda pengangguran kini mendiami kamar itu. Kata mereka, Lima menghabiskan waktunya dengan mabuk-mabukan sebelum akhirnya mati diterjang sedan Impala hitam. Kepada Belano, mereka mengaku sebagai “murid terakhir Ulises Lima”. Ketiganya mendirikan rock band bernama El Ojete de Morelos yang mereka klaim meneruskan semangat pemberontakan Ulises Lima. Dengan begitu, berarti tinggal Belano seorang diri sebagai penyintas terakhir kesusastraan avant-garde Mexico.
 Roberto Bolano. Kredit foto, http://www.archiviobolano.it
Roberto Bolano. Kredit foto, http://www.archiviobolano.it
Peran Belano tak berhenti sampai di situ. Dalam proyek novel terakhir yang sudah nyaris selesai ketika Bolaño mati, Belano kembali berperan. Novel itu ialah 2666, sebuah karangan dengan tebal nyaris 900 halaman yang berkisah tentang lima hal yang hampir tak berhubungan satu sama lain. Novel itu dibuka dengan uraian tentang empat kritikus sastra dari berbagai negeri di Eropa sama-sama mengejar seorang novelis misterius bernama Benno von Archimboldi. Mereka memburu setiap rumor tentang penulis itu sampai mereka tiba di padang pasir Sonora, di sebuah kota kecil bernama Santa Teresa, dan pulang dengan tangan hampa. Bagian kedua novel bercerita tentang Amalfitano, seorang dosen filsafat yang sempat menemani para kritikus sastra mencari Archimboldi di Sonora. Amalfitano kerap sibuk dengan pikiran atau imajinasinya sendiri semenjak ditinggal pergi istrinya. Bagian ketiga berkisah tentang Oscar Fate, seorang wartawan kulit hitam yang bekerja pada sebuah surat kabar di New York. Suatu ketika ia diminta untuk meliput pertandingan tinju di Santa Teresa, Mexico. Selama di sana, Fate mendengar keresahan warga tentang pembunuhan berantai yang memakan korban banyak perempuan. Ia kemudian mewawancarai seorang narapidana yang dianggap pelaku pembunuhan, seorang asal Jerman bernama Klaus Haas. Bagian keempat bercerita tentang ratusan kasus pembunuhan terhadap perempuan di Santa Teresa yang dideskripsikan satu per satu secara terperinci sepanjang hampir 300 halaman. Sampai akhir bagian itu kita tidak mendapat kejelasan final tentang siapa pembunuh sebenarnya. Bagian terakhir mengisahkan riwayat hidup Hans Reiter, seorang pemuda desa di Jerman yang tumbuh pada era Perang Dunia, menyukai sastra dan mengadopsi nama pena Benno von Archimboldi. Kisah ini berakhir dengan permintaan Lotte, adik perempuan Reiter, untuk menjenguk dan menolong Klaus Haas, putra Lotte satu-satunya, yang meringkuk akibat tuduhan palsu di penjara Santa Teresa, Mexico. Lalu di mana peran Belano? Di lembar manuskrip yang tak diterbitkan, Bolaño memberikan petunjuk bahwa narator dari seluruh kisah ini adalah Arturo Belano dan pada lembar paling akhir manuskrip itu, Bolaño menambahkan keterangan “untuk akhir novel 2666”: “Begitulah, teman-teman. Aku telah melakukan semuanya, aku telah menghidupi semuanya. Kalau saja aku masih punya tenaga, aku akan menangis. Selamat tinggal semuanya, Arturo Belano.”
Novel 2666 tak pelak lagi merupakan suatu alegori raksasa tentang ketersesatan, tentang pikiran yang ling-lung, tentang kesusastraan avant-garde yang jadi nyaris identik dengan racauan tanpa tujuan. Novel itu seperti mau berkata: dalam suatu dunia yang kacau-balau, dengan kesusastraan yang menghamba pada uang dan pakem-pakem lirisisme gurih yang mudah dipasarkan dan gampang dikemas dalam musikalisasi-musikalisasi yang menguras air mata kelas menengah, dengan prospek politik emansipasi yang madesu dan amburadul, kesusastraan avant-garde hanya dimungkinkan sebagai halusinasi. Dalam situasi semacam itu, Bolaño seperti mau berkata, apa yang kita perlukan adalah keberanian untuk berhalusinasi. Realismenya adalah suatu realisme halusinatoris. Inilah yang ia nyatakan dalam manifesto yang ditulisnya ketika ia masih menjadi penyair bohemian, seperti halnya Arturo Belano, pada tahun 1976:
“Chirico mengatakan: pikiran mesti menjauh dari apapun yang disebut logika dan akal sehat, menjauh dari segala rintangan manusia demikian rupa sehingga hal-ihwal tampil dalam penampakan baru, seakan-akan dicerahi oleh sebuah konstelasi bintang yang menampak untuk pertama kalinya. Kaum infrarealis mengatakan: Kita akan membenamkan hidung kita ke dalam seluruh rintangan manusia, demikian rupa sehingga hal-ihwal mulai bergerak ke dalam diri kita—suatu visi halusinatoris tentang umat manusia.”
Dalam Manifesto Infrarealisme itu Bolaño tampil sebagai Belano, sebagai musuh tradisi kesusastraan yang telah mapan di Amerika Latin, yang direpresentasikan dalam sosok Octavio Paz dalam puisi liris dan Garcia Marquez dalam prosa realisme magis. Ia tampil sebagai pemuda pemarah yang menantang zamannya untuk maju lebih jauh lagi.
Sebagai seorang pemuda, Bolaño punya cukup nyali untuk menentang literary establishment yang bercokol kuat di belantika dunia persilatan sastra Amerika Latin. Dan ia sadar akan risikonya: dikucilkan, jauh dari pengakuan, apalagi dari kesuksesan finansial. Sehari-hari, ia bekerja serabutan sebagai pelayan restoran, tukang cuci piring, tukang sampah dan berbagai pekerjaan yang perlu ia jalankan untuk bisa terus hidup dan menulis puisi. Kebesaran namanya datang jauh belakangan, jauh terlambat, beberapa tahun sebelum ia meninggal, khususnya setelah ia menulis prosa. Salah satu puisinya dari tahun 1990, Karir Sastraku, merekam pergulatan itu:
Penolakan-penolakan dari Anagrama, Grijalbo, Planeta, tentu juga dari Alfaguara,
Mondadori. Kata tidak dari Muchnik, Seix Barral, Destino… Semua penerbit… Semua pembaca…
Semua manajer penjualan…
Di bawah jembatan, selagi hujan, kesempatan emas
untuk melihat diriku sendiri:
seperti seekor ular di Kutub Utara,
tetapi menulis.
Menulis puisi di negeri orang dungu.
Menulis dengan putraku di lututku.
Menulis sampai malam jatuh
dengan guntur seribu iblis.
Iblis-iblis yang akan membawaku ke neraka,
tetapi menulis.
Bolaño telah mengalami semuanya. Kemarahan-kemarahan Arturo Belano, kegamangan-kegamangan Ulises Lima, halusinasi-halusinasi Auxilio Lacouture, racauan-racauan ratusan tokoh yang ia ciptakan sepanjang karirnya sebagai prosais. Roberto Bolaño adalah semua itu.
Prosanya puitis, tapi tidak dalam pengertian liris—tak ada rima yang mudah dilagukan, tak ada ekspose yang mendayu-dayu, tak ada melodrama filosofis. Prosanya puitis dalam arti mengagetkan secara citrawi dan memiliki ritme yang membikin kepala berdenyut. Contohnya adalah monolog Urrutia Lacroix, seorang romo Jesuit yang menjadi tutor privat Pinochet mengenai Marxisme dalam novela By Night in Chile. Narasi sang romo yang acuh-tak acuh tentang proses kejatuhan Allende mencerminkan ideologi konservatif yang dihadirkan secara sama sekali tidak vulgar.
“Biarlah kehendak Tuhan terjadi, kataku. Aku akan membaca lagi para pengarang Yunani. Demi menghormati tradisi, aku memulai dengan Homer, kemudian beralih ke Thales dari Miletus, Xenophanes dari Colophon, Alcmaeon dari Croton, Zeno dari Elea (bagus sekali), kemudian seorang jenderal pro-Allende dibunuh dan Chile mengembalikan hubungan diplomatik dengan Kuba dan sensus nasional mencatat jumlah keseluruhan 8.884.746 orang Chile dan episode perdana opera sabun Hak untuk Dilahirkan disiarkan di televisi, dan aku membaca Tyrtaios dari Sparta dan Archilochos dari Paros dan Solon dari Athena dan Hipponax dari Ephesos dan Stesichoros dari Himnera dan Sappho dari Mytilene dan Anakreon dari Teos dan Pindar dari Thebes (satu di antara kesukaanku), dan pemerintah menasionalisasi tambang tembaga, kemudian industri nitrat dan baja, dan Pablo Neruda memenangkan Hadiah Nobel dan Diaz Casanueva memenangkan Hadiah Sastra Nasional dan Fidel Castro datang berkunjung dan banyak orang mengira ia akan tinggal selamanya di Chile dan Perez Zujovic sang mantan menteri Kristen-Demokrat dibunuh dan Lafourcade menerbitkan Burung Dara Putih dan aku memberinya resensi yang baik, kau bisa katakan aku menyambutnya dalam kata-kata berkilau, walaupun di hatiku aku tahu itu buku yang buruk, dan demonstrasi anti-Allende pertama diorganisasikan, dengan orang-orang menabuh panci dan wajan, dan aku membaca Aeschylus dan Sophocles dan Euripides, semua tragedi, dan Alkaios dari Mytilene dan Aesop dan Hesiod dan Herodotus (raksasa di antara para pengarang), dan di Chile terjadi kelangkaan dan inflasi dan pasar gelap dan antrian panjang atas makanan dan tanah milik Farewell disita dalam Reforma Lahan beserta banyak tanah yang lain dan Biro Urusan Perempuan didirkan dan Allende pergi ke Mexico dan mendatangi kantor PBB di New York dan ada serangan teroris dan aku membaca Thucydides, peperangan panjang Thucydides, sungai-sungai dan dataran, angin dan lembah-lembah yang melintasi halaman Thucydides yang digelapkan oleh waktu, dan orang-orang yang ia gambarkan, para pejuang dengan lengan mereka, dan warga sipil, memetik anggur, atau memandang cakrawala jauh dari lereng gunung, cakrawala di mana aku hanyalah satu dari jutaan makhluk yang masih akan lahir, cakrawala begitu jauh yang diintip Thucydides dan aku di sana gemetar tanpa bisa dibedakan, dan aku juga membaca ulang Demosthenes dan Menander dan Aristoteles dan Plato (yang tak bisa kita baca terlalu sering), dan ada pemogokan-pemogokan dan sang kolonel dari resimen tank mencoba melakukan kudeta, dan seorang kameramen merekam kematiannya sendiri dalam film, dan perwira angkatan laut Allende dibunuh dan terjadi kerusuhan, makian, orang-orang Chile mengeluarkan sumpah serapah, melukis pada tembok-tembok, lalu nyaris setengah juta orang berbaris mendukung Allende, kemudian terjadilah kudeta, pemberontakan militer, pemboman istana La Moneda dan ketika pemboman berhenti, sang presiden bunuh-diri dan itu mengakhiri segalanya. Aku duduk dalam diam, dengan jari di antara halaman untuk menandai tempatku, dan aku berpikir: akhirnya perdamaian.”
Membaca kalimat panjang seperti itu, pikiran kita seperti diseret untuk masuk ke dalam halusinasi apatis sang romo Jesuit dalam memandang kejatuhan Allende. Bolaño menghadirkan isi jeroan seorang reaksioner—lengkap dengan segenap prasangka dan snobisme sastrawinya—ke dalam pikiran pembaca. Prosanya kuat tanpa harus heroik seperti “para penyair petani” ataupun mendayu-dayu seperti para penyair lirik ataupun mendongeng seperti template yang banyak dipakai para prosais dari mazhab realisme magis.
Lantas bagaimana menempatkan Marxisme dalam semesta Bolaño? Seperti sudah disinggung sebelumnya, Marxisme kurang-lebih dapat dipertukarkan dengan kesusastraan avant-garde. Hal ini berlaku dalam semesta Bolaño. Ia tetaplah seorang sastrawan avant-garde biarpun ia menyajikan kisah tentang hal itu dalam nada yang murung dan tak jarang juga disertai olok-olok. Demikian pula dalam hal Marxisme. Ia tetap seorang pengarang yang percaya pada Marxisme. Dalam sebuah wawancaranya di jurnal Turia, ia mengaku selamanya berada di Kiri. Mula-mula ia merupakan seorang Trotskyis karena tidak suka melihat keseragaman yang penuh ketaatan khas “kaum rohaniawan komunis”. Kemudian ia meninggalkan Trotskyisme karena alasan yang sama, bahwa di kalangan Trotskyis juga ada kaul ketaatan dan keseragaman semacam itu. Makanya ia beralih jadi anarkis. Namun ia jengah juga dengan kaum anarkis karena alasan yang sama. “Setiap kali aku menyadari bahwa seluruh dunia bersepakat tentang sesuatu,” kata Bolaño, “setiap kali aku melihat seluruh dunia mengecam sesuatu secara bebarengan, bulu kudukku merinding dan ini membuatku menolaknya.” Itulah yang membuatnya ogah menjadi Stalinis, Trotskyis ataupun anarkis. Namun, ia mengaku, ia selalu berada di Kiri. Sebabnya sudah bisa kita duga. Menjadi Kiri di masa sekarang sama sulitnya seperti menjadi avant-garde. Justru karena itu nyaris mustahil maka itu layak diperjuangkan.
Dengan demikian, seluruh acuan tentang realisme jeroan dan beragam gerakan kesusastraan avant-garde dalam semesta Bolaño dapat dibaca juga sebagai acuan tentang Marxisme—lebih tepatnya, tentang betapa sulitnya menghadirkan Marxisme. Tapi kemustahilan punya pesonanya sendiri. Keterpesonaan pada yang mustahil, ketahanan untuk menolak tunduk pada pakem usang, keberanian untuk menghalusinasikan dan mewujudkan tatanan baru—inilah warisan berharga kesusastraan avant-garde dan Marxisme. Di situlah juga terletak pesona Bolaño bagi generasi kita. Ia adalah pemuda yang tumbuh dewasa di era pasca-Boom sastra Amerika Latin, ia menyaksikan ideal-ideal Kiri gugur di hadapan kerasnya mesin kapitalisme global, ia mengalami sendiri kebuntuan eksperimentasi avant-garde di hadapan rezim kesusastraan yang mapan. Namun ia terus menghumbalangkan diri ke depan, ke masa depan yang tak dikenal, seperti preman kampung yang sesumbar menantang bandar judi kelas kakap. Ia tak takut, sebab ia tahu, dalam genggamannya ada oncor yang menyala-nyala, yang tak akan padam walau diguyur air mata lirisisme, yang tak akan padam walau ditenggelamkan dalam rawa-rawa kapitalisme. Dan oncor itu adalah kegilaan kita.***
18 Januari 2016
————-
[1] Saya berterima kasih pada Yusi Avianto Pareanom yang telah memperkenalkan karya Roberto Bolaño pada saya beberapa bulan lalu.