Tanggapan untuk Dodi Faedlulloh
BEBERAPA upaya di kalangan gerakan untuk kembali menjajal koperasi sebagai bentuk pengorganisasian sudah mulai marak bermunculan. Dikatakan ‘kembali menjajal’ karena sebenarnya memang koperasi selama ini sudah terlebih dahulu dianggap “sokoguru ekonomi Indonesia”—entah apakah ada makna dalam ungkapan ini atau tidak. Setidaknya, demikianlah yang jadi objek hapalan kita selama duduk di bangku SD sampai SMA, bahkan universitas. Namun demikian, sebagaimana yang juga diulas oleh Dodi Faedlulloh di harian ini, koperasi hanyalah avatar alias penjelmaan dari ekonomi negara maupun ekonomi kapitalis di negeri ini. Sebagai avatar ekonomi negara, koperasi hanyalah dilihat sebagai varian dari bentuk perusahaan yang didorong oleh negara—dengan tujuan-tujuan yang selalu telah dikoridorkan oleh pemerintah. Sementara sebagai avatar ekonomi kapitalis, koperasi hanya menjadi salah satu bentuk usaha untuk mengakumulasi modal perseorangan atau kelompok. Pola lainnya sebagai avatar ekonomi kapitalis, koperasi menjadi alat untuk membuat kelompok-kelompok yang tertinggal menjadi mampu untuk mengejar ketertinggalan mereka untuk bergabung dalam riuhnya persaingan di pasar bebas. Kesamaan dari ketiganya jelas: ekonomi pasar kapitalis tetap menjadi background yang tidak dipermasalahkan. Bahkan, khusus untuk bentuk ketiga, koperasi malah menjadi perantara untuk menghantarkan ke arena pasar bebas yang, setelah itu, perantara tersebut memudar, menjadi tidak terbedakan dengan entitas-entitas ekonomi kapitalis lainnya.
Upaya pengarusutamaan koperasi sebagai ihwal politis yang disampaikan Dodi Faedlulloh, saya kira, adalah upaya yang teramat penting dalam rangka mengevakuasi koperasi dari portofolio ekonomi negara dan kapitalis. Dengan tetap membawa semangat yang sama dengan Dodi, tulisan ini ingin memberi beberapa catatan kritis. Tujuannya bukan untuk mendiskualifikasi poin-poin argumen beliau, namun justru untuk membawa argumen tersebut ke implikasi-implikasi yang lebih jauh. Setidaknya ada tiga poin:
1. Tentang kehadiran negara dalam koperasi.
Dodi melihat negara serba hadir dengan menunjukkan pada kenyataan turut campurnya negara dalam pembentukan, pendorongan, pengarahan, pengaturan dan bahkan pengoordinasiannya secara nasional, misalnya, dengan Dekopin. Namun apabila dipertimbangkan lagi lebih jauh, anggapan ini sebenarnya justru mengafirmasi suatu asumsi yang amat spesifik dan partikular mengenai ‘kehadiran negara’. Negara dianggap hadir pada saat ia mengerahkan aparatus dan aparaturnya, baik orang, regulasi maupun institusinya dalam dinamika perkoperasian. Angapan ini, sayangnya, hanya melihat ‘kehadiran’ sebagai suatu tindakan aktif. Pula anggapan ini mengidealkan kondisi yang mana absensi negara adalah suatu kondisi positif bagi koperasi; sementara kehadiran negara dianggap sesuatu yang negatif. “Fobia negara,” adalah istilah Foucault untuk anggapan-anggapan seperti ini yang, nyatanya, adalah berasal dari keluarga liberalisme, baik yang konservatif maupun yang anarkis sekalipun. Negara dianggap mengganggu keharmonisan spontanitas dari kolektivitas di dalam koperasi. Efek sampingnya bagi gerakan koperasi, kita akan selalu punya excuse ampuh saat koperasi gagal: ‘habis negara ikut campur sih!’
Yang menjadi terlewatkan dari anggapan demikian ada beberapa. Pertama, yaitu suatu kenyataan bahwa sebenarnya negara telah selalu hadir, sekalipun secara kongkrit ia pasif dan cuci tangan dari perkoperasian. Akibatnya, kedua, anggapan ini tidak bisa melihat pasivitas negara justru sebagai sebentuk kehadiran tersendiri, sebentuk intervensi aktif par excellence. Pasivitas bisa dilihat sebagai suatu aktif-itas apabila kita melihatnya sebagai sebentuk pembiaran dan pengabaian: dibiarkan mati, dibiarkan menderita, dibiarkan terhanyut dalam ‘ganasnya’ kompetisi di pasar bebas, sedemikian rupa sampai koperasi akhirnya mengakui bahwa hanya dengan negara lah ia bisa maju dan hidup. Dengan kata lain, kita beresiko untuk mengabaikan bentuk kehadiran yang seolah pasif, namun sebenarnya sangat aktif dari kejauhan.
Memahami aktivitas dari kejauhan ini tidak sukar. Dengan memberi ruang, tempat dan dukungan (regulasi, moril, simpati) pada sistem dan mentalitas pasar bebas kapitalistik, negara telah secara pasif hadir dalam perkoperasian. Bagaimana demikian? Untuk ini, kita harus melihat kekinian atau kontemporalitas dari kapitalisme, terutama pola dan cara kerjanya yang spesifik di hari ini. Salah satunya adalah dengan modus frustrasi. Kapitalisme hari ini akan oke oke saja dengan koperasi dan/atau bentuk pengorganisasian ekonomi lainnya yang (seolah–olah) nir-kapitalis. Hanya saja sistem yang dibuatnya akan dengan sendirinya membuat koperasi dan lainnya menjadi semakin tidak relevan dan cepat putus asa sepanjang mereka mencoba memutuskan diri dari sirkuit dan logika ekonomi pasar bebas. Penciptaan sistem kapitalis yang memfrustrasikan seperti ini hanya ada karena ia “diizinkan” oleh negara tentunya. Tepat di sinilah bagaimana negara telah selalu hadir dalam ekonomi pasar. Tanpa perlu intervensi langsung, koperasi menjadi terkondisikan oleh kapitalisme.
Sedikit catatan, pandangan mengenai kehadiran dari kejauhan ini tidak serta merta bisa disamakan dengan kehadiran negara secara tidak langsung. Sama sekali berbeda. Kehadiran tidak langsung selalu mensyaratkan perantara atau proxy. Istilahnya, negara menggunakan tangan lain untuk mengatur koperasi. Namun bukan ini yang dimaksud aktivitas dari kejauhan. Poinnya ada pada intensi; intervensi tidak langsung mensyaratkan kesengajaan ke objek, sementara intervensi dari kejauhan sama sekali tidak mensyaratkan kesengajaan ke objek yang hendak diintervensikan. Contohnya adalah bagaimana negara ikut mendorong dan melestarikan pendidikan, reproduksi artifak kebudayaan (film, tayangan, seminar, tulisan, dst.) yang menekankan ide-ide kreativitas, kebebasan dan eksplorasi yang kesemuanya berbasiskan pada narsisisme dan individualisme vulgar—ketimbang berbasis solidaritas kolektif. Efeknya, tentu saja individu-individu generasi muda produk-produk pendidikan ini menjadi asing terhadap koperasi. Koperasi menjadi suatu aktivitas nyentrik yang esoterik. Atau dalam tulisan Dodi, ia menjadi suatu sampingan semata yang benar-benar tereduksi dari nilai-nilai solidaritas, boro-boro perlawanan terhadap sistem. Di sini, negara hadir justru melalui ketidakhadirannya. (Inilah yang disebut Foucault sebagai negara neoliberal. Untuk uraian ini, lihat Birth of Biopolitics dan Security, Territory, Population).
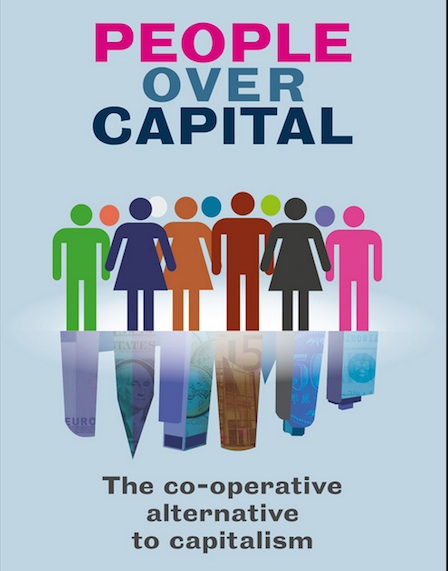 Ilustrasi gambar diambil dari http://newint.org dengan sedikit penyesuaian
Ilustrasi gambar diambil dari http://newint.org dengan sedikit penyesuaian
2. Masih terkait dengan poin pertama sebenarnya. Dalam tulisan Dodi, dinamika perkoperasian amat kental, bahkan sampai taraf tersandera, pada elitisme, institusionalisme dan oknumisme—siapa yang mengarahkan, siapa yang menyetir, siapa yang mengatur, dst. Tipologi Dawam Raharjo yang diikuti Dodi pun jelas sangat elitis, yang mengasumsikan koperasi sebagai suatu entitas yang nir-kontradiksi yang bisa di-wrap-up dan diarahkan sesuka hati. Alegori “koperasi yang berdiri tanpa diri” dan aspirasi “koperasi yang berbicara bagi dirinya sendiri” yang dipakai Dodi juga kental mengasumsikan ini; sebuah antropomorfisme yang, ironisnya, mendasari seluruh politik totaliter dan fasistik. (Saya membahas ini secara ekstensif di buku saya, Asal Usul Kedaulatan).
Perlu ditekankan di sini, hal ini bukan berarti bahwa persoalan elit, kepemimpinan dan institusi bukan hal yang penting untuk dipikirkan. Namun yang ingin ditekankan justru bagaimana melihat problem-problem ini secara berbeda; tidak top-down, melainkan bottom-up; tidak sebagai sesuatu kekuasaan yang terkonstitusi (constituted power), melainkan sebagai kekuatan konstituensi (constituent power). Karena tanpa pergeseran pandangan demikian, ketiga pekerjaan rumah yang diusulkan Dodi hanya akan menjadi ceklis-ceklis pimpinan/pengurus koperasi saja. Misalnya, tentang pendidikan ekopol koperasi. Tanpa pergeseran pandang dari elitisme ke solidaritas kolektivisme, ia hanya akan menjadi kursus dan kelas-kelas dari suhu-suhu koperasi semata; ia hanya akan selalu menjadi mata pelajaran dan bukan poin-poin pembelajaran. Lalu tentang kolaborasi dengan gerakan lain; jelas ini adalah hal yang penting, terutama apabila itu dikaitkan dengan aspirasi koperasi sebagai gerakan politik. Namun, sekali lagi, apabila ini menjadi ceklis program atau to-do list semata, dan bukan sebagai agenda politik yang disadari dan dirumuskan bersama sebagai satu-satunya cara agar koperasi bisa tetap hidup, tetap menghidupi ekonomi anggota, dan tetap mampu menghidupkan gerakan politik melawan kapitalisme, maka kolaborasi lintas-gerakan hanya akan menjadi arisan-arisan nostalgik heroik saja, dan malah menjadikan koperasi sebagai tahanan kolektivitas—yang penting kumpul dan terdaftar, tapi dinamika internal kosong, pertukaran ide minim, hutang-hutang anggota menumpuk, produktivitas anggota stagnan, dst. Poinnya adalah bahwa ketiga PR yang diusulkan Dodi sama sekali tidak salah, dan bahkan saya pribadi juga tengah mengupayakan hal serupa. Namun yang terpenting bahwa itu semua haruslah menjadi sesuatu yang ditemukan di lapangan di dalam kiprah anggota dalam berkoperasi, dan bukan suatu agenda yang dipaksakan dari atas atau dari luar. Akibatnya, kita harus juga menerima kemungkinan bahwa bisa saja anggota koperasi tidak mengganggap ketiga PR itu penting untuk dikerjakan, dan bahwa kita tidak lantas melihat itu sebagai “koperasi yang tidak politis.” Ini membawa kita pada poin ketiga.
3 Tentang yang politis dari koperasi.
Bagi Dodi, koperasi yang politis adalah yang ‘keluar dari kotak keajegan koperasi yang hanya beraktivitas dalam soal ekonomi saja. Koperasi perlu politis, yaitu kritis terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka wajib melek kondisi ekonomi-politik baik Indonesia maupun global.’ Bagi saya, konsepsi ini masih kurang terelaborasi, dan saya yakin Dodi mampu mengelaborasinya lebih jauh. Bagaimanapun juga, catatan saya, frasa ‘koperasi yang politis’ adalah suatu pleonasme, sama seperti mengatakan “masuk ke dalam” dan “naik ke atas.” Ia mengatakan sesuatu yang sebenarnya sudah jelas, yaitu bahwa koperasi memang pada dasarnya, khitah-nya, adalah memang politis. Saya melihat aspek politis koperasi di sini sebagai suatu fakta objektif, ketimbang aspirasi subjektif. Dengan kata lain, tanpa anggotanya berniat mempolitisasi koperasi (dalam artian Dodi, atau dalam artian konvensional—aksi massa, parlemen, pemerintahan) pun, koperasi itu sendiri telah selalu politis. Bagaimana demikian?
Di titik ini saya kira saya harus berbeda pendapat dengan Dodi yang memusuhi ide mengenai koperasi sebagai suatu “medan kekosongan.” Katanya,
“[s]elubung gelap merasuki pemahaman masyarakat tentang koperasi. Inilah yang berbahaya. Bila tidak segera direformasi, koperasi akan menjadi medan kekosongan. Koperasi beraktivitas tapi minus subjek yang paham dengan dirinya sendiri. Koperasi diusung, dibangga-banggakan, diseremonialkan ─setidaknya setiap tanggal 12 Juli, tapi tanpa ruh sama sekali.”
Berbeda dari Dodi, saya melihat ini bukan hanya sebagai sesuatu yang positif, melainkan bahwa itu memang adalah koperasi sebagaimana adanya: suatu medan kekosongan. Bagaimana apabila kenyataan bahwa koperasi mungkin untuk diapropriasi oleh negara dan diekspropriasi oleh pasar kapitalistik adalah tanda bahwa koperasi memang suatu medan kekosongan? Bukankah karakter kekosongan ini pula yang, sebaliknya, memungkinkan kita untuk menjadikannya alat perjuangan melawan kapitalisme dan neoliberalisme negara? Alih-alih menafikan, saya justru hendak mengusulkan suatu afirmasi mengenai koperasi sebagai medan kekosongan. Karena hanya dengan mengakui dan mengafirmasi koperasi sebagai medan kekosongan yang bisa dipolitisasi (tidak hanya negara dan pasar, melainkan juga aktivis pergerakan), dengan itulah kita bisa mendemistifikasi normalitas yang berlaku saat ini bahwa koperasi hanya bisa berjalan dengan negara dan bahwa arena pasar bebas adalah muara takdir satu-satunya bagi koperasi. Afirmasi kekosongan tidak harus selalu menjadi eskapis dan apatis, justru ia bisa menjadi (ehem..) revolusioner. Itulah mengapa, bagi saya, afirmasi koperasi yang politis haruslah selalu dalam bentuk pleonasme. Yaitu untuk selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa koperasi adalah selalu politis di tengah upaya negara dan pasar untuk mendepolitisasi koperasi dan menjadikannya sebagai semata-mata komponen kekuasaannya.
Saya kira kita harus jelas mengenai natur koperasi, yaitu pada dirinya adalah suatu bentuk pengorganisasi dan/atau manajemen ekonomi: produksi, anggota, dan orientasi. Sebagai sebentuk pengorganisasian ekonomi yang nir-esensialis, koperasi bisa mengambil bentuk apa saja. Itulah mengapa kita mesti mampu membayangkan, misalnya, Starbucks diorganisasikan secara koperatif, dan sebaliknya, bahwa koperasi petani di desa bisa malah menjadi supereksploitatif. (Contoh fenomenal lainnya adalah Koperasi Mondragon, yang sekalipun berbasiskan kolektivisme, tetap saja bisa menjadi eksploitatif).[1] Dengan kata lain, apabila menggunakan kategori moral, ‘baik dan jahat’-nya, suksesnya koperasi tidak dilihat dari apa yang diproduksinya, melainkan dari bagaimana dinamika itu diorganisir dan diarahkan … secara ideologis. Lebih spesifiknya, bagaimana ia diarahkan secara kontesktual-spesifik untuk membangkrutkan dan membuat sistem yang ada (kapitalisme) menjadi tidak relevan. Singkatnya, menjadi koperasi tidak lantas nir-kapitalis atau bahkan anti-kapitalistik; dan sebaliknya, koperasi yang mengaku nir-kapitalis juga tidak serta-merta berarti anti-kapitalistik, dan bisa jadi malah tanpa disadari justru memperkuatnya.
Dengan kata lain, untuk menjadi revolusioner, koperasi harus menjadi pembeda yang antagonis terhadap kapitalisme. Dalam konsepsi inilah frase “berbeda adalah melawan” dari Antonio Negri harus diartikan.[2] Berbeda haruslah berbeda dan anti-tesis bagi corak yang berlaku dan berkuasa. Sehingga sekalipun berangkat dari konteks spesifik anggotanya (urban, sub-urban, rural, dst.), koperasi yang berbeda-beda corak ini tetap harus bermuara pada tohokan pada universalitas kapitalisme. (Poin ini tidak bisa saya elaborasi di sini, mungkin di kesempatan lain). Untuk menjadi pembedaan yang melawan, maka kapitalisme juga mesti dilihat dari corak organisasional dan manjerialnya untuk bisa diperbandingkan dengan pengorganisasian dan manajemen secara koperatif. Sehingga akhirnya kita bisa menggariskan pembedaan, misalnya, Starbucks yang dikelola secara kapitalistik dengan yang dikelola secara koperatif.
Aspek nir-esensial ini yang memungkinkan kita untuk membatalkan stigmatisasi koperasi sebagai melulu yang ada di desa, sebagai melulu milik kalangan ekonomi menengah ke bawah, dan stigma-stigma lainnya. Aspek nir-esensial (namun tidak anti-esensial!) yang mendorong kita untuk tidak mengutamakan corak koperasi yang satu ketimbang lainnya (misalnya, koperasi petani ketimbang koperasi buruh atau pegawai, atau lainnya). Dan akhirnya, justru aspek nir-esensial inilah yang menjadi kondisi objektif yang mampu menyatukan koperasi-koperasi yang berbeda corak ini sebagai suatu kesatuan untuk menjadi penantang kapitalisme, yang notabene juga memanifestasi pada bentuk-bentuk usaha yang beragam (mulai yang di desa sampai kota bahkan internasional, mulai yang sok DIY, ekonomi kreatif, M-SMEs, industri rumah tangga, sampai industri besar, mulai arisan sosialita sampai kartel bahkan pakta seperti BITs, TPP, RECP, dst.)[3]. Aspek nir-esensial koperasi inilah yang menjadikannya sebagai suatu politik tersendiri; koperasi adalah politis karena ia memungkinkan untuk menjadi medan kontestasi terbuka kepentingan dan aspirasi politik.
Lalu pertanyaan kemudian, corak pengorganisasian seperti apa yang menjadikan koperasi koperatif dan nir-kapitalistik, bahkan anti-kapitalistik? Pengorganisasian produksi seperti apakah yang membedakan koperasi dari sentralitas kepemilikan modal kapitalisme? Pembagian kerja seperti bagaimanakah yang membedakan koperasi dari kapitalisme? Pengukuran nilai kerja dengan standar seperti apakah yang membedakan koperasi dari pengaburan nilai kerja dengan waktu kerja yang dipakai kapitalisme? Lalu politik seperti apakah dari pengorganisasian produksi koperatif yang potensial untuk menjadi alternatif dalam membangkrutkan kapitalisme? Pertanyaan ini saya serahkan kepada kawan-kawan pegiat koperasi lainnya untuk meneruskan dan menghidupkan wacana ‘koperasi yang politis’ ini. Tidak hanya Dodi Fadlulloh dan kawan-kawan Kopkun Institute atau kawan-kawan saya di Koperasi Riset Purusha, melainkan juga kawan-kawan lain di, misalnya, Koperasi Litera, Koperasi Sorge, Credit Union Gerakan Lingkar Massa, Koperasi Komunitas Kalimetro, dan lainnya yang mungkin luput saya sebutkan.
Mengakhiri risalah singkat ini, saya ingin menukil surat Lenin kepada Maxim Gorky pada 1913. Dalam keprihatinan mendalam terhadap kawannya yang saat itu mendukung ideologi humanisme universal, Lenin mengingatkan Gorky untuk menjaga kesehatannya supaya tidak terkena flu mengingat saat itu sedang musim dingin. Kita saat ini tengah berada pada musim penghujan ideologi kapitalisme neoliberal, maka tidak ada salahnya bagi kita untuk saling mengingatkan kawan-kawan kita dan koperasinya untuk juga menjaga kesehatan masing-masing agar tidak terjangkit flu ideologis ini.***
Penulis adalah pegiat di Koperasi Riset Purusha
————-
[1] Lihat terjemahan kawan-kawan dari Koperasi Litera, “Belajar dari Kebangkrutan Mondragon: Keterbatasan Kooperasi dalam Sistem Kapitalisme,” http://literasi.co/Belajar-dari-Kebangkrutan-Mondragon)
[2] Lihat “The Italian Difference,” Cosmos & History, 5, 1, 2009.
[3] DIY—do-it-yourself; M-SMEs—Micro, Small and Medium Enterprises; BITs—Bilateral Investment Treaties; TPP—Trans-Pacific Partnership; RECP—Regional Economic Partnership.






