Fransiskus Hugo, Mahasiswa Antropologi Universitas Padjadjaran, Anggota Perhimpunan Muda
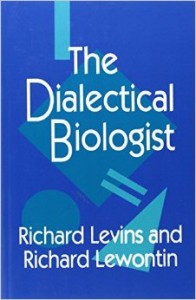
Judul Buku : Dialectical Biologist
Penulis : Richard Levins & Richard Lewontin
Penerbit : Aakar Books, 2009
Tebal : 296 Halaman
“Questions of science, science and progress, do not speak as loud as my heart.”
–Chris Martin
Pengantar
Sebagian dari kita pasti pernah belajar biologi di bangku sekolah, jika pun tidak minimal mengenal namanya. Kata biologi berasal dari dua kata Yunani yaitu bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Maka secara umum biologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mahkluk hidup (Ayala, 2009: 1-2). Pada tulisan sebelumnya, penulis telah membahas mengenai keterkaitan dari teori evolusi dari Darwin beserta kaitannya dengan Marxisme. Kali ini penulis akan menceritakan sedikit apa yang sudah penulis baca dari buku karya Richard Levins dan Richard Lewontin yang berjudul The Dialectical Biologist (2009). Richard Levins merupakan ahli ekologi, ahli genetik populasi, ahli matematika ekologi, aktivis sekaligus pengajar di Harvard T. H. Chan School of Public Health. Sedangkan Richard Lewontin, yang juga rekan satu almamater Levins di Columbia University Amerika Serikat, merupakan ahli biologi evolusioner, ahli genetik dan sekaligus akademisi. Keduanya menuliskan suatu karya yang cukup penting di dalam dunia akademik biologi pada buku ini. Tulisan Levins dan Lewontin ini kurang lebih membicarakan permasalahan biologi sebagai ilmu yang di satu sisi merupakan suatu pencerah dunia ilmu pengetahuan dan di sisi yang lain merupakan alat bagi kelas tertentu untuk mempertahankan posisinya di dalam struktur masyarakat yang sedang eksis. Selain itu, buku ini juga menawarkan cara berpikir materialisme dialektis dalam menghadapi jebakan-jebakan reduksionisme dan determinisme dari cara berpikir fisikalis atau mekanis.
Buku ini dibagi menjadi tiga bagian besar dan bab tambahan terakhir sebagai kesimpulan. Levins dan Lewontin memulai pembahasannya mengenai evolusi melalui bagian pertamanya yang berjudul On Evolution, pada bagian kedua mereka mulai menjelaskan mengenai analisis melalui bagian On Analysis. Lalu dilanjutkan pada bagian ketiga yaitu mengenai ilmu pengetahuan itu sendiri yang merupakan produk sosial beserta konsekuensi dari ilmu pengetahuan itu sendiri pada bagian Science as a Social Product and the Social Product of Science. Pada bagian terakhir Levins dan Lewontin menutup dengan bab berjudul Conclusion yang berisi tentang pentingnya cara berpikir secara dialektis dalam biologi.
Penulis tentu tidak akan membahas isi dari setiap bab dalam buku ini, namun penulis akan mencoba merangkum hal-hal atau pesan-pesan penting yang disampaikan oleh Levins dan Lewontin beserta implikasi teoritis juga praktis yang dihasilkan dari pembacaan buku ini. Meski penggunaan bahasa Inggris pada buku ini cukup sulit, mengingat penulis masih pemula dalam pembahasan mengenai bahasa dari ilmu biologi dan juga kurang fasihnya berbahasa Inggris, namun bagi pembaca yang lain mungkin direkomendasikan untuk membaca buku yang sangat bermanfaat ini, khususnya bagi pembaca yang merupakan salah satu akademisi biologi. Selain berguna untuk para akademisi yang berada dalam ranah biologi, cara berpikir materialisme dialektis yang ditawarkan oleh Levins dan Lewontin ini berguna sebagai pegangan filosofis dalam mengambil sikap.
Sekilas Biologi
Biologi yang kita ketahui sekarang ini sesungguhnya telah hadir sejak masa Yunani melalui pemikir seperti Aristoteles dan juga hingga masa para pemikir Romawi seperti Galen, meski pada kenyataannya hingga sebelum abad ke-16 ilmu biologi sangatlah terbengkalai. Namun, biologi mulai kembali dipergunakan oleh sekolah-sekolah medis di abad ke-16 dan juga para pemikir yang berpegang pada ilmu pengetahuan alam atau para naturalis. Banyak pemikir-pemikir filsafat yang mengaitkan biologi dengan cara pandang mereka, akan tetapi sejauh yang telah ada, biologi didasari oleh acara berpikir fisikalis sejak Rene Descartes, atau biasa disebut dengan Cartesianisme (Mayr, 2004: 16-17). Hal tersebut terjadi karena biologi merupakan salah satu cabang dari sains yang pada perkembangannya di abad pertengahan berkaitan erat dengan para tokoh-tokoh sains mekanis atau fisikalis.
Dalam biologi sendiri terdapat dua aliran yang besar, yaitu aliran biologi mekanistis atau fungsional dan biologi historis atau biologi evolusioner. Keduanya muncul dan berkembang pada periode tahun 1828 hingga 1866. Biologi fungsional berurusan dengan fisiologi dari seluruh aktivitas mahkluk hidup dan seluruh proses fungsional ini dapat dijelaskan secara mekanis oleh kimia dan fisika. Sedangkan biologi historis berurusan dengan evolusi, segala aspek kehidupan dapan ditelusuri secara historis atau dengan kata lain melalui evolusi itu sendiri. Perkembangan biologi ini mulai memuncak ketika Charles Darwin menerbitkan The Origin of Species pada tahun 1859. Mengingat sebelumnya biologi sangat didominasi oleh cara berpikir vitalisme dan teleologis.
Sebelumnya mungkin penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai vitalisme dan teleologis. Vitalisme merupakan pandangan yang menyatakan bahwa di balik kehidupan di dunia ini terdapat suatu kekuatan yang mengendalikannya, sama seperti gerakan bintang-bintang dan planet-planet yang dikondisikan oleh gravitasi, begitu juga dengan alam biologis yang digerakan oleh kekuatan tak terlihat yang disebut lebenskraft atau vis vitalis. Sedangkan Teleologi merupakan cara pandang yang menyatakan bahwa alam memiliki proses yang secara otomatis membawanya ke dalam suatu tujuan tertentu. Dengan terbitnya karya dari Darwin tersebut, cara berpikir vitalisme dan teleologis yang selama ini mendominasi dalam cara berpikir biologi pun mulai ditinggalkan karena penjelasan-penjelasan yang ada tak masuk akal.
Meski cara berpikir vitalisme dan teleologis sudah dikesampingkan dari biologi, muncul suatu pertentangan baru yang lebih panas dibandingkan sebelumnya. Pertentangan panas dalam biologi tersebut disebabkan karena masih berakarnya cara berpikir Cartesianisme. Yaitu karena masih bertahannya cara berpikir Cartesianisme di dalam biologi, yang secara terlihat atau tidak terlihat, disadari atau tak disadari masih menempel di dalam biologi kita hingga hari ini. Apakah yang dimaksud dengan cara berpikir Cartesian itu? Cartesianisme merupakan cara berpikir bahwa dunia ini merupakan sebuah jam yang oleh karenanya dapat ditelaah mesinnya seperti jarum jam, geligi-geligi, baterai dan lain-lain sebagai bagian-bagian penyokong jam tersebut lengkap dengan sifatnya masing-masing, sehingga bagian-bagian tersebut menentukan keseluruhan. Lalu, apa yang bermasalah dengan cara berpikir Cartesianisme tersebut? Tentu saja karena cara berpikir Cartesianisme, yang mana merupakan cara berpikir fisikalis, tidak sesuai dengan cara berpikir dalam ranah biologi. Misalnya dari cara berpikir esensialisme atau tipologi, determinisme dan reduksionisme (Mayr, 2004: 26-28). Apakah itu? Untuk lebih jelasnya, penulis akan mencoba memaparkan satu per satu hal-hal yang disebutkan di atas.
Esensialisme atau tipologi merupakan sebuah konsep tradisional yang hadir sejak masa Phytagoras hingga Plato yang menyatakan bahwa keragaman di dunia ini terdiri dari esensi tetap dan pembatasan tajam yang dalam jumlah terbatas. Determinisme sendiri merupakan konsekuensi dari penerimaan cara berpikir hukum Newton yang deterministis, bahwa sesuatunya yang ada di masa depan dapat diramalkan atau dapat diprediksi apabila kita mengerti hukum-hukum pasti atau alam yang ada. Sedangkan reduksionisme yang sering hadir dalam biologi ini merupakan cara berpikir yang menyatakan bahwa permasalahan di dalam suatu sistem dapat diselesaikan melalui pereduksian sistem tersebut menjadi komponen bagian-bagian kecil yang dianggap menyusun keseluruhannya. Hal-hal tersebut tidak sesuai dengan biologi yang mengenal keragaman dan peluang yang sehingga reduksionisme dan determinisme tak dimungkinkan. Sama seperti evolusi yang merupakan proses buta alam yang bergerak tanpa tujuan apapun, sehingga perubahan yang ada tidak selalu hadir menuju suatu hasil yang progresif namun dapat juga dapat regresif (Blackledge, 2002: 9). Pada akhirnya, terdapat beberapa tokoh-tokoh di dalam biologi yang merasa harus adanya pemisahan antara cara berpikir fisikalis tersebut dari biologi dan biologi bukanlah merupakan cabang ilmu dari fisika. Meski keberadaannya mengandaikan adanya fisika, bukan berarti cara berpikir biologi dapat direduksi ke dalam cara pikir fisikalis. Pertanyaannya kemudian, mengapa cara-cara berpikir ini tidak sesuai dengan biologi? Mari kita membicarakannya lebih lanjut dengan sedikit keluar dari jalur.
Sains Sebagai Ideologi
Jika kita mengingat apa yang mengkondisikan hadirnya masyarakat manusia tentu kita juga tak akan lupa dengan materialisme historis, bahwa perkembangan kesadaran berkorespondensi dengan perkembangan tenaga produktif dan relasi produksi (Suryajaya, 2012: 53). Selain itu, kita juga harus mengingat bahwa sejarah hingga hari ini merupakan perjuangan kelas, antara siapa yang ditindas dengan siapa yang menindas. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan sendiri merupakan produk dari masyarakat yang di dalamnya terdapat kontradiksi-kontradiksi dan perjuangan kelas tersebut. Dalam The German Ideology, Marx menjelaskan hal yang serupa, bahwa ide-ide dari kelas yang berkuasa merupakan ide yang berkuasa pada setiap zamannya dengan kata lain kelas yang menguasai sarana produksi pada saat yang bersamaan juga menguasai kekuatan intelektual (Marx & Engels, 1998: 67). Hal ini terlihat dari masa Renaissance hingga diterbitkannya The Origin of Species bahwa ilmu pengetahuan merupakan suatu alat yang mutakhir untuk menumbangkan tatanan yang sudah berdiri sebelumnya, yaitu feodalisme untuk digantikan dengan tatanan masyarakat yang lebih mutakhir yaitu kapitalisme tentu saja.
Munculnya ilmu pengetahuan revolusioner yang mampu menumbangkan feodalisme tersebut tentu merupakan produk dari masyarakat itu sendiri di satu sisi dan di sisi yang lain juga merupakan alat yang membangun tatanan sesudahnya (kapitalisme). Bila kita berbicara mengenai sains, kita tentu tak mungkin melepaskan pembicaraan tersebut kepada beberapa hal seperti metode, konsep-konsep, atau teori-teori, atau bahkan institusinya yang ada seperti profesor-profesor, jurnal dan universitas tertentu. Maka, sains bukanlah sesuatu hal ihwal yang berdiri sendiri netral terhadap segalanya yang ada di dunia ini, melainkan bagian dan produk dari masyarakat manusia itu sendiri. Sains tak akan terlepas dari urusan ekonomi dan politik dalam suatu masyarakat tertentu. Keduanya, struktur masyarakat dan sains, saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Namun, prasyarat dari adanya sains yang kita pahami hari ini tentunya hadir dari suatu bentuk masyarakat yang sudah bukan merupakan masyarakat yang berbentuk feodalisme lagi, melainkan masyarakat kapitalisme yang telah menumbangkan dominasi bentuk masyarakat feodalisme sebelumnya.
Sains yang ada hingga hari ini secara garis besar merupakan dan telah menjadi alat untuk melanggengkan tatanan kapitalisme. Jadi, wajarlah bila sains seakan menjadi agama baru. Wajar pula bila Richard Dawkins dengan karyanya The Selfish Gene dan E. O. Wilson dengan karyanya Sociobiology seakan menjadi nabi bagi para ilmuwan borjuis. Karya-karya itu pun menjadi kitab bagi ilmuwan-ilmuwan borjuis, tentu karena ilmu yang mereka tawarkan sejalan dengan logika yang terdapat di struktur masyarakat kapitalisme. Memulai penjelasannya dari gen ke organisme hingga populasi, Dawkins menyatakan bahwa tubuh hanya merupakan mesin yang digerakan oleh gen dengan kata lain tubuh merupakan boneka bagi gen. Mengapa? Karena menurutnya seleksi alam berada di ranah gen tersebut, maka dengan demikian individu cenderung untuk mempertahankan gen dan juga cenderung untuk mereproduksi sebanyak mungkin gen tersebut. Dengan demikian, Dawkins dapat mengambil kesimpulan bahwa organisme merupakan individu yang egois dan individualistis, karena selain dirinya atau satu gen atau kerabat dekat merupakan sesuatu yang lain dari dirinya yang mampu dieksploitasi (Dawkins, 2006: 66).
Padahal pada kenyataannya, realitas tidak dapat serta merta dikerucutkan melalui reduksi tersebut, mengingat terdapat keragaman dan peluang-peluang tertentu pada suatu spesies. Contohnya seperti kebudayaan dalam masyarakat manusia yang dalam batas-batas tertentu mampu mengkondisikan basis. Untuk dapat memahami lebih jelas mengenai sosiobiologi ini, pembaca dapat menyimaknya kembali di Kolom Logika Dede Mulyanto tentang Marxisme dan Sosiobiologi. Namun tak hanya mereka berdua yang berada di ranah ilmu alam, tapi di ranah ilmu sosial seperti ekonomi, hukum, sosiologi hingga antropologi pun demikian. Mengapa hal itu bisa sampai terjadi? Mari kita bicarakan lebih lanjut.
Pertama, yaitu bahwa di balik segala macam sains yang ada terdapat suatu cara pikir mekanistis yang diwariskan oleh para pemikir-pemikir atau ilmuwan-ilmuwan pelopor sains. Cara berpikir tersebut mucul sejak Rene Descartes lalu mendominasi sejak masa Galileo Galileidan semakin berkembang semenjak Isaac Newton mengemukakan Hukum Gravitasinya tersebut pada 1687. Cara berpikir ini sering disebut dengan Fisikalisme atau cara berpikir fisikalis atau Cartesianisme (Mayr, 2004: 17). Konsekuensi dari cara berpikir Cartesianisme inilah yang nantinya membawa ilmu pengetahuan berperan sebagai penyokong bentuk masyarakat yang sedang eksis hari ini.
Biologi yang selama ini kita anggap sebagai salah satu cabang sains yang memiliki keunggulan tersendiri ternyata juga tak terlepas dari jerat cara berpikir Cartesianisme.Untuk mempermudah pemahaman, Levins dan Lewontin (2007) dalam The Dialectical Biologist menyimpulkan cara berpikir Cartesian ditandai dengan 4 komitmen ontologis di bawah ini yaitu;
- Terdapat sekumpulan suatu bagian-bagian alamiah di mana suatu sistem keseluruhan dibuat.
- Suatu bagian-bagian atau unit-unit ini merupakan homogen di dalam dirinya sendiri, setidaknya sejauh mereka mempengaruhi keseluruhan yang di mana mereka hadir sebagai bagian.
- Bagian-bagian hadir secara ontologis mendahului suatu keseluruhan. Bagian-bagian hadir dalam pemisahan dan hadir bersama sebagai keseluruhan. Bagian memiliki pada dirinya sendiri sifat atau cirinya. Dengan kata lain, suatu keseluruhan merupakan hasil jumlah dari semua bagian-bagiannya.
- Suatu penyebab terpisah dengan akibat. Penyebab merupakan sifat dari subjek, sedangkan akibat merupakan sifat dari objek.
Keempat komitmen di atas itulah yang ditemukan dalam cara berpikir Dawkins dan Wilson dalam karya-karyanya. Tapi selain pada sosiobiologi, salah satu dampak dari pengamalan iman Cartesianisme ini juga terlihat dari cara pandang biomedis dalam ilmu-ilmu kesehatan dewasa ini. Winkelman (2009) menjelaskan bahwa pandangan biomedis dicirikan dengan pendekatan-pendekatan ilmiah dan membedakan dirinya dengan sistem etnomedisin yang dianggap selama ini berkaitan dengan hal-hal religius, takhayul, perdukunan atau bahkan penipuan (Winkelman, 2009: 6). Oleh karena itu, pandangan biomedis terkadang abai akan peluang terjadinya beberapa bentuk sakit atau illness yang sifatnya kultural, sebagai contoh masuk angin atau praktik kerokan dan lain-lainnya yang dianggap tidak ilmiah oleh pandangan biomedis.
Karena biomedis cenderung lebih melihat suatu penyakit dari faktor biologisnya saja, maka menurut hemat penulis biomedis pun jatuh dalam sifat deterministis dan reduksionistis yang penulis telah jelaskan di atas tadi. Seperti penyebaran penyakit flu atau Tuberculosis (TBC) yang cepat menyebar pada penduduk di suatu lingkungan kumuh kampung perkotaan misalnya hanya dilihat dari patogen virus atau bakteri penyebabnya saja tanpa mempertimbangkan berbagai faktor lain yang mendukung penyebaran penyakit tersebut. Biomedis abai terhadap faktor-faktor seperti lingkungan, tata ruang, perilaku-perilaku tertentu bahkan ekonomi politik yang juga ikut mengkondisikan penyebaran flu atau TBC tersebut. Meski patogen memiliki peranan penting dalam penyebaran penyakit tersebut, namun bukan berarti faktor-faktor lain tidak ikut mempengaruhinya. Contohnya, pengaruh tata ruang bangunan pemukiman yang padat di perkotaan Jakarta memungkinkan penghuninya sering berinteraksi satu dengan lainnya secara sadar atau tak sadar mereka hidup berdekatan, sehingga tak dapat dipungkiri bahwa suatu penyakit sebagai contoh influenza mampu dengan cepat menyebar dari satu penghuni kepada yang lainnya. Ini baru satu contoh dari penyebaran penyakit, masih terdapat contoh-contoh wabah yang lainnya yang tentu saja pembaca sering melihatnya di kehidupan sehari-hari.
Konsekuensi dari pengimanan Cartesianisme tersebut pada saatnya tentu juga akan berdampak kepada hal-hal praktis seperti pengambilan keputusan, kebijakan, hukum dan lain-lainnya. Sebagai contoh beberapa kebijakan pemerintah terkait kesehatan warganya juga terlihat masih tak tepat sasaran. Menurut hemat penulis, hal tersebut disebabkan karena pemahaman mengenai isu-isu kesehatan yang tidak holistik atau tak menyeluruh. Tentu hal ini karena masih mendominasinya cara pandang Cartesianisme dari para pengambil kebijakan yang berada di dalam struktur pemerintahan. Misalnya yaitu Kartu Jakarta Sehat (KJS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan pengobatan gratis yang kini mampu dinikmati warga DKI Jakarta bila berobat ke puskesmas atau rumah sakit umum. Di satu sisi, kebijakan tersebut dianggap sebagai jalan keluar bagi permasalahan kesehatan, namun di sisi lain, kebijakan tersebut menyasar bayang-bayang. Tentunya hal itu disebabkan oleh jumlah warga Jakarta yang tak sepadan dengan sarana-sarana pelayanan serta tenaga kesehatan yang terdapat di Jakarta. Oleh karena itu, wajarlah bila puskesmas atau rumah sakit kurang maksimal dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan dapat kita saksikan sendiri penuh setiap harinya. Selain itu, jaminan sosial seperti BPJS pun menjadi sejenis asuransi-asuransi kesehatan yang digalangkan. Di satu sisi membuat warga merasa sayang bila uang yang ditabungnya di asuransi tersebut tak dipergunakan, sehingga hal itu menimbulkan perilaku “sedikit, sedikit berobat, sedikit, sedikit berobat.” atau dengan kata lain menciptakan suatu ketergantungan. Di sisi lain, kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai rencana dan ternyata lebih membawa permalasahan baru ketimbang menyelesaikan permasalahan kesehatan.[1]
Dengan demikian, ada benarnya bila Womack (2010) menyatakan bahwa kekurangan dari sains dan khususnya biomedis ini ialah asumsinya yang menyatakan bahwa variabel yang kompleks dapat direduksi ke dalam satu variabel saja (Womack, 2010: 180). Bukan berarti penulis menyatakan bahwa biomedis tidak memiliki pengaruh yang positif dan bermanfaat, namun penulis mencoba mengevaluasi kembali cara berpikir biomedis ini.
Apakah yang dapat kita temukan di sana? Tentu saja bagaimana tradisi cara berpikir Cartesianisme tersebut sejalan dengan logika masyarakat kapitalisme yang hari ini eksis sebagai moda produksi yang paling unggul. Melalui Cartesianisme, patogen seperti virus dan bakteri menjadi satu-satunya penyebab dari berbagai macam penyakit, individu-individu merupakan fokus dari suatu penyakit, sehingga dengan demikian obat-obatan farmasi lah menjadi jalan keluar satu-satunya, sedangkan di satu sisi perusahaan farmasi pun menjadi mampu terus mengakumulasikan modalnya. Oleh karena itu, calon-calon dokter dididik menjadi tenaga medis yang hanya mendukung berjalannya akumulasi perusahaan farmasi atau rumah sakit tertentu, mengingat dokter memiliki legitimasi untuk pengkonsumsian obat-obatan. Karena mencetak tenaga-tenaga yang diperlukan untuk pasar maka akhirnya ongkos pendidikan tenaga medis pun semakin tak terjangkau dan para tenaga medis pun terdorong untuk membalik modal yang menyebabkan tak jarang membuka praktik dengan harga yang juga tak terjangkau. Selain itu, tenaga medis pun hanya dididik untuk menjadi roda-roda kecil yang menjalankan mesin akumulasi kapital dalam masyarakat kapitalisme. Kenyataan tersebut juga terlihat dari lebih berorientasinya sarana kesehatan seperti rumah sakit kepada pelayanan kuratif-rehabilitatif dan mengesampingkan pelayanan promotif-preventif karena memang hanya memiliki sedikit nilai ekonomis jika dibandingkan dengan pelayanan kuratif-rehabilitatif (Supratman & Prasetyo, 2010: 40-41).
Cerita seperti ini bahkan juga terjadi di antara ranah pendidikan ilmu sosial, ketika universitas hanya mencetak lulusan semacam geligi dan pelumas untuk menjalankan tatanan ini. Terlihat dari kebijakan untuk cepat meluluskan peserta didiknya dengan kurun waktu di bawah tujuh tahun. Maka ketimbang mendidik mahasiswanya sebagai intelektual yang kritis akan kesadaran rakyat pekerja. Inilah fakta yang yang sesungguhnya dari keselarasan antara kapitalisme dan Cartesianisme, karena semua hal tersebut hanya dimungkinkan oleh mode produksi kapitalisme itu sendiri. Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa alangkah baiknya mencegah dibandingkan mengobati. Maka konsekuensinya yaitu perbaikan lingkungan hidup bukanlah hanya di penyediaan prasarana atau pun sarana kesehatan saja melainkan pengkajian kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan kemaslahatan masyarakat. Seperti salah satu contohya yaitu kebijakan pemerintah mengenai pembangunan pemukiman rakyat yang sehat atau tentu saja pengaturan tata ruang kota yang lebih baik lagi. Sedangkan dari sisi medis peran preventif serta promotif dari puskesmas serta sarana kesehatan lainnya harus dilaksanakan kembali, mengingat selama ini puskesmas lebih sering berperan layaknya klinik atau poliklinik saja yang hanya mengobati dan mengobati.
Untuk melakukan langkah-langkah besar tersebut tentunya kita takan mampu menggapainya tanpa melalui langkah kecil pertama. Melalui pemahaman mengenai bagaimana sains khususnya biologi tersebut bekerja dan mengevaluasi lagi apa yang dapat kita lakukan, maka kita akan dapat melanjutkan langkah selanjutnya. Menurut Levins dan Lewontin, salah satu cara dari biologi untuk keluar dari cengkeraman Cartesianisme itu sendiri ialah dengan memikirkan kembali konsep bagian-bagain dan keseluruhan menggunakan cara berpikir dialektis, sehingga kita takkan terjebak oleh jebakan-jebakan empiris atau positivis dari sains dewasa ini.
Jalan Keluar Dialektis
Mengetahui bahwa kebangkitan sains modern didukung oleh perjuangan kelas yang hadir secara historis tersebut maka sains itu sendiri layaknya sebuah pisau, sedangkan pisau dapat digunakan oleh siapa pun yang berniat menggunakannya. Bagi seorang Danjen Kopassus, pisau merupakan alat untuk melumpuhkan para Pejuang Fretilin di Timor Leste. Sedangkan bagi Chef Farah Quinn, pisau merupakan alat untuk memotong bumbu serta bahan-bahan untuk memasak Chicken Cordon Bleu. Dengan demikian sains harus kembali kepada realitas. Dengan kata lain tidak melupakan unsur realisme, mengingat realisme merupakan premis pertama dari dari materialisme dialektis itu sendiri yang berarti mengakui keberadaan dan objektivitas materi yang mendahului subjek (kesadaran) dan objek (keterberian pada kesadaran) (Suryajaya, 2012: 53). Maka konsekuensinya kita tidak dapat serta merta membelah suatu permasalahan ke bagian paling kecil partikel penyusunnya sambil mengandaikan seluruh faktor ceteris paribus, melainkan berangkat dari kenyataan kondisi realita yang ada yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Bahwa terdapat kondisi-kondisi riil objektif yang perlu juga dipertimbangkan dalam menentukan tiap langkah yang akan dijejaki. Oleh karena itu, penting kiranya dipertimbangkan bila melalui sains, khususnya biologi, kita mampu memulai langkah untuk pembebasan mereka yang selama ini ditindas dan dieksploitasi.
Levins dan Lewontin menggambarkan cara pandang yang dijelaskan prinsip-prinsip di atas sebagai dunia yang terasing, sama seperti keterasingan yang dirasakan oleh kelas pekerja di dalam tatanan masyarakat yang sedang eksis ini. Dunia di mana suatu bagian terpisah dari keseluruhan, mengabstraksi pada dirinya sendiri, lalu suatu penyebab terpisah dari akibat dan suatu subjek terpisah dari objek. Menurut mereka berdua, hal tersebut merupakan dunia fisik yang mencerminkan struktur dunia sosial yang terasing. Bahwa individu-individulah yang memerankan peranan penting kehidupan, bukan masyarakat sebagai struktur. Hal inilah yang sejalan dengan nafas kapitalisme dengan ilmu pengetahuan sebagai oksigennya, yaitu suatu bentuk masyarakat yang dengan semangat perniagaan dan individualisme.
Untuk membendung cara berpikir Cartesianisme tersebut, Levins dan Lewontin pun mengupayakan jalan keluar yaitu sebuah pengertian mengenai prinsip-prinsip dialektika dalam sains dengan prinsip utama ialah bahwa (1) keseluruhan merupakan relasi dari bagian-bagian yang beraneka ragam yang tak memiliki keberadaannya sendiri yang mendahului sebagai bagian-bagian. Prinsip kedua yaitu bahwa (2) secara umum sifat dari bagian-bagian tak memiliki keberadaan tersendiri yang mendahului, namun diperoleh sebagai bagian dari keseluruhan tertentu. Prinsip ketiga yaitu bahwa (3) interpenetrasi atau kesalingterobosan antara bagian-bagian dan keseluruhan merupakan konsekuensi dari kemampuan untuk saling berubah-ubah antara subjek dan objek, antara sebab dan akibat. Prinsip keempat yaitu(4) karena setiap elemen saling menciptakan satu dengan lainnya dengan berinteraksi dan dengan demikian diciptakan dari keseluruhan yang merupakan terdiri dari bagian-bagian, perubahan merupakan suatu karakteristik dari segala sistem dan semua aspek dari semua sistem (Levins & Lewontin, 2009: 273-275). Prinsip-prinsip di atas bila kita perhatikan tentunya berlawanan dengan keempat komitmen dari cara berpikir Cartesianisme yang sebelumnya sudah penulis ceritakan. Namun, cara berpikir dialektis yang dijelaskan di atas bukanlah seperti dialektika yang dijelaskan oleh Hegel yang mana relasi internal berlaku secara asali atau universal, melainkan materialisme dialektis yang harus ditemukan melalui analisis dan bukan yang dipostulatkan sejak semula (Suryajaya, 2012: 65-66). Maka, kita mesti memandang dialektika tersebut secara realis dan materialis agar tak terjebak dalam lingkaran idealisme tak terputus antara subjek-objek. Hal ini pun ditegaskan oleh Levins dan Lewontin ketika menolak menganggap dialektika ini sebagai suatu hukum pasti yang berasal dari alam, melainkan mereka melihat dialektika ini sebagai sebuah asas-asas yang sifatnya seperti asas variasi, heritabilitas dan seleksi dari Darwin yang kuantifikasi dan prediksinya memiliki batasan tertentu atau term of reference (Levins & Lewontin, 2009: 267-268). Oleh karena itu, penting bagi pembaca untuk mengingat bahwa dialektika yang digunakan bukanlah dialektika Hegel yang idealis melainkan materialisme dialektika yang tentunya realis dan historis.
Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa suatu bagian-bagian hanya dapat menjadi bagian apabila ada suatu keseluruhan yang menjadikan dirinya sebagai bagian-bagian. Selain itu, kita juga harus mengingat bahwa suatu bagian-bagian mempengaruhi suatu keseluruhan dan keseluruhan pun mempengaruhi bagian-bagian. Maka dengan demikian, cara berpikir empirisme materialis para ilmuwan-ilmuwan akan terjatuh dan terjebak dalam lubang idealisme yang sama dan melupakan realitas. Sebagai contoh pada isu kesehatan, sehingga kita tak hanya melihat permasalahan kesehatan hanya kepada individu-individu atau pengobatan-pengobatannya saja melainkan secara aspek keseluruhan. Yaitu bahwa manusia merupakan mahkluk biologis sekaligus mahkluk sosial, sehingga suatu permasalahan kesehatan bukanlah karena patogen atau genetika semata melainkan terdapat faktor-faktor lain pendukungnya seperti lingkungan, kebudayaan, perilaku, ketersediaan sarana kesehatan tertentu, hingga faktor ekonomi politik tertentu seperti kebijakan-kebijakan pemerintah atau pasar.
Penulis berpendapat bahwa kajian-kajian lintas ilmu pengetahuan tampaknya akan sangat baik bagi para pemuda dan tentunya bagi pergerakan rakyat pekerja. Melalui pengujian kembali kebenaran Marxisme dengan ilmu pengetahuan, sekaligus menggunakan sains melalui nafas materialisme historis dialektis, maka kita telah melakukan langkah awal perjuangan dengan cara yang relevan. Maka materialisme saja tanpa dialektika sangatlah berbahaya, karena mau tak mau akan terjatuh ke dalam reduksionisme yang demikian ilmu pengetahuan akan terus menjadi penyokong tatanan yang eksis hari ini. Kepada siapa saja yang bergerak di ranah biologi, penulis memberikan saran untuk tetap mempelajari filosofi dari biologi, supaya tidak terjebak dalam cara bepikir fisikalis yang sudah dijelaskan di atas. Dengan kata lain, para biolog harus lebih kritis lagi dan harus terus selalu bertanya. Akhir kata, mungkin sudah saatnya penulis mengajak para intelektual untuk segera turun dari menara gading keilmuannya dan dengan ilmu yang dimiliki menghadapi kehidupan nyata serta berkontribusi dalam pembebasan rakyat pekerja.
Mengingat hal itu, kesadaran perjuangan kelas harus dibangun. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk itu? Tentu melalui pembelajaran kembali Marxisme dan persiapan membangun partai revolusioner yang mampu menampung arah perjuangan gerakan kita sehingga perjuangan kelas pekerja memiliki satu arah yang pasti. Sebab revolusi bukanlah sesuatu yang datang sendiri atau jatuh dari langit, melainkan harus diraih melalui perjuangan. Untuk itu tampaknya kita harus kembali mengingat poin kesebelas Marx dari Theses On Feuerbach yang berbunyi “Para filsuf hanya menafsirkan dunia dalam berbagai cara; pada intinya adalah mengubahnya.”(Marx & Engels, 1998: 571). Kemudian oleh Levins dan Lewontin kalimat tersebut diparafrasakan kembali di akhir buku ini menjadi “Para filsuf dialektis hanya menjelaskan sains, namun pada intinya adalah mengubahnya.”
Daftar Pustaka Tambahan
Ayala, Fransisco. 2009. Contemporary Debates in Philosophy of Biology. Sussex: Willey-Blackwell.
Blackledge, P., & Kirkpatrick, G. 2002. Historical Materialism and Social Evolution. Hampshire: Palgrave Macmillan.
Dawkins, Richard. 2006. The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press.
Mayr, Ernst. 2004. What Makes Biology Unique? Considerations on the Autonomy of a Scientific Discipline. Cambridge: Cambridge University Press.
Marx, Karl., Engels, Friederich. 1998. The German Ideology. New York: Prometheus Books.
Supratman, Dedi., & Prasetyo, Eko. 2010. Bisnis Orang Sakit. Yogyakarta: Resist Book.
Suryajaya, Martin. 2012. Materialisme Dialektis. Yogyakarta: Resist Book.
Winkelman, M. 2009. Culture and Health. San Fransisco: Jossey-Bass
Womack, Mari. 2010. The Anthropology of Health and Healing. Lanham: AltaMira Press
[1]Lihat. http://solidaritas.net/2015/06/bpjs-semakin-mencekik.html






