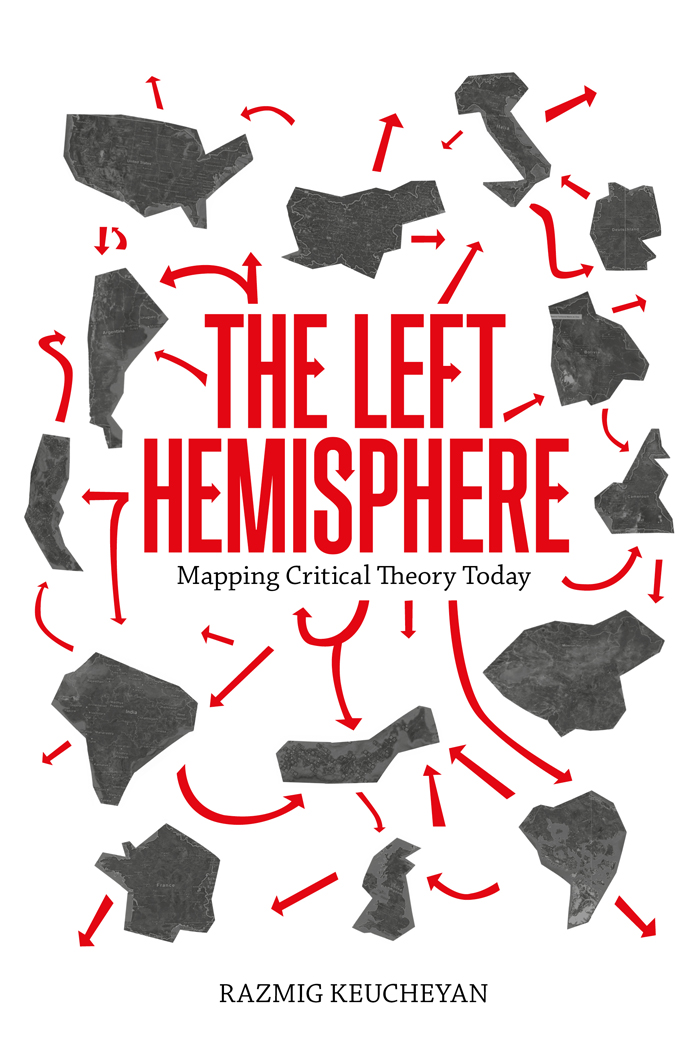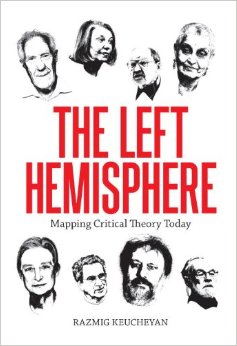
Judul buku : The Left Hemisphere Mapping Critical Theory Today
Penulis : Razmig Keucheyan
Penerbit : Verso, London, 2014
Tebal : 257 hal.
SEBAGAI editor, saya sangat sering menerima tulisan yang penuh dengan kutipan-kutipan para raksasa pemikir dunia. Kesan pertama melihat tulisan seperti itu adalah ‘sang penulis bacaannya luar biasa panjang.’ Setelah membaca lebih teliti, umumnya yang saya temukan adalah jenis tulisan dimana si penulis sudah memiliki opininya terlebih dulu dan para pemikir itu dikutip untuk melegitimasi pemikirannya tersebut. Banyak membaca tapi tidak disiplin dalam berteori.
Akibat dari praktik pengutipan seperti ini, kita temukan sebuah tulisan dimana Marx dicampur dengan Weber atau Adorno dipadu dengan Foucault secara serampangan. Di sini penulis tidak bergumul dengan serius pemikiran pemikir yang dikutipnya, atau menghadapi pemikir yang dikutipnya dengan sikap yang kritis. Akibatnya, tegangan metodologis dan analitis dari masing-masing pemikir tersebut diabaikan, serta bingung tak karuan dalam memformulasikan idenya sendiri. Tentu saja saya tak menolak tradisi eklektik dalam pemaparan argumentasi sejauh kita (1) mengetahui dengan jelas posisi teoritik dari penulis yang kita kutip; (2) memaparkan perbedaan posisi tersebut kepada pembaca; dan (3) menunjukkan posisi teoritik kita sendiri di antara berbagai posisi teoritik yang digunakan itu.
Pengutipan seperti ini mensyaratkan seorang penulis untuk sungguh-sungguh memahami pemikiran dari orang yang dikutipnya, konteks sosial politik ketika pemikiran itu dituliskan, serta relevansinya dengan kondisi sosial politik kekinian. Dengan demikian, penulis atau intelektual sejatinya adalah seorang pengelana yang tangguh: ia diharuskan untuk kembali ke masa lalu, menginvestigasi dan melakukan verifikasi secara hati-hati terhadap peristiwa-perisitwa di masa tersebut dan kemudian menarik sebuah abstraksi untuk memahami masa kini dan memproyeksikan sebuah perubahan.
Buku Keucheyan ini sungguh membantu kita untuk tidak terjerumus dalam praktik pengutipan yang serampangan. Sebagaimana judulnya, Benua Kiri Pemetaan Teori Kritis Hari Ini, Keucheyan dengan singkat, padat dan jelas menunjukkan kepada kita tentang geografi dan genealogi para pemikir kritis kontemporer serta gagasan yang mereka usung. Walaupun buku ini merupakan ringkasan pemikiran, ia sama sekali terhindar dari reduksionisme. Keucheyan berhasil menunjukkan esensi dari pemikiran para pemikir tersebut. Karena itu, saya menyebut buku ini sebagai bacaan ringan yang berat. Ringan karena bahasanya yang tidak njlimet dan penuturannya yang mengalir lancar sehingga Anda seperti dituntun dengan hati-hati untuk memasuki samudra pemikiran kritis kontemporer ini, sekaligus berat karena Anda juga paling tidak telah sedikit terbiasa dengan karya-karya para pemikir tersebut. Sebab, jika tidak Anda terpaksa harus terus membolak-balik karya-karya mereka untuk meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang ditulis Keucheyan benar adanya.
Dalam buku ini, Keucheyan menunjukkan akar tradisi pemikiran dari para pemikir yang diulasnya, seperti apa konteks hubungan sosial dan politik yang mengispirasi dan kemudian mendorong mereka dalam merumuskan pemikirannya. Dengan demikian kita tahu bahwa intelektual besar itu senantiasa berdiri di atas pundak intelektual besar lainnya, dan lebih mendasar lagi, sebuah pemikiran merupakan hasil pergumulan si pemikir dengan hubungan sosial-politik pada masanya. Tidak ada karya intelektual yang jatuh dari langit. Semua memiliki tradisinya, merupakan hasil kerja manusia yang nyata.
Buku ini terdiri dari dua bab besar. Bab I membahas tentang konteks kemunculan teori kritis baru itu, sedangkan bab II membahas teori-teori dari para pemikir kritis baru tersebut. Bagi pembaca ilmu sosial di Indonesia, bab II mungkin merupakan bagian paling menarik karena ia membahas pemikiran dari nama-nama yang populer berseliweran dalam jagad intelektual kita. Dari lebih dari 33 penulis yang diulasnya, kita menemukan para idola seperti Antonio Negri, Slavoj Žižek, David Harvey, Benedict Anderson, Jurgen Habermas, Judith Butler, Nancy Fraser, Giorgio Agamben, Gayatri Spivak, Alain Badiou, atau Jacques Ranciere.
Namun demikian, ulasan ini akan fokus pada bab I, yang menurut saya paling relevan untuk dibandingkan dengan Indonesia. Saya tidak akan meringkas buku ringkasan pemikiran ini. Itu kerja sia-sia yang akan membuat minat dan keseriusan pembaca membaca buku ini hancur berantakan. Apa yang ingin saya soroti dari buku ini, dengan demikian, bukan keberhasilan Keucheyan dalam menyarikan pemikiran para pemikir tersebut, tetapi lebih kepada bagaimana ia menunjukkan hubungan antara pemikiran dari para pemikir tersebut dengan kondisi sosial politik yang dihidupinya serta bagaimana mereka meresponnya.
Sebelum lanjut, Keucheyan memberikan klarifikasi tentang apa yang ia maksud dengan teori kritis terbaru, apa yang dimaksud dengan teori dari teori kritis tersebut, serta apa yang kritikal dari teori tersebut. Kebaruan disini merujuk pada pemikiran yang muncul pasca runtuhnya tembok Berlin pada 1989. Tentu saja teori kritis Baru ini memiliki akarnya pada pemikiran sebelum 1989, tetapi mereka umumnya menjadi penting pasca 1989. Sementara Teori yang dimaksud Keucheyan tidak hanya bermakna sebagai analisis atau interpretasi, tidak sekadar refleksi tentang apa yang terjadi dengan menjelaskan realitas sosial di masa lalu dan masa kini sebagaimana layaknya ilmu sosial empiris. Teori disini sekaligus mempertanyakan apa yang diinginkan dari analisa atau penafsiran tersebut. Dengan demikian teori ini mengandung keberpihakan politik, ia menolak klaim ilmu sosial sebagai ‘bebas nilai’ sebagaimana yang dikemukakan oleh Max Weber. Adapun Kritikal bermakna teori kritis baru ini secara total atau komprehensif menantang tata sosial yang ada. Mereka tidak memiliki perhatian pada aspek-aspek tertentu atau partikular dari sistem sosial yang ada, melainkan keseluruhan tata sosial itu sendiri yang dipersoalkan. Keucheyan mencontohkan, para pemikir baru ini tidak mempertanyakan soal efektivitas penerapan pajak transaksi keuangan global (melalui penerapan Tobin Tax), tetapi pada karakter umum dari sistem kapitalisme kontemporer (h. 1-3).
Pengutamaan Pada Superstruktur
Salah satu diktum Marx paling terkenal adalah ‘kesadaran (consciousness) manusia ditentukan oleh keberadaan sosialnya (social being).’ Konsekuensinya, untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi bukan dengan menganalisa apa yang manusia pikirkan (kesadaran), sebaliknya, keberadaan sosial (kondisi-kondisi material dan kontradiksi antara kekuatan produksi dan hubungan produksi) itulah yang harus dianalisa untuk mengetahui kesadaran tersebut.
Diktum ini tampak sangat kuat melatari metodologi Keucheyan dalam buku ini. Sebelum memaparkan pemetaannya atas para pemikir kritis kontemporer itu, Keucheyan terlebih dulu mengulas tentang latar belakang sosial politik dari kemunculan beragam pemikiran itu. Kesimpulannya, pemikiran kritis baru ini adalah produk dari sebuah periode yang kalah. Periode tersebut adalah runtuhnya Tembok Berlin pada 1989.
Keruntuhan Tembok Berlin itu menandai kegagalan tiga eksperimen penting dalam sejarah pemikiran dan gerakan: pertama, gagalnya apa yang disebut sebagai gerakan Kiri Baru (New Left) yang muncul pada dekade 1950an. New Left ini merujuk pada gerakan Maois, Trotskys, Anarkhis dan yang disebut ‘gerakan sosial baru/new social movement’,seperti gerakan feminism dan politik ekologi. Kedua, kegagalan itu juga merujuk pada bangkrutnya eksperimen gerakan-gerakan sosial politik non-kapitalistik yang untuk pertama kalinya muncul di Rusia pada Oktober 1917, yang populer disebut Revolusi Bolshevik. Gerakan Kiri Baru itu sendiri lahir, salah satunya, sebagai respon atas Stalinisme yang dianggap totaliter dan telah menyimpang jauh dari Marxisme dan Leninisme. Jika ditarik lebih ke belakang, runtuhnya Tembok Berlin juga menandai kegagalan atas apa yang disebut sebagai proyek modernisasi yang ditandai oleh Revolusi Prancis tahun 1789. Dari perspektif ini maka apa yang dikenal dalam sejarah sebagai Revolusi Rusia dan Revolusi Cina, sebenarnya hanya turunan dari ideal-ideal yang sudah dipancangkan semenjak Revolusi Prancis tersebut. Karena itu, apa yang selama ini dikenal dalam kategori-kategori intelektual, seperti ilmu pengetahuan (science), akal (reason), waktu (time) dan ruang (space); serta kategori-kategori politik, seperti kedaulatan (sovereignity), kewargaan (citizenship) dan wilayah (territory), yang selama ini identik dengan politik modern harus diabaikan, diganti dengan kategori-kategori baru seperti jaringan (network) dan identitas (identity). Intinya, apa yang sudah diawali sejak tahun 1789, 1914-1917, dan 1956 berakhir pada 1989 (hal. 7-9).
Keucheyan selanjutnya mengatakan, walaupun tidak dengan sendirinya terkait langsung dengannya, para pemikir kritis baru ini adalah pewaris yang sah dari apa yang disebut Marxisme Barat (Western Marxism) (hal. 12). Dengan demikian, untuk mengerti gagasan dan praktik politik pemikiran kriti baru kita mesti melihat ciri utama dari Marxisme Barat dibandingkan dengan Marxisme Klasik.
Tabel 1
Tokoh-Tokoh Marxisme Klasik dan Marxisme Barat
| Marxisme Klasik | ||
| Nama | Periode | Tempat Lahir |
| Karl Marx | 1818-1883 | Trier (Rheinland) |
| Fridriech Engels | 1820-1895 | Barmen (Westphalia) |
| Antonio Labriola | 1843-1904 | Cassio (Campania) |
| Franz Mehring | 1846-1919 | Schlawe (Pomerania) |
| Karl Kautsky | 1854-1938 | Prague (Bohemia) |
| Georgi Plekhanov | 1856-1918 | Tambov (Central Rusia) |
| Lenin | 1870-1923 | Simbirsk (Volga) |
| Rosa Luxemburg | 1871-1919 | Zamosc (Galicia) |
| Rudolph Hilferding | 1877-1941 | Vienna |
| Leon Trotsky | 1879-1940 | Kherson (Ukraine) |
| Otto Bauer | 1881-1938 | Vienna |
| Yevgeni Preobrazhensky | 1886-1937 | Orel (Central Rusia) |
| Nikolai Bukharin | 1888-1938 | Moscow |
| Marxisme Barat | ||
| Georg Lukacs | 1885-1971 | Budapest |
| Karl Korsch | 1889-1961 | Todstedt (West Saxony) |
| Antonio Gramsci | 1891-1937 | Ales (Sardinia) |
| Walter Benjamin | 1892-1940 | Berlin |
| Max Horkheimer | 1895-1973 | Stuttgart (Swabia) |
| Galvano Della Volpe | 1897-1968 | Imola (Romagna) |
| Herbert Marcuse | 1898-1979 | Berlin |
| Henri Lefebvre | 1901-1991 | Hagetmau (Gascony) |
| Theodor Adorno | 1903-1969 | Frankfurt |
| Jean-Paul Sartre | 1905-1980 | Paris |
| Lucien Goldman | 1913-1970 | Bucharest |
| Louis Althusser | 1918-1990 | Birmandreis (Algeria) |
| Lucio Colletti | 1924-2001 | Rome |
Sumber: Perry Anderson, Considerations of Western Marxism, dengan sedikit penyesuaian.
Pada mulanya, istilah Marxisme Barat digunakan oleh Komunis Sovyet untuk menyebut pembalikan Marxisme kepada Hegelianisme dan bentuk-bentuknya yang kritis dari pemikiran Marxis di Barat. Tapi kemudian istilah ini diadopsi oleh intelektual Marxis seperti Georg Lukacs dan Karl Korsch untuk membedakan penafsiran Marxis mereka yang lebih independen dan kritis dibandingkan dengan penafsiran partai dan ‘ilmiah/scientific dari Internasional I dan Internasional II.[1] Tetapi, menurut Perry Anderson, kemunculan Marxisme Barat lebih dari sekadar perbedaan penafsiran dengan kalangan Marxisme Klasik (classical Marxism) setelah Engels, melainkan secara keseluruhan merupakan produk dari sebuah kekalahan (defeat, huruf miring dari Anderson).[2] Kekalahan yang dimaksud adalah gagalnya penyebaran revolusi sosialis di luar Rusia, penyebab dan konsekuensi dari korupsi yang terjadi di Rusia, yang menyebabkan terjadinya isolasi dan keputusasaan politik dari para pemikir Marxisme Barat ini.
Anderson mencatat bahwa Lukacs, seorang Hungaria, menulis buku klasiknya History and Class Consciousness (1923) ketika ia sedang tinggal di pengasingan di Vienna, Austria, ketika Teror Putih (White Terror) sedang merajalela di negaranya menyusul penindasan terhadap Komune Hungaria. Gramsci menulis Notebooks setelah pemberangusan gerakan buruh menyusul kemenangan fasisme di Italia. Dua karya terpenting Sekolah Frankfurt (Frankfurt School) diterbitkan ketika reaksi politik berada di titik terendah di Jerman dan Amerika: karya Adorno Minima Moralia (1951) terbit di tengah proses pelarangan terhadap KPD di Jerman sedang dimulai, sementara Eros and Civilization (1954) karya Marcuse terbit di tengah histeria McCarthyism di Amerika. Buku Sartre Critique of Dialectical Reason (1960) terbit setelah keberhasilan kudeta Gaulist pada 1950, dan buku pertama dan paling orisinil dari Althusser Contradiction and Over-Determination (1963) terbit bertepatan dengan penerapan aturan presiden langsung secara otoriter dan konsolidasi secara menyeluruh dari Republik Kelima.[3]
Apa dampak dari kekalahan politik ini pada pemikiran Marxisme Barat? Kellner menulis bahwa Marx dan Engels memfokuskan energi intelektual dan politik mereka untuk menganalisa modus produksi, perkembangan ekonomi terkini dan perjuangan politik, perubahan-perubahan dari pasar dunia dan masyarakat modern yang kini diteorikan sebagai globalisasi dan modernitas. Pada generasi kedua dari Marxis kKasik mulai dari Sosial Demokrat dan kaum Radikal Jerman hingga Marxis Rusia, fokus perhatian mereka lebih sempit lagi, yakni pada soal-soal ekonomi dan politik. Di sini, Marxisme menjadi doktrin resmi dari banyak gerakan kelas pekerja di Eropa dan dengan demikian sangat erat dengan kebutuhan untuk perjuangan politik sejak wafatnya Marx pada 1883 hingga memasuki abad ke-20.[4] Sebaliknya, dalam Marxisme Barat, studi-studi seperti ini menghilang dari perhatian mereka dan mengalihkan fokus studinya pada filsafat, fenomena kultural, bahasa dan teori sosial. Dalam bahasa Keucheyan, kalangan Marxisme Barat ini lebih fokus pada pengembangan bentuk-bentuk pengetahuan yang abstrak, pengetahuan yang otonom, yang sulit diakses oleh pekerja biasa, dan tidak memiliki hubungan langsung dengan strategi politik (hal. 11-12). Atau meminjam istilah Anderson, kalangan Marxisme Barat ini lebih menekankan studinya pada aspek suprastruktur ketimbang aspek basis.
Tercerabut Dari Gerakan Massa
Carl Schmitt, filsuf politik kenamaan Jerman yang pro Hitler, suatu ketika mengatakan bahwa penanda terpenting dari era modern adalah ketika ‘Lenin membaca Clausewitz.’ Sementara, menurut Keucheyan, Marxisme Barat dan pewarisnya saat ini (dengan pengecualian Alvaro Garcia Linera), adalah ‘non- Clausewitzian’ (hal. 12).
Kita sudah bahas di atas bahwa perhatian utama kalangan Marxis klasik adalah menjawab soal-soal ekonomi dan politik yang konkret. Yang dalam bahasa Lenin adalah bagaimana melakukan analisa yang konkret atas situasi yang juga konkret (concrete analysis of the concrete situation).
Dari sini, menurut Keucheyan ada dua karakteristik utama dari Marxis klasik: Pertama, mereka adalah sejarawan, ekonomi, dan sosiolog–yang secara singkat memiliki perhatian pada ilmu empiris. Publikasi-publikasi mereka terutama berkaitan dan fokus pada situasi-situasi politik yang aktual. Kedua, mereka adalah pemimpin partai, karenanya mereka adalah ahli-ahli strategi dalam berhadapan dengan problem politik yang nyata. Bagi mereka, menjadi Marxis berarti menjadi pemimpin organisasi kelas pekerja dalam sebuah negeri (hal. 10). Karl Kautsky, misalnya, selain seorang teoritisi utama Internasional II, sehingga dijuluki sebagai ‘Paus Marxis/Pope of Marxism’, juga adalah salah satu pemimpin Partai Buruh Sosial-Demokratik Jerman (SDP); Lenin, adalah pendiri Partai Bolshevik Rusia; Rosa Luxemburg adalah teoritisi utama dari Partai Sosial-Demokratik Polandia dan kemudian menjadi pendiri dari Partai Komunis Jerman; Hilferding, yang karyanya kini kembali menjadi aktual Finance Capital, adalah wakil ketua parlemen terkemuka dari Partai Sosial-Demokratik Jerman.
Kedua karakteristik ini saling berkelindan satu dengan lainnya. Karena mereka adalah ahli strategi politik, maka mereka dituntut untuk memiliki pengetahuan empiris agar bisa membuat kebijakan dan mengambil keputusan. Inilah makna pernyataan Lenin di atas, analisa konkret atas sebuah situasi konkret. Sebaliknya, karena peran mereka sebagai ahli strategi maka refleksi mereka atas sebuah persoalan konkret menjadi semakin berkembang. Dialektika teori-praktik inilah yang mewarnai keseluruhan aktivitas kalangan Marxis Klasik. Tidak ada pemisahan antara intelektual dan aktivis, antara mereka yang berpikir dan mereka yang mengorganisir, antara kerja tekun dan kerja kobar, atau antara analis politik dan pelaku politik (politisi). Kalau memparafrasekan kata-kata Julien Benda yang sangat populer itu, kalangan Marxis klasik ini ‘bukanlah intelektual yang berumah di atas angin.’ Mereka tidak tercerabut dari gerakan massa. Mereka bukan hanya bagian dari gerakan massa, tapi bahkan menjadi pemimpinnya. Mereka adalah intelektual yang berkeringat, yang kakinya kotor penuh lumpur, sekaligus aktivis politik yang berteori, yang gairahnya dalam membaca buku sama besarnya dengan gairahnya ketika berpolitik.
Dua karaktetiristik yang menyatu inilah yang hilang dari Marxisme Barat. Kata Anderson, karakter pertama dan fundamental dari kalangan Marxisme Barat ini adalah tercerainya secara struktural Marxisme dari praktik politik.[5] Menariknya, tiga proponen utama Marxisme Barat, yakni Lukacs, Gramsci dan Korsch adalah pejabat tinggi partai pada awalnya, tetapi dengan satu dan lain hal mereka kemudian terlempar dari partai. Lukacs, setelah dipecat dari partai kemudian berhenti menjadi seorang politisi militan sejak 1929 dan mencurahkan energi intelektualnya pada kritisisme sastra dan filsafat. Korsch setelah terlempar dari partai dan bersamaan dengan kemenangan fasisme di Jerman, akhirnya hidup kesepian di pengasingannya di Amerika. Gramsci lebih tragis lagi, hidup terisolasi di penjara dan kemudian mati akibat hantaman penyakit.
Generasi selanjutnya dari Marxisme Barat ini semakin berjarak dari politik. Khususnya Sekolah Frankfurt, dimana Horkheimer, misalnya, bahkan tidak pernah menjadi anggota partai politik. Kalau mereka bergabung ke dalam partai Marxis, posisi mereka hanyalah sebagai anggota dan selalu memiliki hubungan yang kompleks dengan partai.
Apa penyebab tercerabutnya mereka dari gerakan kelas pekerja? Keucheyan mengatakan bahwa dalam kasus Lukacs, Korsch dan Gramsci penyebabnya adalah kekalahan organisasi-organisasi buruh di hampir seluruh negara Eropa saat itu. Kegagalan Revolusi Jerman pada 1923, misalnya, membuat harapan bahwa kapitalisme bisa dihancurkan saat itu juga menjadi musnah. Kegagalan ini selanjutnya memicu munculnya bentuk baru hubungan antara intelektual/pemimpin dengan organisasi-organisasi kelas pekerja. Hal lain yang menyebabkan perceraian ini adalah ketika Stalinisme berkuasa dan menjadikan Marxisme sebagai dogma yang beku dan partai adalah sumber kebenaran. Jika pada era Marxisme klasik perdebatan adalah sebuah keniscayaan, maka pada Stalinisme perdebatan ditutup rapat. Kondisi ini menyebabkan para intelektual berada dalam posisi yang sulit, dimana pilihannya hanya dua: tunduk dan patuh atau dipecat atau keluar dari partai. Pada saat yang bersamaan, universitas semakin berkembang dengan pesat dimana aktivitas intelektual dari para akademisi ini semakin terprofesionalisasi dan bahkan terbirokratisasi yang menyebabkan hubungannya dengan politik semakin jauh jaraknya (hal.11).
Pemikir Kritis Baru
Kita telah lihat bahwa ciri utama pemikiran Marxisme Barat lebih fokus pada aspek suprastruktur, dimana hal itu merupakan konsekuensi dari ketercerabutan mereka dari politik, dari keterputusan dialektik antara teori dan praktek. Penyebab utama dari keterputusan dialektis ini adalah kekalahan gerakan buruh di hadapan kapital. Inilah juga yang menjadi ciri utama dari pemikiran kritis baru yang menjadi fokus utama buku ini. Bahkan, dalam beberapa hal lebih parah dari Marxisme Barat.
Pada para pemikir kritis baru ini, kita akan sedikit sekali menemukan analisa yang berpusat pada kelas sosial, kesadaran kelas, perjuangan kelas, sudut pandang kelas, atau gerakan-gerakan berbasis kelas. Pemikiran mereka semakin abstrak dan canggih sehingga, kecuali para mahasiswanya, sulit sekali dimengerti oleh massa rakyat pekerja. Kecanggihan itu bisa juga dibaca bahwa mereka faktanya sangat inovatif dalam mengembangkan pemikirannya, dalam arti mereka tidak ragu-ragu untuk mengadopsi teori-teori dan analisa-analisa non-marxis dan kemudian meramunya dengan Marxisme. Dalam kenyataannya, ramuan pemikiran ini sering sekali menghasilkan sesuatu yang begitu jauh dari gagasan Marx.[6] Oleh karena itu, Keucheyan dengan sedikit sinis mengatakan bahwa inovasi ini hanya penampakkan luar dari kekalahan gerakan rakyat pekerja yang begitu masif dan mengglobal saat ini.
Kita bisa melihat, misalnya, Antonio Negri sangat terpengaruh dengan pemikiran Spinoza ketika merumuskan Multitude sebagai subjek emansipatorisnya. Atau pengaruh Hegel dan Lacan yang begitu besar pada Žižek ketika ia mencoba menemukan kembali Lenin. Hibridisasi pemikiran itu juga bisa kita temukan pada Butler dan Laclau yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran pascastrukturalisme (Post-Structuralism), khususnya Lacan dan Derrida, dalam memformulasikan pemikiran mereka yang kemudian disebut pascamarxisme (Post-Marxisme). Satu contoh lagi bisa dimasukkan, yakni feminis Seyla Benhabib, yang merupakan generasi ketiga dari Sekolah Frankfurt bersama dengan Axel Honneth dan Nancy Fraser. Pemikiran Benhabib sangat dipengaruhi oleh ‘etika komunikatif’nya Jurgen Habermas dan republikanisme Hannah Arendt (hal. 63).
Dan seperti pendahulunya Marxisme Barat, para pemikir kritis baru ini pun (sekali lagi dengan pengecualian Garcia Linera), tidak memiliki hubungan yang organik dengan gerakan rakyat pekerja. Bahkan, dalam derajat tertentu, hubungan mereka dengan gerakan rakyat pekerja itu lebih berjarak lagi ketimbang pendahulunya. Dalam tulisannya yang lain, Keucheyan membandingkan antara Sartre sebagai proponen Marxisme Barat dengan Žižek yang merupakan proponen teori kritis baru. Dalam tulisan itu, Keucheyan menceritakan tentang seorang Žižek yang berorasi di hadapan massa Occupy Wall Street(OWS), di taman Zuccoti, NY, AS, pada 2011. Orasi Žižek itu mengingatkanya pada orasi serupa yang dilakukan Sartre di pabrik otomobil Renault di Boulogne-Billancourt dekat Paris, pada 1970. Dua pidato dari dua orang filsuf paling terkenal di masanya masing-masing itu mendorong Keucheyan untuk membuat sebuah perbandingan, yang saya kutip agak panjang:
“….Sartre berbicara di depan (pabrik) otomobil, yakni industrial, buruh, sementara Žižek, Butler and West berbicara di depan massa yang cair (indeterminate). …. Selain itu, Žižek, Butler and West berbicara bukan di depan sebuah pabrik yang sedang diduduki, sebagaimana yang Sartre lakukan, tetapi di sebuah tempat umum. Pendudukan tempat-tempat umum memang sedang menjadi tren dari gerakan-gerakan baru saat ini, dan perbedaan ini sangat krusial…..
“Perbedaan krusial kedua antara dua kejadian ini adalah, Sartre, walaupun tidak pernah benar-benar menjadi anggota organisasi kelas pekerja, tapi aktivitas politik dan intelektualnya secara umum diorganisasikan di sekitar organisasi kelas pekerja. Dan itu tampak secara struktual di lapangan ketika ia memberikan orasinya kepada buruh. Bagaimana dengan Žižek, Butler and West? Mungkin ini hal yang baik atau tidak, tetapi intelektual kritis hari ini, tidak peduli sekuat apapun komitmen mereka, posisi mereka adalah “mengapung bebas/free-floating” dan tidak memiliki hubungan yang organik dengan organisasi apapun.
Perbedaan terakhir antara dua peristiwa itu adalah Sartre bukanlah seorang akademisi. Ia sangat mencurigai lembaga-lembaga borjuis dan menolak hadiah Nobel sastra pada 1964…… Sartre sangat terkenal sebagai seorang novelis dan filosof, yang mengijinkan penyingkiran ‘aristokratik’ atas segala hal-hal yang vulgar dari borjuasi. Žižek, Butler and West, di sisi lain, adalah akademisi, yang seperti kebanyakan, jika tidak semua, adalah pemikir-pemikir kritis hari ini.”[7]
Pelajaran Untuk Kita
Buku ini tak pelak lagi sangat penting untuk dibaca oleh para intelektual kritis di Indonesia. Bahkan dibandingkan dengan rekan-rekannya di negara lain, posisi intelektual kritis Indonesia lebih parah lagi. Dari segi pemikiran, para intelektual kritis Indonesia tidak memiliki akar yang kuat pada tradisi Kiri dalam negeri. Kita bisa mengajukan pertanyaan, siapa intelektual kritis kita yang menekuni dan mengembangkan pemikiran Tan Malaka, Soekarno, Sjahrir, Aidit, atau Nykto untuk merespon situasi sosial dan politik saat ini?
Secara politik, praktis posisi intelektual kritis Indonesia berada di luar lingkaran gerakan rakyat pekerja. Umumnya mereka tidak terkait secara organisasional dengan organisasi rakyat pekerja yang ada. Sedikit sekali yang menjadi anggota, lebih-lebih sebagai pemimpin organisasi. Sebagian besar hubungannya lebih berbentuk jaringan yang sebenarnya hanya mengukuhkan keterpisahan jarak dan posisi antara keduanya.
Tentu saja, mengikuti argumen Anderson dan Keucheyan, posisi intelektual kritis Indonesia saat ini merupakan produk dari kekalahan yang sangat telak dari gerakan rakyat pekerja di semua lini semenjak genosida pada tahun 1965. Tidak saja organisasi rakyat pekerja dihancurkan, pemimpin dan anggotanya dibunuh dan dipenjara, tetapi secara intelektual pun dinyatakan terlarang untuk dipelajari. Tidak ada negara di dunia ini yang begitu anti peradaban, anti ilmu pengetahuan, selain rezim Orde baru dan rezim sesudahnya. Kondisi ini membuat kita harus mengakui bahwa lahir dan munculnya para intelektual kritis saat ini di Indonesia, sudah merupakan sebuah kemajuan yang patut diapresiasi setinggi-tingginya. Sebab, berbeda dengan pemikir kritis baru yang dibahas Keucheyan dalam bukunya ini, dimana mereka memiliki keistimewaan untuk bebas mengakses, memformulasikan, dan menyebarkan gagasan-gagasannya, para intelektual kritis Indonesia praktis memulai dari nol dalam memformulasikan gagasannya, akses terhadap bahan bacaan yang sangat terbatas, iklim akademik yang tidak mendukung, dan harus lebih nekat dalam menyebarkan gagasannya karena tidak ada jaminan bahwa kebebasannya tidak akan diberangus oleh penguasa sekarang berdasarkan undang-undang yang ada.
Dari sini kita bisa mengatakan bahwa memang ada jarak yang cukup jauh antara gerakan rakyat pekerja dengan kalangan intelektual kritis di Indonesia. Tetapi jarak itu tidak terutama disebabkan oleh faktor psikologis dan kultural, melainkan karena faktor politik: keduanya-duanya adalah produk dari sebuah periode kekalahan yang panjang. Memang pada dekade 1990an, coba dibangun hubungan yang organik antara kalangan intelektual dan rakyat pekerja, yang kemudian terformulasikan dalam bentuk Partai Rakyat Demokratik (PRD). Tetapi menyusul Peristiwa 27 Juli 1996 dimana rezim orde baru memburu dan menangkapi para pimpinan PRD, yang umumnya adalah para intelektual muda, maka eksperimen politik ini mati suri. Momen lain dari kekalahan itu adalah kalah telaknya PRD dalam pertarungan pemilihan umum terbuka dan bebas untuk pertama kalinya pasca runtuhnya orde baru pada 1999. Setelah kedua momen kekalahan itu, kita mendapati hubungan yang tegang antara kalangan intelektual dan aktivis pergerakan.
Buku ini tidak memberikan solusi bagaimana mengatasi jarak jauh yang membentang antara intelektual kritis dan gerakan rakyat pekerja. Nadezhda Konstantinovna ‘Nadya’ Krupskaya, istri Lenin, pernah mengatakan bahwa salah satu kebiasaan Lenin ketika ia menghadapi persoalan adalah dengan kembali kepada Marx, berdialog kritis dengan teks-teks Marx. Filsuf muda Marcello Musto, juga merekomendasikan agar kini saatnya kita kembali kepada Marx. Kalau mengikuti pemikiran buku ini, maka kembali kepada Marx mestinya kembali kepada Marxisme Klasik, yakni menyatunya teori dan praktik, intelektual sekaligus pemimpin organisasi rakyat pekerja, aktivis politik militan sekaligus pemikir yang disiplin berteori.
Tetapi, dari mana memulainya? Solusinya, mungkin, memang tidak bisa secara idealis, tetapi bersandar pada situasi-situasi konkret sehari-hari. Dan kenyataan hari-hari ini menunjukkan kepada kita bahwa menjadi Marxis kKasik itu adalah keniscayaan. Bangkitnya perlawanan massa besar-besaran di Yunani dan Spanyol terhadap rezim kapitalisme-neoliberal telah mendorong para intelektual universitas terjun langsung dalam mengorganisir dan memimpin pergerakan. Di Yunani, kita mencatat nama ekonom Yanis Varoufakis dan filsuf Stathis Kouvelakis yang ikut memimpin partai kiri Syriza yang kini berkuasa. Di Spanyol, pemimpin partai sayap kiri Podemos, yang kini sedang populer dan berpotensi memenangi Pemilu pada Desember nanti, adalah Pablo Iglesias, seorang ilmuwan politik. Sebelumnya, di Chile, kita sudah akrab dengan nama Camila Vallejo, perempuan muda anggota parlemen Chile dari Partai Komunis Chile. Camila juga lahir dari perlawanan massal mahasiswa Chile yang menuntut pendidikan gratis. Dalam buku ini, Keucheyan menunjuk Alvaro Garcia Linera sebagai pengecualian dari proponen teori kritis baru yang memiliki hubungan organik dengan massa. Garcia Linera adalah matematikawan-cum sosiolog, aktivis gerakan masyarakat adat Bolivia dan kini menjadi wakil presiden Bolivia dari MAS (Gerakan Menuju Sosialisme). Di Inggris kita mengenal nama Alex Callinicos, sosiolog dan juga anggota komite sentral Partai Buruh Sosialis (SWP) Inggris, dan editor jurnal teoritik SWP International Socialism.
Bersandar dan bergerak bersama massa rakyat pekerja, mungkin itulah solusi untuk mengeliminasi jurang aktivis dan intelektual saat ini. ***
[1] Lihat Douglas Kellner, ‘Western Marxism’ dalam Austin Harrington, Modern Social Theory: An Introduction, Oxford University Press, 2005, p. 154-174.
[2] Perry Anderson, p. 42.
[3] Ibid, p.42-43.
[4] Kellner, Ibid.
[5] Ibid., p. 29.
[6] Marcello Musto mengatakan bahwa ramuan teoritik itulah, walaupun kabur, justru yang membuat pemikiran mereka menjadi menarik. Lihat A Marx for the Left Today: Interview with Marcello Musto, http://clogic.eserver.org/2010/Musto_Oittinen_Maidansky.pdf. Diunduh pada Selasa, 9 Juni 2015.
[7] Razmig Keucheyan, ‘How to break the stranglehold of academics on critical thinking’ The Guardian, 2 Januari 2015, http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jan/02/academics-critical-thinking-occupy-intellectuals