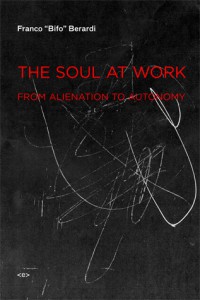Judul buku: The Soul at Work: From Alienation to Autonomy
Penulis: Franco “Bifo” Berardi, , terj. F. Cadel & G. Mecchia
Penerbit: (LA: Semiotext(e), 2009)
Tebal: 232 h.
GILLES Deleuze dan Felix Guattari suatu kali pernah mengatakan bahwa pertanyaan mendasar yang selalu menghantui kolaborasi mereka adalah sebuah puzzle mengenai perlawanan: ‘the problem is not why people revolt, but why they don’t.’ Bahkan, di Anti-Oedipus, keduanya juga terpusingkan dengan teka-teki ‘why do people desire their own repression?’
Pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja berseberangan dengan pandangan umum yang selalu menyatakan (kadang secara mesianik), apabila seseorang ditindas sampai titik nadirnya maka ia akan melawan balik. Jika masa-masa perjuangan anti-kolonial (formal) dulu yang menjadi backdrop sosial-politik bagi pertanyaan-pertanyaan ini, maka bisa saja pertanyaan ini menjadi tidak relevan. Sebabnya, para pejuang anti-kolonial toh pada akhirnya bangkit balik melawan penjajahnya demi merebut kemerdekaan. Adalah kapitalisme pasca-industri (atau pasca-Fordis) yang menjadi latar yang memungkinkan pertanyaan ini muncul dan menjadi relevan, setidaknya bagi Deleuze dan Guattari. Lebih spesifiknya, Deleuze akan menyebut kapitalisme seperti ini sebagai ‘masyarakat kontrol’ (society of control).
Terhadap latar belakang ini pulalah, Franco Berardi, yang akrab dipanggil Bifo, mencoba menawarkan jawaban dan jalan keluar melalui buku ini. Lebih khususnya, Bifo, setia namun sekaligus mencoba keluar dari jaket ketat tradisi Marxis-Otonomianya, berupaya menjelaskan pertanyaan ini melalui pergeseran logika yang dilihatnya dalam pemaknaan kerja (labor) itu sendiri. Pergeseran tersebut adalah dari pemaknaan kerja sebagai apa yang disebut Mario Tronti sebagai ‘kebutuhan pekerja’ (worker needs) yaitu ‘kebutuhan untuk melawan’ yang memanifestasi dalam ‘penolakan kerja’ (refusal of work), beralih kepada suatu logika dimana kerja itu sendiri justru menjadi sesuatu yang dihasrati, sesuatu yang tanpanya buruh tidak akan mampu hidup otonom. Dengan kata lain, Bifo ingin menunjukkan bagaimana secara subyektif, buruh tidak lagi melihat kerja sebagai sebentuk alienasi. Di sinilah Bifo menggariskan kontribusi yang sangat menarik, sekaligus kontroversial.

Secara umum buku ini membahas mengenai teori alienasi dan tawaran Bifo (baik teoritis maupun praksis) terkait problem alienasi ini. Posisi Bifo adalah: ketimbang melihat alienasi sebagai sesuatu yang ‘buruk,’ Bifo malah melihatnya sebagai sesuatu yang ‘baik’—dalam artian ketat sebagai menguntungkan bagi visi perlawanan terhadap kapital itu sendiri. Logikanya, bagaimana mungkin pekerja melakukan perlawanan terhadap kapitalisme apabila ia tidak merasakan bahwa dirinya ter-alienasi dari kapitalisme itu sendiri? Pekerja tidak akan merasa (meminjam istilah Tronti) ‘butuh’ untuk melakukan suatu perlawanan terhadap kapital, jika ia tidak merasakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari kapital, bahwa ia sedang tereksploitasi karena alienasi ini. Justru tepat di logika inilah, teknologi (machinery) kontrol buruh oleh kapital menunjukkan kecanggihan dalam mengeksploitasinya: pekerja dibuat sedemikian rupa melihat kerja sebagai sesuatu yang bukan hanya tidak alien, melainkan juga sesuatu yang sudah seharusnya dihasrati. Pekerja akhirnya menjadi sedemikian ketagihan (addictive) pada kerja. (Ketagihan tidak harus selalu mewujud dalam workaholism kelas menengah, tapi juga dalam ketidakberdayaan pekerja untuk senantiasa menggantungkan hidupnya pada kapital untuk mempekerjakannya).
Lalu, bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana pergeseran logika ini dimungkinkan? Jawabannya adalah apa yang tertulis sebagai judul buku ini: dengan mempekerjakan jiwa (soul). Ya, perkembangan teknologi kontrol pekerja dalam kapitalisme pasca-Fordis, telah mampu sedemikian rupa menundukkan dan ‘mempekerjakan’ jiwa demi kepentingan akumulasi profit itu sendiri.
Spiritualis?—mungkin banyak yang akan langsung bereaksi spontan demikian. Namun, Bifo nampaknya sadar benar dengan kemungkinan reaksi demikian sehingga ia mengantisipasinya, bahkan di kalimat awal pembahasannya.
The soul I intend to discuss does not have much to do with the spirit. It is rather the vital breath that converts biological matter into an animated body. I want to discuss the soul in a materialistic way. What the body can do, that is its soul, as Spinoza said. (h.21)
Secara terang-terangan, saya kira, Bifo di sini sudah mengklarifikasi secara sederhana tentang bagaimana memahami ‘jiwa’ secara materialistik, sehingga dengan demikian menghindari jebakan spiritualis. Disebut jebakan, karena, sebagaimana yang telah jauh-jauh hari diperingatkan Epikuros, ‘those who maintain that the soul is incorporeal are talking nonsense, because it would not be able to act upon or be acted upon if it were of such a nature’ (dikutip dari Bifo, h.21). Padahal, sebagaimana tradisi Marxis yang juga dikampanyekan Bifo, tujuan akhir dari analisis dan teorisasi adalah, tentu saja, ‘mengubah dunia.’ Bahkan, bila lebih eksplisit mengacu ke tradisi Marxis-Otonomia, teorisasi adalah sebuah eksperimen pemikiran yang kemudian hasilnya dieksperimentasikan lagi di lapangan dalam praksis-praksis perlawanan, dan begitu seterusnya. Itulah mengapa sedari pendefinisian awal, Bifo meletakkan problem jiwa secara materialistik, sehingga memungkinkan transformasinya.
Bifo melihat bahwa jiwa adalah segala sesuatu yang menghidupkan (animate) tubuh, atau bahkan lebih kongkrit lagi, otot-otot. Lebih spesifik lagi, Bifo menghubungkan jiwa ini dengan hal-hal seperti: bahasa, kognisi, pemikiran, afeksi, dan emosi. Dengan menandaskan bahwa jiwa adalah apa yang ‘menyutradarai’ seonggok tubuh untuk melenggak-lenggok hidup, maka harus diperhatikan di sini bahwa ia menggunakan jiwa sebagai sebuah metafora. Aspek penting lainnya dari jiwa adalah ‘relasi’. Hal-hal kejiwaan yang disebutkan tadi, bagi Bifo, adalah modalitas manusia untuk membentuk relasi-relasi yang bisa tak terhitung banyaknya.
In a sense we could say that the soul is the relation ro the other, it is attraction, conflict, relationship. The soul is language as the construction of the relationship with alterity, a game of seduction, submission, domination and rebellion. (h.115)`
Dari pendefinisian demikian, maka bisa kita pahami bahwa relasi-relasi ini membentuk jejaring yang kompleks, bahkan dalam bahasa Maurizzio Lazarato, ia membentuk dunia! (‘From Capital-Labour to Capital-Life,’ Ephemera, 4, 3, 2004). Jadi, menggunakan bahasa yang lebih akrab di telinga kita hari ini, jutaan tubuh dan jiwa ini membentuk dunia relasi yang mencakup mulai dari dialek, meme, tren, gaya, mood, gosip, cara berpakaian, cara bercinta, pola dramatisasi kehidupan, preferensi konsumsi, sampai ke imaji superstar, ambisi menjadi idol, dan bahkan fantasi horor dunia ditabrak meteor. Jiwa mentransformasikan keributan menjadi harmoni musikal, komposisi otot menjadi macho/sexy, alfabet menjadi rangkaian puisi, pakaian menjadi fashion, dst. Inilah apa yang mampu dihasilkan oleh jiwa.
Saya kira cukup sudah untuk penjelasan mengenai apa dan mengapa Bifo memobilisasi ‘jiwa’ untuk menjelaskan problem alienasi. Pertanyaan penting berikutnya, ‘bagaimana jiwa dipekerjakan oleh kapital?’ Menjawab pertanyaan ini, Bifo menggunakan argumen historis untuk menunjukkan transisi bagaimana jiwa direkrut oleh kapitalisme guna menjadi pekerjanya. Bifo, sebagaimana khas yang juga dilakukan para Otonomia lainnya, mematok transisi tersebut pada tahun 1977. Tahun tersebut memiliki arti spesial (dalam artian traumatik) bagi Otonomia. Tahun tersebut menandai sebuah pergeseran dari ‘penolakan kerja’ (refusal of work) kepada ‘kecanduan kerja’ (Bifo menggunakan bahasa ‘teracuni’ (poisoned, h.106)). Di Italia saat itu terjadi pergeseran dalam proses kerja di pabrik-pabrik, yaitu dengan apa yang umum disebut sebagai proses mekanisasi—memanfaatkan mesin-mesin yang terotomasi untuk menjalankan produksi. Titik ini hanyalah titik mula dari proses untuk membuat kapital memiliki otonomi relatif terhadap pekerja, karena di tahun 1980an, kita melihat proses komputerisasi produksi. Bahkan, berdasar pengamatan saya sendiri, bisa dilanjutkan: jika tahun 70an adalah dekade mekanisasi, 80an adalah dekade komputerisasi, maka tahun 90an adalah dekade informasionalisasi dan internetisasi, tahun 2000an adalah dekade real-time network dan robotisasi.
Tapi yang perlu ditekankan di sini, terutama dari perspektif Otonomia, adalah salah besar jika memahami mutasi teknologi kapitalisme ini sebagai suatu proses yang linier! Mutasi teknologi kapitalisme adalah cara kapital untuk survive dari gelombang-gelombang serangan para pekerja. Ya, para Otonomia meletakkan sentralitas dan primasi ‘kekuatan pekerja’ (potere operaio). Pandangan ini, tentunya, bertentangan dengan keyakinan umum bahwa para pekerjalah yang selalu reaksioner: komplain upah yang kecil, marah karena sanitasi kurang, berontak karena jam kerja semena-mena, protes karena aturan tidak jelas, dst. Bifo, dan para Otonomia lainnya, justru membalik cara melihat demikian: adalah kapital yang reaksioner terhadap kekuatan pekerja, sehingga ia selalu bersusah-payah mencari cara untuk meredam kekuatan ini, bahkan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam era pasca-Fordisme saat ini, menjadikannya impoten.
Demikianlah mutasi kapitalisme terjadi. Jadi, perspektif Bifo ini mampu menunjukkan bahwa adalah pekerja yang menjadi jiwa dari kapitalisme, adalah kekuatan pekerja yang ‘menghidupkan’ roda-roda produksi kapitalis dan memaksa ‘tubuh’ kapital untuk senantiasa bermutasi ke bentuk-bentuk yang baru.
Lalu, bagaimana tepatnya jiwa dipekerjakan dalam kapital? Bifo mendedikasikan bab 2 dan 3 untuk menjelaskan ini. Di bab 4, Bifo melangkah lebih jauh untuk menunjukkan implikasinya. Adalah ‘semio-kapitalisme,’ istilah Bifo untuk kapitalisme pasca-Fordisme, yang ensembel teknologinya mampu merekrut jiwa-jiwa untuk menjadi pekerja setianya. Semio-kapitalisme merupakan konsekuensi saat produksi telah terinformatisasi. Dengan komputer, mesin-mesin produksi, komando pabrik dan pekerja, koordinasi jejaring pasokan dan distribusi, semuanya dilakukan melalui kode-kode yang ditransmisikan melalui teknologi komunikasi dan informasi. Semio-kapitalisme, dengan demikian, bisa terwujudkan secara vulgar melalui revolusi teknologi informasi ini. Semio-kapitalisme ini, sayangnya, tidak hanya berdampak pada cara-cara produksi secara de facto. Ia punya implikasi yang lebih jauh, lebih intim, sampai merasuk ke relung-relung jiwa.
Bifo menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kerja yang disyaratkan semio-kapitalisme, menunjukkan pergeseran dalam proses employment itu sendiri. Jika dulu—tepatnya, bagi Bifo, sebelum 1977—pekerja hanya perlu menggunakan (employ) tubuh dan ototnya untuk bekerja, kini dalam semio-kapitalisme, pekerja harus menggunakan (employ) seluruh jiwa (dalam arti yang dijelaskan barusan) dan raganya untuk mengabdi pada kapital demi sejumput upah. Jadi, dimanakah jiwa-jiwa hari ini? Ah, mereka sedang sibuk bekerja.
Dalam semio-kapitalisme, adalah skill yang terspesialisasi yang diperlukan. Artinya, kuat dan bertenaga saja tidak cukup, bahkan untuk beberapa kasus, tidak begitu relevan. Untuk mendesain sebuah iklan promosional, anda cukup menyediakan waktu berjam-jam (atau berhari-hari) untuk menumpahkan segala kreativitas anda pada bit-bit digital di laptop anda. Begitu pula untuk menjadi teller bank, anda cukup perlu cekatan menghafalkan letak-letak tuts keyboard saja. Kita melihat di sini, semakin suatu pekerjaan itu terspesialisasi, maka semakin tinggi tingkat kesukarannya, dan semakin banyak pula pengetahuan/keterampilan yang dibutuhkan (dan juga mungkin makin tinggi upahnya). Apa implikasinya spesialisasi kerja ala semio-kapitalis ini bagi jiwa pekerja?
Ada dua yang saya tangkap dari Bifo. Pertama, seperti yang sudah sedikit banyak disinggung, jiwa menjadi dipekerjakan dalam kapital. Jiwa, yang tadinya (dianggap) bebas melayang-layang dan bergulung-gulung riang secara ekspresif, kini harus ditempa, didisiplinkan dan diarahkan demi mengakselerasi roda-roda kapital demi hiper-akumulasi profit. Terkait ini, Bifo menunjukkan hal unik terkait transisi tahun 1977. Dengan metode ‘analisis komposisi-kelas’ (class composition analysis) khas otonomia, atau yang dinamai Bifo ‘komposisionisme’ (compositionism), ia menunjukkan bagaimana pertama kali intelektual, yang sedari Lenin sampai Gramsci dan Sartre, bahkan Marcuse selalu dianggap di luar kapital, kini telah disambut masuk (atau dijebloskan?) ke pabrik produksi untuk dipekerjakan oleh kapital. Analisis komposisionis ini akan selalu memfokuskan pada dinamika dialektis (dalam artian Marxis: konflik) antara komposisi kelas pekerja dengan komposisi teknologi kapital.
Dalam perspektif Otonomia yang meletakkan primasi kekuatan pekerja, mutasi teknologi kapital selalu didedikasikan demi merespon perlawanan buruh untuk ‘kerja! kerja! kerja!’ Di sinilah penting untuk memfokuskan pada teori mesin (machine) Marx dalam Grundrisse, yaitu mesin sebagai kristalisasi pengetahuan yang dimiliki pekerja dalam melakukan proses kerjanya. Mesin, akhirnya menjadi pekerja-mati (dead labor). Penjelasan lebih jauh bukan kompetensi ulasan ini, tapi saya kira ini cukup untuk mengikuti alur berpikir Bifo saat mengklaim bahwa mutasi teknologi kapitalis adalah proses konstan untuk senantiasa membekukan/mengkristalisasikan pengetahuan-pengetahuan dari pekerja dan kemudian diolah menjadi sebarisan mesin-mesin yang digunakan terhadap pekerja (untuk menggantikan pekerja-hidup, living labor). Pengetahuan yang terkristalkan inilah yang juga menjadi salah satu konsep krusial Otonomia: intelek umum (general intellect)—atau dalam bahasa saya, ‘living knowledge in a dead labor.’ Apa artinya? Sekali lagi, intelektualitas kini dipekerjakan.
Bersatunya mahasiswa dan pekerja dalam demo-demo tahun 1960 dan 70an (bahkan sampai saat ini), dimaknai Bifo sebagai suatu gejala bahwa telah terjadi transisi dalam paradigma kapitalisme, yaitu menuju semio-kapitalisme, menuju ekspropriasi intelektualitas dan dibekukan dalam kristal-kristal energi untuk menyuplai energi bagi berjalannya roda-roda produksi.
Implikasi kedua. Spesialisasi kerja akan berpengaruh ke aspek psikis sang pekerja. Semakin ia mampu menspesialisasi skill-nya, maka semakin pula ia mampu ‘menemukan jati dirinya’—ketat dalam artian ababil-ababil (ABG labil) di era Golden Way Mario teguh. Jika lima dekade lalu, kerja adalah membosankan dan menyebalkan karena harus melakukan hal monoton berulang-ulang, kini kerja bisa fun`, ‘gue banget,’ ‘sesuai sama passion elo,’ dst. Para pekerja intelektual akan ‘menemukan dirinya’ dalam ….. kerja! Akibatnya, hidup itu sendiri menjadi teridentifikasikan, dan kemudian menjadi terkaburkan batasnya, dengan kerja itu sendiri. ‘Life = work’ itulah ‘Jalan Emas Kehidupan’ hari ini. Segala sesuatu dalam dunia dan kehidupan, akhirnya terkanalisasi ke muara yang sama: kerja. Tidak pelak para orang tua hari ini melihat sekolah anaknya sebagai ‘investasi.’ Memilih sekolah kini didasarkan pada seberapa pasti jawaban terhadap pertanyaan ‘kalo lulus bisa kerja apa?’ diberikan.
Alhasil, semakin kecil kemungkinan terjadi penjarakkan dari kerja itu sendiri, apalagi kritisisme, bahkan ‘revolusi proletariat.’ Mogok? Oh…lupakan! Inilah yang disebut dengan ‘alienasi.’ Bifo mencurahkan perhatian khusus untuk memahami konsep ini; ia memisahkan antara ‘alienasi’ dengan ‘keterasingan’ (estrangement). Kedua-duanya merupakan akibat dari kuatnya obyek (kapital) eksternal dalam mendominasi sang subyek (pekerja), hanya saja jika dalam alienasi kesadaran subyek akan dominasi ini telah hilang, sementara dalam keterasingan, kesadaran ini masih tetap ada. Atau, jika dibahasakan-ulang dengan menyoroti aspek kejiwaan: dalam alienasi, jiwa telah terinklusi dan terdomestifikasi ke dalam kapital; sementara dalam keterasingan, jiwa masih belum terinklusi. Bifo menandaskan bahwa dalam keterasingan, masih terdapat ‘refusal to identifiy with the general interest of the capitalist economy’ (h.46). Sementara dalam alienasi, subyek pekerja mengalami gerhana kejiwaan oleh (semio-)kapital. Adalah alienasi dalam artian keterasingan ini yang saya maksud di depan sebagai titik berangkat dari perlawanan, sebagai obyek pengorganisasian demi memunculkan kekuatan pekerja—Tronti menyebutnya ‘pengorganisasian alienasi’ (the organization of alienation).
Jiwa adalah revolusioner. Adalah jiwa yang mampu menggerakkan dan menghentikan (baca: memogokkan) tubuh dan otot dari proses kerja kapitalis di pabrik. Adalah jiwa yang ditakuti oleh kapital. Adalah jiwa yang terhadapnya seluruh barisan dan mutasi teknologi pertahanan kapital diarahkan. Saat jiwa telah disulap menjadi baterai dari kapitalisme itu sendiri, maka praktis perlawanan buruh tidak akan ada lagi. ‘Saat revolusi tak ada lagi,’ kata seorang sastrawan ternama Indonesia, maka ia sebenarnya ingin juga mengatakan bahwa tidak ada lagi jiwa-jiwa yang bebas berkeliaran di luar logika produksi kapitalis—termasuk karya-karya nyeni dan nyastra dari sang sastrawan itu sendiri. (Lazzarato, Judith Revel, juga Luc Boltanski dan Eve Chiapello, punya pandangan menarik mengenai bagaimana produksi artistik disambut dan dirayakan dengan sukacita dan riang gembira oleh kapitalisme pasca-Fordis).
Tapi, apakah kemudian revolusi sudah tidak ada lagi? Bahwa jiwa sudah tertundukkan dalam logika produksi?
Tidak!
Rangkaian-rangkaian krisis multi-dimensional yang kita rasakan, setidaknya dalam satu dekade terakhir, dibaca Bifo sebagai ‘kembalinya jiwa.’ Hanya saja, kembalinya jiwa ini merupa dalam sisi-sisi gelapnya.
The dark side of the soul—fear, anxiety, panic and depression—has surfaced after looming for a decade in the shadow of the touted victory and the promised eternity of capitalism. (h.207)
Sebagaimana yang sudah kita ketahui, mutasi teknologi kapitalisme tentunya bukan hanya sekadar ditujukan untuk melemahkan pekerja, melainkan ujungnya tetap pada mempertahankan atau meningkatkan akumulasi kapital, singkatnya: profit. Semakin canggih, semakin mutakhir kapitalisme itu, makin semakin cepat pula sirkulasi akumulasi kapital itu berputar, bahkan sampai pada titik tertentu: secara real-time. Bill Gates dan Marx, uniknya, akan bersepakat untuk hal ini: Gates berbicara tentang ‘business @ the speed of thought’ sementara Marx, di Grundrisse, meramalkan tentang kemungkinan kapital bersirkulasi ‘without circulation time.’ Kecepatan yang hyper ini bukan tanpa konsekuensi.
Tubuh material manusia memiliki batas. Otot dan saraf manusia juga memiliki kapasitasnya sendiri. Kenyataan bahwa ia bisa terus dilatih, adalah hal lain. Plus, latihan tersebut juga perlu waktu, dan tidak semua mampu menjalani waktu-waktu itu ‘dengan selamat.’ Sialnya, sebagaimana ditunjukkan Bifo, mereka-mereka yang tidak selamat ini jumlahnya mayoritas dan bahkan membuat kapitalisme masuk ke epos krisis yang baru: krisis semio-kapitalisme. Panik dan depresi. Inilah gejala kembalinya jiwa, sebagaimana dilihat Bifo. Panik terjadi saat tekanan dari luar terjadi semakin cepat, liar dan kompleks, melampaui batas yang mampu diatasi, baik oleh tubuh dan pikiran. Dalam bahasa Bifo,
Panic happens when things start swirling around too quickly, when we can no longer grasp their meaning, their economic value in the competitive world of capitalist exchange. Panic happens when the speed and complexity of the surrounding flow of information exceed the ability of the social brain to decode and predict. In this case desire withdraws its investments, and this withdrawal gives way to depression. (h. 217)
Setelah panik, maka orang akan depresi. Satu-per-satu kemampuan fisik dan mentalnya terlumpuhkan. Bisa jadi, ia akan sakit dan bahkan mati (dalam artian jiwa—gila, atau bahkan, fisik).
Depression is the deactivation of desire after a panicked acceleration. When you are no longer able to understand the flow of information stimulating your brain, you tend to desert the field of communication disabling any intellectual and psychological response. (h.214)
Depression is based on hardening of one’s existential refrain, on its obsessive repetition. The depressed person is unable to go out, to leave the repetitive refrain and s/he keeps going back into the labyrinth. (h. 216)
Inilah konsekuensi alienasi jiwa yang menjadi ekses dari blue-print subordinasi semio-kapitalisme. The Great Depression, dengan demikian, harus diartikan secara literal: lumpuhnya tubuh dan otak sosial akibat derasnya laju sirkulasi kapital.
Sayangnya, tawaran yang diberikan oleh Bifo cenderung lebih retorik ketimbang praktis. Bifo mengusulkan skizoanalisis ala Guattari sebagai cara untuk ‘how to heal a depression?’ (h. 214). Skizoanalisis bertujuan untuk membuka cakrawala berpikir sang analisan (‘pasien’) untuk dapat melihat kemungkinan lain dari kondisi ‘kegilaannya’ saat ini. Artinya, skizoanalisis tidak ingin mengajak sang analisan untuk bernostalgia ke masa-masa lalunya, dan menghadirkannya di masa kini. Tidak. Skizoanalisis bahkan tidak mengusulkan apa-apa. Ia membantu sang analisan untuk secara otonom membayangkan cara untuk terbang (flight) dari kondisi saat ini dan menemukan kemungkinan-kemungkinan yang sama sekali baru. Terapi skizoanalitis ini ditumpangkan Bifo dalam paradigma pertemanan (friendship). Bifo menganggap teman adalah semacam tempat curhat (curahan hati) untuk berbagi beban. Pertemanan sejati, dengan demikian, menjalankan proses ‘terapi patogenik’ untuk senantiasa menjadi anti-depresan.
Berbicara tentang anti-depresan, terhadap ‘the great depression’ ini, Bifo melihat bahwa kapitalisme mulai mencoba bermutasi kepada apa yang disebutnya ‘ekonomi Prozac’ (Prozac adalah obat anti-depresan). Prozac di sini memang sebuah merek, namun tidak harus lantas diartikan secara literal. Bailout pemerintah untuk menstimulus pasar harus dilihat sebagai prozac economy! Upaya-upaya yang ditempuh siapapun dalam rangka menyegarkan dan menengking depresi, harus dilihat sebagai anti-depresan juga. Bentuk-bentuk outing dan outbound yang dilakukan perusahaan-perusahaan hari ini, juga harus dilihat sebagai sebentuk manajemen prozac. Begitu pula dengan penghargaan-penghargaan: karyawan terbaik bulan ini, karyawati paling lebar senyum bulan ini, teknisi paling muka obeng bulan ini, sampai dosen ter-asyik bulan ini: semua ini harus dipahami sebagai cara-cara prozac untuk menyembuhkan depresi pekerja, untuk kembali bekerja demi kemaslahatan kapital.
Pertanyaan sederhana bagi Bifo, namun ini juga yang saya lihat dari seluruh keluarga Otonomia yang pernah saya sambangi (Hardt, Negri, Virno, Lazzarato, Fumagalli, Marazzi, Mezzadra, Pasquinelli, Dyer-Witherford, Parisi, Terranova, dst.), yaitu, apa yang mereka usulkan sebagai cara-cara untuk melawan kapital justru pada dasarnya adalah cara-cara yang juga digunakan kapital untuk mensubjugasi pekerja itu sendiri. Tentang pertemanan yang ditawarkan Bifo, saya teringat seorang maha-guru manajemen yang saya kira semua kelas menengah (Indonesia) tahu, ia mengatakan kurang lebih seperti ini: ‘buat pertemanan sebanyak mungkin hari ini, karena kita tidak akan tahu kapan di masa depan nanti kita akan membutuhkan mereka.’
Ah… mungkin saya saja yang terlalu percaya bahwa masih ada pertemanan yang tidak dilandasi rasio pertukaran kapitalistik.
¶
Hizkia Yosie Polimpung, Peneliti di PACIVIS Center for Global Civil Society Studies, Universitas Indonesia; Mahasiswa Doktoral Dept. Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia