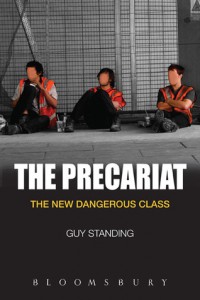Judul buku: The Precariat: the New Dangerous Class
Penulis: Guy Standing
Penerbit: Bloomsbury Academic, 2011
Tebal: 197 h + ix
MENJADI buruh kontrak dan buruh outsourcing/alih daya, seolah merupakan kewajaran yang tak dapat ditolak rakyat pekerja akhir-akhir ini. Itu, misalnya, tampak pada meningkatnya sistem kerja kontrak dan outsourcing menjadi sistem kerja wajib yang diterapkan oleh hampir semua perusahaan di Indonesia. Dalam data statistik yang dikeluarkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),[1] terlihat bahwa jumlah tenaga kerja setengah pengangguran, yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap, selalu mengalami peningkatan selama enam tahun terkahir. LIPI mencatat, pada tahun 2005, tenaga kerja setengah pengangguran berjumlah 28,64 juta jiwa. Namun, pada tahun 2010, jumlahnya meningkat menjadi 32,8 juta jiwa. Pada tahun 2011, LIPI memperkirakan jumlahnya akan meningkat menjadi 34,32 juta jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja atau buruh yang tidak memiliki pekerjaan tetap tidaklah sedikit. Dari data itu juga dapat dilihat bahwa jumlah buruh yang bekerja dengan ketidakpastian pekerjaan tersebut selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Buruh yang tidak memiliki pekerjaan tetap itu dapat diidentifikasi sebagai buruh kontrak dan atau outsourcing. Artinya, jumlah buruh kontrak dan outsourcing terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, setidaknya sejak tahun 2005.
Dalam sebuah pertemuan dengan kelompok diskusi buruh pabrik di daerah Bogor, hampir semua buruh perempuan dalam kelompok tersebut mengeluhkan status kerja mereka yang masih kontrak. Dengan status kerja kontrak tersebut, selain tidak memiliki kepastian kerja (job security), mereka pun mendapatkan komponen upah yang jauh berbeda dengan buruh tetap dan tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai buruh, seperti cuti, dan sebagainya. Begitupun yang terjadi dengan buruh-buruh kontrak yang bekerja di sebuah pabrik di daerah Cikupa, Tangerang, yang selalu mengalami pemecatan (PHK) menjelang hari raya Idul Fitri.
Hal serupa bukan hanya dialami oleh buruh-buruh yang bekerja di pabrik, melainkan juga mereka yang bekerja di sektor jasa. Dalam sebuah wawancara dengan seorang pekerja perempuan penjaga stand pijat refleksi di sebuah mall di Depok, ia bercerita jika bukan demi anaknya, ia tak mau bekerja dengan status kerja kontrak dengan penghasilan yang tidak menentu seperti itu. Penghasilannya, yang amat ditentukan dari banyaknya pengunjung yang datang ke stand-nya, membuatnya harus berusaha keras mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan alat-alat olahraga yang ada di stand tersebut. Dengan itu, ia baru bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp. 25.000,00 per harinya. Begitupun dengan yang dialami oleh buruh-buruh outsourcing di sebuah perusahaan di wilayah Bogor. Selain masih mendapatkan upah dibawah UMK, mereka tidak diperkenankan mengikuti serikat buruh/serikat pekerja yang ada di perusahaannya.
Mendesaknya berbagai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi serta minimnya pilihan kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah, membuat buruh-buruh kontrak tersebut tak punya banyak pilihan. Mereka tak kuasa menolak untuk bekerja, meski di bawah sistem kerja yang tidak memberikan jaminan dan perlindungan apapun serta hanya memberikan berbagai kesulitan, seperti kontrak dan outsourcing.
Precariat: Buruh Kontrak dan Outsourcing di Era Pasar Tenaga Kerja Fleksibel
Meningkatnya sistem kerja kontrak dan outsourcing ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia. Praktek ini sudah berlangsung di seluruh dunia. Hal itulah yang dijelaskan Guy Standing dalam bukunya The Precariat: the New Dangerous Class. Gambaran dari kondisi para buruh kontrak dan outsourcing di berbagai daerah di Indonesia tersebut, serupa dengan kondisi jutaan buruh/pekerja lainnya di seluruh dunia. Menurut Standing, data statistik menunjukkan bahwa jumlah buruh/pekerja kontrak telah meningkat dengan tajam selama lebih dari tiga dekade terakhir. Di Jepang, lebih dari sepertiga dari jumlah keseluruhan pekerja di sana bekerja dengan status kontrak. Di Korea Selatan, lebih dari setengah dari jumlah keseluruhan pekerja bekerja dengan status kontrak. Begitu pun dengan yang terjadi di berbagai negara lainnya, seperti Inggris, Spanyol, Italia, dan sebagainya, termasuk para pekerja migran, serta para imigran tak berdokumen. Mereka, para buruh/pekerja kontrak tersebut, didefinisikan Standing, dalam bukunya sebagai precariat.
Buku ini terdiri atas 7 (tujuh) bab, di mana dalam bab 1, Standing menjelaskan definisi dan ciri-ciri dari precariat. Standing mendefinisikan bahwa precariat bukanlah ‘working class’ atau ‘proletariat.’ Pemberlakuan LMF (labour market flexibility) yang kian masif di seluruh dunia inilah yang kemudian memunculkan kelas baru dalam masyarakat, yakni precariat (precarious proletariat), di mana status kerja kontrak menjadi ciri yang sangat kuat dari precariat. Dengan menggunakan termin Marxian dan Weberian, Standing menjelaskan definisi dan ciri-ciri dari precariat. Dalam termin Marxian, precariat adalah sebuah class-in-the-making atau class in itself, di mana kesadaran dari individu-individu yang tergabung dalam sebuah kelas belum menjadi satu kesatuan dan mereka pun belum bersatu untuk mewujudkan kepentingan bersama.
Sementara itu, dengan menggunakan termin Weberian, Standing menyebutkan beberapa ciri dari precariat, yang di dalamnya mencakup ketiadaan: jaminan pekerjaan tetap (labour market security), perlindungan dari pemecatan sewenang-wenang, atau peraturan dalam merekrut atau memecat (employment security), kesempatan untuk melakukan mobilitas, baik status maupun pendapatan (job security), jaminan perlindungan dari kecelakaan kerja atau sakit yang diakibatkan kerja, melalui, misalnya peraturan mengenai keamanan dan kesehatan, pembatasan jam kerja, dsb. (work security), kesempatan untuk meraih keterampilan tertentu, melalui magang, pelatihan-pelatihan, dll. yang biasa digunakan untuk meningkatkan kompetensi (skill reproduction security), asuransi pendapatan, yang dilindungi melalui, misalnya, upah minimum, indeksasi upah, jaminan sosial komprehensif, pajak progresif untuk mengurangi ketidakadilan dan untuk memberikan kelengkapan bagi mereka yang berpendapatan rendah (income security), serta suara kolektif dalam pasar tenaga kerja, melalui, misalnya, serikat buruh independen, dengan hak untuk melakukan mogok (representation security). Selain itu, Standing menyatakan bahwa precariat juga merupakan denizens, di mana mereka tidak memiliki jaminan atas hak-hak mereka sebagai warga negara (citizens), termasuk hak untuk berserikat.
Dalam bab 2, Standing menjelaskan bahwa kemunculan precariat yang berjalan seiring dengan kian meningkatnya sistem kerja kontrak dan outsourcing ini tidak terlepas dari sistem ekonomi global yang tengah berlangsung. Menurut Standing, kemunculan precariat adalah akibat dari sistem ekonomi politik yang digagas oleh para ekonom neoklasik, atau yang lebih kita kenal dengan neoliberalisme. Lebih tepatnya, melalui Labour Market Flexibility (LMF) atau pasar tenaga kerja fleksibel yang digencarkan oleh para ekonom neoklasik, utamanya pada tahun 1980-an sebagai usaha untuk mengalihkan/mentransfer resiko-resiko dunia usaha dan insecurity kepada para pekerja. Selain itu, dalam bab ini, Standing juga menjelaskan bahwa fleksibilitas yang berlaku dalam pasar tenaga kerja yang memungkinkan kemunculan precariat ini memiliki beberapa modus, di antaranya numerical flexibility yang biasanya dihubungkan dengan sistem kerja outsourcing atau offshoring, dimana kedua sistem kerja tersebut menegaskan ketiadaan jaminan pekerjaan (employment security), serta functional flexibility, yang mengintensifkan ketiadaan jaminan dalam bekerja (job security).
Standing kemudian menyatakan bahwa terdapat berbagai macam precariat dengan tingkat/derajat insecurity yang berbeda-beda pada bab 3. Dalam hal ini, Standing memfokuskan perhatiannya pada perempuan dan kaum muda (youth), yang menurutnya menjadi bagian yang paling banyak dari precariat. Untuk konteks Indonesia, dengan melihat berbagai pola yang dipakai kaum pengusaha/pemilik modal dalam mempraktikkan sistem kerja kontrak dan outsourcing, seperti melakukan PHK terhadap buruh (berstatus kerja) tetap dengan modus pemailitan perusahaan untuk kemudian merekrut lagi buruh tersebut untuk bekerja di perusahaan mereka yang baru, melalui outsourcing serta dengan status kerja sebagai buruh kontrak, terlihat bahwa buruh (dengan status kerja) tetap pun menghadapi kerentanan dan bisa dikatakan pula bahwa mereka merupakan precariat.
Pada setiap bab di dalam buku ini, Standing selalu menekankan globalisasi neoliberal melalui Labor Market Flexibility (LMF) atau pasar tenaga kerja fleksibel sebagai penyebab kian meningkatnya precariat di seluruh dunia. Menurut geografer Marxis David Harvey, kedua sistem kerja (kontrak dan outsourcing) merupakan bagian terpenting dari Labor Market Flexibility (LMF), di mana dalam pasar tenaga kerja fleksibel, menyelamatkan dunia usaha (pengusaha, pemilik modal, dan investor) adalah lebih penting dan lebih diprioritaskan untuk dilakukan negara daripada menyelamatkan hak-hak dan jaminan kepastian kerja kaum buruh.[2] Dengan sendirinya, kepentingan dunia usaha sangat diuntungkan dengan diterapkannya sistem kerja kontrak dan outsourcing, karena pengusaha dapat merekrut buruh/pekerja untuk jangka waktu yang biasanya pendek, untuk kemudian direkrut kembali dengan sistem kontrak atau outsourcing dan diberhentikan sewaktu-waktu. Ibarat pedang Damocles, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setiap saatnya bisa memancung lehernya para buruh/pekerja.
Terkait dengan itu, neoliberalisme yang sangat mengagungkan pasar bebas melancarkan usaha agar jangkauan geografis dari pasar semakin luas dan waktu kontrak yang digunakan juga semakin singkat. Usaha tersebut disebut sebagai globalisasi. Harvey menyebutnya sebagai ‘space time-compression’[3] dimana karakter dari neoliberalisme adalah relasi-relasi kontrak, dan dalam hal pasar tenaga kerja, fleksibilitas menjadi kata kuncinya. Globalisasi neoliberal tersebut, ‘diisi’ oleh berbagai Multi National Corporation (MNC), Trans National Corporation (TNC), dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank (WB), dan kekuatan-kekuatan modal lainnya.[4]
Kemunculan neoliberalisme sendiri tidak terlepas dari peranan besar seorang ekonom Austria bernama Friedrich August von Hayek, yang gigih memperjuangkan neoliberalisme. Karyanya yang berjudul The Constitution of Liberty menjadi ‘kitab suci’ bagi para penganut neoliberalisme.[5] Neoliberalisme pun kemudian berkembang di negara-negara seperti Inggris, Amerika Latin, dan mengalami perluasan hingga ke negara-negara dunia ketiga.[6] Menurut Norena Heertz, neoliberalisme ditandai dengan diberlakukannya kebijakan pemangkasan pengeluaran publik; pemotongan pajak agar produksi bisa semakin besar; mengontrakkan sejumlah fungsi negara; negara tidak lagi memiliki peran dalam redistribusi kekayaan; sektor swasta diberi kebebasan dan negara dipinggirkan; deregulasi ekonomi; mencabut kontrol atas harga minyak; serta membatasi kekuatan serikat buruh. Neoliberalisme ini pun ditandai dengan tiga kebijakan umum yang diambil negara yaitu deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi.[7]
Terkait dengan karakter dari neoliberalisme sebagaimana diungkapkan Harvey, Standing mengungkapkan bahwa pasar tenaga kerja tidak dicirikan oleh penjualan tenaga kerja dalam relasi yang temporer atau sementara atau dapat juga disebut kontrak. Kondisi seperti itu (penjualan tenaga kerja dalam relasi yang temporer/kontrak) hanya ditemui dalam pasar budak atau slavery labor market. Dalam hal ini, termin yang seperti itu lebih mengacu pada pasar tenaga kerja fleksibel. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pasar tenaga kerja yang fleksibel merupakan karakter dari neoliberalisme sebagai usaha untuk meningkatkan kejayaan pasar.[8]
UUK 13/2003 dan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel di Indonesia
Di Indonesia, pemberlakuan LMF atau pasar tenaga kerja fleksibel yang kian masif pasca rezim Soeharto tidak terlepas dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan negara-negara lainnya pada tahun 1997. Dalam kondisi krisis pada waktu itu, Indonesia ‘bekerja sama’ dengan lembaga keuangan internasional, International Monetary Fund (IMF), untuk memperoleh bantuan keuangan dalam rangka pemulihan negara dari krisis. Namun, tak ada lagi makan siang yang gratis. Dalam memberikan bantuannya, IMF menyertakan sejumlah persyaratan sebagai ‘resep’ kebijakan yang harus dipenuhi Indonesia. Penandatanganan LoI (Letter of Intent) antara Indonesia, melalui Soeharto, dengan IMF sejak tahun 1997, diikuti dengan program-program penyesuaian struktural seperti yang berlaku di negara-negara berkembang lainnya.[9] Resep kebijakan IMF untuk Indonesia mengenai pasar tenaga kerja fleksibel sendiri tercantum secara eksplisit dalam LoI dengan IMF pada tanggal 18 Maret 2003, bunyinya:
“…We are working with labor and business to ensure that the laws strike an appropriate balance between protecting the rights of workers, including freedom of association, and preserving a flexible labor market.”[10]
LoI tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk regulasi, yakni UU no.13/2003 mengenai ketenagakerjaan, yang didalamnya dengan jelas melegalkan pemberlakuan sistem kerja kontrak dan outsourcing.[11] Terkait hal tersebut, Standing juga menyatakan bahwa dalam globalisasi terjadi re-regulation di mana lebih banyak regulasi yang ditawarkan dalam era globalisasi ini melebihi apa yang pernah terjadi dalam sejarah.[12] Berbagai regulasi memang dibutuhkan negara neoliberal untuk memuluskan jalan bagi akumulasi kapital melalui berbagai macam investasi. Pelegalan sistem kontrak dan outsourcing melalui regulasi (yang kemudian dimanifestasikan dalam UUK 13/20003) pun memang merupakan permintaan dari pihak pengusaha (APINDO).
‘…Kemudian, setelah bergulirnya proses pembahasan UUK 13/2003 ini, pihak APINDO memunculkan keinginan untuk melegalkan itu (borongan/ outsourcing)…’[13]
Di Indonesia, alasan yang selalu digunakan pengusaha dan kemudian dibenarkan pemerintah dalam memberlakukan sistem kerja kontrak dan outsourcing, bahwa sistem kerja kontrak dan outsourcing akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi yang akhirnya dapat memacu ekspansi dan berujung pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.[14] Nyatanya, penyerapan tenaga kerja yang digunakan sebagai dalih atau alasan tersebut tidak terbukti benar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per periode 2004 – April 2005 misalnya, menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja sektor informal meningkat sekitar 1,4 juta orang atau dari 63,2% per Agustus 2004 menjadi 63,9% per Februari 2005.[15] Artinya, tidak banyak tenaga kerja yang dapat terserap di sektor formal, meski sistem kerja kontrak dan outsourcing telah diterapkan. Jumlah pekerja/buruh kontrak di Indonesia sendiri, berdasarkan data yang dikeluarkan ILO pada tahun 2010 berjumlah 65%.[16]
Selain itu, kemunculan precariat pun berkaitan dengan gejala sosial lain yang selalu menjadi polemik di Indonesia, yakni buruh/pekerja migran. Seperti yang diungkapkan oleh Heriyanto,[17] misalnya, bahwa banyaknya buruh di Kab. Karawang yang selalu mendapatkan ketidakpastian dari sistem kerja kontrak dan outsourcing yang akhirnya menjadi buruh/pekerja migran, menunjukkan bahwa buruh/pekerja migran memang merupakan salah satu konsekuensi penting dari sistem kerja kontrak dan outsourcing. Sebagaimana diungkapkan Standing dalam bab 4 buku ini, para buruh/pekerja migran (termasuk juga para imigran tak berdokumen) telah menjadi bagian terbesar dari precariat di seluruh dunia.[18]

Precariat dan Komodifikasi Pendidikan
Yang juga menarik adalah apa yang diungkapkan Standing dalam bab 5. Standing menjelaskan bahwa kemunculan precariat sangat erat kaitannya dengan komodifikasi pendidikan yang dilancarkan neoliberalisme. Rendahnya tingkat pendidikan tentu semakin mendekatkan calon-calon pekerja pada precariat. Dalam hal ini, neoliberalisme melancarkan prinsip-prinsip pasar ke seluruh kehidupan, tidak terkecuali ke dalam pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.
Dalam neoliberalisme, orientasi pendidikan tinggi berubah menjadi pembangunan gedung-gedung universitas yang mewah secara fisik, penambahan fasilitas-fasilitas yang tidak pokok bagi mahasiswa, dan sebagainya. Kita dapat melihat kondisi tersebut dengan sangat jelas di Indonesia. Pengesahan berbagai regulasi yang mengesahkan komersialisasi dan privatisasi pendidikan tinggi di Indonesia semenjak awal tahun 2000, mulai dari PP BHMN (Badan Hukum Milik Negara), UU BHP (Badan Hukum Pendidikan), dan kini UU Pendidikan Tinggi, memang ditujukan untuk menjadikan pendidikan sebagai sektor jasa.[19] Dengan demikian, pendidikan hanya dapat dinikmati oleh segelintir, yang dapat ‘membeli’ jasa tersebut. Akibatnya, precarisation terjadi kian masif dan termasuk (juga) mengancam mereka yang menikmati pendidikan tinggi. Hal ini juga menegaskan bahwa tingkat pendidikan tidak menjadi jaminan seseorang dapat menghindar dari ancaman precarisation, meski dengan degree/derajat yang berbeda dengan mereka yang (bahkan) tidak dapat menikmati pendidikan tinggi.
Politik Precariat
Selain dihadapkan pada berbagai ketiadaan jaminan dan perlindungan, precariat pun dihadapkan pada apa yang disebut Standing sebagai politics of inferno atau politik buruk. Inilah yang dijelaskan Standing pada bab 6 bukunya. Politics of inferno atau politik buruk yang dimaksud Standing adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik di mana baik dari segi kebijakan maupun institusi tidak menguntungkan precariat. Selain itu, komodifikasi politik yang terjadi secara global, dimana situasi yang muncul adalah didominasinya politik oleh para praktisi pasar, membuat precariat dimandulkan secara politik. Sementara itu, precariat tidak memiliki serikat yang dapat merepresentasikan mereka dengan baik. Kondisi-kondisi inilah yang menurut Standing, akan menggiring precariat pada politik ekstrem atau politics of inferno tersebut.
Sebagai tawaran solusi atas politics of inferno tersebut, Standing, dalam bab 7 buku ini, kemudian menawarkan politics of paradise atau politik baik, dimana precariat dapat membangun berbagai agenda politik progresif mereka dalam rangka menghadapi politics of inferno atau politik buruk tersebut. Menurut Standing, precariat membutuhkan mekanisme untuk menghasilkan demokrasi deliberatif sebagai gerakan perlawanan mereka atas politik buruk yang terjadi. Politics of paradise atau politik baik melalui demokrasi deliberatif tersebut di antaranya diwujudkan dengan cara bahwa precariat memiliki serikat yang dapat merepresentasikan kepentingan mereka dengan baik.
Politics of inferno yang dialami precariat di Indonesia berbeda dengan yang dialami berbagai negara lain yang masih dapat secara terbuka menyatakan right-wing dan left-wing dalam politik resminya. Di Indonesia, akses politik dijauhkan, bukan hanya dari precariat tetapi juga dari serikat buruh itu sendiri. Semua kaum buruh, baik yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan precariat maupun yang belum memiliki ciri-ciri tersebut, diajuhkan dari politik. Hal tersebut tidak terlepas dari depolitisasi serikat buruh yang dilakukan Orde Baru yang hingga kini masih terus dirasakan keberlanjutan dan dampaknya. Selain itu, adanya desentralisasi di Indonesia, membuat kehidupan precariat makin memburuk, misalnya terjebak pada berbagai pungutan pemburu rente di daerah. Sehingga, terkait dengan tawaran Standing mengenai politics of paradise, dimana precariat harus membangun serikatnya, dalam konteks Indonesia, hal tersebut bukan perkara gampang, mengingat tradisi politik serikat buruh yang terorganisir dengan sangat baik juga telah diberangus pada masa Orde Baru Soeharto.
Penutup
Apa yang berlaku dalam sistem kerja kontrak dan outsourcing saat ini mengingatkan penulis pada ratusan tahun yang lalu, di mana dalam bentuk dan mekanisme yang tidak sama persis, sistem kerja kontrak dan outsourcing telah diberlakukan sejak masa kolonial. Seperti diketahui, sistem kerja kontrak telah muncul di Hindia sejak masa kolonial Belanda pada sekitar pertengahan abad ke-19. Pada masa itu, kaum buruh, yang kebanyakan bekerja pada perkebunan-perkebunan[20] di Sumatera, khususnya di Deli, Jawa, dan pulau-pulau lainnya serta bekerja pada industri dan pelabuhan-pelabuhan di Jawa, dipekerjakan dengan cara kontrak serta dengan perekrutan yang tidak langsung.[21]
Tawaran Standing mengenai politics of paradise atau politik baik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut penulis, bukanlah hal yang baru, di mana pengalaman Indonesia telah pernah menunjukkan hal tersebut. Misalnya, dengan terorganisirnya kekuatan buruh pada masa Soekarno, melalui SOBSI, sistem kerja kontrak tersebut sempat menghilang dari Indonesia. Dari berbagai regulasi yang ada pada masa itu, tidak ada satu pun regulasi yang melegalkan sistem kerja kontrak. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara situasi hubungan kerja dengan kekuatan buruh yang terorganisir.
Namun, dalam konteks saat ini dan khususnya di Indonesia, penulis bersepakat dengan Standing, bahwa kunci dari politics of paradise saat ini memang ada pada serikat-serikat buruh yang telah ada. Di sini, peran serikat buruh sangat vital, dalam ‘merangkul’ precariat dan mendorong terbentuknya serikat precariat yang benar-benar merepresentasikan kepentingan dari precariat. Akan tetapi, tidak hanya sampai disitu, pembentukan serikat precariat ini juga harus dilihat, bukan hanya dari relasi kerja, melainkan relasi produksi secara keseluruhan. Seperti yang telah penulis jelaskan di atas, tingkat pendidikan tidak menjadi jaminan terbebasnya seseorang dari precarisation, sehingga daya tawar hanya dapat diajukan melalui organisasi. Prespektif keterorganisiran serikat yang tidak hanya berfokus pada relasi kerja, tapi juga relasi produksi secara keseluruhan penting diterapkan dalam pembentukan serikat precariat mengingat dimensi ‘space time-compression’ ala globalisasi neoliberal yang membuat precarisation tidak hanya terjadi di satu sektor atau satu wilayah, melainkan di semua sektor dan di semua wilayah.
Mengingat kemunculan precariat merupakan konsekuensi dari globalisasi neoliberal melalui pasar tenaga kerja fleksibel, maka studi mengenai kemunculan precariat seperti yang diungkapkan Standing dalam bukunya ini memiliki signifikansi yang cukup besar dalam diskursus dan praktek perjuangan kelas buruh di masa mendatang. Karena itu pula, kemunculan buku ini sangat penting dibaca oleh para intelektual yang menggeluti sektor perburuhan dan, tentu saja, para aktivis buruh.***
¶
Fathimah Fildzah Izzati, anggota redaksi Left Book Review (LBR). Penulis beredar di Twitterland dengan id @ffildzahizz.
Bacaan Tambahan :
Harvey, David. Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis. Trans. Eko Prasetyo Darmawan. Yogyakarta: Resist Book, 2009.
Wibowo, I. dan Francis Wahono (ed.). Neoliberalisme. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003.
Wibowo, I. Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi. Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2010.
Breman, Jan. Menjinakkan sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli di Sumatera Timur pada awal abad ke-20. Trans. Koesalah Soebagyo Toer.Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997. Trans. of Koelies, planters en koloniale politiek: het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingenaan Sumatra’s Oostkust in het begin van de twintigste eeuw, 1992.
Negara adalah Kita: Pengalaman Rakyat Melawan Penindasan. Jakarta: Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat, Perkumpulan Praxis, YAPPIKA (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi), 2006.
Priambada, Komang & Maharta, Agus Eka. Outsourcing versus Serikat Pekerja? Jakarta: Alihdaya Publishing, 2008.
Standing, Guy. Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice. New York: ST Martin’s Press Inc., 1999.
Data dari internet :
“Awal Tahun 2011 Pengangguran Masih 9,25 juta”; diperoleh dari http://jarno.web.id/general/awal-tahun-2011-pengangguran-masih-925-juta.html#axzz1f7i29IpH; Internet; diakses 4 November 2011.
International Monetary Fund, “Indonesia—Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of UnderstandingJakarta, Indonesia, March 18, 2003”; diperoleh dari : http://www.imf.org/external/np/loi/2003/idn/01/; Internet; diakses 13 Februari 2010.
Rosalina, “Pekerja Outsorcing di Indonesia Mencapai 65 Persen”; diperoleh dari http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/12/23/brk,20101223-301134,id.html; Internet; diakses 7 Maret 2011.
Dokumen :
Indonesia Managing Highern Education for Relevance dan Efficiency (IMHERE).
Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Wawancara :
Wawancara dengan Dametua Sagala, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Disnaker Kab. Karawang, Selasa, 19 Juli 2011 di Kantor Disnaker Kab. Karawang.
Wawancara dengan Heriyanto, Ketua Umum FSPEK- Karawang, Minggu, 10 Juli 2011 di Sekretariat FSPEK Karawang, Klari-Kab. Karawang.
Wawancara dengan Riden, Ketua DPC FSPMI Kab. Tangerang, Sabtu, 25 Juni 2011 di Sekeretariat FSPMI, Cimone-Tangerang
[1]“Awal Tahun 2011 Pengangguran Masih 9,25 juta”; diperoleh dari http://jarno.web.id/general/awal-tahun-2011-pengangguran-masih-925-juta.html#axzz1f7i29IpH; Internet; diakses 4 November 2011.
[2]David Harvey, Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis (trans.) (Yogyakarta: Resist Book, 2009), 117-136.
[3] Ibid., 6.
[4]I. Wibowo, Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi (Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2010), 87-119.
[5]B. Herry Priyono, “Dalam Pusaran Neoliberalisme”, dalam Neoliberalisme, ed. I. Wibowo dan Francis Wahono, 47-84. (Yogyakarta : Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), 53.
[6]David Harvey, op .cit.
[7]Norena Heertz, “Hidup di Dunia Material: Munculnya Gelombang Neoliberalisme” dalam Neoliberalisme, ed. I. Wibowo dan Francis Wahono,13-46. (Yogyakarta : Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), 13-27.
[8]Guy Standing, Global Labour Flexibility : Seeking Distributive Justice (New York : ST Martin’s Press Inc, 1999).
[9]David Harvey, op. cit.
[10]International Monetary Fund, “Indonesia—Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of UnderstandingJakarta, Indonesia, March 18, 2003”;diperoleh dari : http://www.imf.org/external/np/loi/2003/idn/01/; Internet; diakses 13 Februari 2010.
[11]Sistem kerja kontrak dan outsourcing dibahasakan lain dalam UU No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Dalam UU No.13 tahun 2003, kerja kontrak dibahasakan dengan Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) dan perusahaan outsourcing dibahasakan dengan Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja.
[12]Guy Standing. The Precariat: The New Dangerous Class. op. cit., hlm. 26.
[13]Wawancara dengan Riden, Ketua DPC FSPMI Kab. Tangerang, hari Sabtu, 25 Juni 2011.
[14]Komang Priambada & Agus Eka Maharta, Outsourcing versus Serikat Pekerja? (Jakarta: Alihdaya Publishing, 2008), 8. Penyataan ini dibenarkan oleh Disnaker Kab. Karawang, dalam wawancaranya dengan penulis pada Juni 2012.
[15]Anwar “Sastro” Ma’ruf, “Buruh dalm Skema Penjajahan Baru”, dalam Negara adalah Kita: Pengalaman Rakyat Melawan Penindasan (Jakarta: Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat, Perkumpulan Praxis, YAPPIKA (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi), 2006), 479.
[16]Rosalina, “Pekerja Outsorcing di Indonesia Mencapai 65 Persen”; diperoleh dari http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/12/23/brk,20101223-301134,id.html; internet; diakses 7 Maret 2011.
[17] Informan dari FSPEK-Karwang dalam wawancara dengan penulis pada Minggu 10 Juli 2011.
[18]Guy Standing. The Precariat: The New Dangerous Class. op. cit., hlm. 90.
[19]Hal tersebut dapat dilihat dalam dokumen Bank Dunia: Indonesia Managing Highern Education for Relevance dan Efficiency (IMHERE).
[20]Kaum buruh yang bekerja di perkebunan-perkebunan ini disebut koeli atau kuli. Dalam tulisannya, Jan Breman menyatakan: “Kuli adalah istilah kolonial. Maknanya sangat merendahkan derajat si kuli, dan itu memang sesuai dengan penindasan yang dilakukan tuan kebun terhadap mereka, bukan secara tradisional, tapi modern.” Lihat Jan Breman, Menjinakkan sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli di Sumatera Timur pada awal abad ke-20 (trans.) (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997).
[21]Dalam konteks saat ini, perekrutan buruh secara tidak langsung disebut dengan outsourcing.