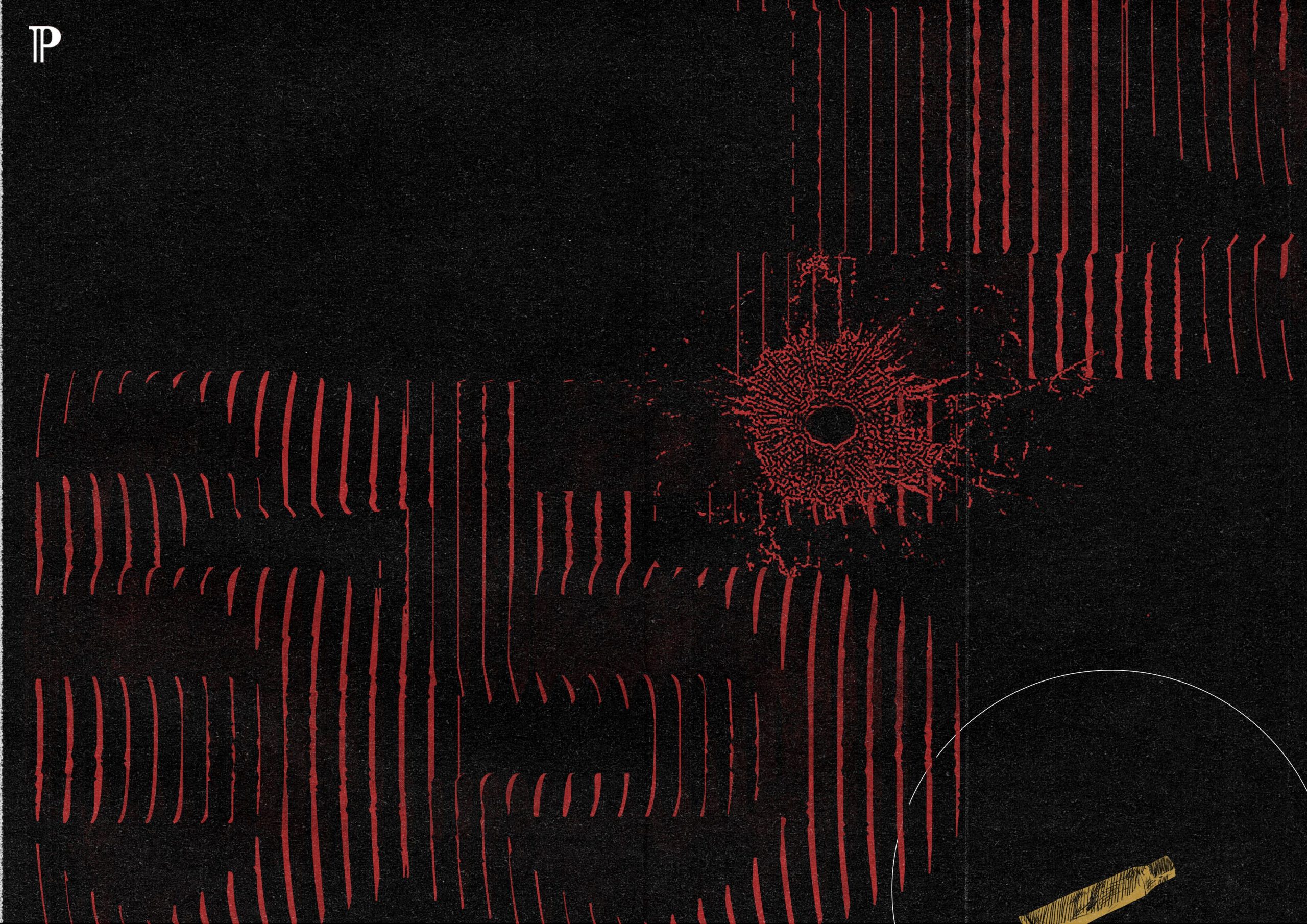Ilustrasi: illustruth
PENYUSUNAN ulang sejarah resmi tidak bisa dianggap sebagai kado ulang tahun ke-80 republik seperti yang dikatakan pemerintah. Di baliknya tersembunyi motif yang patut diungkap. Penulisan sejarah resmi oleh negara bukanlah praktik netral, melainkan strategi hegemonik untuk mengukuhkan legitimasi ideologis; upaya yang dapat dibaca sebagai konsolidasi narasi dominan demi membentuk kesadaran nasional yang sesuai dengan kepentingan kekuasaan saat ini. Proyek semacam ini sering kali menjadi sarana untuk meneguhkan identitas politik tertentu dengan mengorbankan representasi kelompok-kelompok yang mengalami kekerasan sejarah.
Untuk melihat bagaimana negara secara sistematis menampilkan sejarah secara selektif, tulisan ini akan mengangkat dua periode kekerasan paling besar dalam sejarah Indonesia, pembantaian 1965-1966 dan pemerkosaan Reformasi 1998.
I. Pembantaian 1965-1966
Negara dan Politik Pelupaan
Dalam periode 1965–1966, lebih dari 500 ribu orang diyakini menjadi korban pembantaian dengan dalih penumpasan Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun, seperti ditunjukkan oleh John Roosa, narasi kudeta oleh PKI adalah dalih semata (Roosa, 2006). Bukti-bukti kuat berasal dari arsip-arsip militer (Melvin, 2018) dan kesaksian korban yang dikumpulkan dalam proyek-proyek sejarah lisan oleh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia (Roosa et al., 2004). Dalam buku Tahun yang Tak Pernah Berakhir, wawancara dengan para penyintas menunjukkan bahwa banyak penangkapan dan pembunuhan dilakukan oleh militer lokal tanpa proses hukum, sering kali sekadar berdasarkan laporan dari tetangga atau aparat desa, bukan karena keterlibatan nyata dalam aktivitas PKI (Roosa et al., 2004). Kekerasan ini adalah operasi yang dirancang secara sistematis oleh militer (Robinson, 2018), yang juga mendapat legitimasi internasional sebagai bagian dari Perang Dingin sebagaimana dikaji Mattias Fibiger, yang menyebut rezim Soeharto sebagai pion regional dalam proyek kontra-revolusioner Amerika Serikat (Fibiger, 2023).
Di atas tumpukan tubuh tak bernyawa, narasi negara mendefinisikan peristiwa ini sebagai “penyelamatan bangsa”—dan melanggengkannya melalui film, museum, patung, kurikulum sekolah, serta upacara kenegaraan. Sebagaimana ditulis Ariel Heryanto, ini adalah bentuk teror simbolik: bukan hanya membungkam para korban, tetapi juga mengontrol cara rakyat mengingat dan menceritakan masa lalu mereka (Heryanto, 2005).
Negara menarasikan tragedi 1965 sebagai “pemberontakan” yang berhasil digagalkan. Dalam narasi ini, militer adalah pahlawan, sedangkan korban dihapuskan dari teks. Narasi ini dikokohkan melalui kurikulum pendidikan sejarah di sekolah menengah, buku teks resmi seperti Sejarah Nasional Indonesia, dan penggambaran visual dalam film Pengkhianatan G30S/PKI yang disiarkan setiap tahun hingga 1998. Seperti ditunjukkan Saskia Wieringa, penggambaran perempuan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) sebagai sadis dan tidak bermoral adalah bagian dari strategi misoginis negara dalam membentuk lanskap ingatan yang domestik, patriarkal, dan penuh rekayasa (Wieringa, 2002; 2019). Propaganda ini berhasil membangun ketakutan moral yang hingga kini masih bekerja secara efektif dalam menekan wacana alternatif.
Grace Leksana menyebut domestikasi ruang-ruang publik oleh negara sebagai pembentukan “lanskap ingatan” (Leksana, 2023). Budiawan (2004) menambahkan bahwa wacana anti-komunis telah menjadi struktur wacana yang diwariskan lintas rezim—dari Orde Baru hingga era Reformasi—yang terus-menerus mendefinisikan siapa yang dianggap sebagai bagian dari bangsa dan siapa yang dikucilkan. Dengan demikian, kita tidak sedang berhadapan dengan sejarah, tetapi dengan narasi tentang sejarah yang sangat politis.
Luka yang Tak Terucap: Trauma, Diam, dan Perjuangan Ingatan
Luka yang tidak diakui ini menjalar antar-generasi. Para penyintas dan keluarga korban tak hanya kehilangan orang yang dicintai, tetapi juga hak hidup, pekerjaan, pendidikan, dan martabat. Mereka dicap “eks-tapol”, disisihkan secara sosial, dan diawasi dalam diam. Trauma mereka diwariskan dalam bisik-bisik keluarga, cerita makan malam, dan nyanyian tidur. Salah satu kisah dalam buku Tahun yang Tak Pernah Berakhir mengisahkan seorang perempuan di Blitar yang baru menyadari bahwa ayahnya korban pembantaian setelah menemukan catatan rahasia yang disembunyikan ibunya selama puluhan tahun (Roosa et al., 2004). Leksana menyebut bentuk pewarisan seperti ini sebagai “ingatan terbenam” (embedded remembering), di mana memori trauma tetap hidup meskipun tidak diberi ruang dalam narasi resmi. John Roosa dan Hilmar Farid menyebut bentuk ingatan ini sebagai “ingatan yang terpenjara” (Roosa et al., 2004).
Dua film Joshua Oppenheimer—The Act of Killing (2012) dan The Look of Silence (2014)—menunjukkan dengan jelas bagaimana narasi pelaku dan korban beradu dalam ranah ingatan publik. The Act of Killing bahkan memperlihatkan bagaimana para algojo bangga atas pembantaian yang mereka lakukan, sementara The Look of Silence berfokus pada keberanian seorang adik korban untuk menghadapi para pembunuh saudaranya. Respons publik terhadap film ini sangat beragam: di satu sisi, banyak penonton yang terguncang dan mulai mempertanyakan narasi resmi; di sisi lain, negara dan sebagian elite militer menunjukkan resistansi dan menolak untuk membuka kembali peristiwa ini. Penolakan terhadap pemutaran film secara luas di Indonesia mencerminkan betapa narasi negara masih dominan dan berusaha menutupi ruang bagi ingatan alternatif. Gerombolan pelaku merasa bangga karena negara tak pernah menindak mereka, sementara para korban hanya bisa menyimpan dendam dan duka dalam sunyi.
II. Pemerkosaan Mei 1998
Kekerasan Simbolik dan Politik terhadap Perempuan
Dalam bincang-bincang di sebuah stasiun televisi pada 8 Juni silam, Menteri Kebudayaan Fadli Zon melontarkan pernyataan kontroversial. Ia meragukan terjadinya pemerkosaan massal terhadap perempuan dalam kerusuhan Mei 1998. Menurutnya itu sebatas rumor. “Enggak ada proof-nya,” katanya. Peristiwa itu “hanya cerita” yang menurutnya belum ada dalam buku sejarah. Klaim ini, alih-alih menawarkan klarifikasi sejarah, justru memperpanjang derita para korban dan mencerminkan sikap negara yang terus gagal menegakkan keadilan.
[TW: dua paragraf berikutnya memuat konten eksplisit tentang kekerasan seksual dan rasial]
Laporan Komnas Perempuan dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu Mei–Juli 1998, setidaknya 168 kasus kekerasan seksual terjadi terutama di Jakarta, termasuk pemerkosaan bergilir, penyiksaan seksual, mutilasi, dan pembakaran hidup-hidup (Komnas Perempuan, 1999). Komnas Perempuan menyebut sebagian besar korban adalah perempuan Tionghoa. Korban lain termasuk perempuan pekerja dan perempuan miskin kota yang kebetulan berada di wilayah kekerasan massa. Kenapa mayoritas perempuan Tionghoa yang jadi target pemerkosaan? Dalam laporan itu disebut: perempuan Tionghoa secara khusus ditargetkan karena simbolisasi mereka sebagai “asing”, “kaya”, dan bukan bagian dari bangsa Indonesia.
Lebih lanjut laporan itu menulis: kekerasan itu bukan kebetulan atau spontan. Ia adalah kekerasan simbolik dan politik, mengandung pesan: “karena kamu Cina, kamu diperkosa.” Pemerkosaan dijadikan alat untuk menghina identitas etnis, meruntuhkan harga diri komunitas, dan menanamkan teror. Dalam banyak kasus, pemerkosaan dilakukan secara berkelompok, di depan keluarga, bahkan sambil diteriakkan makian rasial (TGPF, 1999). Artinya tubuh perempuan dijadikan “panggung” simbolis untuk mempermalukan komunitas yang disasar—rasial, kelas, dan gender menjadi titik temu kekerasan politik.
Ariel Heryanto dalam esainya yang penting, Rape, Race, and Reporting (1999), menjelaskan bahwa kekerasan seksual Mei 1998 memiliki empat karakteristik: (1) kebrutalan yang dipertontonkan secara masif, (2) penciptaan rasa takut kolektif, (3) kekebalan pelaku dari hukum, dan (4) absurditas dari tindakan itu sendiri—bahwa ia terjadi bukan karena kebutuhan, melainkan demi mempertahankan dominasi simbolik.
Kekerasan ini bukan sekadar tindak kriminal melainkan bagian dari struktur kekuasaan negara pascakolonial yang bersifat maskulin dan represif. Pemerkosaan itu merupakan bentuk kekerasan simbolik yang dirancang untuk menanamkan rasa takut kepada kelompok tertentu: perempuan, etnis Tionghoa, dan warga sipil. Ia menyebut bahwa kekerasan ini dilakukan dalam konteks “vulgar masculinist postcolonial state power”, sebuah relasi kuasa yang menggabungkan brutalitas maskulin, kekebalan hukum bagi pelaku, dan represi negara. Kekerasan tersebut menyasar tubuh perempuan untuk menunjukkan dominasi politik dan kultural atas komunitas yang dianggap “asing” dan tidak berhak atas rasa aman di Indonesia.
Heryanto juga menyingkap lapisan lain dari tragedi ini: para secondary victims (korban sekunder)—mereka yang tidak diperkosa secara langsung namun hidup dalam ketakutan, stigma, dan kerentanan yang ekstrem. Dalam konteks perempuan Tionghoa, banyak yang meninggalkan Indonesia, berhenti bekerja, atau mengasingkan diri akibat trauma kolektif yang tidak pernah diakui negara secara utuh.
Hal ini ditegaskan pula oleh Charlotte Setijadi dalam Memories of Unbelonging (2023). Ia menulis bahwa peristiwa Mei 1998 meninggalkan luka identitas mendalam bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Perempuan-perempuan Tionghoa tidak hanya menjadi korban kekerasan seksual, tetapi juga menjadi lambang dari eksistensi yang selalu disangkal oleh negara. Setijadi menuliskan bagaimana perempuan Tionghoa menjadi simbol dari konstruksi “yang asing” di Indonesia—meski telah hidup di tanah ini selama generasi. Saat kerusuhan terjadi, perempuan dari komunitas ini tidak hanya diserang karena jenis kelamin, tetapi juga karena representasi simboliknya sebagai “komunitas asing yang makmur”—narasi lama yang terus dihidupkan oleh elite kekuasaan.
Pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 adalah bentuk kekerasan politik berbasis ras dan gender, yang dipicu oleh runtuhnya legitimasi Orde Baru dan dibiarkan oleh aparat keamanan. Jemma Purdey dalam Anti-Chinese Violence in Indonesia (2006) menyebut bahwa serangan tersebut dilandasi oleh pengorganisasian yang memungkinkan kekerasan menjadi alat penyaluran frustrasi kolektif sambil tetap menjamin keamanan pelaku.
Hingga kini, tidak satu pun pelaku kekerasan seksual dibawa ke pengadilan. Laporan Komnas HAM dalam Merawat Ingatan Menjemput Keadilan (2020) menyatakan bahwa rekomendasi penyelidikan oleh Komnas Perempuan, TGPF, maupun lembaga internasional tidak pernah ditindaklanjuti secara serius oleh negara. Hanya tiga dari lima belas kasus pelanggaran HAM berat yang berhasil dibawa ke meja hijau, dan pemerkosaan Mei 1998 bukan salah satunya. Padahal, Presiden B.J. Habibie dalam autobiografinya Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (2006) secara eksplisit menyatakan telah menerima langsung kesaksian dari para relawan dan korban kekerasan seksual, yang kemudian mendorongnya membentuk Komnas Perempuan dan mengutuk kekerasan itu secara publik. Ia menyadari bahwa keadilan tidak bisa ditunda, dan negara harus bertanggung jawab.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
Penutup: Dari Luka yang Disangkal ke Ingatan yang Diperjuangkan
Sejarah Indonesia dalam versi resmi kerap tampil dalam narasi yang rapi, tertib, dan penuh kepastian. Namun, di balik konstruksi itu, terdapat kekacauan, luka, dan penderitaan yang disingkirkan. Tragedi 1965 dan kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 adalah dua peristiwa besar yang tak hanya ditandai oleh kebrutalan, tetapi juga oleh upaya sistematis negara untuk menafikan keberadaannya dalam memori kolektif bangsa.
Setelah pembantaian massal 1965, negara menyusun narasi tunggal tentang “penumpasan pengkhianatan G30S/PKI”, menjadikan militer sebagai pahlawan dan menghapus para korban dari sejarah resmi. Kisah tentang ratusan ribu orang yang dibunuh, dipenjara, dan disiksa tanpa proses hukum dikaburkan lewat kurikulum, film propaganda, dan monumen. Dalam narasi ini, kebenaran tidak hanya diredam, tetapi juga direkayasa secara simbolik.
Tiga dekade kemudian, pada Mei 1998, sejarah kekerasan berulang. Di tengah keruntuhan Orde Baru, kekerasan massal menyasar komunitas Tionghoa. Tubuh perempuan menjadi simbol dominasi politik—diperkosa, dibakar, disiksa—bukan karena siapa mereka secara personal, tetapi apa yang mereka wakili secara etnis dan sosial. Namun, seperti pada 1965, tragedi ini segera dibungkam. Negara membentuk tim investigasi, tapi tak satu pun pelaku diadili. Peristiwa itu tidak diajarkan di sekolah, tidak ada peringatan nasional, bahkan tidak ada pengakuan formal yang konsisten.
Elizabeth Drexler dalam Infrastructures of Impunity (2024) menjelaskan bahwa kekerasan negara di Indonesia bukan hanya soal tindakan fisik, tetapi dilestarikan melalui infrastruktur impunitas: hukum yang tumpul, institusi yang lemah, dan narasi yang selektif. Kekerasan terjadi tetapi dihapus dari buku teks, tidak disebut dalam peringatan resmi, dan tidak mendapat tempat dalam kurikulum pendidikan nasional. Dengan kata lain, kekerasan itu tidak selesai di jalanan, melainkan terus berlangsung dalam bentuk penyangkalan dan penghapusan ingatan.
Puncak dari penyangkalan ini terjadi pada 8 Juni 2025, ketika Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa “tidak ada bukti pemerkosaan massal pada Mei 1998.” Pernyataan ini bukan sekadar penolakan fakta, tetapi bentuk kekerasan simbolik yang membunuh kembali para korban yang telah dihancurkan oleh trauma dan pengabaian. Seperti dicatat Komnas HAM (2020), inilah bentuk nyata dari politik impunitas—negara yang tidak hanya gagal memberikan keadilan, tetapi secara aktif memproduksi kebisuan.
Apa yang terjadi bukan sekadar penghilangan data atau kejadian, melainkan produksi makna yang dimonopoli oleh negara. Sejarawan posmodern seperti Alun Munslow menegaskan bahwa sejarah bukanlah cermin objektif dari masa lalu, melainkan konstruksi naratif yang dibentuk oleh ideologi, posisi sosial, dan strategi wacana dari penulisnya (Munslow, 2006). Sejarah tidak ditemukan, tetapi diciptakan—melalui proses emplotment dan troping, yakni pemilihan fragmen, struktur, dan bahasa yang mengarahkan pemaknaan tertentu.
Menurut Munslow, sejarah bukan tentang “apa yang sebenarnya terjadi”, tetapi soal bagaimana peristiwa itu dinarasikan. Dalam konteks negara, sejarawan memilih dan menyusun fragmen-fragmen masa lalu dalam plot tertentu—romansa, tragedi, atau satire—yang pada akhirnya mengukuhkan posisi kekuasaan. Dalam sejarah Indonesia, terutama pasca-1965, yang terbentuk adalah emplotment hegemonik yang represif dan eksklusif terhadap suara korban.
Narasi resmi yang lahir dari proses ini selalu tampak sah dan tertutup. Namun kenyataan sejarah bersifat kompleks dan penuh luka. Munslow menyebutnya sebagai sublime history—sejarah yang tak dapat direpresentasikan sepenuhnya karena kedalaman traumanya. Ketika menulis sejarah hanya sebagai laporan kronologis “apa yang terjadi” dan menutup ruang tafsir dari perspektif korban, maka negara sedang menyingkirkan kemungkinan narasi yang lebih adil dan manusiawi.
Dalam kondisi semacam ini, kita membutuhkan sejarah yang jujur bukan untuk membuka luka lama, tetapi menyembuhkannya. Pendekatan dekonstruksionis seperti yang ditawarkan Munslow sangat relevan: kita harus menyadari bahwa setiap sejarah adalah representasi—dan karenanya, harus membuka ruang bagi representasi alternatif, khususnya dari mereka yang selama ini dibungkam.
Rekonsiliasi yang sejati hanya mungkin terjadi jika sejarah ditulis dari sudut pandang yang inklusif dan plural. Seperti dikemukakan John Roosa (2020), rekonsiliasi tidak mungkin terwujud tanpa pengakuan negara, penyebutan pelaku, dan restitusi bagi korban. Tanpa elemen-elemen itu, yang kita miliki hanyalah “rekonsiliasi semu” yang melanggengkan impunitas dan memperkuat dominasi narasi negara.
Luka sejarah bukan sekadar urusan masa lalu; ia adalah persoalan hari ini dan masa depan. Jika kita terus membiarkan negara menarasikan sejarah secara tunggal dan hegemonik, kita sedang menciptakan generasi yang buta terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Perjuangan melawan pelupaan adalah perjuangan untuk keadilan yang paling dasar.
Reformasi 1998 memang melahirkan harapan, tetapi juga mewariskan pengkhianatan—terutama terhadap para perempuan yang tubuhnya dijadikan medan perang simbolik. Mereka diperkosa bukan karena kesalahan pribadi, tetapi karena konstruksi sosial yang menjadikan mereka target.
Maka pertanyaannya kini bukan sekadar “apa yang terjadi”, tetapi: sejarah siapa yang sedang ditulis? Jika pemerkosaan massal Mei 1998 dan pembantaian 1965 terus dihapus dari ingatan sejarah nasional, maka yang kita rayakan di ulang tahun Indonesia yang ke-80 nanti bukanlah kebebasan, melainkan keberhasilan penyingkiran.
Melawan pelupaan bukan nostalgia akan luka lama, melainkan perlawanan terhadap kekuasaan yang terus berusaha menghapus jejak kekerasan yang dilakukannya.
Referensi
Budiawan. Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Suharto. Jakarta: ELSAM, 2004.
Drexler, Elizabeth. Infrastructures of Impunity: New Order Violence in Indonesia. Cornell University Press, 2024.
Fibiger, Mattias. Suharto’s Cold War: Indonesia, Southeast Asia, and the World. Oxford: Oxford University Press, 2023.
Habibie, B.J., Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi. Jakarta: THC Mandiri, 2006.
Heryanto, Ariel, “Rape, Race, and Reporting”, dalam Reformasi: Crisis and Change in Indonesia, ed. Arief Budiman dkk. Monash Asia Institute, 1999.
Heryanto, Ariel. State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging. London & New York: Routledge, 2005.
Komnas HAM. Merawat Ingatan Menjemput Keadilan: Ringkasan Eksekutif Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat. Jakarta: Komnas HAM, 2020.
Komnas Perempuan, Seri Dokumen Kunci: Laporan TGPF dan Relawan untuk Kemanusiaan, Jakarta: Komnas Perempuan, 2002.
Leksana, Grace Tjandra. Memory Culture of the Anti-Leftist Violence in Indonesia: Embedded Remembering. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2023.
Melvin, Jess. The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2018.
Munslow, Alun. Deconstructing History. 2nd ed. London & New York: Routledge, 2006.
Purdey, Jemma. Anti-Chinese Violence in Indonesia, 1996–1999. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2006.
Robinson, Geoffrey B. The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965–66. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2018.
Roosa, John, et al. Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65. Jakarta: ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), 2004.
Setijadi, Charlotte. Memories of Unbelonging: Ethnic Chinese Identity Politics in Post-Suharto Indonesia. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2023.
Wieringa, Saskia E. Sexual Politics in Indonesia. Houndmills, Basingstoke, Hampshire & New York: Palgrave Macmillan, 2002.
Wieringa, Saskia E., and Nursyahbani Katjasungkana. Propaganda and the Genocide in Indonesia: Imagining Victims and Perpetrators. London & New York: Routledge, 2019.
Dian Purba, alumni Pascasarjana Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada dan dosen di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung.