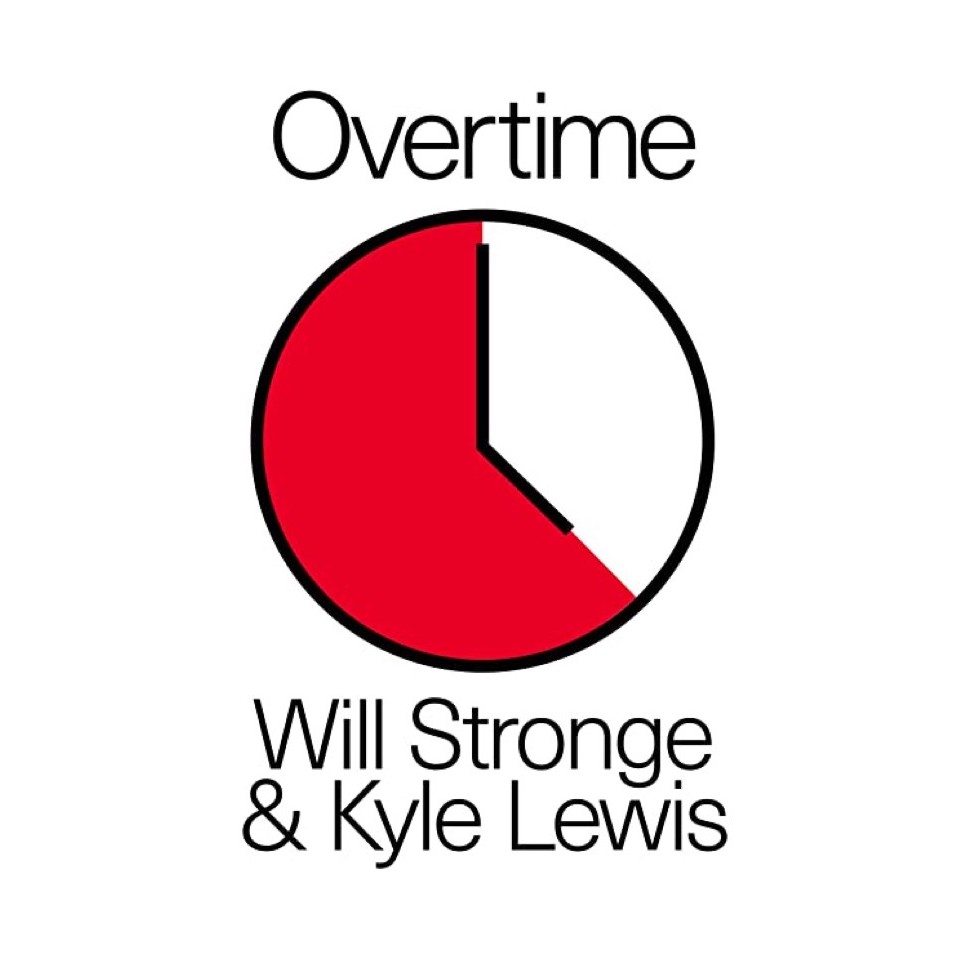Tulisan ini adalah tinjauan atas buku Overtime: Why We Need A Shorter Working Week, karya Kyle Lewis dan Will Stronge, terbitan Verso (2021, 162 hlm). Tinjauan ini menggunakan edisi epub dari buku tersebut.
KALIMAT kampanye dari sebuah serikat pekerja menyedot perhatian saya beberapa tahun lalu. Ia dikampanyekan di mana-mana, dari jalanan, media sosial, sampai dicetak di kaos yang sampai sekarang masih sering saya pakai. Kalimatnya sederhana dan mudah diingat karena berima:
“KURANGI REVISI PERBANYAK REKREASI”
Dibaca dengan cara lain, kalimat tersebut pada dasarnya adalah sebuah tuntutan: pengurangan jam kerja agar tersedia waktu lebih banyak untuk melakukan hal lain yang lebih menyenangkan. Tuntutan semacam ini tidak umum di Indonesia. Biasanya, serikat buruh, baik yang “merah” atau “kuning”, menuntut hal-hal terkait upah. Redaksionalnya bisa beragam, dari mulai yang umum seperti “naikkan upah minimum”, “hentikan politik upah murah”, hingga yang spesifik seperti “cabut regulasi x”, “batalkan peraturan y”, dan sebagainya.
Beberapa hari lalu, ketika berselancar di dunia maya, saya menemukan sebuah buku yang mengelaborasi lebih lanjut tuntutan tersebut. Buku itu berjudul Overtime: Why We Need A Shorter Working Week (selanjutnya disebut Overtime), terdiri dari lima bab plus pendahuluan, diterbitkan Verso pertengahan September lalu, ditulis oleh Kyle Lewis and Will Stronge, peneliti sebuah lembaga pemikir bernama Autonomy.
Overtime tak hanya mengulas soal dampak buruk dari jam kerja berlebih dan keuntungan dari pengurangan jam kerja–termasuk menjaga dan memperbaiki kesehatan mental–sebagaimana yang sudah banyak peneliti-peneliti lain lakukan. Lewis dan Stronge juga juga memberikan konteks: apa arti jam kerja dalam ekonomi kapitalis hingga menggali sejarah perjuangan serta implikasi politiknya. Tuntutan menurunkan waktu kerja bagi mereka merupakan “aspek sentral dari pembaruan politik sosialis” sebab tak hanya menguntungkan pekerja laki-laki, tapi juga pekerja perempuan yang memikul beban kerja ganda di masyarakat patriarkis dan lingkungan hidup.
Oleh karenanya, bagi Lewis dan Stronge yang saya sepakati, menuntut waktu kerja lebih pendek semestinya jadi agenda sentral gerakan pekerja hari ini.
Pengurangan jam kerja sebagai hasil perjuangan
Ketika fajar kapitalisme menyingsing di Inggris seperti bisul yang pecah dari kulit feodalisme, para petani penggarap yang tercerabut terlempar dalam situasi di mana tak bisa menjual apapun untuk bertahan hidup kecuali tenaga kerja. Satu-satunya tempat untuk menjajakan itu adalah pabrik-pabrik di kota industri awal mula. Mereka dihadapkan pada situasi yang sama sekali berbeda dari era feodalisme yang sangat bergantung pada cuaca untuk berproduksi, yaitu bekerja 60 jam per pekan atau rata-rata 12 jam jika bekerja lima hari pada 1800-an. Itu pun di pabrik yang “normal”. Di pabrik yang disebut “dark satanic mills“, para buruh harus pekerja sampai 16 jam dalam kondisi yang buruk.
Bahkan untuk ukuran zaman itu pun kondisi kerja tersebut sama sekali tak manusiawi. Wajar jika kemudian protes bermunculan dari balik dinding-dinding pabrik. Alih-alih berkurang karena kebaikan hati kapitalis, pengurangan jam kerja adalah buah dari perjuangan serikat buruh.
Namun keberhasilan pertama pengurangan jam kerja menjadi 8 jam per hari seperti yang lazim hari ini tak datang dari Inggris, tapi Melbourne, Australia, pada 1856. Tukang batu dan buruh bangunan di sana tercatat dalam sejarah sebagai kelompok pertama yang berhasil menekan bos untuk menerapkan jam kerja normal. Di Inggris, keberhasilan serupa baru terjadi pada 1889. Serikat GMB, yang salah satu pendirinya adalah anak Karl Marx, Eleanor Marx, berhasil merealisasikan tuntutan 8 jam kerja di sektor industri gas.
Delapan jam kerja perhari dan 48 jam per pekan menjadi praktik umum di Eropa sejak 1919 atau setahun setelah Perang Dunia I usai. Pada tahun itu pula International labour Organisation (ILO) terbentuk dengan tujuan utama juga memperjuangkan 8 jam kerja per hari.
Sejak itu, atau lebih dari satu abad lalu, durasi kerja secara umum di seluruh dunia tak pernah lagi berkurang. Ia membeku meski dunia telah berganti rupa dan segala teknologi canggih ditemukan.
Pada titik itulah Overtime memproblematisasi situasi kerja hari ini. Lewis dan Stronge menyebut saat ini sedang terjadi crisis of work ‘krisis kerja’, dan karenanya penting untuk memikirkan bagaimana cara keluar dari itu–yang tidak lain mempersingkat jam kerja sekali lagi. Beberapa krisis yang dimaksud seperti kerja lembur yang tak dibayar, ketimpangan yang semakin menganga–di mana upah riil menurun sementara kekayaan yang pindah ke pemilik kapital semakin besar, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat kerja jauh lebih panjang ketimbang sepuluh tahun lalu, termasuk jumlah pekerjaan tidak tetap yang terus meningkat tajam. Menurut mereka bahkan kisah mengerikan yang diuraikan Friedrich Engels dalam The Condition of the Working Class in England (1845) terjadi juga saat ini.
Lewis dan Stronge juga menyinggung bagaimana perkembangan teknologi tak serta merta mempersingkat waktu kerja sebagaimana yang diyakini ekonom John Maynard Keynes. Keynes optimistis bahwa karena inovasi dan teknologi, kekayaan umum semakin melimpah dan karenanya jam kerja akan semakin pendek. Dalam esai “Economic Possibilities For Our Grandchildren” yang pertama kali dipresentasikan pada 1928, ia bahkan bernubuat satu abad kemudian jam kerja hanya 15 jam per pekan.
Sebagian ramalan Keynes jauh dari kenyataan. Kekayaan memang semakin berlimpah, dibuktikan dengan PDB per kapita Eropa Barat dan Amerika Utara naik empat kali lipat antara awal 1930-akhir 2000-an. Tapi sama sekali tak ada tanda-tanda pengurangan jam kerja (2028 hanya tinggal 7 tahun lagi!). Lewis dan Stronge mengutip beberapa riset di Eropa Barat dan Amerika Utara yang menyatakan sebaliknya. Agar lebih kontekstual, saya mengutip laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun lalu yang menyebut rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas menghabiskan waktu 41,49 jam per pekan untuk kerja pada 2019. Jika dirinci, ada 29 persen yang masih bekerja lebih dari 48 jam per pekan. Tahun lalu rata-rata jam kerja memang berkurang 7 persen, tapi itu pun karena pandemi Covid-19 dan berimplikasi pada penurunan upah.
Kegagalan prediksi ini, kata Lewis dan Stronge, karena Keynes gagal mengurai duduk perkara. Bahwa pengurangan jam kerja yang terjadi berangsur pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 buka hasil dari hukum ekonomi, tapi upaya radikal dari serikat pekerja. Lewis dan Stronge mengatakan Keynes mengabaikan “politik distribusi” yang memungkinkan perubahan terjadi. “Tanpa tekanan–sering kali dari serikat pekerja–jam kerja per pekan masih bisa sekitar tujuh puluh jam per pekan,” tulis keduanya.
Dalam ekonomi kapitalis, panjang-pendeknya waktu kerja bukan soal inovasi terkini. Tak ada determinasi teknologi di sini. Teknologi yang dikuasai kapitalis, sebagaimana tampak dari fenomena ekonomi platform hari ini, justru semakin mengintensifikasi eksploitasi. Maka pemendekan waktu kerja adalah persoalan politik atau berada dalam lokus perjuangan kelas.
Jam kerja panjang kunci eksploitasi
“Mempertanyakan kenapa begitu banyak waktu kita dihabiskan oleh pekerjaan,” kata Lewis dan Stronge, “membantu kita memahami mengapa sepanjang sejarah semua pekerja telah berjuang melawan panjangnya minggu kerja.”
Untuk menjawab pertanyaan itu mereka kembali ke Karl Marx, orang Jerman yang mendedikasikan seumur hidupnya untuk pembebasan proletariat dan untuk itu membuat sebuah buku yang menguliti kapitalisme sampai ke akar-akarnya, Kapital (1867). Dalam buku itu Marx menguraikan perkara hari kerja dalam satu bab tersendiri (Jilid I, bab 10). Di sana Marx menjelaskan bagaimana hari kerja adalah kunci untuk memahami bagaimana eksploitasi kapitalisme bekerja.
Untuk memproduksi sesuatu, kapitalis butuh apa yang disebut kapital konstan (alat-alat produksi dan bahan baku) dan kapital variabel (tenaga kerja). Kapital konstan hanya dapat bekerja jika ia diberi “sentuhan” oleh kapital variabel. Membiarkan kapital konstan tak bekerja jelas menyebabkan kerugian. Kapitalis bahkan kemudian menerapkan sistem shift (sekarang umumnya satu hari dibagi tiga) agar mesin tetap berjalan tanpa putus.
Anggaplah bahwa tenaga kerja dibeli dan dijual sesuai dengan nilainya. Sebagaimana komoditas lain, nilai dari tenaga kerja juga dikondisikan oleh waktu kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Jadi, misalnya produksi tenaga kerja untuk sehari itu butuh 6 jam, maka seorang buruh hanya perlu 6 jam pula untuk bekerja kepada kapitalis. Katakanlah nilai dari 6 jam kerja itu adalah Rp100 ribu (harga/uang adalah ekspresi moneter dari nilai yang abstrak), maka si kapitalis harus membayar Rp100 ribu untuk dapat mempekerjakan seorang buruh. Pertukaran ini tampak adil di permukaan.
Masalahnya, kapitalis membeli tenaga kerja buruh untuk durasi hari, yang mana sepanjang 24 jam. Dengan begitu, dalam ilustrasi Marx, buruh tersebut bisa saja dipekerjakan untuk 7, 9, hingga 12 jam sesuai keinginan kapitalis. Kelebihan 1, 3, dan 6 jam kerja itulah yang disebut sebagai kerja surplus (surplus-labour), yang, singkatnya, berarti buruh bekerja tanpa dibayar. Sifat pertukaran pun kini jadi terang: tak adil sama sekali.
Maka, semakin panjang surplus-labour, semakin untung pulalah si kapitalis.
Batas dari penggunaan tenaga kerja buruh bukanlah waktu kerja yang diperlukan untuk memproduksi tenaga kerja tersebut (dalam hal ini berarti 6 jam kerja), melainkan batasan fisik dan moral. Dalam batasan fisik, tentu tak mungkin mempekerjakan buruh selama 24 jam meski sebanyak apa pun minuman energi yang mereka minum. Sementara keterbatasan moral terkait waktu yang dibutuhkan buruh untuk memuaskan keinginan intelektual dan sosialnya, kata Marx, yang tingkat dan jumlahnya dikondisikan oleh keadaan umum kemajuan sosial.
Oleh karena itu, kata Marx, hari kerja pada dasarnya bukanlah kuantitas yang konstan. Ia bisa berubah, dan memang berubah sebagaimana yang dibuktikan oleh sejarah. Satu bagiannya ditentukan oleh waktu kerja yang diperlukan untuk untuk memproduksi tenaga kerja, sementara jumlah totalnya bervariasi dengan penambahan surplus-labour tadi.
Lalu apa yang menjadi faktor penentu jam kerja yang pada dasarnya cair ini? Tidak lain, mengutip Marx, adalah “perjuangan antara modal kolektif yaitu kelas kapitalis dan kerja kolektif yaitu kelas pekerja.”
Kontradiksinya jadi tampak jelas, sekaligus menjawab pertanyaan awal mengapa perjuangan menuntut jam kerja lebih pendek itu konsisten terdapat dalam gerakan proletariat sepanjang zaman: sementara kapitalis butuh jam kerja panjang untuk memperbesar keuntungan dan menganggap setiap detik adalah potensi waktu produktif, bagi pekerja, waktu adalah fondasi yang dibutuhkan untuk mengaktualisasikan diri sendiri di luar dinding-dinding tempat kerja.
Untuk pembebasan perempuan dan lingkungan
Jam kerja yang panjang karena penguasaan atasnya berada di tangan kapitalis terutama merugikan perempuan dan lingkungan hidup. Maka pemendekan waktu kerja akan turut memperbaiki kehidupan keduanya. Demikianlah kira-kira tesis utama dari bab 3 dan 4 Overtime.
Untuk membahas posisi perempuan dalam kapitalisme, Lewis dan Stronge banyak mengutip dan mengafirmasi tesis-tesis dari sarjana feminis seperti Nancy Fraser dan Kathi Weeks.
Kapitalisme yang berkelindan dengan patriarki menghasilkan situasi di mana perempuan berperan sebagai tenaga kerja tak dibayar di rumah (kerja-kerja reproduktif seperti melahirkan dan membesarkan anak, mencuci, menyediakan masak, dan lain-lain). Kerja seperti ini tidak mengenal bunyi sirine yang biasanya menandakan waktu dimulai dan berakhirnya sif di pabrik-pabrik.
Kerja reproduktif bukan main beratnya. Sebuah survei menyebut seorang ibu menghabiskan waktu 97 jam per minggu hanya untuk mengurus anak. Namun, meski sangat menguras tenaga, kerja reproduktif tak dianggap kerja dalam skema kapitalisme, padahal itulah yang menopang sistem ini langgeng.
Ketika masuk ke pasar tenaga kerja, ketimbang dibebaskan dari kerja rumah tangga tersebut, para perempuan justru dipaksa untuk melakukan keduanya: ya kerja reproduktif, ya kerja produktif.
Mengulang argumen Silvia Federici, karena kerja reproduksi yang tak dibayar (bahkan tak diakui sebagai “kerja”) adalah manipulasi paling luas dan paling halus dari kapitalisme modern dan semestinya diakhiri, maka muncullah desakan untuk membayar tiap-tiap kerja tersebut (wages for housework) sebagaimana kerja produktif laki-laki di pabrik-pabrik (Center for Time Use at University College London memperkirakan jika kerja reproduksi sosial dinilai sebagaimana kerja produksi, ia akan setara 25 persen PDB Inggris, itu belum termasuk biaya bahan baku).
Namun menuntut upah atas kerja-kerja tersembunyi tersebut, bagi Federici yang dikutip Lewis dan Stronge, bukan berarti sekadar soal menerima kompensasi material (entah itu dari negara atau kapitalis). Ketika kerja reproduksi telah dianggap sebagai kerja dan ada kompensasi upah, maka perempuan dapat menolak sebagian di antaranya dan bahkan seluruhnya. Pada akhirnya ini kembali ke soal pertarungan untuk mengontrol waktu kerja, dan, seperti juga buruh laki-laki, ibu rumah tangga berhak mengaktualisasikan diri dengan prasyarat mengontrol penuh waktu mereka.
“Di sini,” kata Lewis dan Stronge, “perjuangan untuk waktu bebas bersinggungan dengan tuntutan feminis untuk revaluasi; perjuangan untuk mengontrol waktu sekaligus memperjuangkan kesetaraan gender.”
Dengan menyinggung peran perempuan dalam kapitalisme, Overtime hendak menukik lebih jauh soal proposal memperjuangkan jam kerja yang lebih pendek. Definisi “kerja” itu sendiri harus dirumuskan ulang dari sudut pandang feminis, bahwa ada kerja yang selama ini tak dibayar bahkan sekadar dianggap; dan tempat kerja itu tak hanya kantor, gudang atau pabrik, tapi juga rumah di mana eksploitasi juga terjadi dengan cara yang amat halus.
Kemudian soal aspek lingkungan. Lewis dan Stronge memulai bab 4 dengan fakta sederhana: bahwa kapitalisme dan visi pertumbuhan ekonominya tidak berkelanjutan (karena memproduksi efek rumah kaca, karbon, pemanasan global, dan lain-lain). Maka untuk meminimalisasi itu mereka mengusulkan gagasan yang yang dikampanyekan oleh aktivis ekologi Andre Gorz, degrowth, yang intinya adalah menurunkan pertumbuhan ekonomi alih-alih terus mengejarnya tanpa henti.
Dan salah satu komponen kunci dari degrowth adalah pengurangan waktu kerja. Lewis dan Stronge mengutip sebuah penelitian yang menyatakan jika jam kerja dikurangi hingga seperempatnya di 27 negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), jejak karbon kita dapat berkurang hingga 30 persen.
Gig Economy?
Saya membaca buku ini seperti membaca pamflet politik yang agitatif dalam definisi yang dijabarkan Vladimir Lenin di What Is To Be Done? (1902). Arsitek negara proletar pertama di dunia ini mengatakan untuk menjelaskan suatu persoalan seorang agitator akan menjabarkan soal “fakta paling mencolok dan paling banyak diketahui oleh pendengarnya.” Ia berbeda dengan propagandis yang “menyajikan banyak ide” namun tetap “sebagai satu kesatuan yang utuh.”
Contoh: ketika bicara tentang upah, seorang propagandis akan menjelaskan tentang “sifat kapitalistik dari krisis, penyebab krisis yang tak terhindarkan dalam masyarakat modern, perlunya transformasi masyarakat menjadi masyarakat sosialis, dll.” Sementara agitator, untuk masalah yang sama, umumnya akan menjelaskan “tentang kematian keluarga pekerja yang menganggur karena kelaparan, pemiskinan yang semakin meningkat, dll.” Ringkasnya ia menyulut sumbu kemarahan dengan cara-cara yang lebih sederhana ketimbang lewat penjelasan rumit dan berbelit.
Memang Overtime memberikan landasan teoretis dari waktu kerja dengan mengutip Marx, tapi secara umum ia tetap lebih bersifat agitatif. Di Overtime kita menemukan penjabaran bahwa pengurangan jam kerja bakal memberikan banyak keuntungan kepada para pekerja (dan lingkungan), alih-alih, misalnya, penjelasan tentang socially necessary labour-time‘waktu-kerja yang diperlukan secara sosial’.
Saya menduga ini memang soal pilihan penulis belaka. Masalahnya, karena menjelaskan “fakta paling mencolok dan paling banyak diketahui,” Overwork jadi meninggalkan beberapa celah cukup menganga.
Pertama, soal pengurangan waktu kerja dari sudut pandang kapitalis. Apakah kapitalis benar-benar dirugikan dari itu? Faktanya kita dapat dengan mudah menemukan artikel-artikel dengan judul seperti “bagaimana jam kerja pendek dapat menguntungkan perusahaan“, yang argumennya sederhana belaka: jika jam kerja pendek, maka kondisi fisik buruh akan lebih baik dan dengan demikian meningkatkan produktivitas. Atau, dengan hari kerja pendek, buruh akan lebih loyal terhadap perusahaan dan perusahaan pun akan berhemat mengeluarkan anggaran untuk perekrutan dan pelatihan tambahan.
Selain itu, semenjak berada dalam totalitas kapitalisme dan seluruh aspek kehidupan adalah ruang akumulasi modal, pengurangan jam kerja tidak berarti menghentikan eksploitasi terhadap individu pekerja. Artikel Muhammad Ridha di IndoProgress yang tayang pada 2014 lalu berjudul “Recreation: Merebut Kembali Kehidupan Harian Kita yang Terampas?” membicarakan soal itu. Ia mengutip Harry Cleaver (sales filsafat anti-kerja) dalam Reading Capital Politically yang mengatakan bahwa “kapital telah mencoba mengintegrasikan waktu ini (waktu non-kerja) ke dalam proses akumulasi” dengan memberi contoh bagaimana industri pariwisata semakin penting untuk menggerakkan ekonomi. Pun pengurangan waktu kerja dalam artikel itu disebut sebagai upaya “pengurangan konflik kelas.”
Ringkasnya, menurut Ridha, “alih-alih berkurangnya jam kerja itu sebagai kemenangan kelas pekerja, justru di sini memperlihatkan kemenangan mutlak kelas kapitalis.”
Bagaimana kapitalis membajak kemenangan pekerja inilah yang tidak ada dalam Overwork.
Di luar itu, tentu saya tidak sepakat dengan Ridha. Bagaimana mungkin membebaskan diri dari bekerja belasan jam dalam sehari dalam kondisi yang buruk tak bisa disebut kemenangan? Mengatakan bahwa pengurangan jam kerja merupakan “kemenangan kapitalis” sama seperti menolak tuntutan upah yang lebih tinggi hanya karena dengan itu daya beli kaum buruh semakin tinggi dan dapat lebih mungkin membeli produk-produk kapitalis.
Bahwa kemudian kelas pemodal memanfaatkan itu untuk akumulasi kapital, bagi saya, lebih merupakan reaksi atas kekalahan mereka mempertahankan waktu kerja yang panjang. Lagi pula, tak selamanya waktu luang itu untuk akumulasi modal. Buruh tetap bisa bebas dalam tindakan-tindakan spesifik, termasuk aktivitas-aktivitas yang mempercepat penggalian kubur kapitalisme seperti berperan aktif membesarkan serikat buruh atau partai Kiri (Saya sempat terlibat dalam keduanya, dan salah satu persoalan mengapa banyak anggota tak aktif adalah ketiadaan waktu luang).
Memperjuangkan jam kerja yang lebih pendek memang tuntutan reformis, seperti juga mendesak kenaikan upah atau jaminan sosial yang lebih luas. Hasil-hasil dari gerakan reformis itulah yang kita nikmati saat ini.
Kedua, soal jam kerja di dunia ekonomi pertunjukan (gig economy) dan kapitalisme platform (platform capitalism) yang dicirikan dengan durasi kontrak yang sangat pendek dan penggunaan platform yang mempertemukan antara pencari dan pemberi kerja secara digital. Tuntutan mengurangi jam kerja sangat kontekstual dan langsung pada pokok persoalan ketika dilihat dari kacamata manufaktur, tapi perlu penjelasan memutar–yang sayangnya luput dibahas–ketika dihadapkan pada jenis kerja baru yang muncul karena internet, misalnya pekerja lepas (freelancer) dan kurir antar jemput.
Kontrak seorang pekerja manufaktur akan mencakup jam kerja, jam istirahat, dan hal-hal terkait lain seperti cuti. Hal itu tak bakal ditemukan dalam pekerja gig sebab mereka dibayar ketika produk yang diminta selesai dikerjakan. Memang ada tenggat waktu tertentu untuk satu proyek, katakanlah satu pekan, namun perkara kapan persisnya pekerjaan itu dilakukan, entah itu pagi atau malam, semua diserahkan ke pekerja itu sendiri. Batas antara jam kerja dan jam-jam lain, yang sangat jelas dalam konteks manufaktur, menjadi kabur.
Ringkasnya, mereka mengalami apa yang disebut jam kerja fleksibel. Fleksibilitas semacam ini sebenarnya telah dimulai saat neoliberalisme muncul pada dekade 1970-an. Ia ditandai dengan runtuhnya status pekerja tetap dan digantikan dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Regulasi ketenagakerjaan dibuat selonggar mungkin sehingga ongkos produksi ditekan sedemikian rupa. Jika ada yang disebut “kemenangan mutlak kapitalis,” maka inilah bentuk nyatanya.
Memang, sama seperti pekerja pabrik, mereka juga mengalami jam kerja yang panjang. Tapi ini bukan karena instruksi langsung dari si pemberi kerja, melainkan karena beban kerja yang terlampau berat. Jam kerja yang panjang ada sebagai hasil dari beban kerja yang berat.
Laporan Viriya Singgih untuk Project Multatuli memberikan contoh yang baik. Untuk mengantar rata-rata 30 paket dalam sehari ia perlu bekerja selama 10 jam. Tentu si pemberi kerja tak memerintahkannya “Bekerjalah 10 jam agar saya cepat kaya dan naik haji!” tapi menetapkan bahwa untuk mendapatkan uang Rp100 ribu lebih sedikit pekerja harus mengantar sebanyak 40 paket. Atau, dalam kasus pengemudi aplikasi daring, satu-satunya cara untuk mendapatkan cukup uang adalah sebanyak-banyak mengambil penumpang. “Pengunciannya” terletak pada upah per potong yang minim, bukan seberapa lama diwajibkan bekerja.
Contoh lain kerap dialami para pekerja lepas. Mereka terjerat dalam lingkaran setan: karena bekerja untuk satu proyek tak bakal cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka solusinya–dimungkinkan karena jam kerja fleksibel–adalah mengambil proyek lain yang berarti memperpanjang jam kerja. Ini belum termasuk permintaan seenak jidat para pemberi kerja untuk, misalnya, revisi atau tiba-tiba mempercepat tenggat.
Singkatnya, selain perlu penjelasan memutar khusus untuk para pekerja jenis baru ini, tuntutan pengurangan waktu kerja juga harus dibarengi dengan tuntutan-tuntutan lain yang lebih konvensional seperti peningkatan upah (entah harian, per proyek, atau per paket) dan penurunan beban kerja.
Penutup
Jika dibuat sebagai medium untuk menjelaskan jam kerja dalam totalitas kapitalisme, buku ini bisa dibilang seadanya dan bahkan, sebagaimana saya tulis pada bagian sebelum ini, ada hal-hal yang semestinya dibahas karena sangat beririsan tapi absen. Sebetulnya cukup mengejutkan tak ada sama sekali pembahasan soal gig economy dan platform capitalism dalam buku ini semenjak dua tema itu semakin sering dibahas para sarjana di luar sana, praktiknya masif akhir-akhir ini terutama ketika pandemi menyerang dan keluhan para pekerjanya tak jauh-jauh dari overwork, plus usia penulis yang masih muda sebagaimana banyak pekerja di sektor tersebut.
Tapi, jika Overtime dimaksudkan sebagai kampanye agar pengurangan jam kerja semestinya menjadi isu sentral dalam gerakan rakyat pekerja, maka ia layak diperhitungkan. Bahasa yang sederhana membuat buku ini relatif bisa dibaca siapapun bahkan jika tidak akrab dengan teks-teks ekonomi-politik.
John McDonnell, anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh, mengatakan buku ini sangat berharga bukan hanya untuk memahami perjuangan pengurangan jam kerja, tapi juga, dan yang lebih penting, bagi mereka yang hendak terlibat di dalamnya. Ya, tepatnya bagi kita semua yang ingin mengurangi revisi agar bisa memperbanyak rekreasi.***
Rio Apinino adalah editor IndoPROGRESS