Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, Alumnus Hubungan Internasional UGM
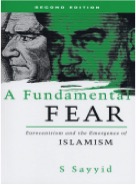
Judul Buku: A Fundamental Fear: Eurocentrism and The Emergence of Islamism
Penulis: Bobby S. Sayyid
Tempat Terbit: London
Penerbit: Zed Books
Tahun Terbit: 1997
Tebal: 179 halaman
–Ia tak bisa tampil sendiri; ia harus ditampilkan–
Edward Said
APA artinya menjadi gerakan Islam di abad ke-20? Memasuki dekade kedua di abad ke-20, dunia diramaikan oleh fenomena perubahan politik yang terjadi di berbagai negara Timur Tengah. Setelah beberapa dekade memerintah, pemerintahan otoriter Zine el-Abidine Ben Ali di Tunisia, Muammar Qadhafi di Libya, Hosni Mubarak di Mesir dan beberapa negara lain akhirnya tumbang. Gejolak demonstrasi massa memaksa mereka untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan transisi dan, sedikit demi sedikit, membawa proses demokratisasi. Kendati di beberapa negara seperti Mesir dan Syria proses transisi tersebut justru berakhir dengan kembalinya militer dan perang saudara berkepanjangan, Timur Tengah secara umum menghadapi proses transformasi yang mengajak para penstudi kawasan ini untuk memikirkan ulang asumsi-asumsi teoretik yang ada tentang Islam dan Politik di kawasan.
Perubahan politik yang kita kenal sebagai Arab Spring ini, pada perkembangannya, mengangkat kembali pembicaraan tentang isu yang selama ini banyak mewarnai kawasan Timur Tengah: gerakan ‘Islam Politik’ –kemudian kita sebut sebagai Islamisme. Proses transisi yang menyertai Arab Spring kemudian membawa banyak negara masuk pada proses demokratisasi yang selama ini dihambat oleh pemerintahan otoritarian yang berkuasa. Konsekuensinya, beberapa gerakan Islam di berbagai negara menemui momentumnnya.
Kita bisa melihat contoh bangkitnya gerakan Islam –yang membawa ‘Islamisme’ sebagai bagian penting dari diskursus politik ini— di beberapa negara: Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Turki. Di Mesir, Al-Ikhwan Al-Muslimun (kemudian kita sebut Ikhwan) yang menjadi oposisi selama lebih dari lima dekade memiliki kesempatan untuk tampil di pentas demokratisasi dengan membentuk Hizb al-Hurriyah wa al-‘Adalah atau Freedom and Justice Party (kemudian kita sebut FJP). Di Tunisia, Rachid Ghannouchi akhirnya kembali ke tanah airnya setelah dua dekade berada di pengasingan di London, dan mendirikan Partai An-Nahdha (Renaisans). Begitu juga dengan Omar Ghoul (Aljazair) dan aktivis-aktivis Islamis di berbagai negara, tak terkecuali Maroko yang berhasil menempatkan partai mereka sebagai pemenang Pemilu.
Secara mengejutkan, mereka berhasil merebut dukungan populer dan beberapa di antaranya (Mesir, Tunisia, Maroko) membentuk pemerintahan. Fenomena ini perlu menjadi sorotan: apa yang menyebabkan gerakan-gerakan Islamis tersebut mampu menjadi kekuatan ‘alternatif’ setelah rezim-rezim otoritarian runtuh di Timur Tengah? Bagaimana mereka bisa membangun tatanan politik yang baru di Timur Tengah dan bagaimana gagasan mereka berkontestasi di masing-masing negara?
Bobby Sayyid, ‘murid’ dari Ernesto Laclau yang kini merintis ‘Kajian Islam Kritis’ (Critical Muslim Studies)[1], mencoba untuk mengelaborasi beberapa problem tersebut dalam bukunya, A Fundamental Fear: Eurocentrism and The Emergence of Islamism (1997). Di buku tersebut Sayyid mencoba untuk membongkar, secara epistemologis, pandangan-pandangan keliru soal gerakan Islam dan memberikan sebuah cara pandang baru mengenai ‘bagaimana’ sebenarnya gerakan-gerakan Islam itu –mengartikulasikan identitasnya di tengah modernitas yang dikonstruksi di negara-negara Muslim.
Sayyid membagi bukunya ke dalam 5 Bagian. Di bagian pertama, ia menyajikan kritik terhadap pandangan banyak orang terhadap apa yang disebut sebagai ‘Fundamentalisme Islam’, sesuatu yang menurutnya keliru dan lebih bermakna peyoratif daripada menjelaskan esensi gerakan Islam. Bagian kedua kemudian memberikan kerangka teoretik untuk memahami Islamisme sebagai sebuah diskursus politik, yang ia bingkai melalui post-strukturalisme Laclau & Mouffe serta psikoanalisis Lacanian. Di bagian Ketiga, Sayyid mengurai kelahiran Islamisme dari runtuhnya ‘Khilafah Utsmaniyah’ pada tahun 1924 yang juga menandai runtuhnya hegemonic order di dunia Islam.
Sementara itu, bagian keempat, Sayyid bercerita mengenai persilangan jejak antara ‘Islamisme’ dan munculnya ‘modernitas’ yang ditandai oleh kolonialisme dan proses dekolonisasi pasca-Perang Dunia II. Bagian terakhir mencoba untuk merekonstruksi gambaran perjuangan gerakan-gerakan Islamis dalam melawan invisible empire di tatanan global yang ada, antara lain melalui perlawanan mereka terhadap rejim-rejim otoritarian yang muncul di negeri muslim serta kehadiran kekuatan politik global di antara mereka.

Memahami Islamisme: Dari Orientalisme ke ‘Politik Hegemoni’
Sayyid berangkat dari sebuah titik pemikiran yang cukup fenomenal di akhir tahun 1970an: Orientalisme. Istilah ini pertama kali dibahas secara mendalam oleh Edward Said (1978) dan kemudian membuka perdebatan tentang konstruksi-konstruksi berpikir ‘Barat’ dalam memandang Islam dan ‘dunia Timur’ pada umumnya. Diakui oleh Sayyid (h. 49), karya Edward Said tersebut membuka sebuah cara baru untuk mendekati studi-studi tentang Timur Tengah secara lebih kritis. Edward Said-lah yang pertama kali membongkar tradisi keilmuan tentang Timur Tengah di Barat, yang selama ini dikenal sebagai tradisi Orientalism.
Menurut Said, selama ini literatur-literatur tentang Timur Tengah tidaklah bebas dari ‘nilai-nilai tertentu’. Ia melihat, dari banyak tulisan, pidato hingga karya-karya sastra, ada semacam upaya untuk menampilkan wajah Timur untuk kepentingan Barat. ‘Timur’ ditampilkan sedemikian rupa, dengan deskripsi karikatural, esensialis, dan penuh tendensi, untuk memperlihatkan superiroritas Barat atas Timur. Ia senada dengan Foucault, yang melihat bahwa pada dasarnya teks-teks itu menampilkan hubungan kekuasaan tertentu yang jika dilacak akan bermuara pada narasi-narasi kolonial ‘Barat’ atas ‘Timur’. Dengan melacak relasi-relasi kuasa dari teks-teks kajian Orientalisme di Eropa dan Amerika Serikat, ia berkesimpulan bahwa kajian Orientalisme bukan sekadar kajian yang netral kepentingan; justru, di antara halusnya pembicaraan dalam kajian-kajian itu, orientalisme bertendensi untuk menengaskan superioritas Barat atas ‘Yang-Lain’ –dalam hal ini Islam.
Pandangan Said tentang Orientalisme inilah yang kemudian dikritik oleh Bobby Sayyid. Bagi Sayyid, Said telah terjebak pada ‘esensialisme’ –melakukan oversimplifikasi ‘Barat’ dan ‘Timur’ hanya pada satu cara pandang tertentu (h. 32). Sayyid membedakan dua jenis orientalism (h. 33-34): Weak Orientalism dan Strong Orientalism. Dalam Weak Orientalism, relasi Timur-Barat dipetakan sekadar sebagai relasi knowledge/power, yang melihat tekstualitas sebagai relasi ‘dominasi’ antara Europe dan The Other. Argumen-argumen yang dibangun oleh Said, baik dalam bukunya Orientalism maupun Covering Islam dibangun di atas analisis ini.
Kritik Sayyid sederhana: relasi Timur-Barat sebagai sesuatu yang saling bertentangan cenderung simplistis dan gagal membaca (1) beragamnya narasi ‘Barat’ tentang Islam (yang tidak semuanya diilhami oleh kajian Orientalisme) dan beragamnya dunia Islam; serta (2) bagaimana proses pembentukan ‘Timur’ oleh ‘Barat’ itu berlangsung (h. 34). Bagi Sayyid, cara pandang ini sangat terbatas karena melihat relasi-relasinya hanya pada sejarah dominasi Barat atas ‘Islam’ dan bukannya melihat bagaimana dominasi itu terjadi, ruang dominasinya seperti apa, hingga (yang sebetulnya penting sebagai implikasi kajian) bagaimana melawan narasi-narasi keliru tersebut.
Sementara itu, cara pandang kedua, strong orientalism, analisis diarahkan pada ‘bagaimana Barat membentuk Timur. Dengan cara pandang ini, relasi keduanya dilihat sebagai konstruksi identitas yang adversarial, di mana ‘eksistensi’ Barat hanya dimungkinkan melalui ‘negasi’ atas Timur (Ia melihat ini pada analisis Turner dan Derrida). Sayyid melihat analisis Said gagal melihat kemungkinan untuk melihat orientalisme dalam perspektif ini, yang mana memungkinkan kita untuk melihat bagaimana ‘Timur’ dikonstruksikan oleh ‘Barat’ sebagai sebuah identitas. Dalam pembacaan Sayyid, kerangka ‘weak orientalism’ seperti ditampilkan oleh Said justru terjebak pada pembacaan simplistis ketika ia mulai membaca Islam, karena orientalisme mengimplikasikan adanya totalitas pembacaan terhadap Islam. Mungkinkah kita membaca ‘Islam’ tanpa menjadi orientalis jika kita berada di luar tatanan yang bernama ‘Islam’ tersebut?
Dari kritiknya terhadap Said tersebut, Sayyid beranjak ke sebuah pemahaman yang lebih kritis tentang ‘Islam’. Mengacu pada analisis Hamid el-Zien dan Talal Asad yang melihat Islam dalam perspektif antropologi kritis, ia melihat bahwa analisis mengenai Islam pada dasarnya tidak bersifat monolitik. Ada pluralitas tersendiri dalam pembacaan tentang Islam (p. 37). Dari sini, Sayyid melihat bahwa identitas ‘Islam’ ditentukan oleh artikulasinya (p. 42). Oleh sebab itulah, ia menolak istilah ‘fundamentalis’ yang menurutnya sangat esensialis dalam memandang Islam (h. 43).
Dengan menggunakan cara pandang diskursif sebagaimana dikembangkan oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe (1986), Sayyid lebih suka menggunakan istilah ‘Islamisme’ yang ia definisikan sebagai diskursus politik yang menjadikan Islam sebagai ‘penanda utama’ artikulasinya (h. 47). Cara pandang diskursif menjadi penting untuk membedakan banyaknya artikulasi-artikulasi gerakan Islam, dari yang menggunakan politik parlementer sebagai jalan maupun yang berorientasi kekerasan (lihat Ayoob, 2000). Mereka bisa saja bersimpang jalan dalam strategi dan pendekatan politik yang mereka anut, tetapi pada dasarnya diikat oleh satu ‘penanda’ yang sama, yaitu ‘Islam sebagai tujuan dan cita-cita utama’ (dalam bahasa Ikhwanul Muslimin: “Al-Islam Huwal Hal”).
Sayyid mengembangkan argumennya secara lebih lanjut dengan meminjam konsepsi Jacques Lacan tentang master signifier (penanda-utama). Berdasarkan pendekatan ini, Sayyid melihat para Islamis sebetulnya berupaya untuk menjadikan ‘Islam’ sebagai pusat dari tatanan politik yang ada (political order), atau menjadikan ‘Islam’ sebagai master signifier yang mengikat setiap artikulasi umatnya (h. 47). Dalam psikoanalisis yang berakar pada pemikiran Jacques Lacan, master signifier adalah “penanda yang tidak memiliki konten yang ditandai, tetapi mempertemukan semua makna yang terbentuk dari segala macam bentuk artikulasi” (Wood, 2012). Islamisme menjadikan ‘Islam’ sebagai penanda utama dengan menjadikannya cita-cita utama dari segala macam bentuk artikulasi yang menggunakan Islam baik dalam konten maupun repertoar (lihat Ismail, 2006). Pada titik inilah Sayyid kemudian masuk pada jargon ‘Islam is the solution’ atau ‘penerapan syariah Islam’ –yang digelorakan oleh beberapa gerakan Islam seperti Ikhwanul Muslimin atau Hizb at-Tahrir— (h. 49).
Dari sinilah muncul ‘antagonisme’, karena Islam yang mengikat setiap artikulasi dan political order tersebut tidak dapat diterima oleh para non-Islamis. Bagi para Islamis, ‘Islam’ harus menjadi penanda utama dari setiap artikulasi yang membentuk tatanan politik yang ada di semua tingkatan. Namun, sebaliknya, bagi non-Islamis, master signifier itu pasti bukan Islam, karena ia tidak dapat menempati posisi ‘pusat’ (centre) dari tatanan politik yang sedang terbangun. Pada titik inilah antagonisme terbentuk. Artikulasi Islamis berporos pada gagasan tentang ‘Islam’ sebagai penanda utama dan direspons oleh kalangan-kalangan yang tidak menghendaki hal tersebut. Namun demikian, artikulasi tersebut tidak pernah berada pada maknanya yang ‘total’. Selalu ada dinamika, konflik, dan kontestasi yang kemudian menyertai proses antagonisme tersebut, yang membuat ‘Islamisme’ sebetulnya juga bukan merupakan sesuatu yang bersifat final.
Kemalisme dan Terbentuknya ‘Islamisme’
Beranjak dari analisis tersebut, Sayyid berpindah pada pertanyaan: bagaimana ‘Islam’ menjadi master signifier bagi kaum Islamis? Sayyid melakukan rekonstruksi terhadap kemunculan Islamisme dengan melacaknya Khilafah Islamiyah. Sayyid mengilustrasikan Khilafah tidak hanya sebagai ‘tatanan politik’ di dunia muslim, tetapi juga sebagai pengikat dari artikulasi politik Muslim (h. 52). Khalifah ‘menetapkan’ makna Islam dan memberikan umat Islam rasa ‘nyaman’ yang memungkinkan tatanan politik terbentuk atas nama Islam (h. 53).
Dengan melihat diskursus tentang Islam and The State, ia berpendapat bahwa ‘Islam’ menjadi master signifier ketika era Khilafah Usmaniyah (h. 53-54). Khilafah mengikat dan menetapkan makna ‘Islam’ dalam sebuah institusi yang baku, menjadikan setiap artikulasi di luar itu menjadi tidak mungkin. Ini yang ia sebut Khilafah sebagai Lawgiver, pembentuk tatanan hukum yang membekukan semua artikulasi politik dan menetapkan simbol-simbolnya (h. 55).
Namun, pada tahun 1920an, muncul krisis. Ketika itu, Turki baru saja kalah dalam Perang Dunia I dan muncul ketidakpuasan terhadap Khilafah. Di saat yang bersamaan, muncul gerakan ‘Turki Muda’ dengan Mustafa Kemal Pasha sebagai lokomotif utamanya, yang segera mengajukan tuntutan politik. Krisis memuncak, dan akhirnya Khalifah dijatuhkan di tahun 1924, menempatkan Mustafa Kemal sebagai penguasa baru. Ia segera melakukan abolisi Khilafah dengan memperkenalkan 4 paket modernisasi di Turki: (1) sekularisme; (2) nasionalisme; (3) modernitas; dan (4) westernisasi. Keempat tema inilah yang menggantikan ‘ideologi’ Kekhilafahan yang didasarkan pada norma-norma Islam yang baku secara politik (p. 63-69).
Dari sinilah Sayyid masuk pada analisisnya tentang kemunculan ‘Islamisme’. Ketika Kemal Attaturk mengabolisi Khilafah dan menggantinya dengan sistem negara sekuler, makna Islam tersebut ‘buyar’. Empat paket modernisasi Kemalis ‘mengambangkan’ makna Islam dan membuat ikatan baku yang menjadikan diskursus ‘Khilafah’ hegemonik selama beberapa abad kemudian menjadi runtuh (h. 57). Dengan cara ini, Kemalisme membawa diskursus hegemonik lama ke dalam krisis dan membangun tatanan politik baru, dengan referensi pada modernisasi. Diskursus ini ditopang oleh politik de-Islamisasi yang dilakukan baik dengan mengganti institusi-institusi lama menjadi institusi baru yang sarat dengan modernitas, serta melalui jalur kebudayaan dengan menggantikan bahasa ‘Arab’ dengan ‘Turki’. Dengan kata lain, Kemalisme berhasil menjadikan diskursusnya tentang Islam yang menjadikan ‘makna Islam’ harus sesuai dengan kerangka ‘modernitas’ sebagai diskursus hegemonik di Mesir (h. 59).
Namun, Sayyid tidak berfokus hanya pada Kemalisme di Turki. Ia juga melihat bahwa kecenderungan serupa di beberapa negara pasca-kolonial, di mana discourse tentang modernitas menjadi sangat signifikan untuk melihat relasi ‘Islam and the State’ atau Islam dalam Political Order yang ada (h. 69-70). Kecenderungan serupa diperlihatkan oleh rezim Pahlevi di Iran atau Quasi-Khalifah di Arab Saudi yang menempatkan Islam sebagai ‘agama’ yang asing dengan politik. Rezim Pahlevi menjadikan nilai-nilai Pra-Islam sebagai penanda utama rezim politik yang ia bangun di Iran, dengan melekatkan diskursus ‘Aryanisme’ sebagai identitas kultural-politik di Iran (h. 71). Di sisi lain, rezim Quasi-Khilafah di Arab Saudi dan negara-negara Teluk menempatkan ‘Kerajaan’ dan sistem politik yang meniru (mimetic) konsep-konsep negara-Bangsa ‘modern’ yang dibingkai dengan slogan-slogan Khalifah (h. 72-73).
Di dua bentuk ‘negara’ tersebut, Islam memang diterapkan sebagai basis legitimasi negara (dengan apparatus ulama, simbol syariah, dan sejenisnya), tapi tidak mengikat diskursus lain semisal pembangunan ekonomi atau politik yang dikelola dengan rujukan modern (h. 72). Arab Saudi atau negara-negara teluk menggunakan konsep ‘kebangsaan’ sebagai dasar negara dan sistem ekonomi yang sangat kapitalistik. Dengan demikian, diskursus hegemoniknya tetap modernitas. Kita bisa membaca satu hal penting dari analisis Sayyid ini: ‘Islam’ sebagai diskursus hegemonik, dalam kasus Kemalisme, digantikan oleh modernitas.
Dalam perspektif Kemalis, ‘Islam digambarkan sebagai sesuatu yang anti-modernitas dan harus dimodernisasi. Islam menjadi ‘objek’ dari proses modernisasi (h. 87). Negara-negara quasi-khalifah, terutama Arab Saudi yang diilhami oleh revolusi Wahabi di abad ke-18, menjadikan ‘tradisi’ sebagai sesuatu yang harus diganti dengan dasar-dasar ‘Islam’ yang modern. Namun, berbeda dari Kemal, modernitas yang dipahami oleh Muhammad ibn Abdul Wahab justru berporos pada negara-bangsa (yang ia pahami sebagai Ke-Arab-an dengan batas-batas yang ditentukan Ibn Saud) dan diisi dengan konten-konten pemurnian Islam. Pemurnian, sebagaimana diulas oleh Fazlur Rahman, kemudian menjadi trademark penting dari reformisme Islam di awal abad ke-20 (lihat Rahman, 1972).
Dari Turki, Sayyid beralih ke Iran. Diskursus hegemonik yang ditandai oleh Aryanisme Pahlavi bertahan sampai, kira-kira, ketika Ayatollah Khomeini dan pengikut Syiah-nya menggetarkan dunia dengan revolusi di Iran. Di sini muncul hal lain yang menarik: Khomeini memberikan sebuah cara pandang baru yang mencoba untuk mendislokasi hegemonic discourse yang ada. Dengan revolusi Islam-nya, ia bertujuan tidak untuk menciptakan dialog dengan ‘Barat’. Ia bertujuan mengganti tatanan politik yang ada dengan Islam (h. 89). Khomeini, dengan demikian, melakukan proses peminggiran (de-centering) terhadap diskursus Aryanisme modern yang dibangun oleh Pahlavi sebagai satu-satunya discourse yang mungkin menjadi political order di negara-negara Muslim.
Kerangka Islam yang ditampilkan oleh Khomeini inilah yang menjadi ciri khas Islamisme: bertujuan untuk decentring the west dari posisinya sebagai diskursus hegemonik, dan menjadikan Islam sebagai ‘penanda utama’ dari tatanan politik yang ada di ruang negaranya. Dengan kata lain, Islamisme merupakan alternatif dari diskursus tentang ‘modernitas’ yang selama ini dipandang sebagai satu-satunya jalan menuju kemajuan (h. 88-90). Gambaran yang ditunjukkan oleh Khomeini terhadap ‘Barat’ ini. dalam beberapa hal, muncul dalam gambaran Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb (pemikir terkemuka Ikhwanul Muslimin) tentang ‘Islam’ dan ‘Barat’. Jika Khomeini melihatnya dalam bentuk anti-modernitas, al-Banna dan Qutb melihatnya dalam diskursus anti-Kolonialisme yang memosisikan ‘Islam’ sebagai kekuatan alternatif terhadap imperialisme Barat melalui Kolonialisme. Slogan-slogan al-Banna dan Qutb ini kemudian banyak direpetisi sebagai jargon oleh gerakan-gerakan Islam, terutama yang menginduk pada Ikhwanul Muslimin.
Islamisme vis-à-vis Eurosentrisme: Pertarungan Identitas
Dengan cara pandang ini, Sayyid kemudian memahami Islamisme merupakan sebuah artikulasi identitas. Islamisme adalah model penggunaan Islam secara ‘politis’ yang bertujuan untuk membangun diskursus alternatif terhadap hegemoni ‘proyek modernisasi’ yang ditanamkan melalui persilangan kolonialisme dan otoritarianisme di negeri-negeri Muslim. Dengan menggunakan teori-teori tentang ‘diskursus hegemonik’ dan ‘penanda utama’ yang dipinjam dari studi post-strukturalisme, Sayyid mencoba untuk membaca Islamism sebagai sebuah artikulasi yang ‘menantang’ modernitas sebagai konstruksi dominan tentang Islam.
Pembacaan atas Islamisme sebagai kritik terhadap modernitas yang Eurosentris, sebagai konsekuensinya mengantarkan kita pada sebuah pembacaan kritis terhadap kajian-kajian tentang Islam dan Islam Politik dengan menghadapkannya pada klaim bahwa ‘modernitas’ –yang menjadi penanda utama dari artikulasi politik non-Islamis di negeri-negeri Muslim harus berkiblat pada ‘Barat’ dan ‘Eropa’ –atau kerap disebut Eurocentrism. Sayyid melihat bahwa ‘modernitas’ tidaklah tunggal; ada beragam (multiple) jenis dari modernitas karena artikulasinya di medan sosial masing-masing berbeda. Sayyid, pada titik ini, sampai pada analisis bahwa Islamisme, disadari atau tidak, juga memiliki akar pada multiplisitas modernitas tersebut.
Menurut Sayyid, setelah secara panjang lebar mengupas kajian Sami Zubaida tentang Khomeini, ia berkesimpulan bahwa Islamisme pada dasarnya juga punya akar dari ‘modernitas’ karena titik berangkatnya dari respons terhadap proses modernisasi di dunia Muslim (h. 99) Namun, berbeda dengan Zubaida, ia melihat bahwa Islamisme pada dasarnya mengartikulasikan konsepsi tentang ‘modernitas’ yang berbeda dengan modernitas ‘Eropa’ –yang ditopang oleh asumsi bahwa ‘The West leads the Rest’ (h. 101-102). Itulah yang kemudian disebut sebagai ‘Eurosentrisme’. Konsepsi ini menjadi sasaran utama dari Islamisme, karena ia punya tendensi diskursif untuk mengeksklusi Islamisme sebagai sesuatu ‘yang-lain’, yang harus mau dipimpin oleh ‘Eropa’ (h. 106). Dominasi Eurocentrism dalam kajian dan praksis politik di negeri-negeri Muslim telah meletakkan Islam berada di bawah subordinasi diskursus-diskursus yang berakar pada identitas ke-Eropa-an.
Dengan demikian, disimpulkan oleh Sayyid bahwa Islamisme hadir sebagai manifestasi ‘kontra-diskursus’ terhadap modernitas yang Eurosentris. Dengan menantang Eurocentrism, Islamism bukan lagi menjadi sebuah ‘cara untuk kembali ke masa lampau’ sebagaimana dituding oleh Bernard Lewis atau Bassam Tibi’. Islamism berarti sebuah upaya untuk mendisartikulasi modernitas dari klaim-klaim unggulan lain dan menempatkan adanya kemungkinan lain tentang masa depan dunia (h. 111). Islamisme, dengan demikian, adalah sebuah proyek hegemoni yang ingin ‘menantang’ universalisme Eropa dan menyatakan bahwa dirinya bukanlah pusat dari segala macam bentuk artikulasi –dan dengan demikian melakukan apa yang disebut Sayyid sebagai ‘provinsialisasi Eropa’ (h. 129).
Tantangan ini sangat terkait dengan pengalaman interaksi dunia Islam dan ‘Barat’ yang selama ini sarat dengan praktik kolonialisme, imperialism, dan westernisasi yang kemudian ‘mencaplok’ makna Islam dalam kategori mereka sejak Khilafah diabolisi (lihat al-Attas, 1978). Pertentangan identitas yang selama ini terjadi, semenjak munculnya Khilafah, kemudian menyebabkan Islamisme menjadi diskursus yang sangat resisten terhadap ‘Barat’ –terlihat dari retorika-retorika yang ditampilkan oleh Khomeini dan, pada beberapa titik, Hasan Al-Banna. Hal yang membuat Islam menjadi ‘istimewa’, menurut Sayyid, adalah dimensi ‘itness’ –walaupun Islam bisa digunakan untuk melegitimasi berbagai diskursus yang ada, ia tidak melebur. Islam tetap akan menjadi Islam, yang kemudian memberi energi politik bagi artikulasi identitas yang merujuk pada narasi yang ada di dalamnya (dalam hal ini, Islamisme).
Pada konteks yang lebih luas, munculnya Islamisme sebagai sebuah diskursus dalam politik global kemudian digarisbawahi oleh Sayyid dengan munculnya ‘globalisasi’. Dari sisi ekonomi, globalisasi menegaskan ‘hegemoni Eropa’ dengan pembagian ‘Utara-Selatan’ (h. 132). Dalam perspektif pasca-kolonial, terlebih dalam relasinya dengan dunia Islam, proses-proses globalisasi yang terbentuk secara historis telah menegaskan superioritas ‘Eropa’. Upaya inilah yang kemudian coba ditantang oleh Islamisme dan diskursus-diskursus ‘subaltern’ yang lain (h. 134-135). Islamisme, secara lebih spesifik, mengartikulasikan satu imajinasi tentang Umma yang berada di level global, yang kemudian menjadi alternatif atas ‘universalisme Eropa’. Konsepsi ini kemudian menyebabkan kontestasi identitas antara ‘Islam’ dan ‘Barat’ terjadi secara terus-menerus dan dinamis.
Sebagai kesimpulan, Sayyid menyatakan bahwa Islamisme merupakan sebuah diskursus politik yang muncul akibat melemahnya narasi hegemonik ‘Kemalisme’ dan varian-variannya yang serupa di negara lain. Islamisme mendapatkan kesempatan untuk membangun proyek hegemoni baru ketika (1) narasi hegemonik yang ada mengalami krisis dan (2) sebagai diskursus ia punya kredibilitas tertentu. Mengutip Laclau & Mouffe (1986), kredibilitas sebuah diskursus tertentu bukan terletak pada persepsi ‘eksternal’ terhadap dirinya, melainkan pada kemampuannya membangun chain of equivalence (rantai persamaan) dan membangun tatanan politik baru. Islam punya kekuatan sejauh ia punya retorika yang mampu mengikat semua diskursus lain—atau menjadi Master Signifier bagi para pengikutnya.
Kendati tidak disebut secara spesifik oleh Sayyid, manifestasi dari kebangkitan Islamisme ini dapat dilihat dari munculnya Islamisme setelah Arab Spring. Dengan kekuatan ‘retorika’ yang ia miliki, gerakan Islam seperti Ikhwan di Mesir berhasil membangun aliansi dengan kelompok Islam yang lain dan membentuk pemerintahan pada tahun 2012. Namun, proyek hegemoni mereka berantakan setelah chain of equivalence yang mereka bangun buyar oleh kehadiran militer (lihat Umar, 2013). Namun, sebagaimana dicatat oleh Sayyid, Islamisme tidak bisa didomestifikasi hanya pada batas ‘negara-bangsa’. Karena referensi ‘universal’ yang ada di dalamnya, ia melintasi batas-batas kebangsaan itu –yang manifestasinya bisa kita lihat pada jejaring kompleks Islamisme dari Timur Tengah, Asia Tenggara, hingga Eropa dan Amerika (lihat Rubin, 2010).
Kendati demikian, Sayyid mengakui bahwa Islamisme tidaklah tunggal. Ada beragam artikulasi yang merujuk pada Islamisme dan semuanya punya ragam tuntutan dan bentuk pengorganisasian. Namun, bukan berarti Islamisme tidak punya koherensi. Dalam titik tertentu, ketika diskursus lain mengancam, mereka justru mampu menjalin titik temu dan menjadikan diskursusnya kuat (h. 159-160). Inilah sebabnya, bagi Sayyid, Islam bisa menjadi satu penanda tentang ‘harapan’ tentang tatanan yang lebih baik (h. 160).
Islamisme dalam ‘Kajian Islam Kritis’: Catatan dan Evaluasi
Buku yang ditulis oleh Bobby Sayyid ini sedikit banyak telah membuka pandangan kita mengenai gerakan-gerakan Islam kontemporer yang kini sedang mengambil momentum demokratisasi di Timur Tengah. Selama ini, gerakan-gerakan Islam, baik yang moderat seperti AKP di Turki atau Jihadi di Mesir dan Afghanistan, lebih sering diposisikan secara politis daripada akademis. Mereka dipandang, dengan cara pandang yang sangat orientalis, sebagai ‘ancaman’ terhadap tata dunia yang beradab dan dicita-citakan Amerika Serikat. Pandangan ini, jika mengikuti kritik Sayyid, jelas terjerembab pada jebakan esensialisme dan dalam beberapa hal terlampau menggeneralisasi persoalan (lihat juga Ramadan, 2013).
Menarik jika kita membaca analisis Mahmood Mamdani (2002), juga tulisan singkat Tariq Ramadan (2010) tentang ‘Good Muslim and Bad Muslims’. Analisisnya tentang ‘Muslim’ setelah tragedi 9/11 memperlihatkan bahwa diskursus tentang Islam telah dibelah oleh kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat: ada profil ‘good muslims’, yang diceritakan sebagai muslim yang moderat, cinta-damai, dan tidak berorientasi kekerasan (jihad), sementara ada orang-orang lain yang dicitrakan sebagai ‘Bad Muslims’ yang menggelorakan jihad, menentang imperialism Amerika Serikat, atau kritis terhadap Barat.
Sebagai konsekuensinya, kita bisa melihat citraan mengenai ‘Islam Moderat’ mendominasi berbagai diskursus dari akademik hingga politik luar negeri. Upaya beberapa negara seperti Indonesia, yang melihat Islam Moderat sebagai sesuatu yang mesti dibawa keluar, mencerminkan adanya diskursus hegemonik yang melihat Islam harus sesuai dengan kerangka modernitas, dan mengeksklusi cara pandang lain yang menentangnya. Cara pandang semacam ini, dalam beberapa hal, mengartikulasikan Islam sebagai representasi kepentingan tertentu dan justru mengeksklusi representasi kepentingan lain yang juga ingin merujuk pada Islam.
Melalui buku ini, Sayyid telah memperingatkan kita secara dini untuk tidak terjerembab terlalu dalam pada jebakan cara pandang tersebut. Dalam kajian Islam di Indonesia, hal ini memiliki relevansi tertentu. Beberapa kajian, seperti Abuza (2007) atau catatan-catatan Sidney Jones, cenderung melihat ‘Islamisme’ dalam diskursus keamanan yang membuat Islamisme cenderung diposisikan sebagai ‘tersangka’ dalam berbagai kasus terror (tanpa memahami tuntutannya, sementara kajian lain terlalu menyoroti tuntutan Syariatnya sehingga jatuh pada overgeneralisasi dalam membaca Islamisme (lihat Nashir, 2013). Kajian Islam Kritis yang dibangun oleh Sayyid berkontribusi untuk menyelamatkan kajian Islam dari jebakan esensialisme yang hanya melihat ‘Islamisme’ hanya sebagai sebuah upaya untuk kembali pada peradaban primitif yang sekarang sudah tidak relevan lagi. Islamisme harus dipandang secara lebih kompleks dengan memahami konstruksi identitas di dalamnya.
Namun, tentu saja ada kelemahan yang terkandung di dalamnya. Saya mencatat ada tiga kelemahan mendasar dari kajian Sayyid. Pertama, kajian Sayyid tentang ‘Islamisme’ melupakan basis material dari tuntutan dan diskursus yang ditampilkan oleh gerakan-gerakan Islam yang jadi sasaran kajiannya. Karena terfokus membaca Islamisme dalam konteks diskursus dan identitas, Sayyid lupa bahwa gerakan-gerakan Islam menyuarakan diskursus dan tuntutannya tersebut dalam masyarakat yang hidup. Akibatnya, pembacaan Sayyid tentang ‘Islamisme’ dan kritik terhadap ‘Eurosentrisme’ juga terjerembab pada overgeneralisasi. Ada konteks sosial dan ekonomi-politik yang juga penting untuk menjelaskan, misalnya, mengapa Ikhwanul Muslimin gagal mempertahankan legitimasi politiknya di Mesir atau mengapa ‘ekonomi Islam’ –pada level intelektual—sampai saat ini belum bisa menghadirkan alternatif yang konkret atas krisis ekonomi global. Kajian-kajian yang berorientasi pada analisis Sosiologi Sejarah atau Ekonomi-Politik bisa berkontribusi untuk menutup gap ini.
Kedua, kajian Sayyid juga belum banyak membantu kita untuk memahami transformasi gerakan Islam yang saat ini terjadi, baik di tingkat lokal, nasional, ataupun global. Hal ini bisa jadi karena penjelasannya yang sangat teoretis atau karena konteks waktu yang terbatas (buku ini ditulis pada tahun 1997), Sayyid belum banyak memberi penjelasan, misalnya, bagaimana gerakan-gerakan Islamis setelah dekade 2000-an justru membangun dialog kritis dengan peradaban ‘Barat’ dan menerima sebagian konsepnya (hal ini bisa dilacak, misalnya, pada pemikiran Rachid Ghannouchi, Recep Erdogan, dan dalam beberapa hal Anwar Ibrahim). Walaupun Sayyid mengakui, di bagian akhir tulisannya, bahwa ‘Islamisme tidak tunggal’, kita bisa bertanya: bagaimana relasi generasi ‘post-Islamis’ –jika boleh meminjam istilah ini— dengan modernitas yang muncul dari Barat? Apakah ada ‘transformasi identitas’ atau justru ini hanyalah dinamika yang bisa memunculkan diskursus politik baru? Pertanyaan ini belum terjawab di buku Sayyid ini dan menuntut penjabaran lebih lanjut.[2]
Ketiga, sebagaimana dikritik dalam dua book review dari Beverley Milton-Edwards (1998) dan Muzaffar Iqbal (1999), buku ini akan susah dipahami oleh pembaca yang tidak mengetahui kajian-kajian Derrida, Laclau, Mouffe, Lacan, atau Zizek. Selain sangat filosofis, yang menyebabkan ia susah diterjemahkan dalam kerangka metodologis tertentu untuk menganalisis isu-isu yang bersifat lebih ‘grass-root’. Di sisi lain, yang lebih teoretis, kajian ini juga terlampau menekankan pada bentuk ‘Islamisme’ sebagai identitas politik dan kurang mengelaborasi dimensi-dimensi praksisnya, semisal retorika, jaringan yang mereka bangun di ranah lokal, serta sikap-sikap ‘Islamis’ terhadap isu kontemporer, semisal kapitalisme. Sehingga, alih-alih menggali sisi ‘progresif’ dari Gerakan Islam yang terlihat dari keterlibatannya dengan isu-isu di tingkat lokal, buku ini justru terkesan ‘menarik batas’ antara Islamisme dan ‘Eurosentrisme’ sebagai sebuah diskursus. Walaupun memang ada kontestasi di antara keduanya, persinggungan di level yang lebih praksis tetap penting untuk diajukan untuk memahami gerakan Islam kontemporer.
Kendati demikian, Buku setebal 178 halaman ini sangat menarik untuk dibaca oleh para penstudi dan aktivis yang mendalami gerakan politik Islam kontemporer. Dengan bahasa Inggris yang mudah dibaca dan sistematis, buku ini cukup memberikan ‘alternatif’ atas kajian-kajian Islam yang selama ini didominasi oleh orientalisme dan stigma negatif atas Gerakan Islam. Dengan beberapa kelemahan yang telah saya urai di atas, beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam kajian lanjutan adalah: dengan memahami Gerakan Islamis sebagai manifestasi perlawanan terhadap ‘Eurosentrisme’, mungkinkah mereka berubah menjadi progresif dengan memperjuangkan kelas yang tertindas dalam skema politik global? Bukankah mereka yang selama ini tertindas oleh kapitalisme global adalah juga umat Islam? Jawaban yang lebih komprehensif atas pertanyaan ini akan membantu kita untuk membangun jembatan yang pernah putus antara ‘Islamisme’ dan ‘Sosialisme’, wa bil khusus di Indonesia.
Referensi Tambahan
Abuza, Z. (2007). Political Islam and Violence in Indonesia. London and New York: Routledge.
Ayoob, M. (2000). The Many Faces of Political Islam. Chicago: University of Michigan Press.
al-Attas, SMN. (1978). Islam and Secularism. Kuala Lumpur: ABIM and ISTAC.
Ismail, S. (2006). Rethinking Islamist Politics: Culture, Politics, and Islamism. London: Zed Books.
Laclau, E & Mouffe, C. (1986). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical and Democratic Politics. London: Verso.
Mamdani, M. (2002). “Good Muslim, Bad Muslim: A Political Perspective of Culture and Terrorism” American Anthropologist 56.
Rahman, F. (1972). Islam. Chicago: Chicago University Press.
Ramadan, T. (2010). “Good Muslim, Bad Muslim” New Statesman, 12 February. Retrieved from http://www.newstatesman.com/religion/2010/02/muslim-religious-moderation
Ramadan, T. (2013). Beyond Islamism. Retrieved from Tariq’s personal website, http://www.tariqramadan.com/
Ramadan, T. (2012). Islam and Arab Awakening. Oxford: Oxford University Press.
Rubin, B. (2010). The Muslim Brotherhood: The Organization and Policies of a Global Islamist Movement. Basingstoke: Palgrave.
Said, E. (1978). Orientalism. New York: Penguin
Umar, ARM. (2013). “Perjuangan Hegemonik Ikhwanul Muslimin setelah Kejatuhan Hosni Mubarak” Unpublished Bachelor Thesis. Yogyakarta: Department of International Relations, Universitas Gadjah Mada.
Wood, K. (2012). Zizek: A Reader’s Guide. London and New York: Wiley.
[1] Istilah Critical Muslim Studies diperkenalkan oleh Center of Study and Investigation for Decolonial Dialogue yang bermarkas di Barcelona, Spanyol, yang secara rutin menggelar Summer School bertajuk “Critical Muslim Studies: Decolonial Struggles and Liberation Theologies”. Di samping itu, Sayyid juga aktif mendirikan dan menjadi editor utama dari ReOrient: Journal of Critical Muslim Studies di samping juga mengajar satu subjek tentang Critical Muslim Studies and Postcolonialism di University of Leeds, tempatnya mengajar. Dalam beberapa hal, beberapa pemikir Muslim seperti Tariq Ramadan (cucu dari Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin) dan Farid Essack juga mulai mengadopsi perspektif ini dalam beberapa kajian mereka, walaupun dengan titik tolak yang berbeda.
[2] Beberapa penjelasan tentang hal ini banyak didiskusikan di buku Sayyid terbaru: Recalling the Caliphate: Decolonization and World Order (London: Hurst, 2014). Buku tersebut menyajikan beberapa dialog antara ‘Islam’ dan konsep-konsep yang berakar dari tradisi Eropa, seperti Demokrasi, Sekularisme, dan Reflektivisme. Lihat review atas buku ini, yang ditulis oleh Darren Atkinson, di http://www.e-ir.info/2014/10/23/review-recalling-the-caliphate-decolonization-and-world-order/






