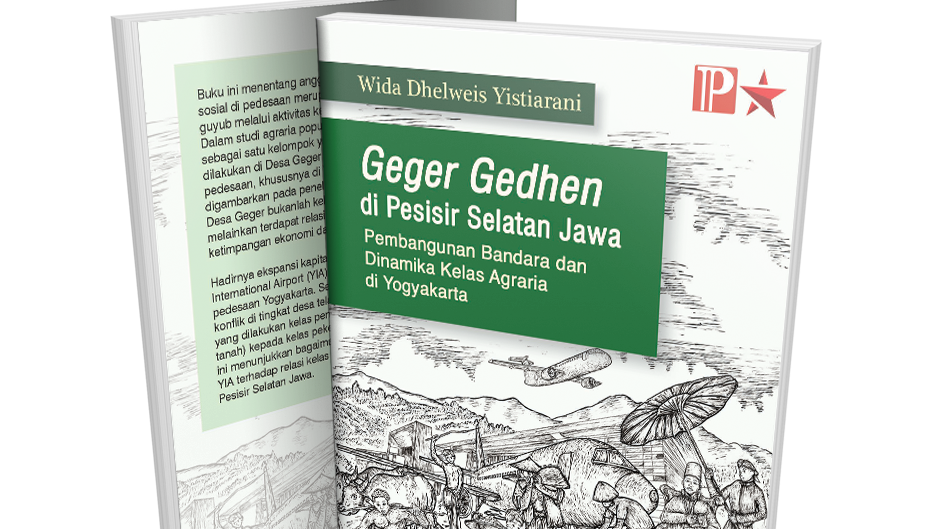Foto: Penerbit Independen
Judul Buku: Geger Gedhen di Pesisir Selatan Jawa: Pembangunan Bandara dan Dinamika Kelas Agararia di Yogyakarta
Penulis: Wida Dhelweis Yistiarani
Penerbit: Independen dan IISRE
Tahun Terbit: 2024
SELAMA INI kajian agraria di Indonesia didominasi oleh perspektif populisme yang memandang desa sebagai lokus kehidupan yang tenteram, guyub, atau gemah ripah loh jinawi. Petani yang menjadi pekerjaan mayoritas masyarakat desa akhirnya dipahami dalam kesatuan kelas yang homogen. Bukan hanya itu, produksi yang dilakukan oleh petani juga dianggap semata-mata hanya untuk menunjang kebutuhan hidup (subsisten), sekalipun gempuran pasar makin merangsek ke seluruh penjuru dunia. Dalam konteks itulah buku Geger Gedhen di Pesisir Selatan Jawa: Pembangunan Bandara dan Dinamika Kelas Agraria di Yogyakarta terbit. Buku yang ditulis oleh Wida Dhelweis Yistiarani ini berusaha mematahkan perspektif tersebut dengan menyoroti ketimpangan dan eksploitasi dalam struktur sosial perdesaan.
Melalui penelitian di Desa Geger (bukan nama sebenarnya) yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, ia menegaskan bahwa gambaran cerah dalam kehidupan desa sungguh naif mengingat petani hidup dalam diferensiasi sosial yang akut. Diferensiasi itu tak terelakkan mengingat sebagian besar alat produksi yang ada di sana dikuasai oleh petani kapitalis atau tuan tanah. Dengan kondisi seperti ini, produksi yang dijalankan oleh petani tentu tak bercorak subsisten, melainkan demi kebutuhan pasar.
Diferensiasi itu makin dalam ketika pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) dilaksanakan.
Konteks Penelitian
Wida mengawali bukunya dengan menceritakan bahwa pembangunan YIA merupakan salah satu proyek infrastruktur pada masa pemerintahan Joko Widodo yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Proyek ini menghabiskan dana sebesar Rp12 trilliun, disokong oleh Angkasa Pura I dan II serta Republik Rakyat Cina (RRC) dengan keikutsertaan Indonesia dalam proyek Belt and Road Initiatives (hal 2-3).
Bandara baru dibuat dengan alasan Adisutjipto yang berada di Sleman sudah kelebihan kapasitas, apalagi itu dimiliki Angkatan Udara sehingga tak pantas dijadikan komersial. Namun sebenarnya juga ada dorongan kapitalisasi dalam pembangunan itu: memuluskan akses wisatawan ke Yogyakarta. Hal ini tampak dari pengembangan objek-objek wisata yang terintegrasi dengan jalur bandara. Dorongan kapital itu terasa jauh lebih penting walau harus menggusur setidaknya lima desa di Kulon Progo.
Wida menjelaskan kasus tersebut melalui konsep accumulation by dispossession (ABD) yang dicetuskan oleh ahli geografi David Harvey. Konsep yang merupakan pengembangan dari akumulasi primitif Marx tersebut menjelaskan karakter kapitalisme kontemporer yang mencari ruang-ruang baru demi terhindar dari krisis. ABD menunjukkan bagaimana kapital melakukan perampasan dan privatisasi alat produksi dari produsen yang dilegitimasi oleh regulasi negara dan dieksponensi oleh kapital finansial. Dampaknya ialah tercerainya produsen dari alat produksi yang mendorong penciptaan pasar tenaga kerja dan mendesak petani kecil hidup dalam kondisi yang semakin rentan (hal 12).
Setelah melakukan eksplorasi atas pembangunan infrastruktur Indonesia, Wida kemudian memaparkan tata penguasaan tanah di Yogyakarta yang problematis sejak diberlakukannya UU Keistimewaan Yogyakarta pada 2012. UU tersebut mengakibatkan sultan sebagai gubernur dan adipati sebagai wakil gubernur memiliki hak penguasaan dan kontrol atas sebagian besar tanah di Yogyakarta. Tanah milik Kasultanan (Sultan Ground) meliputi Kota Yogyakarta, Sleman, Gunungkidul, Bantul, dan area pegunungan Kulon Progo; sementara tanah Kadipaten (Pakualam Ground) meliputi pesisir selatan Kulon Progo. Dengan pengaturan tanah yang demikian, agaknya ada kongkalikong antara penguasa lokal dengan pusat untuk memuluskan proyek YIA.
Konteks tersebut menjadi titik awal bagi Wida untuk mengisi kekosongan dalam penelitian sebelumnya yang masih menggunakan pisau analisis populis (perubahan penghidupan, konflik agraria, ekspansi geografis, dan degradasi lingkungan). Melalui empat pertanyaan ekonomi politik Bernstein yang meliputi siapa memiliki apa; siapa melakukan apa; siapa mendapatkan apa; dan apa yang mereka lakukan dari apa yang mereka dapatkan, Wida membedah kontur dinamika kelas pra-pembangunan YIA dan bagaimana transformasi konfigurasi tersebut pasca-pembangunan.
Dinamika Kelas Pra-pembangunan YIA
Konstruksi atas dinamika kelas di Desa Geger dilakukan oleh Wida dengan menggunakan konsep lokasi kelas. Lokasi kelas yang dimaksud di sini bukan hanya merujuk pada relasi produksi, melainkan juga bagaimana sejarah dan aspek sosial dari lokasi keberadaan mereka. Dengan lain kata, lokasi kelas dilihat “berdasarkan relasi rumah tangga dalam kepemilikan properti dan relasi produksi, serta bagaimana posisi mereka di dalam pasar tenaga kerja dan aktivitas non-pertanian” (hal 34).
Berpegang pada konsep tersebut, Wida melihat bahwa posisi teratas dalam struktur kelas di Desa Geger ditempati oleh kelas penguasa. Kelas ini memiliki kemampuan untuk mempekerjakan orang lain menjadi buruh di lahan pertanian mereka atau melakukan pemerasan hasil usaha petani lain melalui sistem bagi hasil. Mereka biasanya memiliki penguasaan alat produksi berupa sawah dan tegalan sebesar 0,8 ha hingga 1 ha. Kepemilikan lahan yang luas itu membuat mereka dapat menjual seluruh hasil panen untuk kemudian diinvestasikan kembali dalam wujud alat-alat produksi substansial.
Ada empat kategori dalam kelas ini: pertama, petani kapitalis menguasai alat produksi luas sehingga memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola aktivitas produksi pertanian. Mereka masih sesekali ikut menjalankan aktivitas pertanian walau hanya untuk mengisi waktu luang dan bukan untuk menambah pemasukan. Kegiatannya misalkan menyiangi rumput atau nyemprot. Dalam menjalankan aktivitas produksi pertanian, mereka mempekerjakan buruh dan bukan melalui bagi hasil.
Kedua, petani kapitalis birokrat yang memiliki penguasaan atas tanah bengkok karena posisinya sebagai birokrat desa. Mereka memiliki kemampuan mengatur alat produksi dengan menyerahkan seluruh atau sebagian dari tanah bengkok yang akan digarap oleh warga melalui sistem bagi hasil. Dorongan untuk menarik dukungan warga dan rasa kasihan pada warga yang tidak memiliki lahan garapan menjadi alasan mengapa mereka melakukan bagi hasil. Namun, ada dari mereka yang menyisakan sebagian kecil lahan untuk digarap sendiri dan terkadang mempekerjakan buruh.
Ketiga, petani kapitalis yang memiliki dan mengelola lahan yang luas, tapi juga memiliki pekerjaan profesional yang didukung oleh jenjang pendidikan yang tinggi. Karena itu, mereka dilibatkan dalam urusan pemerintahan desa dan mendapatkan status sosial yang tinggi dalam struktur sosial desa.
Keempat, tuan tanah yang memberikan hak kontrol lahan kepada orang lain melalui sistem bagi hasil. Hak kontrol itu diberikan mengingat mereka tidak memiliki kapabilitas untuk memobilisasi tenaga kerja. Mereka hampir tak terlibat atau bahkan sama sekali tak terlibat dalam aktivitas produksi pertanian. Kendati demikian, mereka tetap mendapatkan keuntungan dari surplus yang diperoleh atas hasil kerja petani yang menggarap lahannya. Mereka hanya menyediakan lahan dan sama sekali tak urun modal pembibitan, pupuk, pengairan, dsb.
Posisi kelas selanjutnya ditempati oleh Produsen Komoditas Kecil (PKK). Mereka adalah kelas yang tidak masuk dalam pasar tenaga kerja dan mengerjakan lahan dengan luasan kurang dari 0,8 hektare yang diperoleh melalui hak milik ataupun hak kontrol. Dalam mengelola lahan pertanian, mereka mengandalkan tenaga kerja keluarga dan terkadang juga buruh. Hasil produksi mereka bisa dibilang cukup untuk membiayai produksi selanjutnya, walau tak bisa untuk melakukan akumulasi (reproduksi sederhana). Dalam hal ini, mereka menjual sedikit hasil panen dari sawah dan menjual seluruh hasil panen dari tegalan.
Secara internal, mereka mengalami diferensiasi yang bisa dilihat dalam dua aspek: dinamika penguasaan alat produksi dan pemenuhan kebutuhan. Berdasarkan pada dinamika penguasaan alat produksi, ada PKK substansial dan PKK formal. PKK substansial adalah mereka yang memiliki lahan yang cukup luas (0,4 ha), sehingga memberinya kemampuan untuk melakukan produksi tanpa menjual tenaga kerja atau melakukan bagi hasil dengan tuan tanah. Sedangkan PKK formal adalah mereka yang tidak memiliki lahan tapi mampu mengontrol lahan dalam jumlah yang cukup luas (0,4 ha) yang diperoleh melalui sistem bagi hasil.
Dengan semua itu, mereka dapat memenuhi kebutuhan substansial tanpa menjual tenaga kerja, kendati tentu hasil produksinya lebih rendah ketimbang PKK substansial. Namun, mereka tetap berada dalam kondisi yang rentan mengingat relasinya dengan tuan tanah. Di sini mereka mengurus semua pembiayaan proses produksi (pembibitan, pemupukan, pengairan, dsb) tanpa bantuan sedikitpun dari tuan tanah. Namun, hasil produksi dari usaha mereka dinikmati secara rata dengan tuan tanah (50:50).
Sementara berdasarkan pemenuhan kebutuhan, ada PKK klasik dan aspiring. PKK klasik adalah mereka yang sudah merasa cukup dengan kehidupan subsitensi sehingga tak ada keinginan untuk menjual tenaga kerjanya. Ini berbanding terbalik dengan PKK aspiring yang bersedia menjual tenaga kerjanya atau menambah penguasaan lahan demi mencapai kebutuhan di luar garis subsistensi seperti, membiayai kuliah anak atau membeli lahan pertanian.
Posisi selanjutnya, posisi terbawah, ditempati oleh kelas pekerja. Seperti halnya dengan PKK, kelas ini tidaklah homogen. Kelas ini terbagi menjadi tiga, yakni semi-proletar, proletar, dan fully-pledge proletar. Kelas semi-proletar adalah kelas yang masih memiliki lahan walau hanya secuil (kurang dari 0,3 ha). Penguasaan lahan yang kecil itu membuat mereka tetap menjual tenaga kerjanya sepanjang tahun. Bagaimanapun, mengelola lahan yang kecil tak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di bawahnya ada kelas proletar, yaitu kelas yang memiliki alat produksi paling kecil yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Selanjutnya adalah kelas buruh sepenuhnya atau biasa disebut dengan fully-pledge proletar. Kelas ini tidak memiliki alat produksi sama sekali sehingga menggantungkan hidup sepenuhnya dengan menjual tenaga kerja Kendati demikian, jumlah mereka di Desa Geger jauh lebih kecil ketimbang dua kelas pekerja lainnya.
Dengan memahami konfigurasi lokasi kelas tersebut, kita tak akan kaget melihat relasi kelas yang terbentuk dalam dunia keseharian petani di Desa Geger. Wida menjelaskan bagaimana kepentingan antara kelas penguasa dan kelas pekerja yang tak pernah bertemu serta posisi kelas pekerja yang kerap dirugikan dalam kohesi sosial. Ini bisa dilihat dari cerita tuan tanah yang menolak PKK formal dan petani kelas pekerja saat mengusulkan bagi hasil menjadi 60:40 dalam kegiatan rembuk desa. Di kegiatan yang sama pula, ada cerita petani kelas pekerja pemilik traktor yang ditolak oleh setiap kelas ketika meminta kenaikan upah.
Namun, bukan berarti kelas pekerja hanya bergeming. Perlawanan sehari-hari hampir sudah menjadi bagian dari kehidupan kelas pekerja meski tak pernah frontal seperti membicarakan petani kapitalis secara diam-diam dan duduk berteduh atau tidur ketika petani kapitalis sedang tidak mengawasinya bekerja.
Dinamika Kelas Pasca Pembangunan YIA
Proyek pembangunan YIA pada tahun 2018 telah menggusur 32 ha sawah, 108 ha tegalan, 22, 8 ha tanah pekarangan, 113, 6 ha tanah pasir, dan dua pedukuhan (dusun) di Desa Geger. Penggusuran ini memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap setiap kelas petani. Di sinilah pentingnya kita melihat lokasi kelas pasca pembangunan YIA.
Adalah petani kapitalis yang cenderung survive dan tidak terlalu terdampak oleh penggusuran itu. Luas tanah mereka memang berkurang, tetapi mereka mendapatkan uang ganti rugi besar yang kemudian digunakan untuk membangun usaha sewa kos-kosan atau kontrakan. Mereka pun tetap melanjutkan usaha tani dengan mempekerjakan buruh atau menyewakan lahan dengan sistem bagi hasil.
Namun, variabel yang dipakai untuk mengidentifikasi petani kapitalis pasca pembangunan YIA tentu berubah. Hal ini mengingat banyak lahan sawah atau tegalan yang tergusur. Dalam hal ini, hanya perangkat desa yang memiliki lahan seluas 1 ha atau lebih yang merupakan tanah bengkok. Petani kapitalis atau tuan tanah lain yang kini lahannya kurang dari 1 hektare lebih menggantungkan pendapatan dari usaha sewa kos-kosan atau kontrakan.
Berbeda dengan kelas penguasa, kelas PKK cenderung terdampak pembangunan YIA. Sebab, lahan yang tak cukup luas memaksa mereka untuk menerima ganti rugi yang tak besar. Karena itu, ada beberapa kasus di mana mereka justru menjadi bagian dari kelas pekerja. Ini menunjukkan ada watak ganda dari PKK: ia bisa melakukan perluasan reproduksi ketika akumulasinya berjalan lancar sekaligus bisa mengalami himpitan reproduksi ketika berada pada masa-masa sulit yang mendorongnya menjadi petani semi-proletar atau bahkan tunakisma (hal 65).
Menariknya, ada beberapa kasus di mana kelas pekerja justru berubah status menjadi PKK. Di sini uang ganti rugi yang mereka peroleh dimanfaatkan untuk menyewa lahan tegalan di desa lain dan membuka usaha non-pertanian (hal 62 dan 64). Namun, Wida tetap setia untuk melihat perubahan lokasi tersebut berdasarkan pada relasi produksi dan tanah, bukan pada gaji atau privilese sebagaimana pandangan kelas dari weberian.
Kendati demikian, tak berarti bahwa posisi kelas pekerja yang lain akan mengalami mobilitas vertikal juga. Mereka justru menjadi kelas yang paling terdampak oleh pembangunan YIA. Ini mengingat kelas pekerja tak mendapatkan ganti rugi sepeser pun karena memang tak memiliki lahan. Banyak dari mereka yang akhirnya menjadi pengangguran mengingat lahan sawah dan tegalan berkurang secara drastis. Kalaupun beruntung, mereka hanya bisa menjadi petani semi-proletar atau buruh di di luar pertanian.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
Tanggapan
Buku ini patut diacungi jempol karena berusaha menawarkan perspektif baru dalam kajian agraria. Di sini konflik agraria tak lagi dilihat semata-mata sebagai petani vis a vis melawan korporasi atau penguasa, melainkan bahwa konflik itu juga terjadi dalam kelompok petani yang termanifestasi pada diferensiasi kelas. Wida pun menjelaskan bahwa petani terbagi dalam kelas penguasa, kelas PKK, dan kelas pekerja dalam studinya di Desa Geger yang terkena imbas pembangunan YIA.
Namun, bukan berarti apa yang dituliskan oleh Wida tanpa kekurangan. Saya akan memberikan beberapa tanggapan.
Pertama, Wida seharusnya menjelaskan secara detail bagaimana respons dari tiap-tiap kelas petani ketika lahan mereka akan digusur untuk pembangunan YIA. Sepanjang saya membaca buku ini, penjelasan tersebut hanya muncul dalam bab penutup yang menegaskan bahwa kebanyakan petani kapitalis dan tuan tanah cenderung netral ketika ada rencana pembangunan, karena akan mendapatkan ganti rugi yang besar, sementara PKK dan kelas pekerja adalah kelompok yang paling getol melawan rencana tersebut karena sumber utama penghidupan mereka berasal dari pertanian. Pembahasan yang cukup detail mengenai hal tersebut cukup penting karena buku ini hendak menyorot dinamika kelas dalam konteks konflik agraria.
Kedua, Wida seharusnya menjelaskan perubahan lokasi kelas pasca-pembangunan bandara secara lebih kritis. Ketika menjelaskan perubahan lokasi kelas dari kelas PKK menjadi kelas pekerja dan sebaliknya, Wida tak cukup menjelaskan mengapa kedua lokasi kelas tersebut bisa berubah. Ia hanya menunjukkan kasus-kasus yang ada dan menerokanya melalui relasi produksi dan relasi tanah.
Terakhir, Wida tak mendemonstrasikan sama sekali jumlah petani dari tiap-tiap kelas secara statistik. Absennya dimensi ini membuat ketimpangan kelas yang ingin ditunjukkan oleh Wida terasa kurang. Pembahasan ini sangat penting karena menunjukkan pembaca secara kuantitatif bahwa desa bukanlah struktur yang egaliter karena terdapat diferensiasi sosial.
Kendati demikian, apa yang dilakukan oleh Wida patut diapresiasi karena menggulirkan bola wacana baru dalam kajian agraria di Indonesia. Dengan ini, peneliti agraria di Indonesia dapat meneruskan dan mengembangkan dari apa yang telah dilakukan Wida.
Muhammad Akbar Darojat Restu Putra adalah mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya