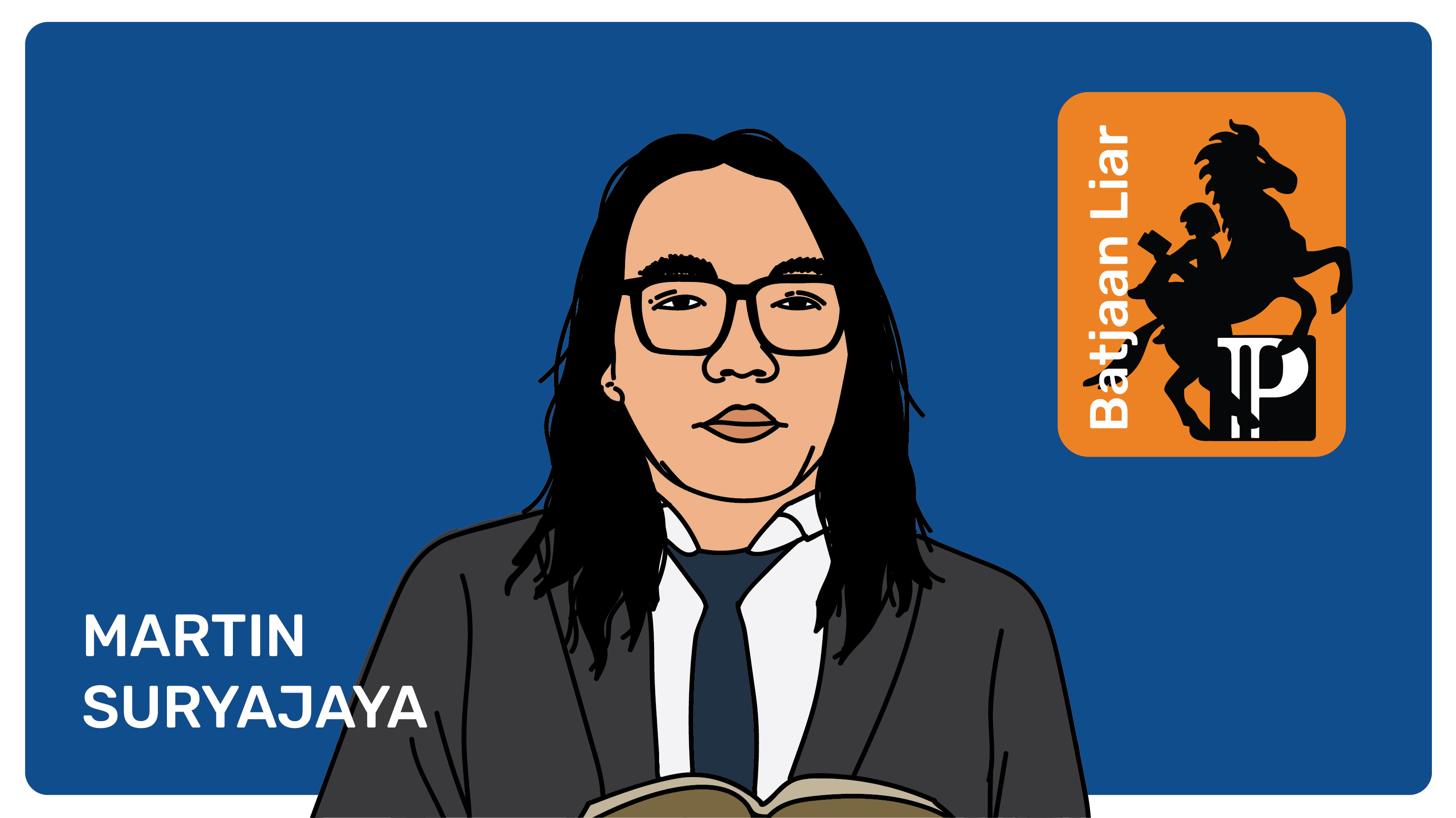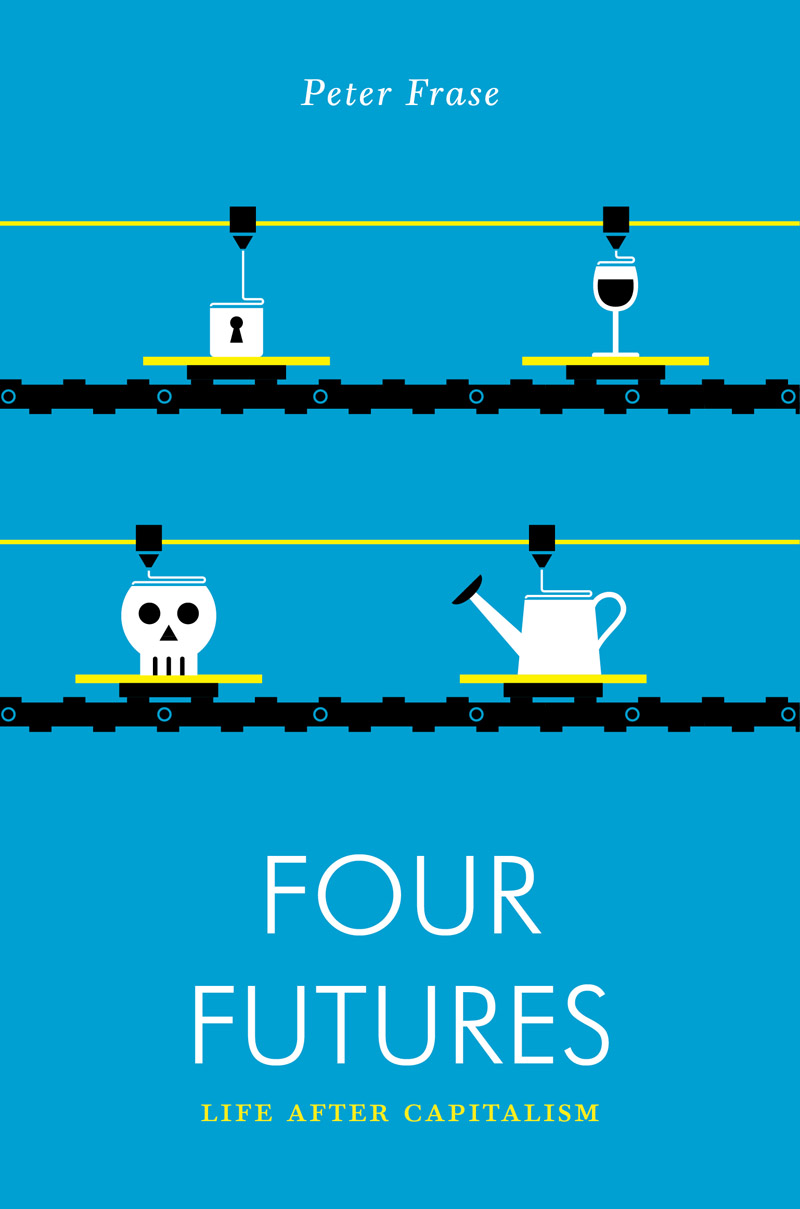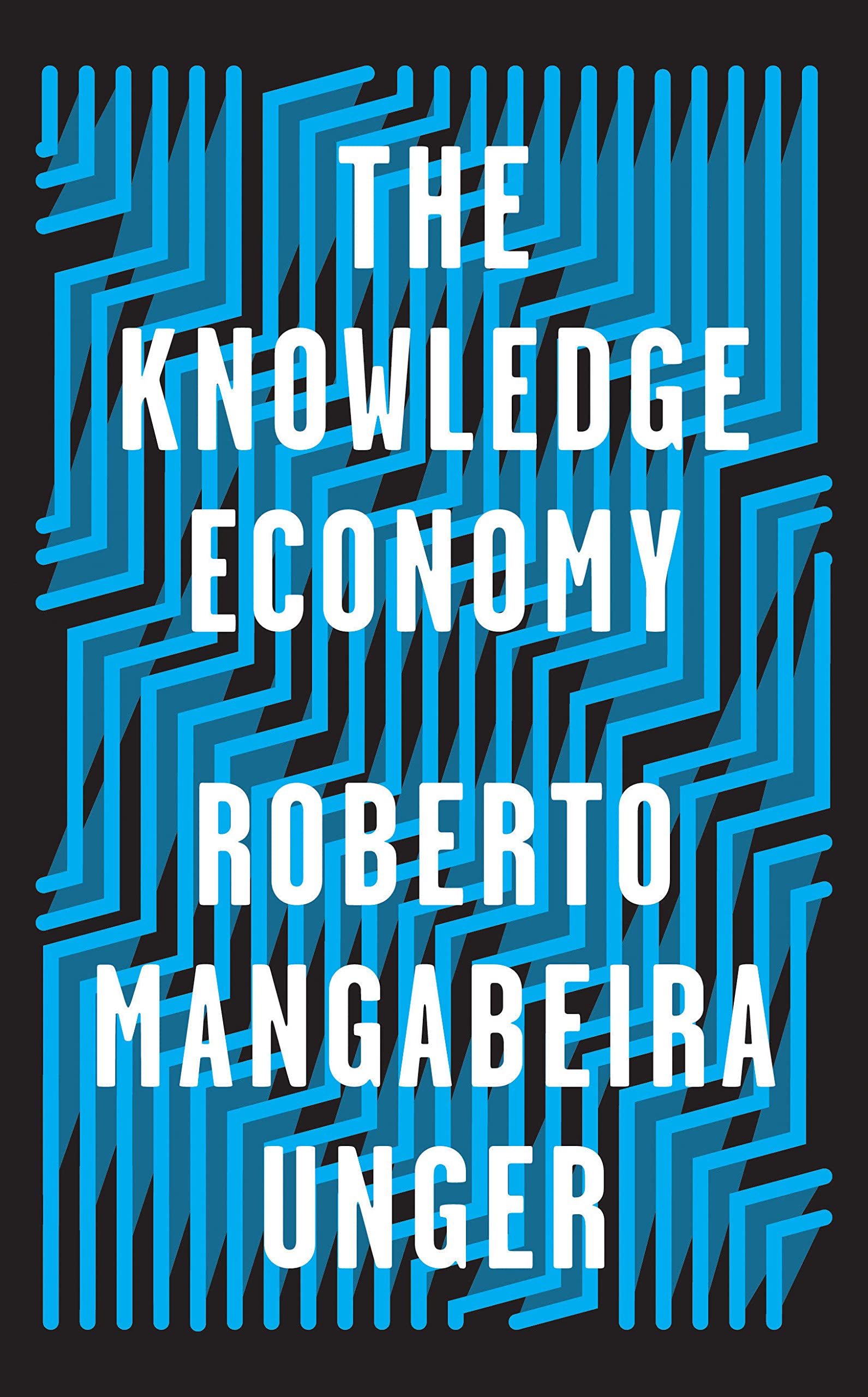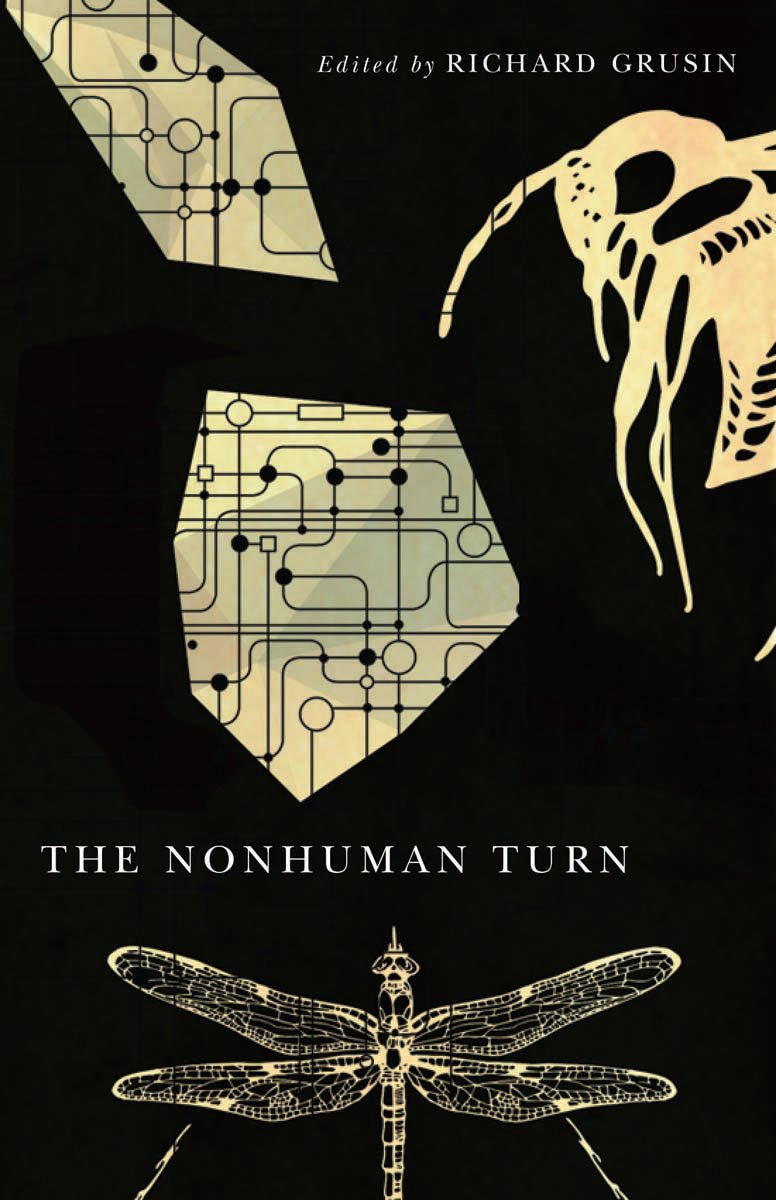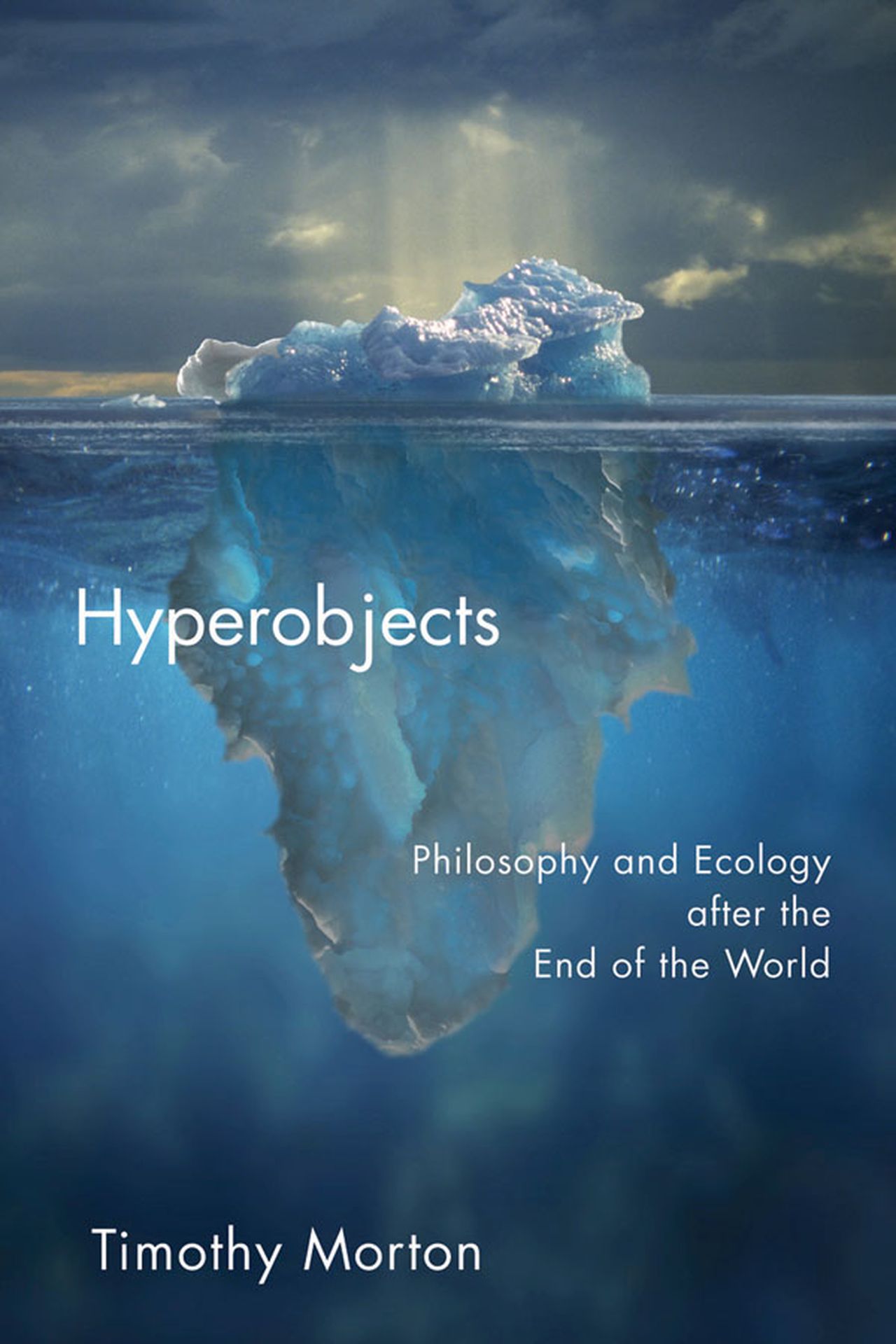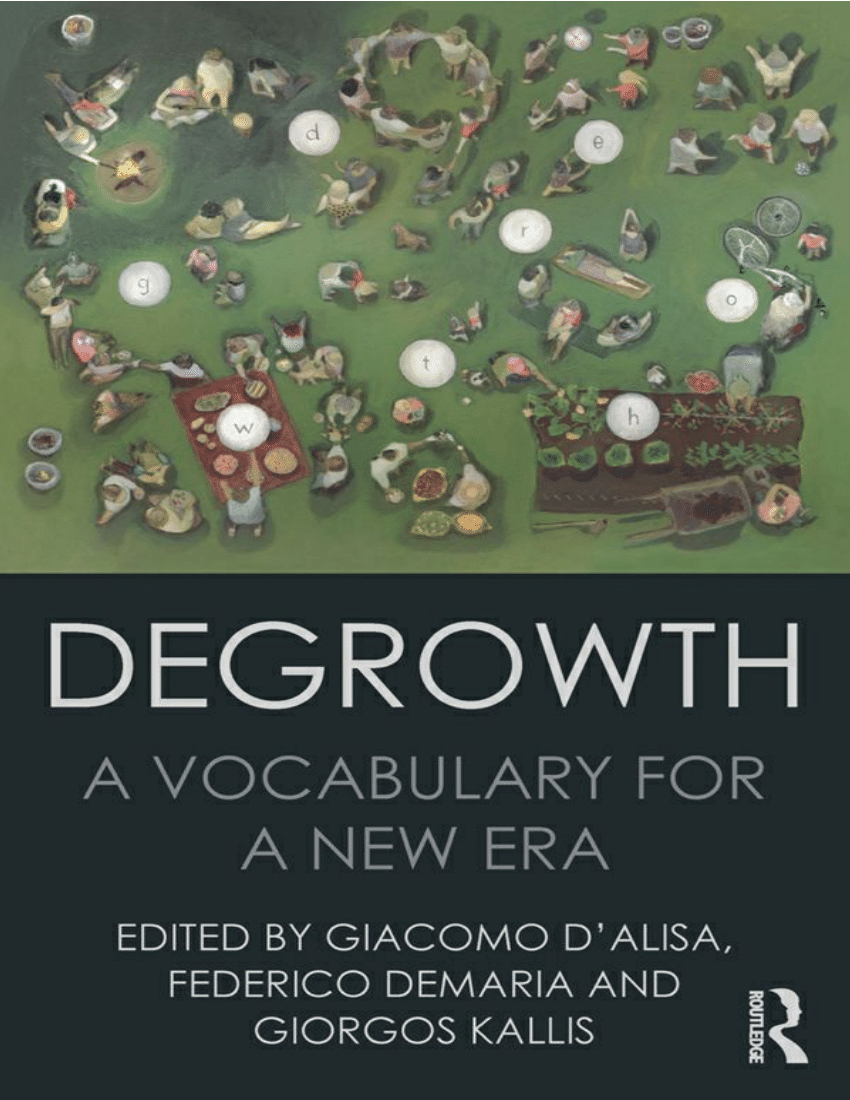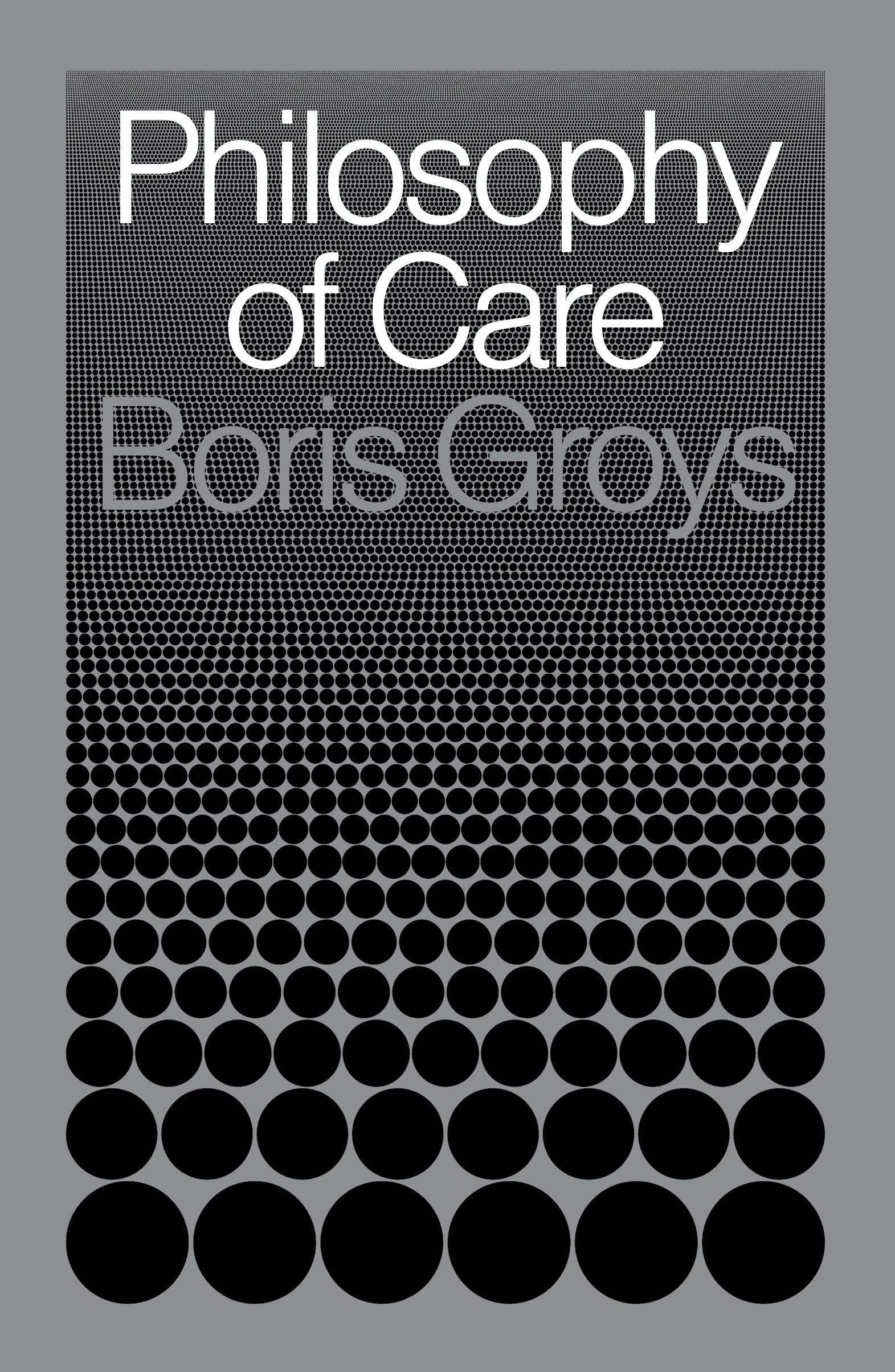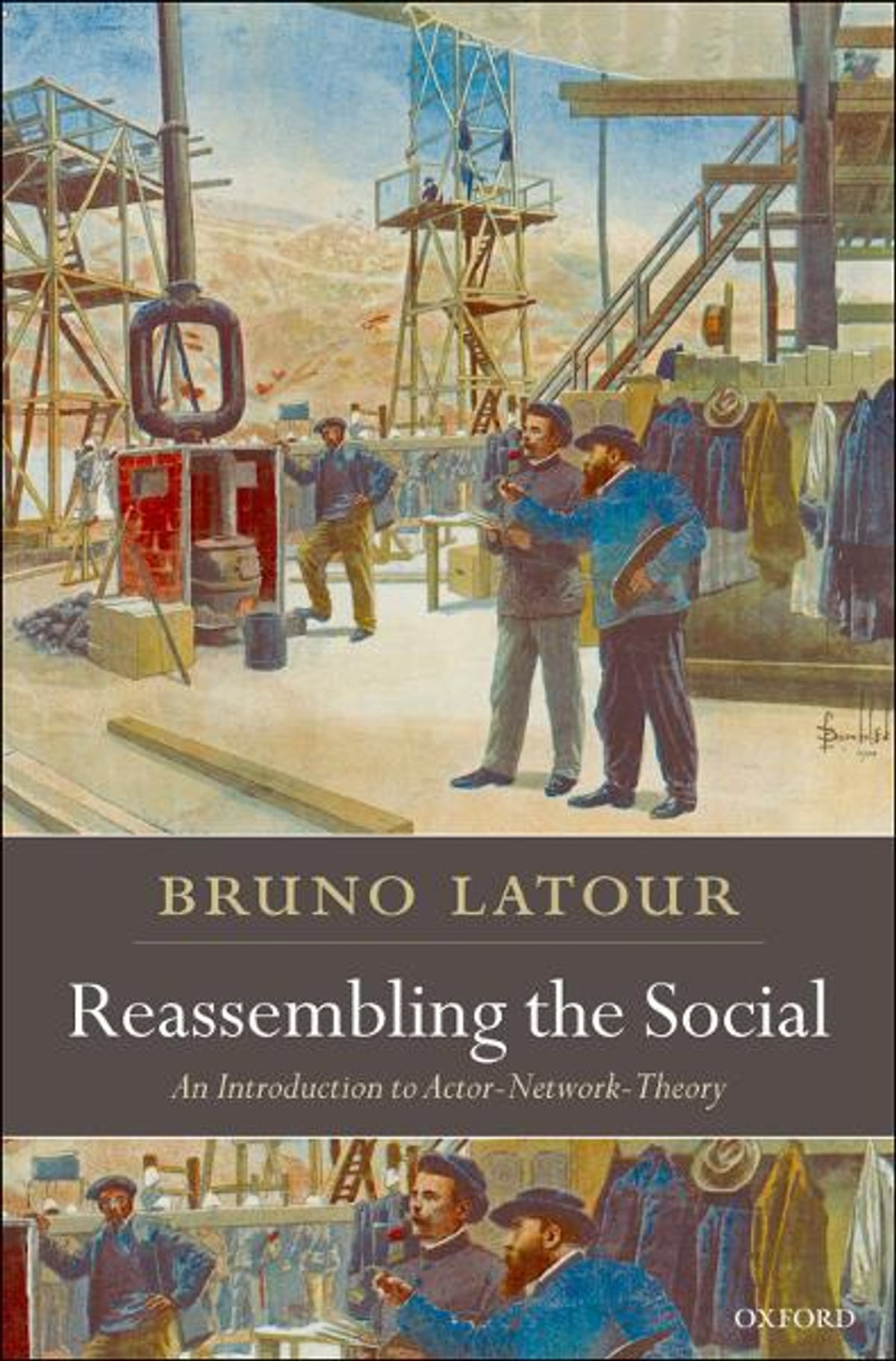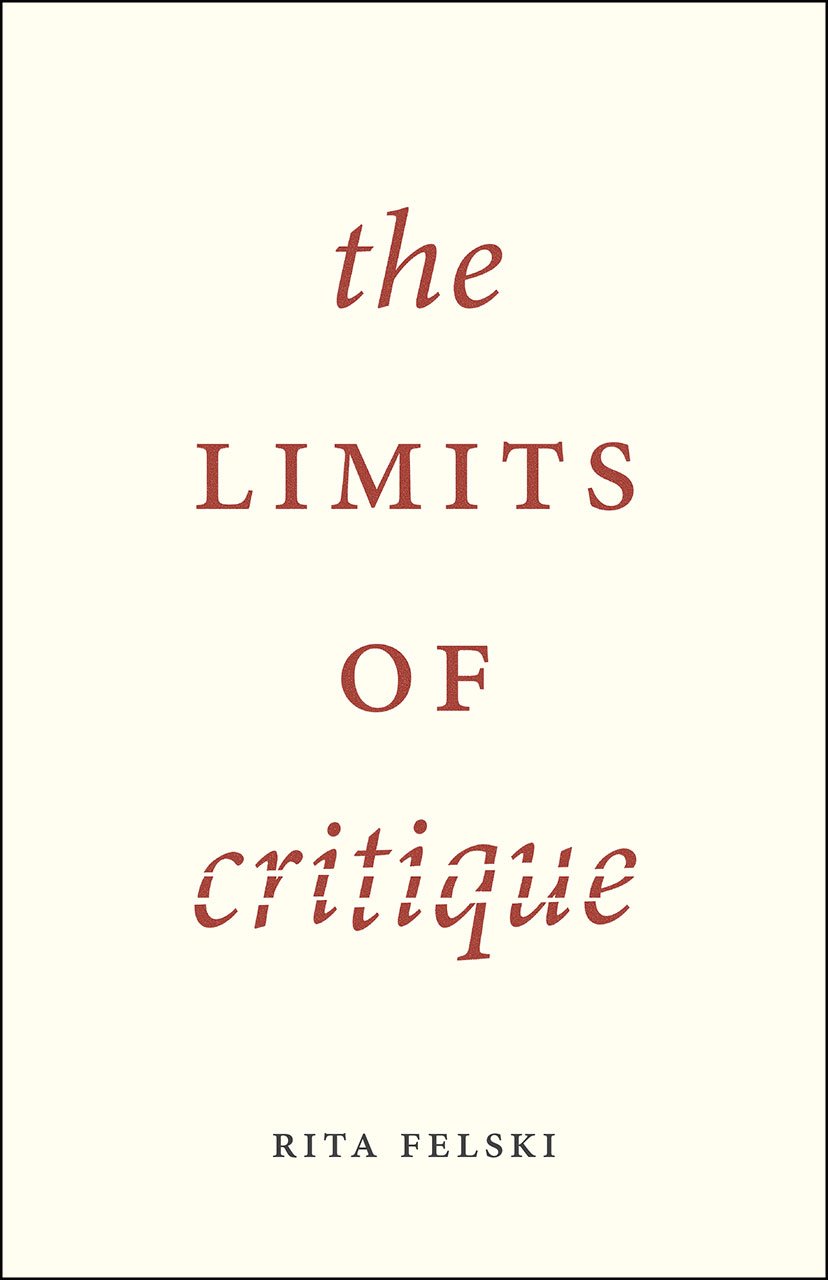Kritisisme yang Membosankan
KIRI hari ini berhadapan dengan fakta yang kurang mengenakkan: dunia sudah berganti rupa, tetapi tidak untuk kemenangan kita. Ada banyak kesadaran kritis, ada banyak aksi politis, tetapi tidak ada perubahan drastis (setidaknya yang mengarah ke “kemenangan kita”). Dalam jarak belasan tahun, begitu banyak idiom dan kerangka konseptual baru memasuki wacana publik kita. Cara kita menyelenggarakan kehidupan sehari-hari pun berubah drastis, dibentuk oleh kekhasan wahana kanal-kanal komunikasi dan transportasi digital. Kenyataan memang berubah, tetapi tidak ke arah yang kita harapkan.
Pada 2007, sewaktu Kiri Indonesia masih berkomunikasi lewat SMS, ketika orang masih berdebat apakah climate change adalah istilah yang lebih tepat dibanding global warming, ketika kapasitas sarana komunikasi belum memungkinkan terjadinya infodemic, sebagian dari kita khusyuk mengikuti kurpol tentang MDH dan menggelar aksi-aksi massa yang mengkritisi ketidakadilan, sedangkan sebagian lain asyik berdiskusi tentang simbolisme tersembunyi di balik paragraf-paragraf Das Kapital. Pada 2022, sewaktu Kiri Indonesia sudah fasih mencari promo gofood, ketika IPCC sudah merilis Special Report on Global Warming of 1.5 °C dan cancel culture sudah diterima sebagai hal yang wajar dan sepantasnya, sebagian dari kita masih melakukan hal yang sama seperti lima belas tahun sebelumnya. Tentu saja belajar MDH itu perlu dan menggelar aksi massa lebih perlu lagi, sebagaimana mempelajari Das Kapital. Namun, sekarang, itu saja tidak cukup.
Kiri adalah kritik. Ia terlahir sebagai kekuatan untuk mengkritik dan mengubah kenyataan. Namun, apa artinya kritik ketika semua orang sudah kritis? Menjadi kritis, hari ini, bukanlah suatu privilese. Orang tidak perlu menunggu buku datang dari kakak pergerakan yang sedang kuliah di Cornell atau Leiden agar menjadi yang terdepan dalam ide-ide dan imajinasi. Dahulu kala, orang harus membaca Soe Hok Gie, Ariel Heryanto atau Mansour Fakih agar menjadi intelektual kritis. Hari ini, berkat kemudahan akses informasi dan kecepatan tren aktivisme digital, setiap orang bisa berpikir seperti Ariel Heryanto setiap hari minggu, Mansour Fakih setiap senin-kamis dan Soe Hok Gie pas lagi pengen romantis. Pagi hari rapat dengan klien, siang hari ikut aksi menuntut pengurangan jam kerja bagi pekerja kreatif, sore hari healing dengan secangkir Kintamani, putar lo-fi, dan posting quotes Sylvia Plath di IG, malam hari lembur kejar deadline kerjaan. Hari ini, orang bisa kritis dalam berbagai macam gaya, dalam sembarang mazhab dan pendekatan, hanya dengan bermodal wifi.
Kalau ada satu konsep anak-anak otonomis yang paling produktif untuk membaca keadaan sekarang, saya pikir konsep itu adalah intelek umum (general intellect). Dirumuskan melalui studi Antonio Negri mengenai Grundrisse, khususnya dalam fragmen mengenai mesin, intelek umum adalah kecerdasan sosial secara umum, yakni tingkat pengetahuan publik yang melandasi keseluruhan modus produksi masyarakat sebagaimana tercermin dalam pengembangan teknologi produksi. Mesin, AI, algoritma adalah buah dari perkembangan kecerdasan umum masyarakat, yang semula berkembang dalam diskusi akademik dan praktik sosial sehari-hari, di luar rencana kapital. Lebih dari itu, saya melihat sikap kritis itu sendiri sekarang dapat disebut sebagai intelek umum. Ia telah menjadi bagian dari udara yang kita hirup, suatu cuaca kultural yang besar bersama gerakan #metoo, Black Lives Matter, Greta Thunberg dan sebagainya.
Keadaan ini memunculkan pertanyaan yang mungkin kurang mengenakkan bagi kita: ketika masyarakat umum sudah begitu kritis (bahkan remaja yang tumbuh dan dibesarkan oleh media sosial sudah tahu bahwa identitas adalah konstruksi sosial, bahwa tatanan dunia kapitalis ini bertumpu pada eksploitasi, bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja), lalu apa fungsi yang semestinya diperankan oleh Kiri? Melanjutkan kritik sebagai business as usual kalangan Kiri menjadi redundant di masa sekarang ini. Jika Om-Om dan Tante-Tante Kiri mesti bersaing kritis dengan remaja 4.0 di media sosial, itulah tandanya bahwa kalangan Kiri, para avant-garde perubahan sosial ini, mesti move on. Perjuangan kalian, upaya kalian membentuk hegemoni tandingan, sudah berhasil, sudah terbukti dalam tumbuhnya sikap kritis tentang kelas, gender dan etnisitas yang sekarang bahkan dimiliki oleh remaja paling tidak imajinatif di media sosial. Sekarang saatnya buat Om dan Tante (baca: kita semua ini) untuk go beyond criticism.
Pertanyaannya, ada apa setelah kritik? Adakah sesuatu di seberang kritik yang bukan mengulang dogmatisme lama yang dulunya dikritik? Dalam tulisan pendek ini tidak mungkin saya menguraikan jawaban atas pertanyaan sebesar itu. Apa yang akan dijalankan dalam tulisan ini lebih sederhana: mengadakan suatu stockopname ide-ide terkini yang boleh jadi berguna untuk mendudukkan standar kesadaran kritis hari ini. Ada 10 buku yang bisa dibaca sebagai rujukan tren terbaru dalam imajinasi kritis Kiri hari ini. Semuanya menunjuk kepada suatu kemungkinan lain di masa depan. Dengan demikian, sekalipun masih berada dalam lingkup kritik dan kritik atas kritik, 10 bacaan ini bisa dijadikan pijakan untuk mulai membayangkan modalitas baru beyond criticism.
Mengerti Apa yang Dipertaruhkan
Rangkaian buku pertama berkenaan dengan tantangan dunia masa kini. Ada empat buku yang penting:
1. Peter Frase. (2016). Four Futures: Visions of the World After Capitalism. London: Verso.
Buku ini membahas empat model masa depan masyarakat yang diklasifikasi berdasarkan dua sumbu, yakni sumbu hierarki sosial dan sumbu ketersediaan sumber daya. Dengan kedua sumbu itu, diperoleh empat kuadran masyarakat masa depan: (1) masyarakat yang setara dan berkelimpahan, (2) masyarakat yang hierarkis dan berkelimpahan, (3) masyarakat yang setara dan berkekurangan, (4) masyarakat yang hierarkis dan berkekurangan. Keempatnya berturut-turut menandai (1) tata masyarakat yang mengalami dekomodifikasi dengan setiap kebutuhan dasar dapat dicukupi tanpa harus menjual tenaga kerja (atau communism dalam kosakata Frase), (2) tata masyarakat yang bertopang pada sewa atas kepemilikan intelektual (atau rentism dalam kosakata Frase), (3) tata masyarakat dengan pembatasan akses yang setara untuk menjamin reproduksi planet Bumi (atau socialism dalam kosakata Frase) dan (4) tata masyarakat dengan komunisme untuk orang kaya dan kapitalisme untuk orang miskin (atau exterminism dalam kosakata Frase).
2. Roberto Mangabeira Unger. (2019). The Knowledge Economy. London: Verso.
Buku ini mengupas seluk beluk ekonomi berbasis pengetahuan yang dewasa ini kian berkembang menjadi bentuk perekonomian global. IP licensing, ekonomi berbasis pengolahan konten transmedial, pematenan sepihak atas pengetahuan agrikultur turun temurun milik masyarakat, semua itu membentuk realitas ekonomi dewasa ini yang cenderung mengarah ke komodifikasi atas pengetahuan dan aneka bentuk turunannya. Unger membongkar jalan yang mesti ditempuh untuk mengawal proses kapitalisasi intelek umum tersebut, termasuk pranata legal yang mesti diperhatikan. Selain itu, buku ini juga memberikan uraian tentang bagaimana teknologi digital yang terkesan menyetarakan justru dikendalikan oleh logika paling tidak setara dalam sejarah peradaban manusia, suatu logika yang mengotomasi ketidaksetaraan.
3. Richard Grusin (Ed.), (2015). The Nonhuman Turn. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Buku ini adalah bacaan wajib bagi mereka yang punya kesadaran untuk melihat manusia sebagai salah satu unsur dari ekosfer. Binatang, tumbuhan dan bahkan entitas takhidup seperti formasi batuan, sungai, bukit dan laut adalah bagian dari apa yang dewasa ini dipelajari dalam Nonhuman Studies. Wacana mengenai antroposen yang berkembang beberapa tahun terakhir juga mendorong perluasan kesadaran ini: sekarang kita telah tiba pada masa ketika untuk menyelamatkan manusia, kita mesti menyelamatkan seluruh isi Bumi persis karena manusia telah mengacak-acak seisi Bumi. Kerja-kerja politik kita diukur bukan dengan satuan puluhan atau bahkan ratusan tahun, melainkan jutaan tahun—keseluruhan lanskap geologis adalah medan aktivisme kita hari ini. Berfokus hanya pada manusia adalah berfantasi kita masih hidup di awal Revolusi Industri.
4. Timothy Morton. (2013). Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Buku ini agak sedikit filosofis. Morton adalah semacam rising star dalam dunia ekokritisisme dalam sastra. Sarjana yang mengawali karisnya sebagai pakar sastra Romantik ini sejak belasan tahun terakhir bergeser ke environmentalisme dengan menggunakan pendekatan ontologi berorientasi objek. Dalam buku ini, ia berfokus ke hiperobjek, yakni aneka jenis objek yang ditemukan di mana-mana tetapi hadir sebagai suatu gejala sistemik. Contohnya adalah plastik dan limbah kimia yang ditemukan di berbagai tempat di belahan bumi, termasuk di dalam diri kita, tetapi tidak bisa kita lihat sebagai objek individual yang terpisah-pisah. Mikroplastik yang ada dalam tubuh kita dan ikan paus yang mati terdampar adalah mikroplastik yang satu dan sama. Itulah hiperobjek—suatu objek yang tidak dapat diindividuasi tanpa menghapuskan manusia dari muka bumi. “Dunia antroposen adalah unggun-timbun hiperobjek,” demikianlah mungkin penulis Das Kapital abad ke-21 akan memulai bukunya.
Mendesain Isu Strategis
Setelah melihat berbagai tantangan zaman ini, kita dapat memeriksa juga isu-isu strategis yang seharusnya kita ajukan. Penekanan khusus ada pada desain isu. Sebuah isu, agar dapat bergulir sebagai proposal perubahan sosial yang dapat diikut-sertai oleh sebanyak mungkin orang, mesti didesain dengan memperhitungkan ketersambungan dan aliansi yang memperluas dan bukannya malah mengunci diri di satu posisi kaku yang tidak bisa ditawar. Ada empat buku yang bisa dibaca:
5. Guido Ruivenkamp dan Andy Hilton (Eds.), (2017). Perspectives on Commoning: Autonomist Principles and Practices. London: Zed Books.
Commoning—itulah kata kunci gerakan zaman kita. Kita sudah capek dengan isme-isme. Apa yang kita butuhkan adalah perikatan-perikatan baru yang mendorong partisipasi orang banyak. Commoning, yang bisa diterjemahkan sebagai proses pengelolaan kolektif atas sumber daya, adalah praktik nyata yang sekarang terjadi di mana-mana: mulai dari gerakan penghuni liar (squatter movement) mengklaim kembali rumah kosong, reruntuhan pabrik dan fasilitas umum yang tidak terpakai, gerakan Occupy Wall Stret atau yang di sini sempat terkenal sebagai Occupy Bursa Efek Jakarta, dan juga gerakan mendirikan komune di Bogor atau Sleman dengan konsep hidup dari upaya tani sendiri. Dulu kita mengenal istilah the commons atau ‘yang berkenaan dengan milik bersama’, antara lain dikembangkan dalam studi Elinor Ostrom tentang bagaimana pengelolaan atas barang milik bersama bisa berhasil dan tidak terjatuh ke dalam tragedy of the commons. Belakangan ini nomina commons berubah menjadi verba commoning untuk menandai suatu proses aktif gotong-royong—sebuah manuver retoris tipikal anak gerakan yang gemar merayakan peralihan dari kata benda ke kata kerja. Buku ini ditulis dari perspektif Marxis otonomis yang memang sejak lama sudah mengangkat tentang isu-isu seputar pembangunan komune dan gerakan non-elektoral. Another world is possible, semestinya.
6. Giacomo D’Alisa, Federico Demaria dan Giorgos Kallis (Eds.), (2017). Degrowth: A vocabulary for a new era. New York: Routledge.
Buku ini semacam ensiklopedia tentang konsep-konsep dan pengalaman kunci seputar agenda degrowth atau pertumbuhan negatif. Agenda ini ramai diangkat dalam sepuluh tahun terakhir, bermula dari Eropa, dan menyerukan bahwa dunia tidak akan selamat jika seluruh negeri menghentikan upaya pembangunan. Kaum Ontgroei ini berargumen bahwa setiap pertumbuhan ekonomi ekuivalen dengan penghancuran dunia, bahwa frasa “pembangunan berkelanjutan” adalah kontradiksi. Di situ dibahas juga isu mengenai kebijakan degrowth untuk negara dunia ketiga yang sedang membangun: apakah degrowth bukan hanya kemewahan aktivis negara maju yang justru akan mereproduksi dependensi jika diterapkan untuk negara dunia ketiga? Untungnya, ada argumen menarik yang diberikan dalam buku ini untuk mengatasi pertanyaan itu. Ada semacam strategi untuk mem-bypass pertumbuhan sama sekali.
7. Patricia Hill Collins. (2019). Intersectionality as Critical Social Theory. Durham: Duke University Press.
Buku ini adalah satu dari banyak buku tentang interseksionalitas, sebuah cara pandang yang dewasa ini makin banyak digunakan dalam aktivisme global. Perspektif ini pertama kali dicetuskan oleh pengacara hak sipil Kimberlé Crenshaw pada 1989 ketika ia melihat bahwa diskriminasi yang dilakukan General Motors terhadap pekerja perempuan tidak bisa diklasifikasi berdasarkan gender atau ras saja, tetapi melibatkan keduanya. Interseksionalitas adalah kesadaran bahwa identitas adalah gejala komposit, dibentuk oleh gender, kelas, ras, agama, usia, berat badan, dan sembarang penanda kultural lain yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini pastinya bikin pusing Kiri tradisional yang terbiasa mencari-cari identifikasi kelas sebagai litmus test bagi agenda progresif. Mau tidak mau kita mesti mengakui bahwa identitas seseorang adalah apa pun yang ia percayai tentang dirinya dan bagaimana masyarakat menafsirkan performativitasnya di ruang publik. Kelas cuma salah satu unsur saja dan belum tentu unsur yang menentukan. Bagi Kiri yang mau menang, intersectionality is a must.
8. Boris Groys. (2022). Philosophy of Care. London: Verso.
Buku ini mengulas sejarah pemikiran di balik caring economy. Dewasa ini berkembang kesadaran baru bahwa ekonomi kapitalis hanya bisa hidup di atas aneka jenis kerja yang tidak dinilai: kerja domestik, kerja reproduktif, kerja nemenin curhat, dan aneka bentuk kerja yang sekarang disebut care atau perhatian. Kalau semua jenis kerja itu dihitung, maka akan terlihat bahwa kapitalisme menghasilkan kerugian bagi setiap orang; selama ini kapitalisme terlihat menguntungkan di atas kertas karena care tidak pernah ditulis di atas kertas. Selain itu, buku ini juga cocok dibaca oleh Kiri generasi Z yang sudah paham bahwa healing dan me time adalah hak asasi manusia, sesuatu yang masih harus dipelajari untuk dapat diterima oleh Om dan Tante Kiri generasi X. Apakah ada me time kalau aksi terosss? Mental health sama pentingnya dengan kesehatan dompet, gaes.
Memperluas Horison Imajinasi
Setelah melihat aneka agenda strategis masa kini, terakhir kita akan meninjau dua buku yang bagus untuk memperluas perspektif dan pendekatan kita hari ini. Horison imajinasi kita mesti diperluas dan cara kita mengamalkan kritik perlu diperiksa kembali.
9. Bruno Latour. (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. New York: Oxford University Press.
Buku ini agak tua, tapi bagus. Actor-Network Theory sudah beredar lama di ilmu sosial Indonesia. Cara pandangnya bagus untuk mengobati antroposentrisme karena Latour di sini memperjelas bahwa yang dimaksud “aktor” bukan melulu orang, melainkan bisa juga benda, peristiwa, kata-kata, batu, virus, dan sebagainya. Sembarang hal bisa jadi aktor (atau lebih tepat, aktan) asalkan hal itu menghasilkan perubahan terhadap relasi yang ada. Latour memang agak aneh. Dulu dia menulis Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts (1979) yang menempatkan para ilmuwan seperti suku-suku yang sedang diamati antropolog: setiap teori, fakta-fakta ilmiah, tidak lain adalah konstruksi suku ilmuwan sesuai dengan kredo iman keilmuan mereka. Ini adalah sebuah konstruktivisme sosial yang dulu keren tapi sekarang sudah menjemukan. Sekarang, Latour merevisi idenya: yang ia maksudkan adalah “konstruktivisme, bukan konstruktivisme sosial”. Aktornya bukan masyarakat tetapi sembarang hal yang punya daya efektual. Uniknya, justru inilah posisi realisme entitas Ian Hacking di tahun 1980-an yang dulu sempat mengkritik keras konstruktivisme sosial Latourian. Hacking berpandangan bahwa entitas teoretis dikatakan ada sejauh dapat menimbulkan efek pada entitas lain. Ide inilah yang dipungut Latour dan menjadi dasar bagi Nonhuman Studies yang memuja Latour: aktan adalah apa pun yang menimbulkan efek pada keadaan. Sekalipun begitu, buku ini bagus untuk mengerti cara pandang baru yang non-antroposentrik tentang realitas sosial. Latour sudah bertobat dan sekarang kembali menyerukan perlunya realisme keilmuan. Itu sudah bagus.
10. Rita Felski. (2015). The Limits of Critique. Chicago: The University of Chicago Press.
Sekalipun buku terakhir ini berasal dari kajian sastra, relevansinya saya pikir berlaku juga untuk setiap ilmu sosial dan humaniora. Terinspirasi dari kritik Paul Ricoeur atas “hermeneutika kecurigaan”, kritik Eve Sedgwick atas “pembacaan paranoid” dan keluhan Latour atas kritisisme yang dewasa ini dimanfaatkan oleh para pemuja bumi datar dan teori konspirasi, Felski menginisiasi lahirnya pascakritik. Dalam buku ini, ia memperlihatkan bahwa hampir seluruh tradisi kritis kita bercorak simtomatik dan paranoid: melihat ‘teks’ sebagai alegori, simbol, gejala, dari sesuatu yang lain, seperti logika falus, heteronormativitas, kapitalisme neoliberal, atau metafisika kehadiran. Dalam cara baca paranoid seperti itu, ‘teks’ itu sendiri surut ke belakang dan sebagai gantinya mengemukalah medan perang konseptual yang abstrak dan sebetulnya tidak terlalu menjelaskan ‘teks’ itu sendiri. Felski ingin menyudahi tradisi kritik-sebagai-suudzon semacam ini dan kembali membaca ‘teks’ secara lebih apresiatif dan atentif terhadap rincian tekstual tanpa terburu-buru menafsirkannya secara simtomatik. Ia juga mengkritik kecenderungan para teoretisi untuk menjalankan denaturalisasi demi menegakkan anti-esensialisme dan konstruktivisme sosial: sebuah repetisi tanpa akhir bahwa “tidak ada x yang natural” (gantilah x dengan gender, tatanan sosial, mentalitas atau apapun dan kita peroleh seluruh teori kritis hari ini).
Demikianlah 10 buku yang dapat dibaca Kiri masa kini untuk membayangkan masa depan secara lebih kreatif. Seperti dibilang di awal, buku-buku itu sendiri tetaplah merupakan laku kritisisme dan belum betul-betul menghadirkan suatu proposal alternatif di luar kritik atas apa yang ada. Namun, setidaknya buku-buku bisa meng-update wawasan kritis kita yang dituntut untuk relevan dengan situasi dunia hari ini. Jika dari situ muncul percik-percik pemikiran baru yang membuka jalan bagi identifikasi agenda masa depan yang dapat menarik seluruh tenaga sosial kita ke arah sana seperti halnya para intelektual era 1960-an mengidentifikasi agenda yang sekarang direalisasikan dalam wujud cancel culture, maka tulisan ini sudah melaksanakan tugasnya.***