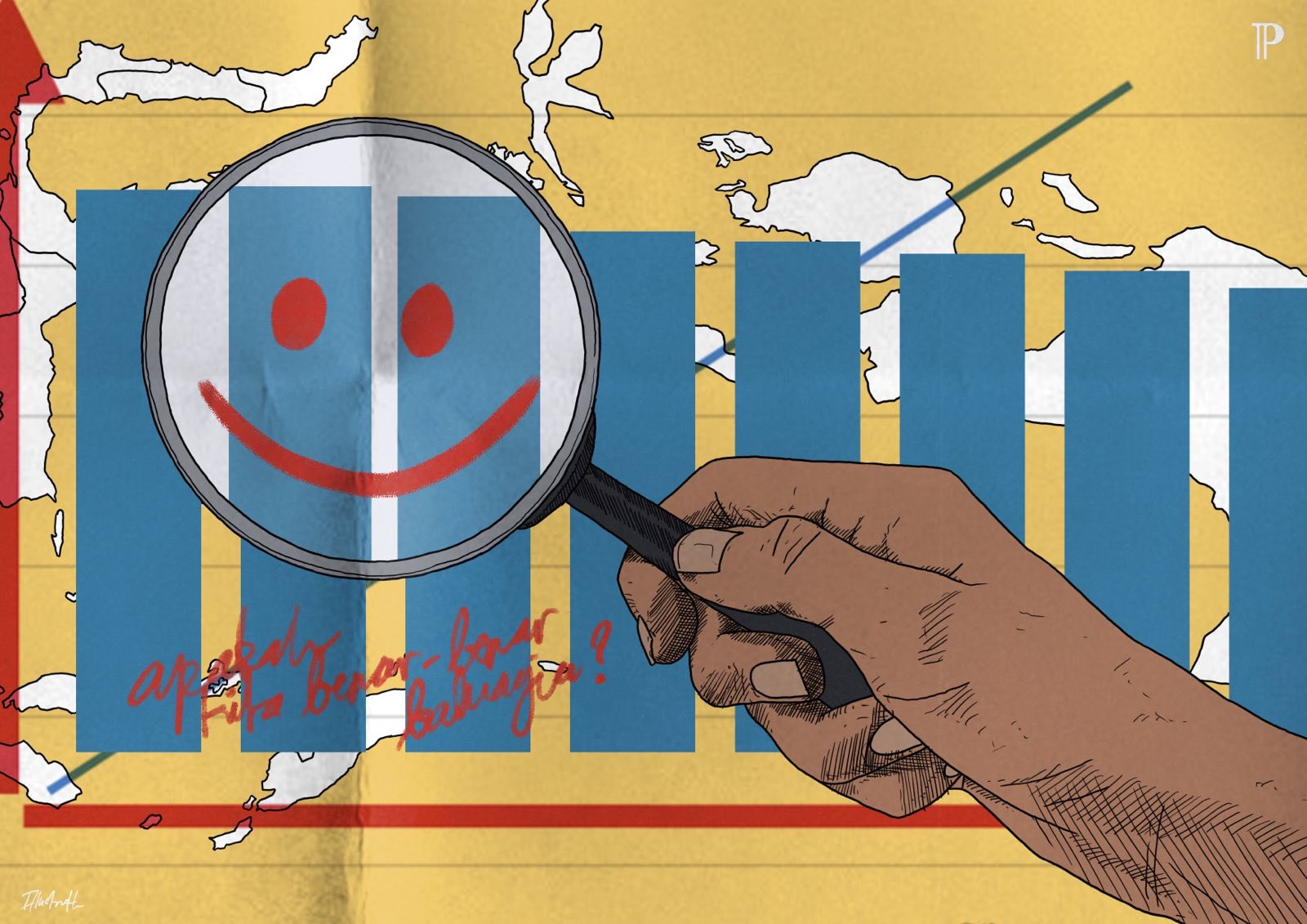Ilustrasi: Illustruth
BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) baru saja mengeluarkan Indeks Kebahagiaan 2021 (IK 2021). IK diukur berdasarkan Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan yang dilakukan sekali dalam tiga tahun, dan dihitung berdasarkan kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Berdasarkan perhitungan seperti ini, walaupun dihantam badai Covid-19 sejak Maret 2019, IK 2021 mengalami kenaikan 0,8, yakni menjadi 71,49 dibandingkan dengan skor tahun 2017.
Berdasarkan data kemiskinan Maret 2021, lima provinsi yang memiliki persentase kemiskinan satu digit masuk 10 besar provinsi paling bahagia di Indonesia, yakni Maluku Utara (6,89%), Kalimantan Utara (7,36%), Jambi (8,09%), Sulawesi Utara (7,77%), dan Kepulauan Riau (6,12%). Sementara itu, ada lima provinsi yang lain yang masuk 10 besar dengan rata-rata kemiskinan dua digit, yakni Maluku (17,87%), Gorontalo (15,61%), Papua Barat (21,84%), Sulawesi Tengah (13,00%) dan Sulawesi Tenggara (11,66%).
Data IK 2021 cukup mengejutkan. Provinsi miskin, seperti provinsi Maluku dengan rata-rata kemiskinan sebesar 17,87%, mampu menempati urutan 3. Begitu juga dengan Papua Barat yang menempati nomor urut 8 dengan rata-rata kemiskinan 21,84%. Sementara itu, provinsi yang jumlah kemiskinannya rendah seperti Kalimantan Tengah dengan rata-rata kemiskinan 5,16% justru menempati urutan 15, dan provinsi Bangka Belitung yang rata-rata kemiskinannya hanya 4,90% menempati urutan 14. Begitu juga provinsi DKI yang rata-rata kemiskinannya hanya 4,72% menempati urutan 27. Provinsi Banten yang rata-rata kemiskinannya hanya 6,66%, menempati posisi paling bontot, yakni 34. Yang lebih mengagetkan, tak satu pun provinsi di pulau Jawa—pusat kemajuan ekonomi Indonesia—masuk dalam 10 besar. Sementara itu, dari formasi 10 besar provinsi paling bahagia ini, terdapat tujuh provinsi di Indonesia Timur, yang selama ini terkenal sebagai konsentrasi daerah terluar, termiskin, dan tertinggal.
Pertanyaannya, mengapa provinsi yang rata-rata kemiskinannya rendah seperti provinsi DKI, Kalimantan Tengah dan Bangka Belitung justru menempati posisi yang rendah dalam IK 2021? Saya kira jawabannya bisa seperti ini. Provinsi yang menyandarkan ekonominya pada industri ekstraktif seperti industri tambang, industri kayu, dan perkebunan—yang menjadi andalan provinsi Bangka Belitung dan Kalimantan Tengah—biasanya akan membuat masyarakatnya tidak bahagia walau mereka tidak begitu miskin. Alasan ketidakbahagiaan ini adalah kecenderungan industri ekstraktif menimbulkan dampak lingkungan yang buruk dan rawan konflik sehingga merugikan masyarakat banyak. Lalu bagaimana dengan provinsi DKI? Ketidakbahagiaan orang DKI disebabkan oleh polusi suara, polisi udara, banjir, macet dan kesenjangan ekonomi sebagai akibat dari pembangunan yang tidak adil dan tidak terkontrol. Efek pembangunan seperti ini mungkin telah membuat warga DKI tidak bahagia.
Bagaimana dengan provinsi Maluku dan Papua Barat masing-masing masuk urutan 3 dan 8 provinsi paling bahagia di Indonesia walau rata-rata kemiskinannya mencapai 17,87% dan 21,84%? Saya pernah mengunjungi provinsi Maluku dan Papua Barat. Berdasarkan kunjungan ini, saya ingin mengomentari skor IK 2021.
Berbagai Kesenjangan
Di provinsi Maluku, saya mengunjungi pulau Ambon dan Seram antara 2009-2014. Saya memang melihat provinsi Maluku sebagai provinsi miskin. Kemiskinan itu masih menjadi persoalan serius hingga pada Maret 2021, dengan persentase sebesar 17,87%. Walaupun rata-rata penduduk di provinsi Maluku memiliki akses yang relatif mudah terhadap tanah dalam sistem tata kelolah tanah tradisional yang disebut pertuanan,[1] buruknya infrastruktur publik dan ketegangan sosial yang belum sirna akibat efek konflik agama pada 1990an dan 2000an, serta sumber daya manusia yang masih rendah telah menyebabkan kemiskinan dan stagnasi ekonomi.
Jika Anda berkunjung ke provinsi Maluku, Anda akan segera menangkap kesenjangan itu. Infrastruktur publik dan transportasi publik lebih terkonsentrasi di daerah pesisir pantai daripada di daerah pegunungan dan menciptakan kesenjangan ekonomi di antara penduduk di kedua wilayah. Kesenjangan ekonomi ini pula yang telah menimbulkan konflik agama di Maluku. Warga Muslim yang umumnya tinggal di daerah pesisir, menikmati infrastruktur publik yang lebih baik, dan lebih terbuka dengan dunia luar yang memperlebar akses ekonomi mereka, lebih maju daripada ketimbang warga Kristen yang rata-rata tinggal di daerah pegunungan dengan di kontak dan relasi ekonomi ke dunia luar yang agak terbatas. Situasi di pegunungan diperparah oleh minimnya infrastruktur publik seperti jalan raya, sekolah dan sarana kesehatan. Kesenjangan antara ‘masyarakat pegunungan’ dan ‘masyarakat pesisir’ atau ‘masyarakat Islam’ dan ‘masyarakat Kristen’ ini akhirnya juga terefleksikan dalam struktur birokrasi dan politik, yang memberi keuntungan lebih besar bagi masyarakat yang mampu mengakumulasi lebih banyak modal dan kekayaan ekonomi dalam sistem ekonomi pasar hari ini, yakni masyarakat pesisir yang kebetulan mayoritas beragama Islam.
Kesenjangan ini diperburuk dengan penetrasi (pekerja) migran beragama Islam dan beretnis Buton, Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan yang tinggal di kampung-kampung tersendiri dan mendominasi sektor informal seperti perdagangan dan transportasi di kota-kota di provinsi Maluku (kota Ambon, Masohi, Piru dan Bula). Para migran ini akhirnya juga memiliki pengaruh terhadap lembaga birokrasi dan politik. Entah melalui politik patronase atau politik identitas, pengaruh para migran bisa saja memperkuat kesenjangan struktur birokrasi dan politik, yang didominasi ‘masyarakat pesisir’. Selanjutnya, kesenjangan ini akhirnya menyingkirkan orang-orang Maluku, terutama ‘masyarakat pegunungan,’ yang kebetulan adalah orang Kristen, sehingga sulit bagi mereka untuk berkompetisi dalam sektor formal dan informal di provinsi Maluku. Apalagi, industrialisasi tidak berkembang di kota-kota di provinsi Maluku.
Dengan kondisi ekonomi politik seperti ini, aneh jika provinsi Maluku diumumkan sebagai provinsi miskin sekaligus paling bahagia bernomor urut 3 di berdasarkan IK 2021. Kenyataannya, kemiskinan dialami oleh 17,87% masyarakat provinsi Maluku. Dalam sejarahnya, kemiskinan ini pula yang telah menyulut konflik agama di tengah masyarakat yang hingga hari ini masih tersegregasi berdasarkan agama,[2] persaingan ekonomi dan politik dengan para pendatang dari Sulawesi Selatan dan, yang akhirnya kontrol militer yang kuat.[3]
Saya pernah mengunjungi kota Sorong dan Manokwari yang terletak di Papua Barat pada 2014. Di sana, saya lebih banyak menemukan para pendatang dari Jawa, Sulawesi, NTT, dan berbagai tempat lain di Indonesia, yang menguasai lapak-lapak ekonomi. Pembangunan kedua kota tidak berbeda jauh dengan kota-kota besar ideal di Indonesia. Tampilan luarnya kelihatan ideal; Anda bisa menemukan apapun yang Anda biasa temukan kota-kota besar di Jawa, kecuali polusi udara, polusi suara, banjir, kemacetan dan kemiskinan. Di dua kota ini, saya tidak menemukan wajah kemiskinan Papua Barat. Jika survei IK 2021 hanya dilakukan di perkotaan, maka tidak heran jika provinsi Papua Barat menempati posisi 8.
Wajah kemiskinan Papua akan sangat nampak di pedesaan dan perkampungan. Pada 2014, saya juga mengunjungi dua kampung di provinsi Papua Barat, yaitu kampung Yarmatum dan Isim. Untuk mencapai dua kampung di pedalaman Papua ini, saya harus ke Mamey. Akses jalan ke Mamey sangat sulit kala itu sehingga saya harus menggunakan kendaraan beroda tinggi.
Yarmatum dan Isim adalah dua kampung yang hutan adatnya dipenuhi pohon Merbau. Dengan luas sekitar 250 hektar, tempat ini menjadi wilayah HGU sebuah perusahaan kayu bernama Tembagapura sejak 2003. Sejatinya sudah ada ada perusahan kayu lain, yakni perusahaan Jayanti Group yang pernah berada di pulau Seram pada 1970an dan 1980an. Perusahaan Jayanti Group mendapat HGU dari 1990-1996.
Perusahan kayu ini tidak selalu melakukan apa yang dijanjikan. Perusahaan Tembagapura memiliki sekitar 120 pekerja saat itu, mayoritas berasal dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Pekerja paling banyak berasal dari Kalimantan dan paling sedikit dari Papua (kurang dari 20 orang). Dengan jumlah pekerja seperti ini, Tembagapura bisa bisa menebang 50.000 kubik per tahun. Satu hektar bisa menghasilkan 500 kubik karena pohon Merbau yang diizinkan untuk ditebang minimal berdiameter 60 cm di hutan produksi terbatas dan 50 cm di hutan produksi.[4] Masyarakat adat mendapatkan kompensasi Rp60.000 untuk setiap kubik kayu yang dihasilkan oleh perusahaan. Berdasarkan data ini, jika sudah beroperasi sejak 2003, maka perusahan Tembagapura ini bisa sudah menghasilkan 500.000 kubik kayu hingga 2013. Karena itu, masyarakat adat berhak mendapatkan sekitar Rp30.000.000.000. Tetapi, dalam kenyataan, masyarakat adat di dua kampung itu hanya mendapatkan Rp150.000.000 dalam 10 tahun. Perusahan berjanji untuk menanam kembali pohon di wilayah hutan yang sudah ditebang, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh perusahaan, terutama oleh perusahaan Jayanti Group yang telah pergi itu.
Kehidupan masyarakat di dua kampung ini tidak mengalami perubahan signifikan—bahkan tambah sulit—dengan keberadaan perusahaan kayu ini. Ada sekitar 192 keluarga di kedua kampung. Namun, 3-4 keluarga bisa tinggal dalam satu atap. Rata-rata angka harapan hidup di kedua kampung hanya mencapai 40-50 tahun. Memang ada pelayanan pendidikan dan kesehatan di kampung Isim, yang memiliki 1 Sekolah Dasar (dengan 2 guru) dan 1 Sekolah Menengah Pertama (dengan 3 guru). Di Puskesmas hanya ada 4 orang tenaga kesehatan, yang kebetulan adalah warga asli Isim. Pendapatan masyarakat sekitar Rp200.000 per bulan. Akses terhadap air bersih sangat sulit akibat kerusakan hutan di tangan pihak perusahaan kayu. Demikian pula akses ke pasar juga sulit. Masyarakat kedua kampung harus berjalan kaki 2-3 hari ke pasar terdekat untuk menjual hasil kebun.
Berdasarkan data ini, dengan infrastruktur publik yang buruk dan terbatas, tingkat kemiskinan yang tinggi, yakni 21,84%, dan penetrasi kapital pertambangan, kayu dan perkebunan, serta dominasi ekonomi para pendatang, sangat tidak masuk akal jika Papua Barat menjadi provinsi paling bahagia nomor 8 di Indonesia.
Secara umum, berdasarkan pengalaman ini, saya mempertanyakan sekaligus meragukan skor IK 2021 untuk provinsi Papua Barat dan provinsi Maluku secara khusus dan Indonesia Timur pada umumnya. Skor IK 2021 tidak mencerminkan keadaan eksploitatif dan kemiskinan di Indonesia Timur. Berdasarkan skor IK 2021, tak satu pun provinsi di pulau Jawa yang masuk 10 besar. Sementara itu, tujuh provinsi di Indonesia Timur masuk 10 besar IK 2021. Padahal, konsentrasi ekonomi dan pembangunan sejauh ini terkonsentrasi pada pulau Jawa. Jika IK 2021 bukan sebuah sinisme untuk kemiskinan dan eksploitasi di Indonesia Timur, maka ada tujuan politis lain dari IK 2021. Konsep kebahagiaan ini barangkali memang dibuat agar orang-orang Indonesia Timur tidak perlu terlalu menuntut terlalu banyak pada pemerintah, sebab toh Anda bisa hidup bahagia walaupun miskin.***
Emilianus Yakob Sese Tolo adalah Anggota Forum Academia NTT
Catatan Akhir
[1] Para migran dari Sulawesi, seperti di pulau Seram, misalnya, bisa mengolah dan mendiami pertuanan orang-orang asli Maluku dengan relatif mudah.
[2] Pada 2014, saya berkunjung ke Sawai bersama seorang sopir dari Piru. Sopir saya ini beragama Kristen Protestan. Ketika bagun pagi di penginapan sederhana di kampung Sawai, sopir saya mengaku bahwa malam tadi dia tidak bisa tidur karena trauma konflik pada 1990an dan 2000an tiba-tiba menyelimuti dirinya. Sebab, kampung Sawai adalah kampung muslim, yang membuat sopir saya mencurigai kemungkinan buruk yang terjadi pada dirinya sebagai orang Kristen yang makan, minum dan tidur di sebuah penginapan di sebuah kampung muslim.
[3] Kontrol militer yang kuat ini bisa dilihat dari pos-pos militer cukup banyak di kota Ambon yang kecil itu.
[4] Berdasarkan pengamatan di lapangan, penebangan selektif sulit dilakukan. Pohon-pohon besar yang ditebang menindih pohon-pohon kecil. Karena itu, kerusakan hutan yang masif tak dapat dihindari.