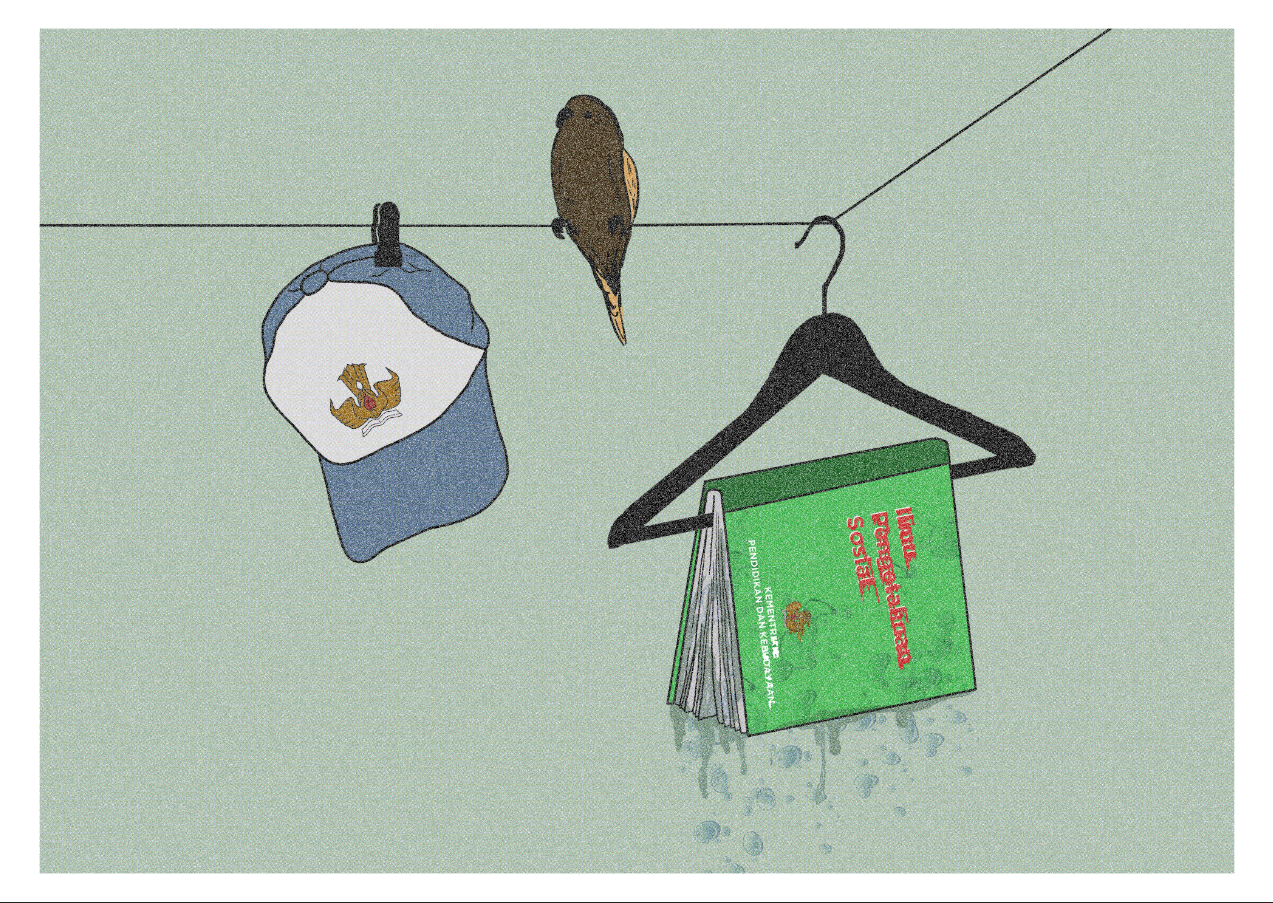Ilustrasi: Jonpey
(Bagian kedua dapat dibaca di tautan berikut.)
LEMAHNYA daya berpikir kritis, merdeka dan argumentatif dalam diri sebagian besar pelajar Indonesia tidak saja kontraproduktif dengan tujuan 4C-Competencies yang kini diakui sebagai rambu-rambu kualitas pendidikan dunia, tapi juga membawa dampak negatif yang lebih luas, baik dalam ekosistem internal sekolah maupun ketika siswa diajak turut melebur dalam komunitas masyarakat majemuk setelah ia merampungkan studi formalnya.
Dalam ekosistem internal sekolah, daya kritis siswa yang lemah membentuk relasi kuasa yang memperlebar disparitas dengan pendidik serta mentransformasi komunikasi dua arah yang resiprokal dan dialogis menjadi satu arah yang mendikte dan pasif. Lingkungan seperti ini adalah iklim yang cocok untuk bertumbuh-kembangnya bibit-bibit hierarki dan birokratisme.
Inilah tantangan pertama yang mutlak dipecahkan dalam memulai pendidikan demokrasi, yaitu mengeliminasi kompleks inferior di dalam diri siswa terhadap para pendidik sebagai superior dan sebaliknya.
Sementara dampak eksternal yang timbul dari daya berpikir kritis yang [di]lemah[kan], dalam jangka pendek akan menimbulkan ketidakberdayaan siswa untuk berpartisipasi dalam perlawanan radikal dan sistematis terhadap persoalan yang kontekstual seperti politik adu-domba, diskriminasi rasial dan gender, perubahan iklim, pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, hingga gejala makin dalamnya kesenjangan sosial-ekonomi di tengah pandemi. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, ketidakberdayaan kolektif ini berpotensi menggagalkan usaha demokratisasi pendidikan sekaligus memberi celah lebar kembalinya militerisme dan manipulasi ‘kebebasan yang bertanggung jawab’.
Dampak-dampak inilah yang akan menjadi benang merah catatan ini.
Tulisan ini merupakan bagian terakhir dari dua catatan empiris yang telah terbit sebelumnya. Harapannya, dengan tiga catatan empiris yang dapat terus diperbandingkan dan diperbaiki ini, maka kompleksitas masalah pendidikan demokrasi di Indonesia dapat menemukan kekurangan yang ada padanya serta mampu mengakselerasi pendidikan demokrasi radikal yang diutarakan secara komprehensif oleh Ben K.C. Laksana dalam serial esainya. Sementara untuk pendidik seperti Ben, semoga catatan ini dapat memberi tinjauan yang lebih luas untuk merintis pendidikan demokrasi di Indonesia dari sudut pandang saya sebagai pelajar.
Di bagian akhir catatan ini saya akan menyertai beberapa butir refleksi masa depan pelajar Indonesia dan apa yang seharusnya dilakukan pendidikan demokrasi di Indonesia di masa mendatang.
Salah Kaprah Memaknai Kepatuhan
Ditinjau dari sudut pandang mana pun, corak pendidikan yang masih mensyaratkan kepatuhan sesungguhnya berkarakter ambivalen dan cenderung multitafsir. Kepatuhan selalu dimaknai sebatas unsur yang melegitimasikan relasi vertikal dalam masyarakat serta menjadi parameter nisbi ‘warga negara yang baik’. Tak mengherankan jika hingga catatan ini ditulis dan entah sampai kapan institusi pendidikan dasar dan menengah masih menjadikan nilai kepatuhan sebagai indikator ‘watak baik’ yang wajib dimiliki tiap siswa tanpa kecuali. Dengan indikator tersebut, para siswa yang berbakat unggul namun memiliki kecenderungan pembangkang akan kesulitan menemukan ruang hidup yang pantas sehingga ia pun terpaksa tunduk pada arus pendapat umum.
Sisi pertama kepatuhan yang ambivalen itu dapat ditinjau secara umum dalam nuansa positif. Dalam suasana kepatuhan, siswa mendapatkan pemahaman yang cukup akan pentingnya kesadaran menjunjung tinggi hukum sebagai pedoman tertinggi dalam bersikap. Implementasi rule of law sejak dini merupakan praktik yang esensial dalam membentuk pribadi berkarakter demokratis. Dalam sisi ini, kepatuhan dapatlah dimaknai sebagai pembentuk sikap prinsipil dan integritas sehingga siswa mampu cerdas secara sosial serta berkomitmen tinggi terhadap kesepakatan bersama.
Akan tetap, pada sisi lain, kepatuhan dimaknai sebagai alat menegaskan kekuasaan seseorang, terutama yang mendaku diri sebagai ‘penegak hukum’, serta menjustifikasi tindakan-tindakannya—termasuk yang menyalahi aturan sekalipun—sebagai bagian dari ‘penegakan hukum’. Dalam sisi ini, kepatuhan menjadi upaya pertama dan terutama dalam mengondisikan taklid orang-orang di bawah sang ‘penegak hukum’ sehingga terbentuklah kekuasaan yang represif. Dalam sisi inilah kepatuhan yang didikkan kepada siswa berpotensi menimbulkan penindasan dan kesewenang-wenangan.
Kendati bertolak belakang satu sama lain, kedua corak kepatuhan tersebut wajib ditempatkan dalam satu kerangka yang membingkainya secara komplementer. Prinsip yang telah disepakati akan mudah disalahgunakan dan dilanggar jika tidak ada otoritas yang tegas kewenangan dan tugasnya. Sebaliknya, otoritas tanpa komitmen dan prinsip untuk dipegang dalam menentukan batas-batas hak dan kewajiban akan melahirkan preseden suatu dominasi kuasa sekelompok manusia atas manusia lain berdasarkan kepentingan kelompok penindas. Dominasi ini lebih populer dalam slogan Revolusi Perancis sebagai exploitation de l’homme par l’homme, eksploitasi manusia oleh manusia.
Dalam lingkungan institusi pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, corak kepatuhan dominan pada kecenderungan kedua yang menegaskan kedudukan seseorang (in casu, para pendidik) serta menundukkan yang lain dengan legitimasi kedudukan itu. Dalam kecenderungan ini, kepatuhan bukan bertujuan melatih siswa menjunjung tinggi hukum dan tata tertib, namun mengajarkan siswa untuk serta-merta tunduk tanpa syarat serta membenarkan perilaku snobistik kakak kelas pada adik kelasnya yang membentuk pola pergaulan yang subordinatif. Dari fenomena ini, saya kerap mendengar anekdot: siswa lebih takut kepada guru pencatat pelanggaran tata tertib daripada tata tertib itu sendiri.
Situasi ini kerap terjadi di masa orientasi tahun ajaran baru. Sekolah saya, misalnya, memilih siswa-siswa tertentu untuk menjadi guide siswa baru dalam melaksanakan masa pengenalan lingkungan. Mereka yang ditunjuk rata-rata merupakan anggota pasukan pengibar bendera yang—harus saya akui—amat terobsesi militerisme. Alhasil, hanya untuk menegur satu kesalahan kecil yang didapatinya, mereka sengaja (atau doyan?) menggunakan kalimat bernada tinggi dan imperatif yang menyudutkan dan mengecilkan hati yang ditegur. Setiap perintah itu pula harus dijawab “Siap!”, persis seperti kadet di barak tentara.
“Ah, biasa. Supaya mereka tahan banting dan punya mental,” dalih mereka ketika saya (dalam perasaan jengkel) bertanya kepada mereka apa perlunya perintah-perintah bernada tinggi itu. Tidak salah lagi, mental yang mereka maksud adalah mental pengecut, sehingga siswa angkatan baru harus pasrah menjadi pelampiasan dari ketakutan yang pernah dirasakan kakak kelasnya sewaktu ada dalam posisi mereka. Di sana tidak ada unsur tanggung jawab, kedewasaan dalam berpikir, bersikap ngemong (mengayomi), atau mendidik dengan teladan (learning by doing). Yang ada hanya perintah, perintah, dan perintah yang eksak, lurus, disertai sanksi berat jika tak dilaksanakan. Mental semacam inilah yang diistilahkan oleh Pramoedya Ananta Toer sebagai ‘jawanisme’, taat dan setia pada atasan secara membabi buta tanpa memikirkan pihak lain sama sekali (Vltchek & Indira, 2006: 45)
Kepatuhan dan Miskonsepsi Massal
Ketiadaan etos dan tanggung jawab yang benar dalam mendidik dan membangun relasi kakak dan adik kelas ini bukan semata-mata timbul karena senioritas, melainkan juga berasal dari akumulasi sikap pendidik selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Di dalam ruang kelas yang steril dari debat dan kritik, para pendidik berusaha agar kegiatan belajar berjalan semulus-mulusnya tanpa sanggahan dan debat yang dianggap hanya membuang-buang waktu. Siswa wajib menjawab pertanyaan yang dilemparkan secara pasti, benar, tanpa kurang satu titik atau koma. Jawaban yang berbeda diasosiasikan sebagai jawaban ‘salah’ dan jawaban yang ‘salah’ mengindikasikan bahwa siswa yang dimaksud tak dapat menangkap pelajaran dengan baik—eufemisme dari kata ‘bodoh’. Seperti kasus perintah tersebut, jawaban selain ‘siap!’ akan ditanggapi dengan makian yang lebih keras dan sanksi yang lebih berat.
Kasus-kasus yang konon telah menjadi rahasia umum itu, saya yakin, bukan pengetahuan yang asing bagi negara selaku institusi yang bertanggung jawab atas rancangan pendidikan secara holistik, termasuk menyiapkan lingkungan belajar yang ideal. Akan tetapi, dari keadaan demikian, kurikulum justru lagi-lagi menyodorkan kepatuhan sebagai resep manjur untuk membuat persamaan akan satu logika: logika para pendidik.
Secara sederhana, melalui resep kepatuhan ini, bukan guru yang diwajibkan memahami logika dan potensi unik dalam diri setiap siswa, tetapi sebaliknya. Siswalah yang dituntut berjuang mati-matian—bahkan sampai benar-benar meninggal dunia—mengubah paradigma yang ia miliki sebelumnya agar semirip mungkin dengan cara pandang sang guru. Celakanya, apabila seorang pendidik ternyata mempunyai miskonsepsi atas suatu isu, maka yang kemudian timbul adalah miskonsepsi massal yang akan sulit diubah, lebih-lebih jika terjadi di jenjang sekolah dasar.
Terdapat banyak kasus penyeragaman paradigma yang berujung miskonsepsi. Salah satunya terjadi dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Sejarah Wajib. Lebih kurang sembilan tahun terakhir sejak siswa diajak mempelajari soal-soal kedaulatan nasional dan integrasi, babak Gerakan 30 September 1965 konsisten dikutuk sebagai biang disintegrasi yang diotaki kelompok banaspati komunis. Pelajaran diarahkan pada usaha keras mengumpulkan sebanyak mungkin bukti bahwa hanya Partai Komunis Indonesia-lah yang bertanggung jawab atas terbunuhnya tujuh perwira Angkatan Darat dan bukan mengenal apa dan bagaimana Tragedi 1965 peristiwa yang logis dan berimbang berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang makin hari semakin terkuak.
Pengumpulan bukti ini lantas digunakan untuk mendukung pembantaian besar-besaran dan reproduksi kebencian terhadap kaum komunis dalam rangka “mengingatkan bahaya laten komunis”; dan siapa pun dalam konteks apa pun yang ingin membantah bahwa dalang G30S bukan PKI harus dipolisikan.
Pola tersebut menggambarkan bagaimana pendidikan sejarah di sekolah dasar dan menengah telah menutup diri terhadap kenyataan dan keterbukaan mengenai peristiwa sejarah katastrofial yang sekurang-kurangnya telah menewaskan 500 ribu hingga satu juta orang Indonesia tanpa peradilan. Cara dan pendekatan ini kontras dengan pendidikan di Jerman yang mengakui praktik kekejaman di masa kekuasaan Reich Ketiga secara terbuka atau kurikulum Amerika Serikat yang, kendati merasa berat, namun perlahan-lahan mulai mengajarkan siswanya tentang kekejaman perbudakan negro yang pernah berlangsung selama dua setengah abad.
Dari keterbukaan ini, sebuah ruang dialog yang memajukan kesetaraan dan kebebasan dalam menyatakan pendapat akan terbuka sehingga kemungkinan miskonsepsi semakin tipis. Sayangnya, pola sosialisasi ini justru baru dibuka di perguruan tinggi, di mana konsep-konsep yang telah tertanam dalam pribadi siswa sebelumnya berisiko besar berkonfrontasi dengan gagasan-gagasan baru yang hadir di dalam ruang-ruang dialog tersebut.
Pertanyaannya, jika ruang dialog yang terbuka dan bebas pretensi tak dibuka dengan alasan-alasan tertentu sejak sekolah dasar, dari mana siswa diajar memahami hakikat kebebasan yang sejati?
Memaknai Kebebasan, Memaknai Individu
Dalam kerangka kepatuhan, aspek-aspek pembebasan cenderung menjadi delusi romantis dan ideal namun bukan untuk dilaksanakan. Aspek-aspek pembebasan dipandang miring, menjadi kata ganti dari ketidakteraturan, kekacauan dan kerusakan. Hal ini tentu cocok dengan sikap patuh yang mensyaratkan ketidakbebasan dan pengekangan untuk mencapai tujuan. Ini pula yang menyebabkan jargon-jargon ‘kebebasan yang bertanggung jawab’ cenderung lebih laku, lebih keras digaungkan serta diunggulkan sebagai praktik kebebasan yang paling aman ketimbang kebebasan yang sejati.
Fabrikasi jargon kebebasan yang bertanggung jawab di Indonesia bukanlah barang baru dan aneh. Tiga dasawarsa Orde Baru secara aktif mengampanyekannya sebagai praktik kebebasan dalam masyarakat yang Pancasilais. Berbagai media dipergunakan, mulai dari televisi hingga buku-buku pelajaran. Contoh kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab melulu dicitrakan buruk dan punya akibat mencelakakan orang lain maupun diri sendiri. Sebaliknya, kebebasan yang bertanggung jawab melulu digambarkan sebagai keadaan yang tentram, dan damai—keadaan yang secara ambisius mau diwujudkan Orde Baru dalam segala dimensi.
Jargon ‘kebebasan yang bertanggung jawab’ bukan menjadi masalah ketika siswa memahami dan merasakan ‘kebebasan’ serta mampu memaknai tanggung jawab lewat tindakan konkret. Tetapi dalam praktik, kebebasan yang bertanggung jawab justru ditanamkan dalam diri siswa sebagai satu tandem yang seolah tidak terpisahkan. Karenanya, alih-alih dipahami, frasa tersebut justru menjadi semacam paradoks: siswa belajar makna ‘kebebasan namun sejatinya ‘tidak bebas’; siswa dipaksa mengerti akan ‘tanggung jawab’—dalam arti keterikatan akan sesuatu—namun harus tetap merasa ‘bebas’. Makna yang janggal ini tentu akan lebih sulit dan membingungkan ketika harus dipraktikkan dalam keseharian, khususnya menentukan kesempatan: kapan siswa harus menikmati ‘kebebasan’ dan kapan siswa harus ‘bertanggung jawab’. Akibatnya, baik dimensi kebebasan maupun tanggung jawab, keduanya terpaksa mengalami reduksi makna yang saling mendeformasi.
Masih tepatkah ‘kebebasan yang bertanggung jawab’ itu diajarkan di sekolah-sekolah?
Bukan ‘kebebasan yang bertanggung jawab’ yang menjadi masalah, melainkan dampak jargon itu yang menyebabkan siswa kerap merasa takut melanggar tanggung jawab saat ia harus menikmati kebebasan dan merasa bebas saat ia harus melaksanakan tanggung jawab. Dari pengalaman seperti ini, saya sependapat dengan Betty Luceigh yang berpandangan, “merupakan tanggung jawab setiap orang untuk mengenali dirinya sendiri terlebih dulu untuk tidak merasa kehilangan kebebasan yang ia miliki.” Karenanya, kebebasan mesti dipahami kembali dan dilepaskan dari slogan ‘tanggung jawab’ yang menyertainya; pun sebaliknya, tanggung jawab dipahami berdasarkan tindakan konkret tanpa harus dibebani janji manis bahwa ‘ketidakbebasan’ itu dilakukan dalam keadaan ‘bebas’.
Memberikan kesempatan kepada siswa memahami kebebasan dan tanggung jawab secara terpisah dan proporsional bagi saya adalah langkah yang adil untuk membuka kemungkinan tiap siswa kelak mampu memaknai secara tepat akan masing-masing nilai yang korelatif dengan kehidupan itu. Pemaknaan inilah yang memberikan arti lebih mendalam mengenai pengenalan akan diri sendiri dan peranan apa yang akan dibawa seorang siswa kepada masyarakatnya kelak.
Paradigma Baru atau Langkah Konkret Baru?
Dalam esainya yang terakhir, Ben menekankan bagaimana harapan memiliki daya yang begitu besar terhadap perubahan radikal. “Tanpa harapan, hanya sedikit yang bisa kita lakukan,” katanya. Saya tidak bisa menganggap pernyataan ini sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah. Tiga catatan empiris yang memotret kenyataan-kenyataan yang saya rasakan selama menempuh pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa untuk mengejar kemajuan dalam waktu satu dekade, pendidikan di Indonesia tidak memiliki harapan untuk sampai ke sana. Pun, sebagai anggota dari angkatan yang diagungkan sebagai generasi ‘Indonesia Emas 2045’, saya sendiri tidak yakin apakah angkatan saya benar-benar dapat diharapkan dan dibuktikan keunggulannya.
John Holt dalam hal ini benar ketika menyimpulkan bagaimana peranan sekolah membentuk generasi saya, “Sekolah cenderung menjadi tempat yang tidak jujur, juga tidak nyaman. Orang-orang dewasa mengajari anak-anak bukan dengan apa yang mereka pikirkan, melainkan dengan apa yang orang dewasa rasa harus mereka pikirkan” (Holt, 2010: 292). Oleh karenanya, saya tidak heran jika angkatan saya memang diciptakan sebagai ‘generasi penerus’, bukan ‘generasi pengubah’. Sebuah paradigma telah membawa sebagian terbesar generasi kami menjadi pasrah kepada nasib, termasuk kalau tanah air kami benar-benar bubar, kami pun hanya dapat berpasrah—dalam kelakar, bolehlah keadaan demikian itu sudah ‘ditakdirkan Tuhan’ (sic!).
Adakah generasi kami membutuhkan paradigma baru? Atas pertanyaan itu, izinkan saya untuk menyatakan pertanyaan balik, “untuk apa?” Ya, paradigma yang bagaimanapun—termasuk pendidikan yang diklaim ‘memerdekakan’ siswa itu—tidak akan membuat generasi kami jadi lebih unggul dari generasi sebelumnya. Satu-satunya keunggulan kami adalah ketahanan dan kemampuan beradaptasi dengan digitalisasi mondial yang semakin meluas ini. Lain dari itu tidak ada.
Oleh karenanya, langkah konkret baru jauh dibutuhkan untuk memberikan enlightment dan keberanian mendobrak keadaan yang direkonstruksi menurut cetak biru negara. Kepatuhan yang mengekang haruslah diwacanakan ulang dan dipertanyakan relevansinya, didukung daya bernalar kritis dan menggugat keadaan yang telah diamalkan dan mengonstatasi ketidaksetaraan. Inilah intisari ketiga catatan empiris yang telah saya tuliskan sepanjang Desember ini.
Sebagai refleksi atas perjalanan saya sebagai pelajar sekolah dasar dan menengah di Indonesia selama 12 tahun, tiga catatan empiris saya tentu berbeda dengan siswa lain. Tantangan yang dihadapi setiap siswa di Indonesia pun belum tentu tercakup dalam catatan panjang ini. Karenanya, untuk tiap pelajar Indonesia yang telah bersedia membaca tiga catatan ini, saya ingin mengajak Anda semua merumuskan abad kita yang akan datang: abad 100 tahun Indonesia Merdeka, abad yang membuat tiap orang merasakan kemerdekaan, bukan hanya membayangkan dan mengharapkan.
Tugas kita bukan mencontoh para pendahulu, melainkan mengoreksinya secara besar-besaran untuk mengejawantahkan cita-cita kemerdekaan, persatuan, dan keadilan sosial yang kini direifikasi menjadi seolah utopis.
Innallaha la yughayyiru maa bi qaumin hatta yughayyiru maa bi anfusihim (Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu mengubah keadaannya sendiri). ***
Chris Wibisana adalah pelajar dan peneliti sejarah independen .