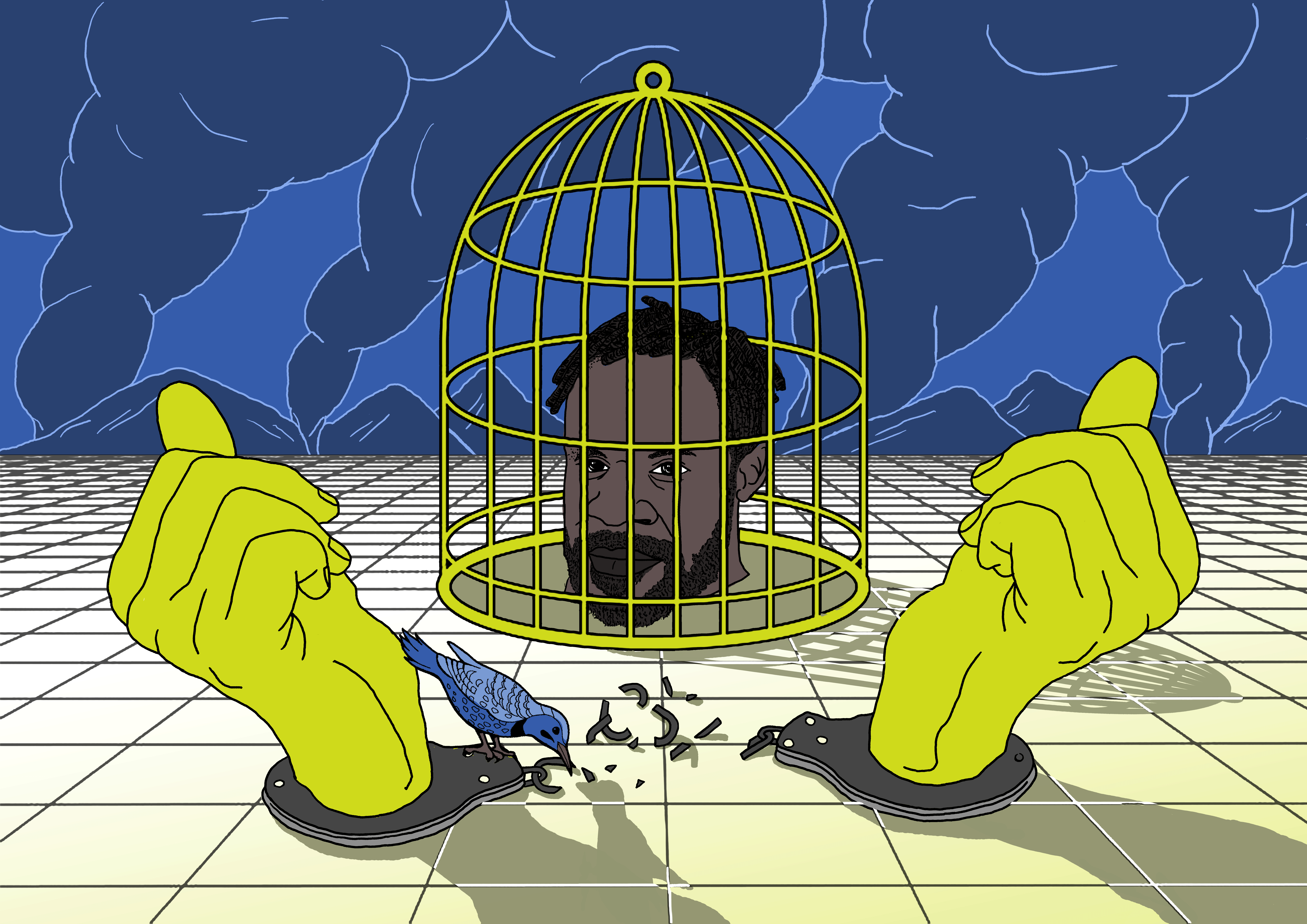Ilustrasi oleh Jonpey
[Peringatan: beberapa deskripsi di dalam tulisan ini mungkin akan mengganggu kenyamanan pembaca]
MUSIM semi, 19 April 1989. Jam sembilan malam, puluhan remaja belasan tahun keturunan Afrika-Amerika dari Harlem bagian timur bergerombol menuju Central Park Manhattan, New York City, Amerika Serikat. Tak berapa lama terjadi keributan kecil. Dua anggota gerombolan berkelahi. Tiba-tiba sirine mobil polisi memecah keriuhan. Anak-anak itu lari kocar-kacir: melompati pagar beton; bersembunyi di semak-semak; bergelinding menuruni bukit. Tapi toh polisi berhasil menangkap belasan di antaranya.
Di malam yang sama, sekitar pukul setengah dua dini hari, perempuan kulit putih bernama Trisha Meili (28), bekerja sebagai bankir investasi, sedang joging di sudut lain Central Park saat tiba-tiba seorang lelaki datang menyerang. Saksi menemukan Meili di semak hutan dengan kondisi mengenaskan dan langsung menelepon polisi.
Ia tak hanya diperkosa, tapi juga dipukuli secara brutal. Tengkoraknya retak dan kehilangan banyak darah. Ia koma selama 12 hari. Nyawanya nyaris melayang.
Beberapa jam kemudian, Kepala Unit Kejahatan Seksual Kejaksaan Manhattan, Linda Fairstein, datang ke tempat kejadian perkara. Seorang polisi lalu mengabarkan ke Linda kalau malam itu juga mereka menangkap belasan bocah kulit hitam. Segera Linda berkesimpulan: merekalah pelaku penyerangan dan pemerkosaan Meili. Agar tudingannya sahih, Linda mengubah waktu dan rute joging Meili saat merekonstruksi kejadian.
Lima pemuda, kelak dikenal sebagai ‘Central Park Five’, Kevin Richardson (14), Raymond Santana (14), Antron McCray (15), Yusef Salaam (15), dan Korey Wise (16) lantas divonis bersalah meski dalam persidangan tidak ada bukti ilmiah seperti DNA, sidik jari, darah, atau sperma. Putusan hakim didasarkan pada pemeriksaan awal yang penuh intimidasi.
Para pemuda ini baru bebas pada 2002 setelah Matias Reyes, seorang pembunuh dan pemerkosa berantai, mengakui kalau dialah pelaku sebenarnya.
Saat ini, kasus tersebut kerap dijadikan contoh ‘rasisme yang dilembagakan’. Puluhan tahun berlalu dan rasisme yang dilembagakan masih sangat nyata. George Floyd, seorang pria kulit hitam, meninggal dunia setelah lehernya ditindih dengan lutut oleh polisi bernama Derek Chauvin sampai kehabisan napas. Ia dituding membeli rokok dengan uang palsu. Pembunuhan ini memicu demonstrasi besar-besaran menantang rasisme dan brutalitas polisi, tak hanya di Amerika tapi juga berbagai belahan dunia lain. Gerakan solidaritas bangkit dengan membawa slogan ‘Black Lives Matter’.
Di Indonesia, slogan tersebut diadopsi menjadi ‘Papuan Lives Matter’. Seperti namanya, gerakan ini menentang rasisme dan diskriminasi yang dialami oleh orang Papua. Upaya tersebut juga dilakukan untuk mendapatkan respons internasional terhadap kasus kekerasan dan kriminalisasi kepada para aktivis Papua.
Penangkapan dan kriminalisasi terhadap aktivis Papua marak terjadi setelah demonstrasi besar-besaran menentang rasisme tahun lalu. Demonstrasi itu sendiri dipicu oleh tindakan rasis aparat dan warga terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus 2019. Para mahasiswa dituding merusak Merah Putih yang dipasang di depan asrama—dan setelah diinterogasi, ternyata tak terbukti.
Rangkaian penangkapan bermula di Jakarta. Enam orang ditangkap, kemudian menjalani sidang kurang lebih delapan bulan. Mereka lantas dovinis hukuman penjara delapan sampai sembilan bulan karena dituding makar. Mereka semua kini sudah bebas. Pengadilan para tahanan yang dijuluki ‘The Jakarta Six’ ini merupakan kasus politik Papua pertama yang diperkarakan di luar Papua.
Atas tudingan yang sama, tujuh aktivis Papua yang bersidang di Balikpapan, Kalimantan Timur, divonis penjara sepuluh sampai sebelas bulan pada pekan lalu. Mereka, disebut ‘Balikpapan Seven’, ditangkap di Jayapura. Karena polisi tak mau ada kerusuhan, persidangan dipindah ke Pengadilan Negeri Balikpapan meski tanpa persetujuan keluarga.
Penangkapan ini adalah bentuk nyata ketidakadilan. Penggunaan pasal makar adalah cara ugal-ugalan untuk menghukum orang yang menyampaikan aspirasi dalam negara demokrasi. Belum lagi di penjara mereka diremehkan, disepelekan, diintimidasi, serta dianggap jorok dan bau. Namun toh kekuatan dan harapan mendapatkan keadilan tetap ada dan berlipat ganda. Itu tampak ketika tiga aktivis Papua dari The Jakarta Six mengisahkan dirinya kepada saya.
Ambros: Soal Kemanusiaan, Ini Tanggung Jawab Kami Orang Papua Sama-Sama
Juni 2012, ketika lulus dari sekolah menengah di Wamena, Ambrosius Mulait Yakobus bertolak ke Jayapura untuk mendaftar kuliah. Ia mendaftar di dua kampus sekaligus: Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) jurusan informatika dan Universitas Cendrawasih (Uncen) jurusan komputer. Dua-duanya tidak lulus. Tak berselang lama Ambros mendapat kabar kalau bapaknya sakit terserang stroke. Ia segera pulang. Setelah tiga hari dirawat di rumah sakit, sang bapak meninggal. Ia meninggalkan Ambros, istri, dan empat anak.
Situasi itu sempat membuat Ambros hilang harapan untuk melanjutkan studi. Ia pikir tak ada cukup biaya untuk mendaftar apalagi menyelesaikan kuliah. Tapi, keinginan untuk mengenyam bangku pendidikan masih kerap muncul. Sekitar dua minggu, ia terus saja memikirkan hal itu. Ia lalu memutuskan: bagaimana pun caranya, harus kuliah. Ambros kemudian berjualan noken buatan mamanya. Ada yang dihargai Rp600 ribu, ada yang Rp400 ribu, tergantung ukuran. Ambros berhasil menjual sepuluh, dia dapat Rp6 juta. Ia juga dapat tambahan biaya Rp14 juta dari hasil jual babi.
Ambros memang cukup lihai urusan berdagang. Ia sudah melakukan itu sejak SMP. Setelah pulang sekolah, ia biasanya berdagang telepon genggam bekas. “Itu paling setahun lebih,” ingat Kris Walilo, kawan karib Ambros di SMP Negeri 2 Wamena.
Ketika uang kuliah sudah terkumpul, ia mengalihkan perhatian ke Pulau Jawa. Ambros memilih berkuliah ke Jakarta. Ia mendaftar di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) dan berhasil diterima. STIPAN adalah salah satu kampus yang banyak dihuni anak-anak Papua. Pemerintah provinsi menyediakan beasiswa. Biaya kuliahnya cukup mahal, satu semester bisa sampai Rp24 Juta, sudah termasuk ongkos asrama.
Sejak awal kuliah Ambros sudah aktif berorganisasi di Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) dan Ikatan Keluarga Mahasiswa Wamena. Mahasiswa Papua rata-rata ikut paguyuban ini, apalagi yang tinggal di asrama.
Pada 2014, mahasiswa yang dijanjikan mendapat bantuan pembiayaan kuliah dari tahun sebelumnya terancam dikeluarkan karena pemerintah Kabupaten Jayawijaya ternyata belum juga membayar uang kuliah ke pihak kampus. Mereka bahkan sudah tak diperbolehkan tinggal di asrama sejak enam bulan terakhir. Kabar yang sampai ke telinga Ambros, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pilkada, sementara alasan resmi adalah pemerintah kabupaten mengalami defisit anggaran.
Ambros dan kawan-kawan akhirnya mengorganisasikan aksi protes di bulan Juni. Ini barangkali aksi pertama Ambros yang cukup militan. Mereka menduduki kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua di Jalan Suryo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selama tiga hari. “Kami menjadikan [kantor] rumah sementara,” kata Ambros. Pada Rabu 25 Juni dini hari, kepala kantor penghubung Ricky D. Ambrauw mendatangkan polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Para mahasiswa diangkut paksa. Ada sekitar 20 orang yang ditahan di polres. “Kami belum tahu tidur atau pulang. Tetapi kemungkinan kami ditahan untuk tidur di sini,” Kata Musa Mawel, salah satu mahasiswa STIPAN dari Jayawijaya yang diangkut paksa kepada Jubi.
Kabar tersebut sampai ke Tanah Papua. Besoknya, orang tua mahasiswa dan beberapa aktivis menggalang aksi solidaritas: mendatangi kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya. Mereka meminta bupati bertanggung jawab dan menepati janji akan membiayai para mahasiswa. Jika pemda tak sanggup membiayai, kata mereka, sebaiknya para mahasiswa dipulangkan saja. Respons pemda tentu normatif. Mereka juga bilang baru tahu kalau para mahasiswa yang terlibat aksi di Jakarta ditahan.
Beberapa mahasiswa Papua di STIPAN memutuskan pulang untuk mengurus masalah ini. Seingat Ambros, waktu itu ada sembilan orang yang berencana berangkat, termasuk dirinya. Tujuh orang menumpang Hercules, sementara Ambros dan Musa Mawel naik pesawat komersial. Ambros, juga kawan-kawan yang lain, cuma mau meneruskan sekolah, meneruskan jalan menuju cita-cita. “Kami mau kuliah tapi kendala biaya,” pilu Ambros.
Ambros dapat uang beli tiket dari kakak perempuannya, tiga setengah juta. Tapi Ambros tak jadi ikut pulang karena ijazahnya ketinggalan. Akhirnya cuma Musa Mawel yang berangkat. “Waktu itu nasib bagus, agak murah tiketnya. Kami beli tiket sisanya itu dibantu sama teman-teman ke Jayapura,” kata Ambros. Sampai Jayapura, mereka nanti dibantu lagi oleh kawan-kawan untuk berangkat ke Wamena.
Para mahasiswa ke sana kemari menemui pejabat pemerintah, dari Gubernur Lukas Enembe sampai Bupati John Wempi Wetimpo–saat itu sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya, sekarang menjabat Wakil Menteri PUPR. Para pejabat rata-rata cuma menanggapi sambil lalu. Karena itulah para mahasiswa memutuskan menggelar unjuk rasa. Untung usaha para mahasiswa tak sia-sia. Selang dua hari kepulangan mereka dari Papua, informasi baik datang: Gubernur Enembe sudah memerintahkan Biro Otonomi Khusus untuk membiayai kuliah mereka di STIPAN sampai selesai. “Segera kami rangkul teman-teman dari Papua yang biaya bermasalah untuk registrasi,” kata Ambros.
Di lingkaran perkawanan, Ambros memang dikenal sebagai aktivis mahasiswa ulet. Dihitung-hitung, sudah delapan tahun dia terlibat dalam gerakan mahasiswa. Apalagi kalau untuk urusan Papua, ia sebisa mungkin meluangkan waktu. “Walaupun kampusku sering tekan. Saya bilang: soal kemanusiaan ini tanggung jawab kami orang Papua sama-sama.”
Ambros memilih berkuliah di sekolah pemerintahan bukan tanpa alasan. Dia jengkel betul dengan para pejabat di daerahnya terutama saat menghadapi isu hak asasi manusia. “Dalam merespons pelanggaran HAM pemerintah itu berbeli-belit dan membuat kami kecewa,” katanya.
Kekecawaan Ambros kian tebal setiap hari karena pemerintah masih saja mengerahkan militer dalam setiap penyelesaian konflik di Papua. Ambros punya pengalaman pahit dengan militer. Mamanya pernah bercerita kalau 43 tahun yang lalu sang paman ditembak mati. Itu sebab ia juga tak bersimpati kepada tentara maupun polisi sampai sekarang. “Orang Papua itu punya ingatan traumatik yang panjang,” Ambros menekankan, diam sebentar, lalu melanjutkan, “misalnya orang Papua dibunuh, ditembak. Kami lakukan protes itu malah balik ditembak.” Itu juga yang membuat banyak orang Papua lebih memilih diam, katanya.
Permasalahan serius lain yang sering dialami Ambros dan kawan-kawannya adalah perlakuan rasis yang datang dari berbagai pihak, termasuk pejabat Jakarta. Ambros masih ingat betul ucapan Luhut Binsar Pandjaitan tahun 2016 lalu saat menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Luhut bilang, kalau mau merdeka, pergi saja ke Melanesia.
Lima bulan setelah penyataan itu, pada 17 Agustus, peristiwa penyerangan asrama Papua terjadi di Yogyakarta. Empat ormas: Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia, Pemuda Pancasila, Paksi Katon, dan Laskar Jogja mendatangi asrama di siang bolong. Mereka sampai hati meneriaki para mahasiswa “monyet” dan berbagai ujaran rasis yang menyayat-nyayat. Mereka yang bersekolah di luar Papua memang berulang kali mengalami hal serupa. “Kalau dibilangi monyet, saya secara pribadi marah. Marah sekali. Sangat marah,” kata Ambros. “Sampai kuliah di sini lebih parah rasismenya.”
Pernah sekali waktu ia naik angkutan kota. Orang yang duduk di sampingnya sampai pindah tempat. Ambros merasa karena stigma bau badan. Dia cuma bisa diam, tapi “dalam hati memang sakit juga. Mau bagaimana lagi.”
***
Kampus Ambros masih kental dengan budaya senioritas, demikian pula sikap Ambros ke para juniornya. Kadang ia menghukum seorang junior untuk push up hanya karena main selonong saat lewat di hadapannya. “Kalau kami salah sedikit, dia tegur langsung,“ kata Yosafat Elopere, mahasiswa STIPAN setahun di bawah Ambros. Ia pernah sekali dihukum push up oleh Ambros. Sikap Ambros kalau menegur juniornya diterangkan Yosafat dengan ringkas: tegur, marah, marah, selesai. “Dia tidak pendendam,” katanya.
Kalau di mata adik-adiknya di kampus Ambros dikenal sebagai sosok yang tegas, maka di lingkungan kawan seangkatan ia lebih banyak bercanda. Ambros kerap menjadikan peristiwa yang sehari-hari terjadi di asrama sebagai bahan lelucon, dari makanan sampai tingkah para penghuni. “Tegasnya kalau ke adik. Kalau ke teman angkatan tidak mungkin,” Kata Kris Walilo, teman SMP Ambros. Ia bertemu Ambros lagi di kampus.
Baik Yosafat dan Kris sepakat tentang satu hal tentang Ambros: rokoknya kuat sekali, sehari bisa habis tiga bungkus. Satu lagi, Ambros kuat sekali minum kopi. Sudah seperti makan, minimal tiga kali sehari. “Tiga gelas kurang kalau dia sudah duduk lama,” kata Yosafat.
Di antara suka duka pertemanan itu, sebagaimana pemuda pada umumnya, Ambros juga memiliki kisah asmara. Tanggal 30 Maret 2019 di LBH Jakarta, di sela ‘Bakar Batu Solidarity’, sebuah aksi penggalangan donasi bagi para pengungsi Nduga yang terusir karena tentara, mata Ambros diam-diam memperhatikan seorang perempuan bernama Dessy Ariks, mahasiswi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, asal Kota Sorong. Ambros menitip salam ke kawannya yang juga karib Dessy. Kepada temannya itu Ambros sekalian meminta nomor Whatsapp Dessy. Begitu dapat, ia langsung menghubungi dan mengajak kenalan. Berawal dari basa-basi meminta pertemanan di Facebook sampai mengajaknya jalan-jalan ke Ancol.
Dessy baru masuk kuliah tahun 2018, sedangkan Ambros sudah melanjutkan pendidikan ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Suatu hari pada bulan Mei, Ambros memberanikan diri mengajak Dessy ke Puncak, Bogor. Di situlah ia menyatakan perasaannya. “Adek mau tidak jadi pacar?” kenang Desi mengulang perkataan Ambros dengan senyum malu-malu. Perempuan berwajah mungil itu mengiyakan. Sebenarnya sejak pertama kali jumpa di acara bakar batu, Dessy juga menaruh rasa pada lelaki berambut keriting gimbal pendek itu. “Ambros orangnya baik, penyayang, manja-manja,” katanya lagi, masih dengan senyum malu-malu dan tertunduk-tunduk, menceritakan alasan kenapa dia suka sama Kakak Ambo–panggilan sayangnya.
Betapa pun kasmarannya Ambros, dorongan sebagai seorang aktivis, setidaknya sampai saat ini, tetap lebih mendominasi. Ia tak sungkan mengajak sang kekasih untuk ikut aksi Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme di Jakarta pada 22 dan 28 Agustus 2019. Aksi ini diselenggarakan untuk merespon kerusuhan yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Asrama diserang oleh beberapa anggota Pemuda Pancasila (PP) dan Front Pembela Islam (FPI). Beberapa warga sipil ikut-ikutan melempar batu dan melontarkan umpatan rasis. Tak ketinggalan aparat keamanan yang ada di situ: TNI, Polri, Satpol PP juga terlibat. Mereka menyerang dengan kata dan tindakan.
Mahasiswa Papua di Jakarta tergerak melakukan aksi protes sebagai wujud solidaritas. Dessy ikut karena alasan yang sama, bukan semata-mata karena diajak sang pacar. Pada aksi itu Ambros bertugas sebagai juru bicara mendampingi Suryanta Ginting, salah satu anggota The Jakarta Six.
Dua hari sesudah aksi, Ambros mendengar kabar bahwa dua temannya, Charles Kossay dan Dano Anes Tabuni, ditahan di Polda Metro Jaya. Segera ia meminta kawan-kawannya berkumpul di Asrama Wamena di Jalan Jengki, Kebon Pala, Jakarta Timur. Sekitar jam sembilan malam, mereka memutuskan langsung bergerak menuju Polda Metro Jaya. Mereka bermalam di depan polda, tidur di trotoar jalan. Sampai besok pagi, mereka sesekali berorasi menuntut pembebasan Charles dan Dano.
Polisi meminta lima orang mahasiswa untuk masuk berdialog. Ambros salah satunya. Baru melewati pintu utama ia curiga ada yang tidak beres. Bayangan dirinya akan ditangkap berseliweran di kepala. Dan benar saja, “kami belum sampaikan maksud dan tujuan, mereka langsung tunjukkan surat penangkapan atas nama Ambros dengan Isai Wenda.” Ambros dan Isai diborgol, digiring naik ke mobil. Mereka dibawa ke Mako Brimob Depok menyusul Charles dan Dano yang sudah duluan ditahan di sana. Dua lagi yang kena tangkap hari itu adalah Suryanta dan Arina Elopere.
Dano: Hati Nurani Saya Ingin Bebas dari Penindasan
Pada sebuah siang yang terik, 20 Februari 2020, para tahanan politik (tapol) Papua masuk ke ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sudah empat bulan para tapol menjalani sidang. Dano Anes Tabuni, salah satu di antaranya, lebih tegap dan berotot dibanding tahanan lain. Ia kemudian membuka baju begitu meletakkan nokennya di bangku paling depan. Badannya penuh tulisan berwarna putih kebiru-biruan. Awal terlihat seperti cat, tapi kalau didekati dan dibaui ternyata odol. Lama-kelamaan tulisan itu mengering dan retak-retak. Bagian depan tertulis: tikus sampah monyet. Di belakangnya: Aku sampah tidak jelas.
Melihat tulisan di badan kedua tahanan itu, salah seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegur. Tentu saja Dano tak menghiraukan karena itu pesan yang perlu mereka sampaikan ke publik dan dalam rangka protes. Tulisan itu adalah respons atas komentar Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD beberapa hari sebelumya mengenai laporan tapol Papua yang diserahkan oleh tim Veronica Koman kepada Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Australia. Dokumen itu berisi nama dan lokasi 57 tapol Papua yang dikenakan pasal makar. Selain itu, ada 243 nama korban sipil yang meninggal selama operasi militer di Nduga sejak Desember 2018. Menkopolhukam bilang kalau data itu hanyalah sampah. Dua hari berselang dia memperbaiki kata-katanya sendiri meski nuansanya masih sama.
Banyak yang menyayangkan pernyataan Mahfud. Salah satu pengacara para tahanan bilang sebaiknya Mahfud dipecat saja.
Sidang belum juga dimulai meski para tapol sudah ada di ruangan nyaris tiga jam. Persidangan masih menunggu saksi dari jaksa yang belum juga muncul. Sementara itu Dano asyik bersenda gurau dengan sang istri, Yumilda Chika Tua, perempuan Kupang yang selalu terlihat bersemangat dan tak pernah alpa di tiap persidangan. Keduanya duduk melantai di depan ruangan, atau di sudut mana pun di pengadilan. Hampir di tiap persidangan istrinya duduk paling depan.
Sekitar pukul tiga sore sidang dibuka, tapi hanya untuk ditunda lagi karena yang ditunggu-tunggu ternyata tidak bisa hadir. Sidang para tapol Papua biasanya diselenggarakan pada hari senin. Kalau ditunda, biasanya diundur ke hari kamis.
Para terdakwa dituding makar karena dalam demonstrasi pada 22 dan 28 Agustus 2019 mereka menyerukan referendum dan mengibarkan Bintang Kejora. Surya mengatakan dalam aksi itu banyak sekali orang datang untuk bersolidaritas dan tidak ikut dalam rapat-rapat sebelumnya. Maka jika ada yang mengibarkan bendera, itu adalah spontanitas massa. “Dan saya sudah sampaikan ke polisi tidak ada perencaan pengibaran bendera,” tekan Surya, yang bertanggung jawab sebagai juru bicara di aksi itu.
Barang bukti yang diperlihatkan JPU adalah topi, kaos abu-abu usang dan satu bendera yang sama-sama bergambar Bintang Kejora. JPU mengangkat barang itu sembari bertanya kepada para saksi, “apakah saudara saksi melihatnya saat aksi?” Rata-rata saksi ragu-ragu untuk mengatakan pernah. Jelas tak ada yang bisa mengingat dengan baik detail saat demonstrasi seperti itu. Begitu hakim mengatakan, “kalau pernah bilang pernah, kalau tidak bilang tidak”, barulah para saksi menjawab “tidak pernah.”
Para saksi dan terdakwa dipanggil ke depan meja hakim untuk melihat alat bukti rekaman video dan foto. Nanti saksi akan menjawab lagi, “pernah” atau “tidak” melihat apa yang terekam dalam video. Pada sesi itu Dano kadang bertingkah seperti anak-anak: mendorong-dorong temannya untuk maju terlebih dulu dan dia di belakang hanya mengintip rekaman sebentar atau membikin sesuatu. Pernah satu kali, ia malah berfoto dengan pengacara sementara yang lain serius menyaksikan video.
Sidang lebih sering berjalan dengan santai, bahkan penuh tawa, jika jawaban para saksi membingungkan atau tak sesuai dengan pertanyaan hakim. Saat hakim mengajukan pertanyaan detail, seperti berapa jarak saksi dari kerumunan demonstrasi; apakah benar ada bendera; berapa bendera yang dilihat; berapa jumlah orang yang ikut aksi; adakah seruan referendum; dan apakah saksi melihat para tahanan ini mengucapkannya, tak ada yang menjawab dengan pasti. Sidang yang paling riuh oleh gelak tawa terjadi ketika JPU menghadirkan saksi penyewa mobil komando. Meski raut mukanya nampak gugup, tapi cara menjawabnya enteng sekali bak di tongkrongan. Ia kadang menoleh ke belakang lalu nyengir ke arah kawannya yang duduk bangku peserta sidang.
Perdebatan yang sengit antara JPU dan pengacara—seperti di persidangan lain—hampir tak ada. Interupsi juga tak banyak terlontar. Baru ketika saksi ahli bahasa dari JPU memberikan keterangan suasana sidang menegang. Bolak-balik pengacara menanyakan apa makna ‘referendum’ dan yel-yel ‘Papua bukan merah putih’. Sang ahli cuma menjelaskan bahwa teks itu baru bermakna jika ditempatkan ke dalam konteks. Argumennya berputar di situ-situ saja. Nampak kejengkelan di muka para peserta sidang, termasuk Istri Dano. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras) juga ikut merespon dengan mengatakan kalau sang ahli tidak kompeten, ditambah lagi keterangannya dalam berkas perkara salin-tempel.
Demikianlah suasana sebelum sidang dilakukan secara virtual karena pandemi COVID-19. Setelah Corona, hakim, JPU, dan kuasa hukum terdakwa berada di ruang pengadilan, sementara para terdakwa di rumah tahanan masing-masing.
Waktu para tahanan masih mengikuti sidang di PN Jakpus, ketika selesai bersidang, mereka diberikan kesempatan sekitar setengah jam untuk meladeni pertanyaan-pertanyaan para wartawan. Kadang itu digunakan untuk membaca puisi hingga berorasi.
Dalam satu kesempatannya, Dano memberikan ucapan belasungkawa atas kematian Andy Ayamiseba, tokoh penting dalam gerakan West Papua (terma yang merujuk ke Papua dan Papua Barat dalam gerakan kemerdekaan), salah satu pendiri WPNCL (West Papua National Coalition Liberation atau Koalisi Nasional West Papua untuk Pembebasan). Sejak 2014, WPNCL bergabung menjadi anggota Persatuan Gerakan Pembebasan West Papua atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Jabatan terakhir Andy di ULMWP adalah Wakil Ketua I komite legislatif. Andy Ayamiseba sebelumnya lebih dikenal sebagai manajer sebuah grup band legendaris Papua, Black Brothers.
“Salah satu pejuang keadilan untuk rakyat Papua telah pergi pada tanggal 21 Februari hari Jumat kemarin, dan seluruh rakyat Papua, kami juga, merasa berduka cita,” Dano memulai pidato. Hari itu dia tidak menghiasi badannya seperti biasa dan memilih berpakaian serba hitam untuk mengenang sang tokoh. Dano memang mengaguminya. Semakin lama menceritakan sosok Andy, air mata kian tak terbendung meski berusaha disembunyikan. “Hari ini kami kehilangan salah satu tokoh pejuang keadilan rakyat Papua yang bermartabat,” Dano menutup pidatonya.
Apa yang dilakukan Andy, bagi Dano, adalah perjuangan panjang untuk melepaskan diri dari penindasan. Ia bilang ujung dari semua itu ialah kebebasan: bebas untuk hidup di kampung sendiri dan melindungi tanah sendiri. “Makanya tanpa saya tidak mengerti sama sekalipun, saya tetap mendukung,” jelas Dano, yang baru bisa baca di kelas empat sekolah dasar.
***
Keterlibatan Dano dalam aktivisme dimulai tahun 2008. Kala itu ia bersekolah di SMK Yapesli Wamena. Saat peringatan Hari Pribumi Internasional di Lapangan Sinapuk, Wamena, 9 Agustus 2008, terjadi penembakan terhadap Opinus Tabuni. Ketika itu Dewan Adat Papua (DAP) menginisiasi sebuah demonstrasi tanggal 17 September. Mereka long march dari Waena Jayapura menuju gedung DPR Papua. Perkiraan Dano, yang turut serta dalam demonstrasi, massanya tidak sebanyak di Lapangan Sinapuk.
Satu bulan berselang, aktivis muda Papua menggelar demonstrasi di Expo Waena Jayapura, mendukung peluncuran International Parliamentarians for West Papua atau Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) yang diselenggarakan di London Inggris pada 15 Oktober. IPWP dibentuk untuk menggalang dukungan gerakan kemerdekaan West Papua ke parlemen internasional. Agenda lain IPWP adalah menggagas International Lawyers for West Papua (ILWP).
Di waktu yang bersamaan, terjadi gelombang eksodus mahasiswa Papua dari Manado dan Jawa-Bali. Mereka yang kembali ke Papua membangun tenda di lapangan makam seorang tokoh kharismatik yang dibunuh Kopassus, Theys Eluay, di Sentani. Empat hari setelah peluncuran IPWP, mereka dan para aktivis muda Papua lainnya, bersama faksi-faksi politik West Papua, membentuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di aula Sekolah Tinggi Teologi Walter Post.
Dano, masih bocah sekolah menengah, berkontribusi menyebarkan pamflet aksi di sekolah-sekolah. Tindakan yang kemudian membuatnya diburu intelijen. “Tahu dari kakak polisi, lalu saya lari tidak ikut ujian nasional,” katanya. Dano sampai ke Jakarta dengan bantuan seorang kawan. Pelarian itu membawanya kepada jalur penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dano tak mau jadi TKI dan memilih kembali ke Papua. Tanggal 16 September ia sampai dan tinggal di Kampung Harapan, Sentani, Jayapura. Dua bulan kemudian, di kampung itu terlaksana Kongres 1 KNPB. Visi kongres ini adalah memperkuat simpul-simpul perjuangan. Selama di Jayapura ini ia lima kali ikut unjuk rasa.
“Hati nurani saya ingin bebas dari sebuah penindasan yang terjadi di Papua,” katanya, menjelaskan kenapa masih tetap terlibat aktivisme meski pernah diburu aparat.
Bepak Dano sebenarnya tidak sepakat dengan aktivitas anaknya ini. Tapi beberapa pamannya merestui dan bahkan memberikan dukungan. Berkat bantuan pamannya pulalah ia sekali lagi ke Jakarta. Kali ini bukan dalam rangka melarikan diri, namun mengadu nasib.
Dano mulanya bekerja sebagai satuan pengaman (satpam) di Kator Pelayanan Pajak Pratama Pademangan, Jakarta Utara. Di situ ia bertahan selama tiga tahun. Pernah juga ia bekerja sebagai calo Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Terakhir, ia bekerja di perusahaan penyedia jasa internet PT Parsaoran Global Datatrans (HSP Net). Kebetulan salah satu direksi HSP Net satu gereja dengan Dano di GPPI (Gereja Pusat Pantekosta Indonesia) Pondok Daud, Pancoran.
Dano memang pemuda yang aktif dalam pelayanan gereja. Di sana pula ia bertemu dengan sang istri, Chika. Mereka bersama mengurus Persekutuan Oikumene Generasi Yosua (POGY), sebuah forum kerohanian bagi mahasiswa Kristen Papua di Jakarta. Pelayan firmannya adalah Arina Elopere (satu-satunya perempuan dari The Jakarta Six). Tahun 2018, Dano dipilih menjadi dewan penasihat POGY. Dari sinilah ia mulai bersinggungan dengan aktivis mahasiswa Papua di Jakarta.
Bagi para pelajar yang baru datang dari Papua, Dano adalah salah satu sosok panutan, setidaknya begitu yang dilihat sang Istri. “Selalu mengarahkan yang baik-baik,” kata Chika. Ia juga mengatakan Dano suami yang penyayang meski dari luar terkesan cuek, tegas, dan jauh dari persona romantis. “Saya, kan, cengeng, dia bisa baca situasi dan bisa langsung tebak.”
Saat aksi menentang rasisme Agustus tahun lalu, Dano mengambil tugas sebagai koordinator lapangan. Ini kali kedua ia terlibat demonstrasi di ibukota. Demonstrasi pertamanya di Jakarta adalah aksi solidaritas korban Nduga. Demonstrasi menentang rasisme itu dilakukan da kali, yang pertama bersamaan dengan Aksi Kamisan, tanggal 22 Agustus; yang kedua 28 Agustus.
“Saya sampaikan bahwa kami tidak anarkis. Sekalipun dibilangi monyet, kita tunjukkan orang Papua punya martabat,” Kata Dano, mengulang pernyataannya waktu aksi.
30 Agustus malam, Dano berada di asrama mahasiswa Papua dekat Universitas Indonesia, Depok. Ketika itu kelompok ini membahas situasi mahasiswa setelah demontrasi karena mulai muncul intimidasi. Rumah Dano, misalnya, sempat kedatangan orang tak dikenal 29 Agustus pagi. Ia juga merasa selalu ada orang yang membuntutinya. Firasatnya buruk. Sekitar setengah delapan malam, saat memasak daging kelinci, firasat Dano jadi kenyataan. Polisi tanpa seragam datang menangkapnya. Malam itu Dano dan Charles langsung dibawa ke Polda Metro Jaya, lalu dikirim ke Mako Brimob jam sebelas malam. Mereka semua ditahan dan disangkakan pasal makar.
Akumulasi pengalaman ini membawanya pada satu kesimpulan: “Dulu saya tidak pernah pikir orang Indonesia itu baik. Saya pikir semua jahat sama orang kulit hitam. Termasuk kawan Surya juga saya pikir dia itu orang jahat,” kata Dano. Ia baru sepenuhnya menyadari bahwa baik buruknya orang tidak berdasarkan warna kulit.
Suryanta Ginting: Banyak Aktivis HAM, tapi Tidak Menghargai Orang Papua
“Setelah datang ke sana [Papua], bertemu dengan mereka, wajar kecurigaan itu,” aku Suryanta Ginting, mengonfirmasi pernyataan Dano. Surya mengunjungi Tanah Papua dalam rangka merintis Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP). Ia mengatakan demikian setelah mendapat banyak cerita langsung dari orang Papua.
Salah satunya tentang cerita orang asli Papua yang dibunuh dengan gampangnya.
Senin, 14 April 2020, Eden Armando Debari (19) dan Rony Wandik (23) tengah memancing di Kali Biru, dekat areal pertambangan PT. Freeport Indonesia, Kabupaten Mimika. Dua orang itu mati kena tebak dari anggota Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) TNI. Mereka mengira dua pemuda itu bagian dari kelompok separatis yang hendak menyerang Freeport. Sementara menurut keterangan keluarganya, Eden dan Rony sudah sering memancing di tempat itu.
Selain itu, dalam laporan Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati: Pembunuhan dan Impunitas di Papua, Amnesty International Indonesia mencatat kasus pembunuhan di Papua yang terjadi di luar hukum periode Januari 2010 sampai Februari 2018 sebanyak 69 kasus. Korban jiwa 95 orang, 85 di antaranya orang Papua. 41 kasus pembunuhan terjadi saat pihak keamanan menangani aksi protes yang berujung kerusuhan dan karena salah tangkap. 28 kasus lain saat pihak keamanan menangani demonstrasi damai yang politis, dalam upacara pengibaran bendera, serta perayaan keagamaan atau peringatan acara tertentu.
Polisi terlibat dalam 34 kasus, sementara militer 23 kasus. 11 kasus melibatkan keduanya. Satu kasus lain melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak perlu oleh pihak keamanan menjadi sebab utamanya.
Paska kerusuhan Wamena, 23 September 2019, Tirto dan Jubi melaporkan sebelas orang Papua meninggal, alias berbeda dari laporan pemerintah yang hanya menyebut delapan. Perbedaan data juga terjadi pada Peristiwa Nduga. 45 ribu penduduk Nduga mengungsi sejak pembunuhan enam belas pekerja jalan Trans Papua di Gunung Kabo, Desember 2018. Majelis Rakyat Papua (MRP) mencatat, 4.000 orang masih ada yang mengungsi di Jayawijaya, Lanny Jaya, dan Asmat. Dari sekian ribu pengungsi, tim kemanusiaan yang dibentuk pemerintah Kabupaten Nduga mengklaim ada 182 kasus meninggal. Sementara klaim Kementrian Sosial, yang meninggal ‘hanya’ 53.
Kasus Nduga adalah contoh paling menonjol penggunaan pendekatan militeristik dalam menangani masalah di Papua. Militer Indonesia menangkap dan menyiksa warga. Menurut kesaksian Irian Kogoya, salah satu warga di pegunungan Papua, dalam video dokumenter Program Foreign Correspondent ABC News, ada helikopter menjatuhkan bom ke kampungnya. Pemerintah membantah. Mereka bilang yang dipakai adalah granat.
Kembali ke peristiwa Surabaya, Surya mengatakan sejak malam sampai pagi ia tak pernah putus menjalin komunikasi dengan para mahasiswa. “Sampai detik-detik penembakan gas air mata,” katanya.
Ia juga segera menghubungi beberapa kelompok demokratik seperti Gereja Komunitas Anugerah (GKA), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), dan Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi). Lantas mereka, yang bergabung dalam aliansi Komitmen (Komisi Satu Mei untuk Kemerdekaan, Kesejahteraan dan Kesetaraan), menggelar konferensi pers di salah satu kafe di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada 18 Agustus 2019.
Surya juga menyampaikan ke para aktivis mahasiswa Papua di Jakarta agar segera mengadakan rapat. Besoknya, jam setengah delapan malam, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), FRI-WP, Pembebasan, dan himpunan-himpunan mahasiswa Papua berkumpul di Asrama Jayawijaya. Mereka menamai gerakan solidaritas itu sebagai: Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme. Pada pertemuan itu dibahas persiapan aksi tanggal 22. Mereka aksi dari siang sampai sore. Bergabung dengan Aksi Kamisan–aksi rutin yang dilakukan tiap Kamis, menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Tiga hari kemudian para aktivis mengadakan rapat lagi. Agendanya mengevaluasi demonstrasi, memantau perkembangan situasi, rencana aksi lanjutan, dan eksodus. Rencana aksi lanjutan cukup memakan waktu lama. Banyak yang berkeberatan jika aksi selanjutnya berbarengan dengan Kamisan dengan alasan konsentrasi massa terpecah. Sementara menurut Surya, aksi bersama kelompok Kamisan membuat isu Papua dapat didengar kelompok yang lebih beragam. Forum akhirnya memutuskan opsi pertama. Aksi berikutnya ditetapkan pada Rabu 28 Agustus.
Di antara sekian banyak pembahasan, eksodus jadi pembicaraan yang paling melelahkan. Sebelumnya, mereka mendapatkan informasi kalau Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Gubernur Lukas Enembe menyarankan untuk eksodus. Ada yang setuju, ada pula yang tidak. “Teman-teman yang sekarang ditangkap, berposisi untuk tidak eksodus,” terang Surya.
Jam dua belas lewat, massa yang menggunakan kereta berkumpul di Stasiun Juanda untuk bersama menuju titik kumpul demonstrasi, yaitu di depan Markas Besar (Mabes) TNI AD. Mereka akan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang lokasinya tepat di samping Mabes TNI AD. Setelah dari situ, barulah bergerak ke depan Istana. Pukul 14.17 massa berkumpul di depan Kemendagri dan mulai berorasi. Aksi itu merupakan aksi damai. Tak ada kerusuhan, apalagi bentrok.
***
Surya ditangkap tanggal 31 Agustus di Plaza Indonesia, ketika hendak meladeni wawancara wartawan sekaligus aktivis dari Malaysia dan menghadiri acara Amnesty International Indonesia. Surya terlambat mengikuti acara Amnesty sehingga langsung menuju ke sebuah restoran, dekat Sate Senayan, untuk menemui pewawancara itu. Surya mulai merasa ada yang tidak beres ketika di sela wawancara ia melihat salah satu pelayan laki-laki terus menatapnya curiga.
Begitu wawancara selesai, tiba-tiba datang tujuh polisi tanpa seragam sembari menunjukkan surat penangkapan. “Yang saya pikirkan di detik-detik penangkapan itu adalah menyelamatkan ponsel. HP langsung saya kasih teman, lalu menghadapi polisinya.”
“Saya tidak diborgol nih?” kata Surya ke polisi, berusaha tenang. “Bapak bukan penjahat,” jawab salah satu polisi.
Sebelum naik mobil, Surya minta waktu merokok sebentar untuk menenangkan pikiran. Sampai di Polda Metro Jaya, persis di pintu masuk utama, Surya bertemu Direktur Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Suyudi Ario Seto. Ia menyapa Surya dengan nama kecilnya, Anta, kemudian mengatakan kalau kali ini polisi harus menangkapnya karena Papua sudah rusuh.
Hanya sebentar di Polda Metro Jaya, Surya dibawa langsung ke Mako Brimob. Di sana, sebelum sesi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dengan pemantauan Kepala Sub Direktorat Keamanan Negara, ia diberondong pertanyaan. Dua di antaranya bikin Surya kesal: OPM itu bagaimana, dan kenapa dua mendukung kemerdekaan Papua. Surya jawab sembarangan, “mau jadi presiden.” Jawaban itu dipelintir oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Di hadapan wartawan dia bilang Surya mau jadi presiden Papua, padahal Surya hanya ogah menjawab. “Saya kesal dengan pertanyaan bodoh itu karena sering sekali ditanyai, padahal saya sudah empat kali ditangkap dalam isu Papua.”
***
Lelaki yang perutnya mulai membuncit semenjak menikah ini pernah mendaftar ke Akademi Angkatan Bersenjata (Akabri, sekarang Akmil alias Akademi Militer). Ia bahkan sampai ke tahap seleksi akhir, yaitu wawancara. Ia tidak lulus karena satu pertanyaan mengenai keputusan Presiden kala itu, Gus Dur, yang hendak mencabut pelarangan ideologi komunisme, marxisme, dan leninisme. Surya menjawab setuju dengan keputusan tersebut, sementara kita tahu TNI anti betul dengan ideologi itu. Merekalah yang membantai para kader PKI dan para simpatisannya tahun 1960an.
Gagal masuk Akabri, ia memilih berkuliah di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta. Di sanalah ia mulai mengenal dan terlibat dengan gerakan sosial. Ia bergabung ke dalam Aliansi Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (Amukra). Amukra kemudian berhimpun bersama beberapa organisasi mahasiswa lain dan membentuk LMND. Dari situ Surya berkenalan dengan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD). LMND adalah organisasi sayap PRD, relasinya mirip dengan PKI dan CGMI.
Tahun 2004, ketika terpilih menjadi pengurus pusat PRD, ia hengkang ke Jakarta. “Saya menjabat di departemen yang tidak usah disebutkan namanya, underground-lah,” katanya. Setelah tiga tahun, sehari sebelum ulang tahun PRD, ia didepak. Surya tidak sepakat dengan keputusan partai bahwa kader dapat mencalonkan diri di pemilu legislatif lewat Partai Bintang Reformasi (PBR). Menurutnya PBR adalah partai borjuis, juga konservatif, sementara PRD adalah partai yang mengusung gagasan sosial-demokrasi. “Kami yang tidak bersepakat dianggap melanggar keputusan kongres—intervensi Pemilu 2009.”
Meski tak lagi di PRD, Surya tetap berjibaku di gerakan sosial, khususnya di gerakan buruh. Sementara untuk mencari uang, ia bekerja paruh waktu.
Dalam forum diskusi tahun 2010, di mana Surya ditugaskan menulis notula, ia bertemu dengan dengan Lucia Fransisca, perempuan yang kelak menjadi istrinya. Lucia juga aktif di PRD periode 1995 sampai 2000. “Mungkin karena background itu yang membuat lebih gampang nyambung,” kata Sisi, sapaan Lucia. Lucia sadar pilihan politik suaminya memiliki konsekuensi yang besar. “Sebelum menikah juga sempat sekali atau dua kali ditangkap. Saya susul dia ke Polres Jakarta Pusat.” Tapi toh itu tak membuatnya menghalangi pilihan sang suami yang vokal terhadap persoalan Papua. “Manusia yang memiliki hati nurani dan kemanusiaan tidak akan bisa diam melihat apa yang terjadi di Papua.”
Keterlibatan Surya dalam isu-isu Papua baru intensif sejak 2016. Ini masa-masa dia membentuk FRI-WP. Ia pernah mengunjungi Papua untuk mengunjungi berbagai faksi politik. Banyak tudingan miring yang sampai ke telinganya saat membentuk FRI-WP. Yang paling sering adalah dia cuma cari duit dari sana. Ringkasnya, ‘sekadar proyek HAM’. Tudingan serupa juga datang dari orang-orang Papua. Salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Papua, yang termasuk Balikpapan Seven, Buchtar Tabuni, pernah bilang kalau FRI-WP adalah kaki-tangan pemerintah Indonesia. Surya maklum. “Karena banyak aktivis Papua di Indonesia, bicara HAM Papua, tapi tidak mau menghormati posisi mereka dalam soal penentuan nasib sendiri,” kata lelaki kelahiran Medan yang menghabiskan masa remajanya di Bandung ini.
Setelah bebas, Surya bilang tak hanya ingin menekuni soal-soal politik Papua, tapi juga menyelami kebudayaannya. Ia sekarang sudah fasih menyanyikan beberapa lagu Papua. Dengan setengah berteriak, di sela-sela waktu menunggu sidang dulu, Surya kerap menyanyi, “salam doe, salam doe….”
Arief Bobhil saat ini sedang menulis di spektator.id (untuk isu COVID-19) dan di lefo.id (umum).
Catatan: tulisan ini memang hanya mewawancarai para tahanan pria The Jakarta Six karena kisah tahanan perempuan, Erina Elopere, sudah ditulis dengan apik oleh Natalia Yewen.